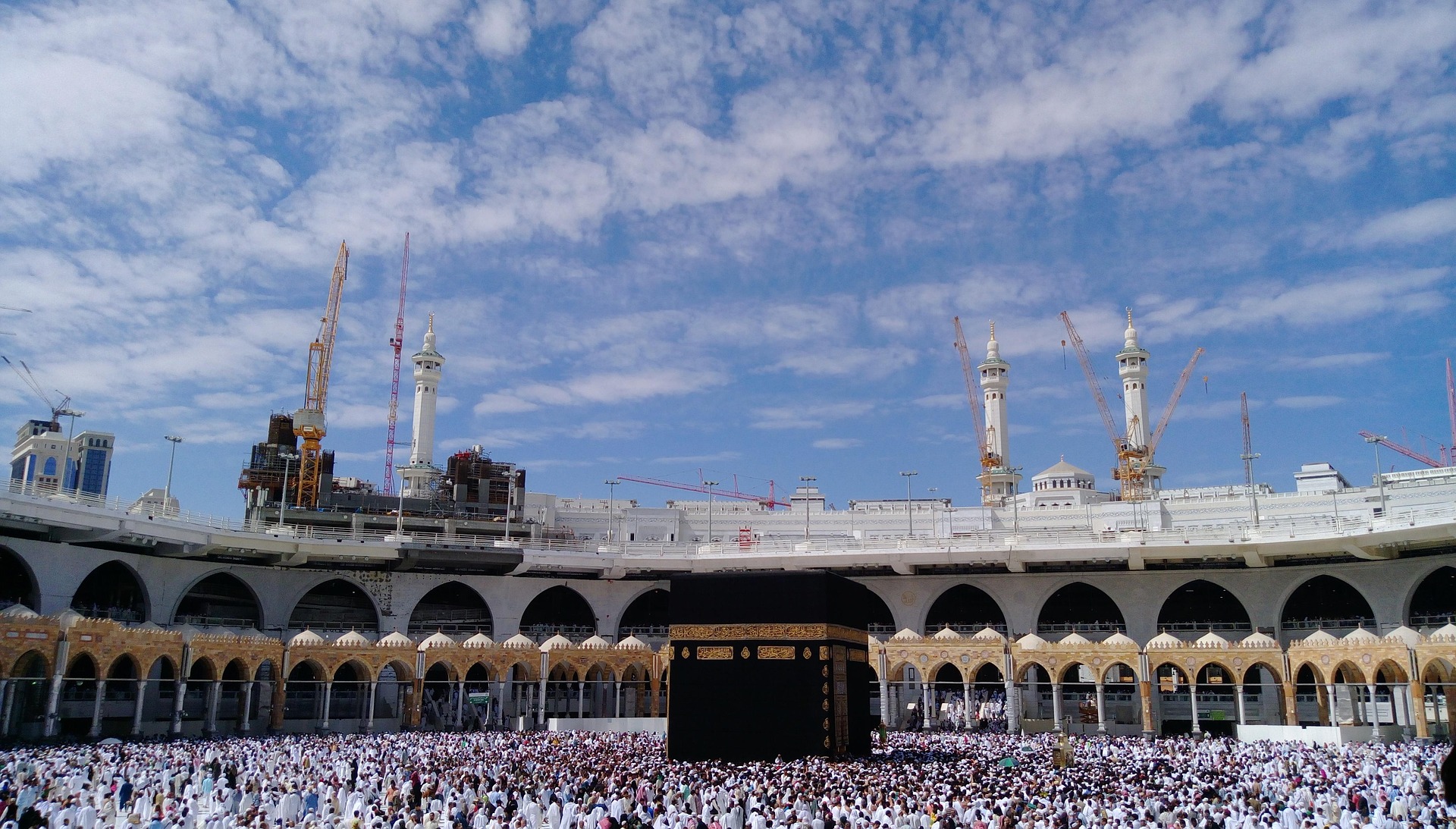SISTEM KEBIJAKAN POLITIK ISLAM (POLITIK SYARI’AH)
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ
Pelajaran: 1 Kebijakan Syariah: Konsepnya, Hukum-hukumnya, Dalil-dalil Pertimbangannya
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
- Konsep Kebijakan Syariah dan Syarat-syarat Penerapan Hukum-hukumnya
- Konsep Kebijakan Politik Islam
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu junjungan kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Anak-anakku, para mahasiswa program pascasarjana di Universitas Madinah Internasional, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah-kuliah tentang mata kuliah Kebijakan Syariah, dan kita akan memulai dengan membahas konsepnya, topik-topik yang dicakupnya, dan dalil-dalil pertimbangannya.
Sekarang kita mulai menjelaskan konsep Kebijakan Syariah. Definisi Kebijakan Syariah dalam bahasa: Disebutkan dalam (Al-Mishbah Al-Munir): Zaid mengelola suatu urusan (sasa Zaid al-amra yasusuhu) artinya: mengaturnya dan menangani urusannya. Dan disebutkan dalam (Lisan Al-Arab) karya Ibnu Manzhur Al-Afriqi: As-Saus artinya kepemimpinan, dikatakan: mereka memimpin mereka (sasuuhum sausan), dan jika seseorang dijadikan pemimpin, dikatakan: sawwasuhu, dan asasuhu. Dan kita mengatakan: mengatur urusan dengan kebijakan (sasa al-amra siyasatan) artinya: menanganinya. Dan kita mengatakan: kaum menjadikannya sebagai pengatur mereka (sawwasahu al-qawmu) artinya: mereka menjadikannya mengatur mereka. Dan dikatakan: si fulan mengatur urusan bani fulan (sawwasa fulanun amra bani fulanin) artinya: dia ditugasi mengatur mereka. Dan siyasah (kebijakan) adalah menangani sesuatu dengan apa yang memperbaikinya.
Dari sini menjadi jelas bahwa kata siyasah (kebijakan) digunakan dalam bahasa dengan berbagai penggunaan, dan maknanya dalam semua penggunaannya berkaitan dengan mengatur sesuatu, dan mengelolanya dengan apa yang memperbaikinya. Inilah definisi Kebijakan Syariah dalam bahasa.
Adapun definisi Kebijakan Syariah dalam istilah para ahli fikih, para ahli fikih memiliki beberapa pendapat: Dikatakan dalam definisi Kebijakan Syariah: adalah tindakan sesuatu dari penguasa untuk kemaslahatan yang dilihatnya, meskipun tidak ada dalil parsial yang menunjukkan tindakan tersebut – maksudnya: dalil terperinci dari Al-Quran, atau Sunnah, atau Ijma’, atau Qiyas. Sebagian yang lain juga mendefinisikannya bahwa: adalah tindakan yang dengannya manusia lebih dekat kepada kebaikan, dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkannya dan tidak turun wahyu tentangnya. Dan definisi ini terdapat dalam buku (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Mashdar li At-Taqnin) karya Dr. Abdullah Muhammad Muhammad Al-Qadhi, cetakan 1410 – 1989, Dar Al-Kutub Al-Jami’iyyah Al-Haditsah Thantha, hal. 32.
Sebagian yang lain juga mendefinisikan Kebijakan Syariah bahwa: adalah apa yang dilihat oleh imam (pemimpin), atau dikeluarkannya berupa hukum-hukum dan keputusan-keputusan sebagai pencegahan dari kerusakan yang terjadi, atau pencegahan dari kerusakan yang diperkirakan, atau pengobatan untuk kondisi khusus. Dan definisi ini adalah milik Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah) cetakan pertama 1419 H – 1989 M, Maktabah Wahbah Mesir, hal. 15 dan seterusnya.
Juga sebagian yang lain mendefinisikan Kebijakan Syariah bahwa: adalah mengatur urusan-urusan negara Islam yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash yang tegas, atau yang sifatnya dapat berubah dan berganti demi kemaslahatan umat, dan sesuai dengan hukum-hukum syariat serta prinsip-prinsip umumnya. Dan definisi ini adalah milik Dr. Mahmud As-Sawi dalam bukunya (Nizam Ad-Dawlah fi Al-Islam) cetakan pertama 1418 – 1998, Dar Al-Hidayah Mesir, hal. 39.
Syarat-syarat Pengamalan Hukum-hukum Kebijakan Syariah
Kita simpulkan dari definisi-definisi Kebijakan Syariah yang berbeda ini bahwa maksudnya adalah: bahwa tidak adanya petunjuk dari nash-nash yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah terhadap hukum-hukum Kebijakan Syariah secara terperinci tidaklah membahayakan, dan tidak menghalangi untuk menyifatnya dengan sebutan Kebijakan Syariah. Adapun yang membahayakan dan menghalangi dari itu adalah jika hukum-hukum tersebut bertentangan secara nyata dengan nash dari nash-nash terperinci, yaitu: Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Ini adalah nash-nash terperinci yang dimaksudkan untuk menjadi syariat umum bagi manusia di setiap zaman dan di setiap tempat. Maka ketika Kebijakan Syariah, atau hukum-hukum Kebijakan Syariah, selamat dari pertentangan dengan nash-nash terperinci ini, dan sejalan dengan ruh syariat serta prinsip-prinsip umumnya; maka ia menjadi sistem Islam dan Kebijakan Syariah yang kita ambil dan kita ambil hukum-hukumnya. Oleh karena itu Ibnu Aqil Al-Hanbali berkata: Kebijakan adalah tindakan yang dengannya manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkannya dan tidak turun wahyu tentangnya – sebagaimana telah kita katakan sebelumnya.
Oleh karena itu, adalah sesuatu yang keliru atau salah apa yang diklaim oleh sebagian penentang bahwa tidak ada kebijakan kecuali yang sesuai dengan syariat. Maka perkataan ini mengandung kesalahan dan penyesatan, yaitu: tidak ada kebijakan kecuali yang sesuai dengan syariat, di dalamnya terdapat kesalahan dan penyesatan jika yang dimaksud dengannya adalah bahwa tidak dianggap dari syariat Islam sesuatu dari hukum-hukum parsial yang terwujud dengannya kemaslahatan atau tertolak dengannya kerusakan, kecuali jika syariat menyatakannya dan ditunjukkan – dengan yakin – oleh nash-nash dari Al-Quran atau Sunnah, maka ini akan ditolak.
Adapun jika yang dimaksud dengan tidak ada kebijakan kecuali yang sesuai dengan syariat, jika maknanya adalah: bahwa tidak ada kebijakan: yaitu kesesuaian dengan syariat adalah jika hukum-hukum parsial tersebut sejalan dengan ruh syariat dan prinsip-prinsip kuliahnya, dan dengan itu tidak bertentangan dengan nash dari nash-nash terperincinya yang dimaksudkan untuk menjadi syariat umum; maka perkataan bahwa tidak ada kebijakan kecuali yang sesuai dengan syariat adalah perkataan yang benar dan lurus, didukung oleh syariat itu sendiri, dan disaksikan olehnya amal para sahabat, para khalifah yang mendapat petunjuk, dan para imam mujtahid. Dan hal-hal ini disebutkan, atau pembicaraan yang telah saya bicarakan disebutkan dalam buku (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah wa Al-Fiqh Al-Islami) karya Syaikh Abdurrahman Taj, cetakan pertama 1373 H – 1953 M, Dar At-Ta’lif Mesir, hal. 11.
Kesimpulan perkataan dalam masalah ini adalah bahwa hukum yang dituntut oleh kebutuhan umat menjadi Kebijakan Syariah yang diakui jika terpenuhi padanya dua perkara:
Perkara pertama: bahwa ia sejalan dengan ruh syariat, bersandar pada kaidah-kaidah kuliahnya dan prinsip-prinsip dasarnya.
Perkara kedua: tidak bertentangan secara nyata dengan dalil dari dalil-dalil syariat yang terperinci yang kami maksudkan dengannya Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Dan dalil-dalil terperinci ini adalah yang telah ditetapkan sebagai syariat umum bagi manusia di semua zaman dan di semua kondisi.
Berdasarkan itu, jika tidak ada dalil terperinci dari Al-Quran, atau Sunnah, atau Ijma’, atau Qiyas yang telah menunjukkan kebalikan dari hukum kebijakan, atau ada pertentangan tetapi pertentangan tersebut bersifat lahiriah dan bukan hakiki, atau diketahui bahwa apa yang ditunjukkan oleh dalil terperinci tidak dimaksudkan untuk menjadi syariat umum, melainkan untuk hikmah khusus dan sebab yang tidak ada pada selain peristiwa hukum tersebut; ketika itu pertentangan hukum kebijakan tidak menjadi pertentangan terhadap dalil-dalil syariat dan hukum-hukum Islam.
Dengan penerapan pada apa yang telah kami sebutkan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran syariat, melainkan dianggap dari hukum-hukum Kebijakan Syariah hal-hal berikut:
Perkara pertama: Apa yang dilakukan oleh sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta’ala anhu berupa pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf; sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta’ala anhu melihat bahwa kemaslahatan terletak pada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, dan dia melakukan itu karena kemaslahatan manusia dan kemaslahatan kaum muslimin menuntut hal itu, dan kemaslahatan masuk dalam bab Kebijakan Syariah.
Juga perkara kedua: Apa yang didirikan oleh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ta’ala anhu berupa diwan-diwan (lembaga-lembaga), dan diwan-diwan: menyerupai sekarang kantor-kantor pemerintahan yang dicatat di dalamnya nama-nama pegawai, gaji-gaji mereka, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perangkat administratif, didirikan oleh sayyidina Umar bin Al-Khaththab, dan tidak ada pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun pada zaman sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu – namun demikian dia mendirikannya; karena kemaslahatan kaum muslimin menuntut hal itu, dan ini dianggap sebagai hukum dari hukum-hukum Kebijakan Syariah. Demikian pula apa yang diwajibkannya berupa kewajiban kharaj – yaitu pajak atas tanah – ini juga diwajibkan oleh sayyidina Umar bin Al-Khaththab, dan tidak ada hal itu pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun pada zaman sayyidina Abu Bakar, melainkan didirikan oleh sayyidina Umar; karena kemaslahatan kaum muslimin menuntut hal itu, dan tidak ada yang mengingkarinya; oleh karena itu hal itu termasuk dalam bab Kebijakan Syariah.
Perkara ketiga: Adalah penggandaan mushaf-mushaf pada awal Islam merupakan perkara biasa, karena dibolehkan bagi setiap sahabat untuk menulis mushaf dengan huruf yang didengarnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika kemaslahatan hilang; karena perbedaan dalam bacaan; sayyidina Utsman bin Affan memerintahkan untuk mempertahankan satu mushaf, dan membakar mushaf-mushaf yang lain. Mengapa sayyidina Utsman bin Affan melakukan itu? Dia melakukan itu demi kemaslahatan kaum muslimin ketika dia melihat bahwa ada beberapa perselisihan yang akan muncul di antara kaum muslimin karena bacaan-bacaan yang beragam ini; oleh karena itu dia ingin menghapus fitnah ini sejak awal; oleh karena itu dia mempertahankan satu mushaf, dan membakar selainnya.
Yang membuatnya melakukan itu adalah jenis dari Kebijakan Syariah – yaitu: demi menjaga kemaslahatan kaum muslimin.
Perkara lain: yang dianggap sebagai jenis dari Kebijakan Syariah – dan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap nash-nash Al-Quran dan Sunnah – adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu berupa penghilangan bagian orang-orang yang dilembutkan hatinya (muallafatu qulubuhum) dari bagian sedekah – meskipun bagian ini telah ditetapkan untuk mereka dalam Al-Quran secara tegas dengan firman Allah ta’ala: “Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus sedekah, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan” (Surah At-Taubah: Ayat: 60).
Kami katakan: meskipun ada nash yang tegas ini bahwa ada bagian untuk orang-orang yang dilunakkan hatinya; sayyidina Umar bin Al-Khaththab tidak mengambil makna lahir lafaz, dan tidak berhenti pada literalitas nash, bahkan memperhatikan rahasia nash dan hukum ruh nash, dan memutuskan bahwa ayat yang mewajibkan bagian bagi orang-orang yang dilunakkan hatinya ini tidak melakukan itu; agar dijadikan syariat umum yang diamalkan dalam setiap kondisi dan zaman, melainkan untuk hikmah khusus dan sebab yang tidak lagi ada setelahnya. Dan dia menunjukkan ini dengan ucapannya: “Sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan membuatnya tidak membutuhkan mereka” – maksudnya: membuat Islam tidak membutuhkan orang-orang yang dilunakkan hatinya ini. Umar radhiyallahu anhu melihat bahwa bagian orang-orang yang dilunakkan hatinya telah diwajibkan oleh Allah ta’ala karena kebutuhan kaum muslimin kepada orang yang mendukung mereka dan menolong mereka, atau tidak menghasut kabilah-kabilah terhadap mereka; maka jika kaum muslimin menjadi kuat dan mulia, dan hilang makna yang karenanya bagian itu diwajibkan; maka imam boleh membelanjakannya dari orang-orang yang dilunakkan hatinya itu kepada apa yang lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi kaum muslimin.
Dan pembicaraan ini terdapat dalam buku Syaikh Abdurrahman Taj tentang Kebijakan Syariah. Bukan berarti ini membatalkan bagian orang-orang yang dilunakkan hatinya sama sekali, melainkan urusannya berputar dengan sebab tersebut ada dan tidaknya. Maksudnya: bahwa bagian orang-orang yang dilunakkan hatinya tidak dihapus secara mutlak, tetapi itu tergantung pada sebab yang disyariatkan karenanya; telah disyariatkan karena kaum muslimin dalam keadaan lemah, dan mereka membutuhkan orang-orang yang mereka luluhkan hatinya; agar mereka berdiri di sisi mereka dan tidak menghasut kabilah-kabilah terhadap mereka.
Tetapi jika sebab ini tidak ada lagi, ketika kaum muslimin menjadi kuat; maka dalam kondisi ini sebab tidak ada lagi, dan oleh karenanya hukum tidak berlaku. Karena hukum berputar dengan illatnya, ada dan tidaknya. Bahkan jika timbul bagi kaum muslimin kebutuhan untuk pelunakan hati – sebagaimana ada kebutuhan untuk itu pada awalnya – maka sah bagi imam untuk membelanjakan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya sesuai dengan apa yang dilihatnya dari kemaslahatan umum.
Disebutkan dalam kitab (Ahkam al-Quran) karya Ibnu Arabi dalam tafsir ayat tentang sedekah, beliau mengatakan: Terjadi perbedaan pendapat mengenai keberadaan golongan muallaf (orang yang dilunakkan hatinya), sebagian berpendapat: mereka sudah tidak ada lagi -maksudnya: mereka tidak lagi menerima dari sedekah, dan tidak memiliki bagian- pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah ulama, dan dipegang oleh Malik semoga Allah meridhainya. Sebagian lain berpendapat: mereka masih ada karena imam mungkin memerlukan untuk menarik simpati orang kepada Islam, dan Umar menghentikan pemberian kepada mereka ketika melihat Islam telah kuat. Adapun menurut saya -ini adalah perkataan Ibnu Arabi- beliau berkata: Menurut saya, jika Islam telah kuat maka mereka tidak ada lagi -artinya: tidak diberi bagian dari zakat- namun jika masih diperlukan maka mereka diberi bagian muallaf, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.
Pernyataan ini dinukil dari Ibnu Arabi dalam kitab (Ahkam al-Quran) karya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Arabi, cetakan pertama Dar al-Kutub al-Ilmiyah Beirut, jilid kedua halaman 530.
Bahkan sebagian ulama berpendapat: Pemberian kepada muallaf masih memiliki tempatnya sekarang; karena sebagian orang masuk Islam lalu terputus dari keluarganya dan kaumnya, dan mungkin dia memiliki pekerjaan lalu dipecat dari pekerjaannya; maka dari hak mereka ini untuk dialokasikan dari zakat untuk bagian muallaf; guna meneguhkan keimanan mereka, dan mencegah mereka dari fitnah dalam agama mereka berupa fitnah materi. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Abdul Khaliq al-Nawawi dalam bukunya (An-Nizham al-Mali fi al-Islam) cetakan pertama tahun 1971 M, Maktabah al-Anglo al-Mishriyah halaman 180.
Juga termasuk perkara yang tidak ada pertentangan di dalamnya antara nash-nash syariat -dan di dalamnya diambil berdasarkan hukum-hukum politik syariat- saya katakan: Bukan termasuk pelanggaran terhadap nash-nash syariat apa yang dilakukan oleh sayyidina Utsman bin Affan semoga Allah meridhainya terhadap unta yang tersesat, yaitu dia memerintahkan untuk mengumumkannya; jika pemiliknya datang maka dia mengambilnya, dan jika tidak datang maka dijual, dan harganya disimpan. Beliau semoga Allah meridhainya tidak melanjutkan apa yang berlaku sebelumnya di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam dan zaman Abu Bakar, serta zaman Umar. Dahulu unta yang tersesat dibiarkan lepas tidak disentuh siapa pun; hingga pemiliknya menemukannya. Sayyidina Utsman tidak berhenti pada hurufiah nash yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya tentang barang temuan, maka beliau bersabda: “Kenali tali dan wadahnya kemudian umumkan selama satu tahun; jika pemiliknya datang (maka berikan), jika tidak maka terserah padamu.” Laki-laki itu bertanya: Bagaimana dengan kambing yang tersesat wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala” -artinya: jika kamu tidak mengambilnya; hampir saja serigala mengambilnya. Maksudnya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambilnya dan mengumumkannya selama satu tahun. Laki-laki itu bertanya: Bagaimana dengan unta yang tersesat wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Apa urusanmu dengannya, bersamanya ada tempat minumnya dan sandalnya, dia mendatangi air, dan memakan pohon; hingga pemiliknya menemukannya.”
Dalam masalah unta yang tersesat, Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada laki-laki ini bahwa unta tidak diambil, dan tidak dipungut, bahkan seharusnya dibiarkan di tempatnya; hingga pemiliknya datang kepadanya; karena tidak ada kekhawatiran terhadap unta; bersamanya ada air, dan juga makanan; oleh karena itu kita tidak khawatir terhadapnya. Larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk memungut unta -sebagaimana telah kami katakan- berlangsung seperti itu di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam dan di zaman Abu Bakar, serta di zaman Umar -semoga Allah meridhai mereka semua- namun sayyidina Utsman bin Affan tidak berhenti pada hurufiah nash ini, bahkan beliau menyelisihinya secara zhahir; karena beliau melihat keadaan telah berubah, dan bahwa hadits tersebut datang pada masa di mana tidak dikhawatirkan unta yang tersesat akan hilang, dan tangan-tangan mengambilnya; ketika beliau melihat tangan-tangan telah mengambilnya; karena lemahnya penghalang agama pada orang-orang; maka beliau memerintahkan semoga Allah meridhainya untuk mengumpulkannya dan memungutnya, serta menjualnya; untuk menyimpan harganya bagi pemiliknya, atau memanfaatkan harga ini untuk kepentingan umum kaum muslimin -jika tidak muncul pemiliknya.
Maka Utsman semoga Allah meridhainya jika secara zhahir menyelisihi hadits ini; maka sesungguhnya dalam kenyataan, dan batin perkara beliau beramal dengan hadits ini, dan berpegang teguh dengan ruhnya, dari sisi bahwa keadaan yang membuatnya khawatir terhadap unta yang tersesat telah berubah keadaannya, dan tidak lagi keadaan kedua sejenis dengan keadaan yang disebutkan dalam hadits tersebut – maksudnya: bahwa unta dahulu tidak dikhawatirkan di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam dan di zaman sayyidina Umar; karena orang-orang takut kepada Allah tabaraka wa taala dan penghalang agama tersedia. Adapun ketika orang-orang menjauh dari agama, dan menjadi lemah dalam penghalang agama; maka sayyidina Utsman bin Affan berpendapat untuk menyelisihi hukum yang berlaku, dan yang disebutkan dalam hadits, dan penyelisihan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam syariat yang datang untuk menjaga harta orang-orang, karena menjaga harta adalah termasuk lima perkara dharuri yang semua syariat datang untuk menjaganya yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan.
Maka sayyidina Utsman bin Affan ketika keluar dari ketentuan nash ini, atau dari hukum yang disebutkan dalam hadits ini, sesungguhnya beliau memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin, dan inilah yang ditetapkan oleh politik syariat.
Kesimpulannya: bahwa tidak sah dalam suatu tindakan dari tindakan-tindakan, atau hukum dari hukum-hukum yang disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum bahwa dikatakan: sesungguhnya itu bertentangan dengan syariat; berdasarkan apa yang terlihat di dalamnya berupa penyelisihan zhahir terhadap dalil dari dalil-dalil, bahkan wajib memahami dalil-dalil ini, dan mengetahui ruhnya, dan mengungkap maksud-maksudnya, dan rahasia-rahasia pensyariatan di dalamnya, serta membedakan antara yang datang karena sebab khusus, dan yang termasuk pensyariatan umum yang tidak berubah; karena menyelisihi jenis kedua adalah yang berbahaya yang mencegah masuknya hukum-hukum politik dalam lingkup syariat Islam.
Demikianlah telah jelas bagi kita dari perbuatan sayyidina Umar, dan perbuatan sayyidina Utsman bahwa mereka keluar dari hukum-hukum yang dinashkan, namun ini adalah keluar yang dihasilkan dari pemahaman mereka terhadap nash-nash, dan dihasilkan dari pemahaman mereka terhadap ruh nash-nash ini, dan rahasia pensyariatan dalam nash-nash ini; oleh karena itu termasuk dalam bab politik syariat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin di setiap zaman, dan di setiap tempat; oleh karena itu tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.
Dan yang harus diperhatikan di sini bahwa politik ini disifati dengan syariat; karena ijtihad penguasa dalam peristiwa dan kejadian yang baru, dan yang masuk dalam bidang ilmu politik syariat tidak dibangun atas hawa nafsu dan keinginan, melainkan atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang diakui secara syar’i. Hal-hal ini dijelaskan dalam (As-Siyasah asy-Syar’iyah karya Dr. Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi halaman 36, dan Syaikh Abdurrahman Taj halaman 18, dan seterusnya). Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan dalam hal ini: Sesungguhnya politik syariat adalah politik yang berdiri atas kebijakan syariat, hukum-hukumnya, dan tuntunan-tuntunannya. Maka tidak setiap politik kita hukumi sebagai syariat, banyak politik yang memusuhi syariat, dan berjalan dalam jalannya sesuai dengan persepsi dan hawa nafsu pemiliknya. Ini ada dalam (As-Siyasah asy-Syar’iyah karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi halaman 27) di dalamnya ada rincian lebih lanjut.
Topik-topik Ilmu Politik Syariat
Setelah kami menjelaskan yang dimaksud dengan politik syariat, atau konsep politik syariat, sekarang kita berbicara tentang topik-topik ilmu politik syariat: Sesungguhnya topik-topik yang masuk dalam politik syariat terdapat dalam beberapa perkara, pertama peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan yang diperintah, dari penentuan kekuasaan penguasa, dan penjelasan hak-haknya, dan kewajibannya, serta hak-hak rakyat, dan kewajibannya, serta kekuasaan-kekuasaan yang berbeda dalam negara dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Topik-topik ini yang berhubungan dengan sistem politik dalam Islam adalah yang diatur olehnya, atau yang mengaturnya adalah ilmu politik syariat; oleh karena itu nash-nash al-Quran, dan Sunnah tidak banyak datang dalam topik pengaturan politik negara Islam, melainkan meletakkan kaidah-kaidah umum, dan nash-nash umum, dan setelah itu menyerahkan kepada umat untuk memilih bentuk yang sesuai dengan kemaslahatan mereka; oleh karena itu penjelasan hubungan penguasa dengan yang diperintah seharusnya tunduk pada kemaslahatan umum negara Islam, dan kemaslahatan umum ini sesungguhnya diatur oleh ilmu politik syariat. Demikian juga kekuasaan-kekuasaan penguasa, dan batasan kekuasaan ini, serta hak-hak penguasa atas yang diperintah, demikian juga hak-hak rakyat atas penguasa, dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semua perkara ini sesungguhnya diatur oleh ilmu politik syariat. Ketika Islam menyerahkannya kepada ilmu politik syariat, sesungguhnya ingin membuktikan kepada manusia bahwa syariat Islam fleksibel, dan berkembang, dan cocok untuk diterapkan di setiap zaman, dan tempat; maka kita boleh menegakkan pemerintahan dalam Islam, namun cara yang dilakukan dengan itu, semua itu diserahkan oleh Islam.
Hak-hak dan kewajiban seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin, dan realita kaum muslimin; oleh karena itu termasuk karunia Allah kepada kita bahwa perkara-perkara ini diserahkan, dan di dalamnya ada ruang untuk ijtihad demi terwujudnya kemaslahatan umum. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan yang diperintah, dan dengan penentuan kekuasaan penguasa, dan penjelasan hak-haknya, dan kewajibannya, serta hak-hak rakyat, dan kewajibannya, dan penjelasan kekuasaan-kekuasaan yang berbeda, dan fungsi setiap kekuasaan dari kekuasaan-kekuasaan ini adalah yang dicakup oleh materi yang disebut -dalam fikih Islam- sistem pemerintahan dalam Islam; oleh karena itu materi sistem pemerintahan dalam Islam membahas perkara-perkara ini secara rinci. Sistem pemerintahan dalam Islam adalah materi yang sejajar dalam sistem-sistem positif dengan materi yang disebut: hukum konstitusi. Materi: hukum konstitusi dalam sistem-sistem positif dipadankan dalam Islam dengan materi: sistem pemerintahan dalam Islam.
Juga termasuk topik-topik yang masuk dalam ilmu politik syariat: peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara lain dalam keadaan damai, dan dalam keadaan perang. Ini yang disebut: sistem internasional dalam Islam. Sistem internasional dalam Islam yang dibangun atas hubungan kaum muslimin dengan yang lain, dan yang dibangun atas dasar bahwa dasar hubungan ini sesungguhnya berdiri atas prinsip timbal balik, dan bahwa dasar dalam perlakuan negara Islam terhadap negara-negara lain sesungguhnya adalah perdamaian, bukan perang, dan bahwa negara Islam tidak menggunakan perang kecuali dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan membela diri, dan lain-lain. Semua itu dijelaskan sepenuhnya dalam materi yang dipelajari, disebut sistem internasional dalam Islam, menjelaskan dasar: dasar hubungan negara Islam dengan negara-negara lain, yaitu bahwa hubungan ini berdiri atas perdamaian. Juga dijelaskan jika terjadi perang, dan ada kebutuhan mendesak bagi kaum muslimin untuk masuk dalam perang; maka politik syariat masuk dalam menjelaskan bagaimana kaum muslimin memperlakukan yang lain dalam keadaan perang, bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, dan lain-lain dari perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara peperangan. Semua ini diatur oleh kaidah-kaidah politik syariat, dan sesungguhnya mengaturnya, atau yang mengaturnya adalah ilmu politik syariat -sebagaimana telah kami katakan- karena ilmu politik syariat berdiri atas mewujudkan kemaslahatan umum bagi umat Islam.
Selama yang dikehendaki dari itu adalah mewujudkan kemaslahatan umum; maka seharusnya kita melihat kepada realitas, dan bagaimana musuh memperlakukan kita, dan seharusnya kita memperlakukan mereka dengan seperti apa mereka memperlakukan kita. Ini adalah penerapan prinsip persamaan dalam hubungan internasional. Hukum ini yang dipadankan dengannya yaitu sistem internasional dalam Islam dipadankan dalam hukum positif dengan hukum yang disebut: hukum internasional.
Maka hukum internasional yang ada dalam sistem-sistem positif dipadankan pada kita dengan sistem internasional dalam Islam. Bahkan fuqaha syariat telah berbicara panjang lebar tentang hubungan negara Islam dengan negara-negara lain, baik dalam keadaan damai, maupun dalam keadaan perang. Bahkan mungkin sistem-sistem Barat telah mengambil manfaat dari hukum-hukum ini, dan mengambilnya dalam hukum internasional mereka.
Juga termasuk topik-topik yang masuk dalam ilmu politik syariat adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pajak dan pemungutan harta, dengan pajak dari zakat, dan dari kharaj, dan dari usyur -sebagaimana akan kita lihat insya Allah- semua itu -artinya: mengaturnya, atau yang mengaturnya adalah ilmu politik syariat. Demikian juga sumber-sumber negara, dan pengeluaran-pengeluaran umumnya, serta sistem baitul mal- ini yang dikhususkan bagi ilmu politik syariat. Ini yang dicakup oleh hukum yang dipelajari disebut: sistem keuangan dalam Islam. Maka sistem keuangan dalam Islam, atau topik-topik yang ditangani oleh hukum, atau sistem keuangan dalam Islam, sesungguhnya bergantung dalam dasarnya pada politik syariat karena -sebagaimana telah kami katakan-: sistem keuangan, dan setiap sistem seharusnya dimaksudkan darinya, atau tujuan darinya sesungguhnya adalah mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin; oleh karena itu diserahkan kepada ilmu politik syariat.
Sistem keuangan dalam Islam dipadankan dalam sistem-sistem positif dengan ilmu keuangan umum. Artinya bahwa fuqaha -fuqaha muslimin terdahulu- telah mendahului fuqaha hukum internasional dalam mengatur perkara-perkara ini. Jika pada mereka ada ilmu keuangan umum, kami katakan kepada mereka: dalam syariat Islam -dan sejak lebih dari empat belas abad yang lalu- fuqaha telah menjelaskan sistem keuangan dalam Islam dengan sangat teliti.
Demikian pula di antara topik-topik yang masuk ke dalam ilmu politik syariah adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peredaran harta, dan bagaimana mengatur investasi harta ini, dan inilah yang mencakup materi sistem ekonomi dalam Islam. Para ahli fikih telah menjelaskan hal ini, dan mereka membahas tentang sistem ekonomi dalam Islam, dan bagaimana berinvestasi dengan harta ini melalui mudharabah Islami, dan berbagai cara lainnya seperti muzara’ah, musaqah, dan sebagainya yang banyak terdapat dalam kitab-kitab para ahli fikih, yang membahas tentang sistem ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi dalam Islam ini adalah yang sejajar dengan materi yang disebut: ilmu ekonomi dalam sistem-sistem buatan manusia. Maka ilmu ekonomi yang ada dalam sistem-sistem buatan manusia telah didahului oleh ilmu sistem ekonomi dalam Islam; karena kaum muslimin atau para ahli fikih kaum muslimin telah membahas secara panjang lebar tentang topik ini -topik bagaimana berinvestasi dengan harta- mereka membahas tentang mudharabah Islami, dan syarat-syarat mudharabah ini, dan bagaimana investasi yang memberikan kebaikan yang melimpah kepada individu dan kepada masyarakat, insya Allah.
Juga di antara topik-topik yang masuk ke dalam ilmu politik syariah adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sistem peradilan, dan cara-cara peradilan, dan penjelasan alat-alat pembuktian, semua itu tercakup atau terkandung dalam ilmu politik syariah -dan sebagaimana kami katakan- karena hal-hal ini tunduk pada kondisi masyarakat, dan perkembangan masyarakat, dan realitas masyarakat; dan oleh karena itu masuk dalam ilmu politik syariah sistem-sistem peradilan, dan cara-cara peradilan, dan peradilan yang dikhususkan dan yang tidak dikhususkan, dan jenis-jenis peradilan, dan penjelasan alat-alat pembuktian, penjelasan alat-alat pembuktian dari pengakuan, dan dari kesaksian, dan dari qasāmah dalam bab pembunuhan, dan sebagainya dari berbagai cara yang berbeda yang menjamin hak-hak manusia, dan tidak ada kerugian bagi seorang pun dari manusia. Sistem peradilan ini dijelaskan oleh para ahli fikih kaum muslimin dengan penjelasan yang memuaskan, dan berdasarkan dalam pengaturannya pada ilmu politik syariah. Sistem peradilan dalam Islam ini sejajar dengan sistem-sistem buatan manusia dengan undang-undang yang disebut undang-undang acara perdata dan perdagangan dalam sistem-sistem buatan manusia. Ini -sebagaimana kami katakan- jika undang-undang acara perdata dan perdagangan ada dalam undang-undang buatan manusia; maka telah didahului oleh para ahli fikih kaum muslimin dengan waktu yang sangat lama, dan dengan periode yang sangat panjang, dan diatur dalam Islam dengan pengaturan yang cermat, bahkan undang-undang buatan manusia yang mengatur acara perdata dan perdagangan ini telah dipengaruhi oleh pengaturan kaum muslimin mengenai cara-cara ini. Dan topik-topik khusus yang berkaitan dengan masalah peradilan ini telah dibahas oleh para ahli fikih kita terdahulu dengan berbagai madzhab dan kecenderungan mereka dalam bab-bab fikih umum.
Namun kami menemukan sebagian ahli fikih membahasnya secara mandiri, artinya: para ahli fikih dalam hal-hal ini menjelaskannya dalam kitab-kitab fikih umum yang membahas tentang ibadah, dan membahas tentang yang lainnya, mereka membahas peradilan di dalamnya, dan cara-cara hukum, dan alat-alat pembuktian. Namun -meskipun demikian- kami menemukan spesialisasi yang lebih dalam hal ini, dan kami menemukan dari para ahli fikih terdahulu yang mengkhususkan diri, atau yang memfokuskan pada topik ini, dan menulis di dalamnya banyak kitab; dan oleh karena itu kami menemukan dari kitab-kitab yang khusus dalam topik peradilan, dan pengaturan peradilan, dan alat-alat pembuktian, di antaranya misalnya: kitab (Al-Ahkam As-Sultaniyyah) karya Al-Mawardi Asy-Syafi’i, kitab ini menjelaskan di dalamnya banyak hukum yang berkaitan, atau menjelaskan pengaturan peradilan dalam negara Islam, bahkan menjelaskan di dalamnya tiga kekuasaan dalam negara Islam: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan demikian pula juga membahas di dalamnya administrasi dalam Islam, dan sistem administrasi dalam Islam menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan, dan berbicara di dalamnya tentang kementerian; kementerian pendelegasian, dan kementerian pelaksanaan -sebagaimana akan kita lihat- itu di dalamnya, insya Allah.
Dan demikian pula ada kitab yang disebut (Al-Ahkam As-Sultaniyyah) karya Abu Ya’la Al-Hanbali, juga berbicara di dalamnya tentang peradilan, dan berbicara di dalamnya tentang kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif secara panjang lebar, dan demikian pula kitab (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Ishlah Ar-Ra’i war-Ra’iyyah) karya Ibnu Taimiyyah Al-Hanbali yang terkenal, berbicara dalam politik syariah ini tentang kaidah-kaidah umum yang seharusnya ditempuh atau dijalani oleh para penguasa kaum muslimin, baik dalam pemerintahan mereka terhadap manusia, atau dalam penugasan mereka terhadap para pekerja, dan menjelaskan bahwa politik syariah yang bijaksana adalah yang memperhatikan kemaslahatan manusia dalam semua sisi kehidupan mereka. Dan ada juga di antara kitab-kitab yang dikhususkan dalam topik politik syariah adalah kitab (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah wal-Fiqh Al-Islami) karya Syaikh Abdurrahman Taj, berbicara secara panjang lebar juga di dalamnya tentang hal ini, dan berbicara banyak tentang bagaimana pemerintah mengelola kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam negara Islam.
Dan ada juga kitab (Al-Hisbah) karya Ibnu Taimiyyah Al-Hanbali, dan ada juga kitab-kitab yang berbicara tentang cara-cara penghakiman, yaitu kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang berbicara di dalamnya tentang cara-cara ini, dan berbicara di dalamnya tentang sistem peradilan, dan berbicara di dalamnya tentang alat-alat pembuktian dalam fikih Islam, menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan. Dan ada juga kitab-kitab yang mengkhususkan diri dalam bidang-bidang keuangan seperti kitab (Al-Kharaj) karya Abu Yusuf, yaitu pajak-pajak yang dibebankan pada tanah, dan demikian pula juga kitab yang disebut kitab (Al-Kharaj) karya Yahya bin Adam Al-Qurasyi, dan demikian pula kitab yang disebut (Al-Amwal) karya Abu ‘Ubaid bin Salam.
Semua ini adalah hal-hal yang berbicara tentang politik syariah secara umum, dan berbicara tentang topik-topik yang dicakup oleh ilmu politik syariah.
Dan kita simpulkan dari apa yang telah disebutkan bahwa politik syariah tujuannya adalah mencapai pengaturan urusan negara Islam dengan pengaturan dari agamanya, dan penjelasan tentang kecukupan Islam dengan politik yang adil, dan penerimaannya terhadap pemeliharaan kemaslahatan manusia di berbagai masa dan negeri, dan mengikuti perkembangan-perkembangan sosial dalam setiap keadaan dan zaman dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum Islam. Dan ini maknanya bahwa kita tidak bisa mengabaikan politik syariah. Maka politik syariah sesungguhnya mewakili perkembangan dalam kehidupan umat Islam, dan dialah yang menjelaskan dengan jelas, dan menegaskan dengan dalil bahwa syariat Islam cocok untuk berkembang, dan ia cocok untuk diterapkan di setiap zaman, dan di setiap tempat, hingga Allah mewarisi bumi dan siapa yang ada di atasnya.
Inilah topik-topik terpenting yang masuk ke dalam ilmu politik syariah.
Demikian, dan dengan Allah lah taufik.
Perhatian Syariat terhadap Kondisi Manusia dalam Apa yang Disyariatkannya dari Hukum-hukum
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, pemimpin kami Muhammad, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita beralih kepada topik lain, yaitu: dalil-dalil pertimbangan politik syariah – artinya: dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita seharusnya mengambil politik syariah. Ada banyak segi yang menjadi bukti pertimbangan politik syariah, atau yang menunjukkan bahwa kaum muslimin seharusnya tidak mengabaikan politik syariah, dan bahwa mereka wajib mengambil hukum-hukumnya, dan dalam berbagai tempatnya. Dan topik ini dijelaskan secara terperinci dalam kitab (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah karya Syaikh Abdurrahman Taj hal. 65). Dan di antara segi-segi pertama yang menunjukkan pertimbangan politik syariah, pertama: Sesungguhnya kita menyaksikan pada syariat-syariat samawi terdahulu – bahwa mereka memperhatikan kemaslahatan umat-umat, dan kebutuhan setiap zaman; maka mereka mengubah dalam suatu syariat beberapa hukum dari syariat sebelumnya karena perubahan kondisi dan keadaan. Dan di antara contoh-contoh tentang itu: maka dahulu haram bagi Bani Israil bekerja pada hari Sabtu, dan haram bagi mereka sebagian lemak hewan setelah hal itu halal bagi yang sebelum mereka, kemudian kembali menjadi halal bagi yang sesudah mereka. Dan maknanya bahwa hal-hal ini; pengharaman bekerja pada hari Sabtu, dan pengharaman sebagian lemak hewan, sesungguhnya diwajibkan kepada orang-orang tertentu, dan tidak diwajibkan kepada yang lain. Dan mungkin sebabnya adalah perubahan kondisi, dan perubahan keadaan. Dan ini jika menunjukkan maka sesungguhnya menunjukkan pengambilan politik syariah.
Maka seakan-akan syariat-syariat itu sendiri memperhatikan pengambilan prinsip politik syariah, yaitu bahwa hukum-hukum berubah dengan berubahnya zaman. Perubahan hukum dengan berubahnya zaman, telah ada, atau telah diperhatikan dalam syariat-syariat terdahulu. Dan juga di antara contoh-contoh tentang itu: dahulu halal -pada awal masa manusia- bahwa seorang laki-laki menikahi saudara perempuannya, atau bibinya, kemudian itu diharamkan ketika keturunan bertambah banyak, dan individu-individu jenisnya bertambah banyak – artinya: maknanya dahulu diperbolehkan, awalnya bagi laki-laki bahwa ia menikahi saudara perempuannya, atau bibinya, namun itu karena sebab tertentu, tidak ada keturunan, tidak ada banyaknya jenis, tetapi ketika jenis bertambah banyak, dan manusia bertambah banyak; tidak ada lagi kebutuhan untuk membolehkan bagi laki-laki menikahi saudara perempuannya, atau bibinya.
Jadi hukum berubah; karena perubahan kondisi, dan perubahan masa dan zaman. Dan jika demikian halnya, maka wajib syariat Islam yang merupakan penutup syariat-syariat mengikuti keadaan manusia – artinya: jika ada sebagian perubahan pada sebagian hukum dalam syariat-syariat terdahulu; maka lebih utama untuk itu syariat Islam; karena syariat Islam sesungguhnya adalah penutup syariat-syariat, dan Allah menghendakinya untuk menjadi penutup syariat-syariat; dan oleh karena itu seharusnya berkembang sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan. Saya katakan: jika demikian halnya berkaitan dengan syariat-syariat terdahulu; maka wajib syariat Islam yang merupakan penutup syariat-syariat mengikuti keadaan manusia, mewujudkan tuntutan kebutuhan-kebutuhan yang terus muncul. Dan yang memenuhi itu adalah bagian politik syariah, atau ilmu politik syariah.
Jadi kita keluar dari ini, atau kita simpulkan dari ini bahwa ilmu politik syariah sesungguhnya bekerja, atau menegaskan bahwa syariat Islam cocok untuk diterapkan di setiap zaman dan tempat; karena tidak ada suatu peristiwa atau kejadian melainkan ilmu politik syariah menemukan untuknya hukum yang sesuai dengannya. Juga di antara dalil-dalil pertimbangan politik syariah adalah bahwa telah disaksikan dalam syariat Islam sendiri bahwa ia memperhatikan perbedaan keadaan dalam apa yang disyariatkannya sejak awal dari hukum-hukum; dan oleh karena itu diperketat dalam kesaksian apa yang tidak diperketat dalam periwayatan, artinya: dalam kesaksian para ahli fikih memperketat, dan mensyaratkan syarat-syarat tertentu, dan mensyaratkan keadilan pada saksi dan sebagainya, tetapi mereka tidak mensyaratkan itu dalam hal periwayatan, yaitu: dalam hal pemberitaan.
Jadi ia memperhatikan kondisi-kondisi maka disyaratkan pada yang pertama -yaitu kesaksian- apa yang tidak disyaratkan pada yang kedua -yaitu periwayatan- mengapa? Karena apa yang biasanya ada di antara manusia berupa persaingan – artinya: mengapa disyaratkan pada yang pertama, dan disyaratkan pada kesaksian syarat-syarat yang sangat cermat, dan syarat-syarat yang sangat sulit, sehingga kita menerima kesaksian saksi? Kami katakan: karena apa yang biasanya ada di antara manusia berupa persaingan, dan permusuhan yang mungkin mendorong pemiliknya kepada kesaksian, walaupun tanpa kebenaran. Dan oleh karena itu disyaratkan pada kesaksian zina apa yang tidak disyaratkan pada pembunuhan.
Dalam kesaksian zina harus ada empat orang saksi -sebagaimana diputuskan oleh para ahli fikih- berdasarkan ajaran Al-Quran Al-Karim. Adapun berkaitan dengan kesaksian pembunuhan; maka cukup di dalamnya dengan dua orang saksi saja. Sebab itu adalah bahwa syariat sesungguhnya memperhatikan kondisi-kondisi manusia, dan memperhatikan kondisi-kondisi manusia, dan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada manusia. Dan ini menjadi bukti pertimbangan politik syariah.
Juga di antara dalil-dalil pertimbangan syariat, atau pertimbangan hukum-hukum syariah, atau politik syariah adalah bahwa syariat juga memperhatikan perbedaan keadaan dengan apa yang diciptakannya berupa keringanan-keringanan -artinya: ada pada kita hukum-hukum keringanan, dan hukum-hukum azimah- maka syariat Islam memperbolehkan bagi sebagian manusia keringanan. Keringanan-keringanan ini sebenarnya bertentangan dengan azimah -artinya: dengan hukum asli. Syariat Islam meringankan bagi manusia, dan memperbolehkan bagi mereka keringanan-keringanan karena kebutuhan manusia, dan karena meringankan bagi manusia; dan oleh karena itu kita dapati Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa” (Surat Al-Baqarah, sebagian dari ayat: 185). Namun kita dapati bahwa manusia jika sedang bepergian, maka dalam keadaan ini kita dapati bahwa syariat Islam memperbolehkan bagi musafir berbuka pada siang hari Ramadhan. Maka jika puasa wajib baginya namun syariat memberi keringanan baginya, dan memperbolehkan baginya berbuka, sedangkan ia musafir.
Maka syariat Islam ketika meringankan, dan ketika memberi keringanan baginya dalam itu mengapa? Melakukan itu karena menjaga musafir ini; karena safar di dalamnya ada kesulitan, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Safar adalah sepotong dari azab.”
Maka jadi syariat Islam dengan pensyariatannya terhadap keringanan-keringanan; ini menunjukkan bahwa ia memperhatikan kemaslahatan manusia, dan memperhatikan meringankan bagi mereka, dan meringankan bagi manusia, dan memudahkan bagi mereka, dan mengangkat kesulitan dari mereka sesungguhnya masuk ke dalam ilmu politik syariah.
Di antara dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa siyasah syar’iyah (politik syariah) harus dipertimbangkan dan kita wajib mengambilnya adalah bahwa kondisi manusia pada masa-masa akhir ini telah berubah dari kondisi mereka pada awal Islam. Kerusakan telah merebak, dan penyakit-penyakit sosial telah menyebar di berbagai umat yang memerlukan berbagai jenis pengobatan yang cocok untuk umat-umat tersebut dan sesuai dengan kondisi serta kesiapan mereka, agar lebih berhasil dalam menghilangkan kerusakan dan penyakit-penyakit tersebut, dengan syarat tidak bertentangan dengan pokok-pokok Islam.
Oleh karena itu, para ulama—dalam bab kesaksian—mengatakan: apabila di suatu negeri tidak ditemukan selain orang-orang yang tidak adil, maka yang ditegakkan untuk kesaksian adalah orang yang paling baik dan paling sedikit kefasikannya. Hal yang serupa juga dikatakan tentang hakim dan lainnya, agar kepentingan-kepentingan tidak sia-sia, dan hak-hak serta hukum-hukum tidak terhenti.
Makna dari hal ini adalah: apabila para fuqaha (ahli fikih) telah mensyaratkan dalam kesaksian bahwa saksi-saksi harus adil, bahkan sebagian fuqaha tidak cukup dengan terwujudnya keadilan lahiriah atau keadilan yang tampak ini, melainkan mengatakan: harus ada penelitian terhadap hal-hal yang tersembunyi. Oleh karena itu, terdapat sistem yang disebut: sistem muzakki (pemberi rekomendasi) di sisi hakim. Tugas para muzakki ini adalah hakim bertanya kepada mereka tentang keadaan saksi tersebut. Mereka meneliti hal-hal tersembunyi yang berkaitan dengan saksi ini. Apabila para muzakki berkata: dia tidak layak untuk kesaksian, meskipun memiliki keadilan yang tampak, maka dalam keadaan ini kesaksiannya tidak diterima.
Kesimpulannya: para fuqaha sangat ketat dalam masalah kesaksian dan mensyaratkan—dan mereka semua mensyaratkan hal ini—bahwa saksi harus adil. Hal ini diambil dari Kitabullah Tabaraka wa Ta’ala, karena Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kalian” (Surat Al-Baqarah, ayat 282).
Oleh karena itu, para fuqaha berkata: keadilan dalam hal ini harus ada. Namun dengan perkembangan zaman, dan menjauhnya manusia dari pengawasan agama, serta sedikitnya pengawasan agama pada mereka—yaitu bahwa kita mungkin tidak menemukan orang yang menjadi saksi dan berada pada tingkat keadilan yang tinggi sebagaimana diminta oleh para fuqaha dan mereka nyatakan—maka apa yang harus dilakukan? Apakah hak-hak dibiarkan terhenti dan tidak menerima kesaksian? Apakah hakim tidak mengambil dalil pembuktian ini yaitu kesaksian, yang datang setelah pengakuan, ataukah apa yang kita lakukan? Apakah hak-hak dibiarkan terhenti ataukah kita, sejalan dengan kondisi yang telah dicapai manusia, mengambil perkara yang pertengahan, yaitu kita menerima kesaksian orang-orang yang tidak adil ini, tetapi kita memilih yang paling sedikit kerusakannya dan paling sedikit kefasikannya di antara mereka.
Sesungguhnya siyasah syar’iyah yang bijaksana mengatakan: kita mengambil kesaksian orang-orang ini yang belum mencapai tahap keadilan sempurna, karena dibolehkan dalam kondisi-kondisi di mana keadilan hampir tidak ada untuk mengambil yang paling sedikit kefasikannya dan paling sedikit kefasikannya, agar bersaksi di hadapan hakim. Hakim mengambil kesaksian ini dan mengeluarkan putusannya berdasarkan kesaksian tersebut. Hal-hal ini, atau pendapat bahwa dibolehkan menerima kesaksian orang yang tidak adil, yang membuat kita mengatakan demikian adalah siyasah syar’iyah. Namun jika kita berjalan dengan kaidah-kaidah umum dan dengan nash-nash para fuqaha, maka kita tidak akan menerima kesaksian orang yang tidak adil. Tetapi siyasah syar’iyah mengatakan kepada kita: bahwa kemaslahatan manusia adalah agar kita tidak menutup pintu kesaksian, tidak menutup sarana penting ini dari sarana-sarana pembuktian, yaitu kesaksian. Oleh karena itu, kita mengambil kesaksian orang yang tidak adil, tetapi kita memilih siapa yang paling sedikit kerusakannya dan siapa yang paling sedikit kefasikannya berkaitan dengan masalah kesaksian. Perkara ini juga diputuskan berkaitan dengan peradilan.
Para fuqaha mensyaratkan syarat-syarat yang banyak berkaitan dengan hakim, dan yang utama adalah keadilan. Apabila keadilan disyaratkan pada saksi, maka dari pintu yang lebih utama, keadilan diminta dan lebih penting lagi pada hakim. Namun, kita sampai pada—jika kita anggap bahwa kondisi manusia telah mencapai titik di mana kita tidak menemukan hakim yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan para fuqaha. Para fuqaha—misalnya—kebanyakan mereka mensyaratkan bahwa hakim harus mujtahid. Namun jika kita sampai pada tahap di mana kita menemukan bahwa manusia telah sampai pada tingkat di mana kita tidak menemukan hakim yang mujtahid, maka apa yang harus dilakukan dalam keadaan ini? Apakah kita menutup pintu peradilan, ataukah kita mengangkat hakim meskipun dia bukan mujtahid? Demikian juga jika kita tidak menemukan orang yang adil dan keadilan tidak terwujud pada seseorang untuk menjadi hakim, maka apa yang harus dilakukan dalam keadaan ini? Apakah kita menahan diri dari mengangkat hakim dan kepentingan-kepentingan manusia terhenti, dan perselisihan-perselisihan di antara manusia tidak diputuskan, ataukah kita memilih yang paling sedikit kerusakannya? Dan memilih yang paling baik dari yang ada?
Sesungguhnya siyasah syar’iyah di sini tampak dan mengatakan: kita mengambil yang paling baik dari yang ada. Apabila syarat-syarat tidak terwujud pada seseorang, maka kita mengambil orang yang memiliki syarat-syarat ini paling banyak. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia, agar kehidupan berjalan, agar fungsi peradilan di masyarakat Muslim tidak terhenti, karena peradilan sangat penting dan kita tidak dapat membayangkan masyarakat yang tidak memiliki peradilan yang memutuskan perselisihan-perselisihan manusia.
Jadi, siyasah syar’iyah ikut campur di sini dan mengatakan: kita memilih yang paling baik kemudian yang lebih baik, baik berkaitan dengan kesaksian maupun berkaitan dengan hakim, agar kepentingan-kepentingan manusia tidak terhenti. Mungkin hal ini telah diketahui atau telah dipahami oleh ulama Hanafiyah yang tidak mensyaratkan pada hakim bahwa dia harus mujtahid—yaitu: kita jika melihat ijtihad: apakah itu syarat pada hakim atau tidak? Demi Allah, kita dapati mayoritas fuqaha mensyaratkan pada hakim bahwa dia harus mujtahid—yaitu: telah mencapai tingkat ijtihad. Namun kelompok Hanafiyah tidak mensyaratkan itu dan membolehkan peradilan bagi hakim muqallid (peniru) yang mengikuti mazhab tertentu.
Ini juga seperti sejenis siyasah syar’iyah dari kelompok Hanafiyah. Oleh karena itu, kita sampai pada tingkat bahwa harus ada hakim, harus ada saksi meskipun syarat-syarat tidak terwujud. Yang mengatakan demikian adalah siyasah syar’iyah, siyasah syar’iyah yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan manusia dan tidak menutup pintu peradilan di masyarakat Muslim.
Di antara dalil-dalil lain untuk mempertimbangkan siyasah syar’iyah adalah bahwa hukum-hukum siyasah syar’iyah secara keseluruhan kembali pada kaidah kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari manusia. Secara keseluruhan dan secara umum kembali pada kaidah kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari manusia, serta prinsip hukum dengan keadilan, saling berwasiat dengan kebaikan, dan bahwa urusan kaum Muslimin di antara mereka adalah musyawarah yang mereka kelola dengan apa yang mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka dan menjamin kebahagiaan mereka. Prinsip-prinsip ini muhkam (pasti) dan telah ditetapkan, ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah untuk memperhatikannya.
Dari Al-Qur’an, firman Allah Ta’ala: “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian” (Surat Al-Baqarah, ayat 185). Dan firman-Nya Ta’ala: “Allah tidak hendak menjadikan kesulitan atas kalian” (Surat Al-Ma’idah, ayat 6). Dan firman-Nya Ta’ala: “Dan Dia tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam agama” (Surat Al-Hajj, ayat 78). Dan firman-Nya Ta’ala: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil” (Surat An-Nisa’, ayat 58). Dan firman-Nya Ta’ala: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya” (Surat Asy-Syura, ayat 38).
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengumpulkan seluruh agama dalam nasihat, maka beliau bersabda: “Agama adalah nasihat—tiga kali—para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, untuk siapa? Beliau menjawab: Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk para imam kaum Muslimin, dan kaum Muslimin pada umumnya.” Hadits ini terdapat dalam (Sunan At-Tirmidzi Cetakan Pertama 1419 H – 1999 M Penerbit Dar Al-Hadits Kairo Juz 4 hal. 99, Bab tentang Nasihat).
Pemeliharaan prinsip-prinsip umum ini yang mewujudkan musyawarah dan keadilan di antara manusia serta menghilangkan kesulitan dari manusia, sesungguhnya yang mewujudkannya adalah ilmu siyasah syar’iyah. Karena telah jelas bagi kita bahwa menghilangkan kesulitan dari manusia dan memperhatikan kondisi manusia adalah yang dibahas oleh ilmu siyasah syar’iyah. Demikian juga kepentingan-kepentingan manusia dibahas oleh ilmu siyasah syar’iyah. Kepentingan manusia dalam menetapkan hukum dengan adil, dan kepentingan manusia agar ada musyawarah: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu)”, “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”.
Siapa yang mengatur musyawarah? Benar bahwa Allah Tabaraka wa Ta’ala memerintahkan kita untuk melaksanakan musyawarah: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu)” (Surat Ali ‘Imran, ayat 159). Dan berfirman: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”. Tetapi cara bermusyawarah, apa sarana yang dapat mewujudkan musyawarah? Ini Al-Qur’an Al-Karim serahkan kepada ilmu siyasah syar’iyah.
Ilmu siyasah syar’iyah-lah yang mewujudkan hal-hal ini. Jika ada kaidah menghilangkan kesulitan dari manusia, maka cara mewujudkan kaidah ini, yang menjelaskan kepada kita cara mewujudkan kaidah ini dan menerapkannya pada manusia adalah ilmu siyasah syar’iyah. Jika Al-Qur’an Al-Karim memerintahkan kita untuk menetapkan hukum dengan adil, maka bagaimana keadilan terwujud di antara manusia? Dan apa sarana-sarana yang mewujudkan keadilan ini? Semua perkara ini dilakukan oleh ilmu siyasah syar’iyah. Demikian juga jika Allah Tabaraka wa Ta’ala memerintahkan kita dengan musyawarah dengan firman-Nya: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”, dan firman-Nya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu)” (Surat Ali ‘Imran, ayat 159). Ini adalah prinsipnya—prinsip musyawarah di antara kaum Muslimin. Tetapi bagaimana musyawarah terwujud? Dan apa sarana-sarana yang mewujudkan musyawarah ini? Dan apa cara-cara yang dilakukan musyawarah dengannya? Ini diserahkan kepada ilmu siyasah syar’iyah. Mengapa diserahkan kepada ilmu siyasah syar’iyah? Karena ilmu siyasah syar’iyah bekerja untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan manusia sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai dengan lingkungan mereka, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berubah dengan perubahan zaman.
Jadi, siyasah syar’iyah-lah yang mewujudkan prinsip-prinsip ini untuk kita, dari menetapkan hukum dengan adil, dari musyawarah, dan dari menghilangkan kesulitan dan kesukaran dari manusia. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan siyasah syar’iyah seolah-olah berdiri dengan nasihat untuk kaum Muslimin ketika beliau bersabda: “Agama adalah nasihat.” Tetapi siapa yang menasihati? Siapa yang menasihati kaum Muslimin, kaum Muslimin pada umumnya, dan para imam kaum Muslimin? Seperti yang telah kita katakan—kaidahnya: siyasah syar’iyah, atau ilmu siyasah syar’iyah-lah yang menjelaskan hal itu.
Pemeliharaan prinsip-prinsip ini—seperti yang telah kita katakan—prinsip-prinsip umum—seperti yang telah kita katakan—yang dibawa oleh Islam adalah prinsip-prinsip umum. Namun rincian-rinciannya, penguasaan pemahamannya, dan pengetahuan tentang tempat-tempat prinsip-prinsip ini mampu membukakan kepada manusia pintu-pintu luas yang dapat dimasuki oleh setiap orang yang memiliki urusan dalam mengatur umat, dan orang yang peduli agar urusan-urusan mereka berdiri di atas kaidah-kaidah kebaikan dan petunjuk.
Kesimpulan perkataan dalam dalil ini—yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan ilmu siyasah syar’iyah—adalah bahwa kaidah-kaidah umum ini—seperti yang telah kita katakan—baik berkaitan dengan menetapkan hukum dengan adil di antara manusia dan mengatur peradilan, atau melaksanakan musyawarah di kalangan kaum Muslimin, atau menghilangkan kesulitan dan kemudahan dari manusia, prinsip-prinsip umum ini yang mengaturnya adalah ilmu siyasah syar’iyah. Mengapa tidak disebutkan caranya dalam Al-Qur’an dan Sunnah?
Seperti yang telah kita katakan—karena perkara-perkara ini berubah dan berganti dari masa ke masa dan dari kondisi ke kondisi. Oleh karena itu, hal yang paling sesuai adalah ilmu siyasah syar’iyah yang mengatur, merinci, dan menerapkannya. Ini maknanya bahwa Syariat Islam sesungguhnya cocok untuk diterapkan di setiap zaman dan di setiap tempat, dan cocok untuk menghadirkan solusi terhadap masalah-masalah yang baru terjadi dan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Siapa yang melakukan itu dan mampu melakukannya? Sesungguhnya adalah ilmu siyasah syar’iyah.
Pertimbangan Mashalih Mursalah sebagai Dalil untuk Mempertimbangkan Hukum-Hukum Siyasah Syar’iyah
Di antara dalil-dalil lain untuk mempertimbangkan siyasah syar’iyah adalah mashalih mursalah (kemaslahatan yang tidak terikat)—yaitu: pada kita termasuk dari perkara-perkara yang dibicarakan para fuqaha dalam ilmu ushul fikih, yaitu mashalih mursalah. Mashalih mursalah termasuk di antara dalil-dalil yang diperselisihkan di antara para fuqaha: apakah itu dalil dari dalil-dalil hukum atau bukan dalil dari dalil-dalil hukum?
Karena ketika kita membahas dalam ushul fikih, pada kita ada dalil-dalil yang disepakati, yaitu: Al-Qur’an, Sunnah, ijma’ (konsensus), dan qiyas (analogi). Ini adalah dalil-dalil yang disepakati di antara para fuqaha. Namun ada dalil-dalil yang diperselisihkan di dalamnya yang sangat banyak, di antaranya: istihsan (juristic preference), istishab (presumption of continuity), syar’u man qablana (hukum syariat sebelum kita), dan perkara-perkara lain. Di antaranya juga: mashalih mursalah.
Hubungan mashalih mursalah dengan siyasah syar’iyah adalah hubungan yang erat, tampak dalam apa yang akan kita katakan sekarang: Mashalih mursalah adalah yang tidak ada dalil dari syara’ yang menunjukkan pertimbangannya atau pembatalannya. Makna mashalih mursalah adalah: kita—peristiwa tertentu—tidak menemukan nash dari Al-Qur’an tentang pertimbangan hal-hal ini atau ketidakpertimbangannya. Tidak ada nash baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah yang menunjukkan kepada kita tentang ketidakpertimbangan kemaslahatan ini atau ketidakpertimbangannya. Oleh karena itu, dinamakan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak terikat), karena ia mutlak dari dalil. Mengapa dinamakan maslahah mursalah? Mereka berkata: karena ia mutlak dari dalil pertimbangannya atau pembatalannya—yaitu: tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dipertimbangkan secara syar’i, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dibatalkan secara syar’i.
Berdasarkan ini, sesungguhnya maslahah mursalah tidak terwujud kecuali pada peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan oleh pembuat syariat, dan tidak memiliki asal tertentu yang dapat diqiyaskan kepadanya, dan terwujud padanya makna yang sesuai. Makna yang sesuai adalah apa yang mendatangkan manfaat kepada manusia atau menolak bahaya darinya.
Saya berkata: Dan terwujud di dalamnya makna yang sesuai yang layak menjadi landasan bagi hukum syariat. Menurut pendapat yang lebih kuat, maslahah mursalah dianggap sebagai salah satu sumber legislasi syariah -sebagaimana telah kami katakan-. Maslahah mursalah ini termasuk dalil-dalil syariat yang diperselisihkan. Sebagian ulama fikih tidak mengambil maslahah mursalah ini dan tidak menganggapnya sebagai dalil dari dalil-dalil hukum. Sebagian ulama fikih lainnya mengambil maslahah mursalah ini dan menganggapnya sebagai dalil dari dalil-dalil syariat.
Mereka yang berpendapat bahwa maslahah mursalah merupakan dalil dari dalil-dalil syariat dan menganggap maslahah mursalah ini, sesungguhnya mereka sedang menerapkan prinsip siyasah syariah. Karena siyasah (kebijakan) ada di mana ada kemaslahatan. Jika ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka ada siyasah syariah, dan diambillah hukum-hukum siyasah syariah tersebut. Kami katakan: Menurut pendapat yang lebih kuat, maslahah mursalah dianggap sebagai salah satu sumber legislasi syariah. Karena orang yang menelusuri fikih para imam akan mendapati mereka mengambil maslahah mursalah sebagai salah satu cara istidlal (pengambilan dalil) dari nash-nash, dan tidak ada yang menolak pengambilan dengan cara ini, hanya saja mereka menyebutnya dengan nama-nama lain selain istidlal mursalah atau maslahah mursalah. Artinya, masalah ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih -sebagaimana telah kami katakan-. Sebagian mengambil maslahah mursalah ini, dan sebagian tidak mengambilnya.
Di sisi lain, tidak ada seorang pun dari mereka -yaitu dari para ulama fikih- yang meninggalkan nash-nash syariat demi maslahah. Namun diterapkan kaidah-kaidah tarjih (penguatan) antara dalil-dalil ketika maslahah bertentangan dengan nash syariat. Artinya, kesimpulan dalam hal ini adalah: bahwa maslahah-maslahah ini -yang tidak ada dalil dari syariat yang menunjukkan dianggapnya, atau tidak ada dalil yang menunjukkan dibatalkannya- saya katakan: tidak dipandang menurut kesepakatan para ulama fikih terhadap maslahah ini jika ada nash syariat yang menyelisihinya. Karena jika ada nash syariat yang menyelisihinya, berarti maslahah tersebut adalah maslahah yang dibatalkan, maslahah yang tidak diakui secara syariat.
Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat tentang maslahah mursalah ketika tidak ada nash yang menunjukkan pembatalannya. Karena itu, jika maslahah ini bertentangan dengan nash syariat dari Al-Quran, atau dari Sunnah, atau dari ijma’, maka dalam hal ini tidak disebut maslahah, bahkan ia adalah maslahah yang dibatalkan -artinya: tidak diakui secara syariat-. Oleh karena itu, maslahah yang dijadikan hujah oleh para ulama fikih, atau para imam yang berpendapat untuk mengambilnya, mereka katakan: adalah maslahah yang sesuai -yaitu yang disaksikan oleh nash-nash secara umum-, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip umum fikih Islam. Maslahah ini haruslah -mereka yang berpendapat untuk mengambil maslahah ini mensyaratkan bahwa maslahah itu harus disaksikan oleh nash-nash secara umum-, artinya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, mereka menetapkan syarat-syarat untuknya. Apa saja syarat-syarat maslahah ini agar kita bisa mengambilnya?
Mereka berkata: Disyaratkan dalam maslahah yang diakui sebagai sumber dari sumber-sumber legislasi syariah hal-hal berikut:
Syarat pertama: Tidak bertentangan dengan hukum yang tetap berdasarkan nash atau ijma’. Karena jika terjadi pertentangan, maka dalam hal ini dianggap termasuk maslahah yang dibatalkan, yaitu yang dibatalkan oleh pembuat syariat (asy-Syari’). Contohnya: mewajibkan puasa dua bulan dalam kaffarah jimak (bersetubuh) di siang hari Ramadhan bagi orang yang memiliki budak. Karena kepemilikannya tidak akan membuatnya jera dengan kewajiban memerdekakan budak sebagai kaffarah berbuka puasa, karena hal itu mudah baginya. Hal ini sesuai -yaitu mewajibkan puasa dua bulan untuk kaffarah jimak tanpa memerdekakan budak-. Mereka katakan: hal itu sesuai untuk mewajibkan puasa kepadanya sebagai bentuk penjeraan maksimal agar tidak melampiaskan syahwat kemaluannya dengan melanggar kehormatan puasa. Ini termasuk maslahah yang dibatalkan. Artinya: seseorang yang kaya memiliki budak -para budak itu sekarang sudah tidak ada lagi-. Dulu termasuk kaffarah dalam fikih Islam adalah ketika seseorang misalnya bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadhan, mereka katakan: ia wajib mengqadha dan membayar kaffarah. Apa yang dimaksud kaffarah? Mereka katakan: memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka puasa dua bulan. Jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Artinya, dimulai dengan apa? Dimulai dengan memerdekakan budak.
Sebagian ulama fikih berkata, atau sebagian yang mempertimbangkan maslahah berkata: Lebih baik bagi orang kaya ini yang memiliki para budak, yang telah bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadhan, dan dengan itu ia melanggar firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa” (Surat Al-Baqarah, sebagian dari ayat 185) sebagai hukuman baginya. Mereka katakan: ia mengqadha hari tersebut, kemudian setelah itu ia wajib membayar kaffarah.
Apa itu kaffarah? Al-Quran menyebutkan bahwa kaffarah dimulai terlebih dahulu -kaffarah di sini bertingkat-, yaitu kita mulai dengan memerdekakan budak. Sebagian ulama fikih mempertimbangkan masalah ini dan berkata: Jika kita wajibkan kepadanya memerdekakan budak, ia tidak akan terpengaruh dengan itu. Ia orang kaya dan orang berada, memiliki banyak budak. Ketika kita katakan kepadanya: merdekakanlah budak, ini adalah perkara yang sangat ringan baginya. Betapa banyaknya budak yang ia miliki. Dengan demikian, ia tidak terpengaruh dengan hukum ini atau dengan hukuman ini. Oleh karena itu, sebagian ulama fikih berkata apa? Mereka katakan: kita wajibkan kepadanya puasa dua bulan -yaitu sebagai pengganti memerdekakan budak-. Tidak, kita katakan kepadanya: kamu wajib puasa dua bulan. Mengapa? Mereka katakan: Karena puasa dua bulan dalam hal ini akan mengakibatkan hukuman, yaitu ia akan merasakan hukuman tersebut, sehingga ia tidak akan mengulanginya lagi.
Tetapi pendapat tentu saja -pendapat seluruh ulama fikih- menolak hal ini dan berkata: Mereka yang menginginkan orang kaya yang memiliki budak ini untuk berpuasa dua bulan sebagai pengganti memerdekakan budak, mereka katakan bahwa maslahah menghendaki demikian, karena ia telah melanggar kehormatan puasa, dan maslahah menghendaki agar kita wajibkan kepadanya puasa dua bulan, bukan memerdekakan budak. Karena yang akan berpengaruh padanya dan menjadi hukuman yang efektif baginya adalah mewajibkan kepadanya puasa dua bulan, bukan memerdekakan budak.
Namun hal ini dibantah. Kami katakan kepada mereka: Maslahah yang kalian pertimbangkan ini adalah maslahah yang dibatalkan. Dibatalkan mengapa? Mereka katakan: Karena bertentangan dengan nash dari nash-nash Al-Quran. Al-Quran al-Karim menjelaskan bahwa orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadhan wajib qadha dan kaffarah, dan kaffarah dimulai -sebagaimana telah kami katakan- bertingkat, dimulai dengan memerdekakan budak. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kita: kita mulai dengan memerdekakan budak, sedangkan kalian berkata: Maslahah menghendaki agar dikatakan, atau dihukum dengan puasa dua bulan berturut-turut, atau perkataan kalian puasa dua bulan sebagai pengganti memerdekakan budak. Jadi maslahah yang kalian pertimbangkan ini adalah maslahah yang dibatalkan, tidak diakui sama sekali. Dan kami mensyaratkan dalam maslahah agar tidak bertentangan dengan nash dari nash-nash Al-Quran atau Sunnah.
Ini adalah syarat pertama agar maslahah ini dapat diamalkan. Kami katakan: dibatalkan secara syariat, karena pilihan-pilihannya bertingkat -sebagaimana telah kami katakan-, yaitu memerdekakan, kemudian puasa, kemudian memberi makan.
Juga mengenai syarat-syarat pengamalan maslahah mursalah ini: Maslahah harus masuk dalam maqashid asy-syariah (tujuan-tujuan syariah). Artinya: jika kita ingin mengakui maslahah mursalah ini, atau mereka yang berpendapat dengannya, mereka katakan: dari syarat-syaratnya -sebagaimana telah kami katakan- adalah tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan dengan nash atau ijma’.
Syarat kedua untuk mengamalkan maslahah ini: Maslahah harus masuk dalam maqashid asy-syariah, dan maqashid asy-syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Syariah datang untuk menjaga lima hal yang dharuriyah (pokok), atau lima kulliyat (prinsip universal). Lima perkara ini, atau lima kulliyat ini adalah: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Dan sebagai catatan: semua syariah datang untuk menjaga lima kulliyat ini. Maslahah tidak akan diakui, tidak akan dianggap sah, dan tidak akan diakui -menurut mereka yang mengakuinya- kecuali jika berputar di sekitar lima kulliyat ini, atau dimaksudkan untuk menjaga salah satu dari lima kulliyat ini, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.
Setiap maslahah yang berputar dalam orbit syariah ini -yaitu berputar di sekitar menjaga lima perkara ini, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta- semuanya- maslahah yang berputar dalam orbit syariah ini adalah maslahah yang diakui secara syariat. Dan setiap maslahah yang tidak memiliki dalil kecuali akal saja, maka ia ditolak secara syariat.
Dengan kata lain: Maslahah harus bersifat dharuriyah (darurat), qath’iyah (pasti), dan kulliyah (universal). Dharuriyah adalah yang termasuk salah satu dari lima hal dharuriyah -sebagaimana telah kami katakan-, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Artinya: jika tidak dimaksudkan untuk salah satu dari lima perkara ini, atau dimaksudkan untuk sesuatu selain menjaga salah satu dari lima perkara ini, maka tidak diakui. Juga disyaratkan bahwa ia harus qath’iyah. Qath’iyah adalah yang dipastikan terjadinya maslahah padanya. Adapun kulliyah adalah yang menghasilkan manfaat.
Kami berikan contoh untuk itu -agar maslahah ini diakui bahwa maslahah harus masuk dalam maqashid asy-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta-: Jika orang-orang kafir yang menyerang berlindung di balik tawanan kaum muslimin -yaitu mereka mengambil tawanan muslimin yang ada di sisi mereka dan datang ke negeri kita untuk menyerang atau membunuh kita. Berlindung di balik orang-orang kafir yang menyerang- artinya mereka menempatkan tawanan muslimin di barisan depan pasukan, sehingga jika kaum muslimin menyerang mereka, mereka akan menyerang tawanan muslimin tersebut. Ini adalah sistem tatarrus (berlindung di balik)-. Jika orang-orang kafir yang menyerang, yaitu yang menyerbu kita, berlindung di balik tawanan kaum muslimin, yaitu menempatkan tawanan muslimin di barisan depan pasukan, dan kita yakin bahwa jika kita tidak menyerang dan memerangi mereka, mereka akan membinasakan kaum muslimin yang dijadikan perisai dan lainnya. Artinya: jika kita menahan diri dari tatarrus, mereka akan menyerang kita, menguasai negeri kita, dan membunuh seluruh kaum muslimin, termasuk tatarrus -yaitu termasuk tawanan yang bersama mereka dan yang dijadikan perisai-. Dan jika kita menyerang tatarrus, kita akan membunuh seorang muslim tanpa dosa yang keluar dari dirinya.
Maka membunuh tatarrus -dalam keadaan seperti ini adalah maslahah- mursalah, karena tidak pernah dijumpai -dalam syariat- kebolehan membunuh seorang muslim tanpa dosa, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya membunuhnya ketika hal itu mengandung maslahah umum bagi kaum muslimin. Namun ia adalah maslahah dharuriyah, qath’iyah, dan kulliyah. Oleh karena itu, sah untuk diakui, yaitu: boleh ijtihad seorang mujtahid sampai kepada pendapat bahwa: tawanan ini terbunuh dalam segala keadaan. Maka menjaga seluruh kaum muslimin lebih dekat kepada maqshud (tujuan) syariat daripada menjaga seorang muslim saja.
Makna maslahah tersebut -yaitu jika orang-orang kafir ini berlindung di balik kaum muslimin -tawanan yang ada di sisi mereka-, dan mereka melakukan itu karena mereka tahu bahwa kaum muslimin tidak akan membunuh sesama muslimin-. Dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak menyerang orang-orang kafir karena khawatir terhadap kaum muslimin yang dijadikan perisai, dan dalam hal ini jika kita tidak menyerang mereka, mereka akan menguasai kita dan membunuh kita, dan juga membunuh mereka yang dijadikan perisai? Apa solusinya dalam hal ini? Apakah kita menjaga kehidupan tatarrus dari kaum muslimin, yang merupakan maslahah khusus, ataukah kita memandang maslahah umum seluruh kaum muslimin? Mereka katakan: Demi Allah, maslahah menghendaki -dalam hal ini- agar kita berkorban dengan tatarrus ini, atau dengan sebagian kaum muslimin ini, atau tawanan dari kaum muslimin -yang bersama mereka-. Kita berkorban dengannya demi apa? Demi maslahah umum.
Dan ini memiliki pendukung dalam kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu, kami katakan: Demi Allah, dharar (bahaya) khusus ditanggung demi menolak dharar umum. Dan maknanya: bahwa maslahah umum didahulukan atas maslahah khusus. Artinya: jika dua mafsadah (kerusakan) bertentangan, diperhatikan yang paling besar dengan melakukan yang paling ringan. Ini adalah kaidah-kaidah fikih.
Kaidah-kaidah fikih harus kita atur atau kita terapkan dalam hal ini. Kami katakan: Jika kita membunuh orang-orang kafir bersama tatarrus -muslim yang bersama mereka-, dalam hal ini ada dharar khusus terhadap muslim ini yang kita bunuh, yang dijadikan perisai oleh orang-orang kafir. Namun kita mewujudkan maslahah umum, yaitu menjaga kaum muslimin lainnya dan menjaga negara Islam. Oleh karena itu, kita mengorbankan maslahah khusus ini, maslahah khusus yang diwakili untuk menjaga kehidupan tatarrus, demi maslahah umum, yaitu menjaga kaum muslimin lainnya dan menjaga negara kaum muslimin. Dan ini -sebagaimana telah kami katakan- didukung oleh kaidah-kaidah fikih yang dikenal, yaitu: kaidah fikih yang menyatakan: Jika dua mafsadah bertentangan, diperhatikan yang paling besar dengan melakukan yang paling ringan.
Dan juga maslahah umum didahulukan atas maslahah khusus. Ini adalah syarat-syarat terpenting yang dikatakan para ulama fikih. Namun sebenarnya Imam Malik meluaskan masalah ini dan berkata: Tidak wajib maslahah itu bersifat kulliyah, dharuriyah, dan qath’iyah. Beliau berkata: Yang penting ada maslahah. Jika ada maslahah umum ini, maka dalam hal ini didahulukan atas maslahah khusus. Dan karena syariat Islam menjadikan maslahah mursalah sebagai salah satu sumber legislasi Islam -sebagaimana telah kami katakan-, karena ada sebagian ulama fikih yang berpendapat bahwa maslahah mursalah itu layak menjadi dalil dalam legislasi Islam. Kami katakan: Karena syariat Islam menjadikan maslahah mursalah sebagai salah satu sumber legislasi Islam, maka ini berarti bahwa maslahah ini dapat mencakup kejadian-kejadian yang baru dan maslahah-maslahah yang tidak terbatas, yang tidak terjangkau oleh nash-nash, karena nash-nash itu terbatas, sedangkan yang terbatas tidak dapat memenuhi yang tidak terbatas.
Dan maslahah mursalah dapat menghadapi apa yang baru terjadi pada umat berupa kejadian-kejadian dan masalah-masalah baru. Artinya: maslahah mursalah yang dikatakan para ulama fikih, yang kami kuatkan dengan syarat-syarat yang dikatakan para ulama fikih, kami katakan: Mengambil maslahah mursalah ini berarti: akan mengakibatkan berbagai hal. Hal-hal ini adalah: bahwa semua kejadian dan peristiwa yang baru dalam kehidupan kaum muslimin kita pandang dengan perspektif maslahah bagi kaum muslimin. Jika kejadian-kejadian ini mengandung maslahah bagi kaum muslimin, kita harus memberikan hukum yang mewujudkan maslahah bagi kaum muslimin secara umum. Artinya: kita tidak memandang maslahah-maslahah khusus, tetapi kita memandang maslahah-maslahah umum. Sesungguhnya kejadian-kejadian dan peristiwa manusia itu terus diperbarui dan tidak terbatas. Namun kita memiliki Al-Quran dan Sunnah berupa nash-nash. Nash-nash Al-Quran dan nash-nash Sunnah itu terbatas dan terhitung. Namun kejadian-kejadian dan masalah-masalah baru yang terus terjadi dan ada setiap hari, ini tidak terbatas. Setiap hari terjadi hal-hal baru.
Misalnya, Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukum untuk masalah transplantasi organ -transplantasi organ manusia misalnya-, tidak menetapkan hukum untuk masalah kloning, baik kloning tumbuhan, hewan, maupun manusia. Apa yang harus kita lakukan terhadap perkara-perkara baru ini?
Benar, sebagaimana telah kami katakan: bahkan para ulama fikih kita -semoga Allah Tabaraka wa Ta’ala meridhai mereka- terdahulu tidak membahas masalah-masalah baru ini, tidak membahas kejadian-kejadian ini. Tidak ada pada zaman mereka transplantasi organ manusia, misalnya memindahkan ginjal seseorang -dari seseorang kepada orang lain-. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Apa hukum syariah dalam hal itu? Inilah peristiwa-peristiwa, inilah perkara-perkara baru, inilah masalah-masalah yang harus kita pandang, harus kita lihat dalam perspektif Islam dan dalam timbangan fikih Islam, dan kita berikan hukumnya.
Sebagaimana telah kami katakan: tidak ada nash baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun ijma’ tentang hukum perkara-perkara baru ini, seperti transplantasi organ manusia, atau hukum kloning -sebagaimana telah kami katakan- untuk pertanian, hewan, atau manusia. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Apakah jika kita hanya berdiri pada nash-nash, nash-nash Al-Quran dan nash-nash Sunnah, dan ingin mengambil hukum dari nash-nash ini, kita tidak akan menemukan nash tersebut. Mengapa? Karena -sebagaimana telah kami katakan- sesungguhnya nash-nash ini terbatas dan terhitung. Adapun peristiwa manusia, kejadian-kejadian, dan masalah-masalah baru, maka terus diperbaharui dan tidak terbatas. Maka ketika kita pergi kepada Al-Quran atau Sunnah, kita tidak akan menemukan hukum untuk masalah-masalah baru ini seperti transplantasi organ atau kloning. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita katakan: kita tidak tahu sesuatu? Apakah kita katakan: tidak ada hukum? Kita tidak bisa mengatakan: tidak ada hukum dalam Islam untuk masalah-masalah baru dan kejadian-kejadian baru ini. Karena jika kita mengatakan demikian, berarti kita mengatakan bahwa syariat kita kaku, tidak berkembang, dan tidak cocok untuk zaman dan tempat.
Namun Syariat Islam, ketika Allah Tabaraka Wataala menjadikannya sebagai syariat terakhir, Dia menghendaki agar syariat ini layak diterapkan di setiap zaman dan di setiap tempat, hingga Allah mewarisi bumi dan seisinya. Oleh karena itu, kita harus meneliti—sebagaimana telah kami katakan—tidak ada nash dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kejadian-kejadian baru ini, lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita beralih kepada ilmu siyasah syariah (politik syariah), yaitu ilmu siyasah syariah yang berdiri di atas perwujudan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita beralih kepada kaidah-kaidah umum, dan kita pasti akan menemukan hal-hal ini. Kita melihat, apakah hal-hal baru ini—seperti transplantasi organ manusia—mengandung kemaslahatan bagi manusia atau justru mengandung kemudaratan bagi mereka? Dari sudut pandang inilah kita ingin memberikan hukum.
Jadi, tolok ukurnya adalah kemaslahatan yang sedang kita bicarakan sekarang. Kita meninjau peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa baru lainnya, dan akan terus muncul peristiwa-peristiwa baru seiring perkembangan zaman. Kita menempatkannya dalam kerangka kemaslahatan dan kemudaratan. Apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan kemaslahatan di dalamnya lebih banyak daripada kemudaratan, maka kita perbolehkan. Dan apa yang mendatangkan kemudaratan bagi manusia, atau kemudaratan di dalamnya lebih banyak daripada kemaslahatan, maka kita cegah.
Jadi—sebagaimana telah kami katakan—dari sinilah muncul hukum al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan yang terlepas/tidak ada nash khususnya). Maka al-mashalih al-mursalah, ketika kita mengambilnya, ia mewujudkan bagi kita ilmu siyasah syariah. Artinya: al-mashalih al-mursalah menjadi tempat berlakunya hukum siyasah syariah, karena—sebagaimana telah kami katakan—siyasah syariah memperhatikan kemaslahatan manusia dalam urusan agama dan dunia. Oleh karena itu, al-mashalih al-mursalah sesungguhnya mengekspresikan siyasah syariah. Maka dari itu—sebagaimana telah kami katakan—jika kita tidak bersandar pada al-mashalih al-mursalah ini, artinya kita tidak akan mampu menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa baru dan masalah-masalah kontemporer dalam kehidupan manusia—sebagaimana telah kami katakan. Peristiwa-peristiwa ini kita hadapkan kepada prinsip-prinsip umum dalam Syariat Islam, kita hadapkan kepada siyasah syariah, kita hadapkan dari segi kemaslahatan dan kerusakan—sebagaimana telah kami katakan. Apa yang mengandung kemaslahatan, kita perbolehkan, dan apa yang mengandung kemudaratan, kita cegah.
Sebenarnya—di antara yang dikatakan tentang legalitas maslahat adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam perdebatan yang terjadi antara Ibnu Aqil Al-Hanbali dengan sebagian fuqaha (ahli fikih). Di dalamnya disebutkan—yaitu perdebatan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin Jilid keempat halaman 309, cetakan Dar al-Hadits Kairo.
Dalam perdebatan tersebut terdapat topik yang berkaitan dengan al-mashlahah al-mursalah, dan kami ingin menyampaikannya karena sesungguhnya di dalamnya terdapat maslahat, dan menunjukkan sejauh mana para fuqaha kita—semoga ridha Allah Tabaraka Wataala tercurah kepada mereka—memahami bahwa Syariat layak diterapkan di setiap zaman dan tempat, dan segala sesuatu yang mengarah kepada hal itu patut kita dukung dan kita ambil.
Sebagaimana telah kami katakan, Ibnu Taimiyah menyebutkan perdebatan yang terjadi antara Ibnu Aqil dengan sebagian fuqaha. Dalam perdebatan ini disebutkan, pihak lain—yaitu yang berdebat dengan Ibnu Aqil—berkata kepadanya: Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak. Yang berbicara dengan Ibnu Aqil berkata kepadanya: Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak. Maka Ibnu Aqil—seolah-olah ingin menjelaskan maksud siyasah kepadanya—berkata kepada Ibnu Aqil: “Siyasah adalah perbuatan-perbuatan yang dengannya manusia menjadi lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan—meskipun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkannya dan tidak ada wahyu yang turun tentangnya.”
Perhatikanlah hal ini—wahai pelajar laki-laki dan perempuan—perhatikanlah perkataan Ibnu Aqil ini. Inilah orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang baik. Inilah orang yang memahami Syariat dengan pemahaman yang baik, dan mengetahui bahwa kita harus menjadikannya layak untuk diterapkan di setiap zaman dan tempat, dan kita tidak boleh berdiri tidak berdaya di hadapan peristiwa-peristiwa baru. Ibnu Aqil menjawab pihak lain yang berkata kepadanya: Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak. Ia berkata kepadanya: “Siyasah adalah perbuatan-perbuatan yang dengannya manusia menjadi lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.” Dan ini—sebagaimana telah kami katakan—adalah al-mashalih al-mursalah yang melakukannya—sebagaimana telah kami katakan. Sekarang kita melihat peristiwa-peristiwa: apa yang mendatangkan kemaslahatan, kita perbolehkan, dan apa yang mendatangkan kemudaratan, kita cegah. Apa yang kemaslahatan di dalamnya lebih banyak daripada kerusakan, kita perbolehkan, dan apa yang kerusakan di dalamnya lebih banyak daripada kemaslahatan, kita cegah. Ibnu Aqil mendukung makna ini dengan perkataannya.
“Siyasah adalah perbuatan-perbuatan yang dengannya manusia menjadi lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkannya dan tidak ada wahyu yang turun tentangnya”—maksudnya: meskipun tidak ada nash dalam peristiwa ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah.
Jadi, bagaimana kita menyikapi mereka—yaitu suatu peristiwa yang terjadi tetapi kita tidak menemukan hukumnya, baik dalam Kitabullah maupun dalam Sunnah Rasulullah. Inilah maksud “tidak disyariatkan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam dan tidak turun wahyu tentangnya.” Lalu apa yang kita lakukan? Ibnu Aqil berkata: Kita hadapkan, kita tinjau dari sudut pandang kemaslahatan. Apa yang mendatangkan kemaslahatan, kita perbolehkan, dan apa yang tidak mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan kemudaratan, kita cegah. Ia berkata: “Meskipun Rasul shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkannya dan tidak turun wahyu tentangnya. Jika engkau maksudkan dengan perkataanmu”—ini Ibnu Aqil berkata kepada pihak lain yang berdebat dengannya—”jika engkau maksudkan dengan perkataanmu ‘tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak’—yaitu: tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh syarak—maka benar. Dan jika engkau maksudkan bahwa tidak ada siyasah kecuali yang diucapkan oleh syarak, maka keliru, dan ini adalah kesalahan terhadap perbuatan para Shahabat radiyallahu Tabaraka Wataala anhum.”
Jadi, Ibnu Aqil ingin mengatakan kepadanya: Jika kita maksudkan dengan kalimat “tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak,” apakah yang dimaksud dengan itu—yaitu: harus ada nash tentang hukumnya atau tidak?
Demi Allah, jika engkau maksudkan dengan perkataanmu: tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak—yaitu: tidak ada siyasah kecuali yang diucapkan oleh syarak, artinya yang ada nashnya dalam Al-Quran, atau Sunnah, atau Ijmak—ini adalah perkataan yang tidak bermanfaat, dan ini adalah perkataan yang tidak kita ambil sama sekali. Karena jika kita mengambil perkataan ini dengan makna ini, yaitu bahwa kita tidak mengambil sesuatu kecuali dari Al-Quran hanya jika ada nash tentangnya atau tentang hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah.
Sebagaimana telah kami katakan, artinya syariat kita akan menjadi kaku. Mengapa? Karena—sebagaimana telah kami katakan berulang kali—bahwa nash-nash syariat yang terwakili dalam Al-Quran dan Sunnah adalah terbatas dan terhingga, adapun peristiwa-peristiwa manusia dan masalah-masalah kontemporer tidak terbatas dan tidak terhingga. Oleh karena itu, jika kita mengatakan: tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak—yaitu yang diucapkan oleh syarak—maka ini akan mengakibatkan hal-hal yang sangat berbahaya, dan bahwa Syariat tidak layak diterapkan di setiap zaman dan di setiap tempat.
Tetapi jika kita maksudkan dengan perkataan kita “tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syarak”—yaitu: tidak ada siyasah jika bertentangan dengan syarak—maka ini boleh. Mengapa? Karena pertentangan artinya pertentangan umum dengan hukum-hukum Syariat. Dan setiap siyasah syariah harus berada dalam kerangka umum Islam—yaitu prinsip-prinsip umum, hukum-hukum umum, dan kaidah-kaidah kulliyah fikih Islam.
Jadi, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, kita ambil, dan tidak ada masalah di dalamnya. Adapun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, kita tidak mengambilnya. Dan bagaimana kita tahu bahwa ia bertentangan dengan prinsip-prinsip umum atau tidak? Sebagaimana telah kami katakan: kita tinjau dari segi kemaslahatan dan tidak adanya kemaslahatan. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, kita perbolehkan, dan jika di dalamnya ada kemudaratan, kita cegah.
Dan kita menyimpulkan dari ini bahwa tidak adanya dalil dari nash-nash yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hukum-hukum siyasah syariah secara terperinci tidaklah membahayakan dan tidak menghalangi siyasah syariah untuk menjadi syar’i. Artinya—sebagaimana telah kami katakan—tidak wajib maslahat itu harus ada nash tentang hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah, tetapi cukup saja jika ia tercakup dalam siyasah syariah, atau dalam prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum umum Syariat Islam. Selama peristiwa-peristiwa ini—sebagaimana telah kami katakan—sesuai dengan dhawabith (ketentuan-ketentuan) umum dan hukum-hukum syariah, maka kita mengambilnya.
Adapun yang membahayakan dan menghalangi dari itu adalah bahwa hukum-hukum siyasah syariah tersebut bertentangan secara nyata dengan nash dari nash-nash terperinci.
Saya katakan: artinya, hukum-hukum siyasah syariah dapat diambil dan kita ambil selama tidak bertentangan dengan nash terperinci, selama tidak bertentangan dengan nash dari nash-nash Al-Quran, atau nash dari nash-nash Sunnah, atau dari Ijmak, maka kita mengambilnya.
Tetapi jika hukum-hukum yang dikatakan oleh siyasah syariah ini bertentangan secara nyata dengan nash dari nash-nash terperinci—dan yang kami maksud dengan nash-nash terperinci adalah hukum-hukum terperinci yang dibicarakan oleh ilmu ushul fikih, yaitu dalil-dalil ijmali (global) seperti: Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas—maka jika hukum-hukum siyasah syariah ini bertentangan dengan hukum dari hukum-hukum yang dinashkan oleh Al-Quran, atau hukum-hukum yang dinashkan oleh Sunnah, atau hukum-hukum yang dinashkan oleh Ijmak, atau Qiyas, dalam hal ini kita tidak mengambilnya, karena ia tidak dianggap sebagai siyasah syariah dalam masalah ini.
Kita katakan: Apabila terbebas dari pertentangan ini, dan sejalan dengan ruh Syariat dan prinsip-prinsip umumnya, maka ia adalah sistem Islam dan siyasah syariah. Artinya: meskipun ada pertentangan, tetapi bukan pertentangan yang nyata. Kita katakan: Jika ada pertentangan yang nyata dan benturan yang nyata dengan nash dari nash-nash Al-Quran, atau Sunnah, atau Ijmak, atau benturan dengan Qiyas, kita tidak mengambilnya.
Tetapi misalkan ada pertentangan, namun hanya pertentangan zhahiri (lahiriah)—yaitu dalam penampakan saja, tetapi ketika kita cermati dan kita renungkan, kita dapati sesungguhnya tidak ada pertentangan. Dan ini tentu saja—sebagaimana telah kami katakan, sebagaimana kami berikan contoh sebelumnya tentang masalah al-muallafatu qulubuhum (orang-orang yang dilunakkan hatinya), dan masalah dhallatu al-ibil (unta yang tersesat/hilang), atau apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Umar bin Al-Khaththab—apa yang mereka lakukan bukanlah pertentangan yang nyata dengan nash, melainkan sesungguhnya hanya pertentangan zhahiri, dan tidak ada pertentangan yang nyata. Mengapa? Karena jika kita melihat substansi hukum, dan melihat rahasia hukum, dan hikmah dari hukum ini yang diambil oleh Sayyidina Umar, kita dapati bahwa ia tidak bertentangan dengan nash, tetapi ia menemukan bahwa illat (alasan hukum) yang menjadi dasar hukum tidak terwujud pada waktu tertentu, yaitu ketika kaum muslimin menjadi kuat.
Jadi, sesungguhnya tidak ada—jika ada pertentangan, itu hanya zhahiri saja, tetapi ketika kita renungkan, kita dapati tidak ada pertentangan. Demikian juga halnya, jika ada pertentangan tetapi zhahiri, dan bukan pertentangan yang nyata. Ini terjadi dengan sikap Sayyidina Utsman bin Affan terhadap dhallatu al-ibil—sebagaimana telah kami katakan. Unta yang tersesat, asalnya tidak boleh diambil dan dibiarkan hingga pemiliknya datang mengambilnya, karena tidak ada kekhawatiran atasnya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Bersamanya tempat minumnya dan sandalnya (kuat kakinya), ia mendatangi air dan memakan pohon.” Oleh karena itu, beliau meminta orang yang bertanya agar membiarkannya dan tidak mengganggunya hingga pemiliknya datang.
Ketika Sayyidina Utsman bin Affan berbuat berbeda dalam hal itu, apakah ia bertentangan dengan nash? Ini dalam zhahirnya. Tetapi bukan pertentangan yang nyata, melainkan hanya pertentangan zhahiri saja. Maksudnya: jika kita cermati sikap Sayyidina Utsman bin Affan, kita akan dapati bahwa ia sesungguhnya tidak menentang nash, melainkan melihat substansi nash, dan hikmah dari nash, dan rahasia nash ini.
Oleh karena itu, ia sesungguhnya menemukan bahwa jika nash didasarkan pada bahwa unta-unta ini tidak akan diganggu oleh siapa pun—mengapa? Sebagaimana dijelaskan dalam hadits, karena ada wazi’ dini (penghalang agama) yang mencegah mereka dari mengambil unta-unta ini. Tetapi ketika kondisi manusia berubah, dan wazi’ dini menjadi lemah pada mereka, maka illat yang menjadi dasar hukum Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits bahwa unta tidak boleh diambil tidak lagi ada. Illat tidak lagi ada, bahkan illat berubah, dan manusia tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengambil dan mencuri unta-unta ini. Oleh karena itu, Sayyidina Utsman menemukan bahwa illat, atau bahwa hukum beredar bersama illatnya, ada dan tidaknya. Ketika ia menemukan bahwa orang-orang ini tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengambil unta-unta ini, maka ia berkata: Unta itu diambil, diumumkan, kemudian dijual, dan harganya disimpan.
Demikianlah, dan dengan pertolongan Allah-lah kesuksesan.
Pelajaran 2: Konsep Sistem-Sistem Islam dan Kemunculannya di Mekah dan Madinah
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Konsep Sistem-Sistem Islam dan Kemunculannya di Mekah
Pengalaman Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Pengaturan Kehidupan Kesukuan Sebelum Diutus
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita akan membicarakan dalam kuliah ini -insya Allah- tentang konsep sistem-sistem Islam, kemudian tentang munculnya sistem-sistem ini. Maka kami katakan -dan kepada Allah kami mohon pertolongan-:
Sistem (nuzum) diartikan sebagai bentuk jamak dari sistem (nizam), yaitu kata yang digunakan untuk segala sesuatu yang di dalamnya diperhatikan keteraturan, keserasian, dan keterkaitan. Dengan pertimbangan ini, sistem menyerupai kalung dari segi keteraturan batu-batunya satu sama lain. Sistem suatu negara terdiri dari kumpulan hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan tradisi-tradisi yang menjadi landasan kehidupan di negara tersebut. Di antara sistem-sistem ini adalah: sistem politik, sistem administrasi, sistem keuangan, dan sistem peradilan. Ada pula sistem-sistem lain seperti ibadah-ibadah yang meliputi: shalat, puasa, haji, dan zakat. Dan ada jenis sistem lain yaitu sistem-sistem sosial yang membahas tentang keadaan masyarakat.
Jika kita ingin membicarakan tentang kemunculan sistem-sistem Islam, maka kita akan membahas tentang sumber-sumber awal sistem-sistem Islam ini. Kita akan membahas tentang pengaturan-pengaturan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian tentang pengaturan-pengaturan beliau shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan sekarang kita mulai dengan membahas tentang pengaturan-pengaturan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Mekah:
Dakwah Islam dan perjuangan Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkannya membentuk konsep-konsep pemikiran yang menjadi sandaran semua sistem dan lembaga-lembaganya yang dikenal oleh Negara Islam. Hal itu karena ajaran-ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kepribadian Rasul yang mengajarkannya, sebagaimana kepribadian Rasul yang mulia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya bangsa Arabnya. Semua hal ini memiliki hubungan erat dalam membangun sistem-sistem Islam pada tingkat yang mengharuskan mempelajarinya secara bersama-sama, karena masing-masing melekat pada yang lain seperti melekatnya kehamilan pada ibu yang mengandungnya.
Perkembangan budaya bangsa Arab telah mengalami -pada tahun-tahun pertama kehidupan Rasul yang mulia sebelum diutus- krisis hebat yang mengguncang sendi-sendi kehidupan kesukuan di seluruh Jazirah Arab, dan melumpuhkan semua sistem kesukuan dengan berbagai manifestasinya, mulai dari kerajaan-kerajaan di Yaman, emirat-emirat di pinggiran Bulan Sabit Subur, kesyeikhan-kesyeikhan di pedalaman negeri Arab dan khususnya di Mekah. Inti dari krisis ini adalah konflik antara semangat individualis yang menjadi fitrah sistem-sistem kesukuan, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok suku untuk membangun persekutuan-persekutuan yang layak menjadi inti masyarakat-masyarakat politik besar.
Tujuan dari sistem kesukuan bukanlah mendirikan persekutuan besar atau membangun masyarakat yang stabil, melainkan sistem ini terus bekerja untuk memantapkan pengaruh keluarga besar, atau mengangkat derajat klan atau suku dan mengangkatnya ke posisi terdepan di antara suku-suku sejenisnya.
Masyarakat-masyarakat politik yang berdiri di atas dasar sistem kesukuan ini ditandai dengan sempitnya pandangan, dan pendeknya umur lembaga-lembaga di dalamnya. Suku tetap menjadi satuan politik tertinggi, dan syeikhnya adalah pemimpin tertinggi tanpa pandangan kesukuan yang sempit mengizinkan terjadinya peristiwa-peristiwa besar menuju pembangunan satu masyarakat yang saling terkait. Gambaran kehidupan kesukuan di negeri Arab sebelum diutusnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadi gambaran bangunan yang runtuh, disertai dengan kekacauan dalam semua sistem yang menguasai kehidupan tersebut.
Tanda-tanda keruntuhan dalam sistem kesukuan mulai terdengar sejak tahun 571 Masehi yang menyaksikan kelahiran Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi ash-shalatu was-salam tumbuh di tengah kehidupan kesukuan yang hiruk-pikuk ini dan menyaksikan dari dekat semua sistemnya melalui banyak pengalaman pribadi yang mempersiapkan beliau alaihi ash-shalatu was-salam untuk memikul amanah dan menunaikan risalahnya dengan mengeluarkan bangsa Arab dari kegelapan sistem-sistem tersebut menuju cahaya Islam dan sekaligus mempersiapkan mereka untuk menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia.
Demikianlah Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam memperoleh di tempat kelahirannya di Mekah sebelum diutus lima tahun, memperoleh gambaran lengkap tentang kondisi yang dialami kehidupan kesukuan dengan berbagai sistem dan lembaganya. Hal itu karena Mekah menjadi dan berubah sebagai akibat pencapaiannya saat itu menjadi pusat keagamaan dan perdagangan pertama di negeri Arab, dan datangnya delegasi-delegasi suku dari berbagai penjuru negeri tersebut. Saya katakan: Mekah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang bertentangan, di mana mengendap di dalamnya sistem-sistem suku-suku tersebut, baik yang badui maupun yang berperadaban.
Pertentangan ini terwujud dalam sistem-sistem yang dianut oleh suku Quraisy sendiri. Individu dari mereka mempertahankan fanatisme kesukuan dalam bentuknya yang paling buruk dari segi penjarahan dan perampasan, membanggakan kebangsawanan dan nasab, dan pada saat bersamaan bangga dengan pembedaan kelas yang menyertai kehidupan menetap di pusat keagamaan dan perdagangan ini, yaitu Mekah. Orang Quraisy dari golongan pemuka -dan pemuka ini adalah majelis yang menghimpun para pemimpin kampung-kampung Quraisy setelah bersatu- membanggakan klannya dari satu sisi dan kekayaannya dari sisi lain. Dia berjalan di jalan-jalan dengan hidung terangkat penuh kebanggaan dan kesombongan hingga hampir merobek bumi dengan kakinya karena ingin mencapai ketinggian gunung, kemudian dia melaju saat berjalan dengan cepat marah dan sangat zalim, menampar siapa saja yang menghalangi jalannya dari kalangan orang-orang tertindas, yaitu mereka yang tidak memiliki klan atau suku besar yang melindungi mereka.
Mekah berubah menjelang diutusnya Rasul yang mulia lima tahun menjadi masyarakat yang penuh pertentangan dalam sistem-sistem kesukuan. Ia adalah pusat peradaban yang penduduknya pada saat bersamaan berpegang teguh pada tradisi-tradisi badui yang tampak, dan mematuhinya secara formal dalam realita kehidupan mereka, dan apa yang berhubungan dengan kehidupan tersebut berupa ciri-ciri dan manifestasi. Hidup di sana golongan pemilik kekayaan luas dan kemewahan yang berlebihan di samping kelompok-kelompok orang miskin yang tidak puas dan tunduk pada berbagai bentuk eksploitasi berupa riba dan perlakuan buruk. Sistem-sistem kesukuan menjadi alat di tangan para pemuka dari tuan-tuan Quraisy yang mereka manfaatkan untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kenikmatan dengan mengorbankan kesengsaraan dan penderitaan orang lain.
Inilah sistem-sistem yang ada di Mekah sebelum diutusnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kami telah menjelaskannya dan menjelaskan bagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan ini, mengalami pengalaman-pengalaman ini, dan mengetahui secara mendalam tentang sistem-sistem kesukuan yang berlaku di Mekah. Namun dengan turunnya Al-Quran yang mulia, meletus revolusi terhadap kehidupan kesukuan ini beserta sistem-sistem dan lembaga-lembaganya.
Sebagaimana kami katakan, ketika turun wahyu berupa Al-Quran yang mulia kepada Rasul yang amanah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia empat puluh tahun, saat beribadah di Gua Hira, Al-Quran yang mulia turun sebagai revolusi sosial dan keagamaan melawan kecenderungan-kecenderungan kesukuan, sistem-sistem dan lembaga-lembaganya yang terpusat di Mekah. Al-Quran menyeru untuk menetapkan sistem-sistem baru dalam rangka membangun masyarakat yang terbebas dari pandangan kesukuan yang sempit, dan berdiri di atas dasar keadilan universal.
Jadi, dengan turunnya Al-Quran yang mulia, terjadilah revolusi terhadap sistem-sistem usang yang berdiri atas dasar fanatisme dan kecintaan kepada suku lebih dari yang lain, yang berlaku di kalangan orang Arab di Mekah. Al-Quran yang mulia datang untuk mengumumkan revolusi terhadap sistem-sistem usang ini dan untuk mewujudkan sistem-sistem lain yang lebih luas pandangannya dan mencakup seluruh dunia.
Pengaturan-pengaturan Rasul selama menyebarkan dakwah dilakukan dalam dua tahap penting yang saling terkait:
Pertama: Rasul yang mulia bertujuan di dalamnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang mengatur kehidupan individu di Mekah, untuk terbebas dari belenggu fanatisme kesukuan di benteng kesukuan yang berdosa ini, yaitu Mekah.
Adapun tahap kedua: Rasul yang mulia bekerja di dalamnya setelah hijrah ke Madinah untuk mengatur komunitas kaum beriman di sana guna mengangkat derajat masyarakat Islam yang baru lahir dan mempersiapkan anak-anaknya untuk membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.
Kaidah-Kaidah yang Diletakkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam di Mekah
Rasul yang mulia berjuang di Mekah untuk meletakkan kaidah-kaidah berikut, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran yang mulia:
Kaidah pertama dari kaidah-kaidah yang ingin diletakkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah turunnya Al-Quran yang mulia di Mekah adalah:
Dakwah kepada keesaan Allah pencipta segala sesuatu, dan menjadikan akidah keagamaan ini sebagai dasar untuk membangun masyarakat baru yang memiliki sistem-sistemnya dan cita-cita luhurnya, yang bertentangan secara diametral dengan masyarakat kesukuan dan sistem-sistem serta tradisi-tradisi yang menguasainya yang lahir dari fanatisme. Hal-hal ini kemudian dikenal dalam istilah Islam dan dakwah Islam dengan nama: dakwah jahiliyah.
Dakwah kepada keesaan Allah adalah perusak yang menghancurkan kebekuan yang membelenggu kehidupan kesukuan, dan merupakan jalan untuk membangkitkan pemikiran dan membebaskannya dari tidur panjang yang dikaitkan dengan semangat konservatif yang didakwahkan oleh sistem-sistem kesukuan. Al-Quran yang mulia menjelaskan pentingnya dakwah baru ini, dan bahwa bangsa Arab tidak mengetahuinya sebelumnya. Allah Ta’ala berfirman: “Dan Kami tidak memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka pelajari dan Kami tidak mengutus kepada mereka sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun.” (Saba’: 44)
Dakwah kepada keesaan Allah dikaitkan dengan perlunya menggunakan akal dan tidak mengikuti secara membabi buta apa yang didakwahkan oleh sistem-sistem kesukuan berupa berpegang teguh pada warisan nenek moyang meskipun mereka tidak mendapat petunjuk. Al-Quran yang mulia mengecam kebekuan ini dalam banyak ayat. Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam kesesatan, maka mereka (mengikuti) jejak-jejak mereka dengan tergesa-gesa. Dan sungguh, telah sesat sebelum mereka kebanyakan orang-orang terdahulu.” (Ash-Shaffat: 69-71)
Al-Quran yang mulia pada saat bersamaan mendorong untuk berpikir, memperhatikan, dan menggunakan akal, dan bahwa pembuktian wujud dan keesaan Allah tampak bagi manusia dengan perenungan akal terhadap ayat-ayat Sang Pencipta, berupa keterkaitan alam semesta dan hukum-hukum alam, bahkan dalam perenungan manusia terhadap dirinya sendiri atas apa yang Allah karuniakan berupa pendengaran, penglihatan, dan sebab-sebab kehidupan lainnya. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan pada diri kalian sendiri. Maka apakah kalian tidak memperhatikan?”
Kaidah kedua dari kaidah-kaidah yang ingin diletakkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam di Mekah, untuk menghapus sistem-sistem kesukuan yang usang ini adalah:
Menetapkan ide kebangkitan dan perhitungan setelah kematian, di mana manusia akan mendapatkan surga yang kekal atau siksa neraka sesuai dengan apa yang telah dilakukan tangannya dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Setiap jiwa terikat dengan apa yang diusahakannya.” (Al-Muddatstsir: 38) Dan Allah Ta’ala berfirman: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” (An-Najm: 39-40) Dan Allah Ta’ala berfirman: “Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dan ibunya, dan ayahnya, dan istri serta anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.” (Abasa: 34-37)
Sebagaimana kami katakan: kaidah ini berarti menetapkan ide kebangkitan dan perhitungan setelah kematian, di mana manusia akan mendapatkan surga yang kekal atau siksa neraka, sesuai dengan apa yang telah dilakukan tangannya dalam kehidupan dunia. Akidah ini bertujuan menghancurkan konsep usang dari konsep-konsep kehidupan kesukuan, dan menetapkan prinsip baru bagi masyarakat Islam yang baru lahir.
Tanggung jawab seseorang dalam akidah kebangkitan dan perhitungan setelah kematian adalah tanggung jawab individual, di mana manusia dibalas dengan apa yang diusahakan tangannya. “Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Az-Zalzalah: 7-8)
Ayat-ayat Al-Quran yang mulia menjelaskan dengan terang tanggung jawab individual ini, atas dasar bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa pada hari kiamat seorang ayah tidak ditanya tentang anaknya, dan seorang anak tidak akan menanggung apa pun dari ayahnya, dan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya pada hari kiamat.
Oleh karena itu, akidah ini menghancurkan dakwah jahiliyah yang berdiri di atas fanatisme kesukuan, yang menetapkan bahwa individu diambil karena kejahatan orang lain, seperti yang ditetapkan oleh adat balas dendam di suku, dan apa yang dikaitkan dengannya berupa seruan kepada setiap individu dari suku untuk menolong saudaranya baik dia zalim maupun terzalimi.
Ini berarti bahwa ide kebangkitan dan perhitungan menetapkan tanggung jawab individual manusia, dan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. “Setiap jiwa terikat dengan apa yang diusahakannya.” (Al-Muddatstsir: 38) “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” “Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”
Ini berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem-sistem kesukuan pada masa jahiliyah. Tanggung jawab individual tidak dikenal, melainkan mereka mengambil seseorang karena kejahatan orang lain dan dosa orang lain, seperti yang terjadi dalam balas dendam.
Islam menetapkan bahwa pembunuh dibunuh, tetapi mereka jika tidak dapat membunuh si pembunuh, mereka membunuh siapa saja dari anggota keluarganya. Ini adalah hal yang ditolak oleh Islam dan dihancurkan oleh Islam dengan akidah yang dibawanya yaitu: tanggung jawab individual seseorang.
Al-Quran yang mulia menggambarkan hari kebangkitan dan perhitungan dengan penggambaran yang menegaskan kepada manusia pentingnya tanggung jawab individual, dan bahwa dahsyatnya hari itu membuat setiap ibu yang menyusui lupa akan apa yang disusuinya, dan bahwa setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka pada hari kiamat dikeluarkan untuk setiap manusia sebuah kitab yang ditemuinya terbuka, tertulis di dalamnya: “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab atas dirimu.” (Al-Isra’: 14) Dan juga “Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dan ibunya, dan ayahnya, dan istri serta anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.” (Abasa: 34-36) “Pada hari (ketika) kamu melihatnya, setiap ibu yang menyusui akan melalaikan anak yang disusuinya, dan setiap wanita yang hamil akan melahirkan kandungannya, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras.” (Al-Hajj: 2)
Demikianlah akidah kebangkitan dan perhitungan serta apa yang dikaitkan dengannya berupa tanggung jawab individual, menghancurkan ikatan fanatisme kesukuan yang berdiri di atas darah, dan menggantikannya dengan tanggung jawab baru yang menjadikan manusia sebagai inti untuk kesatuan yang dapat meluas atas dasar memelihara hati nurani dan takwa kepada Allah secara rahasia maupun terang-terangan. Yang kami maksud dengannya adalah: kesatuan di mana individu berdiri di samping yang lain seperti bangunan yang kokoh, sebagian menguatkan sebagian yang lain.
Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota mengeluh, maka seluruh tubuh akan merasakan tidak bisa tidur dan demam.” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”
Kaidah ketiga dari kaidah-kaidah yang telah dicoba dan diperjuangkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menegakkannya di Mekah adalah: menjadikan takwa sebagai pengganti fanatisme kesukuan sebagai dasar untuk membangun nilai-nilai akhlak yang luhur yang cakupannya melampaui batas-batas kabilah, dan pada saat yang sama tidak hanya meliputi bangsa Arab saja, tetapi juga seluruh bangsa-bangsa yang bertetangga dengan mereka. Takwa dalam Islam menetapkan ukuran-ukuran akhlak yang baru untuk membangun masyarakat yang tidak dikuasai oleh ukuran-ukuran kesukuan. Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (Surah Al-Hujurat: 13, sebagian ayat)
Jadi, Allah Tabaraka wa Taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa dasar keutamaan di antara manusia adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Taala dan amal saleh, dan bahwa pembedaan melalui jenis kelamin, bahasa, agama, atau lainnya, semua itu adalah perkara-perkara yang tidak dipandang oleh Islam. Islam hanya memandang kepada takwa saja: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”
Nabi shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa tidak ada keutamaan bagi orang kulit putih atas orang kulit hitam kecuali dengan takwa dan amal saleh. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Manusia itu sama seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan bagi seseorang atas yang lain kecuali dengan takwa.” Oleh karena itu, syariat Islam datang untuk menyamakan antara manusia, dan bahwa mereka sama di antara mereka di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Namun yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya adalah takwa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam ayat yang telah kami sebutkan: “Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” Bangsa-bangsa dan suku-suku dalam Islam bukanlah unit-unit yang terpisah, melainkan mereka membentuk masyarakat-masyarakat yang di dalamnya manusia setara di hadapan Islam tanpa memandang asal-usul dan jenis kelamin mereka, dan bahwa perbedaan di antara manusia adalah perbedaan akhlak, bukan berdasarkan keturunan, sebagaimana yang diserukan oleh fanatisme kesukuan, dan bahwa setiap individu mendapatkan kedudukan tinggi yang diinginkannya bukan berdasarkan kebangsawanan, nasab, dan kekayaan, tetapi sesuai dengan usaha, kebaikan, dan takwanya.
Takwa dalam Islam dan ukuran-ukuran akhlak yang terkandung di dalamnya mulai mengatur hubungan antara manusia berdasarkan kaidah-kaidah baru, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan sistem-sistem kesukuan yang keburukannya telah mencapai tingkat yang fatal dalam masyarakat Mekah. Sistem-sistem Islam yang ditetapkan oleh takwa mengingkari materialisme rendahan yang dikaitkan dengan sistem kesukuan di Mekah, di mana manusia telah dilalaikan oleh kesibukan mengumpulkan harta, menghitung dan mencintainya dengan cinta yang berlebihan, disertai merampas harta anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tenggelam dalam kemaksiatan, merusak hubungan sosial di antara keluarga, dan mengikuti hawa nafsu dalam memperlakukan manusia secara ekonomi dan moral. Inilah keadaan yang terjadi pada masa jahiliah. Keadaan pada masa jahiliah didasarkan pada cinta harta, cinta kekayaan, kezaliman yang kuat terhadap yang lemah. Namun datanglah takwa untuk menjelaskan bahwa manusia itu sama, dan bahwa tidak ada keutamaan bagi seseorang atas yang lain kecuali dengan takwa, dan bahwa tidak ada pembedaan berdasarkan kebangsawanan, nasab, dan kekayaan.
Rasul yang mulia mulai membacakan ayat-ayat Alquran yang mengharamkan sistem-sistem kesukuan yang usang, dan yang menetapkan prinsip-prinsip takwa untuk mengatur masyarakat baru dan kebahagiaan serta kesejahteraan para anggotanya. Allah Taala berfirman: “Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai dia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara (bersaksi), maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.'” (Surah Al-An’am: 151-152)
Islam menegaskan pada saat yang sama bahwa takwa dan prinsip-prinsipnya tidak berarti melakukan kewajiban-kewajiban yang disebutkan sebelumnya hanya secara lahiriah saja, melainkan tujuannya adalah untuk meraih keridhaan Allah Tabaraka wa Taala. Artinya: dituntut dari seorang Muslim ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepadanya agar melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Taala: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama” (Surah Al-Bayyinah: 5, sebagian ayat). Harus ada keikhlasan dalam beramal untuk Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju.” Oleh karena itu, sebagaimana kami katakan: Islam menegaskan pada saat yang sama bahwa takwa dan prinsip-prinsipnya tidak berarti melakukan kewajiban-kewajiban hanya secara lahiriah saja, melainkan tujuannya adalah keridhaan Allah, karena individu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.
Kita sampai pada kaidah keempat dari kaidah-kaidah yang sangat diperhatikan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menegakkannya dalam sistem-sistem Islam di Mekah. Kaidah ini berarti: penegasan tentang kesatuan risalah-risalah (agama-agama samawi), dan bahwa semuanya mengambil ajaran-ajarannya dari satu sumber yaitu Allah Subhanahu wa Taala, dan itu untuk menghapuskan keberagaman keyakinan dalam kehidupan kesukuan, dan apa yang menyertai sistem-sistem keagamaannya berupa penyembahan berhala, syirik, dan juga kebingungan di antara pengikut agama Kristen atau Yahudi. Alquran Karim menjelaskan bahwa dakwah Islam adalah pembenaran terhadap apa yang terdapat dalam kitab-kitab samawi, dan dakwah bagi bangsa Arab khususnya untuk mengikuti agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Allah Taala berfirman: “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima) apa yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada (agama)-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).” (Surah Asy-Syura: 13)
Jadi, kesatuan risalah-risalah diserukan oleh Islam karena semua risalah itu berputar pada satu makna yaitu mengesakan Allah Tabaraka wa Taala, dan Islam adalah dasar dari semua agama tersebut. Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.” (Surah Ali Imran: 19, sebagian ayat) Dan Allah juga berfirman: “Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” (Surah Ali Imran: 85) Jadi, semua risalah datang untuk satu tujuan yaitu mengesakan Allah Tabaraka wa Taala. Inilah yang dianjurkan oleh agama yang baru ini, dan ini berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem-sistem kesukuan sebelum diutusnya Nabi shallallahu alaihi wasallam, di mana terdapat keberagaman keyakinan, mulai dari penyembahan berhala, penyembahan patung-patung, dan lain-lain. Islam datang dan menjelaskan kepada mereka bahwa asal risalah-risalah adalah satu, dan bahwa agama di sisi Allah adalah Islam.
Alquran Karim menyapa bangsa Arab bukan sebagai keturunan Qahtan atau Adnan, artinya: bukan sebagai suku-suku Arab, melainkan ayat-ayat Alquran mengingatkan mereka tentang agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Allah Taala berfirman: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dialah (Allah) yang menamai kamu orang-orang Muslim sejak dahulu.” (Surah Al-Hajj: 78, sebagian ayat) Kesatuan risalah-risalah menjadi jalan yang diperjuangkan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan bangsa Arab dari lingkup perpecahan kesukuan menuju lingkup kesatuan, yang beliau serukan kepada mereka sebagai penutup para Nabi, dan bahwa agama Islam adalah agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Allah Taala berfirman: “Katakanlah, ‘Sesungguhnya Tuhanku telah menunjukiku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik.'” (Surah Al-An’am: 161) Dan Allah Taala berfirman: “Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Nabi Muhammad) serta orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad), dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.” (Surah Ali Imran: 68)
Itulah kaidah-kaidah yang ditegakkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau bekerja keras untuk menegakkannya di Mekah berkenaan dengan sistem-sistem Islam. Namun, apakah penduduk Mekah dan orang-orang kafir Mekah membiarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam begitu saja untuk menghancurkan sistem-sistem kesukuan yang mereka hidup di bawah naungannya, dan yang mereka peroleh manfaat darinya? Tidak, mereka menghadang Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ada perlawanan dari sistem-sistem kesukuan terhadap sistem-sistem Islam yang ingin ditegakkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam di Mekah sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Rasul yang mulia menempuh, berdasarkan petunjuk Alquran Karim, jalan bertahap dan perkembangan untuk menyebarkan dakwah Islam dan menetapkan sistem-sistem baru yang dibawa oleh dakwah tersebut dalam menghadapi perlawanan sengit yang dihadapinya dari sistem kesukuan di Mekah.
Alquran Karim menetapkan tahap-tahap perkembangan dari jihad Rasul di Mekah sebagai berikut:
Pertama: Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Rasul untuk memulai dari kaumnya dan orang-orang yang dekat dengannya, sebagaimana firman-Nya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (Surah Asy-Syu’ara: 214) Kaum, karena kedekatannya dengan Rasul, akan lebih siap untuk menolongnya ketika memperluas cakupan dakwahnya kepada selain mereka dari kaum-kaum dan kabilah-kabilah lain.
Kedua: Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Nabi setelah itu untuk menyampaikan risalahnya kepada Mekah dan sekitarnya, dalam firman-Nya: “Agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang ada di sekitarnya.” (Surah Al-An’am: 92, sebagian ayat) Tahap ini menunjukkan perpindahan dakwah dari kaum kepada suku Quraisy yang memiliki kedaulatan di Mekah, beserta sekutu-sekutu mereka yang tersebar di luar Mekah sendiri.
Ketiga: Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Rasul untuk menjelaskan kepada manusia bahwa dakwahnya dan tahapan dalam penyebarannya tidak berarti bahwa dakwahnya terbatas pada Quraisy dan suku-suku Arab saja, melainkan ini adalah dakwah untuk seluruh umat manusia, dan bahwa semua yang dibawa oleh dakwah tersebut berupa akidah dan sistem, pentingnya yang besar terlihat dalam firman-Nya: “Tidak lain (Alquran) itu adalah peringatan bagi seluruh alam.” (Surah Yusuf: 104, sebagian ayat) Dan firman-Nya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.” (Surah Saba’: 28, sebagian ayat) Dakwah ini adalah dakwah universal untuk semua manusia, dan tidak aneh dalam hal itu karena ini adalah dakwah terakhir dan Rasul shallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Oleh karena itu, dakwah ini adalah untuk semua manusia. Sesungguhnya aku diutus untuk seluruh manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam.
Sejumlah orang dari kerabat terdekat Rasul merespons dakwah Islam, tetapi itu adalah respons individual yang pendorongnya adalah iman yang tulus terhadap apa yang dibawa oleh Alquran Karim, dan bukan karena fanatisme. Artinya: sejumlah orang ini yang beriman kepada dakwah Nabi shallallahu alaihi wasallam dari kaumnya, tidak beriman kepada dakwahnya shallallahu alaihi wasallam karena fanatisme dan karena beliau dari kaum mereka, tetapi karena keyakinan mereka terhadap dakwah ini sebagaimana dijelaskan oleh Alquran Karim.
Rasul yang mulia mendapat manfaat dari kaumnya ketika pamannya Abu Thalib berdiri di sampingnya pada hari-hari pertama dakwah Islam. Namun Rasul yang mulia tidak menginginkan pada saat yang sama untuk bergantung sepenuhnya pada kaumnya, atau membatasi dirinya dengan mereka, karena itu tidak sesuai dengan dakwahnya yang bertujuan untuk menghancurkan fanatisme kesukuan dalam segala bentuknya. Kemudian fanatisme kaum itu sendiri menentang Rasul dengan penentangan membabi buta dan mulai menurunkan siksaan yang sangat keras kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab dan istrinya. Turunlah tentang orang musyrik yang fanatik ini firman Allah Taala: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.” (Surah Al-Masad: 1-5)
Ini artinya bahwa dakwah Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak didasarkan pada fanatisme, dengan bukti bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu pamannya, berdiri menghadangnya dan memeranginya. Oleh karena itu, ketika dakwah ini aktif dan menguasai dunia, itu tidak berarti bahwa ini adalah dakwah fanatisme dan kesukuan, melainkan ini adalah dakwah untuk semua manusia. Manusia ketika masuk dalam dakwah ini tidak masuk melalui pintu fanatisme dan kesukuan, melainkan melalui pintu apa yang dibawa oleh dakwah berupa dalil-dalil bahwa ini adalah dakwah yang benar, yang harus dimasuki oleh semua manusia.
Api fanatisme berkobar dari kaum kepada suku Quraisy ketika dakwah Islam berhasil menantang sistem-sistem kesukuan, dan jumlah orang yang memeluk Islam pertama kali bertambah. Al-Mala’ -yaitu aristokrasi Quraisy dari para pemuka kaum dan klan- memimpin gerakan ini melawan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka memimpin gerakan perlawanan terhadap Rasul ketika mereka merasakan bahaya pengorganisasian para pengikutnya terhadap sistem kesukuan mereka dan eksistensi pribadi mereka yang didasarkan pada tradisi sistem ini.
Jadi: Ketika mereka menemukan bahwa dakwah ini akan meruntuhkan sistem kesukuan yang telah mereka jalani sebelum dakwah datang, mereka melihat bahaya dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka menghadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memerangi beliau dan mempertahankan sistem kesukuan yang menetapkan kepentingan mereka. Maka dari itu, para pembesar mengumumkan penolakan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasul yang mulia, dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang asing bagi tradisi kesukuan mereka. Mereka berkata tentang dakwah ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran: “Dan kami tidak pernah mendengar hal ini pada nenek moyang kami yang terdahulu” (Surah Al-Qashash: 36) dan juga “Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir” (Surah Shad: 7).
Fanatisme kesukuan mendorong para pembesar Quraisy—yaitu: para pemimpin Quraisy—untuk beralih dari sekadar penolakan menjadi perlawanan terhadap Rasul baik secara material maupun moral, ketika menjadi jelas bagi mereka bahwa dakwahnya meskipun dimulai sebagai dakwah agama, namun ajarannya mulai menanamkan sistem-sistem baru di antara para pengikutnya yang mengancam kesatuan sistem kesukuan dan tradisi-tradisinya. Para pengikut agama baru ini memisahkan diri dari klan dan suku mereka, meninggalkan fanatisme kesukuan dan ikatan-ikatannya, dan membentuk kelompok yang memiliki ikatan baru, cita-cita dan nilai-nilai baru. Al-Quran menunjukkan sifat konflik ini dalam satu keluarga yang sebagian anggotanya masuk Islam sementara yang lain tidak, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya: ‘Cis bagi kalian berdua, apakah kalian berdua memperingatkan aku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu umat-umat sebelumku,’ sedang keduanya memohon pertolongan kepada Allah: ‘Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar.’ Lalu dia berkata: ‘Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu'” (Surah Al-Ahqaf: 17).
Kemudian Al-Quran menetapkan pedoman pengaturan khusus untuk fenomena awal ini dalam firman-Nya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau menaati keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembali kalian, lalu Aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan” (Surah Al-Ankabut: 8). Para pembesar Quraisy melihat bahwa masyarakat Mekkah terbagi menjadi dua: masyarakat yang sistem-sistemnya siap untuk berkembang dan aktif yang terdiri dari orang-orang beriman kepada Islam, dan masyarakat yang jumud dan menuju keruntuhan yaitu masyarakat kesukuan yang dipimpin oleh para pembesar di Mekkah. Situasi menuntut para pembesar untuk segera bertindak melawan Rasul, yang ajaran dan standar barunya mengancam kekuasaan para pembesar itu sendiri, dan kedudukan suku Quraisy tidak hanya di dalam Mekkah tetapi juga di luarnya. Dakwah Islam dan sistem-sistem baru yang dikumandangkannya yang berdiri atas dasar ketakwaan sebagai landasan keunggulan sosial, menggantikan sistem kesukuan yang berdiri atas dasar fanatisme dan kekayaan, mulai membentuk pelopor baru untuk kepemimpinan umum, yang tidak ada bagian di dalamnya bagi para pembesar dan para pemuka klan. Ketakutan para pembesar terhadap pelopor kepemimpinan baru ini semakin bertambah karena urusan tertingginya, menurut sistem Islam, diserahkan kepada Rasul sendiri, di mana ayat-ayat Al-Quran menyerukan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Para pembesar mengungkapkan ketakutan mereka terhadap pelopor sistem Islam baru ini karena perbedaannya dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan sistem kesukuan untuk kepemimpinan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: “Dan mereka berkata: ‘Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dari dua negeri (Mekkah dan Thaif) ini?'” (Surah Az-Zukhruf: 31). Al-Quran juga menunjukkan hakikat alasan-alasan yang membuat para pembesar takut atas kedudukan mereka di Mekkah dalam firman-Nya: “Dan Kami tidak mengutus seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: ‘Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.’ Dan mereka berkata: ‘Kami lebih banyak harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami tidak akan diazab.’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.’ Dan bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka di dalam kamar-kamar (surga) aman sentosa'” (Surah Saba’: 34-37).
Akhirnya, para pembesar menemukan dalih untuk mengerahkan barisan seluruh Quraisy dan klan-klannya di bawah panji mereka, ketika ajaran Islam menyerang paganisme Quraisy dan tuhan-tuhan orang musyrik. Para pembesar melihat bahwa kejayaan dakwah Islam yang baru berarti: lenyapnya kejayaan Quraisy yang berdiri atas dasar penjagaan berhala-berhala suku-suku di Ka’bah, dan mengalihkan pedagang suku-suku itu dan penduduknya dari Baitullah yang mulia. Al-Quran menunjukkan konflik yang terjadi antara para pembesar dan Rasul mengenai masalah ini dalam firman-Nya: “Dan mereka berkata: ‘Jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.’ Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan berapa banyak negeri yang Kami binasakan, yang (penduduknya) telah bersikap melampaui batas dalam kehidupannya; maka itulah tempat kediaman mereka, yang tidak didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sedikit. Dan Kami-lah yang mewarisi(nya)'” (Surah Al-Qashash: 57-58).
Konflik antara para pembesar dan Rasul yang mulia berlangsung dalam beberapa tahap, hasil dari setiap tahapnya mengungkapkan bahwa sistem kesukuan telah kehilangan kekuasaannya dan bahwa perlawanan yang ditampakkannya hanyalah kedutan kematian belaka, sementara sistem-sistem Islam membawa dari kesegaran dan keluhuran apa yang memberi kabar gembira tentang pelopor masyarakat universal yang baru. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta’ala menuliskan kemenangan bagi dakwah ini. Demikianlah ajaran Islam mampu mewujudkan bagi keteguhan para pengikutnya di hadapan para pembesar Quraisy sebuah prinsip baru yaitu bahwa kewajiban individu tidak lagi terbatas pada sukunya, melainkan mencakup orang-orang beriman kepada dakwah Islam dengan berbagai asal-usul kesukuan yang mereka miliki. Konsep baru ini mulai mengguncang seluruh kehidupan kesukuan meskipun ada kesombongan Quraisy dan keganasan para pembesarnya dalam mempertahankan kelangsungan hidup kesukuan tersebut. Pada saat yang sama, Rasul yang mulia tidak punya pilihan selain memindahkan konsep ini dan dakwah yang menjadi sandaran konsep ini ke medan baru, yang lebih mirip dari segi bentuk dengan tanaman yang harus ditanam di tanah baru yang lebih cocok untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Karena menjadi jelas bagi Rasul yang mulia bahwa lingkungan Mekkah telah menjadi—dengan kekeraskepalaaan para pembesar Quraisy terhadap beliau—benteng bagi sistem-sistem kesukuan dan fanatisme jahiliahnya, dan bahwa perlu dicari tanah baru selain tanah Quraisy. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih Madinah Al-Munawwarah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 – Munculnya Sistem-Sistem Islam di Madinah
Ciri-ciri Terpenting dari Sistem-Sistem Transisi yang Dibuat Nabi di Madinah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu pemimpin kami Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kami telah membahas dalam kuliah sebelumnya tentang munculnya sistem Islam, atau sistem-sistem Islam, dan kami telah menjelaskan pengaturan-pengaturan Islam yang dibuat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Sekarang kami akan mulai menjelaskan pengaturan-pengaturan Islam yang dibuat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kami katakan—dengan taufik dari Allah—:
Menjadi jelas bagi Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam bahwa lingkungan Mekkah telah menjadi—dengan kekeraskepalaaan para pembesar Quraisy terhadap beliau—benteng bagi sistem-sistem kesukuan dan fanatisme jahiliahnya, dan bahwa perlu dicari tanah baru selain tanah Quraisy. Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam memilih pasar Ukaz sebagai lembaga terpenting dalam kehidupan kesukuan, dan mulai menawarkan dakwah Islam kepada suku-suku Arab yang datang ke pasar ini dari luar Mekkah dan sekutu-sekutunya.
Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang dari suku Aus dari penduduk Yatsrib—yang kemudian menjadi Madinah—yang telah datang ke Mekkah untuk membuat aliansi dengan suku beliau, Quraisy, melawan Khazraj—yaitu suku besar kedua di Yatsrib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kelompok dari Aus ini bahaya konflik kesukuan yang mereka tenggelami, dan bahayanya menyulut api konflik itu dengan bersekutu dengan Quraisy. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu memeluk Islam. Meskipun kelompok ini tidak beriman, namun—ketika kembali ke Yatsrib—mereka menyebarkan di antara penduduknya berita tentang dakwah Islam yang baru dan perjuangan rasulnya Shallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Suku Khazraj terguncang oleh berita yang disebutkan oleh orang-orang Aus tentang nabi baru di Mekkah, dan mereka melihat bahwa keadaan mereka di Yatsrib mendorong mereka untuk mengetahui dakwahnya Shallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena penduduk Yatsrib dari Aus dan Khazraj telah mendengar dari tetangga mereka orang-orang Yahudi tentang akan segera munculnya seorang nabi, dan bahwa orang-orang Yahudi mengeksploitasi ramalan ini untuk memaksakan supremasi mereka atas seluruh Yatsrib.
Oleh karena itu, ketika sekelompok orang dari Bani Abdul Asyhal dari Khazraj pergi ke pasar Ukaz dan bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang Yatsrib pertama yang menerima dakwah Islam agar Aus atau orang-orang Yahudi tidak mendahului mereka dalam hal ini. Dalam diskusi delegasi Khazraj ini dengan Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam terlihat sejauh mana kesediaan suku Khazraj menerima prinsip perluasan kewajiban individu ke luar lingkup suku sebagaimana yang diajak oleh ajaran Islam, dan kelayakan prinsip ini untuk menjadi pelopor pengaturan politik bagi kaum muslimin di Yatsrib yang dipercayai oleh Rasul secara pribadi. Mereka berkata kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami, dan tidak ada kaum yang di antara mereka terdapat permusuhan dan keburukan seperti yang ada di antara mereka. Maka mudah-mudahan Allah mempersatukan mereka melalui engkau. Kami akan datang kepada mereka lalu mengajak mereka kepada urusanmu, dan menampakkan kepada mereka apa yang kami setujui darimu tentang agama ini. Jika Allah mempersatukan mereka atas agama ini, maka tidak ada orang yang lebih mulia darimu.”
Dakwah Islam dan konsep-konsepnya mulai mendapat sambutan di kalangan penduduk Yatsrib, hingga ketika tiba musim haji berikutnya, datang delegasi dari penduduk Yatsrib yang terdiri dari dua belas orang: sembilan dari Khazraj dan tiga dari Aus. Mereka menemui Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam di Aqabah antara Mina dan Mekkah, dan membaiatnya atas Islam. Komposisi delegasi ini dari Khazraj dan Aus merupakan bukti perluasan konsep kewajiban individu, dan bahwa kewajiban itu tidak lagi terbatas pada suku.
Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengambil langkah pengaturan lain yang berdampak pada sistem politik jamaah kaum muslimin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus bersama delegasi ini—ketika mereka kembali ke Yatsrib—salah satu sahabat yang terdahulu masuk Islam, yaitu Mush’ab bin Umair dari Bani Abdi ad-Dar, untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan memberi mereka pemahaman mendalam tentang agama. Sahabat ini dikenal di Yatsrib dengan sebutan Al-Muqri (pengajar Al-Quran), dan ini adalah gelar yang menunjukkan arah baru dalam kepemimpinan untuk mengatur dakwah Islam atas dasar-dasar yang jauh dari fanatisme kesukuan. Al-Muqri ini memimpin orang-orang dalam shalat dari Aus dan Khazraj untuk menghindari memicu sentimen kesukuan. Dengan amanatnya dalam mengikuti jejak Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari segi bertahap dan sabar, ia berhasil merekrut ke dalam jamaah kaum muslimin di Yatsrib dua pemimpin terbesar suku Aus, yaitu: Sa’d bin Mu’adz dan Usaid bin Hudhair. Yatsrib menjadi—berkat pemimpin Al-Muqri ini—menyaksikan pelopor pengaturan politik baru yang berdiri atas dasar agama, bukan fanatisme kesukuan dan ikatan darah. Kekuatan pelopor pengaturan politik baru bagi kaum muslimin ini muncul ketika Mush’ab datang ke Mekkah pada tahun berikutnya untuk haji, bersama delegasi yang terdiri dari tujuh puluh tiga pria dan dua wanita. Mereka menemui Rasul Shallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di mana mereka membaiatnya dalam Baiat Aqabah Kedua yang terkenal. Dalam baiat ini terwujud komitmen timbal balik antara Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin Yatsrib, sesuai dengan pengaturan baru yang diajak oleh ajaran Islam. Peralihan dari sistem kesukuan ke sistem-sistem Islam memasuki tahap pelaksanaan praktis dan pengujian pada saat yang sama, ketika Rasul dan kaum muslimin Yatsrib saling bertukar janji dan perjanjian untuk saling membela dan mendukung.
Abbas bin Abdul Muthalib hadir bersama Nabi dalam pertemuan Aqabah Kedua, dan memulai pembicaraan—meskipun ia belum masuk Islam—untuk mengambil perjanjian dari penduduk Yatsrib untuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata: “Wahai Khazraj, sesungguhnya Muhammad adalah dari kami di mana kalian telah mengetahuinya, dan kami telah melindunginya dari kaum kami yang berpandangan sama dengan kami tentangnya. Maka ia berada dalam kemuliaan dari kaumnya dan perlindungan di negerinya. Dan sesungguhnya ia telah menolak kecuali berpindah kepada kalian dan bergabung dengan kalian. Jika kalian melihat bahwa kalian akan memenuhi apa yang kalian ajak kepadanya dan melindunginya dari orang yang menentangnya, maka kalian dan apa yang kalian tanggung dari itu. Dan jika kalian melihat bahwa kalian akan menyerahkannya dan mengkhianatinya setelah ia keluar bersama kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah ia, karena ia berada dalam kemuliaan dan perlindungan dari kaumnya dan negerinya.” Pemimpin delegasi Khazraj menjawab perkataan Abbas dengan berkata: “Kami telah mendengar apa yang engkau katakan. Maka berbicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Tuhanmu apa yang engkau sukai.” Lalu Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat dari Al-Quran.
Kemudian beliau bersabda: “Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian.” Pemuka kaum, yaitu Al-Bara’ bin Ma’rur, mengambil tangan Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya: Ya, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi istri-istri dan anak-anak kami. Maka baiat-lah kami wahai Rasulullah, karena kami demi Allah adalah ahli perang dan ahli perisai, kami mewarisinya turun temurun dari leluhur kami. Di sini salah seorang dari penduduk Yatsrib meminta dari Rasul lebih banyak perjanjian karena penerimaan mereka terhadap dakwah Islam berarti: memutus hubungan suku-suku Yatsrib dengan orang-orang Yahudi yang bertetangga dengan mereka. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang—maksudnya: Yahudi Madinah—ada tali (hubungan), dan sesungguhnya kami akan memutuskannya. Apakah mungkin jika kami melakukan itu, kemudian Allah memenangkanmu, engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami? Rasul yang mulia tersenyum dan bersabda: “Darah adalah darah, dan kehancuran adalah kehancuran. Aku dari kalian dan kalian dariku. Aku memerangi siapa yang kalian perangi dan aku berdamai dengan siapa yang kalian damaikan.”
Kemudian beliau bersabda kepada mereka: “Keluarkanlah untuk ku dari kalian dua belas orang perwakilan agar mereka bertanggung jawab atas kaum mereka beserta apa yang ada pada mereka.” Maka mereka mengeluarkan dua belas perwakilan: sembilan dari Khazraj dan tiga dari Aus. Rasul bersabda kepada mereka: “Dan kalian bertanggung jawab atas kaum kalian beserta apa yang ada pada mereka, sebagai penjamin seperti penjaminan para hawariyun terhadap Isa bin Maryam, dan aku adalah penjamin atas kaumku.” Baiat ini—yang dikenal dengan nama Baiat Aqabah Kedua atau Baiat Perang, atau apa yang mereka ungkapkan sebagai perang orang hitam dan merah—menjadi pengumuman resmi perpindahan hak membela dakwah Islam dan pembawanya kepada anggota-anggota masyarakat Islam yang baru lahir ini. Perjanjian ini menjadi peristiwa penting yang mengguncang sistem kesukuan dengan guncangan yang kuat, dan menandakan runtuhnya sistem itu dari dasarnya. Hal itu karena sistem politik yang berlaku saat itu tidak mengenal perlindungan bagi individu kecuali dalam perlindungan suku terhadapnya. Adapun hak ini diambil alih oleh kekuatan di luar lingkup suku—sebagaimana yang ditetapkan oleh Baiat Aqabah Kedua—ini adalah pengaturan baru yang tidak mungkin Quraisy dan para pembesar dari para syeikhnya diam terhadapnya.
Para pembesar memang kebingungan ketika berita Baiat Aqabah Kedua sampai kepada mereka, dan mereka tidak menemukan jalan keluar dari sistem-sistem kesukuan mereka selain berkonspirasi membunuh Rasul yang mulia untuk menghalangi antara beliau dan pergi ke Yatsrib. Pertemuan para pembesar yang diselenggarakan di Darun Nadwah menghasilkan keputusan bahwa pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah pembunuhan kolektif yang diikuti oleh seorang pemuda dari setiap klan dari klan-klan Quraisy sehingga darahnya terbagi di antara suku-suku, dan keluarga Rasul tidak mampu memerangi mereka semua, lalu menerima diyat (tebusan darah). Tetapi pemikiran kesukuan ini terbukti tidak mampu mengikuti perkembangan yang menyertai pengaturan-pengaturan politik yang dibuat oleh Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam. Nabi berhasil menghancurkan rencana kesukuan menyeluruh ini, dan berhasil hijrah ke Yatsrib, di mana beliau memulai halaman yang lebih luas dan lebih megah di medan sistem-sistem Islam, dan mengembangkan pencapaian serta tujuannya. Sekarang kami akan membahas tentang sistem jamaah orang-orang beriman di Madinah, atau pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk negara Islam.
Sistem-sistem Transisi: Rasul yang mulia berjalan setelah hijrah ke Yatsrib dengan gaya bertahap dan berkembang yang sama dalam menyebarkan dakwah Islam meskipun tahap itu memerlukan pengaturan yang lebih luas dan lebih banyak daripada apa yang beliau lakukan di Mekkah. Dalam peran baru ini terlihat jelas bakat-bakat politik yang dimiliki oleh Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam dan pengalaman mendalam dengan perkembangan budaya penduduk Yatsrib, dengan cara yang tidak kalah megahnya dari apa yang beliau tunjukkan di Mekkah berupa idealisme sempurna dalam menyatakan dakwah dengan terang-terangan, dan keberanian yang langka dalam mengajarkan atau dalam membela ajaran dakwah tersebut, dan sistem-sistemnya yang sangat berbeda dari sistem-sistem kesukuan yang tertanam kuat.
Pengaturan-pengaturan Rasul yang mulia Shallallahu alaihi wasallam di Yatsrib ditandai dengan kemampuan luar biasa untuk menggabungkan antara perencanaan dan pelaksanaan, baik dalam keadaan yang dipaksakan oleh kenyataan yang ada, maupun yang datang melalui Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Pengaturan-pengaturan Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari-hari pertama hijrahnya ke Yatsrib mencakup sistem-sistem transisional dan sistem-sistem mendasar. Setiap sistem datang sebagai hasil dari masyarakat Islam yang baru, dan ciri-ciri terpenting dari sistem-sistem transisional ini adalah:
Pertama: Sistem persaudaraan (muakhat), yaitu suatu kebijakan yang diperlukan untuk memudahkan jalan penghidupan bagi penduduk Makkah yang Muslim yang meninggalkan negeri mereka, rumah-rumah mereka, dan harta kekayaan mereka, serta berhijrah ke Yatsrib untuk menjaga akidah Islam mereka dan keimanan mereka yang teguh dan kokoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyediakan sebab-sebab kehidupan yang layak bagi sekelompok kaum Muslim ini dengan menetapkan sistem persaudaraan. Sistem persaudaraan adalah alternatif Islam bagi sistem aliansi dalam suku, di mana agama menjadi dasar persaudaraan, bukan fanatisme kesukuan sebagaimana yang berlaku dalam sistem aliansi. Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kelompok Muhajirin dari Makkah berdasarkan sistem persaudaraan, membagikan mereka kepada kaum Muslim Yatsrib dengan mengajak mereka untuk bersaudara dalam Allah secara berpasang-pasangan. Setiap Muhajir dari Makkah hidup bersama saudaranya dari kaum Muslim Yatsrib, dan masing-masing mewarisi yang lain ketika meninggal. Penduduk Yatsrib dari kaum Muslim menunjukkan keikhlasan yang ideal dalam menerapkan sistem persaudaraan, yang merupakan hal yang dipuji oleh Al-Qur’an Al-Karim dalam firman Allah Taala: “Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan. Dan barangsiapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Surat Al-Hasyr: 9).
Setiap Muslim dari penduduk Yatsrib mengizinkan saudaranya dari Muhajirin untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan dan urusan-urusan ekonomi lainnya, serta memberikan segala sesuatu yang meringankan kesulitan hidup Muhajir tersebut. Ketika keadaan Muhajirin stabil dengan meluasnya kekuasaan agama Islam dan bertambahnya pengikutnya, tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkan sistem persaudaraan. Maka turunlah syariat Islam yang membatalkannya dan menghapuskan hukum-hukum transisionalnya, yaitu dalam firman Allah Taala: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surat Al-Anfal: ayat 75).
Di antara sistem-sistem transisional lainnya, atau ciri-ciri terpenting dari sistem-sistem transisional di Madinah adalah penggunaan istilah Islam: Muhajirin dan Anshar untuk menunjukkan pelopor-pelopor organisasi baru di Yatsrib, dan menganggap akidah dan agama sebagai jalan menuju persatuan, bukan fanatisme kesukuan dan sistemnya. Yang dimaksud dengan Muhajirin adalah semua kaum Muslim yang berhijrah dari Makkah, tanpa memandang suku atau klan mereka. Istilah baru ini menjadi identitas yang membedakan mereka dari suku-suku yang sebelumnya mereka ikuti.
Demikian pula istilah Anshar menjadi nama bagi kaum Muslim Yatsrib dari suku Aus dan Khazraj tanpa memandang suku-suku yang sebelumnya mereka ikuti melalui fanatisme kesukuan. Persatuan dalam akidah dan agama menjadi dasar bagi sistem Muhajirin dan Anshar, dan menjadi jalan untuk meninggalkan fanatisme kesukuan yang sempit, serta menghilangkan semua sebab perpecahan yang terkait dengan fanatisme kesukuan. Sistem Muhajirin dan Anshar – beserta sistem persaudaraan yang terkait dengannya – menjadi jalan menuju pembangunan sistem politik baru yang cakrawala luasnya mencakup kedua kelompok ini, kemudian meleburnya dalam satu kesatuan yang dikenal dengan nama jemaah kaum Mukmin.
Kelompok baru ini dan sistemnya menjadikan Yatsrib sebagai kota yang layak disebut dengan nama Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menandakan peran penting yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun sistem Islam baru ini dan memperkuat pondasinya di kota tersebut. Yatsrib meninggalkan kehidupan kesukuan dan menyambut era Islam dengan sistem-sistem dan ajaran-ajarannya yang luhur. Dalam era baru ini, kota tersebut menjadi pusat perhatian semua orang, mencari dalam kepemimpinan Nabi yang mulia apa yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Semua orang menyebutnya dalam era baru ini dengan nama Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan nama yang disebutkan hingga hari ini, dan semua orang mengulang-ulangnya sebagai penghormatan dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Demikianlah tentang sistem-sistem transisional yang diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangannya ke Yatsrib, yaitu Madinah. Kami telah mengatakan bahwa sistem-sistem transisional ini terwujud dalam sistem persaudaraan, kemudian juga dalam sistem Muhajirin dan Anshar.
Sistem-Sistem Mendasar yang Ditetapkan Nabi untuk Jemaah Kaum Mukmin di Madinah
Namun ada juga sistem-sistem mendasar yang dibentuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Organisasi-organisasi mendasar yang ditetapkan oleh Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jemaah kaum Mukmin di Madinah ini merupakan sumber-sumber yang mengalir deras yang darinya sistem-sistem Islam mengambil keasliannya dan sekaligus kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan dan pertumbuhan. Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan dari organisasi-organisasi ini menjadikan jemaah kaum Mukmin sebagai inti yang baik bagi masyarakat baru, yang misinya adalah jihad dalam rangka menyebarkan Islam dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencapai tujuan-tujuan tersebut setelah hijrahnya ke Madinah sebagai hasil dari penetapan sistem-sistem mendasar berikut:
Pertama: Penetapan sistem negara dan hukum, bukan suku dan adat; ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, beliau membawa pengalaman praktis tentang sistem kesukuan yang rusak dan fanatisme buta yang melanda Makkah yang menghalangi suku-suku untuk bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras untuk menghalangi keburukan-keburukan kesukuan ini agar tidak meluas ke jemaahnya yang baru di Madinah, yang masih dalam masa awal kehidupannya. Karena itu, beliau menjadikan agama dan akidah sebagai dasar untuk mengumpulkan kaum Muslim dari Muhajirin dan Anshar dalam satu negara yang penduduknya melihat dalam agama baru mereka ikatan yang kuat dan lebih kokoh daripada ikatan kesukuan.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat sistem ini atas dasar baru juga, yaitu hukum yang berdasarkan syariat, bukan adat kesukuan dengan fanatisme yang membinasakan yang terkait dengannya. Surat-surat Al-Qur’an Al-Karim yang turun kepada Rasul di Madinah penuh dengan perundang-undangan yang memperkuat negara Islam yang baru lahir dan menciptakan darinya kekuatan yang bergerak dan vital, mampu mengungguli masyarakat kesukuan yang kaku dan stagnan di sekitarnya.
Di antara sistem-sistem mendasar yang juga ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menganggap sistem kewarganegaraan dan hak-haknya berdasarkan hijrah untuk melawan kebatilan, bukan fanatisme kesukuan. Kesetiaan kepada negara Islam baru dan menikmati hak-hak kewarganegaraan di dalamnya dasarnya adalah hijrah ke negara tersebut dan meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah dari tempat-tempat kemusyrikan dan kesesatan kesukuan menuju negeri petunjuk, pertolongan agama, dan martabat manusia. Ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan sistem baru ini turun dalam firman Allah Taala: “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab: ‘Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).’ Malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?'” (Surat An-Nisa: ayat 97). Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: “Dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka kamu tidak berkewajiban melindungi mereka sedikitpun hingga mereka berhijrah.” (Surat Al-Anfal: ayat 72). Ide kewarganegaraan dengan makna idealnya mulai terkait dengan negara Islam yang baru lahir dan memperkuat ikatan antara anak-anaknya atas dasar-dasar yang kokoh dan kuat.
Di antara sistem-sistem mendasar yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah juga adalah penetapan sistem musyawarah untuk memperkuat semangat kelompok baru dan melatih mereka untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Perundang-undangan langit yang dibawa oleh Al-Qur’an Al-Karim tidak berarti merampas hak orang untuk berpartisipasi dalam mengatur urusan mereka, tetapi perundang-undangan ini membuka semua jalan bagi anggota negara baru untuk menyatakan pendapat dalam semua masalah, terutama yang bersifat kepentingan umum.
Ayat-ayat Al-Qur’an menjelaskan pentingnya musyawarah, Allah Tabaaraka Wa Taala berfirman: “Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Surat Ali Imran: ayat 159). Dan dalam firman Allah Taala yang menegaskan pentingnya sistem ini dalam kehidupan anggota negara baru, Allah Taala berfirman: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Surat Asy-Syura: ayat 38). Sistem musyawarah dalam negara baru memberikan model hubungan erat antara penguasa – apapun jabatannya – dan yang diperintah – apapun perannya dalam negara. Semua orang – sesuai sistem musyawarah – adalah mitra dalam membangun kehidupan mereka dan menyesuaikan urusan mereka sesuai kepentingan umum dan sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat.
Sistem musyawarah menjadi tolok ukur terpenting yang dijaga oleh kaum Muslim sepanjang perkembangan negara mereka untuk mengetahui sejauh mana kebenaran perkembangan ini dan jauhnya dari penyimpangan dan kesalahan. Sistem musyawarah mewujudkan peluncuran yang benar bagi negara Islam yang muda, di mana sistem ini memungkinkan anak-anaknya pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka serta mengekspresikan semangat demokratis yang memang telah menjadi fitrah orang Arab dengan cara yang lebih luas, lebih akurat, dan lebih teratur.
Di antara prinsip-prinsip mendasar yang juga diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah penetapan sistem masjid, agar menjadi pusat pertemuan anak-anak negara baru, tidak hanya untuk urusan agama mereka, tetapi juga menjadi markas untuk mengelola urusan umum dan pribadi mereka, serta markas kekuasaan baru dengan segala manifestasi yang terkait dengannya dan perbuatan-perbuatan yang keluar darinya. Sistem masjid yang ditetapkan oleh Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sistem yang sederhana dalam bangunan dan maknanya, tetapi dengan perkembangan negara Islam menjadi model yang diikuti oleh kaum Muslim, baik dalam seni arsitektur masjid maupun dalam bidang kehidupan umum.
Kaum Muslim bersungguh-sungguh meniru masjid ini sepanjang perkembangan negara mereka, berhati-hati menjaga kaidah-kaidah dasarnya. Perundang-undangan yang diumumkan oleh Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dari masjid ini menjadi sumber yang dijaga oleh kaum Muslim untuk mengambil darinya petunjuk dan bimbingan dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan-utusan dan menggambarkan untuk jemaah kaum Muslim segala sesuatu yang membimbing mereka ke jalan yang benar.
Di antara organisasi yang sangat penting di Madinah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konstitusi permanen, atau Shahifah – sebagaimana disebut oleh sebagian orang – yang di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis tentang cara berjalannya organisasi baru di negara di Madinah. Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam dokumen atau konstitusi ini hak dan kewajiban setiap orang dalam negara ini. Kami katakan: Sistem-sistem mendasar dan komitmen-komitmennya terwujud dalam konstitusi permanen yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur hubungan bukan hanya antara jemaah kaum Mukmin satu sama lain, tetapi juga antara mereka dan tetangga-tetangga mereka dari penduduk Madinah. Konstitusi ini – yang terkenal dengan nama Shahifah – menjadi dasar negara Islam yang baru lahir dan sumber terpenting dari sistem-sistem Islam yang menyertai perkembangan dan perluasan negara ini sepanjang masa.
Konstitusi ini menetapkan sistem dan prinsip-prinsip penting berikut:
Pertama: Berkaitan dengan konsep umat dan hak kewarganegaraan:
1 – Konstitusi mendefinisikan umat dengan definisi yang tidak berdasarkan pada dasar-dasar dan sistem kesukuan serta fanatisme dan nasab yang terkait dengannya, tetapi memutuskan bahwa umat mencakup semua orang yang menganut agama baru, tanpa memandang asal-usul atau sukunya. Prinsip ini menjadi unsur penting yang menjadikan umat baru sebagai umat yang fleksibel dan dapat berkembang serta merangkul banyak bangsa ke dalam lingkupnya. Konsep baru tentang umat ini terwujud dalam pembukaan konstitusi, yang menyatakan bahwa kaum Mukmin dan kaum Muslim dari Quraisy dan Yatsrib serta orang-orang yang mengikuti mereka, bergabung dengan mereka, dan berjihad bersama mereka adalah satu umat yang berbeda dari manusia lainnya.
2 – Konstitusi menegaskan bahwa umat ini tidak mengakui pembedaan kelas, atau eksploitasi individu sebagaimana yang berlaku dalam sistem kesukuan, melainkan membuka jalan untuk melebur perbedaan-perbedaan dengan menjadikan suku-suku sebagai formasi sosial untuk melayani umat yang baru; maka klan-klan dan suku-suku tetap menjadi anggota umat, namun sesuai dengan konsep baru negara Islam di mana kaum Muhajirin misalnya dianggap sebagai satu klan sebagaimana halnya klan-klan lainnya, dan tugas klan-klan serta kelompok-kelompok tersebut terbatas pada memudahkan tugas individu dalam membayar diyat (tebusan darah) dan menebus tawanan, yakni: konstitusi menentukan hubungan antara umat dan suku-suku dengan penentuan baru yang intinya adalah melayani tuntutan umat ini, dan mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan individu mana pun, dan konstitusi menjelaskan untuk setiap klan secara terpisah jenis kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan kedudukannya dalam umat yang baru, dan tanpa diskriminasi di antara mereka.
3 – Konstitusi menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat yang masih muda untuk formasi barunya berdasarkan dasar-dasar berikut:
Saling menyayangi dan bekerja sama di antara anggotanya dalam berbagai bidang, dan khususnya mereka yang terbebani utang, dan perlunya membantu mereka untuk lepas dari beban utang-utang tersebut.
Juga menentukan tanggung jawab individu, dan mengatur hubungannya dengan keluarga dan tetangganya dari segi kesetiaan, dan itu sesuai dengan kondisi negara dan sistemnya yang baru.
Supremasi hukum dan tindakan pelaksanaan: Piagam mengatur kehidupan manusia di dalam negara yang baru berdasarkan supremasi hukum, dan tindakan pelaksanaan yang terkait dengannya; maka jika seseorang melanggar keamanan, atau melakukan perbuatan keji; maka umat secara keseluruhan yang akan menjatuhkan hukuman yang diperlukan, dan bahwa semua orang dituntut untuk bersatu dalam pelaksanaan hukuman tersebut – walaupun itu anak salah seorang dari mereka. Dan terkait dengan supremasi hukum adalah pengubahan balas dendam menjadi hukuman, dalam arti bahwa itu adalah tindakan yang menjadi tanggung jawab umat, setelah sebelumnya klan-klan dan suku-suku yang melakukannya menurut sistem kesukuan yang batil, dan hukum pada saat yang sama mempertahankan hak individu untuk menentukan jenis hukuman dengan kesepakatan dengan korban dari segi menjatuhkan hukuman, atau menerima tebusan misalnya, dan di antara yang tercantum dalam Piagam ini adalah penetapan kebebasan beragama, dan penentuan hubungan negara dengan pengikutnya.
Piagam menjelaskan prinsip penting dari prinsip-prinsip negara yang baru, yaitu penetapan kebebasan agama-agama samawi, dan bahwa pengikutnya dianggap sebagai warga negara, yang berhak mendapat perlindungan negara, sesuai syarat-syarat yang tercakup dalam konstitusi baru, dan karena suku-suku Yahudi dan kelompok-kelompoknya merupakan unsur terpenting dari unsur-unsur penduduk dalam negara Islam yang baru di Yatsrib; maka Piagam menyebutkan dengan jelas tentang hak-hak dan kewajibannya, baik terhadap tetangga mereka dari warga negara Muslim, atau terhadap negara dan kekuasaannya, dan itu sebagai berikut:
Piagam menetapkan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi, dan suku-suku mereka, dan kelompok-kelompok mereka yang sebelumnya telah bersekutu dengannya kelompok-kelompok Aus dan Khazraj, tetapi dengan keharusan memperhatikan hak-hak kewarganegaraan dengan menjauhi pelanggaran terhadap ketertiban, atau memanfaatkan perlindungan negara untuk melakukan kejahatan dan dosa, dan Piagam menegaskan bahwa hukuman akan sesuai dengan perbuatan, dan bahwa itu dijatuhkan kepada individu, atau keluarganya sesuai dengan kualifikasi hukum kejahatan tersebut.
Dan Piagam juga mengatur hak-hak orang-orang Yahudi, dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dengan kaum Muslim dalam peperangan, dan membela negara baru terhadap bahaya eksternal apa pun, maka jika peperangan itu bersifat defensif maka setiap pihak menanggung biayanya sendiri, adapun dalam peperangan ofensif; maka satu pihak tidak mengharapkan bantuan pihak lain.
Dan juga Piagam menentukan sikap orang-orang Yahudi sebagai penduduk Yatsrib terhadap Quraisy, musuh utama negara Islam yang baru; maka menetapkan perlunya partisipasi orang-orang Yahudi dalam membela Yatsrib jika diserang oleh Quraisy, dan bahwa mengadakan perdamaian dengan Quraisy, atau mengadakan perjanjian apa pun dengannya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pusat yang diwakili oleh Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Juga Piagam memungkinkan penerapan syarat yang sama, bukan hanya pada orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan Aus dan Khazraj saja, tetapi pada suku-suku Yahudi yang besar jika mereka menginginkan itu, dan Piagam menegaskan keadilannya dalam memperlakukan orang-orang Yahudi bahwa ia tidak akan menghukum mereka semua karena kesalahan individu, melainkan akan memperlakukan setiap kelompok dari mereka sesuai dengan apa yang timbul dari mereka.
Dan Piagam membicarakan tentang kedaulatan negara, dan penetapan manifestasi kedaulatan tersebut, dan Piagam memahkotai syarat-syaratnya dengan menetapkan sistem-sistem khusus tentang kedaulatan negara, dan penjelasan hak-hak kepala negara tersebut, yaitu Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kaidah-kaidah kedaulatan negara terwujud dalam hal-hal berikut:
1 – Persatuan seluruh penduduk untuk menangkis agresi apa pun yang menyentuh kedaulatan negara baik agresi ini mengenai individu, atau kelompok yang kegiatan atau tugasnya terkait dengan urusan negara, dan keamanannya, dan sistem ini merupakan kaidah terpenting negara baru, dan sebab keunggulannya atas musuh-musuhnya yang mengelilinginya dari pengikut sistem kesukuan; karena kedaulatan negara menjadi pagar yang melindungi seluruh warga negara, dan kewajiban yang menjadikan mereka satu barisan dalam menangani bahaya-bahaya yang menghadapi mereka.
2 – Menganggap perang dan perdamaian sebagai urusan kedaulatan negara, maka tidak sah bagi individu, atau kelompok untuk menyendiri dalam mengumumkan perang, atau mengadakan perdamaian tanpa negara.
3 – Kehormatan tanah air dan tanahnya, yang pada waktu itu mewakili wilayah Yatsrib, dan kehormatan itu berarti menjaga tanah air dari bahaya apa pun, baik dari dalam maupun dari luar.
4 – Dan akhirnya Piagam mendukung sistem-sistem khusus tentang pelaksanaan tugas kepala negara dengan menjadikannya rujukan dalam setiap perselisihan yang terjadi, baik di antara orang-orang beriman, atau antara mereka dengan tetangga mereka, maka Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah yang mengawasi lapangan-lapangan penerapan semua sistem yang ditetapkan oleh Piagam, dan dia adalah pemutus dalam semua yang berkaitan dengan sistem-sistem tersebut dari penafsiran, atau penjelasan, atau penerbitan keputusan-keputusan, dan kami menyebutkan sebagian dari naskah-naskah dokumen ini:
Telah disebutkan: Dan bahwa tidak berdosa seseorang karena sekutunya, dan bahwa pertolongan untuk yang terzalimi, dan bahwa siapa yang melakukan pembunuhan; maka terhadap dirinya sendiri, dan tidak memperoleh seseorang yang memperoleh kecuali terhadap dirinya sendiri, dan bahwa Allah atas yang paling benar apa yang ada dalam Piagam ini dan paling baik, dan bahwa tidak menghalangi kitab ini terhadap orang yang zalim dan berdosa, dan bahwa siapa yang keluar aman, dan siapa yang tinggal aman di Madinah kecuali orang yang zalim dan berdosa, dan bahwa Allah pelindung bagi siapa yang berbuat baik dan bertakwa, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Dan disebutkan di dalamnya: Dan sesungguhnya kalian apa pun yang kalian perselisihkan tentangnya dari sesuatu maka pengembaliannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan sesungguhnya apa yang terjadi di antara ahli Piagam ini dari peristiwa, atau perselisihan yang ditakutkan kerusakannya; maka pengembaliannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Dan semoga kesejahteraan, rahmat Allah, dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
3 – Sistem Keuangan pada Masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
Lanjutan: Sistem-sistem yang Diletakkan oleh Nabi untuk Jamaah Mukminin di Madinah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, amma ba’du:
Maka sesungguhnya kami telah membicarakan – dalam kuliah yang lalu – tentang lahirnya sistem-sistem Islam dalam negara Islam, dan telah jelas bagi kami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki pengaturan-pengaturan Islam di Makkah, dan pengaturan-pengaturan Islam di Madinah al-Munawwarah, maka adapun pengaturan-pengaturan Islam yang diletakkannya di Makkah; maka itu terwujud dalam meletakkan kaidah-kaidah berikut:
Pertama: Seruan kepada keesaan Allah Ta’ala, dan menjadikan akidah ini sebagai dasar bagi masyarakat baru yang memiliki sistem-sistem dan cita-cita luhurnya.
Kedua: Penetapan ide kebangkitan dan perhitungan setelah kematian, yang menetapkan tanggung jawab individu, dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya, dan bahwa usahanya akan dilihat, dan bahwa tidak menanggung seseorang yang berdosa dosa orang lain, ide ini adalah yang mengalahkan klaim jahiliah yang berdiri atas fanatisme kesukuan.
Ketiga: Menjadikan takwa sebagai pengganti fanatisme kesukuan sebagai dasar untuk membangun nilai-nilai moral yang luhur.
Keempat: Penegasan tentang kesatuan risalah-risalah, dan bahwa sumbernya satu – yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala – dan itu untuk menghapus keberagaman keyakinan dalam kehidupan kesukuan.
Adapun pengaturan-pengaturan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah maka itu terwujud dalam hal-hal berikut:
Pertama: Sistem persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.
Kedua: Penggunaan istilah Islam Muhajirin dan Anshar untuk menunjukkan pelopor-pelopor pengaturan baru negara Islam di Yatsrib.
Ketiga: Penetapan sistem negara, dan hukum sebagai pengganti kesukuan dan adat istiadat.
Keempat: Menganggap sistem kewarganegaraan yang dasarnya adalah hijrah untuk melawan kebatilan.
Kelima: Penetapan sistem musyawarah untuk memperkuat semangat jamaah yang baru, dan mendorong anggota-anggotanya untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu.
Keenam: Penetapan sistem masjid agar menjadi pusat pancaran untuk agama dan dunia sekaligus; di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para khalifah setelahnya melakukan politik dari dalam masjid, dan telah jelas bagi kami bahwa telah terwujud sistem-sistem dasar, dan kewajibannya dalam konstitusi permanen yang diletakkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menetapkan hubungan-hubungan, bukan antara jamaah mukminin sebagian mereka dengan sebagian lain saja, tetapi antara mereka dan tetangga mereka dari penduduk Madinah juga, dan konstitusi ini yang terkenal dengan nama Piagam menjadi dasar negara Islam yang baru lahir, dan sumber terpenting dari sumber-sumber sistem-sistem Islam yang menyertai perkembangan negara ini, dan perluasannya sepanjang masa, dan konstitusi ini – atau Piagam ini – telah menetapkan sistem-sistem dan prinsip-prinsip penting berikut:
Prinsip pertama: yaitu konsep umat, dan hak-hak kewarganegaraan, dan prinsip ini mencakup pasal-pasal:
Pasal pertama: Konstitusi mendefinisikan umat dengan definisi yang tidak bersandar pada dasar-dasar dan sistem kesukuan, dan apa yang dikaitkan dengannya dari fanatisme dan nasab, melainkan menetapkan bahwa umat mencakup setiap orang yang memeluk agama baru tanpa memandang asal atau sukunya, dan prinsip ini menjadi unsur penting yang menjadikan umat yang baru sebagai umat yang fleksibel, dapat diperluas, dan menggabungkan banyak bangsa ke dalam pangkuannya, dan konsep baru tentang umat ini terwujud dalam pendahuluan konstitusi, di mana ia menetapkan bahwa orang-orang beriman, dan Muslim dari Quraisy, dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka lalu bergabung dengan mereka, dan berjihad bersama mereka adalah satu umat selain manusia lainnya.
Pasal kedua: Konstitusi menegaskan bahwa umat ini tidak mengakui pembedaan kelas, atau eksploitasi individu sebagaimana yang berlaku dalam sistem kesukuan, melainkan membuka jalan untuk melebur perbedaan-perbedaan dengan menjadikan suku-suku sebagai formasi sosial untuk melayani umat yang baru.
Adapun Pasal ketiga: maka konstitusi menentukan di dalamnya hak-hak dan kewajiban umat yang masih muda dengan formasi barunya berdasarkan dasar-dasar berikut:
Saling menyayangi, dan bekerja sama di antara anggotanya dalam berbagai bidang – dan khususnya mereka yang terbebani utang, dan perlunya membantu mereka untuk lepas dari beban utang-utang tersebut.
Dan juga menentukan tanggung jawab individu, dan mengatur hubungannya dengan keluarga dan tetangganya dari segi kesetiaan, dan itu sesuai dengan kondisi negara, dan sistemnya yang baru.
Adapun Prinsip kedua yang tercakup dalam konstitusi ini, atau Piagam tersebut adalah: supremasi hukum, dan tindakan pelaksanaan; maka Piagam telah mengatur kehidupan manusia di dalam negara yang baru berdasarkan supremasi hukum, dan tindakan pelaksanaan yang terkait dengannya, maka jika seseorang melanggar keamanan, atau melakukan perbuatan keji; maka umat secara keseluruhan yang akan menjatuhkan hukuman yang diperlukan, dan bahwa semua orang dituntut untuk bersatu dalam pelaksanaan hukuman tersebut, walaupun itu anak salah seorang dari mereka, dan terkait dengan supremasi hukum adalah pengubahan balas dendam menjadi hukuman, dalam arti: bahwa itu adalah tindakan yang menjadi tanggung jawab umat, setelah sebelumnya klan-klan, dan suku-suku yang melakukannya menurut sistem kesukuan yang batil.
Adapun prinsip ketiga yang tercakup dalam konstitusi atau lembaran ini adalah: kebebasan beragama, dan penentuan hubungan para pemeluknya dengan negara. Lembaran ini menjadi prinsip penting dari prinsip-prinsip negara baru, yaitu penetapan kebebasan agama-agama samawi, dan bahwa para pemeluknya dianggap sebagai warga negara yang berhak menikmati perlindungan negara, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam konstitusi baru. Karena suku-suku Yahudi dan kabilah-kabilahnya merupakan unsur terpenting dari penduduk di negara Islam baru di Yatsrib, maka lembaran itu menyatakan dengan jelas tentang hak dan kewajiban mereka, baik terhadap tetangga mereka dari warga Muslim, maupun terhadap negara dan otoritasnya.
Adapun prinsip keempat: telah berbicara tentang pemberlakuan syarat-syarat yang sama oleh lembaran ini, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi yang berbeda dengan Aus dan Khazraj saja, tetapi juga kepada suku-suku Yahudi besar—jika mereka menginginkan hal itu—dan lembaran ini menegaskan keadilannya dalam memperlakukan orang Yahudi bahwa mereka tidak akan diambil semuanya karena kejahatan individu, melainkan setiap kelompok dari mereka akan diperlakukan sesuai dengan apa yang timbul dari mereka.
Adapun prinsip kelima: telah berbicara tentang kedaulatan negara, dan penetapan manifestasi kedaulatan tersebut. Lembaran ini memahkotai syarat-syaratnya dengan penetapan sistem-sistem khusus kedaulatan negara, dan penjelasan hak-hak kepala negara tersebut, yaitu Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah kedaulatan negara terwujud dalam hal-hal berikut:
Poin pertama: bersatunya seluruh penduduk untuk menangkis setiap agresi yang menyentuh kedaulatan negara, baik agresi ini menimpa individu, atau kelompok yang aktivitas atau tugasnya berkaitan dengan urusan negara dan keamanannya.
Dan poin kedua: menganggap perang dan perdamaian sebagai urusan kedaulatan negara; maka tidak sah bagi individu, atau kelompok untuk menyendiri dalam mengumumkan perang, atau mengadakan perdamaian tanpa negara.
Adapun poin ketiga: adalah kehormatan tanah air dan tanahnya, yang ketika itu mewakili wilayah Yatsrib, dan kehormatan itu berarti menjaga keselamatan tanah air dari segala bahaya, baik dari dalam maupun luar.
Adapun poin keempat: lembaran ini mendukung sistem-sistem khusus pelaksanaan tugas kepala negara; dengan menjadikannya rujukan dalam setiap perselisihan yang terjadi, baik antara orang-orang mukmin, atau antara mereka dengan tetangga mereka. Maka Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam adalah yang mengawasi lapangan-lapangan penerapan semua sistem yang ditetapkan oleh lembaran itu, dan dia adalah pemutus dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem-sistem tersebut dari segi penafsiran, atau penjelasan, atau penerbitan keputusan.
Lembaran ini menyatakan hal itu sebagai berikut: “Dan sesungguhnya apa saja yang kalian perselisihkan padanya dari sesuatu maka rujukannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya apa saja yang terjadi di antara pemilik lembaran ini berupa peristiwa, atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya; maka rujukannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.”
Itulah lembaran atau konstitusi yang dibuat oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke Madinah, dan hijrah ke sana. Hak dan kewajiban telah diatur dalam konstitusi ini, dan hubungan antara Muslim dan lainnya dari non-Muslim diatur sesuai dengan konstitusi ini. Namun perlu diperhatikan bahwa sistem politik konstitusi atau lembaran ini telah melewati tiga fase besar, dan pada akhirnya mencapai tingkat sistem Islam yang sempurna yang akan kami jelaskan berikut ini:
Kami katakan: Periode yang terletak antara pembuatan lembaran dengan penduduk Yatsrib dan wafat Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan pengembangan sistem-sistem baru, sesuai dengan pertumbuhan negara Islam, dan penyelarasan antara lembaga-lembaganya juga, hingga semuanya membentuk sistem Islam yang sempurna, dan aspek penerapan ini menjadi mata air yang darinya umat Islam mengambil secara turun-temurun, dan mereka mengangkat kaidah-kaidah negara yang diwariskan kepada mereka oleh Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam dan meletakkan untuknya pada saat yang sama sistem-sistem yang sesuai dengan setiap tahap dari tahap-tahap perluasan negara Islam di berbagai penjuru dunia. Hal itu karena lembaran atau konstitusi yang telah kita bicarakan adalah ide yang kreatif, yang mewujudkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh negara Islam dalam sistem politik yang mampu menghadapi sistem-sistem politik yang memusuhinya, dan mengalahkan mereka satu per satu di Yatsrib pertama, kemudian di seluruh penjuru semenanjung Arab, dan negeri-negeri tetangganya kedua. Sistem politik lembaran ini melewati tiga fase besar—sebagaimana yang kami katakan—dan pada akhirnya mencapai tingkat sistem Islam yang sempurna dengan kelayakan yang ideal, dan pengalaman yang unik.
Fase pertama mencakup lima tahun pertama hijrah Nabi yang mulia, dan dalam fase ini sistem lembaran mampu menjamin perlindungan bagi dakwah Islam yang baru lahir di Yatsrib dari semua musuh-musuhnya di luar—dan di depan mereka adalah Quraisy—dan dari musuh-musuhnya di dalam—dan di depan mereka adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Fase ini berakhir pada tahun kelima dengan terkalahkannya bahaya luar dalam Perang Khandaq, kemudian pengusiran suku Bani Quraizhah, suku Yahudi terakhir dari Yatsrib; sebagai balasan atas pengkhianatan mereka terhadap syarat-syarat lembaran atau konstitusi yang sebelumnya telah kami bicarakan yang telah mereka sepakati.
Sistem baru di Yatsrib telah membuktikan kekuatannya di medan luar dan dalam secara berturut-turut, yaitu dalam hal-hal berikut:
- Kemenangan atas Quraisy dalam Perang Badar, dan perlindungan Yatsrib dari bahaya luar pertama terhadap kehormatannya.
- Pengusiran Bani Qainuqa orang-orang Yahudi dari Yatsrib setelah Perang Badar; karena keluar dari sistem Islam baru.
- Berhadapan dengan Quraisy sekali lagi dalam Perang Uhud.
- Pengusiran Bani Nadhir orang-orang Yahudi dari Yatsrib; karena melanggar syarat-syarat perjanjian dengan sistem Islam baru di Yatsrib.
- Menangkis serbuan besar yang dilakukan oleh Quraisy, dan sekutu-sekutu mereka dari orang-orang Badui, dan Yahudi, terhadap Yatsrib, yaitu dalam Peristiwa Khandaq tahun 5 Hijriah.
Ini adalah periode pertama, atau fase pertama dari fase-fase lembaran atau konstitusi.
Kemudian sistem politik lembaran ini berpindah dari tahap ketahanan setelah Peristiwa Khandaq ke tahap penguatan dan peluncuran, yaitu tahap yang mengisi tahun-tahun fase kedua, dan berakhir dengan Perjanjian Hudaibiyah pada tahun ketujuh Hijriah; karena sistem ini mampu merebut dari Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyah pengakuan atas eksistensi dan kekuasaannya, dan juga mampu membuat sistem-sistem kesukuan berubah dari tahap penyerangan dan serangan ke tahap penarikan diri dan persiapan untuk menyerah. Perkembangan penting ini terwujud dalam penerimaan Quraisy—sebagai kepala sistem-sistem kesukuan—mengizinkan Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan aliansi apa pun yang dikehendakinya dengan suku-suku lainnya, dan memasukkan mereka ke dalam sistem politiknya, dan sesuai dengan syarat-syarat dan komitmennya.
Syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan besar bagi sistem Islam di Yatsrib, meskipun banyak orang—ketika itu—tidak menyadari kebenaran ini. Syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut:
Pertama: Bahwa Muhammad kembali pada tahunnya ini dari Makkah, dengan ketentuan akan memasukinya pada tahun berikutnya, dan Quraisy mengosongkannya untuk beliau selama tiga hari untuk thawaf di Baitullah.
Kedua: Mengadakan gencatan senjata antara Quraisy dan Muslim selama sepuluh tahun, di mana setiap pihak aman dari pihak lainnya.
Ketiga: Mengizinkan suku-suku untuk masuk dalam aliansi Muhammad jika mereka menginginkan, dan masuk dalam aliansi Quraisy siapa yang menginginkan juga. Syarat ini dianggap sebagai keuntungan terpenting sistem Islam, dan kemampuannya untuk menyaingi kedaulatan Makkah sendiri atas negeri Arab.
Keempat: Tercantum dalam syarat-syarat perjanjian ini bahwa siapa yang datang kepada Muhammad dari penduduk Makkah tanpa izin walinya akan dikembalikan kepada mereka, dan siapa yang datang dari sahabat-sahabat Muhammad tidak akan dikembalikan. Syarat ini membuat kaum Muslim marah, dan mereka berdebat dengan Rasul shallallahu alaihi wasallam yang bersikeras untuk melaksanakan perjanjian karena di dalamnya terdapat keuntungan-keuntungan besar yang akan datang sebagaimana yang telah jelas bagi kita setelah itu.
Fase ketiga dan terakhir dari fase-fase sistem politik ditandai dengan fleksibilitas, dan kemampuan lembaga-lembaganya untuk bekerja di luar Yatsrib, dengan efisiensi yang sama seperti yang dilakukan di dalam Yatsrib sendiri. Sistem ini menyebarkan syarat-syarat, perjanjian-perjanjian, dan komitmennya setelah Perjanjian Hudaibiyah, sistem ini menyebarkan kepada suku-suku yang kepercayaan mereka goyah terhadap Quraisy, dan kepercayaan mereka goyah terhadap kepemimpinan Quraisy atas sistem-sistem kesukuan. Sistem ini juga mengembangkan syarat-syarat tersebut pada saat yang sama sehingga mempersiapkan bagi suku-suku tersebut iklim yang baik untuk memahami agama Islam, dan memeluknya berdasarkan keyakinan dan keimanan. Salah satu manifestasi terpenting dari perkembangan baru adalah masuknya Khuzaah—suku Khuzaah—dalam aliansi Rasul shallallahu alaihi wasallam. Suku ini adalah sekutu Abdul Muthalib kakek Nabi shallallahu alaihi wasallam sebelum Islam, dan berkeinginan untuk memperbarui piagamnya dengan Rasul shallallahu alaihi wasallam. Tercantum dalam aliansinya dengan Abdul Muthalib sebagai berikut:
“Dan bahwa Abdul Muthalib dan anak-anaknya dan orang-orang Khuzaah saling bahu-membahu dan saling membantu, dan Abdul Muthalib wajib memberikan pertolongan kepada mereka, dan Khuzaah wajib memberikan pertolongan kepada Abdul Muthalib dan anak-anaknya terhadap semua orang Arab.” Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengakui aliansi ini, setelah menambahkan dua syarat yang sesuai dengan sistem Islam baru, yaitu:
Pertama: Tidak membantu Khuzaah jika mereka adalah orang-orang yang zhalim.
Kedua: Menolong Khuzaah jika mereka dizhalimi. Hal itu karena Khuzaah belum masuk Islam, dan Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam menolak kecuali dasar aliansi adalah dasar sistem Islam yang tidak mengakui aliansi kesukuan, dan kaidahnya yang usang yang mengatakan: Tolong saudaramu baik dia zhalim atau dizhalimi. Fase ketiga ini berakhir dengan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, dan memasukkan benteng kokoh ini—yaitu Makkah—ke dalam kehidupan kesukuan, adalah benteng kokoh bagi kehidupan kesukuan, dan sistem-sistemnya berkat Fathu Makkah.
Benteng ini masuk dalam lingkaran sistem politik jamaah Muslim di Yatsrib, dan kemenangan nyata ini bagi sistem politik lembaran diikuti dengan perubahan mendasar dalam kehidupan kesukuan di berbagai penjuru semenanjung Arab; karena suku-suku Arab—dalam Fathu Makkah—dalam hal itu melihat bukti atas runtuhnya era sistem-sistem kesukuan dengan apa yang mereka sandari dari kebodohan yang bodoh, dan fanatisme yang buta. Suku-suku tersebut mulai masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, dan mengirim delegasi-delegasi mereka pada tahun kedelapan Hijriah, dan sepanjang tahun kesembilan Hijriah juga, mengumumkan kepada Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam di Yatsrib keterikatan mereka dengan sistem politiknya, dan mendapatkan apa yang mereka inginkan juga dari perjanjian-perjanjian dan piagam-piagam.
Rasul yang mulia mendapati bahwa perkembangan dahsyat ini menuntut modifikasi luas dalam sistem politik yang sebelumnya telah beliau tegakkan berdasarkan lembaran—atau konstitusi yang telah kita bicarakan—dengan keharusan berupaya memberikan sistem ini bentuk akhir, yang sesuai dengan kedaulatan tertinggi yang beralih kepadanya atas seluruh penjuru semenanjung Arab.
Ciri-ciri modifikasi terakhir terpusat pada pengaturan hak-hak kewarganegaraan negara Islam dengan cara yang menghilangkan setiap manifestasi perbedaan di antara anak-anaknya, dan yang mengarah pada pengumpulan mereka dalam satu kesatuan; untuk membawa risalah negara tersebut, yaitu menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia; karena Islam adalah dakwah universal untuk semua manusia: “Dan Kami tidak mengutusmu kecuali kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan” (Saba: 28) “Dan Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (Al-Anbiya: 107).
Bagian pertama dari modifikasi terakhir ini adalah mengizinkan orang-orang Yahudi, dan lainnya dari Ahli Kitab untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan bukan melalui perjanjian—sebagaimana ditetapkan dalam lembaran sebelumnya—tetapi melalui pembayaran jizyah. Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang diberi Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri sedang mereka dalam keadaan tunduk” (At-Taubah: 29).
Penetapan sistem ini—yaitu sistem jizyah—berlaku hanya untuk laki-laki yang mampu, tidak termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak. Ini adalah syarat Islam yang membolehkan Ahli Kitab menikmati hak-hak kewarganegaraan di negara baru dengan imbalan perlindungan mereka dan pembebasan mereka dari wajib militer. Karena tujuan utama negara adalah menyebarkan agama Islam, dan agama baru ini mengakui agama-agama samawi seperti Yahudi dan Kristen, maka tidak adil mewajibkan mereka bergabung dengan pasukan militer negara baru. Jizyah menjadi syarat baru yang menggantikan perjanjian dan piagam untuk memperoleh secara resmi hak-hak kewarganegaraan bagi Ahli Kitab dari penduduk negara Islam yang baru lahir.
Bagian kedua dari perubahan terakhir dalam sistem politik khusus untuk selain Ahli Kitab dari suku-suku Arab; maka ditetapkan bahwa memeluk agama Islam adalah syarat pertama dan utama untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan di negara baru. Dengan demikian, tidak ada lagi tempat bagi paganisme untuk bertahan, setelah terbukti bahaya dan kerusakannya, dan setelah Ka’bah dibersihkan dari berhala-berhala—simbol kesyirikan dan lambang eksploitasi sistem kesukuan dan konsep-konsep butanya.
Pada saat yang sama diputuskan untuk tidak mengizinkan kaum musyrik berhaji ke Mekah, karena kewajiban ini telah menjadi simbol keagungan agama baru dan telah menjadi fondasi kokoh bagi negara yang bangkit dan kedaulatannya. Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Surat Al-Hajj: 27, 28, 29)
Bagian ketiga dan terakhir dari perubahan ini khusus mengenai prosedur yang diperlukan oleh manifestasi perluasan hak-hak kewarganegaraan, karena sekelompok orang masuk Islam namun hatinya masih terikat dengan warisan fanatisme kesukuan, atau dipenuhi dengan konsep-konsep kesukuan dan hal-hal yang terkait dengannya seperti bermegah-megahan dan mengejar kemewahan dunia. Kemunafikan atau kekufuran batin semacam ini merupakan salah satu hal yang paling berbahaya bagi hak-hak kewarganegaraan di negara baru, mengapa? Karena sulitnya mengenali pelakunya. Oleh karena itu, perubahan terakhir pada konstitusi memutuskan: melemparkan tugas mengungkap kelompok munafik ini, atau yang disebut di era modern sebagai “kolom kelima”, yang ingin merusak sistem negara, saya katakan: perubahan terakhir memutuskan melemparkan tugas mengungkap kelompok munafik ini, yaitu: yang memainkan hak-hak kewarganegaraan, kepada anggota umat itu sendiri.
Anggota umat sendiri yang mencari golongan manusia semacam ini—orang-orang munafik yang menampakkan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka sembunyikan—karena anggota umat lebih mampu melalui pergaulan sehari-hari mereka untuk mengenali berbagai bentuk penyimpangan dan pelakunya. Syarat moral ini tidak dapat ditangani oleh aparat negara, melainkan dapat dilakukan oleh anak-anak bangsa, dan hanya merekalah yang berhak menyingkirkan kelompok mana pun yang memainkan hak-hak kewarganegaraan atau mencemarkannya. Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirdan: “Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” (Surat At-Taubah: 73, 74)
Perubahan-perubahan baru ini dikeluarkan pada tahun kesembilan Hijriah, dan diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai wakil dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu pada hari Haji Akbar di Mekah. Pengumuman ini terkenal dengan nama “Pernyataan Bara’ah” karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin mengumumkan kepada suku-suku Arab pembebasan beliau dari perjanjian-perjanjian yang tidak lagi ada hubungannya dengan Islam, dan bahwa sistem Islam yang lengkap bersandar pada legislasi langit yang diturunkan melalui “Surat At-Taubah”. Maka dalam teks pengumuman tersebut dibacakan firman Allah Ta’ala: “(Inilah pernyataan) pemutusan (hubungan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (hai orang-orang musyrik itu) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan bahwa Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar, bahwa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik itu. Maka jika kamu (hai orang-orang musyrik) bertaubat, itu adalah lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang kafir, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu; maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana boleh ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan dari sisi Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Surat At-Taubah: 1-7)
Inilah hukum-hukum yang terkandung dalam Surat Bara’ah dari ayat nomor satu sampai ayat keenam. Dengan demikian kita telah selesai menyoroti konsep sistem-sistem Islam, kelahirannya, dan tahap-tahap yang dilalui kelahiran tersebut dalam kehidupan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta pengaturan-pengaturan yang ditetapkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Mekah, demikian juga pengaturan-pengaturan yang ditetapkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah hijrahnya ke Madinah, kemudian konstitusi atau undang-undang dasar ini yang benar-benar merupakan konstitusi yang maju dalam segala bidang, baik dari segi pemerintahan, maupun dari segi administrasi, maupun dari segi penjelasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik terhadap negara, maupun terhadap individu satu sama lain, atau dalam hubungan mereka dengan negara Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara-negara lain.
Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa pada periode ini—dan sebelum Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat dan bergabung dengan Ar-Rafiq Al-A’la—telah ada sistem Islam yang lengkap, dan dengan ini kita cukupkan pembahasan kita dalam perkara ini.
Pelajaran: 3 Sistem Keuangan Negara Islam
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
- Sistem Keuangan di Masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
Zakat sebagai Sumber Keuangan Terpenting di Masa Nabi
Kemudian kita membahas topik lain, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis atau pembagian sistem-sistem Islam:
Pembagian Sistem-Sistem Islam:
Sistem dalam negara mana pun terdiri dari kumpulan hukum, prinsip, dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan di negara tersebut. Di antara manifestasi sistem ini adalah: sistem politik, sistem administratif, sistem keuangan, sistem peradilan, dan sistem-sistem sosial. Kita akan menyoroti sistem-sistem terpenting tersebut sebagai berikut:
Pertama: Sistem Keuangan: Kebijakan keuangan setiap negara bekerja untuk mencapai keseimbangan antara sumber daya dan pengeluarannya; ada pendapatan dan ada pengeluaran. Negara Islam telah menjalankan kebijakan ini sejak kemunculannya; maka dibangunlah Baitul Mal untuk menjaga, memelihara, dan mengelolanya demi kepentingan masyarakat Islam. Ini menyerupai Kementerian Keuangan di era modern, dan penanggungjawabnya menjalankan tugas menteri keuangan, dan ia diberi gelar “Pengelola Baitul Mal”. Sistem keuangan biasanya berputar pada poros dengan dua kutubnya—seperti yang telah kami katakan—yaitu sumber daya dan pengeluaran. Sistem keuangan di negara Islam berjalan sesuai kaidah ini, dan sesuai preseden yang telah ditetapkan di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari segi memperhatikan kepentingan kaum muslimin, tanpa mengabaikan—pada saat yang sama—sunnatullah tentang perkembangan, keadaan zaman dan tuntutannya.
Sistem keuangan negara Islam pun menjadi cermin yang memantulkan pemikiran Islam dengan keluwesan dan realitasnya, sebagaimana sistem politik dan administratif negara tersebut. Dalam pembahasan kita tentang sistem keuangan di negara Islam, patut kita membahas dua hal mendasar dalam perkara atau topik ini:
Hal pertama: yaitu menyoroti sistem keuangan di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu kita membahas tentang sumber-sumber Baitul Mal, atau sumber keuangan negara Islam. Sekarang kita mulai menyoroti sistem keuangan yang berlaku di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan di zaman Khulafaur Rasyidin, maka kita katakan—dengan taufik Allah—:
Pertama: Di Masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Negara Islam di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau masih di Mekah—tidak memiliki sistem keuangan dengan pintu-pintu pendapatan dan pengeluaran yang jelas, melainkan pendapatan negara pada periode ini terwujud dalam harta yang disumbangkan para sahabat untuk dibelanjakan kepada fakir miskin kaum muslimin, atau untuk memenuhi sebagian kebutuhan yang sangat diperlukan. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Madinah, dan bentuk negara Islam mulai tampak dengan jelas dan terang; turunlah ayat-ayat yang mewajibkan zakat atas harta kaum muslimin. Allah Ta’ala berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (Surat At-Taubah: -dari ayat- 103)
Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya.” Dalam hadits ini Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam.
Ayat-ayat Al-Qur’an juga menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.” (Surat At-Taubah: -dari ayat- 60)
Sunnah Nabawiyah menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati, besarnya nisab, dan kewajiban dalam nisab tersebut, kemudian menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada muzakki dan pada harta itu sendiri. Maka zakat menjadi sumber pertama dari sumber-sumber keuangan negara Islam.
Sumber-Sumber Keuangan Terpenting di Masa Nabi: Harta Rampasan Perang, Fai, dan Jizyah
Kemudian datanglah sumber kedua dari sumber-sumber keuangan negara Islam di masa Rasulullah yang mulia shallallahu alaihi wasallam, yaitu harta rampasan perang (ghanimah). Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Anfal dalam firman Allah Ta’ala: “Dan ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Al-Anfal: 41)
Inilah ayat tentang harta rampasan perang—sebagaimana disebut oleh para fuqaha: “Dan ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.” Ayat ini menjelaskan bagaimana cara pembagian harta rampasan perang; seperlima dari harta rampasan perang adalah untuk Rasul shallallahu alaihi wasallam dan untuk kerabatnya, yaitu untuk dibelanjakan dalam kepentingan kaum muslimin. Al-Quran tidak menyebutkan dalam ayat ini tentang empat perlima sisanya; dari sini kita memahami bahwa empat perlima yang tersisa adalah untuk para pejuang yang memperolehnya.
Kemudian datanglah sumber ketiga dari sumber-sumber keuangan negara Islam, yaitu fai (harta yang diperoleh tanpa peperangan) dalam firman Allah Ta’ala: “Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Al-Hasyr: 6-7)
Kemudian datanglah sumber keempat dari sumber-sumber negara Islam, yaitu jizyah (pajak) yang dibebankan kepada non-muslim, sebagaimana firman-Nya Ta’ala: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At-Taubah: 29)
Dari pemaparan singkat ini jelaslah bagi kita bahwa sumber-sumber keuangan negara Islam di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah zakat, harta rampasan perang, fai, dan jizyah.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menunjuk petugas-petugas untuk mengumpulkan harta-harta ini; ada petugas zakat, yaitu yang bertugas mengumpulkan zakat dari kaum muslimin dan memberikannya kepada orang lain yang disebut: al-mustaufi yang menyerahkannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga petugas harta rampasan perang yang ditunjuk dalam setiap peperangan untuk bertugas mengumpulkan harta rampasan dan menjaganya sampai disalurkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syariat. Dan petugas jizyah yang menentukan nilainya, mengumpulkannya dari mereka yang wajib membayarnya. Perlu dicatat bahwa tidak ada baitul mal (perbendaharaan negara) di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan harta-harta ini; karena harta-harta itu dikumpulkan dan langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya; sehingga tidak ada keperluan untuk mendirikan baitul mal.
Bagian untuk Muallaf (Orang yang Dilunakkan Hatinya)
Muallaf mendapat bagian dalam zakat—sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (At-Taubah: 60)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berupaya melunakkan hati banyak orang dengan harta; mengingat kedudukan mereka yang terpandang sehingga ada kebutuhan untuk melunakkan hati mereka demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Di antara mereka adalah Shafwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan anaknya Muawiyah, Al-Harits bin Hisyam, dan lain-lain.
Muallaf terdiri dari tiga golongan:
Golongan pertama: Mereka diberi agar tertarik kepada Islam, seperti Shafwan bin Umayyah. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: Sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberiku padahal ia adalah orang yang paling aku benci, dan beliau terus memberiku sampai ia menjadi orang yang paling aku cintai.
Golongan kedua: Mereka diberi untuk menolak kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, seperti Uyainah bin Hishn dan Al-Aqra’ bin Habis.
Golongan ketiga: Mereka diberi untuk mengokohkan keislaman mereka karena lemahnya keimanan mereka, seperti Abu Sufyan bin Harb yang diberi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam empat puluh uqiyah emas dan seratus ekor unta, dan beliau memberi kedua anaknya Muawiyah dan Yazid. Maka Abu Sufyan berkata kepadanya: “Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, sungguh engkau mulia dalam damai maupun dalam perang.”
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi golongan-golongan ini dari orang Arab pada umumnya, dan dari Quraisy khususnya, dan beliau memberi mereka dengan berlimpah; sampai tidak tersisa apa-apa lagi untuk kaum Anshar. Hal ini mendorong sebagian kaum Anshar untuk mengatakan: “Sungguh ini mengherankan; beliau memberi Quraisy dan meninggalkan kami, padahal pedang-pedang kami masih menetes darah.”
Ketika Rasul mengetahui hal itu, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan mereka, dan berdiri berkhutbah kepada mereka dengan bersabda: “Perkataan apa yang sampai kepadaku dari kalian? Bukankah aku mendapati kalian dalam kesesatan lalu Allah memberi petunjuk kepada kalian melaluiku, dan miskin lalu Allah memperkaya kalian melaluiku, dan bermusuhan lalu Allah mempersatukan hati kalian melaluiku? Sesungguhnya Quraisy baru saja keluar dari kekufuran, dan aku ingin menenangkan mereka dan melunakkan hati mereka. Apakah kalian marah wahai kaum Anshar karena sedikit harta dunia yang dengannya aku lunakkan hati suatu kaum agar mereka masuk Islam, sedangkan aku mempercayakan kalian kepada keislaman kalian”—yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Di sini orang-orang itu menangis dan berkata: “Ya Rasulullah, kami ridha dengan Rasulullah sebagai pembagian dan bagian kami.” Dan mereka ridha dengan hal itu.
Demikianlah perlakuan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap para muallaf.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 – Sistem Keuangan di Masa Abu Bakar dan Umar bin Khaththab Radiyallahu Anhuma
Sistem Keuangan di Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, pemimpin kami Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kami telah membahas dalam kuliah sebelumnya tentang sistem keuangan di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kami membahas tentang sistem keuangan di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radiyallahu anhu wa ardhahu. Kami katakan: Sistem keuangan di masa Abu Bakar radiyallahu anhu tidak berbeda dengan masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, di mana sumber-sumber keuangan negara di masanya adalah sumber-sumber yang sama yang ada di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, berupa zakat, harta rampasan perang, fai, dan jizyah. Abu Bakar menjalankan kebijakan keuangan yang sama dengan yang dijalankan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sehingga radiyallahu anhu menyamakan pemberian kepada semua orang.
Diriwayatkan dari beliau bahwa ia berkata: Barangsiapa yang pernah dijanjikan sesuatu oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia datang. Maksudnya: barangsiapa yang pernah dijanjikan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam sesuatu dari harta, maka hendaklah ia datang kepada kami. Barangsiapa yang pernah dijanjikan sesuatu oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia datang. Maka datanglah Jabir bin Abdullah dan berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku: Jika datang harta dari Bahrain, aku akan memberimu begini dan begini. Abu Bakar berkata kepadanya: “Ambillah.” Maka ia mengambil apa yang cukup untuknya, kemudian menghitungnya dan mendapati lima ratus. Abu Bakar berkata: “Ambillah lagi seribu.” Maka ia mengambil seribu. Kemudian ia memberi setiap orang yang pernah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan tersisa sedikit harta, maka ia membaginya di antara orang-orang dengan sama rata kepada anak kecil dan dewasa, merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan. Maka keluar tujuh dirham sepertiga untuk setiap orang.
Ketika tahun berikutnya datang harta yang banyak, lebih banyak dari itu, maka radiyallahu anhu membaginya di antara orang-orang sehingga bagian setiap orang adalah dua puluh dirham. Maka datanglah sekelompok kaum muslimin dan berkata: “Wahai khalifah Rasulullah, engkau membagi harta ini dan menyamakan semua orang, padahal di antara mereka ada orang-orang yang memiliki keutamaan, kepeloporan, dan kedahuluan dalam Islam. Seandainya engkau memberi keutamaan kepada orang-orang yang memiliki keteguhan, kedahuluan, dan keutamaan sesuai dengan keutamaan mereka.” Maksudnya: seakan-akan mereka meminta Abu Bakar—radiyallahu tabaraka wa ta’ala anhu—agar tidak menyamakan semua orang dalam pemberian. Yaitu sesuatu yang mirip dengan gaji yang diberikan negara kepada pegawai. Mereka memintanya agar tidak menyamakan semua orang dalam pemberian, tetapi membedakan mereka berdasarkan kedudukan dalam Islam, apakah ia lebih dahulu masuk Islam dari yang lain atau memiliki kedudukan dalam Islam. Maka ia berkata: “Adapun apa yang kalian sebutkan tentang kepeloporan, kedahuluan, dan keutamaan, maka aku sangat mengetahui hal itu—maksudnya: aku mengetahui itu dengan baik—dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang pahalanya ada pada Allah jalla tsana’uhu, dan ini adalah penghidupan, maka kesamaan di dalamnya lebih baik daripada membedakan.”
Karena Abu Bakar tidak menyetujui mereka dalam hal itu, yaitu membedakan antara orang-orang dalam pemberian, tetapi ia berkata kepada mereka: Aku mengenal orang-orang yang memiliki kedudukan dalam Islam dan kepeloporan dalam Islam, dan sebagainya. Maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi harta ini adalah penghidupan bagi orang-orang untuk hidup dengannya, maka kesamaan di dalamnya dan kesetaraan di dalamnya lebih baik daripada membedakan, maksudnya lebih baik daripada aku membedakan sebagian orang atas sebagian yang lain dalam hal itu.
Jelaslah bagi kita dari ini bahwa Abu Bakar radiyallahu anhu menyamakan pemberian di antara orang-orang, dan tidak memberi keistimewaan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan dalam menolong Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau yang lebih dahulu memeluk Islam; karena apa yang ia berikan kepada orang-orang adalah penghidupan bagi mereka.
Melunakkan Hati untuk Islam
Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardhahu menjalankan kebijakan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam melunakkan hati sebagian orang untuk Islam, atau menolak kejahatan mereka, atau mengokohkan keislaman mereka karena lemahnya keimanan mereka. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi kepada tiga golongan manusia, seperti yang telah kami katakan, maka Abu Bakar juga berusaha untuk memberi ketiga golongan manusia ini. Ia ingin melunakkan hati mereka, atau menolak kejahatan mereka, atau mengokohkan keislaman mereka, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun terjadilah bahwa Uyainah bin Hishn dan Al-Aqra’ bin Habis datang meminta tanah dari Abu Bakar. Maka ia menyetujui hal itu dan menuliskan surat untuk mereka berdua. Umar bin Khaththab hadir saat itu, maka ia mengambil surat itu dan merobeknya.
Seakan-akan Umar bin Khaththab tidak menyukai perbuatan ini dari Abu Bakar—radiyallahu tabaraka wa ta’ala anhu—dan tidak menyetujui Abu Bakar untuk memberi mereka sesuatu dari tanah-tanah negara Islam. Ia merobek surat itu dan berkata kepada mereka: “Ini adalah sesuatu yang diberikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada kalian untuk melunakkan hati kalian terhadap Islam. Dan sekarang setelah Allah memuliakan Islam dan mencukupkan dari kalian, maka jika kalian bertaubat kepada Islam (maka baik), dan jika tidak, maka antara kami dan kalian adalah pedang.” Kemudian ia membaca firman Allah Ta’ala: “Kebenaran itu dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (Al-Kahfi: dari ayat 29)
Maka keduanya berkata kepada Abu Bakar: maksudnya: Uyainah bin Hishn dan Al-Aqra’ bin Habis berkata kepada Abu Bakar: “Khalifah itu engkau atau Umar, wahai Abu Bakar?!!”
Mereka berbicara dengan Abu Bakar dan berkata kepadanya: Siapa khalifah? Dan perkataan siapa yang berlaku? Engkau ingin memberi kami tanah untuk melunakkan hati, sedangkan ia melarang kami dari itu. Maka siapa khalifah, engkau atau Umar?!! Maka Abu Bakar yang bijaksana berkata: “Dialah, insya Allah.” Dan ia menyetujui pendapat Umar. Maksudnya Abu Bakar radiyallahu tabaraka wa ta’ala anhu menyetujui Umar atas apa yang ia lakukan, dan tidak memberi kepada Uyainah bin Hishn dan Al-Aqra’ bin Habis apa yang mereka minta darinya berupa tanah.
Sebagian orang telah berupaya untuk tidak membayar zakat setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersandar pada firman Allah tabaraka wa ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” (At-Taubah: dari ayat 103) Dan setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat, mereka menolak membayar zakat. Mengapa mereka menolak membayar zakat? Mereka berkata: Karena Allah tabaraka wa ta’ala memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat ketika Ia berfirman: “Ambillah zakat dari harta mereka.” (At-Taubah: dari ayat 103) Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka kami tidak membayar sedekah itu atau tidak membayar zakat itu. Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam-lah yang mengambil zakat dari mereka. Jika beliau shallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka mereka tidak membayar zakat tersebut. Oleh karena itu Abu Bakar bersikap tegas terhadap penafsiran yang keliru terhadap ayat ini.
Abu Bakar marah dan tidak menyukai hal itu, meskipun ia memiliki sifat lemah lembut dan kesabaran yang luas. Ia mengambil sikap keras dan tegas terhadap mereka, dan memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat dan mengumpulkannya dari mereka dengan kekuatan bersenjata. Di sini Umar bin Khaththab radiyallahu anhu menyampaikan kepadanya dengan berkata: “Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: ‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan: Laa ilaaha illallah. Barangsiapa yang mengucapkannya, maka ia telah melindungi hartanya dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya ada pada Allah.'”
Abu Bakar ketika hendak memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat karena penafsiran yang keliru terhadap ayat ini, Umar bin Khaththab keberatan terhadap hal itu dan berkata kepadanya: Wahai Abu Bakar! Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadits bahwa seseorang jika bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ia tidak diperangi. Ketika beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan: Laa ilaaha illallah. Barangsiapa yang mengucapkannya, maka ia telah melindungi hartanya dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya ada pada Allah.” Seakan-akan ia keberatan kepada Abu Bakar, maksudnya: mengapa engkau ingin memerangi mereka padahal mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan yang terjadi dari mereka hanyalah mereka menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar menjawab Umar dan berkata: “Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku seekor kambing kecil yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena menolaknya.”
Ini adalah sikap tegas dari Abu Bakar—radiyallahu tabaraka wa ta’ala anhu—karena ia memandang bahwa zakat itu sama dengan shalat, dengan bukti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu dalam rukun-rukun Islam, ketika beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima hal: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu.” Maka zakat berada dalam satu tingkatan dengan shalat, ia adalah rukun dari rukun-rukun Islam, sebagaimana shalat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Oleh karena itu Abu Bakar menjawab Umar ketika ia berkata kepadanya: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengatakan: Laa ilaaha illallah, ia telah melindungi hartanya dan darahnya dariku kecuali dengan haknya.” Dan ini adalah hak Islam, yaitu zakat. Oleh karena itu Umar berkata: “Demi Allah, tidak lain adalah Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radiyallahu anhu, maka aku mengetahui bahwa itu adalah kebenaran.”
Jadi Umar yang tidak takut celaan orang yang mencela dalam urusan Allah, dan kebenaran mengalir di lisannya sebagaimana diberitakan kepada kita oleh beliau shallallahu alaihi wasallam, menyetujui Abu Bakar atas apa yang ia lakukan, yaitu ia bermaksud memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat—sumber keuangan Islam ini. Abu Bakar menjelaskan kepadanya alasannya, maka ia yakin dan menyetujuinya dalam hal itu.
Perkembangan Sistem Keuangan di Masa Umar bin Khattab
Kemudian kita beralih sekarang kepada perkembangan sistem keuangan di masa Umar bin Khattab:
Sumber-sumber daya baru yang mengalir ke Negara Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin telah mengungkapkan awal-awal respons peradaban antara era Islam yang baru dengan peradaban negeri-negeri yang ditaklukkan dalam bidang pengorganisasian keuangan. Dan yang meletakkan dasar-dasar respons ini adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang tindakan-tindakannya dalam hal tersebut juga merupakan landasan dasar di samping kaidah-kaidah keuangan Rasul yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam, yang kemudian diikuti oleh seluruh khalifah-khalifah Muslim setelah beliau. Khalifah ini—Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu—bertujuan untuk menyelamatkan penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan dari kezaliman dan kesulitan keuangan yang berat yang sebelumnya mereka alami, dan sekaligus berupaya untuk menyediakan bagi negara yang baru berdiri itu sumber-sumber daya yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan politiknya, ekonominya, dan juga militernya. Khalifah Umar bin Khattab dalam menyelesaikan persamaan baru ini—persamaan dalam hal apa?
Persamaan ini terletak pada bahwa Negara Islam memerlukan uang untuk membiayai banyak kebutuhannya, dan pada saat yang sama tidak menzalimi orang-orang yang diambil darinya sumber-sumber keuangan tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang memikirkan penyelarasan dan penyeimbangan antara dua hal ini: bagaimana kita memperoleh uang untuk negara, dan pada saat yang sama tidak menzalimi orang-orang yang kita ambil darinya uang tersebut?
Saya katakan: Khalifah Umar bin Khattab dalam menyelesaikan persamaan baru ini yang dihadapi negaranya mengandalkan landasan yang sama yang ia ikuti dalam pengorganisasian administrasi, yaitu dengan mempertahankan sistem-sistem keuangan yang sebelumnya telah diterapkan di negeri-negeri yang ditaklukkan sambil memperbarui kehidupannya dengan keadilan Islam dan perundang-undangan keuangannya yang luhur. Dan ia menunjukkan dalam hal tersebut keberanian yang jarang ada bandingannya, wawasan yang luas, dan kearifan tinggi yang membuatnya layak disebut sebagai pendiri kedua Negara Islam. Hal itu karena masalah serius muncul segera setelah penaklukan Syam, Irak, dan Mesir, ketika tentara penakluk menuntut agar tanah-tanah di negeri-negeri tersebut dibagikan di antara mereka sesuai dengan kaidah khusus tentang ghanimah perang yang menetapkan bahwa pembagian dilakukan menjadi lima bagian, salah satunya dibagikan sesuai dengan ayat mulia tentang ghanimah, dan empat perlima lainnya menjadi milik para penakluk.
Para penakluk yang memperoleh tanah dari dataran Irak ini, di antara ghanimah yang mereka kuasai adalah tanah-tanah. Mereka mengambil tanah-tanah ini beserta orang-orang yang ada di atasnya, lalu mereka berkata: ini adalah ghanimah, dan mereka menuntut Sayyidina Umar untuk menerapkan sistem ghanimah dan pembagian ghanimah yang disebutkan dalam Surah Al-Anfal dalam firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin” (QS. Al-Anfal: 41). Seolah-olah ayat tersebut—sebagaimana telah kita katakan—ayat tentang ghanimah menjelaskan bahwa ada seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya, dan seperlima lainnya diberikan kepada para penakluk dan pejuang. Dan inilah yang diterapkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada masa beliau. Ghanimah dibagikan seperti ini, dibagi menjadi lima bagian, satu bagian fi sabilillah, kemudian empat perlima sisanya dibagikan kepada para penakluk.
Sebagaimana telah kita katakan, inilah yang diterapkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada masa beliau dan juga diterapkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu. Ghanimah dibagikan dengan cara ini: seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya, dan empat perlima sisanya dibagikan kepada para penakluk. Dan inilah yang dituntut oleh para penakluk, dan yang kita maksud dengan para penakluk di sini adalah mereka yang memerangi orang-orang kafir dan menguasai tanah ini dari mereka—yaitu para pejuang. Ayat menjelaskan bahwa mereka berhak atas empat perlima; oleh karena itu mereka berpegang pada ayat tersebut dan menuntut dari Sayyidina Umar radhiyallahu ‘anhu agar membagikan tanah ini kepada mereka. Dan itu adalah tanah yang sangat luas dan sangat subur, dan mereka menuntut darinya agar membagikan tanah ini kepada mereka.
Saya katakan: para komandan tentara di berbagai wilayah menulis kepada Khalifah Umar bin Khattab menanyakan pendapatnya terkait tuntutan tentara untuk membagi tanah-tanah yang ditaklukkan di antara mereka, di antaranya Sa’ad bin Abi Waqqash yang pertama kali menghadapi masalah ini di dataran Irak, yaitu: tanah Irak. Kemudian menyusul surat dari Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah kepada Umar tentang pembagian kota-kota dan penduduknya serta tanah di Syam, dan apa yang ada di dalamnya dari pohon-pohon dan tanaman.
Saya katakan: Sayyidina Umar ketika berita ini sampai kepadanya, dan sampai kepadanya bahwa tentara yang memperoleh tanah ini menuntut agar tanah ini dibagi—empat perlimannya—di antara mereka, Sayyidina Umar bin Khattab tidak menyetujui hal itu, dan ia memiliki pendapat yang berbeda.
Dan sebagaimana telah kita katakan, Sayyidina Umar bin Khattab selalu memandang kepada kemaslahatan umat Islam yang lebih tinggi; oleh karena itu apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab dalam menghadapi masalah yang ia hadapi ini? Masalahnya adalah ia ingin tanah ini tetap berada di tangan pemiliknya dan dikenakan kharaj (pajak tanah), dan kharaj ini akan menjadi milik kaum Muslimin yang ada sekarang dan yang datang setelah itu. Tetapi para pejuang atau penakluk tidak menginginkan itu, dan mereka ingin ghanimah dibagikan kepada mereka sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu.
Saya katakan: Sayyidina Umar bin Khattab—sebagaimana biasanya—ketika menghadapi suatu perkara dari perkara-perkara penting dan besar ini, ia tidak memonopoli pendapat, melainkan ia bermusyawarah. Dan bagaimana tidak, sedangkan ia yang membaca firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (QS. Ali Imran: 159) dan firman-Nya: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (QS. Asy-Syura: 38)? Sayyidina Umar adalah di antara orang-orang yang paling banyak menerapkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, oleh karena itu kebiasaannya dalam setiap urusan yang ia hadapi adalah memaparkan urusan ini kepada kaum Muslimin untuk bermusyawarah, dan mengambil pendapat yang mereka sepakati.
Khalifah Umar memutuskan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dan ulama mereka dalam masalah baru yang serius ini, karena belum pernah sebelumnya kaum Muslimin menguasai tanah seluas itu, yang penuh kesuburan, makmur dengan penduduk, kota-kota, dan kekayaan. Dan terjadilah perbedaan pendapat antara Umar dengan para penasihatnya dari kalangan sahabat Muhajirin, karena sudut pandang Khalifah Umar radhiyallahu ‘anhu adalah bahwa pembagian tanah di antara tentara akan merampas negara dari sumber penting yang diperlukan untuk membiayai fasilitas-fasilitas umum, perlindungan negara, dan lain-lain dari tuntutan perkembangan sosial dan ekonomi.
Dan pendapat ini ditentang oleh sekelompok pembesar Muhajirin, yaitu: beberapa Muhajirin menentang Sayyidina Umar dalam pendapat ini. Di garis depan mereka yang menentang Sayyidina Umar dalam pendapat ini adalah Abdurrahman bin Auf, yang mempertegas perkataannya kepada Khalifah Umar, dengan mengatakan: bahwa tidak membagi tanah merampas hak dasar para penakluk. Dan yang dimaksud oleh Abdurrahman bin Auf dengan hak-hak dasar ini adalah hak-hak yang telah ditetapkan bagi mereka oleh ayat ghanimah: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin” (QS. Al-Anfal: 41) sampai akhir ayat. Ayat menetapkan bahwa empat perlima ghanimah adalah untuk para penakluk; oleh karena itu Sayyidina Umar—Abdurrahman bin Auf—menjelaskan kepada Khalifah Umar bahwa pembagian tanah di antara para penakluk adalah hak mereka, karena mereka bersandar pada ayat yang jelas, yaitu ayat ghanimah: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang” (QS. Al-Anfal: 41).
Dan kemudian Khalifah memutuskan untuk membentuk komite dari sepuluh orang pembesar Anshar yang akan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin, yang terdiri dari lima orang dari Aus dan lima orang dari Khazraj. Sebagaimana telah kita katakan, Sayyidina Umar bin Khattab menemukan orang-orang yang menentang pendapatnya. Sayyidina Umar bin Khattab ingin tanah tetap di tangan pemiliknya dan dikenakan kharaj atau pajak, dan kharaj atau pajak ini dimasukkan ke baitul mal dan dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan kaum Muslimin yang banyak. Tetapi mereka yang menentangnya, terutama tentara, mengatakan bahwa tanah ini harus dibagi kepada para penakluk, dan tidak dibiarkan di tangan pemiliknya agar dikenakan kharaj atau pajak. Sebagaimana telah kita katakan, Sayyidina Umar bin Khattab memilih sepuluh orang dari pembesar sahabat, lima dari Aus dan lima dari Khazraj. Ia ingin memaparkan masalah kepada mereka, dan memaparkan kepada mereka perselisihan yang terjadi antara dirinya dengan para penakluk dan beberapa sahabat. Ia ingin memaparkan pendapat kepada mereka kemudian mengambil pendapat mereka tentang masalah ini.
Khalifah Umar bin Khattab menjelaskan sudut pandangnya terhadap masalah yang diajukan di hadapan komite sepuluh orang besar itu, ia berkata: “Bagaimana pendapat kalian tentang daerah-daerah perbatasan ini?” Daerah perbatasan ini maksudnya tempat-tempat yang mungkin datang darinya musuh ke Negara Islam dan menyerang negara. Yaitu tempat-tempat yang seharusnya ada tentara di dalamnya untuk menjaga Negara Islam dari musuh-musuh tetangganya. “Bagaimana pendapat kalian tentang daerah-daerah perbatasan ini, ia memerlukan orang-orang yang tinggal di dalamnya?” Tinggal di dalamnya, sebagaimana diketahui, mereka yang membela perbatasan negara dari berbagai tempat. Tinggal di dalamnya, yaitu harus ada tentara yang bertugas menjaga keamanan Negara Islam di daerah-daerah perbatasan ini, yaitu tempat-tempat yang diperkirakan datangnya bahaya dari musuh-musuh terhadap Negara Islam. “Bagaimana pendapat kalian tentang daerah-daerah perbatasan ini, ia memerlukan orang-orang yang tinggal di dalamnya,” yaitu berada di dalamnya, berada di daerah-daerah perbatasan ini dan menjaga keamanan Negara Islam. “Atau bagaimana pendapat kalian tentang kota-kota besar ini, ia memerlukan untuk diisi dengan pasukan dan diberi tunjangan.”
Setelah ia mengarahkan perhatian mereka kepada daerah-daerah perbatasan ini yang memerlukan tentara yang tinggal di dalamnya, dan tentara-tentara ini memerlukan gaji dan biaya untuk mereka, dan senjata untuk berperang, ia berkata kepada mereka: “Semua hal ini—para pejuang yang memerlukan gaji, yang memerlukan sarana untuk berperang atau senjata untuk memerangi musuh jika mereka ingin menyerang Negara Islam—semua hal ini memerlukan biaya, dari mana kita mendapatkan biaya ini?” Dan demikian pula ia berkata kepada mereka: “Kota-kota besar yang telah ditaklukkan kaum Muslimin ini juga memerlukan pasukan Islam untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya, dan pasukan-pasukan Islam ini juga memerlukan biaya, harus ada gaji untuk tentara, harus ada biaya untuk makanan dan minuman mereka, harus ada senjata. Semua hal ini memerlukan biaya yang besar, dari mana diberikan kepada mereka?” Yaitu: karena kita memerlukan—atau Negara Islam memerlukan—sumber daya untuk membiayai pasukan-pasukan ini yang melindungi kota-kota yang ditaklukkan kaum Muslimin atau melindungi perbatasan-perbatasan Negara Islam dari musuh-musuh, yang memerlukan biaya yang banyak. “Dari mana diberikan kepada mereka, yaitu: dari mana didapatkan uang yang dibelanjakan untuk tentara-tentara ini yang melaksanakan tugas membela Negara Islam? Dari mana diberikan kepada mereka jika tanah dan apa yang ada di atasnya dibagi?” Yaitu: ia berkata, “Jika kita membagi tanah ini di antara para pejuang sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu, jika kita membagi tanah ini kepada mereka, dari mana kita mendapatkan biaya-biaya ini?”
Tetapi jika kita biarkan tanah ini di tangan pemiliknya kemudian kita kenakan pajak atau kharaj, berarti akan ada sumber untuk baitul mal dari pajak atau kharaj ini yang dengannya kita dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara Islam, yang di garis depannya adalah pasukan-pasukan Islam yang memerlukan gaji dan memerlukan makanan dan minuman dan memerlukan senjata. Ia berkata kepada mereka: “Dari mana diberikan kepada mereka jika tanah dan apa yang ada di atasnya dibagi?” Kemudian Khalifah mengutip ayat-ayat dari Al-Quran Al-Karim bahwa tanah yang ditaklukkan tidak boleh dibagi di antara para penakluk, melainkan harus dianggap sebagai milik umum negara dan rakyatnya di masa kini dan masa depan, dengan berkata: “Dan fai’ ini telah menjadi milik semua ini, bagaimana kita membaginya untuk mereka dan membiarkan mereka yang datang setelahnya?”
Yaitu seolah-olah Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa akan ada atau sebagian kaum Muslimin yang datang setelah itu. Jika kita membagi tanah subur yang kaya ini kepada para pejuang ini, seolah-olah mereka mengambil bagian terbesar dari kekayaan Negara Islam, lalu apa yang tersisa bagi mereka yang datang setelah mereka: “Dan apa yang diberikan Allah sebagai fai’ (harta rampasan) kepada Rasul-Nya dari mereka, maka untuk itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Hasyr: 6). Kemudian Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7). Maka Sayyidina Umar (berpegang pada): “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Sayyidina Umar menjelaskan bahwa jika kita berikan tanah subur yang luas dan besar ini—jika kita berikan kepada para penakluk atau pejuang atau pasukan ini—mereka akan menjadi golongan yang menguasai seluruh kekayaan, sedangkan kaum Muslimin lainnya tidak menguasai apa-apa. Dan inilah yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta’ala dengan firman-Nya: “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Oleh karena itu ia berkata kepada mereka: “Saya berikan kepada kalian, lalu apa yang tersisa untuk kaum Muslimin yang datang setelah kalian?” Ketika mereka berkata kepadanya: “Yaitu, engkau berikan apa yang kami peroleh sebagai ghanimah kepada orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran, dan kepada anak-anak orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran, bagaimana itu?” Maka ia berkata kepada mereka: “Bagaimana saya berikan kepada kalian tanah ini, kalian memperolehnya dan menjadi orang-orang kaya, sedangkan kaum Muslimin lainnya menjadi miskin? Jika saya berikan tanah ini kepada kalian, apa yang tersisa untuk kaum Muslimin yang datang setelah kalian?”
Saya katakan: ia datang dengan ayat-ayat ini dan berhujjah dengannya. Dan di tengah-tengah ini Sayyidina Umar menceritakan hal ini dan memberikan dalil atas pendapatnya di hadapan komite atau di depan komite yang ia bentuk untuk musyawarah, yaitu—sebagaimana telah kita katakan—sepuluh orang: lima dari Aus dan lima dari Khazraj, dari pembesar sahabat yang ahli dalam urusan-urusan kaum Muslimin. Pada saat itulah komite atau majelis syura, jika boleh kita sebut demikian, menyetujui sudut pandang Khalifah Umar yang menentukan pengertian ghanimah dan fai’, setelah percampuran antara kedua maknanya menjadi sebab timbulnya masalah pembagian negeri-negeri yang ditaklukkan. Khalifah membatasi makna ghanimah pada harta bergerak yang diperoleh sebagai hasil perang, sedangkan makna fai’, Khalifah memperluas maknanya untuk mencakup apa yang diambil dengan kekerasan dan apa yang diambil melalui perdamaian, dan bahwa tanah yang ditaklukkan dan apa yang terkait dengannya dari pengenaan jizyah kepada penduduknya termasuk dalam pengertian fai’, dan menjadi hak umat untuk berijtihad yang diwakili oleh majelis syura.
Sebagaimana telah kami katakan, komite yang dibentuknya menyetujui hal tersebut, dan komite ini menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan. Pendapat yang dikemukakan oleh sayyidina Umar yaitu mempertahankan tanah dan tidak membagikannya kepada para pejuang yang memperoleh ghanimah serta membiarkannya di tangan pemiliknya yang telah ditaklukkan dan dikalahkan oleh kaum Muslim, hal ini tidak bertentangan dengan ayat ghanimah: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah” (Surah Al-Anfal: 41). Artinya: dimungkinkan untuk menggabungkan antara ayat ghanimah ini dengan ayat fai’, dan penggabungan keduanya adalah: bahwa ghanimah yang dibagi menjadi lima bagian, seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya dan empat perlima untuk para pejuang, itu hanya berlaku untuk harta bergerak. Adapun mengenai properti seperti tanah, maka ini tidak termasuk dalam ghanimah dan tanah ini tetap berada di tangan pemiliknya agar dapat dikenakan pajak atau kharaj, dan kharaj atau pajak ini menjadi sumber pendapatan keuangan bagi negara Islam yang ditempatkan di Baitul Mal dan dibelanjakan untuk kepentingan kaum Muslim.
Demikianlah pemahaman sayyidina Umar radhiyallahu Ta’ala ‘anhu, dan yang mendorong sayyidina Umar pada sikap ini serta berpegang teguh pada pendapat ini meskipun menghadapi penentangan besar yang dilihat oleh sayyidina Umar dari para pejuang dan banyak sahabat yang menentangnya dalam pendapat ini, namun ia tetap berpegang teguh padanya. Mengapa ia berpegang teguh? Ini adalah kebijakan keuangan yang dilihat oleh sayyidina Umar bin Al-Khaththab dan ia menemukan bahwa kebijakan keuangan ini mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim, baik sekarang maupun di masa depan. Oleh karena itu, umat berhak untuk berijtihad yang diwakili dalam majelis syura, seperti majelis syura yang dibentuk oleh sayyidina Umar bin Al-Khaththab dalam masalah yang terjadi antara dirinya dengan para pejuang atau orang-orang yang memperoleh ghanimah. Ia membentuk majelis syura, dan ini berarti bahwa syura adalah perkara yang harus diambil oleh kaum Muslim dalam semua urusan mereka, terutama urusan umum yang berkaitan dengan negara Islam.
Kami katakan: umat berhak untuk berijtihad di majelis syura dalam menetapkan undang-undang keuangan baru yang menyatakan bahwa tanah yang telah ditaklukkan adalah wakaf bagi kaum Muslim, setelah anggota syura yakin dengan sudut pandang Khalifah Umar bin Al-Khaththab, dan mereka berkata kepadanya: Pendapatmu benar wahai Umar, betapa baik apa yang engkau katakan dan apa yang engkau lihat.
Demikianlah majelis ini – majelis syura yang dibentuk oleh Umar bin Al-Khaththab – menyetujui pendapat Umar bin Al-Khaththab setelah ia menyebutkan kepada mereka dalil-dalil dan bukti-bukti yang menjadi sandarannya. Dan ketika mereka menyetujui apa yang dilihat oleh Umar, maka Khalifah Umar bin Al-Khaththab menulis surat kepada para panglima pasukan di wilayah-wilayah dengan keputusan ini, memberitahukan kepada mereka keputusan yang diambil berdasarkan majelis syura yang dibentuknya. Keputusan tersebut – sebagaimana telah kami katakan – adalah mempertahankan tanah sebagai wakaf bagi kaum Muslim, artinya: tanah tetap berada di tangan pemiliknya yang dikenakan kharaj atau pajak kharaj, dan tentu saja jizyah dikenakan pada penduduknya. Khalifah Umar bin Al-Khaththab menulis kepada para panglima pasukan di wilayah-wilayah dengan keputusan ini, di antaranya Sa’d bin Abi Waqqash yang pertama kali memicu pasukannya di Irak mengenai permasalahan tersebut. Ia berkata kepadanya untuk melihat apa yang dibawa orang berupa kuda perang atau harta – kuda perang yang dimaksud di sini adalah senjata – maka bagikanlah itu di antara kaum Muslim yang hadir, dan biarkanlah tanah dan sungai-sungai untuk para pekerja dan pemiliknya, agar hal itu dapat menjadi ‘atha (gaji) bagi kaum Muslim, yaitu agar hal itu menjadi sumber pendapatan atau sumber keuangan negara Islam atau dibayarkan darinya ‘atha kaum Muslim dan terwujud dengannya kemaslahatan kaum Muslim. Maka tanah yang ditaklukkan menjadi sumber keuangan tetap dan wakaf bagi umat dengan pergantian generasi-generasinya.
Dan jika kita melihat sistem ‘atha pada masa Khalifah Umar bin Al-Khaththab, kami katakan: Penerapan undang-undang keuangan baru khusus tanah yang ditaklukkan memerlukan penciptaan alat pelaksana yang mengawasi persyaratannya. Hal itu karena undang-undang ini menetapkan untuk memberi kompensasi kepada para prajurit dengan memberikan mereka ‘atha sebagai ganti tanah yang mereka harapkan untuk dibagi di antara mereka. Artinya sayyidina Umar bin Al-Khaththab, meskipun tidak membagi tanah kepada orang-orang yang memperoleh ghanimah dan para pejuang, namun ia memberi mereka kompensasi dengan sebagian harta lainnya.
Dan datanglah sensus khusus luas tanah-tanah yang ditaklukkan tersebut dan penduduk di atasnya yang penuh dengan angka-angka yang sangat besar dan fantastis, karena tanah itu sangat luas. Penguasa-penguasa Sasaniyah dan Bizantium – yaitu penguasa yang memerintah negeri-negeri tersebut sebelum kaum Muslim menguasai negeri-negeri tersebut – yang berdaulat atas tanah-tanah tersebut sebelum penaklukan Islam, mereka memungut kharaj pada tanah – yaitu pajak barang yang sangat berat dan zalim – dan memungut jizyah pada penduduk – yang juga merupakan pajak keuangan yang zalim. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Al-Khaththab memandang untuk mempertahankan kharaj dan jizyah, tetapi dengan cara yang sesuai dengan keadilan Islam dan memperhatikan kemaslahatan atau memperhatikan kemaslahatan rakyat baru negara Islam. Maka penentuan kharaj memperhatikan realitas tanah dan produksinya dan apa yang menjaga kemakmuran dan pertumbuhannya.
Adapun jizyah yang ditetapkan Islam tidak mengandung makna lama yang menunjukkan pada penindasan, kehinaan, dan eksploitasi, melainkan dibayarkan dalam naungan Islam sebagai imbalan perlindungan negara bagi pembayarnya, kebebasan mereka, dan tempat ibadah mereka, yaitu menyerupai pajak pertahanan dan cara untuk menciptakan keseimbangan antara pembayar jizyah dari rakyat negara yang kemudian dikenal dengan nama Ahlu Dzimmah, dan antara kaum Muslim dari rakyat negara yang membayar zakat atas harta mereka.
Kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa sayyidina Umar bin Al-Khaththab setelah mengambil keputusan bersama majelis syura yang dibentuknya dari sepuluh orang sahabat senior, dan mengambil keputusan bahwa tanah ini diwakafkan untuk kaum Muslim, dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dan mengambil keputusan ini, dan bahwa tanah tetap bersama pemiliknya yang dikenakan kharaj, dan penduduknya dikenakan jizyah, sayyidina Umar bin Al-Khaththab menemukan bahwa sistem jizyah dan sistem kharaj – sistem jizyah atas kepala yaitu: atas orang-orang pemilik tanah ini, dan sistem kharaj yang dikenakan pada tanah itu sendiri – menemukan bahwa sistem ini sudah ada di negeri-negeri ini, telah diterapkan oleh penguasa negeri-negeri ini sebelum kaum Muslim menguasai dan menaklukkan negeri-negeri ini. Sayyidina Umar bin Al-Khaththab mempertahankan sistem ini, yaitu bahwa tanah dikenakan kharaj, dan kharaj adalah pajak keuangan yang dikenakan pada tanah atau yang disebut saat ini sebagai sewa tanah pertanian.
Tetapi sayyidina Umar berbeda dengan para penguasa yang menguasai negeri-negeri ini dalam hal yang sangat penting, yaitu bahwa para penguasa yang memerintah negeri-negeri ini memungut pajak atas tanah yang zalim dan tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan tanah dari tanaman, dan mereka juga memungut jizyah dalam jumlah yang zalim yang tidak sesuai dengan kemampuan orang-orang yang dikenakan jizyah ini. Sayyidina Umar bin Al-Khaththab tidak mengambil hal itu, karena Islam adalah agama keadilan. Oleh karena itu ia memungut jizyah dari mereka, tetapi jizyah yang sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Jadi sayyidina Umar memperhatikan kemampuan keuangan para wajib pajak sebagaimana dikatakan pada zaman sekarang. Ia tidak mengambil dari orang-orang mengenai jizyah kecuali apa yang mereka mampu. Oleh karena itu jizyah dibagi menurut tingkat kekayaan, menengah, dan kemiskinan. Orang miskin tidak diambil darinya jizyah. Orang menengah diambil darinya jizyah menengah. Orang kaya diambil darinya jizyah yang lebih besar. Oleh karena itu ia memperhatikan kondisi orang-orang atau kondisi para wajib pajak sebagaimana kami katakan.
Demikian juga mengenai tanah pertanian, sayyidina Umar bin Al-Khaththab memungut pajak kharaj tetapi menjadikan pajak ini sesuai dengan kemampuan tanah dan apa yang dihasilkan tanah. Artinya hal itu memperhatikan kemampuan tanah dan apa yang dihasilkannya dari tanaman. Oleh karena itu pajak itu adil, dan demikian juga jizyah atas kepala juga adil, karena Islam memperhatikan hal itu. Dan Islam ketika memungut jizyah tidak bermaksud menghinakan orang sama sekali. Jizyah yang dipungut oleh orang-orang Sasaniyah dan Bizantium sebelum masuknya Islam ke tanah ini dimaksudkan untuk penindasan, dimaksudkan untuk penghinaan, penindasan, dan eksploitasi. Tetapi kaum Muslim ketika pergi ke tempat-tempat ini tidak bermaksud dengan jizyah untuk eksploitasi sama sekali. Jizyah yang dipungut kaum Muslim hanyalah tanda saja atas kepatuhan orang-orang ini kepada negara Islam. Dan juga jizyah disebabkan karena kaum Muslimlah yang akan membela orang-orang ini – penduduk negeri yang ditaklukkan kaum Muslim – seakan-akan ini dianggap sebagai pajak pertahanan bukan jizyah. Oleh karena itu siapa yang berperang bersama kaum Muslim dari penduduk negeri ini, maka gugur darinya jizyah.
Oleh karena itu sebagian ulama – seperti Syafiiyah – mengatakan bahwa jizyah dipungut dari mereka sebagai imbalan perlindungan dan pembelaan mereka. Oleh karena itu jika mereka sendiri melakukan perlindungan atau pembelaan ini atau bergabung dengan kaum Muslim dalam membela negara Islam, maka gugur dari mereka jizyah ini.
Jadi jizyah yang dipungut Islam berbeda dengan jizyah yang dipungut oleh non-Muslim dari para raja yang lalim. Jizyah itu adil, dan jizyah bukan untuk penindasan atau penghinaan – sebagaimana telah kami katakan – melainkan merupakan petunjuk dan tanda kepatuhan orang-orang ini pada hukum Islam dan pemerintahan Islam. Demikian juga mengenai kharaj ini yang dipungut pada tanah yang ditaklukkan kaum Muslim, pajak kharaj juga merupakan pajak yang sangat adil sesuai dengan tanah. Oleh karena itu nilai kharaj berbeda dari satu tanah ke tanah lain. Tanah yang kuat dan subur kharajnya lebih banyak, dan tanah yang lemah kharajnya lebih sedikit.
Sebagaimana telah kami katakan, jizyah yang ditetapkan Islam tidak mengandung makna lama yang menunjukkan pada penindasan, kehinaan, dan eksploitasi, melainkan dibayarkan dalam naungan Islam sebagai imbalan perlindungan negara bagi pembayarnya, kebebasan mereka, dan tempat ibadah mereka, yaitu menyerupai pajak pertahanan dan cara untuk menciptakan keseimbangan antara pembayar jizyah dari rakyat negara yang kemudian dikenal dengan nama Ahlu Dzimmah dan antara kaum Muslim dari rakyat negara yang membayar zakat atas harta mereka.
Jadi jizyah dari sisi lain adalah untuk persamaan antara rakyat negara Islam. Rakyat negara Islam terdiri dari Muslim dan non-Muslim, karena yang membayar jizyah adalah dari rakyat negara Islam. Kaum Muslim membayar jizyah, maka keadilan menuntut bahwa non-Muslim membayar sesuatu yang lain, yaitu yang diwakili dalam jizyah. Kaum Muslim membayar zakat, sedangkan Ahlu Dzimmah membayar jizyah, dan ini adalah bentuk persamaan antara rakyat negara Islam. Kaum Muslim mendapat manfaat dari fasilitas umum di negara Islam, dan non-Muslim juga mendapat manfaat dari fasilitas umum di negara Islam. Oleh karena itu keadilan menuntut bahwa setiap kelompok menanggung biaya fasilitas ini sesuai dengan mereka. Kaum Muslim membayar zakat, maka keadilan menuntut bahwa non-Muslim – yaitu Ahlu Dzimmah – membayar jizyah.
Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3 – Sistem Keuangan pada Masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘Anhuma
Lanjutan: Perkembangan Sistem Keuangan pada Masa Umar bin Al-Khaththab
Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, washshalatu wassalamu ‘ala al-mab’utsi rahmatan lil ‘alamin, sayyidina Muhammadin wa ‘ala alihi wa ashhabihi, wa man tabi’ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba’d:
Kita telah membicarakan dalam perkuliahan sebelumnya tentang sistem keuangan pada masa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu dan kita telah membicarakan tentang arah Umar mengenai pembagian ‘atha, karena ia membedakan antara orang-orang dalam hal itu. Kita juga telah melihat sikap tegas yang diambil oleh Umar bin Al-Khaththab mengenai tanah yang diperoleh kaum Muslim sebagai ghanimah dari Sawad Irak, di mana ia mewakafkannya untuk kaum Muslim, dan tidak membaginya kepada orang-orang yang memperoleh ghanimah, dan mengenakan kharaj padanya agar menjadi sumber keuangan dari sumber-sumber keuangan di negara Islam.
Dan kita lengkapi dalam perkuliahan ini ciri-ciri utama yang ditempuh oleh Umar bin Al-Khaththab dalam kebijakan keuangan negara Islam, maka kami katakan:
Penerapan undang-undang keuangan baru khusus tanah-tanah yang ditaklukkan memerlukan penciptaan alat pelaksana yang mengawasi persyaratan sistem baru ini. Hal itu karena undang-undang ini menetapkan untuk memberi kompensasi kepada para prajurit dengan memberikan mereka ‘atha sebagai ganti tanah yang mereka harapkan untuk dibagi di antara mereka. Dan datanglah sensus khusus luas tanah-tanah yang ditaklukkan tersebut dan penduduk di atasnya yang penuh dengan angka-angka yang sangat besar dan fantastis. Penguasa-penguasa Sasaniyah dan Bizantium – yang berdaulat atas tanah-tanah tersebut sebelum penaklukan Islam – memungut kharaj pada tanah – yaitu pajak barang yang sangat berat – dan memungut jizyah pada penduduk – yang merupakan pajak keuangan yang zalim. Khalifah Umar bin Al-Khaththab memandang untuk mempertahankan kharaj dan jizyah, tetapi dengan cara yang sesuai dengan keadilan Islam, dan memperhatikan kemaslahatan umum rakyat baru negara Islam. Maka penentuan kharaj memperhatikan realitas tanah, produksinya, dan apa yang menjaga kemakmuran dan pertumbuhannya.
Adapun jizyah yang ditetapkan Islam tidak mengandung makna lama yang menunjukkan pada penindasan, kehinaan, dan eksploitasi, melainkan dibayarkan dalam naungan Islam sebagai imbalan perlindungan negara bagi pembayarnya, kebebasan mereka, dan tempat ibadah mereka, yaitu bahwa ia menyerupai pajak pertahanan, dan cara untuk menciptakan keseimbangan antara pembayar jizyah dari rakyat negara – yang kemudian dikenal dengan nama Ahlu Dzimmah – dan antara kaum Muslim dari rakyat negara – yang membayar zakat atas harta mereka. Yaitu bahwa jelaslah bagi kita dari ini bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu Ta’ala ‘anhu berjalan pada sistem yang sama yang dijalankan oleh mereka yang memerintah negeri-negeri ini sebelum Islam memasukinya. Mereka berjalan pada sistem kharaj dan sistem jizyah. Dan sayyidina Umar bin Al-Khaththab menemukan bahwa ini adalah hal yang baik, maka ia mempertahankan kharaj dan mempertahankan jizyah, tetapi ia memperhatikan dalam hal itu keadilan Islam. Jika para penguasa ini – yang memerintah negeri-negeri ini sebelum penaklukan Islam – berlebihan dalam jizyah dan berlebihan dalam kharaj, dan menzalimi orang-orang, maka hal itu tidak diridhai oleh Umar bin Al-Khaththab, karena Umar bin Al-Khaththab menerapkan ajaran-ajaran Islam yang menuntut kita untuk mewujudkan keadilan di antara manusia. Oleh karena itu ia mempertahankan kharaj tetapi menjadikannya adil, berbeda menurut perbedaan tanah dalam hal kesuburan, dan demikian juga ia mempertahankan jizyah, tetapi ia adil dalam memungut jizyah ini, karena jumlah yang ditentukan pada orang-orang berbeda menurut perbedaan kekayaan dan kemiskinan mereka.
Dan diperlukan pengaturan harta yang terkumpul dari kharaj dan jizyah, serta pembelanjaannya dalam tujuan-tujuan yang ditetapkan untuknya, suatu administrasi yang baru, yaitu bahwa sumber-sumber baru ini yang akan mendatangkan harta bagi negara Islam – yang diwakili dalam jizyah dan kharaj – memerlukan pengaturan yang melakukan hal ini, melakukan pemungutan kharaj dan pemungutan jizyah, kemudian setelah itu melakukan pembelanjaannya dalam tujuan-tujuan yang ditetapkan untuknya dalam fiqih Islam.
Dan Khalifah Umar meminta nasihat para sahabat dalam hal ini juga, karena ia radhiyallahu Ta’ala ‘anhu tidak mengambil keputusan sendirian, bahkan jika ada suatu perkara yang menyangkut kaum Muslim ia meminta nasihat para sahabat dalam perkara ini. Ia meminta nasihat mereka dalam hal ini dan berkata kepada mereka: Kharaj ini dan jizyah itu yang datang kepada kita setiap tahun, apa yang kita lakukan dengannya? Apakah kita bagikan sekaligus ataukah secara bertahap? Atau bagaimana?
Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya: Bagikanlah setiap tahun semua harta yang terkumpul kepadamu, dan jangan menyimpan sedikitpun darinya.
Dan Utsman bin Affan berkata kepadanya: Aku melihat harta yang banyak mencukupi kebutuhan orang-orang, dan jika mereka tidak didata hingga diketahui siapa yang telah menerima dan siapa yang belum menerima, aku khawatir urusan ini akan menjadi kacau.
Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya: Setiap harta yang datang kepadamu, bagikanlah segera. Namun Sayyidina Utsman memiliki sudut pandang lain dan berkata kepadanya: Harus ada pengaturan urusan dan penguasaan urusan; agar kita dapat memastikan bahwa harta tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.
Dan Al-Walid bin Hisyam bin Al-Mughirah berkata: Aku telah datang ke Syam, dan aku melihat raja-rajanya telah membuat daftar catatan, dan mengerahkan tentara, maka buatlah daftar catatan dan kerahkanlah tentara.
Al-Walid bin Hisyam bin Al-Mughirah menyampaikan pendapatnya dalam urusan ini dan berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin, yang terbaik dalam kondisi ini adalah adanya diwan. Dan makna diwan adalah dicatatnya nama-nama orang dan pemberian kepada orang-orang, dan ini adalah urusan yang sudah dikenal di kalangan raja-raja dan negara-negara sebelum kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah ini.
Oleh karena itu, pendapat terakhir ini mendapat persetujuan Khalifah Umar bin Khattab, dan dia memutuskan untuk mendirikan diwan pertama dalam Islam, dengan memanfaatkan sistem Romawi dan Sasania dalam hal tersebut.
Namun kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Khalifah untuk diwan ini adalah murni Islami, dan sesuai dengan tingkatan yang menjaga hak setiap orang yang berhak, dan tidak mengurangi sedikitpun kadar atau usahanya, dan Khalifah menjelaskan dasar-dasar yang telah ia tetapkan dengan mengatakan: “Tidak ada seorangpun kecuali dia memiliki hak dalam harta ini, diberikan kepadanya atau dicegah darinya, dan aku di antara kalian tidak lain hanya seperti salah seorang dari kalian, tetapi kita berada pada kedudukan kita dari Kitabullah, dan pembagian kita dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka seseorang dengan keberadaan lamanya dalam Islam, dan seseorang dengan kedudukannya dalam Islam, dan seseorang dengan kontribusinya dalam Islam, dan seseorang dengan kebutuhannya dalam Islam”.
Itulah arahan-arahan Umar bin Khattab ketika ia hendak meletakkan diwan baru ini, dan Khalifah Umar menyerahkan kepada Aqil bin Abi Thalib, Ibnu Naufal, dan Jubair bin Muth’im, menyerahkan kepada mereka penerapan kaidah-kaidah baru yang telah ia tetapkan; karena kelompok orang ini dari kalangan sahabat besar yang paling luas ilmunya di kalangan Arab tentang nasab Quraisy, dan dia berkata kepada mereka: “Tulislah orang-orang sesuai kedudukan mereka” yaitu: sesuai kadar keutamaan mereka dalam Islam dan kadar kedekatan mereka dengan Rasul yang Mulia shallallahu alaihi wasallam dan itu agar perbedaan dalam pemberian berdiri atas dua dasar ini, yaitu dasar pertama kedudukan orang dalam Islam, kemudian kedekatan mereka dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dengan demikian diletakkanlah sistem keuangan Islam pertama yang terkenal dengan nama Al-Atha (pemberian), yang bersandar pada keadilan dari segi penetapan dan penerapan; karena sekelompok orang mencoba membujuk Khalifah agar memulai daftar Al-Atha dengan dirinya sendiri, tetapi ia menolak dan berkata: “Aku akan mulai dengan Bani Hasyim, kerabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, aku akan mulai dengan Bani Hasyim sesuai yang paling dekat kemudian yang lebih dekat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kaum itu jika mereka setara dalam kekerabatan, maka didahulukan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, dan ia juga memberikan kelebihan dalam Al-Atha kepada ahli masyhad -yaitu mereka yang menyaksikan peperangan dan penaklukan Islam.
Dan tingkat ketelitian sistem Al-Atha mencapai bahwa ia menetapkan untuk setiap bayi seratus dirham, maka jika ia tumbuh besar, pembagiannya mencapai dua ratus dirham, dan yang menarik dalam kaidah ini adalah bahwa bayi pada awalnya tidak ditetapkan pembagian sampai ia disapih -yaitu sampai selesai dari menyusu- lalu Umar memerintahkan penyerunya untuk tidak tergesa-gesa menyapih anak-anak kalian, karena kami menetapkan untuk setiap bayi dalam Islam, artinya ditetapkan untuknya pemberian dari baitul mal, dan ketegasan sistem Al-Atha dan keluhurannya dalam syariat Islam terwujud bahwa Umar bin Khattab menyamakan dalam pemberian antara Arab dan Mawali, dan menetapkan untuk Al-Hurmuzan orang Persia dua ribu dirham, dan ia menulis kepada para panglima pasukan dengan mengatakan: “Dan barangsiapa yang kalian merdekakan dari Al-Humra -yaitu: Mawali- lalu mereka masuk Islam maka masukkan mereka dengan tuan-tuan mereka, bagi mereka apa yang untuk mereka dan atas mereka apa yang atas mereka, dan jika mereka ingin menjadi suku tersendiri maka jadikan mereka setara dalam pemberian”.
Dan Khalifah juga menulis kepada salah seorang walinya yang mengabaikan urusan Mawali dalam pemberian dengan mengatakan: kepadanya maka cukup bagi seseorang dari kejahatan adalah meremehkan saudaranya yang muslim, wassalam.
Seakan-akan Sayyidina Umar bin Khattab mencapai tingkat ketelitian pandangannya dalam urusan ini sehingga ia menjadikan Mawali yaitu mereka yang dulunya budak kemudian dimerdekakan, menjadikan mereka setara dengan kaum muslimin bahkan dengan orang-orang yang memerdekakan mereka dalam urusan ini, dan setiap individu memperoleh di samping pemberian uang juga rizki barang, dan Khalifah Umar bin Khattab menetapkan untuk setiap individu setelah pengalaman praktis rizki bulanan, sebesar dua jarib makanan, dan jarib adalah takaran dari takaran-takaran yang digunakan untuk menakar biji-bijian, dan itu untuk laki-laki, perempuan, budak, dan juga anak-anak, dan menjadi hal yang menarik dalam urusan ini bahwa seseorang jika ingin mendoakan keburukan kepada temannya berkata kepadanya: “Semoga Allah memutuskan darimu dua jaribmu” yaitu: jumlah makanan yang diberikan kepadanya dari baitul mal.
Dan Khalifah Umar bersungguh-sungguh untuk membawa sendiri pemberian beberapa suku dan membagikannya kepada mereka, maka tidak luput darinya perempuan perawan atau janda, ia memberikan kepada mereka di tangan mereka, dan Al-Atha menjadi teladan praktis terbaik untuk kekuatan sistem keuangan dalam Islam, dan keadilan kaidah-kaidahnya serta ketepatannya pada waktu yang sama.
Dan perkembangan dalam sumber-sumber dan pemberian pada masa Umar bin Khattab mengharuskan perhatian terhadap pengaturan keuangan wilayah-wilayah, karena ia merupakan sumber utama yang darinya perkembangan ini mendapatkan komponen dan ciri-cirinya, dan terwujudlah dalam pengaturan ini sejauh mana sistem keuangan Islam ditandai dengan fleksibilitas, dan kemampuan untuk memajukan keadaan wilayah-wilayah; hingga menjadi bangunan kokoh untuk apa yang disebut oleh para fuqaha “Darul Islam” dan setiap wilayah memiliki administrasi keuangannya dengan para pejabatnya yang ahli dalam fasilitas-fasilitas lamanya, yang mampu menghidupkan air kehidupan di dalamnya, sesuai dengan sistem Islam dan keadilannya.
Dan kebenaran itu menjadi jelas di tiga wilayah besar Negara Islam saat itu, yaitu Irak, Syam, dan Mesir, maka berkenaan dengan wilayah Irak, Irak terbagi dari segi pengaturan keuangan menjadi dua bagian:
Salah satunya: adalah bagian selatan yang terkenal dengan nama As-Sawad, dan mencakup tanah-tanah subur. Dan yang lainnya yaitu bagian atas yang terkenal dengan nama tanah Jazirah Furat, dan mencakup tanah-tanah yang membentang antara Tigris dan Efrat.
Dan Khalifah Umar bin Khattab mengirim dua orang ahli untuk mengukur tanah As-Sawad -yaitu: sawad Irak- dan memperkirakan apa yang harus dibayarkan sebagai kharaj atas tanah pertanian dan jizyah atas ahli dzimmah di dalamnya, dan pekerjaan ini dilakukan oleh dua orang ahli dari para ahli kaum muslimin yaitu Utsman bin Hunaif, dan Hudzaifah bin Yaman, yang meminta bantuan penduduk negeri untuk mengetahui sistem-sistem yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sasania atas wilayah-wilayah tersebut, dan Sasania -yaitu penguasa sebelumnya atas negeri-negeri tersebut sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin- membebankan kharaj atas apa yang melindungi manusia dan hewan, yaitu gandum -yaitu: gandum, jelai, beras, anggur, dan zaitun- dan juga atas setiap kebun kurma taman -yaitu: kebun-kebun- dan besaran kharaj ini diperkirakan berdasarkan luas tanah.
Dan para Dahaqin -yaitu kepala-kepala desa- mengambil alih pengumpulan kharaj ini, sehingga mereka menjadikan beban jatuh pada pemilik kecil tanpa pemilik besar, dan Sasania juga membebankan jizyah yang mereka jadikan empat tingkatan sehingga dibebaskan darinya keluarga bangsawan, orang-orang besar, para pejuang, para penulis, dan siapa yang berada dalam pelayanan raja, dan bebannya jatuh pada rakyat biasa pemilik penghasilan sederhana, dan ini adalah kezaliman yang tidak diridhai Islam, karena sistem Islam ini menjamin keadilan dalam pengumpulan kharaj, dan penghapusan pengecualian-pengecualian yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sasania atas pemilik-pemilik kecil, dan terwujudlah kesetaraan dalam naungan sistem keuangan Islam, dan kesetaraan diperkuat dalam naungan sistem keuangan Islam dalam penetapan jizyah hanya atas laki-laki dewasa saja, tanpa perempuan, anak-anak, dan orang tua, yaitu sebesar 48 dirham dan 24 dirham dan 12 dirham dalam setahun sesuai penghasilan individu dan kekayaannya, dan tanpa pengecualian. Dan besaran ini tidak merugikan individu biasa sebagaimana yang dikatakan Khalifah Umar, satu dirham dalam sebulan tidak menyulitkan seseorang, tidak berpengaruh pada seseorang, dan dasar perbedaan dalam pembayaran jizyah dalam naungan sistem keuangan Islam adalah kondisi sosial, dan apa yang menyertainya dari penghasilan, maka atas para Dahaqin -yaitu: mereka yang memakai cincin emas- adalah pada laki-laki empat puluh delapan dirham; karena mereka termasuk golongan orang kaya dan orang kaya raya, dan atas golongan menengah mereka dari para pedagang atas setiap laki-laki dua puluh empat dirham dalam setahun, dan atas para Akara -yaitu para petani dan sisanya dari mereka- dua belas dirham, dan ini artinya bahwa jizyah berbeda dalam besarannya, maka orang-orang sangat kaya atas mereka 48 dirham dalam setahun, dan golongan menengah 24 dirham, dan yang kurang kaya dan menengah atas mereka 12 dirham, maka ini berjalan sesuai dengan kondisi individu atau sesuai penghasilan individu dan kekayaannya.
Dan selesailah pengaturan keuangan untuk negeri Jazirah Furat atas dasar-dasar yang sama yang ditetapkan di tanah As-Sawad, dari segi memperhatikan keadilan Islam, dan juga kondisi keuangan wilayah-wilayah tersebut.
Dan di wilayah-wilayah Syam, kaum muslimin mengikuti dalam penetapan jizyah dan kharaj dasar-dasar yang sama yang mereka ikuti di negeri Jazirah Furat; karena kesamaan kondisi di masing-masingnya, dari segi bergantiannya kekuasaan Persia dan Bizantium atas keduanya.
Dan berkenaan dengan Mesir atau wilayah Mesir, pemungutan jizyah di Mesir berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sesuai kemampuan setiap individu; karena pemimpin “Ikhna” datang kepada Amr bin Ash dan meminta darinya penetapan batas tetap untuk jizyah -yaitu penetapan batas tertentu untuk jizyah dan jumlah tertentu untuk jizyah- agar setiap individu berkewajiban dengannya tanpa melihat kondisi keuangannya, tetapi Amr bin Ash menolak itu dengan keras, menjelaskan bahwa penetapan ini adalah urusan yang tidak praktis, dan bahwa kondisi-kondisi mungkin berubah, dan bahwa wali pemilik hak dalam mengubah apa yang atas individu dari jizyah sesuai tuntutan kondisi-kondisi tersebut.
Dan anak-anak Mesir memiliki tingkat kebebasan dan partisipasi yang besar dalam administrasi keuangan negeri mereka, dan dengan itu mewujudkan bagi mereka keadilan, dan terlepas dari keburukan eksploitasi yang sebelumnya mereka alami banyak di masa Romawi.
Dan pengaturan keuangan di Mesir menjadi sesuai petunjuk memperhatikan kepentingan negara dan penduduknya, dan bahwa tidak dikirim ke Khalifah di Madinah kharaj yang diminta kecuali setelah pemotongan apa yang dibutuhkan negara dari penggalian saluran-salurannya, dan pendirian jembatan-jembatannya, dan pembangunan bendungan-bendungannya… dan lain-lain dari urusan-urusan yang dibutuhkan negara, kemudian bahwa kharaj tidak dikirimkannya oleh Amr bin Ash juga kecuali setelah orang-orang selesai dari pertanian dan pemerasan anggur mereka.
Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini tidak lain adalah penetapan baru dan pengaturan baru untuk kebijakan keuangan Islam berkenaan dengan negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan jika kita melihat kitab-kitab yang membicarakan tentang administrasi dalam naungan masa Islam awal, kita menemukan bahwa ada kitab bernama Al-Idarah Al-Islamiyah fi Izz Al-Arab karangan Muhammad Kurdi Ali, disebutkan dalam kitab ini di halaman 43 perkataan Umar bin Khattab: “Dan barangsiapa ingin bertanya tentang fiqih maka datanglah kepada Muadz bin Jabal, dan barangsiapa ingin bertanya tentang harta maka datanglah kepadaku; karena Allah menjadikanku penjaga dan pembaginya” dan Umar mencatat orang-orang atas suku-suku mereka yaitu: mendata mereka, maka ia menetapkan kewajiban-kewajiban dan memberikan pemberian-pemberian atas keutamaan, yaitu keutamaan dalam Islam, dimulai dengan yang paling dekat kemudian yang lebih dekat dari Rasul, dan menetapkan untuk ahli Badar dan siapa setelah mereka sampai Hudaibiyah dan baiah ridwan, kemudian siapa setelah mereka, dan untuk ahli Qadisiyah dan Yarmuk dan memberikan kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam dan yang lain, dan memberikan rizki anak-anak dan para imam dan muazin dan guru dan hakim, dan bersumpah atas tiga sumpah, maka ia berkata: “Demi Allah tidak ada seorangpun yang lebih berhak atas harta ini dari yang lain, dan aku tidak lebih berhak atasnya dari yang lain, Demi Allah tidak ada seorangpun dari kaum muslimin kecuali baginya dalam harta ini bagian kecuali budak yang dimiliki, tetapi kita berada pada kedudukan kita dari Kitabullah Ta’ala dan pembagian kita dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka seseorang dengan pengorbanannya dalam Islam, dan seseorang dengan kedudukannya dalam Islam, dan seseorang dengan kontribusinya dalam Islam, dan seseorang dengan kebutuhannya”.
Kemudian Umar berkata: “Demi Allah, jika aku masih hidup untuk mereka, niscaya akan sampai kepadaku penggembala di Gunung Sanaa bagiannya dari harta ini sementara dia menggembalakan di tempatnya.” Seakan-akan ini adalah bukti dari keteguhan Umar bin Khattab, semoga Allah Tabaraka Wataala meridhainya, bahwa harta-harta yang datang ke baitul mal melalui jizyah atau kharaj, pasti setiap Muslim memiliki bagian dalam harta-harta ini meskipun dia adalah orang biasa, seorang penggembala yang menggembalakan di Sanaa, di Yaman. Dia bersumpah bahwa pasti akan sampai kepadanya bagiannya dari pemberian ini, karena seperti yang telah kami katakan, dia berkata: “Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas harta ini daripada yang lain,” artinya: setiap orang memiliki bagian dalam harta ini.
Umar mengumpulkan kaum muslimin pada awal masa kepemimpinannya dan berkata: Apa yang halal bagi penguasa dari harta ini? Umar bertanya kepada mereka ketika menjabat sebagai khalifah, dan berkata: Apa yang halal bagi penguasa dari harta ini? Yaitu harta yang datang ke baitul mal dari jizyah dan kharaj… dan selainnya. Mereka semua menjawab: Adapun untuk keperluannya sendiri, maka makanannya dan makanan keluarganya tanpa berlebihan atau berkurang, pakaian mereka dan pakaiannya untuk musim dingin dan musim panas, dua kendaraan untuk jihadnya, keperluannya, shalatnya, hajinya, dan umrahnya, pembagian secara merata, dan memberikan kepada penduduk negeri sesuai dengan jasa mereka, serta memperhatikan mereka dalam kesulitan dan bencana hingga teratasi, dan memulai dengan ahli fai.
Umar apabila membutuhkan, dia mendatangi penanggung jawab baitul mal dan meminjam darinya, yaitu: dia datang kepada penanggung jawab baitul mal dan meminjam darinya, artinya: meminta pinjaman darinya. Kadang-kadang dia terlambat membayar, maka penanggung jawab baitul mal mendatanginya dan menagih darinya, lalu dia mendesaknya, kemudian Umar mencari cara untuknya. Artinya: Umar apabila membutuhkan uang untuk dibelanjakan bagi kepentingan kaum muslimin, dia datang kepada penanggung jawab baitul mal, yang kita sebut sebagai menteri keuangan pada masa sekarang, dan meminta pinjaman darinya seolah-olah dia meminta pinjaman untuk dirinya sendiri, dan berkata kepadanya: Wahai penanggung jawab baitul mal, ketika jatuh tempo pembayaran, datanglah kepadaku untuk mengambil bagianmu, karena ini adalah pinjaman pribadi untukku. Ini adalah kehati-hatiannya, yaitu dari Sayyidina Umar bin Khattab, agar harta tersebut pergi ke tempat yang telah ditentukan untuknya. Kadang-kadang pemberiannya keluar, lalu dia membayarnya dan meminta salah seorang sahabatnya untuk meminjamkan uang kepadanya. Sahabatnya berkata kepadanya: Wahai Umar, apa yang menghalangimu untuk meminjam dari baitul mal? Umar menjawabnya: Sesungguhnya jika dia meninggal dan memiliki utang, mungkin mereka lalai menagih apa yang dipinjamnya. Adapun sahabatnya, karena kebiasaannya terhadap hartanya, dia akan menuntut ahli waris untuk membayar hartanya, maka terpenuhi dan terbebas kewajiban Umar.
Demikianlah kehati-hatian Umar bin Khattab terhadap harta-harta yang ada di baitul mal. Jika dia menginginkan uang untuk membelanjakan kepentingan kaum muslimin, dia pergi kepada salah seorang sahabatnya untuk meminjam darinya. Ketika ditanya mengapa tidak meminjam dari baitul mal, dia berkata: Aku takut jika aku mati. Penanggung jawab baitul mal atau pemilik harta mungkin malas dan tidak menagih uang ini karena itu bukan hartanya sendiri, melainkan harta kaum muslimin, sehingga dia mungkin malas. Tetapi ketika aku mengambilnya dari sahabatku, jika aku mati, dia akan berhati-hati terhadap hartanya dan akan pergi kepada ahli waris, maka mereka akan memberinya uang ini.
Inilah kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab mengenai harta. Di antara hal-hal yang menjadi perhatian Umar adalah menciptakan kondisi-kondisi baru yang dibutuhkan oleh keadaan perluasan penaklukan. Dia adalah orang pertama yang membawa durrah (tongkat sederhana), dan dia adalah orang pertama yang membukukan daftar-daftar mencontoh daftar-daftar Persia dan Romawi, yang dibukukannya oleh Aqil bin Abi Thalib dan Ibnu Naufal serta Jubair bin Mutim, seperti yang telah kami katakan. Mereka adalah orang-orang cerdas dari Quraisy yang memiliki pengetahuan tentang nasab-nasab, masa-masa manusia. Diwan yang kami maksud adalah daftar atau kumpulan lembaran-lembaran. Kitab ditulis di dalamnya tentang ahli tentara dan ahli pemberian. Mereka mendefinisikan diwan sebagai tempat untuk menyimpan apa yang berkaitan dengan hak-hak pemerintahan dari pekerjaan-pekerjaan dan harta-harta, serta siapa yang menanganinya dari tentara dan pekerja. Kata diwan kemudian diterapkan pada semua catatan pemerintah dan pada tempat di mana para penanggung jawab catatan-catatan ini duduk.
Demikianlah Umar menetapkan diwan pertama dalam Islam untuk kharaj dan harta di Damaskus, Bashrah, dan Kufah, sesuai dengan yang ada sebelumnya. Dikatakan: bahwa diwan pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah diwan al-insya. Diwan-diwan Syam ditulis dalam bahasa Romawi, diwan-diwan Irak dalam bahasa Persia, dan diwan-diwan Mesir dalam bahasa Qibti yang ditangani oleh orang-orang Nasrani dan Majusi tanpa orang-orang Muslim. Alasan pembukuan diwan-diwan adalah bahwa petugas Umar di Bahrain suatu hari datang kepadanya dengan lima ratus ribu dirham, maka dia menganggapnya banyak dan berkata: Ini banyak, dia menetapkan penjaga untuk menjaganya di masjid. Sebagian orang yang mengenal Persia dan Syam menyarankan kepadanya untuk membukukan diwan-diwan, mereka menulis di dalamnya nama-nama dan bagian setiap orang, dan menjadikan gaji-gaji bulanan, yaitu: setiap bulan. Umar membuat tabut, yaitu peti, untuk mengumpulkan cek-cek dan perjanjian-perjanjiannya. Dia merekrut pasukan, artinya: membentuk legiun-legiun, sehingga ada tentara di Palestina, di Jazirah dan Mosul, dan lain-lain.
Ketika dia mengutus Abdullah bin Masud ke Irak sebagai menteri dan pengajar bersama Ammar bin Yasir yang dia jadikan pemimpin, dia menulis kepada penduduk Irak: Aku telah menjadikan Abdullah bin Masud sebagai penanggung jawab baitul mal kalian, dan aku mengutamakan kalian dengannya atas diriku sendiri. Dia mengutus ke beberapa wilayah seorang petugas untuk shalat dan perang, dan menamakannya amir (pemimpin), dan seorang petugas untuk peradilan dan baitul mal, dan menamakannya pengajar dan menteri, atau dia menggabungkan untuk petugas antara shalat dan kharaj seperti petugas Mesir. Pembagian tugas-tugas di Syam berbeda dengan Yaman. Petugas Bahrain tidak sama dengan petugas Yamamah. Dia mengutus orang-orang untuk mengukur tanah, orang-orang untuk menaksir kharaj, dan orang-orang lain untuk menghitung penduduk. Dia berkata kepada dua petugasnya: “Lakukanlah pengukuran Irak dan tetapkan kharaj atas sawahnya.” Dia berkata kepada mereka: “Aku khawatir kalian berdua telah membebani tanah dengan apa yang tidak dapat ditanggungnya. Jika Allah menyelamatkan aku, niscaya akan aku biarkan janda-janda Irak tidak memerlukan laki-laki setelahku selamanya.” Dan dia berkata: “Ya Allah, aku persaksikan Engkau atas para pemimpin Anshar, bahwa aku hanya mengutus mereka untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka, Sunnah Nabi mereka Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat adil kepada mereka, membagikan harta rampasan di antara mereka, dan melaporkan kepadaku apa yang mereka ragukan dari urusan mereka.”
Dia memberikan gaji kepada petugas sesuai dengan kebutuhannya dan negerinya. Abu Bakar menyamakan manusia dalam pemberian dan tidak mengutamakan ahli keunggulan dalam Islam, dan berkata: Sesungguhnya mereka bekerja untuk Allah, maka pahala mereka pada Allah. Sesungguhnya harta ini hanya harta yang datang dan pergi yang dimakan oleh orang baik dan orang jahat, dan bukan harga untuk amal-amal mereka. Umar berkata: Aku tidak akan menjadikan orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang berperang bersamanya. Semoga Allah Tabaraka Wataala meridhai engkau wahai Umar.
Sistem Keuangan pada Masa Utsman bin Affan
Setelah Sayyidina Umar, semoga Allah Tabaraka Wataala meridhainya, Utsman Radhiyallahu Anhu menjabat sebagai khalifah. Ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, dia tidak mengubah kebijakan keuangan Umar, meskipun dia memperbolehkan kaum muslimin memiliki kekayaan, membangun istana-istana, dan memiliki lahan-lahan yang luas. Ketegasan Umar yang menakutkan dan membuat mereka takut, yang menghalangi banyak dari apa yang mereka inginkan, telah hilang dari kaum muslimin. Masanya adalah masa kemakmuran bagi kaum muslimin. Kemakmuran ini menyebabkan kenaikan harga-harga, yaitu: masa Sayyidina Utsman Radhiyallahu Tabaraka Wataala Anhu.
Pada masa Utsman, harta-harta melimpah dan pendapatan-pendapatan bertambah. Dia, Radhiyallahu Tabaraka Wataala Anhu, berpendapat bahwa kharaj dan jizyah mencukupinya sehingga tidak perlu menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan sedekah-sedekah. Maka dia menyerahkan kepada para pemilik harta untuk mengeluarkan zakat mereka sendiri dan menyerahkannya kepadanya tanpa menjadikan untuk itu pemungut-pemungut khusus, yaitu: petugas-petugas khusus, berbeda dengan para khalifah Rasyidin sebelumnya. Karena dia berpendapat bahwa uang tunai dan barang dagangan, yang dikenal sebagai harta bathin, telah berlipat ganda jumlahnya, dan bahwa dalam melacak keberadaannya di tangan pemiliknya terdapat kesulitan bagi mereka. Maka dia membiarkan mereka memiliki hak untuk mengeluarkannya sendiri dan memberikannya kepada orang-orang fakir secara langsung. Dia cukup dengan mengumpulkan harta-harta lain yang dikenal sebagai harta zhahir, yaitu hewan ternak (yang dimaksud hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing), tanaman, dan buah-buahan, karena tidak ada kesulitan bagi mereka dalam melacaknya di tangan mereka.
Sistem Keuangan pada Masa Ali bin Abi Thalib
Jika kita membahas sistem keuangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kami katakan: Ali bin Abi Thalib lebih dekat kepada Umar dalam kebijakan keuangannya dari segi ketegasan dan penghematan terhadap dirinya sendiri dan orang-orang terdekat kepadanya. Dia penyayang terhadap rakyat, penuh kasih sayang kepada mereka, menjaga kepentingan mereka, dan memperhatikan urusan-urusan mereka. Diriwayatkan bahwa saudaranya Aqil meminta kepadanya sesuatu dari baitul mal yang tidak dianggap Ali sebagai haknya, maka dia mencegahnya dari itu dan berkata kepadanya: Tidak ada untukmu dalam harta ini selain apa yang telah kuberikan kepadamu, tetapi bersabarlah hingga datang hartaku, maka akan kuberikan kepadamu darinya. Perkataan ini membuat Aqil marah, lalu dia meninggalkannya dan pergi kepada Muawiyah di Syam.
Dia Radhiyallahu Anhu juga menulis kepada salah seorang gubernurnya, berkata kepadanya: Perhatikanlah urusan kharaj dengan apa yang memperbaiki penduduknya, karena dalam memperbaiki dan kesejahteraan mereka terdapat perbaikan bagi selain mereka. Tidak ada perbaikan bagi selain mereka kecuali dengan mereka, karena semua manusia bergantung pada kharaj dan penduduknya. Seakan-akan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kefarasatannya berkata kepada salah seorang gubernurnya dan menasihatkannya tentang urusan kharaj, dan berkata kepadanya: Jika engkau ingin keadaan semua orang baik, maka hendaklah engkau memperbaiki kharaj (memperbaiki tanah kharaj) dan memperhatikan para pemilik tanah ini, pemilik tanah ini yang melakukan pertanian di atasnya. Karena jika engkau memperbaiki dan ada perhatian terhadap tanah ini yang menghasilkan tanaman, ini berarti kharaj akan meningkat. Kharaj tidak akan meningkat dan tanah ini tidak akan baik kecuali jika keadaan orang-orang yang melakukan pertanian di atasnya baik. Demikianlah perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada para gubernurnya.
Dia juga berkata kepadanya: Hendaklah perhatianmu pada kemakmuran tanah lebih besar daripada perhatianmu pada mendapatkan kharaj, artinya: perhatikanlah terlebih dahulu kemakmuran tanah dan perbaikan tanah, sebelum engkau melihat kharaj yang datang darinya. Ya, karena jika tanah tidak layak untuk pertanian, maka tidak akan menghasilkan kharaj. Hendaklah perhatianmu pada kemakmuran tanah lebih besar daripada perhatianmu pada mendapatkan kharaj, karena itu tidak dapat dicapai kecuali dengan kemakmuran, artinya: kharaj yang ingin engkau peroleh ini tidak akan engkau dapatkan kecuali dengan kemakmuran tanah dan dengan memperhatikan tanah ini, karena itu tidak dapat dicapai kecuali dengan kemakmuran. Barangsiapa menuntut kharaj tanpa kemakmuran, maka dia telah merusak negeri. Artinya: gubernur yang hanya memusatkan perhatiannya pada kharaj dan hanya ingin mengambil kharaj tanpa melihat tanah yang menghasilkan kharaj ini, maka kebijakannya akan menyebabkan kehancuran negeri. Mengapa? Karena kharaj tidak akan datang, seperti yang telah kami katakan, melimpah kecuali jika kita melakukan kemakmuran dan perbaikan tanah yang menghasilkan kharaj ini. Karena itu tidak dapat dicapai kecuali dengan kemakmuran. Barangsiapa menuntut kharaj tanpa kemakmuran, maka dia telah merusak negeri, membinasakan hamba-hamba, dan urusannya tidak akan stabil kecuali sebentar. Sesungguhnya kehancuran tanah datang dari kemiskinan penduduknya, artinya: tanah yang menghasilkan kharaj ini kapan menjadi hancur? Menjadi hancur jika kita mengabaikan pemiliknya, jika kita mengabaikan yang mengurusnya. Pada saat itu mereka tidak akan memperbaiki tanah ini dan tidak akan mengolah tanah ini sebagaimana mestinya, dan akibatnya menyebabkan kehancurannya. Dengan demikian tidak ada kharaj. Urusannya tidak akan stabil kecuali sebentar, dan sesungguhnya kehancuran tanah datang dari kemiskinan penduduknya, artinya: dari kebutuhan mereka terhadap harta. Sesungguhnya penduduknya menjadi miskin karena keserakahan para gubernur dalam pengumpulan, buruk sangka mereka terhadap kelangsungan, dan sedikitnya mereka mengambil pelajaran. Artinya: mereka yang menangani kharaj, jika tidak memperhatikan tanah ini dan pemilik tanah ini, maka dalam keadaan ini kita tidak akan memperoleh kharaj, dan akan berakibat pada kehancuran tanah ini, dan dengan demikian tidak ada kharaj.
Surat yang ditulis Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang gubernurnya ini mengandung dasar-dasar dan prinsip-prinsip luhur dalam dasar penetapan pajak dan pengaturannya, serta memperkuat sistem keuangan negara dengan aturan-aturan kokoh yang menambah kemakmurannya dan menjaga harta-hartanya, serta mencegah kehancuran dan kebangkrutannya.
Hal-Hal Baru dalam Keuangan pada Masa Bani Umayyah
Kemudian kami membahas sekarang tentang sistem keuangan Bani Umayyah: Berdirinya Negara Umayyah disertai perkembangan penting dalam sistem keuangan yang intinya adalah wilayah-wilayah memperoleh kemerdekaan terbesar dalam urusan-urusan keuangan mereka. Sistem administrasi desentralisasi Bani Umayyah menuntut pemberian kekuasaan luas kepada para amir di wilayah-wilayah, bukan hanya dalam urusan administrasi saja, tetapi juga dalam urusan keuangan.
Bani Umayyah kadang-kadang berusaha memisahkan urusan administrasi dari urusan keuangan dengan tujuan memperkuat kekuasaan mereka atas wilayah-wilayah. Namun tuntutan sistem administrasi desentralisasi, dan apa yang menyertainya berupa berubahnya beberapa wilayah menjadi basis penaklukan dan perluasan, mengharuskan penggabungan urusan keuangan (yaitu kharaj) di wilayah kepada amir atau memberikan wewenang kepadanya untuk menunjuk petugas-petugas kharaj dari pihaknya. Setiap wilayah memiliki sistemnya yang khas sesuai dengan apa yang dipertahankan oleh setiap amir dari sistem-sistem lokal wilayah, di samping aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai sistem keuangan Khalifah Umar bin Khattab. Sistem keuangan Bani Umayyah dengan demikian memperoleh ciri-ciri baru yang terwujud dalam adanya sumber-sumber syariat yang telah diatur oleh syariat dan preseden-preseden Islam, dan juga adanya sumber-sumber pengecualian yang lahir dari penghidupan kembali adat lokal wilayah-wilayah. Fenomena baru sistem keuangan Umayyah ini terwujud di wilayah Irak, Syam, dan Mesir.
Jika kita melihat Irak misalnya sebagai contoh untuk sistem baru Bani Umayyah ini, yang mengadakan beberapa sumber baru yang tidak ada pada masa Khulafaur Rasyidin, maka Bani Umayyah mempertahankan sistem keuangan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dari segi jizyah dan kharaj. Tetapi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mulai bekerja untuk meningkatkan sumber-sumber negara dari wilayah ini melalui penghidupan kembali beberapa tradisi lokal yang biasa dilakukan orang-orang pada masa Sasaniyah. Yang kami maksud dengan Sasaniyah adalah para penguasa yang memerintah negeri-negeri ini sebelum Islam masuk ke dalamnya.
Saya katakan: Muawiyah ingin mendatangkan sumber-sumber pendapatan baru selain sumber-sumber yang telah lazim dikenal pada masa Umar bin Khattab, yaitu jizyah (upeti) dan kharaj (pajak tanah). Sumber-sumber pendapatan baru ini berupa perolehan uang melalui penghidupan kembali beberapa tradisi lokal yang biasa dilakukan masyarakat pada zaman Sasaniyah. Ia meminta penduduk Sawad (dataran rendah Irak) untuk memberikan hadiah kepadanya pada Hari Raya Nairuz dan Mihrajan, yakni memberikan hadiah kepadanya, yang mencapai sepuluh ribu ribu dirham. Nairuz adalah salah satu hari raya besar orang Persia yang jatuh pada permulaan musim panas, dan dianggap sebagai tanda pembukaan kharaj, pengangkatan pegawai, dan pencetakan dirham. Adapun Mihrajan jatuh pada permulaan musim dingin dan musim dingin; di mana orang Persia telah terbiasa memberikan hadiah kepada raja-raja mereka. Penghidupan kembali tradisi keuangan kuno ini menjadi sumber pendapatan baru dari wilayah Irak pada zaman Bani Umayyah di samping jizyah dan kharaj. Artinya ada jenis baru dari sumber-sumber keuangan yang ditambahkan kepada sumber-sumber Islam, yaitu mereka menambahkan kepada jizyah dan kharaj sumber lain. Sumber lain ini adalah yang disebut hadiah Nairuz dan Mihrajan—dua hari raya pada orang Persia—dan kebiasaan mereka pada hari-hari raya ini adalah memberikan hadiah kepada raja-raja. Hadiah-hadiah ini mencapai jumlah yang besar; oleh karena itu Bani Umayyah menghidupkan kembali kebiasaan ini, yaitu hadiah yang mereka berikan sebelumnya kepada raja-raja mereka—yakni sebelum Islam masuk ke negeri mereka.
Ini adalah jenis baru dan jenis pengaturan baru untuk sumber-sumber baitul mal, yang tidak ada pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak pada masa Abu Bakar, tidak pada masa Umar, dan tidak pada masa Utsman, bahkan hal itu diciptakan oleh Bani Umayyah. Muawiyah juga berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan Irak melalui reklamasi tanah-tanah di daerah yang disebut Bathaaih, yaitu tanah rendah yang membentang antara Basrah dan Kufah yang tergenang air. Ia berhasil melalui pegawai-pegawai kharaj di wilayah Irak mereklamasi perkebunan-perkebunan luas yang hasilnya mencapai lima ribu dirham menurut perhitungan hari-hari ini. Pekerjaan yang dilakukan Muawiyah ini menjadi tradisi penting yang diikuti oleh semua khalifah yang datang setelahnya, hingga sumber-sumber pendapatan Irak memperoleh bagian besar dari tanah-tanah baru tersebut.
Inilah sumber pendapatan kedua dari sumber-sumber yang diciptakan Bani Umayyah pada masa kekuasaan mereka. Kami katakan: Sumber pertama adalah hadiah-hadiah yang diberikan kepada mereka dari penduduk negeri-negeri ini pada hari-hari raya mereka yaitu Nairuz dan Mihrajan.
Sumber kedua yang diciptakan Bani Umayyah adalah reklamasi tanah-tanah. Ada tanah-tanah luas yang tidak ditanami, maka mereka melakukan reklamasi tanah-tanah ini, dan ketika tanah-tanah ini direklamasi, mereka menetapkan pajak atasnya… dan sebagainya; oleh karena itu tanah-tanah ini mendatangkan uang yang sangat banyak; maka dari itu reklamasi tanah menjadi kebiasaan yang diikuti sejak masa Bani Umayyah dan mereka yang datang setelah mereka dalam pemerintahan sangat memperhatikannya. Tanah-tanah yang direklamasi ini mendatangkan sumber pendapatan tetap bagi keuangan negara Islam pada masa Bani Umayyah.
Juga para gubernur Bani Umayyah di Irak memperhatikan pengorganisasian alat keuangan mereka untuk mencapai sumber pendapatan sebesar mungkin. Ubaidullah bin Ziyad menggunakan para dahaqin—yaitu kepala-kepala desa—karena keahlian mereka dalam urusan keuangan daripada pegawai-pegawai Arab. Ini juga merupakan salah satu cara yang ditempuh Bani Umayyah untuk meningkatkan uang yang datang kepada mereka, yaitu mereka juga menjadikan sebagai jenis sumber pendapatan baru bahwa mereka mengganti pegawai-pegawai Muslim dengan pegawai-pegawai lain yang disebut dahaqin—yaitu kepala-kepala desa—karena keahlian mereka dalam urusan keuangan daripada pegawai-pegawai Arab. Mereka ini hanya memperhatikan kebutuhan negara akan uang, dan mungkin tidak memperhatikan kebutuhan kaum Muslimin; oleh karena itu mereka menggunakan mereka sebagai pengganti kaum Muslimin.
Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
4 – Sistem Keuangan pada Masa Bani Umayyah dan Umar bin Abdul Aziz
Lanjutan: Hal-hal Baru dalam Bidang Keuangan pada Masa Bani Umayyah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, Sayyidina Muhammad, dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Kiamat. Amma ba’du:
Kita telah berbicara pada kuliah sebelumnya tentang sistem keuangan pada masa Bani Umayyah, dan telah jelas bagi kita bahwa mereka tidak hanya membatasi pada sumber-sumber keuangan yang ada pada masa Umar bin Khattab berupa: zakat, jizyah, dan kharaj, bahkan mereka menambah sumber-sumber keuangan lain. Kami sebutkan di antaranya: hadiah-hadiah yang mereka wajibkan atas penduduk wilayah-wilayah, yang dahulu mereka bayarkan pada hari-hari raya mereka kepada raja-raja mereka sebelum Islam menaklukkan negeri-negeri mereka. Di antara sumber-sumber baru ini juga: reklamasi tanah-tanah yang tidak digunakan untuk pertanian.
Kami lanjutkan pembahasan dalam kuliah baru ini tentang sumber-sumber pendapatan baru ini. Kami katakan: Para gubernur Bani Umayyah di Irak juga memperhatikan pengorganisasian alat keuangan mereka untuk mencapai sumber pendapatan sebesar mungkin. Ubaidullah bin Ziyad menggunakan para dahaqin—yang dimaksud adalah kepala-kepala desa—karena keahlian mereka dalam urusan keuangan daripada pegawai-pegawai Arab. Ia membenarkan kebijakannya dengan berkata: “Jika aku mengangkat orang Arab, kharaj akan berkurang—yakni: kharaj menjadi sedikit—jika aku menuntut kaumnya atau menagihnya, aku akan membuat hati mereka kesal, dan jika aku membiarkannya, aku akan meninggalkan harta Allah, padahal aku tahu tempatnya. Aku dapati para dahaqin lebih paham tentang pemungutan, lebih amanah, dan lebih mudah dalam penagihan daripadanya.”
Ini adalah jenis yang diciptakan Bani Umayyah dengan tujuan meningkatkan hasil dari jizyah dan kharaj; yaitu mereka menggunakan orang-orang non-Muslim, yaitu kepala-kepala desa negeri-negeri ini dalam pemungutan sebagai pengganti pegawai-pegawai Arab dan Muslim. Hal itu dibenarkan—sebagaimana kami jelaskan—oleh Ubaidullah bin Ziyad yang mengatakan bahwa ketika orang Arab mengelola pemungutan kharaj dan jizyah, maka kharaj akan berkurang, dan kita tidak dapat memintanya pertanggungjawaban atas hal itu. Tetapi jika kita menyerahkan jabatan ini kepada non-Muslim seperti: para dahaqin—yaitu kepala-kepala desa—maka mereka lebih mampu menghimpun jizyah dan menghimpun kharaj; karena mereka lebih tahu tentang hal itu daripada orang Arab; oleh karena itu mereka lebih memilih mereka daripada orang Arab.
Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan terjadi perubahan dalam sistem pajak di Irak utara di tanah Jazirah untuk menjamin peningkatan sumber pendapatan; yaitu ia mengutus Adh-Dhahhak bin Abdurrahman Al-Asy’ari kepada penduduk Jazirah. Ia melakukan sensus jumlah mereka, kemudian menghitung apa yang diperoleh pekerja dalam setahun penuh, kemudian mengurangi biaya hidupnya untuk makanan dan pakaiannya. Ia dapati bahwa yang tersisa setelah itu dalam setahun penuh untuk setiap orang adalah empat dinar, maka ia mewajibkan itu kepada mereka semua dan menjadikan mereka satu tingkatan. Ini juga merupakan salah satu jenis sumber keuangan baru yang diciptakan dan diadakan Bani Umayyah pada masa kekhalifahan mereka, dan ini berupa sensus penduduk, kemudian menetapkan pajak atas mereka yang dikenal sebagai: pajak kepala.
Bani Umayyah menempuh kebijakan sensus penduduk di Irak setiap kali diperlukan perubahan dalam sumber pendapatan. Pekerjaan terakhir Bani Umayyah dalam hal itu adalah yang dilakukan Umar bin Hubairah pada masa kekhalifahan Yazid Kedua tahun seratus lima Hijriah, yaitu ia melakukan survei Sawad—yakni dataran Irak—dan menentukan daerah-daerah yang diambil pajak darinya. Survei inilah yang menjadi dasar sistem keuangan di wilayah itu, bahkan setelah berakhirnya masa Bani Umayyah dan berdirinya Bani Abbasiyah dalam kekhalifahan.
Di Syam, Bani Umayyah mengikuti kaidah-kaidah umum yang sama yang mereka terapkan di Irak, dari segi melakukan sensus penduduk setiap kali diperlukan perubahan dalam sumber-sumber keuangan. Pada saat yang sama, kaidah-kaidah dasar sistem keuangan Khalifah Umar bin Khattab tetap berlaku di negeri Syam; di mana kota-kota membayar kewajiban jizyah dan kharaj mereka secara sekaligus. Tetapi Syam dibedakan dengan adanya baitul mal pusat, yang menerima sumber-sumber pendapatan yang berlebih dari baitul-baitul mal di wilayah-wilayah. Sumber pendapatan utama para khalifah Bani Umayyah di Damaskus datang dari kenaikan-kenaikan yang mereka tetapkan atas beberapa wilayah, atau dari para panglima penaklukan, serta dari shawafi. Shawafi adalah: tanah-tanah yang pada asalnya merupakan milik kaisar-kaisar Persia dan Romawi, atau milik seseorang yang terbunuh dalam perang, atau seseorang yang bergabung dengan ahli harb—yakni dengan musuh. Tanah-tanah ini disebut: shawafi.
Dinamakan shawafi karena khalifah mengistimewakan—yakni menjadikannya khusus—untuk baitul mal. Kadang-kadang disebut juga dengan nama: qatha’i; karena khalifah membagikan sebagiannya sebagai iqtha’ (pemberian tanah) kepada siapa yang dikehendaki dari orang-orang dekatnya. Ini juga merupakan jenis baru dari sumber-sumber keuangan yang diciptakan dan diadakan Bani Umayyah.
Para khalifah Bani Umayyah dengan demikian mampu memikul beban istana di Damaskus, karena banyaknya utusan-utusan yang datang kepada mereka dan pemberian-pemberian tinggi yang diperlukan, serta untuk menenangkan suku-suku yang banyak dan membeli kesetiaan mereka dengan uang. Bani Umayyah meninggalkan warisan seni dan arsitektur yang bersaksi bagi mereka tentang kekayaan yang luas dan baiknya pengaturan keuangan.
Kaidah-kaidah Baru dalam Sistem Keuangan dan Lembaga-lembaganya:
Sekarang kita berbicara tentang kaidah-kaidah baru dalam sistem keuangan dan lembaga-lembaganya. Kita mulai dengan pengaraban diwan kharaj:
Kami katakan: Meluasnya sumber-sumber pendapatan negara dan beragamnya aspek pengeluarannya memerlukan pengendalian lembaga-lembaga keuangan, dan menetapkan kaidah-kaidah baru untuk mengawasi kegiatannya dan jalannya pekerjaan di dalamnya. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang pertama yang merasakan kebutuhan itu, sebagai akibat dari kemandirian keuangan wilayah-wilayah. Ia memerintahkan Amr bin Zubair dengan seratus ribu dirham dan menyerahkan kepadanya surat dengan hal itu agar mengambil jumlah uang itu dari gubernur Irak, Ziyad bin Abihi. Amr bin Zubair membuka surat di perjalanan dan menjadikan seratus itu menjadi dua ratus. Ketika khalifah meninjau anggaran Irak, ia merasa ragu dan mengingkari kecurangan ini. Meskipun otoritas keuangan mengembalikan jumlah ini, namun Muawiyah melihat bahwa perlu ada pengendalian baru untuk lembaga-lembaga keuangan, dan untuk tujuan ini ia mendirikan: diwan khataim (dewan stempel).
Jadi diwan khataim, yang kami maksud dengan khataim adalah: stempel yang digunakan untuk mengecap surat-surat yang keluar dari khalifah.
Peristiwa yang terjadi pada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin Zubair yang menipu dan memainkan kertas-kertas yang ada di tangannya, menjadikan seratus menjadi dua ratus, dan pemalsuan yang terjadi ini membuat Muawiyah berpikir tentang masalah ini; oleh karena itu ia melihat bahwa perlu ada pengendalian baru untuk lembaga-lembaga keuangan karena takut akan pemalsuan yang terjadi ini. Jika ada pemalsuan terhadap khalifah maka lebih-lebih lagi akan ada pemalsuan terhadap pejabat-pejabat lain dalam negara. Oleh karena itu untuk tujuan ini ia mendirikan dewan yang disebut: diwan khataim.
Dewan baru ini menjadi salah satu ciri terpenting dari kaidah-kaidah keuangan baru pada masa Bani Umayyah. Dewan ini memiliki sistem yang teliti dan pegawai-pegawai yang waspada. Jika keluarlah keputusan dari khalifah tentang suatu urusan, keputusan itu dibawa ke dewan tersebut, salinannya dicatat di dalamnya, diikat dengan benang, disegel dengan lilin, dan distempel dengan stempel kepala dewan. Kepemimpinan dewan ini pada masa Muawiyah dipegang oleh salah seorang hakim yang adil, yaitu Abdullah bin Muhshan Al-Himyari, dengan keinginan menyediakan amanah untuk urusan-urusan keuangan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid ternyata bahwa diwan khataim saja tidak lagi cukup, dan pengaturan keuangan negara memerlukan pengaraban diwan kharaj di setiap wilayah, sebagai lembaga keuangan utama yang mengawasi sumber-sumber pendapatan dan semua urusan yang berkaitan dengannya.
Bahasa diwan-diwan kharaj di wilayah-wilayah adalah bahasa yang sama yang mereka gunakan sebelum penaklukan Islam; bahasa diwan kharaj di Irak adalah Persia, di Syam adalah Yunani, dan di Mesir adalah Yunani dan Koptik. Keadaan ini tidak lagi sesuai dengan meluasnya kekuasaan para gubernur Arab dan beragamnya sumber-sumber pendapatan negara. Dorongan untuk mengarabkan diwan-diwan kharaj adalah memampukan para gubernur Arab untuk mengawasi secara penuh urusan-urusan keuangan wilayah-wilayah mereka; karena pencatatan register dengan bahasa-bahasa asing mendorong pegawai-pegawai kecil untuk memalsukan dan memainkan register tanpa terbongkar urusan mereka.
Sulaiman bin Sa’d Al-Khusyani—sekretaris Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk surat-menyurat—adalah yang mengarabkan diwan kharaj Syam yaitu pada tahun 81 Hijriah. Langkah ini merupakan pekerjaan penting dalam pengaturan keuangan negara Islam, di mana pengawas dewan ini dan rahasia-rahasianya sejak masa Muawiyah adalah Manshur bin Sarjun Ar-Rumi. Khalifah memberikan kepada Sulaiman bin Sa’d sebagai imbalan atas pekerjaan mulia ini kharaj Yordania sebagai hadiah, yang jumlahnya seratus delapan puluh ribu dinar.
Penghargaan paling jelas atas keberhasilan pengaraban diwan kharaj adalah ucapan Manshur bin Sarjun kepada para penulis dewan lama dari pemilik bahasa Yunani: “Carilah penghidupan dari selain pekerjaan ini.” Ini adalah bukti bahwa mereka tidak amanah dalam hal ini; ketika orang Arab pada masa Bani Umayyah mengarahkan untuk mengarabkan dewan-dewan dan menjadikannya dengan bahasa Arab, maka orang-orang Ajam ini—non-Muslim yang bekerja di dewan-dewan ini—mendapati bahaya atas mereka dari hal itu, terbongkar urusan mereka, dan ternyata bahwa mereka adalah pemalsu dan memakan harta negara dengan batil. Oleh karena itu salah seorang dari mereka—yaitu Manshur bin Sarjun kepada para penulis dewan lama dari pemilik bahasa Yunani—berkata: “Carilah penghidupan dari selain pekerjaan ini,” yakni: tidak ada lagi tempat bagi kalian dalam urusan ini, kalian tidak lagi dapat memperoleh uang melalui pemalsuan dan sebagainya, setelah dewan-dewan ini diarabkan, dan para gubernur Arab mampu mengawasi secara penuh urusan-urusan keuangan wilayah-wilayah mereka.
Dan yang mengawasi Diwan Al-Kharaj (kantor pajak) di Irak pada saat itu adalah seorang pria bernama “Zadan Farrukh” yang diangkat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ath-Thaqafi. Kebetulan pegawai ini terbunuh saat terjadi fitnah Abdul Rahman bin Al-Asy’ath antara tahun 82 dan 83 Hijriah, dan hal ini memudahkan Al-Hajjaj untuk mewujudkan kebijakan keuangan negara yang baru, yang berupaya untuk mengarabkan diwan-diwan (kantor-kantor pemerintahan). Al-Hajjaj lalu menugaskan seorang pria bernama Shalih bin Abdurrahman yang menguasai bahasa Persia dan Arab untuk mengarabkan Diwan Kharaj Irak. “Mardan Syah”, anak dari “Zadan Farrukh” yang telah terbunuh itu, mencoba menyuap Shalih bin Abdurrahman agar ia membatalkan niatnya dan menghentikan pekerjaannya mengarabkan diwan-diwan, namun pegawai Arab ini menolak dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat sukses. Di bawah bimbingannya, lahirlah sejumlah pegawai keuangan Arab terkemuka di Irak.
Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa para pegawai non-Muslim ini sangat mempertahankan tugas dan pekerjaan mereka, yaitu bekerja di diwan-diwan dengan menggunakan bahasa yang mereka kuasai, yang tidak dikuasai oleh kaum Muslim. Mereka tidak menginginkan pengaraban diwan-diwan karena dengan pengaraban diwan-diwan, orang-orang Arab akan memahami pekerjaan tersebut dengan akurat, dan hal itu berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, kita melihat pria bernama “Mardan Syah” ini mencoba menawarkan suap kepada Shalih bin Abdurrahman agar ia tidak mengarabkan diwan-diwan, sehingga ia dapat melanjutkan pekerjaan ayahnya yang menghasilkan uang berlimpah melalui pemalsuan.
Pengaraban Diwan Kharaj Mesir dilakukan pada masa Walid bin Abdul Malik, di bawah pengawasan saudaranya, wali Mesir Abdullah bin Abdul Malik pada tahun 78 Hijriah/707 Masehi, ketika pemilik diwan ini yang bernama “Athnasy” dipecat dan digantikan oleh seorang Arab bernama Ibnu Yarbu’ Al-Farazi. Setelah itu, dilakukan pengaraban diwan-diwan lainnya di negeri-negeri Maghrib oleh Musa bin Nushair. Yang terakhir adalah Diwan Kharaj Khurasan yang pengarabannya dilakukan pada tahun 124 Hijriah oleh Ishaq bin Tulaiq, atas penugasan dari wali Nashr bin Sayyar.
Seluruh diwan kharaj di Negara Islam kemudian menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Ini merupakan langkah penting yang membuka jalan bagi penyebaran kebudayaan Arab ke seluruh penjuru negara tersebut, karena orang-orang terpaksa mempelajari bahasa Arab untuk memudahkan urusan mereka dengan para pegawai administrasi baru yang berasal dari orang Arab, serta untuk menjamin hak-hak mereka dan melindungi kepentingan mereka juga. Fenomena khusus pengaraban diwan-diwan kharaj inilah yang mengalihkan perhatian dari pentingnya aspek keuangannya kepada pelacakan pengaruhnya dalam bidang peradaban Arab-Islam.
Fenomena ini sekaligus menjadi bukti yang sangat baik bahwa sistem keuangan bukanlah sistem yang kering, sebagaimana studi-studi teoretis modern mencoba memotong ciri-cirinya, melainkan ia adalah organ yang efektif dalam bangunan Negara Arab-Islam, yang berkoordinasi dengan organ-organ lain dari sistem-sistem Islam, demi menjaga keselamatan dan melindungi masyarakat Islam.
Mata Uang Arab Baru:
Pengaraban diwan-diwan kharaj dibarengi dengan pencetakan mata uang baru untuk mendukung sistem keuangan negara, mengatur transaksi keuangan antar wilayah, dan mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak dari rakyat. Beberapa wilayah seperti Syam dan Mesir bertransaksi dengan dinar dari emas, yang merupakan unit dasar mata uang yang berlaku di masing-masing wilayah itu sejak masa ketergantungan mereka kepada Negara Romawi sebelum Islam. Sedangkan Irak dan Persia bertransaksi dengan dirham dari perak, yang berlaku dalam aktivitas ekonomi mereka sejak zaman Sasania sebelum Islam. Orang Arab mengenal kedua jenis mata uang ini sejak masa Jahiliah, ketika dinar-dinar dari Romawi dan dirham-dirham dari negeri Persia masuk ke wilayah mereka. Kurs tukar yang berlaku pada mereka adalah setiap sepuluh dirham sama dengan tujuh dinar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menetapkan hal itu, dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, serta Muawiyah pun menetapkannya.
Namun segera terlihat sulitnya melanjutkan sistem ganda mata uang ini, karena luasnya wilayah negara di satu sisi, dan kerusakan yang merasuki sebagian mata uang ini di sisi lain. Orang-orang terbiasa membayar kharaj dengan mata uang yang bernilai rendah dan menyimpan mata uang yang bernilai tinggi, yang merugikan kharaj dan merusak keadilan dalam pemungutannya. Kondisi buruk ini dihadapi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika orang-orang menuntut kusur (sisa-sisa uang yang tertinggal), dan para pembayar pajak berinisiatif melunasi kusur tersebut dengan mata uang yang bernilai rendah.
Imam Al-Mawardi dalam bukunya (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) menjelaskan fenomena ini dengan berkata: “Kemudian orang-orang menjadi rusak, sehingga pemilik kharaj membayar dengan Thabariyyah (sejenis mata uang) yang beratnya empat dawaniq, dan mereka berpegang pada Wafi yang beratnya seberat mitsqal. Ketika Ziyad memerintah Irak, ia menuntut pembayaran dengan Wafi dan mewajibkan mereka membayar kusur. Para petugas Bani Umayyah terus melanjutkan hal ini hingga Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Ia lalu mempertimbangkan kedua timbangan tersebut dan menetapkan berat dirham pada setengah dan seperlima mitsqal, sementara mitsqal tetap pada keadaannya.” Demikianlah perkataan Al-Mawardi.
Kekacauan mata uang Persia yang digunakan di wilayah-wilayah timur seperti Irak, Persia, dan Khurasan semakin parah karena buruknya timbangan perak di dalamnya dan banyaknya yang palsu. Al-Mawardi mengisyaratkan hal ini dalam perkataannya: “Bangsa Persia ketika urusan mereka rusak, mata uang mereka pun rusak. Islam datang sementara mata uang mereka dari emas dan perak (wariq) tidak murni, namun mata uang itu tetap berlaku dalam transaksi seperti yang murni.” Fenomena ini pada gilirannya menyebabkan buruknya pemungutan kharaj dan berkurangnya jumlah sebenarnya karena masuknya mata uang palsu atau yang tidak bagus cetakannya ke Diwan Kharaj. Situasi ini menuntut segera diterbitkannya mata uang baru yang menghapus kerusakan-kerusakan tersebut dan menghilangkan dampak buruknya.
Wilayah-wilayah negara, khususnya di Mesir dan Syam, mengalami kesulitan jenis lain akibat monopoli Romawi (Bizantium) atas dinar dan pengendalian mereka terhadap harganya. Dengan cepat meledaklah krisis antara Negara Umayyah dan Kekaisaran Romawi yang mempercepat otoritas Umayyah untuk menetapkan mata uang baru bagi wilayah-wilayah mereka pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan sendiri. Mesir mengekspor qirathis (kertas tulis pada masa itu) ke Kekaisaran Romawi sejak ketergantungannya kepada mereka sebelum penaklukan Islam. Orang-orang Qibthi Mesir terbiasa menulis nama Nabi Isa dan kalimat Trinitas di kepala-kepala thaumir (lembaran-lembaran kertas besar).
Namun Khalifah Abdul Malik berpendapat bahwa rumusan ini tidak sesuai dengan penampilan Negara Islam yang baru, maka ia memerintahkan agar rumusan ini diganti dengan kalimat: “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa” (Surah Al-Ikhlas: 1). Qirathis baru ini sampai ke Kekaisaran Romawi dan menimbulkan kegemparan besar di istana. Kaisar “Justinian II” marah dan merasa besar melihat Negara Islam menjalankan salah satu hak kedaulatannya. Ia menulis kepada Khalifah Abdul Malik: “Kalian telah membuat tulisan baru pada qirathis kalian yang kami benci” -maksudnya kalimat yang ditulis pada mata uang ini yaitu: “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa” – “Jika kalian meninggalkannya, baiklah. Jika tidak, akan kami tulis pada dinar-dinar kalian tentang nabi kalian yang kalian benci.” Seolah-olah “Justinian sang Kaisar” mengancam Abdul Malik bin Marwan dan berkata kepadanya: “Kalian harus menghapus apa yang kalian tulis pada mata uang ini yaitu kalimat: “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa” atau kami akan menulis untuk kalian tentang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hal-hal yang kalian benci.”
Surat ini sangat membuat Khalifah Abdul Malik bin Marwan marah dan ia khawatir kondisi mata uang akan kacau akibat ancaman Kaisar Romawi, serta dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya terhadap jiwa kaum Muslim pada umumnya, karena dinar-dinar Romawi adalah mata uang resmi untuk perdagangan di pasar-pasar Islam internal maupun dengan negara-negara luar. Selama krisis ini, tampak kekuatan Dinasti Umayyah dan pemikiran mereka yang dipenuhi keinginan untuk lepas dari ketergantungan moneter ini serta menerbitkan mata uang baru khusus untuk Negara Islam. Khalid bin Yazid menyarankan kepada Khalifah Abdul Malik untuk mempertahankan qirathis baru (yaitu qirathis yang ditulis dengan rumusan: Tiada tuhan selain Allah) tanpa takut pada ancaman Bizantium.
Ia berkata: “Wahai Amirul Mukminin, haramkan dinar-dinar mereka agar tidak diperdagangkan, dan cetaklah untuk rakyat mata uang baru (sikkah), dan jangan bebaskan orang-orang kafir ini dari apa yang mereka benci pada thaumir” maksudnya: jangan hapus kalimat yang membuat mereka marah ini, yaitu kalimat: “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”.
Saran ini sesuai dengan keinginan Khalifah, dan ia melihat bahwa ini merupakan langkah mendasar untuk mendukung sistem keuangan negara dan menciptakan kesatuan ekonomi melalui mata uang khusus untuknya. Abdul Malik mulai mencetak dinar-dinar Islam baru yang bertuliskan ayat-ayat dari Al-Quran, yang dikenal dengan nama: Dinar Dimasyqiyyah (Dinar Damaskus). Ia juga mengeluarkan perintah kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ath-Thaqafi di Irak untuk mencetak dirham-dirham Islam menggantikan dirham Persia. Khalifah menetapkan standar tetap untuk kedua jenis mata uang ini sesuai dengan syariat.
Mata uang Islam baru ini mendapat penghormatan dari orang-orang di mana-mana karena timbangan yang benar, dan mereka segera bertransaksi dengannya tanpa terjadi gangguan dalam sistem keuangan Negara Islam. Transaksi moneter baru ini diperkuat dengan dikeluarkannya perintah Khalifah yang menetapkan bahwa tempat-tempat pencetakan yang dimiliki negara adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak mata uang, mengharamkan mata uang yang dicetak di luar tempat tersebut, dan menarik mata uang lama yang beredar dari pasar-pasar.
Sistem keuangan Negara Umayyah mendapat manfaat dari stabilitas moneter ini, di mana mata uang baru menjamin keadilan bagi rakyat dan kharaj milik negara. Para sejarawan sepakat bahwa timbangan yang digunakan untuk mencetak mata uang tersebut adalah timbangan syar’i yang berlaku pada masa Rasulullah yang Mulia shallallahu ‘alaihi wasallam dari mata uang-mata uang yang baik pada masa itu, yaitu: dirham Persia dan dinar Romawi.
Ibnu Khaldun meriwayatkan dalam menggambarkan orang-orang yang sezaman dengan mata uang baru ini dengan berkata: “Mata uang Abdul Malik terbit sesuai dengan timbangan-timbangan ini, dan ijma’ menetapkan bahwa itulah mata uang syar’i. Semua orang sepakat untuk menggunakannya, para fuqaha menyetujuinya dan menetapkan bahwa itulah yang digunakan untuk zakat dan untuk menunaikan semua hak yang diwajibkan atau dianjurkan oleh syariat. Penggunaan timbangan-timbangan ini terus berlaku di era-era Islam.”
Sikap Umar bin Abdul Aziz terhadap Kesalahan-Kesalahan Keuangan pada Masa Umayyah
Tidak luput dari pembahasan ini untuk membicarakan pengaturan keuangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Kami katakan: Sistem keuangan Umayyah mengalami sejumlah penyimpangan yang menyimpang. Sebagian terjadi akibat masalah penerapan oleh para petugas kharaj di wilayah-wilayah, dan sebagian lainnya akibat masalah perkembangan yang dialami Negara Islam dan perluasannya. Penyimpangan jenis pertama terwujud dalam tindakan sewenang-wenang para petugas kharaj dalam pemungutan pajak. Makna kesewenang-wenangan mereka dalam pemungutan pajak adalah: mereka mengambil lebih dari yang ditetapkan, dan itu merupakan kezaliman yang sangat berat terhadap wajib pajak atau para pembayar pajak ini.
Sementara penyimpangan jenis kedua terjadi karena kebijakan Umayyah dalam memberikan hak-hak istimewa keuangan kepada para pendukung mereka dan keluarga mereka, kemudian karena kebingungan otoritas Umayyah dalam menghadapi perkembangan yang menyertai masuknya penduduk wilayah-wilayah ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Penyimpangan-penyimpangan yang menyimpang ini mencapai puncaknya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik takhta kekhalifahan, dan saat itu menjadi bahaya yang mengancam kehancuran dan keruntuhan struktur keuangan negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera menetapkan pengaturan keuangan untuk menangani penyimpangan-penyimpangan tersebut, karena ia telah mengetahui sebelumnya tentang hal-hal ini dan penyebabnya sebelum menjadi khalifah. Ia mengetahui buruknya perbuatan sejumlah wali-wali Umayyah, dan berkata tentang mereka: “Al-Hajjaj di Irak, Al-Walid di Syam, Qurrah di Mesir, Utsman di Madinah, dan Khalid di Makkah. Ya Allah, dunia telah penuh dengan kezaliman dan penindasan, maka berilah ketenangan kepada manusia.”
Ia berusaha radiyallahu ‘anhu sebelum masa kekhalifahannya untuk memberikan nasihat kepada sebagian wali-wali tersebut dan para petugas kharaj, di antaranya Usamah bin Zaid petugas kharaj Mesir. Umar tidak menerima alasan yang dikemukakan oleh wali tersebut yaitu melaksanakan kebijakan Khalifah Sulaiman, dan berkata kepadanya: “Sesungguhnya itu tidak akan menolongmu sedikitpun dari Allah.” Umar bin Abdul Aziz juga berkata tentang Yazid bin Al-Muhallab dan keluarganya: “Mereka ini adalah orang-orang yang sewenang-wenang (jabbarah), dan aku tidak menyukai orang-orang seperti mereka.”
Umar bin Abdul Aziz membuka masa khalifah dengan memberhentikan Usamah bin Zaid dari Mesir, dan Yazid bin Muhallab dari Khurasan, dan mengangkat sebagai pengganti mereka para pegawai yang lebih adil dan bijaksana. Kemudian ia berupaya menghilangkan penyimpangan-penyimpangan aneh yang sebelumnya terjadi di setiap wilayah. Mesir telah menyaksikan pajak-pajak tambahan yang memberatkan terhadap para rahib, yang sebelumnya dibebaskan oleh pihak berwenang dari pembayaran pajak apapun. Negeri Yaman membayar pajak-pajak yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Adapun Irak telah mencapai penyimpangan-penyimpangan aneh dalam jumlah yang besar, yang terwujud dalam hal-hal berikut:
- Pengenaan pajak yang sama terhadap tanah yang ditanami dan yang tidak ditanami.
- Pemungutan pajak-pajak tambahan, sebagian merupakan penghidupan kembali pungutan-pungutan tradisional Persia yang terkenal dengan nama “al-Abin”, dan sebagian lainnya mencakup upah yang dibayarkan kepada para pekerja yang bekerja di tempat percetakan uang.
- Pemungutan harga kertas yang digunakan dalam permohonan-permohonan resmi dari masyarakat.
- Pengenaan pajak terhadap para pelacur.
- Pengenaan pajak terhadap beberapa rumah.
- Persyaratan para pegawai untuk memungut pajak dengan mata uang yang memiliki berat tertentu, bukan dengan mata uang yang tersedia di tangan penduduk, dan mengambil selisih nilai tukar untuk diri mereka sendiri.
Dan terakhir: Penambahan pajak jenis tertentu terhadap penduduk Najran di Kufah, karena tuduhan bersekongkol dengan beberapa pemberontak terhadap negara.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pegawainya di Kufah yang memerintahkannya untuk membatalkan tindakan-tindakan menyimpang tersebut dengan mengatakan: “Amma ba’du, sesungguhnya penduduk Kufah telah ditimpa bencana, kesulitan, dan kezaliman dalam hukum-hukum Allah, dan kebiasaan buruk yang dijadikan tradisi atas mereka oleh para pegawai yang buruk. Sesungguhnya tegaknya agama adalah keadilan dan ihsan.” Kemudian ia berkata kepadanya: “Janganlah kalian membebankan tanah yang rusak kepada tanah yang subur, dan jangan pula membebankan tanah yang subur kepada tanah yang rusak. Perhatikan tanah yang rusak lalu ambillah darinya apa yang mampu, dan perbaikilah hingga menjadi subur. Janganlah diambil dari tanah yang subur kecuali kewajiban kharaj dengan kelembutan dan ketenangan bagi penduduk negeri. Janganlah kalian mengambil dalam kharaj: upah para pencetak uang, hadiah Nairuz dan Mihrajan, harga lembaran-lembaran, upah para pasukan, upah rumah-rumah, dirham pernikahan, dan kharaj atas orang yang masuk Islam dari penduduk negeri.”
Khalifah memutuskan untuk mengurangi jumlah yang dibebankan kepada penduduk Najran di Kufah dari seribu tiga ratus hullah pada masa Hajjaj menjadi hanya dua ratus hullah saja. Hullah adalah sejenis pakaian, dan itu mencapai sepersepuluh dari apa yang mereka bayarkan sebelumnya—maksudnya: sebelum ia menjabat sebagai khalifah.
Ia memerintahkan pada waktu yang sama agar tidak diambil dari penduduk Yaman kecuali jumlah kharaj yang sesuai syariat, yaitu sepersepuluh atau setengahnya, dengan mengatakan: “Demi Allah, sungguh jika tidak datang kepadaku dari Yaman selain segenggam katam—sejenis pacar—lebih aku sukai daripada menetapkan kewajiban ini.” Dan ia menghapuskan—akhirnya—pajak-pajak yang dibebankan kepada para rahib Mesir.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menghadapi penyimpangan-penyimpangan aneh yang terkait dengan masalah-masalah perkembangan dalam negara Islam; suatu penghadapan yang mengungkapkan keimanan yang tulus terhadap keadilan Islam, dan pengalaman luasnya dalam urusan fikih Islam. Masalah pertama yang ia upayakan untuk diselesaikan adalah masalah shawafi (tanah-tanah milik negara), yang mana anak-anak keluarga Bani Umayyah mendapat bagian terbesar darinya, tanpa memperhatikan sistem keuangan khusus untuk tanah-tanah umum negara tersebut. Para Umayyah ini mengambil hasil dari shawafi ini, tetapi ia berpendapat bahwa tanah-tanah itu tunduk pada sistem umum negara Islam, dan seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan kaum muslimin.
Maka ia menyebut tanah-tanah yang dikuasai oleh Umayyah tersebut dengan nama: mazhalim (kezaliman), ia menganggapnya sebagai kezaliman. Makna dari itu adalah bahwa mazhalim harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ia memulai dengan apa yang ada padanya dan apa yang ada pada keluarganya, lalu mengembalikannya kepada negara. Ia mulai menerapkan hal itu pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Harta-harta atau kekayaan yang datang dari tanah yang disebut shawafi ini dibagikan kepada Bani Umayyah; oleh karena itu ia menganggap bahwa hal tersebut merupakan bentuk kezaliman, dan kezaliman harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bani Umayyah marah terhadap kebijakan tersebut dan akibatnya yaitu berkurangnya pendapatan mereka. Mereka mengirim bibinya, Fathimah binti Marwan, kepadanya untuk menghalanginya dari hal itu—maksudnya: untuk menghalangi dan mencegahnya dari mengembalikan kezaliman-kezaliman ini. Maka ia berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah Taala mengutus Muhammad sebagai rahmat, tidak mengutusnya sebagai azab. Sesungguhnya Allah Taala mengutus Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh manusia, kemudian Allah memilih baginya apa yang ada di sisi-Nya, lalu ia meninggalkan bagi mereka sebuah sungai, minuman mereka di dalamnya sama rata. Kemudian Abu Bakar berkuasa dan membiarkan sungai itu dalam keadaannya. Kemudian Umar berkuasa dan bekerja sesuai dengan cara sahabatnya. Ketika Utsman berkuasa, ia membuat saluran dari sungai itu. Kemudian Muawiyah berkuasa dan membuat saluran-saluran darinya. Kemudian sungai itu terus dibuat saluran-salurannya oleh Yazid, Marwan, Abdul Malik, dan Sulaiman, hingga urusan sampai kepadaku, dan sungai besar itu telah kering. Pemilik-pemilik saluran tidak akan mendapat pengairan hingga dikembalikan kepadanya dari salurannya ke sungai besar seperti keadaan semula.”
Barangkali yang ia maksud dengan sungai tersebut adalah: harta-harta ini, sumber-sumber keuangan Islam yang datang melalui zakat, jizyah, usyur, dan kharaj. Inilah sungainya, yang dulunya semua orang memperoleh manfaat darinya, dan dahulu adalah satu sungai, tetapi setelah itu menjadi memiliki anak-anak sungai. Oleh karena itu ia tidak rela dengan hal tersebut.
“Pemilik-pemilik sungai tidak akan mendapat pengairan”—maksudnya: ia bermaksud seluruh kaum muslimin, dan mereka mengambil hak-hak mereka dari sungai ini. Makna dari itu adalah bahwa sungai ini dimaksudkan—sebagaimana kami katakan—harta-harta yang dimiliki oleh negara Islam; dan pemilik-pemilik sungai tidak akan mendapat pengairan hingga dikembalikan kepadanya dari salurannya ke sungai besar seperti keadaan semula—maksudnya: seperti keadaan pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.
Ia tidak takut dalam mengembalikan kezaliman-kezaliman tersebut terhadap ucapan siapapun, atau reaksi dari pihak keluarganya, dengan mengatakan: “Setiap hari yang aku takuti dan aku khawatiri selain hari kiamat, aku tidak terlindung darinya.” Maksudnya: ia tidak takut terhadap reaksi dari Bani Umayyah yang ingin ia ambil harta-harta yang mereka ambil tanpa hak, dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Ia tidak takut kepada mereka sedikitpun. Ia berkata: Hari yang benar-benar aku takuti hanyalah hari kiamat; adapun jika aku takut terhadap hari lain selain hari kiamat, maka aku tidak berhak atas hal itu.
Ia mampu menjaga bagi negara dengan hal tersebut sumber pendapatan penting yang sebelumnya hilang darinya; karena shawafi—sesuai dengan sistem keuangan—membayar kharaj.
Adapun di tangan Bani Umayyah, tanah-tanah itu hanya membayar sepersepuluh saja. Maksudnya: tanah shawafi ini pada dasarnya dikenakan kharaj, tetapi pada masa Bani Umayyah mereka tidak mengenakan kharaj padanya, melainkan hanya membayar sepersepuluh saja.
Inilah yang dicoba oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk dihindari, dan ia berhasil dalam hal itu.
Khalifah juga menunjukkan terhadap masalah-masalah perkembangan keuangan kemampuan yang luar biasa dalam menyelesaikannya, yang membantunya adalah luasnya ilmunya dalam urusan agama dan keprihatinannya untuk menghormati prinsip-prinsip Islam. Yang paling berbahaya dari masalah-masalah tersebut adalah banyaknya masuknya ahli dzimmah di wilayah-wilayah ke dalam agama Islam, yang mengakibatkan sesuai dengan syariat Islam gugurnya jizyah dari mereka, dan berkurangnya sumber pendapatan negara secara besar-besaran. Ini adalah beberapa masalah yang mungkin dipandang sebagai masalah oleh sebagian orang. Sumber pendapatan negara datang dari kharaj dan datang dari jizyah, tetapi jizyah hanya dibebankan kepada non-muslim. Jika seorang non-muslim masuk Islam maka gugur jizyah darinya pada saat itu, dan makna gugurnya jizyah darinya adalah bahwa sumber pendapatan ini yang dulunya menghasilkan uang bagi negara Islam—yaitu jizyah—mungkin berkurang banyak dari keadaan sebelumnya.
Saya katakan ini adalah masalah dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz mampu menyelesaikan penyimpangan ini dengan penyelesaian yang menjaga sistem keuangan beserta pilar-pilarnya; dan prinsip-prinsip Islam beserta kesuciannya pada waktu yang bersamaan.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelajaran 4: Universalitas Zakat secara Moral dan Material
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Orang Perseorangan dalam Zakat
Pengertian Orang Perseorangan dalam Zakat
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada orang yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kami Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Pada perkuliahan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem keuangan pada masa Dinasti Umayyah, dan sekarang kita ingin beralih untuk membahas tentang sumber-sumber keuangan negara Islam dari zakat, jizyah, kharaj… dan seterusnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembahasan kita tentang sumber-sumber ini adalah pembahasan dari sudut pandang ilmu siyasah syar’iyyah (politik syariah), bukan dari sudut pandang fikih murni.
Penjelasannya adalah bahwa Islam menuntut negara Islam untuk mewujudkan kesetaraan di antara warga negara tersebut, dan mewujudkan keadilan di antara mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kesetaraan dan keadilan merupakan prinsip-prinsip umum yang penjelasan penerapannya, dan cara penerapan ini, diserahkan kepada siyasah syar’iyyah yang selalu memperhatikan kondisi waktu dan kondisi tempat.
Berdasarkan hal ini, kita akan membahas sumber-sumber ini berkaitan dengan perwujudan kesetaraan dan keadilan di antara warga negara Islam. Ini mengharuskan kita untuk membahas tentang universalitas dalam zakat dan sumber-sumber keuangan lainnya, kemudian membahas tentang pertimbangan perundang-undangan keuangan terhadap kondisi pembayar pajak, karena pertimbangan terhadap kondisi-kondisi tersebut termasuk dalam perwujudan keadilan dalam masyarakat Muslim.
Sekarang kita mulai dengan yang pertama dari sumber-sumber tersebut, yaitu zakat:
Zakat dalam bahasa diambil dari kata: az-zaka’, an-nama’, az-ziyadah (pertumbuhan, perkembangan, dan pertambahan). Dinamakan demikian karena zakat menyuburkan harta dan mengembangkannya. Dikatakan: zakaz-zar’u (tanaman tumbuh subur) jika hasilnya banyak. Dikatakan: zakatan-nafaqah (nafkah berkah) jika diberkahi. Ini terdapat dalam kitab Al-Mishbah Al-Munir dalam kata: zaka. Jumlah yang dikeluarkan dari harta dinamakan zakat karena ia merupakan sebab yang diharapkan membawa pertumbuhan. Zakat juga berarti: kesucian, karena ia menyucikan jiwa dari kotoran kikir dan pelanggaran, dan menyucikan harta dengan mengeluarkan hak orang lain darinya kepada yang berhak. Inilah definisi zakat dalam bahasa.
Adapun definisi zakat dalam istilah para ahli fikih adalah: pemilikan harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Artinya: mereka yang memiliki nisab zakat diwajibkan untuk memberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari yang berhak menerima zakat, sejumlah tertentu dari harta mereka melalui cara pemilikan. Oleh karena itu, dalam definisi dikatakan: pemilikan harta tertentu. Yang dimaksud dengan kata “kepada yang berhak” dalam definisi adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang disebutkan dalam Al-Quran dalam firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan” (Surah At-Taubah: ayat 60). Inilah delapan golongan tersebut.
Inilah definisinya – seperti yang telah kita katakan – pemilikan harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, artinya: zakat agar wajib atas seorang Muslim maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu, yang disebutkan para ahli fikih secara terperinci dalam kitab-kitab fikih.
Hukum Zakat dan Dalil Hukum Ini:
Zakat merupakan salah satu kaidah dasar Islam, karena ia adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan merupakan kewajiban individu bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya, dan kefarduannya diketahui dalam agama secara dharuri (pasti). Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dalam firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (Surah Al-Baqarah: ayat 43), dan firman-Nya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (Surah At-Taubah: ayat 103), dan firman-Nya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak yang tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Surah Al-Ma’arij: ayat 24-25).
Dalil kewajiban zakat dari Sunnah adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Islam dibangun di atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”
Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma: “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman, dan beliau berkata kepadanya: Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dalam harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.”
Adapun ijma’, kaum muslimin di semua zaman telah berijma’ atas wajibnya zakat, dan para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya. Dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu berkata: “Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan kepadaku seekor kambing muda yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena menolak memberikannya.”
Karena ijma’ ini, para ahli fikih mengatakan: Barangsiapa yang meyakini tidak wajibnya zakat maka ia telah kafir, karena ia mengingkari sesuatu yang diketahui dalam agama secara dharuri (pasti). Adapun orang yang hanya menolak membayarnya dengan tetap beriman akan wajibnya, ia tidak kafir, tetapi ia berdosa, dan diperintahkan untuk menunaikannya. Jika ia menolak, diambil darinya secara paksa walaupun dengan cara perang, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat.
Jika orang yang mengingkari disertai dengan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan dibunuh karena kekufurannya, ini jika ia tidak bertaubat dan menunaikannya, sebagaimana orang murtad dibunuh, karena kewajiban zakat diketahui dalam agama secara dharuri (pasti). Barangsiapa yang mengingkari kewajibnya berarti telah mendustakan Allah Azza wa Jalla dan mendustakan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam, oleh karena itu dihukumi kafir.
Ini dalam zakat yang telah disepakati kewajiban dan pengeluarannya. Adapun zakat yang diperselisihkan seperti zakat perdagangan, rikaz (harta temuan), zakat buah-buahan selain kurma dan anggur, pertanian di tanah kharaj, zakat dalam harta orang yang belum mukallaf, perhiasan wanita, dan harta piutang bagi pemberi utang atau orang yang berutang, maka orang yang mengingkarinya tidak kafir karena para ulama berbeda pendapat tentangnya.
Universalitas dalam Zakat:
Setelah kita mendefinisikan zakat, menjelaskan hukumnya, dan dalil atas hukum ini, kita akan membahas tentang universalitas dalam zakat:
Sesungguhnya universalitas dalam zakat berarti: bahwa zakat ditunaikan oleh semua orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dibebaskan dari menunaikannya tanpa alasan yang membenarkan. Universalitas ini juga berarti: bahwa zakat diwajibkan atas semua harta ketika terpenuhi padanya syarat-syarat wajib zakat. Artinya: universalitas dalam zakat menggabungkan antara aspek personal dan material, ia bersifat personal dalam melacak individu di mana pun ia berada, dan bersifat material dalam kewajiban atas harta apa pun jenisnya.
Oleh karena itu, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang universalitas personal dalam zakat:
Sesungguhnya universalitas personal dalam zakat berarti – sebagaimana telah kita katakan -: bahwa zakat diwajibkan atas semua orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dibebaskan dari menunaikannya tanpa adanya alasan yang membenarkan pembebasan ini. Orang yang dibebani kewajiban menunaikan zakat dalam hal terpenuhi syarat-syarat wajibnya mungkin merupakan orang perseorangan (pribadi), dan mungkin merupakan badan hukum, dan kita akan menjelaskan hal itu.
Berkenaan dengan orang perseorangan, kita katakan: Perundang-undangan Islam mewajibkan atas orang-orang yang mampu – secara finansial – untuk berkontribusi dalam menanggung sebagian beban keuangan publik yang ditetapkan dalam negara, melalui kewajiban zakat atas setiap Muslim yang memiliki nisab zakat, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, usia, atau kelas sosialnya. Laki-laki dan perempuan, putih dan hitam, bangsawan dan lemah, penguasa dan yang dikuasai, semuanya sama di hadapan kewajiban ini. Hal ini terdapat dalam kitab Fiqhuz-Zakah, Studi Perbandingan tentang Hukum-hukumnya dan Falsafahnya dalam Cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, Jilid Kedua halaman 1039 dan seterusnya, karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Cetakan Keenam, 1981.
Berkaitan dengan hal ini, kita dapati bahwa para ahli fikih telah sepakat bahwa zakat wajib atas setiap Muslim yang merdeka, baligh, berakal, memiliki nisab dengan kepemilikan sempurna, yaitu setelah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkan zakat atas hartanya. Sementara mereka berbeda pendapat mengenai orang murtad, anak kecil, dan orang gila. Jika para ahli fikih telah berijma’ atas wajibnya zakat atas Muslim, maka mereka juga berijma’ atas tidak wajibnya zakat atas orang kafir asli, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi. Ia tidak dituntut untuk membayarnya – sebagaimana dikatakan Asy-Syafi’i – dalam kekufurannya, dan jika ia masuk Islam, ia tidak dituntut untuk membayarnya selama masa kekufuran, karena zakat adalah cabang dari Islam, dan Islam tidak ada padanya, maka ia tidak dituntut untuk membayarnya ketika ia masih kafir, sebagaimana zakat tidak menjadi utang dalam tanggungannya yang harus ia tunaikan jika ia masuk Islam.
Para ulama berdalil atas tidak wajibnya zakat atas orang kafir dengan dalil-dalil yang di antaranya: Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau ajak kepada mereka adalah kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam setiap hari dan malam. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat), yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.”
Hadits ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk menunaikan kewajiban di dunia tidak terjadi kecuali setelah masuk Islam. Maka Islam adalah syarat untuk wajibnya zakat, dan ini merupakan hal yang disepakati.
LIHAT dalam hal ini kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Jilid Kedua halaman 437 dan seterusnya.
Di antara dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa zakat tidak wajib atas orang kafir adalah: bahwa zakat merupakan ibadah, sedangkan orang kafir bukan termasuk ahli ibadah; karena tidak terpenuhinya syarat kelayakan yaitu Islam. Selain itu, zakat adalah salah satu rukun Islam, maka tidak wajib atas orang kafir sebagaimana salat dan puasa. Sebagaimana salat tidak wajib atasnya dan puasa tidak wajib atasnya, maka tidak wajib pula zakat atasnya; karena zakat adalah rukun, sebagaimana puasa adalah rukun dari rukun Islam.
Yang menunjukkan hal itu juga adalah perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam kitab sedekah: “Ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam atas kaum muslimin” dan ini terdapat dalam (Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj) karya Ar-Ramli Asy-Syafi’i juz ketiga halaman 125 dan seterusnya.
Ini berkenaan dengan orang kafir, dan telah jelas bagi kita dengan dalil-dalil bahwa para fuqaha sepakat tentang tidak sahnya zakat dari orang kafir.
Hukum Berkenaan dengan Orang Murtad:
Sekarang kita membicarakan tentang orang murtad, apa hukumnya berkenaan dengan orang murtad?
Orang murtad, para fuqaha berbeda pendapat tentangnya dari dua sisi: Pertama: apa yang telah ditetapkan sebelum kemurtadannya, dan Kedua: apa yang ditetapkan atasnya setelah kemurtadannya, yaitu: dalam keadaan murtadnya.
Adapun sisi pertama -yaitu zakat yang telah ditetapkan atasnya sebelum kemurtadannya-: Mazhab Hanafi berpendapat gugurnya apa yang telah ditetapkan atasnya sebelum kemurtadannya, berdasarkan prinsip dasar menurut mereka: bahwa orang murtad menjadi seperti orang kafir asli, dan ini disebutkan dalam (Hasyiyah Ibnu ‘Abidin Al-Hanafi) juz kedua halaman 5 dan seterusnya.
Mazhab Syafi’i berkata: Sesungguhnya zakat yang telah ditetapkan atas orang murtad sebelum kemurtadannya tidak gugur karena murtad; karena kewajiban itu telah ditetapkan, maka tidak gugur dengan kemurtadannya sebagaimana ganti rugi atas barang yang dirusak, dan ini terdapat dalam (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab) karya An-Nawawi juz kelima halaman 295 dan seterusnya. Pendapat mazhab Syafi’i inilah yang dipilih; karena zakat di sini bukan diambil dari orang kafir, tetapi dari seorang muslim, karena zakat itu telah wajib atasnya, hanya saja sebelum menunaikannya ia murtad, maka tetap berkaitan dengan tanggungannya sebagai utang atasnya hingga diambil darinya.
Kami berpendapat bahwa apa yang dikemukakan mazhab Syafi’i adalah yang lebih kuat; karena mewujudkan kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban zakat, dan agar orang murtad tidak diuntungkan dari kemurtadannya dengan gugurnya zakat darinya, sehingga ia terlepas dari beban kewajiban umum yang seharusnya disetarakan kepada semua orang, selama syarat-syarat yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.
Adapun sisi kedua -yaitu zakat yang ditetapkan atasnya dalam keadaan murtadnya-: maka apa yang ditetapkan atasnya dalam keadaan murtadnya, sebagian mazhab Syafi’i dan sebagian mazhab Hanbali berpendapat: wajib zakat padanya dengan qiyas kepada nafkah dan ganti rugi; dan karena ia adalah hak yang ia ikrarkan dengan Islam, maka tidak gugur dengan murtad sebagaimana hak-hak manusia; dan karena zakat adalah hak harta, maka tidak gugur dengan murtad, dan imam mengambilnya dari harta orang murtad, sebagaimana mengambilnya dari muslim yang menolak secara paksa. Jika ia masuk Islam setelah menunaikannya, tidak wajib atasnya menunaikannya lagi; karena telah gugur darinya dengan pengambilannya, sebagaimana gugur dengan pengambilannya dari muslim yang menolak.
Kami memilih pendapat ini karena; mewujudkan kesetaraan dalam menunaikan zakat antara warga negara, dan agar orang murtad tidak diuntungkan -sebagaimana kami katakan- dari kemurtadannya dengan gugurnya zakat darinya, sehingga terwujud keumuman personal dalam zakat.
Sikap Para Fuqaha Berkenaan dengan Zakat pada Harta Anak Kecil dan Orang Gila
Adapun berkenaan dengan zakat pada harta anak kecil dan orang gila:
Kami katakan: Jika para ulama telah bersepakat tentang kewajiban zakat pada harta muslim yang baligh berakal; maka mereka telah berbeda pendapat dalam harta anak kecil dan orang gila, apakah wajib zakat padanya? Ataukah tidak wajib hingga anak kecil itu baligh dan orang gila itu berakal? Di sini para fuqaha berbeda pendapat dengan perbedaan yang besar, kita dapat mengembalikan mereka kepada dua kelompok utama:
Kelompok pertama: berpendapat tidak wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, baik secara mutlak maupun pada sebagian harta.
Kelompok kedua: berpendapat wajib zakat pada semua harta keduanya.
Kami akan menjelaskan pendapat kedua kelompok, kemudian menerangkan pendapat yang lebih kuat sebagai berikut:
Pertama: Yang berpendapat tidak wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila baik secara mutlak maupun pada sebagian harta, mereka berkata: Tidak ada zakat pada harta keduanya, lihat dalam hal itu (Al-Muhalla) karya Ibnu Hazm juz kelima halaman 303 dan seterusnya, cetakan 1968.
Mazhab Hanafi berpendapat: tidak ada zakat pada harta keduanya kecuali pada tanaman dan buah-buahan, maka wajib zakat padanya. Mereka yang berpendapat demikian berdalil atas apa yang mereka kemukakan bahwa tidak diambil zakat dari harta anak kecil dan orang gila dengan hal-hal berikut: Firman Allah Ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya” (Surah At-Taubah: sebagian dari ayat 103).
Dalil dari ayat: bahwa penyucian hanya dari kotoran dosa, dan tidak ada dosa atas anak kecil dan orang gila hingga memerlukan pembersihan dan penyucian, maka keduanya keluar dari orang-orang yang diambil zakat dari mereka, lihat dalam hal itu Dr. Yusuf Al-Qaradhawi (Fiqhuz Zakah) juz pertama halaman 107 dan seterusnya.
Di antara dalil mereka juga adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Diangkat pena dari tiga orang: dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia sadar.”
Dalil dari hadits: bahwa pengangkatan pena adalah kiasan dari pengangkatan taklif (beban kewajiban), maka keduanya tidak dibebani dengan zakat.
Dari qiyas: mereka berdalil dengan perkataan mereka: Sesungguhnya zakat adalah ibadah murni seperti salat, dan ibadah memerlukan niat, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak dapat melakukan niat, maka tidak wajib zakat atas keduanya, sebagaimana tidak wajib salat atas keduanya. Mereka juga berkata: Sesungguhnya kemaslahatan menghendaki tidak wajibnya zakat pada harta anak kecil. Mereka berkata: Sesungguhnya kemaslahatan keduanya menghendaki agar harta keduanya tetap terjaga, dan tidak diwajibkan zakat padanya; karena hal itu menyebabkan habisnya harta; karena ketidakmampuan keduanya untuk menumbuhkan harta keduanya, sedangkan pertumbuhan adalah ‘illah (alasan hukum) wajibnya zakat, dan kewajiban zakat pada harta keduanya menyebabkan keduanya terpapar pada kehinaan kebutuhan dan kerendahan kefakiran, lihat dalam hal itu Dr. Al-Qaradhawi (Fiqhuz Zakah) juz pertama halaman 107 dan seterusnya, dan (Hasyiyah Ibnu ‘Abidin) Al-Hanafi juz kedua halaman 4 dan seterusnya.
Ini adalah dalil-dalil pemilik pendapat pertama yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta anak kecil dan orang gila.
Jika kita kembali kepada pendapat lain yang berseberangan yaitu pendapat jumhur fuqaha yang berpendapat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila; maka kami katakan: Yang berpendapat wajib zakat pada seluruh harta anak kecil dan orang gila adalah ketiga Imam: Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad, dan ini pendapat Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, Abdullah bin Umar, Ali, Aisyah, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhum ajma’in (semoga Allah meridhai mereka semua), lihat dalam hal itu (Al-Mughni) karya Ibnu Qudamah juz kedua halaman 493 dan seterusnya.
Mereka yang berpendapat demikian berdalil atas apa yang mereka kemukakan dengan hal-hal berikut: Keumuman nash-nash yang menunjukkan wajibnya zakat pada harta orang-orang kaya secara mutlak tanpa pengecualian bagi anak kecil dan orang gila; seperti firman Allah Ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka” (Surah At-Taubah: sebagian dari ayat 103), maka ayat di sini datang secara umum, tidak membedakan antara yang diambil hartanya apakah anak kecil, atau orang gila, atau orang berakal, atau orang baligh; oleh karena itu ayat dengan keumumannya mencakup anak kecil dan orang gila, dan selama ia menuntut muslim untuk mengeluarkan zakat maka ia berlaku juga pada anak kecil dan orang gila. Dan seperti sabdanya shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Mu’adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka”, maka kalimat: “diambil dari orang-orang kaya mereka” datang secara umum, tidak membedakan antara orang kaya ini apakah baligh berakal, dan antara apakah anak kecil atau orang gila.
Maka dengan demikian: Hadits ini menunjukkan bahwa zakat wajib pada harta anak kecil, karena keumuman yang disebutkan dalam hadits.
Maka ayat -sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm- adalah umum untuk setiap orang kecil, dan besar, dan berakal, dan gila; karena mereka semua memerlukan kesucian Allah Ta’ala bagi mereka, dan penyucian-Nya kepada mereka, dan mereka semua termasuk orang-orang yang beriman.
Dan ia berkata dalam hadits: maka ini umum untuk setiap orang kaya dari kaum muslimin, dan ini mencakup anak kecil, dan orang besar, dan orang gila, jika mereka adalah orang kaya, lihat dalam hal itu (Al-Muhalla) karya Ibnu Hazm juz kelima halaman 298 dan seterusnya.
Dan di antaranya juga hadits khusus yang disebutkan dalam perintah menzakati harta anak yatim, maka telah diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perdagangkanlah harta anak yatim atau harta anak-anak yatim, jangan sampai habis atau jangan sampai dihabiskan oleh sedekah”. Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Perdagangkanlah harta anak-anak yatim, jangan sampai dimakan oleh sedekah.”
Dalil dari hadits: bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk bekerja menumbuhkan harta anak-anak yatim, dan demikian juga orang-orang gila dengan perniagaan dan mencari keuntungan, dan memperingatkan dari meninggalkannya tanpa penumbuhan, sehingga dimakan oleh sedekah-sedekah. Tidak diragukan bahwa sedekah hanya memakannya karena pengeluarannya, dan pengeluarannya tidak boleh kecuali jika wajib, karena tidak boleh bagi wali untuk bersedekah dengan harta anak kecil pada yang bukan wajib.
Maka kedua hadits ini menunjukkan dengan demikian wajibnya zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Di antara dalil-dalil juga yang dijadikan dalil oleh yang berpendapat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila: apa yang shahih dari para sahabat tentang pendapat wajib zakat pada harta anak yatim dan orang gila, maka telah shahih hal itu dari Umar, dan Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu ‘anha, dan Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhum ajma’in (semoga Allah meridhai mereka semua)- dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka kecuali beberapa riwayat yang tidak dapat dijadikan hujjah, lihat dalam hal itu (Al-Muhalla) karya Ibnu Hazm juz kelima halaman 302 dan seterusnya.
Mereka juga berdalil dengan qiyas maka berkata: Sesungguhnya setiap orang yang wajib usyur pada tanamannya maka wajib zakat pada seluruh hartanya seperti orang baligh berakal, maka sesungguhnya Abu Hanifah sepakat dengan kami tentang kewajiban usyur pada harta anak kecil dan orang gila, jika berupa tanaman dan buah-buahan, dan kewajiban zakat fitrah pada harta keduanya, dan jika telah ditetapkan kewajiban hal itu pada harta keduanya maka demikian juga wajib zakat pada seluruh harta keduanya; yaitu: bahwa pemilik pendapat ini -yaitu jumhur fuqaha yang berpendapat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila- mereka mengqiyaskan kepada apa yang dikatakan Abu Hanifah bahwa: zakat tidak wajib atas anak kecil kecuali pada tanaman dan buah-buahan yang dimiliki oleh mereka, maka mereka berkata atau jumhur fuqaha berkata: Kami mengqiyaskan kepada tanaman dan buah-buahan, maka sebagaimana zakat wajib pada tanaman dan buah-buahan anak kecil dan orang gila, wajib juga zakat pada harta-harta lainnya dengan jami’ bahwa ini semua adalah harta yang dimiliki oleh anak kecil.
Yang dipegangi oleh jumhur adalah tujuan yang demi tujuan itu zakat disyariatkan, mereka berkata: Sesungguhnya zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, dan meringankan orang fakir, yaitu: bahwa tujuannya adalah: meringankan orang fakir, dan pahala yang didapat bagi orang yang berzakat, dan anak kecil serta orang gila termasuk ahli pahala, dan juga termasuk ahli keringanan; oleh karena itu wajib atas keduanya nafkah kerabat, dan dibebaskan atas keduanya ayah jika keduanya memilikinya maka wajib zakat pada harta keduanya. Ini juga jenis qiyas, yaitu: bahwa sebagaimana wajib atas keduanya nafkah kerabat maka demikian juga -dan nafkah kerabat adalah meringankan- wajib atas mereka zakat; karena zakat juga meringankan orang-orang fakir.
Mereka juga berkata: Sesungguhnya maksud zakat adalah menutup kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya; sebagai syukur kepada Allah Ta’ala, dan pembersihan harta, dan harta anak kecil dan orang gila dapat untuk menunaikan nafkah dan ganti rugi, maka tidak sempit dari zakat, artinya: selama tujuan dari zakat adalah menutup kebutuhan orang-orang fakir dan yang memerlukan, dan berdiri di samping mereka dari harta orang-orang kaya, maka hal ini berserikat di dalamnya anak kecil dan bukan anak kecil, dan orang gila dan bukan orang gila; oleh karena itu wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila.
Pemilik pendapat kedua -yaitu jumhur fuqaha yang berpendapat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila- tidak cukup dengan dalil-dalil ini yang mereka kemukakan dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan apa yang mereka kemukakan; bahkan mereka juga menjawab dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh pemilik pendapat pertama yang berpendapat tidak wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila.
Adapun berkenaan dengan ayat yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya” (Surah At-Taubah: sebagian dari ayat 103) yang dijadikan dalil oleh pemilik pendapat pertama yang berpendapat tidak wajib zakat atas anak kecil dan orang gila, maka mereka berkata: Sesungguhnya penyucian bukan khusus untuk menghilangkan dosa tetapi mencakup pembinaan akhlak, dan penumbuhan jiwa pada keutamaan-keutamaan, dan pelatihannya pada pertolongan dan kasih sayang, sebagaimana mencakup penyucian harta juga.
Maka dengan demikian: Ayat ini adalah umum, bukan terbatas pada penyucian dari dosa, sebagaimana dikatakan oleh pemilik pendapat pertama, tetapi adalah makna yang luas juga, mencakup penyucian dosa, dan mencakup juga penyucian, atau pembinaan akhlak, dan penumbuhan jiwa pada keutamaan-keutamaan, dan pelatihannya pada pertolongan dan kasih sayang, ini masuk di dalamnya anak kecil, oleh karena itu ayat tidak menunjukkan bagi pemilik pendapat pertama atas apa yang mereka kemukakan tentang tidak wajib zakat atas anak kecil dan orang gila.
Mengenai hadits dan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Diangkat pena dari tiga orang” dan beliau menyebutkan di antaranya: “Anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sadar”, maka para ulama pendapat kedua – yaitu jumhur fuqaha – telah menjawabnya bahwa yang dimaksud adalah: diangkat dosa dan kewajiban, dan kami mengatakan: tidak ada dosa atas keduanya, dan tidak wajib zakat atas keduanya, namun wajib zakat pada harta mereka, dan wali mereka diperintahkan untuk mengeluarkannya, sebagaimana wajib pada harta mereka nilai dari apa yang mereka rusak, dan wajib atas wali untuk membayarnya.
Mereka juga mengenai hadits ini – yaitu: “Diangkat pena” – jumhur mengatakan: bahwa makna hadits adalah tidak ada dosa atasnya, dan tidak ada kewajiban atasnya, kami katakan: ya benar, namun kewajiban itu berkaitan dengan harta, dan kewajiban ketika berkaitan dengan harta maka sama saja antara anak kecil dan yang bukan anak kecil, orang gila dan yang bukan orang gila, dan mereka mengqiyaskan hal tersebut kepada hal-hal yang dirusak oleh anak kecil milik orang lain, jika anak kecil merusak harta orang lain dalam kondisi ini kami katakan: ia bertanggung jawab, dan wali harus membayar nilai kerusakan tersebut dari harta anak kecil, maka di sini kewajiban itu mengarah kepada harta, dan kewajiban itu berkaitan dengan zakat, dan ini sama – sebagaimana kami katakan – antara yang baligh dan yang tidak baligh, yang berakal, dan orang gila.
Dan mereka menjawab qiyas mereka: zakat terhadap shalat, dengan kesamaan bahwa semuanya adalah ibadah, mereka mengatakan: kami tidak mengingkari bahwa ia adalah ibadah – yaitu zakat – namun ia adalah ibadah yang dibedakan dengan karakter keuangan sosialnya, maka ia adalah ibadah harta, berlaku di dalamnya perwakilan sehingga dapat terlaksana dengan pelaksanaan wakil, bahkan jika wakil tersebut adalah dzimmi (non-Muslim yang dilindungi) – sebagaimana yang dikatakan Hanafiyah – meskipun ia bukan termasuk ahli ibadah; karena mereka mengatakan: sesungguhnya qiyas zakat terhadap shalat adalah qiyas yang ada perbedaannya; karena shalat adalah ibadah badaniyah murni, tidak sah kecuali dari Muslim, dan dari pelakunya sendiri.
Adapun zakat maka ia juga selain merupakan ibadah badaniyah, ia juga ibadah harta, menggabungkan antara ibadah dan keuangan; oleh karena itu ia dibedakan dengan karakter keuangan sosialnya, maka sebagaimana kami katakan ia: ibadah harta yang berlaku di dalamnya perwakilan, namun shalat tidak berlaku di dalamnya perwakilan; oleh karena itu qiyas zakat terhadap shalat adalah qiyas yang ada perbedaannya, dan oleh karena itu tidak sah berdalil dengan itu; maka zakat dengan ini berbeda dengan shalat dan puasa, karena keduanya adalah ibadah yang khusus dengan badan, sedangkan zakat adalah hak yang berkaitan dengan pemilik, maka menyerupai nafkah kerabat, dan istri, dan diyat jinayat (tebusan tindak pidana), dan nilai kerusakan.
Dan mengenai persyaratan niat untuk sahnya pengeluaran zakat, Ibnu Hazm berkata: ya, dan hanya diperintahkan pengambilannya oleh imam dan kaum muslimin; karena firman Allah Ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya” (Surah At-Taubah: 103), maka jika yang diperintahkan untuk mengambilnya mengambilnya dengan niat bahwa itu adalah sedekah maka mencukupi bagi orang yang tidak hadir, orang yang pingsan, orang gila, anak kecil, dan orang yang tidak punya niat, lihat dalam hal itu (Al-Muhalla) karya Ibnu Hazm Jilid Kelima halaman 305 dan seterusnya.
Maka seolah-olah Ibnu Hazm mengatakan di sini: tidak wajib niat dari anak kecil dan orang gila agar sah darinya zakat; tetapi kami katakan: niat itu ada jika imam mengambil zakat ini dari anak kecil atau orang gila; karena imam dan yang ia wakili sesungguhnya dituntut untuk mengambil zakat ini dalam firman Allah Ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka” (Surah At-Taubah: 103). Dan dalam mendukung pendapat yang mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila, para ulama halaqah studi sosial negara-negara Arab mengatakan dalam buku sesi ketiga Damaskus 1952 halaman 237 Liga Negara-Negara Arab, Sekretariat Umum, Departemen Urusan Sosial percetakan Mesir 1955 penelitian berjudul: “Zakat dan Wakaf” oleh Syekh Abdurrahman Hasan, dan Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Syekh Abdul Wahhab Khallaf: Sesungguhnya zakat adalah hak harta, dan ia adalah taklif (pembebanan) sosial sebabnya adalah kepemilikan harta, tidak ada perbedaan dalam hal itu antara baligh berakal dan lainnya, seperti halnya dalam setiap taklif sosial, sebagaimana kita lihat dalam nafkah kerabat, karena ia wajib pada harta mukallaf dan bukan mukallaf, untuk kerabatnya yang membutuhkan yang tidak mampu bekerja, dan ketika ia adalah hak harta maka ia diambil darinya siapa pun pemiliknya, seperti hukuman pidana harta dalam Islam, dan seperti nilai kerusakan, dan semua ini diambil dari harta mukallaf, dan bukan mukallaf secara taklif agama, lihat dalam hal itu (Halaqah Studi Sosial Negara-Negara Arab) yang kami sebutkan sebelumnya.
Dan telah merekomendasikan konferensi kedua Majma’ Buhuts Islamiyah (Lembaga Penelitian Islam) dalam halaman 402, 403 tahun 1965 bahwa wajib zakat atas mukallaf pada hartanya, dan wajib juga pada harta bukan mukallaf, dan menunaikannya dari hartanya adalah orang yang memiliki perwalian atas harta ini.
Dan pendapat yang rajih (kuat) dari dalil-dalil yang kami sebutkan untuk dua kelompok, dan diskusi yang muncul pada sebagian dalil-dalil ini, dan apa yang kami nukil dari para ulama halaqah studi sosial, dan Majma’ Buhuts Islamiyah menjadi jelas bagi kita: Sesungguhnya apa yang dituju oleh jumhur fuqaha tentang kewajiban zakat pada semua harta anak kecil dan orang gila adalah pendapat yang rajih; dan itu karena hal-hal berikut:
- Karena kuatnya dalil-dalilnya, dan bantahan dalil-dalil kelompok lain, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.
- Bahwa kemampuan mukallaf untuk menunaikan zakat tidak terpengaruh dengan dirinya anak kecil, atau baligh, gila, atau berakal, dan bahwa tidak adanya akal atau tidak adanya baligh tidak menyentuh kemampuan zakat mukallaf, dan posisi keuangannya, sebagaimana penghapusan zakat pada harta anak kecil dan orang gila di dalamnya terdapat pelanggaran nyata terhadap prinsip umum personal dalam zakat; karena tidak menundukkan anak kecil dan orang gila untuk zakat, hal yang menyebabkan hilangnya kesetaraan antara kaum muslimin dalam memikul taklif umum harta; yang termasuk yang terpenting adalah zakat, dan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam atas kaum muslimin.
- Juga: bahwa anak kecil dan orang gila mendapat manfaat dari manfaat umum yang diberikan negara kepada warga negara, maka keduanya menikmati pemanfaatan fasilitas umum di negara Islam dari transportasi, air, listrik, dan lain-lain, seperti warga negara lainnya yang berkewajiban menunaikan zakat dari harta mereka.
- Dan juga: sesungguhnya keduanya menikmati perlindungan yang disediakan negara untuk warga negara, baik perlindungannya dari serangan eksternal atau internal; agar keduanya aman di tempat yang mereka tinggali, atau perlindungan harta mereka dari pencuri, dan perampok jalan, dan sesuai dengan kaidah keuntungan dengan tanggung jawab: maka wajib yang dituntut oleh keadilan bahwa keduanya – yaitu: anak kecil dan orang gila – sama dengan warga negara lainnya dalam memikul taklif umum harta dengan mengeluarkan zakat dari harta mereka; dan dengan demikian terwujud kesetaraan antara warga negara dalam memikul beban umum harta, dan yang termasuk yang terpenting adalah zakat yang ditetapkan di negara Islam.
Dan kami simpulkan dari apa yang telah disebutkan bahwa: Mukallaf yang menunaikan zakat dari orang-orang alami adalah: semua kaum muslimin yang memiliki harta yang terpenuhi padanya syarat-syarat kewajiban zakat, tanpa melihat kepada jenis kelamin orang yang wajib atasnya, atau warnanya, atau nasabnya, atau kelas sosialnya, maka laki-laki dan perempuan, dan kecil dan besar, dan berakal dan gila, dan orang terhormat dan rendah, dan penguasa dan yang dikuasai di hadapan taklif menunaikan zakat sama saja, apa pun tempat yang mereka tinggali. Maka zakat wajib atas Muslim, apa pun tempat tinggalnya, meskipun ia tinggal di negara non-Islam maka dalam kondisi ini wajib atasnya mengirimkan zakat yang wajib atasnya ke negara Islamnya; jika ia tidak mampu maka menjadi hutang dalam tanggungannya sampai ia kembali ke negara Muslimnya, dan dengan ini terwujud kesetaraan penuh antara kaum muslimin dalam memikul beban zakat.
Dan semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya tercurah atas kalian.
2 – Orang Hukum dalam Zakat
Khulthoh (Percampuran) dalam Ternak sebagai Contoh Orang Hukum dalam Zakat
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam Sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan kepada keluarganya, dan para sahabatnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan, amma ba’du:
Maka kami telah berbicara dalam kuliah sebelumnya tentang umum personal berkaitan dengan orang alami dalam zakat dan kami telah berbicara tentang zakat berkaitan dengan kafir dan murtad dan kami sebutkan pendapat para fuqaha dan dalil-dalil mereka berkaitan dengan zakat pada harta anak kecil dan orang gila dan menjadi jelas bagi kita kuatnya pendapat yang mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila.
Dan kita berbicara sekarang tentang umum personal berkaitan dengan orang hukum, maka kami katakan:
Untuk mengetahui keberadaan orang-orang hukum – sebagai jenis kedua mukallaf zakat di samping orang-orang alami – tidak boleh tidak dari penelitian tentang posisi para fuqaha berkaitan dengan pengaruh khultah dalam zakat ternak, bahwa pada awalnya bermanfaat kami isyaratkan di sini bahwa khultah dalam ternak ada dua jenis:
Jenis pertama: khultah syarikah (percampuran kepemilikan bersama), dan mungkin dinyatakan dengan khultah a’yan (percampuran benda), dan khultah syuyu’ (percampuran tak terbagi), dan ia berarti: tidak dibedakan bagian salah satu pemilik atau para pemilik dari bagian yang lain, seperti ternak yang diwarisi sekelompok orang, atau mereka beli maka ia bersama di antara mereka, dan mereka berserikat padanya, tidak ada bagi salah satu dari mereka jumlah yang dibedakan.
Jenis kedua: dari khultah dalam ternak adalah khultah jiwar (percampuran bertetangga) – dari jiwar (bertetangga) – dan mungkin dinyatakan dengan khultah ausaf (percampuran sifat-sifat), dan ia berarti: bahwa harta setiap satu dari para pemilik atau para pemilik tertentu dibedakan dari harta yang lain, seperti seorang pemilik memiliki enam puluh kambing yang diketahui dibedakan, dan yang lain sepertinya, atau kurang, atau lebih, diketahui dibedakan juga, namun semuanya bertetangga bercampur seperti harta satu, dan lihat dalam perincian itu dalam kitab (Al-Amwal) karya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam edisi 1975 yang ditahqiq penerbit Dar Al-Fikr Al-Arabi halaman 491 dan seterusnya, dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam (Fiqh Az-Zakah) Jilid Pertama halaman 217 dan seterusnya, dan juga (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab) karya An-Nawawi Jilid Kelima halaman 406 dan seterusnya.
Dan perlu disebutkan bahwa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam khultah; agar ada pengaruhnya dalam zakat, sebagian syarat-syarat ini bersama antara dua khultah bersama – yaitu: khultah syarikah dan khultah jiwar – dan sebagian yang lain khusus dengan khultah jiwar.
Maka berkaitan dengan syarat-syarat bersama antara dua khultah maka ia terwujud dalam syarat-syarat berikut:
- Bahwa orang yang bercampur atau para khulatha’ (orang bercampur) dari ahli zakat yaitu: yang wajib atas mereka zakat.
- Bahwa harta yang bercampur adalah nishab.
- Berlangsung khultah selama satu tahun penuh, artinya: jika kita ingin berbicara tentang pengaruh khultah berkaitan dengan zakat tidak boleh tidak dari terpenuhinya syarat-syarat ini pertama.
Dan berkaitan dengan syarat-syarat khusus khultah jiwar maka ia terwujud dalam syarat-syarat berikut:
- Bersatunya murahi yaitu: tempat yang bermalam di dalamnya pada malam hari kambing misalnya, atau sapi misalnya, bahwa tempat ini bersatu artinya: bermalam di dalamnya kambing ini, dan kambing ini.
- Bersatunya tempat minum, dengan disiraminya kambing dari air satu, dan juga bersatunya masrah yaitu: tempat yang berkumpul di dalamnya, kemudian digiring ke tempat penggembalaan, dan juga bersatunya tempat penggembalaan yaitu: tempat merumput yang merumput di dalamnya.
Syarat-syarat ini tidak boleh tidak ada sampai kita berbicara tentang pengaruh khultah ini dalam zakat dari tidak adanya; maka jika tidak ada syarat-syarat ini atau tidak ada syarat darinya maka tidak ada dalam kondisi ini urusan khultah, dan tidak ada urusan sesuatu darinya.
Syarat-Syarat Yang Diperdebatkan
Di antara syarat-syarat yang diperdebatkan adalah:
Bersatunya pengembala, yaitu: tidak ada pengkhususan salah satu dari mereka dengan seorang pengembala, artinya: pengembalanya harus satu orang yang menggembalakan kambing ini dan kambing itu.
Dan juga: bersatunya pejantan, yaitu: bahwa pejantan-pejantan dilepas di ternak mereka berdua, tidak ada salah satu dari mereka yang dikhususkan dengan pejantan tertentu.
Dan juga: bersatunya tempat di mana ternak diperah, dan ini adalah syarat seperti bersatunya kandang.
Dan juga: bersatunya pemerah, yaitu orang yang melakukan pemerahan ternak, artinya: tidak ada salah satu dari mereka yang menyendiri dengan pemerah yang mencegah pemerahan ternak yang lain.
Dan juga: bersatunya bejana yang digunakan untuk memerah, yaitu: bahwa wadah-wadah pemerahan adalah milik bersama di antara mereka, maka tidak ada salah satu dari mereka yang menyendiri dengan wadah pemerahan atau wadah-wadah pemerahan yang mencegah dari yang lain.
Kemudian setelah itu tersedianya niat percampuran pada kedua pihak yang bercampur atau para mitra.
Jadi: ada syarat-syarat yang disepakati, dan ada syarat-syarat yang diperdebatkan.
Artinya: sebagian ulama mengatakan dengannya, atau mengatakan bahwa itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan sebagian mengatakan tidak wajib memenuhinya.
Sikap Para Ulama Fikih Tentang Pengaruh Percampuran Dalam Zakat
Kita menuju kepada para ulama fikih, dan mengetahui sikap para ulama fikih berkenaan dengan pengaruh percampuran ini dalam zakat:
Jika kita memberikan contoh untuk ini: kita asumsikan bahwa seseorang memiliki dua puluh ekor kambing, dan orang lain memiliki dua puluh ekor kambing, kemudian terjadi antara mereka percampuran bertetangga -misalnya- dan ada seorang pengembala untuk mereka, maka jumlah kambing-kambing ini adalah: empat puluh, dan kita mengetahui bahwa nishab kambing dimulai dari empat puluh, maka dalam kondisi ini: apakah wajib zakat pada kambing-kambing ini? dengan pertimbangan bahwa kita mengumpulkan bagian salah satu dari mereka kepada yang lain dan dengan demikian kita memandang kepada harta secara keseluruhan atau kepada percampuran secara menyeluruh? Maka dalam kondisi ini kita mengatakan: wajib zakat; ataukah kita tidak memandang kepada itu? Dan bahwa setiap pemilik pada kepemilikannya dan dengan demikian tidak wajib zakat?
Jika kita memandang kepada mereka berdua tanpa percampuran maka pemilik dua puluh tidak wajib atasnya zakat, dan yang lain tidak wajib atasnya zakat, mengapa? Karena masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab; karena nishab kambing yang wajib padanya zakat adalah mencapai empat puluh ekor kambing ke atas, dan setiap satu dari mereka secara terpisah, tidak mencapai nishab ini.
Maka jika kita mengatakan: ada pengaruh bagi percampuran, dalam kondisi ini wajib atas mereka mengeluarkan zakat; karena kita akan mengumpulkan dua puluh dengan dua puluh yang lain, dan dengan demikian terjadi pada kita nishab, dan di sana wajib zakat.
Dan berdasarkan itu maka mereka yang mengatakan bahwa bagi percampuran ada pengaruh dalam zakat mengatakan: wajib atas dua pemilik ini mengeluarkan zakat; karena berkumpulnya harta mereka mendapatkan nishab.
Adapun mereka yang mengatakan bahwa: tidak ada pengaruh bagi percampuran dalam zakat, mengatakan bahwa: tidak ada zakat atas satu pun dari mereka; karena harta setiap satu dari mereka tidak mencapai nishab zakat.
Ini gambaran umum tentang topik percampuran pada ternak agar menjadi jelas; karena hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari membayangkannya, dan contoh adalah sebagai penggambaran topik.
Sikap Para Ulama Fikih Seputar Pengaruh Percampuran Dalam Zakat
Ada beberapa sikap para ulama fikih seputar masalah ini, yaitu sebagai berikut:
1 – Sikap mereka tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran.
2 – Sikap mereka tentang jenis-jenis percampuran yang memiliki pengaruh, dan ini berdasarkan pendapat tentang tetapnya pengaruh ini.
3 – Sikap mereka tentang tempat yang dipengaruhi percampuran berdasarkan pendapat tentang tetapnya pengaruh ini juga; apakah kadar yang wajib saja? Ataukah kadar yang wajib dan nishab bersama-sama.
4 – Sikap mereka tentang jenis-jenis harta yang dipengaruhi percampuran berdasarkan pendapat tentang tetapnya pengaruh ini juga; apakah ada pengaruhnya pada semua jenis harta? Ataukah pada ternak saja?
Ini adalah bentuk-bentuk tertentu yang diperdebatkan oleh para ulama fikih, kita akan melihat -insya Allah- dan mencoba menjelaskan sikap para ulama fikih dalam bentuk-bentuk ini:
Pertama: Sikap para ulama fikih tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran:
Para ulama fikih berselisih seputar masalah ini menjadi dua pendapat:
Pendapat pertama mengatakan: Bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam zakat dengan makna: bahwa ia menjadikan harta dua orang atau lebih seperti harta satu orang dalam zakat, dan ini adalah madzhab jumhur: Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad bin Hanbal. Maka berdasarkan pendapat jumhur ulama fikih: jika seseorang memiliki dua puluh ekor kambing, dan yang lain dua puluh ekor kambing, dan terjadi antara mereka percampuran -dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan- maka dalam kondisi ini wajib atas mereka mengeluarkan zakat, mengapa? Karena bagi percampuran ada pengaruh, dan dengan percampuran mencapai harta dua orang kepada nishab zakat yaitu empat puluh ekor kambing, dan dengan itu dikeluarkan zakat dari nishab ini, dan makna itu: bahwa setiap satu dari mereka akan menanggung setengah ekor kambing, ini adalah dampak pengaruh dalam zakat.
Pendapat kedua: yaitu pendapat Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa: percampuran tidak memiliki pengaruh dalam zakat sama sekali -artinya: secara mutlak- tidak dalam kadar yang wajib, dan tidak dalam nishab, baik setiap satu dari para mitra memiliki nishab, maupun di bawah nishab, dan walaupun jumlah harta para mitra lebih dari nishab, maka jika setiap satu dari mereka memiliki di bawah nishab tidak wajib atasnya zakat, dan walaupun jumlah harta mereka lebih dari nishab, seperti harta dua orang yang bercampur adalah enam puluh ekor kambing untuk setiap mereka tiga puluh, dan itu karena kepemilikan setiap satu di bawah nishab, maka tidak wajib atasnya zakat, sebagaimana jika tidak bercampur dengan yang lain.
Kesimpulan perkataan dalam hal ini bahwa tidak ada pengaruh bagi percampuran secara mutlak tidak dalam kadar yang wajib dan tidak dalam nishab dengan makna: jika kita mengatakan bahwa dua orang setiap satu dari mereka memiliki dua puluh ekor kambing, dan terjadi antara mereka percampuran dengan syarat-syaratnya, berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi: tidak wajib zakat pada harta ini -meskipun jumlah dua harta mencapai nishab yaitu: empat puluh ekor kambing, dan nishab kambing -sebagaimana telah kita katakan- dimulai dari empat puluh -berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi mengatakan tidak ada zakat pada harta ini- mengapa? Mereka mengatakan: karena harta setiap satu dari mereka secara terpisah tidak mencapai nishabnya, dan ini berarti berlawanan dengan apa yang dilihat oleh jumhur ulama fikih.
Maka jumhur ulama fikih mengatakan wajib zakat pada harta ini mengapa karena mereka menjadikan bagi percampuran pengaruh dalam zakat, adapun Mazhab Hanafi maka mengatakan tidak ada zakat pada harta ini mengapa, mereka mengatakan karena mereka tidak menjadikan bagi percampuran pengaruh dalam zakat. Ini adalah sikap para ulama fikih tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran.
Jadi: kelompok -Mazhab Hanafi- yang mencegah pengaruh percampuran dalam zakat, tidak membicarakan setelah itu tentang kadar nishab, atau lainnya, maka mereka mencegah perkara secara tegas, dan selesai perkara, dan mengatakan: tidak dipandang kepada percampuran ini sama sekali, dan hanya dipandang kepada harta setiap satu secara tersendiri.
Ini berkenaan dengan sikap mereka tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran secara umum.
Dan Mazhab Hanafi mengatakan: adapun jika bercampur dalam dua nishab sehingga setiap satu dari mereka memiliki nishab, maka sesungguhnya zakat wajib padanya, seperti harta dua orang yang bercampur adalah delapan puluh, untuk setiap mereka empat puluh, maka wajib padanya satu ekor kambing; karena pada setiap empat puluh ekor kambing ada satu ekor kambing.
Ini -sebagaimana telah kita katakan- pendapat jumhur, dan pendapat Mazhab Hanafi berkenaan dengan pengaruh percampuran berkenaan dengan zakat.
Jumhur ulama fikih beralasan tentang apa yang mereka tuju yaitu bahwa bagi percampuran ada pengaruh dalam zakat?
Pemilik pendapat ini bersandar kepada nash-nash yang disebutkan dalam masalah ini, dan menunjukkan dengan jelas tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran dalam zakat, di antaranya: sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul; karena takut sedekah, dan apa yang ada dari dua mitra maka sesungguhnya keduanya saling mengembalikan dengan sama.” Maka hadits ini menunjukkan dengan jelas bahwa: kepemilikan dua mitra seperti kepemilikan satu orang, dan ini adalah hadits yang mengkhususkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Tidak ada pada unta yang kurang dari lima ekor sedekah.”
Dan berdasarkan itu dalam contoh yang telah kita sebutkan: jika untuk setiap satu dari mereka dua puluh ekor kambing, kemudian terjadi antara mereka percampuran, maka berdasarkan pendapat jumhur ulama fikih: atas mereka mengeluarkan satu ekor kambing; karena dengan berkumpulnya dua harta ditemukan nishab, tetapi ketika mereka mengeluarkan satu ekor kambing: setiap satu kembali kepada temannya, maka setiap satu dari mereka berarti akan menanggung setengah ekor kambing sebagaimana telah kita sebutkan.
Dan pemilik pendapat kedua -yaitu Mazhab Hanafi- keberatan atas apa yang dijadikan dalil oleh pemilik pendapat pertama -yaitu jumhur- dengan perkataan mereka: Sesungguhnya dua orang yang berserikat mungkin dikatakan kepada mereka: dua yang bercampur, dan dimungkinkan bahwa sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul” hanyalah larangan kepada para petugas zakat untuk membagi-bagi kepemilikan satu orang dengan pembagian yang mewajibkan atasnya banyak sedekah seperti: ada seorang lelaki memiliki seratus dua puluh ekor kambing, maka mereka membaginya atasnya kepada empat puluh tiga kali, atau dikumpulkan kepemilikan seorang lelaki kepada lelaki lain di mana mengharuskan pengumpulan banyak sedekah, mereka mengatakan: dan jika ditetapkan kemungkinan ini dalam hadits ini maka wajib untuk tidak mengkhususkan dengannya hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Tidak ada pada unta yang kurang dari lima ekor sedekah” dan makna ini: bahwa mereka berpandangan bahwa pengumpulan antara yang terpisah, dan pemisahan antara yang berkumpul hanyalah pada kepemilikan saja, dan dengan demikian tidak ada dalil dalam itu tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran.
Dan juga dalam keberatan mereka terhadap dalil mengatakan: dimungkinkan bahwa sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul” hanyalah larangan kepada para petugas zakat artinya: kemungkinan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan ucapannya para petugas zakat, dan mengarahkan hadits ini kepada para petugas zakat; dan kita maksudkan dengan mereka: petugas-petugas zakat yang melakukan pengumpulan zakat dari manusia, maka seakan-akan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka: jangan kalian kumpulkan antara yang terpisah, dan jangan kalian pisahkan antara yang berkumpul; agar tidak merugikan pemilik harta-harta ini.
Maka berarti: hadits tidak khusus untuk para pemilik, dan dengan demikian tidak menjadi dalil tentang tetapnya pengaruh percampuran dalam zakat.
Maka seakan-akan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka: jangan kalian lakukan ini, ambillah satu ekor kambing tentang seratus dua puluh, dan jangan kalian pisahkan harta ini; jangan kalian jadikan: empat puluh, dan empat puluh, dan empat puluh; karena mereka jika menjadikannya: empat puluh, dan empat puluh, dan empat puluh, akan mengambil tiga ekor kambing sebagai ganti satu ekor kambing, maka ini adalah larangan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada para petugas ini, atau para petugas zakat untuk memisahkan antara yang berkumpul, artinya: antara sesuatu dalam keseluruhan seratus dua puluh, tidak boleh menjadikannya atau membagikannya kepada tiga, sehingga menjadi jumlahnya tiga ekor kambing yang dikeluarkan oleh lelaki itu, sebagai ganti satu ekor kambing.
Seperti: ada seorang lelaki memiliki seratus dua puluh ekor kambing maka mereka membaginya atasnya kepada empat puluh tiga kali, atau dikumpulkan kepemilikan seorang lelaki kepada lelaki lain, di mana mengharuskan pengumpulan banyak sedekah, juga larangan kepada para petugas zakat, tidak boleh bagi mereka mengatakan bahwa: si fulan ini yang tinggal di sebelah si fulan memiliki dua puluh ekor unta, dan tetangganya yang lain memiliki dua puluh ekor unta maka kita kumpulkan dua bersama-sama, dan kita jadikan mereka empat puluh, dan dengan demikian kita ambil zakat dari empat puluh ini; karena dengan pengumpulan ini terjadi nishab, dan dengan demikian kita ambil zakat, ini dilarang bagi para petugas zakat.
Dan ini, mereka mengatakan: ini adalah makna hadits: tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul karena takut sedekah artinya: karena sedekah, seakan-akan para petugas zakat ingin mengambil zakat dari manusia dengan cara apapun; dan karena itu adalah larangan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.
Jadi: selama perkara demikian maka hadits dimaksudkan dengannya para petugas zakat, dan diarahkan kepada para petugas zakat, dan dengan demikian tidak diarahkan kepada para pemilik, dan dengan demikian tidak ada urusan dengannya tentang pengaruh percampuran dalam zakat.
Jawaban ini datang dari kelompok Mazhab Hanafi; dan karena itu mereka mengatakan: dan jika ditetapkan kemungkinan ini dalam hadits maka tidak diamalkan dengannya; karena ada kaidah yang mengatakan: dalil jika dimasuki kemungkinan maka gugur dengannya pengambilan dalil; dan karena itu mereka mengatakan: selama kemungkinan ini dalam hadits maka wajib untuk tidak mengkhususkan dengannya hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Tidak ada pada unta yang kurang dari lima ekor sedekah” dan makna ini bahwa mereka berpandangan: bahwa pengumpulan antara yang terpisah dan pemisahan antara yang berkumpul hanyalah pada kepemilikan saja, dan dengan demikian tidak ada dalil dalam itu tentang tetapnya pengaruh bagi percampuran, dikembalikan dalam itu kepada (Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid) karya Ibnu Rusyd Juz Pertama halaman 238 dan seterusnya.
Para ulama pemegang pendapat pertama telah menjawab keberatan ini, atau diskusi yang terjadi dari kalangan Hanafiyah, bahwa: lafal al-khulthah (percampuran) lebih jelas menunjukkan pada percampuran itu sendiri daripada pada kemitraan. Dan jika demikian halnya, maka sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: “maka keduanya saling mengembalikan dengan cara yang sama” menunjukkan bahwa hak yang wajib atas keduanya hukumnya adalah hukum satu orang, dan hal itu juga menunjukkan bahwa dua orang yang bercampur bukanlah dua orang yang berserikat; karena dua orang yang berserikat tidak dapat dibayangkan ada saling pengembalian di antara mereka, karena yang diambil adalah dari harta persekutuan; karena persekutuan dianggap sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban terpisah dari para pemegang saham, dan di sini zakat wajib pada harta persekutuan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dibayangkan salah satu sekutu mengembalikan sesuatu kepada sekutu lainnya.
Dan penafsiran hadits ini adalah yang dilihat oleh banyak ulama, dan dipilih oleh Abu Ubaid ketika beliau berkata: Dan menurut saya dalam hal ini adalah apa yang disepakati oleh mereka yang berpendapat bahwa hadits ini adalah larangan bagi pemilik dan petugas zakat bersama-sama; karena kezaliman tidak dapat diamankan dari petugas zakat -pemilik- sebagaimana pelarian dari sedekah tidak dapat diamankan dari pemilik harta.
Dan yang dimaksud dengan petugas zakat di sini adalah: petugas zakat, atau yang melakukan pemungutan zakat, sebagaimana pelarian dari sedekah tidak dapat diamankan dari pemilik harta, maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada keduanya bersama-sama.
Kemudian Abu Ubaid berkata: Dan hal itu jelas dalam hadits yang kami sebutkan dari Suwaid bin Ghaflah, ketika beliau menceritakan dari petugas zakat Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata: “Sesungguhnya dalam perjanjianku agar aku tidak memisahkan antara yang berkumpul, dan tidak mengumpulkan antara yang terpisah”. Maka hal ini telah menjelaskan kepadamu bahwa larangan itu untuk petugas zakat.
Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “berhati-hatilah terhadap sedekah” yakni: takut terhadap sedekah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari telah menjelaskan kepadamu bahwa larangan itu untuk para pemilik harta.
Jadi: ini juga merupakan jenis penggabungan antara hadits, apakah yang dimaksud adalah larangan untuk petugas saja dan tidak ada hubungannya dengan pemilik? Ataukah larangan untuk pemilik saja? Dan tidak ada hubungannya dengan petugas? Jika kita katakan bahwa itu larangan untuk petugas saja, maka ini menunjukkan -sebagaimana dikatakan kalangan Hanafiyah- bahwa tidak ada pengaruh percampuran dalam zakat, dan jika kita katakan bahwa itu ditujukan untuk pemilik, maka hal itu menunjukkan bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam zakat sebagaimana dipandang oleh jumhur fuqaha (mayoritas ahli fikih).
Namun ada juga yang menggabungkan antara keduanya dan berkata bahwa: sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “jangan mengumpulkan antara yang terpisah, dan jangan memisahkan antara yang berkumpul” dapat ditujukan kepada petugas, dan ditujukan kepada pemilik juga.
Ditujukan kepada petugas agar mereka tidak ingin mengambil lebih dari yang diminta, dan ditujukan kepada pemilik -pemilik harta- agar mereka tidak menghindari zakat dengan cara mengumpulkannya dengan sebagian lainnya, atau memisahkannya sehingga zakat gugur, atau zakat berkurang, dan penafsiran ini adalah yang diridhai oleh Abu Ubaid dalam kitabnya (Al-Amwal) halaman 484-486 dan beliau berkata: Sesungguhnya ini layak bahwa hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada pemilik harta, sebagaimana ditujukan kepada petugas, yaitu: mereka yang melakukan pemungutan.
Dan dengan demikian berdasarkan penafsiran ini yang dipilih oleh Abu Ubaid, hadits tersebut sejalan dengan apa yang dituju oleh jumhur fuqaha yaitu bahwa: percampuran memiliki pengaruh dalam zakat, yaitu: percampuran menjadikan harta dua orang seperti harta satu orang dalam zakat -sebagaimana telah kami jelaskan.
Dan kesimpulan dari semua ini adalah bahwa jumhur berpendapat bahwa hadits ini menunjukkan larangan bagi pemilik dan petugas bersama-sama dari semua itu, sebagaimana mereka berpendapat bahwa hal itu berlaku pada percampuran dan pada kepemilikan juga, dan bukan hanya pada kepemilikan saja, sebagaimana dipandang oleh pemegang pendapat kedua, maka dengan ini ingin menetapkan pengaruh percampuran.
Dan kami menguatkan apa yang dituju oleh jumhur fuqaha tentang penetapan pengaruh percampuran dalam zakat, yaitu: bahwa jika dua orang atau lebih bercampur maka mereka mengumpulkan harta mereka dalam zakat, dan berzakat dengan zakat harta satu orang, dan itu karena kuatnya dalil-dalil jumhur dalam apa yang mereka tuju, dan sanggahan mereka terhadap dalil-dalil pendapat yang berlawanan dengan pendapat mereka. Dan jika terbukti bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam zakat -sebagaimana dipandang jumhur fuqaha sebagaimana telah kami jelaskan- maka jenis percampuran yang mana yang terbukti memiliki pengaruh ini? Dan kami akan menjawab hal itu sebagai berikut:
Sikap Para Fuqaha tentang Jenis-jenis Percampuran yang Memiliki Pengaruh:
Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa percampuran ada dua jenis: percampuran persekutuan, dan percampuran bertetangga, dan kami sebutkan juga bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam zakat yaitu: menjadikan harta dua orang seperti harta satu orang, berarti: mereka mengumpulkan harta mereka dalam zakat dan berzakat dengan zakat harta satu orang sebagaimana telah kita lihat; dan para fuqaha yang berpendapat demikian tidak berbeda dalam penetapan pengaruh ini untuk kedua jenis percampuran, baik percampuran benda, atau percampuran sifat, bahkan kita dapati bahwa Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini telah menyampaikan dalam keterangannya ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin bahwa tidak ada perbedaan antara kedua percampuran dalam kewajiban.
Kecuali bahwa sebagian dari mereka mensyaratkan untuk penetapan pengaruh ini: bahwa harta setiap orang dari yang bercampur harus mencapai nisab atau lebih, sementara sebagian lainnya tidak mensyaratkan itu dan mereka adalah jumhur dari yang berpendapat tentang penetapan pengaruh percampuran; maka percampuran memiliki pengaruhnya, baik percampuran benda, atau percampuran sifat, dan baik setiap orang dari yang bercampur memiliki nisab, atau tidak, dan mereka bersandar pada hadits-hadits yang bersifat mutlak dalam hal ini -yang telah kami sebutkan sebelumnya- di mana hadits-hadits itu tidak membedakan antara dua jenis percampuran, sebagaimana tidak membedakan antara apakah harta setiap orang dari yang bercampur mencapai nisab, dan antara yang tidak mencapai nisab, dan dapat dirujuk dalam hal itu kepada (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab) karya An-Nawawi jilid kelima halaman 406 dan seterusnya dan juga (Al-Mughni) karya Ibnu Qudamah jilid kedua halaman 481 dan seterusnya.
Ketiga: Sikap Para Fuqaha tentang Tempat yang Dipengaruhi oleh Percampuran:
Yang dimaksud dengan itu adalah: apakah percampuran mempengaruhi kadar yang wajib saja? Ataukah mempengaruhi kadar yang wajib dan nisab bersama-sama?
Berkenaan dengan masalah ini kita dapati bahwa para fuqaha telah berbeda menjadi dua kelompok:
Kelompok pertama: berpendapat bahwa percampuran hanya mempengaruhi kadar yang wajib saja.
Kelompok kedua: berpendapat bahwa percampuran mempengaruhi kadar yang wajib dan nisab bersama-sama.
Maka pemegang pendapat pertama setelah terbukti pada mereka pengaruh percampuran dalam kadar yang wajib dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “sesungguhnya keduanya saling mengembalikan dengan cara yang sama”, mereka berhenti padanya, dan tidak mengqiyaskan padanya nisab, dan mereka berpendapat bahwa dua orang yang bercampur berzakat dengan zakat satu orang, jika setiap orang dari mereka memiliki nisab, sementara pemegang pendapat kedua tidak berhenti pada itu, melainkan mereka mengqiyaskan nisab pada kadar yang wajib, dan berpendapat bahwa dua orang atau lebih yang bercampur nisabnya adalah nisab satu orang, sebagaimana zakat mereka adalah zakat satu orang, dan sesuai dengan perbedaan ini berbeda pula makna yang dipahami dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “jangan mengumpulkan antara yang terpisah, dan jangan memisahkan antara yang berkumpul” dan masing-masing dari kedua pendapat memahami hadits ini sesuai dengan apa yang mereka tuju.
Kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah: tidak disyaratkan bahwa harta setiap orang dari dua orang yang bercampur secara terpisah telah mencapai nisab, agar kita dapat mengatakan tentang pengaruh percampuran dalam zakat, melainkan cukup -sebagaimana telah kami katakan- bahwa nisab ada dari gabungan kedua harta saja.
Dan kami memilih apa yang menjadi pendapat pemegang pendapat kedua, dengan beramal dengan qiyas (analogi) di mana qiyas diakui secara syara’, selama tidak ada nash yang menyelisihinya, dan masalah kita ini telah ditunjukkan oleh nash sebagaimana telah disebutkan tentang penetapan pengaruh percampuran dalam kadar yang wajib, maka diqiyaskan padanya nisab, dan dengan demikian tempat yang dipengaruhi oleh percampuran adalah kadar yang wajib dan nisab bersama-sama.
Hukum Percampuran dalam Ternak, dan Pengaruhnya dalam Zakat
Sikap Para Fuqaha tentang Jenis-jenis Harta yang Dipengaruhi oleh Percampuran:
Mereka yang mengatakan: bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam zakat, berbeda pendapat berkenaan dengan harta-harta yang dipengaruhi oleh percampuran, dan perbedaan ini dapat dikembalikan kepada dua pendapat:
Pendapat pertama: Pemegang pendapat ini berpendapat bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam ternak saja, adapun selain ternak maka tidak ada pengaruh percampuran padanya.
Pendapat kedua: Pemegang pendapat ini berpendapat bahwa percampuran memiliki pengaruh dalam semua jenis harta, baik ternak, atau uang, atau barang dagangan, atau biji-bijian, atau buah-buahan. Dapat dirujuk dalam perincian pendapat-pendapat ini pada (Al-Mughni) karya Ibnu Qudamah jilid kedua halaman 490 dan seterusnya, dan (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab) karya An-Nawawi jilid kelima halaman 430 dan seterusnya.
Dalil-dalil Pendapat Pertama:
Pemegang pendapat ini yang mengatakan bahwa: percampuran memiliki pengaruh dalam ternak saja, adapun selain ternak maka tidak ada pengaruh percampuran padanya, saya katakan: mereka bersandar pada sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “dan dua orang yang bercampur adalah yang berkumpul pada kolam air, dan pejantan, dan penggembala”. “Dan dua orang yang bercampur adalah yang berkumpul pada kolam air…” dan yang dimaksud dengan “kolam air”: adalah tempat di mana ternak minum, dan “pejantan”: dan ini adalah sesuatu yang khusus untuk ternak, dan “penggembala” juga ini adalah sesuatu yang khusus untuk ternak. Mereka berkata: maka hal itu menunjukkan bahwa apa yang tidak terdapat padanya hal tersebut -yaitu: apa yang tidak terdapat padanya kolam air dan pejantan dan penggembala- tidak ada percampuran yang berpengaruh.
Dan mereka juga bersandar pada sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “jangan mengumpulkan antara yang terpisah karena takut sedekah” di mana mereka berkata: bahwa hal itu khusus untuk ternak saja; karena zakat berkurang dengan mengumpulkannya kadang-kadang, dan bertambah di waktu lain, dan harta-harta lainnya wajib padanya atas yang melebihi nisab sesuai perhitungannya, maka tidak ada pengaruh mengumpulkannya. Yaitu: pengumpulan antara yang terpisah ini, dan pemisahan antara yang berkumpul, mereka berkata: ini mempengaruhi sedekah sungguh-sungguh, tetapi hanya dalam ternak saja, tetapi hal itu tidak dapat dibayangkan untuk harta-harta lainnya seperti uang misalnya; karena uang misalnya ketika mencapai nisab maka wajib padanya zakat berapa pun jumlah yang dicapainya, dan dengan demikian tidak dapat dibayangkan padanya pemisahan antara yang berkumpul, atau pengumpulan antara yang terpisah; dan oleh karena itu mereka berkata: hadits ini juga tidak berlaku kecuali pada ternak saja.
Dan oleh karena itu mereka berkata: pengaruh percampuran dalam zakat hanya khusus untuk ternak saja, maka jika ada percampuran selain ternak maka tidak ada pengaruh percampuran ini dalam zakat, yaitu: bahwa tidak menjadikan harta dua orang seperti harta satu orang; harta dua orang dijadikan seperti harta satu orang hanya dalam hal ternak saja; adapun selainnya maka tidak menjadikan harta dua orang seperti harta satu orang.
Dan dengan demikian dalam hal ini setiap orang benar-benar mandiri dengan barang-barangnya, dan hartanya, maka jika mencapai nisab secara terpisah dia menzakatkannya, dan jika tidak mencapai maka dia tidak menzakatkannya.
Inilah ringkasan pendapat pertama, dan dalil-dalil yang menjadi sandaran pemegang pendapat yang mengatakan bahwa pengaruh percampuran dalam zakat hanya dalam ternak saja, dan tidak pada selainnya dari yang umum.
Adapun pendapat kedua yang mengatakan bahwa: percampuran memiliki pengaruh dalam semua jenis harta, baik ternak, atau uang, atau barang dagangan, atau biji-bijian, atau buah-buahan, mereka beralasan atas apa yang mereka tuju dengan perkataan mereka: bahwa biaya menjadi ringan jika pembuahnya satu, dan pengairan dan tempat penjemuran, demikian juga harta dagangan, dan berbeda juga jika tokonya satu dan timbangan dan penjualnya maka serupa dengan ternak.
Dan An-Nawawi berkata: Dan yang paling shahih penetapannya -yaitu: percampuran- semuanya dalam semuanya yaitu: semua harta karena keumuman hadits: “jangan memisahkan antara yang berkumpul”. Dan beliau menambahkan alasan lain untuk itu yaitu: bahwa percampuran terbukti dalam ternak untuk kemudahan, dan kemudahan di sini ada dengan bersatunya tempat penjemuran; dan bersatunya tempat penjemuran ini untuk biji-bijian dan air dan pemetikan kurma juga untuk biji-bijian, dan toko hanya khusus untuk perdagangan, dan timbangan khusus untuk perdagangan, dan penakar dan penimbang dan pengelola, semua itu khusus untuk biji-bijian dan perdagangan.
Dan telah memilih pendapat tentang pengaruh percampuran dalam semua harta banyak dari ulama kontemporer; kemudian mereka menjadikannya sebagai dasar untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan saham dan sejenisnya dalam hukum zakat dan pemungutannya, yaitu memperlakukannya seperti satu kepribadian.
Dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah untuk kalian.
3 – Zakat pada Hewan
Lanjutan: Hukum Percampuran dalam Ternak, dan Pengaruhnya dalam Zakat
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kita Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan mereka yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan, amma ba’du:
Maka sungguh telah kita bicarakan dalam perkuliahan sebelumnya tentang keumuman personal dalam zakat, dan telah kita jelaskan perbedaan antara orang pribadi dan badan hukum. Dan sungguh telah kita lihat perbedaan-perbedaan fikih seputar masalah percampuran, dan apakah percampuran memiliki pengaruh dalam zakat atau tidak? Dan kita katakan bahwa pendapat yang rajih dalam hal ini adalah yang mengatakan tentang pengaruh percampuran dalam zakat, tetapi kita telah menemukan pendapat lain yaitu dari kalangan Hanafiyah.
Dan juga termasuk di antara masalah-masalah yang diperselisihkan para fuqaha: apakah percampuran mempengaruhi nisab dan kadar yang wajib bersama-sama, ataukah hanya mempengaruhi kadar yang wajib saja?
Saya katakan: kami telah menyebutkan pendapat para ahli fikih dalam masalah-masalah ini beserta dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran dalam mendukung pendapat mereka, dan kami menguatkan pendapat bahwa percampuran (khulthah) berpengaruh terhadap zakat dan pengaruhnya mencakup percampuran dalam kepemilikan dan percampuran dalam bertetangga secara bersamaan, dan bahwa percampuran berpengaruh terhadap nisab dan kadar yang wajib secara bersamaan, dan juga sesungguhnya percampuran berpengaruh pada semua harta dan bukan hanya ternak saja, artinya percampuran berpengaruh pada tanaman, buah-buahan, dirham dan dinar. Berdasarkan hal ini, sebagian ahli fikih kontemporer menerapkan sistem percampuran pada perusahaan-perusahaan saham, di mana mereka memandang perusahaan-perusahaan saham diperlakukan seperti satu orang saja, sehingga zakat diwajibkan pada harta perusahaan saham yang terkumpul secara langsung dengan mengqiyaskan pada ketetapan percampuran dalam ternak.
Maka zakat wajib pada harta perusahaan, bukan pada harta setiap pemegang saham secara terpisah. Dengan demikian, pemegang saham yang memiliki sejumlah saham dengan nilai di bawah nisab zakat tidak dibebaskan dari zakat. Artinya, jika perusahaan ini memiliki saham yang melebihi nisab, tetapi para pemegang sahamnya masing-masing memiliki saham yang tidak mencapai nisab, berdasarkan pengaruh percampuran ini maka zakat wajib pada harta perusahaan meskipun setiap pemegang sahamnya tidak memiliki nisab yang mewajibkan zakat atasnya.
Dan pendapat tentang penerapan zakat juga berlaku pada badan hukum publik yang memiliki aktivitas komersial. Kami telah mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan saham adalah perusahaan-perusahaan di antara individu-individu dalam hukum privat, yang diatur oleh hukum privat. Sebagian ahli fikih mengatakan: seharusnya pengaruh percampuran dalam zakat tidak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan swasta yang dibiayai oleh individu-individu saja, namun sebagian ini berpendapat bahwa penerapan zakat juga berlaku pada badan hukum publik yang memiliki aktivitas komersial. Sebagaimana negara dapat melakukan kegiatan komersial, maka sah kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal ini, pendapat tentang wajibnya zakat pada perusahaan-perusahaan saham tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan sebagai badan hukum privat saja, bahkan mencakup dengan cara qiyas badan hukum publik yang memiliki aktivitas komersial. Dapat dirujuk dalam hal ini pada buku (Akuntansi Zakat Mal: Ilmu dan Praktik) halaman 91 dan seterusnya karya Dr. Syauqi Ismail Syahatah, cetakan pertama 1970, penerbit Maktabah Al-Anglo Al-Mishriyyah. Juga dapat dirujuk pada buku (Sistem Pajak dalam Islam dan Sejauh Mana Penerapannya di Kerajaan Arab Saudi) karya Dr. Abdul Aziz Al-Ali Al-Shalih halaman 28 dan seterusnya.
Dan kesimpulannya: menjadi jelas bagi kita dari uraian di atas bahwa percampuran berpengaruh terhadap zakat, dalam arti bahwa harta dua orang dijadikan seperti harta satu orang, dan pengaruhnya tidak terbatas hanya pada ternak saja, tetapi mencakup semua harta yang dikenai zakat. Inilah yang kami pilih dan kuatkan. Dari ketetapan pengaruh percampuran ini pada semua harta zakat, tampak bagi kita adanya mukallaf non-pribadi dalam zakat di samping mukallaf pribadi di dalamnya. Jika kita ketahui bahwa mukallaf pribadi dalam zakat terdiri dari kaum muslimin yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat wajib zakat tanpa membedakan antara anak kecil dan dewasa, serta tanpa membedakan antara orang berakal dan gila, maka mukallaf non-pribadi terdiri dari:
- Badan hukum privat yaitu para pihak yang bercampur dalam percampuran pada hewan ternak dan lainnya dari seluruh harta zakat, yang dalam Islam menurut pendapat yang rajih diperlakukan sebagai satu orang dalam zakat apabila harta mereka yang terkumpul memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Juga perusahaan-perusahaan saham yang muncul dalam perdagangan dan industri di zaman modern, yang juga diterapkan pada mereka sistem percampuran, dan yang merupakan bentuk investasi terpenting dan terkemuka, yang dicirikan dengan banyaknya jumlah pemegang saham di dalamnya dan memiliki kepribadian hukum yang mandiri.
- Badan hukum publik yang memiliki aktivitas komersial seperti lembaga-lembaga komersial yang didirikan negara untuk mengelola kegiatan komersial di dalam dan luar negeri. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa mukallaf zakat ada dua jenis: Jenis pertama adalah orang-orang pribadi, jenis kedua adalah badan-badan non-pribadi. Kami berpendapat bahwa mewajibkan zakat pada badan non-pribadi adalah hal yang wajib, dan itu sejalan dengan kaidah “keuntungan diimbangi tanggung jawab”. Badan ini menikmati manfaat beberapa fasilitas umum di negara yang sesuai dengan sifatnya, seperti perlindungan negara terhadapnya dari serangan yang mungkin terjadi atau menimpanya. Tidak diragukan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap kenikmatan hak diimbangi dengan kewajiban sesuai kaidah “keuntungan diimbangi tanggung jawab”. Oleh karena itu, badan ini wajib mengeluarkan zakat.
Selain itu, mewajibkan zakat pada badan non-pribadi akan mewujudkan universalitas personal dalam zakat hingga batas maksimal. Dalam kewajiban ini, zakat dapat menjangkau harta-harta yang tidak dapat dijangkau dalam beberapa kondisi jika tidak dibebankan pada badan non-pribadi ini, seperti jika saham setiap pemegang saham yang membentuk badan non-pribadi tidak mencapai nisab yang mewajibkan zakat secara sendiri-sendiri, namun saham tersebut dengan bergabung dengan saham-saham lain mencapai nisab yang mewajibkan zakat, maka wajib zakat padanya pada saat itu.
Kesimpulan perkataan dalam hal ini adalah bahwa jika tidak diterapkan sistem percampuran pada perusahaan-perusahaan ini, dalam arti bahwa harta dua orang diperlakukan seperti harta satu orang, zakat tidak akan dapat menjangkau harta-harta ini. Karena jika kita lihat setiap orang secara individu, kita dapati bahwa ia tidak memiliki nisab, sehingga zakat tidak wajib atasnya. Tetapi ketika kita menggabungkan harta-harta ini satu sama lain dalam perusahaan-perusahaan, kita dapat menjangkau zakat dalam kondisi ini, karena dengan bergabungnya saham-saham ini satu sama lain kita mencapai nisab, sehingga zakat wajib padanya. Jadi artinya ketika kita membebankan zakat pada badan-badan non-pribadi atau badan-badan hukum, ini dapat mengantarkan kita untuk membebankan zakat pada harta-harta yang tidak akan dikenai zakat jika kita tidak mengambil sistem ini. Dengan mewajibkan zakat pada badan-badan non-pribadi baik yang bersifat publik maupun privat—arti kata publik adalah bahwa negara yang mengelola perusahaan-perusahaan ini dan arti privat yaitu individu-individu yang mengelola perusahaan-perusahaan ini—kami katakan bahwa dengan mewajibkan zakat pada badan-badan non-pribadi baik yang bersifat publik maupun privat di samping orang-orang pribadi, kita dapati bahwa zakat telah meluas untuk mencakup semua harta yang layak menjadi objeknya, baik pemiliknya orang pribadi maupun badan non-pribadi. Artinya, universalitas personal dalam zakat telah terwujud hingga tingkat maksimal yang mungkin. Dengan ini terwujud kesetaraan sempurna antara semua orang, baik pribadi maupun non-pribadi, dalam menanggung beban keuangan umum yang paling penting di antaranya adalah zakat yang ditetapkan di negara terhadap rakyatnya.
Setelah selesai membahas universalitas personal dalam zakat, baik universalitas ini berkaitan dengan orang-orang pribadi atau badan-badan non-pribadi atau badan hukum, maka kami katakan: jika universalitas personal telah mencakup semua orang pribadi dan non-pribadi yang mampu, namun universalitas tersebut menjangkau mereka dengan mempertimbangkan harta yang mereka miliki dari berbagai sumbernya, karena pembebanan terkait dengan harta itu sendiri. Artinya, setelah kita membahas universalitas personal dalam zakat, sekarang kita berbicara tentang universalitas material dalam zakat.
Jadi pada kita ada universalitas personal dan telah kita bahas, dan pada kita ada universalitas material, dan sekarang kita mulai membahasnya:
Universalitas material dalam zakat berarti bahwa zakat dibebankan pada semua harta yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Kewajiban zakat telah ditetapkan secara umum pada semua harta sebagaimana jelas dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka” (Surah At-Taubah, ayat 103). Ini menunjukkan bahwa pada asalnya zakat wajib pada setiap harta kecuali jika Sunnah Mulia menjelaskan sebaliknya atau datang dalil syariat bahwa suatu harta tertentu, atau harta tertentu tidak wajib di dalamnya zakat.
Sumber harta adalah perolehan atau apa yang keluar dari bumi, dan kita dapat mengetahui itu dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu” (Surah Al-Baqarah, ayat 267). Jika Alquran Karim telah mewajibkan zakat pada setiap harta, namun Sunnah Mulia telah menjelaskan bahwa kewajiban ini berlaku pada harta-harta berikut:
Pertama atau jenis pertama: Hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing.
Jenis kedua: Tanaman yang dikenai usyur (seperti sepersepuluh atau seperdua puluh), yaitu makanan pokok yang wajib di dalamnya sepersepuluh atau setengah sepersepuluh.
Jenis ketiga: Uang emas dan perak, bahkan yang tidak dicetak.
Jenis keempat: Barang dagangan.
Jenis kelima: Zakat fitrah.
Lima jenis harta ini terdiri dari delapan kategori jenis harta yaitu “emas, perak, unta, sapi, kambing, tanaman, kurma, dan anggur”. Oleh karena itu, zakat wajib untuk delapan kategori dari tingkatan manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan” (Surah At-Taubah, ayat 60). Inilah delapan kategori yang disalurkan kepada mereka harta zakat sebagaimana harta yang wajib di dalamnya zakat ada delapan seperti yang kami sebutkan.
Hewan yang Wajib di Dalamnya Zakat dan Syarat-syarat Zakatnya
Kita mulai dengan jenis pertama yaitu zakat hewan:
Zakat hewan wajib pada hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing yang jinak berdasarkan nash dan ijmak. Di antara nash-nash ini adalah hadits Abu Dzar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Tidaklah pemilik unta, sapi, atau kambing yang tidak menunaikan zakatnya melainkan hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan paling besar dan paling gemuk, menanduknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kukunya. Setiap kali yang terakhir selesai, yang pertama kembali kepadanya hingga diputuskan perkara di antara manusia.”
Syarat-syarat zakat hewan—yaitu ternak—ada enam: Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nisab, haul (satu tahun), dan penggembalaan. Disyaratkan pada hewan yang wajib zakatnya bahwa ia dimiliki oleh seorang muslim berdasarkan ijmak. Artinya, jika dimiliki oleh orang kafir maka tidak wajib di dalamnya zakat, karena di antara syarat sahnya zakat adalah Islam. Juga harus digembalakan (sa-imah), dan penggembalaan artinya bahwa hewan tersebut merumput sendiri tanpa pemiliknya mengeluarkan biaya untuk makanannya, dan harus digembalakan selama masa haul menurut jumhur fuqaha. Itu karena zakat adalah ibadah, dan tidak sah dari orang kafir dalam keadaan kekafiran. Karena hewan yang digembalakan tidak ada biaya di dalamnya, sebab ia merumput di padang rumput yang mubah, berbeda dengan hewan yang diberi makan bukan di padang rumput mubah ini, karena ia membutuhkan biaya untuk makanan dan minumannya dari harta pemiliknya, begitu juga ternak yang bekerja.
Artinya, di antara syarat yang diperlukan agar zakat wajib pada hewan adalah harus digembalakan dalam arti merumput sendiri di padang rumput yang mubah. Jika pemiliknya yang memberi makan, maka dalam kondisi ini tidak wajib zakat. Demikian juga untuk ternak, disyaratkan tidak menjadi hewan pekerja, yaitu digunakan oleh orang yang menggarap sawah atau petani untuk bekerja dalam pertanian. Jika menjadi hewan pekerja, yaitu digunakan untuk pekerjaan pertanian, maka tidak wajib di dalamnya zakat. Ini menurut jumhur fuqaha. Tetapi diriwayatkan dari Malik tentang ternak pekerja dan yang diberi makan bahwa zakatnya wajib jika mencapai nisab berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang zakat unta: “Pada setiap lima ekor (unta) seekor kambing”. Dengan ini diamalkan oleh penduduk Madinah dan tidak ada dalil asli dalam hal itu bagi mereka.
Jadi artinya tidak disyaratkan agar zakat wajib pada ternak bahwa ia harus digembalakan dan tidak harus yang tidak diberi makan. Pada pendapat ini—yaitu menurut Malik—zakat wajib pada ternak meskipun diberi makan, yaitu pemiliknya yang memberi makan, dan meskipun menjadi hewan pekerja yaitu pemiliknya menggunakannya dalam pekerjaan pertanian. Imam Malik ketika mewajibkan zakat pada hewan pekerja dan yang diberi makan bersandar pada hal itu—sebagaimana kami katakan—pada keumuman hadits yang di dalamnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai unta: “Pada setiap lima ekor seekor kambing”. Ketika beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Pada setiap lima ekor seekor kambing” yaitu pada setiap lima unta seekor kambing, hadits datang secara umum. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah unta itu diberi makan atau tidak diberi makan, dan tidak membedakan apakah unta itu bekerja atau tidak bekerja. Oleh karena itu, Imam Malik memandang keumuman ini yang terdapat dalam hadits, dan mewajibkan zakat pada ternak meskipun menjadi hewan pekerja, meskipun diberi makan.
Tetapi jumhur memiliki dalil-dalil dalam mensyaratkan penggembalaan untuk wajibnya zakat. Jumhur berdalil bahwa disyaratkan penggembalaan untuk wajibnya zakat—dan penggembalaan sebagaimana kami katakan adalah bahwa ternak merumput di padang rumput yang mubah—berdalil dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Pada setiap ternak yang digembalakan, pada setiap empat puluh ekor seekor anak unta betina yang masih menyusu induknya”. Ini menunjukkan bahwa tidak ada zakat pada selainnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadits ini tentang penggembalaan, lalu bersabda: “Pada setiap ternak yang digembalakan”. Dengan mafhum mukhalafah (pengertian kebalikan) bahwa selain yang digembalakan yaitu yang diberi makan tidak wajib di dalamnya zakat. Maka jumhur berdalil bahwa disyaratkan penggembalaan untuk wajibnya zakat pada ternak, berdalil dengan hadits ini yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Pada setiap ternak yang digembalakan, pada setiap empat puluh ekor seekor anak unta betina yang masih menyusu induknya”. Ini adalah hadits—sebagaimana kami katakan—yang menunjukkan dengan mafhum mukhalafah bahwa ternak yang diberi makan tidak ada zakat di dalamnya.
Mereka juga beralasan dengan apa yang diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menulis surat tentang sedekah wajib kepada para pegawainya, dia menulisnya dan di dalamnya tertulis: “Sedekah kambing adalah pada yang digembalakan apabila mencapai empat puluh maka padanya ada sedekah” yang berarti seolah-olah Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwa zakat kambing itu wajib apabila mencapai empat puluh ekor, tetapi disyaratkan harus yang digembalakan ketika beliau berkata: “Sedekah kambing adalah pada yang digembalakan” maka di sini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa taala anhu menegaskan tentang penggembalaan juga, dengan mafhum (pemahaman tersirat) bahwa tidak wajib zakat pada yang diberi pakan.
Mereka juga berkata bahwa hewan yang bekerja—yaitu ternak yang digunakan untuk bekerja—dan yang diberi pakan dari ternak itu tidak dipelihara untuk berkembang, melainkan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia, sehingga menjadi seperti pakaian badan dan perabot rumah yang tidak ada zakatnya tanpa khilaf di antara para fuqaha (ahli fikih). Juga jumhur fuqaha mengatakan bahwa harus disyaratkan penggembalaan, mereka beralasan dengan hal itu bahwa hewan yang bekerja dan yang diberi pakan dari ternak itu tidak dipelihara untuk berkembang, yaitu yang memeliharanya pada umumnya memeliharanya untuk kepentingan dan kebutuhannya yang mendesak, sedangkan zakat pada dasarnya wajib pada harta yang berkembang, tetapi ini tidak diambil untuk berkembang, dan oleh karena itu menjadi seperti pakaian badan, yaitu pakaian yang dikenakan manusia ini termasuk kebutuhannya, dan oleh karena itu tidak wajib zakatnya.
Dan tidak wajib zakat pada ternak selain itu. Kita telah mengatakan bahwa ternak yang wajib zakatnya adalah unta, sapi, dan kambing. Apakah wajib pada jenis lain selain ketiga jenis ini? Tidak wajib zakat pada ternak selain itu seperti kuda, bagal, dan keledai berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada zakat atas seorang Muslim pada budaknya dan tidak pula pada kudanya”. Ini merupakan nash (teks) bahwa zakat tidak wajib pada budak dan tidak pada kuda, artinya tidak wajib kecuali pada jenis-jenis yang disebutkan dalam hadits, yaitu unta, sapi, dan kambing.
Sebagaimana tidak wajib pada hasil perkawinan antara hewan peliharaan dan hewan liar, dan tidak pula pada apa yang tidak dimiliki seorang Muslim dengan kepemilikan sempurna, dan tidak pula pada apa yang belum berlalu satu tahun (haul), berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum—dan ini adalah mazhab ulama Madinah dan ahli berbagai negeri, dan karena tidak sempurna pertumbuhan ini umumnya sebelum lewat satu tahun. Jadi harus berlalu satu tahun. Mengapa mereka mensyaratkan haul supaya wajib zakat pada hewan-hewan ini? Mereka berkata karena berlalunya haul ini adalah bukti pertumbuhan, yaitu umumnya terjadi pertumbuhan dalam satu tahun penuh, adapun sebelum setahun maka umumnya tidak terjadi pertumbuhan; oleh karena itu mereka menjadikan haul dan mensyaratkan haul. Dan sapi mencakup sapi liar, dan kambing meliputi domba dan kambing pula.
Hanafiyah mensyaratkan penggembalaan seperti jumhur, tetapi mereka tidak mensyaratkan penggembalaan sepanjang haul, melainkan hanya sebagian besar haul saja, yaitu lebih dari setengah. Oleh karena itu jika memberi pakan setengah haul maka tidak wajib zakatnya; karena tidak dianggap digembalakan.
Dan dalam pensyaratan haul—yaitu sempurnanya haul—ada hadits Abu Dawud dengan sanadnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun padanya”. Harta tidak sempurna pertumbuhannya pada umumnya—sebagaimana kita katakan—kecuali setelah sempurna satu tahun. Dan dalam pensyaratan penggembalaan sepanjang haul menurut jumhur adalah keumuman berita dari Anas radhiyallahu anhu: “Dan pada sedekah kambing yang digembalakan ada zakatnya” dan berita Abu Dawud dan lainnya: “Pada setiap unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor ada bint labun” dan ini sahih sanadnya sebagaimana dikatakan Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Al-Khatib.
Jadi penggembalaan—sebagaimana kita katakan—pensyaratannya oleh jumhur fuqaha kecuali Malikiyah dalam pendapatnya, meskipun jumhur fuqaha telah sepakat bahwa disyaratkan pada hewan agar wajib zakatnya harus digembalakan yaitu di padang rumput yang mubah (bebas) yang tidak membebani pemiliknya biaya makan dan minum. Jika mereka telah sepakat tentang itu, namun mereka berbeda pendapat: apakah disyaratkan penggembalaan sepanjang tahun, ataukah cukup sebagian besar tahun? Ahnaf (pengikut Abu Hanifah) berkata cukup lebih dari setengah yaitu sebagian besar tahun, setengah atau lebih. Dalam hal ini mereka mensyaratkan atau tidak mensyaratkan bahwa penggembalaan harus sepanjang haul, tetapi jumhur fuqaha berkata harus penggembalaan sepanjang haul.
Dan sekarang kita sampai pada nisab zakat unta. Nisab pertama unta adalah lima dengan ijma (konsensus), maka tidak wajib zakat padanya kecuali jika mencapai lima ekor yang digembalakan selama satu tahun penuh menurut jumhur fuqaha, dan itu berdasarkan hadits dalam Shahihain: “Tidak ada sedekah pada kurang dari lima ekor unta”. Dzud adalah jenis unta. Maka hadits ini mengatakan bahwa jika tidak mencapai lima ekor unta maka tidak ada sedekahnya, tidak ada sedekah pada kurang dari lima dzud dari unta. Maka jika unta mencapai lima ekor, di sini mencapai nisab, tetapi apakah kita mengeluarkan zakat dari jenis unta atau tidak? Di sini kita katakan: jika unta mencapai lima ekor maka wajib zakatnya, dan yang wajib adalah seekor kambing dari domba, dan ini dari selain jenis harta itu, dan itu berbeda dengan prinsip asal.
Prinsip asal adalah bahwa zakat dikeluarkan dari jenis harta itu, tetapi di sini disepakati oleh para fuqaha bahwa unta jika mencapai lima ekor maka di sini telah mencapai nisab yaitu wajib zakatnya, tetapi kadar yang wajib dikeluarkan bukan dari jenisnya, melainkan kita mengeluarkan seekor kambing untuk lima ekor unta ini, dan ini sebagaimana kita katakan berbeda dengan prinsip asal. Mengapa berbeda dengan prinsip asal? Untuk kemudahan bagi pemilik harta dan fakir bersama-sama; karena prinsip asal adalah zakat harta dikeluarkan dari harta itu yaitu dikeluarkan dari harta itu, dan jika yang wajib di sini dikeluarkan dari jenis harta itu maka jika berupa unta lengkap maka pemilik dirugikan; karena banyak, dan jika kita wajibkan hanya sebagian unta saja maka orang-orang fakir dirugikan, bahkan pemilik harta juga karena ketidakmampuannya menyerahkan sebagian kepada mereka tanpa keseluruhan kecuali dengan menyembelihnya, dan ini merugikan baginya, dan mungkin ini mengurangi nilainya, dan mungkin orang-orang fakir tidak membutuhkan daging, bahkan mereka membutuhkan roti atau pakaian misalnya, dan mereka tidak menemukan yang membeli daging dari mereka. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya yaitu memerintahkan agar kita mengeluarkan seekor kambing sebagai ganti mengeluarkan satu dari unta; karena nilai kambing sebagaimana kita katakan jauh lebih rendah dari nilai satu ekor unta, dan oleh karena itu—sebagaimana kita katakan—jika diwajibkan kambing; karena dalam hal itu terwujud kepentingan kedua pihak.
Kepentingan fakir agar tidak terhalang dari zakat pada kadar harta ini, dan juga kepentingan pemilik harta; karena jika kita wajibkan padanya satu dari empat dari unta, jika kita wajibkan padanya satu ekor unta dari lima ekor ini maka itu akan menimbulkan kerugian baginya; oleh karena itu—sebagaimana kita katakan—ada keseimbangan antara fakir di satu sisi atau antara orang-orang fakir di satu sisi dan pemilik harta di sisi lain. Sebagaimana kita katakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu yaitu memerintahkan agar kita mengeluarkan untuk lima ekor unta seekor kambing, dan para khalifah rasyidin serta kaum Muslim setelahnya menjalankannya.
Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis ketika menugaskannya ke Bahrain sebagai petugas zakat dengan berkata: “Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas kaum Muslim, dan yang diperintahkan rasul-Nya, maka barangsiapa dimintai darinya dari kaum Muslim menurut ketentuannya maka hendaklah dia memberikannya, dan barangsiapa dimintai melebihinya maka jangan dia berikan. Pada dua puluh empat ekor unta ke bawah adalah kambing, pada setiap lima ekor seekor kambing. Maka jika mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima maka padanya bint makhad”—dan bint makhad dari unta adalah yang berusia satu tahun dan masuk tahun kedua, dan dinamakan demikian; karena induknya setelah setahun melahirkannya sudah waktunya untuk hamil lagi, sehingga dengan kehamilan itu menjadi dari yang hamil (dzawat al-makhad) atau yang hamil— “maka padanya bint makhad betina, jika tidak ada bint makhad maka ibn labun jantan. Maka jika mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh lima maka padanya bint labun betina”—dan ibn labun adalah yang berusia dua tahun dari unta dan masuk tahun ketiga; karena induknya sudah waktunya melahirkan sehingga menjadi labun yaitu yang memiliki susu— “Maka jika mencapai empat puluh enam sampai enam puluh maka padanya hiqqah”—dan hiqqah dari unta adalah yang berusia tiga tahun dan masuk tahun keempat, dan dinamakan demikian; karena berhak ditinggali pejantan, dan pada jantan berhak menjadi pejantan pemacak, atau karena berhak untuk dinaiki dan dimuati— “Maka jika mencapai empat puluh enam sampai enam puluh maka padanya hiqqah yang siap dikawin pejantan. Maka jika mencapai enam puluh satu sampai tujuh puluh lima maka padanya jadza’ah”—dan jadza’ah dari unta yang berusia empat tahun dan masuk yaitu masuk tahun kelima, dinamakan demikian; karena telah tanggal gigi depannya yaitu gugur, dan dikatakan karena sempurna giginya— “Maka jika mencapai tujuh puluh enam sampai sembilan puluh maka padanya dua bint labun. Maka jika mencapai sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh maka padanya dua hiqqah yang siap dikawin pejantan. Maka jika bertambah atas seratus dua puluh maka pada setiap empat puluh ekor bint labun, dan pada setiap lima puluh ekor hiqqah.”
Dan kambing yang wajib pada kurang dari dua puluh lima ekor unta adalah jadza’ah domba, yaitu yang telah tanggal gigi depannya yaitu menyempurnakannya atau menggugurkannya, baik mencapai satu tahun atau kurang darinya, meskipun yang benar adalah yang mencapai satu tahun atau kurang darinya dengan tidak sampai enam bulan. Dan mencukupi untuk menggantikan jadza’ah domba atau untuk menggantikan jadza’ah domba adalah tsaniyah kambing yaitu yang berusia dua tahun menurut pendapat yang sahih, dan dikatakan satu tahun.
Dan yang mengeluarkan yaitu yang mengeluarkan zakat bisa memilih dalam pengeluaran dari kambing antara jadza’ah domba atau tsaniyah kambing menurut pendapat yang paling sahih; karena kambing mencakup keduanya. Dan disyaratkan dalam yang dikeluarkan—yaitu kambing—atau selainnya dari hal-hal yang kita keluarkan sebagai zakat disyaratkan padanya atau disyaratkan dalam yang dikeluarkan bahwa harus sehat, meskipun yang dizakati darinya sakit jika mampu mendapatkan yang sehat, yaitu jika harta-hartanya meskipun sakit sekalipun seharusnya dia mengeluarkan yang sehat jika mampu melakukan itu. Jika tidak mampu mendapat yang sehat maka wajib mengeluarkan nilai yang sehat dari uang yang sahih yang dominan dalam transaksi ahli sedekah atau pemilik harta-harta yang dizakati dengan memperhatikan yang lebih menguntungkan bagi keduanya. Dan barangsiapa diwajibkan dalam zakat mengeluarkan bint makhad dari unta lalu tidak memilikinya dan dia memiliki bint labun maka memberikannya untuk zakat dan mengambil dua kambing atau dua puluh dirham dari perak, atau nilai salah satunya jika sama dengan memperhatikan bahwa pilihan ada pada yang menyerahkan, baik itu pemilik atau petugas zakat.
Adapun nisab zakat sapi, maka nisab pertama zakat sapi adalah tiga puluh ekor sapi. Kita katakan nisab pertama zakat unta adalah lima ekor unta, tetapi zakat sapi, nisab pertama zakat sapi adalah tiga puluh ekor sapi, dan padanya tabi’ dari sapi yaitu yang berusia satu tahun dan masuk tahun kedua. Dan pada setiap empat puluh ekor musinnah dari sapi, yaitu yang berusia dua tahun dan masuk tahun ketiga. Dan demikianlah kelebihan dihitung atas dasar ini, maka pada setiap tiga puluh ekor tabi’, dan pada setiap empat puluh ekor musinnah berapa pun jumlahnya. Dan itu berdasarkan hadits Mu’adz: “Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil dari penduduk Yaman dari setiap orang baligh satu dinar, dan dari sapi pada setiap tiga puluh ekor tabi’ atau tabi’ah, dan dari setiap empat puluh ekor musinnah.”
Dan nisab pertama kambing adalah empat puluh ekor dan padanya seekor kambing. Dan pada seratus dua puluh satu ekor dua kambing. Dan pada dua ratus satu ekor tiga kambing. Kemudian pada setiap seratus ekor seekor kambing. Dan itu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dalam surat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu kepadanya tentang sedekah yang wajib pada kambing: “Jika mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh dan seratus ekor kambing, yaitu jika mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh dan seratus—seekor kambing—yaitu padanya seekor kambing— Maka jika bertambah atas dua ratus sampai tiga ratus maka padanya tiga kambing. Maka jika bertambah atas tiga ratus maka pada setiap seratus ekor seekor kambing.”
Dan kita telah membahas tentang khultah (percampuran) atau zakat khultah dan sejauh mana pengaruhnya dalam zakat sebelumnya ketika kita berbicara tentang keumuman personal berkaitan dengan zakat. Dan di sini datang pembahasan tentang zakat syirkah (persekutuan) dan khultah dalam ternak. Maka harta bersama dari ternak yaitu yang bersama antara dua orang, harta bersama dari ternak wajib zakatnya jika mencapai nisab, baik syirkah itu secara syuyu’ (tidak terbagi) atau secara ikhtilath (bercampur) menurut jumhur fuqaha, dan dengan syarat kesatuan tempat penggembalaan pagi hari, tempat kembali sore hari, tempat minum, tempat pemerahan, pejantan, penggembala, dan berlalunya satu tahun penuh atas syirkah, dan ini mazhab Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad dan jumhur fuqaha dari sahabat dan tabi’in, meskipun fuqaha mazhab berbeda pendapat di antara mereka dalam sebagian syarat-syarat ini. Sementara sebagian ashab (murid) Malik berkata: tidak diperhitungkan dalam khultah kecuali dua syarat: penggembala dan tempat gembalaan. Syafi’iyah dan Hanabilah berkata: disyaratkan padanya tempat penggembalaan pagi hari, tempat kembali sore hari, tempat minum, pejantan, penggembala, dan tempat pemerahan selama satu tahun penuh, maka dizakati dengan zakat satu orang.
Dan Abu Hanifah berkata: tidak ada pengaruh khultah dalam zakat, di mana nisab diperhitungkan untuk setiap satu dari para sekutu secara terpisah. Maka jika mencapai nisab pada hartanya sendiri maka wajib zakatnya, dan jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya. Dan menurut ini jika bersekutu—yaitu berdasarkan itu—jika bersekutu dua orang dalam khultah kambing misalnya, jumlahnya mencapai nisab empat puluh ekor, untuk setiap satu dari mereka dua puluh ekor atau kurang atau lebih maka tidak ada zakat atas satu pun dari mereka; karena dia tidak memiliki nisab lengkap sendiri. Dan jika memiliki bersama delapan puluh ekor untuk setiap satu dari mereka empat puluh ekor maka wajib atas setiap satu dari mereka seekor kambing; karena dia memiliki nisab tersendiri, dan menurut ini wajib pada delapan puluh ekor dua kambing.
Ini mazhab siapa? Ini menurut mazhab Abu Hanifah; karena kita sebutkan sebelumnya bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada pengaruh khultah dalam zakat, dan oleh karena itu—sebagaimana kita katakan—dia berpendapat bahwa jika ada khultah antara dua orang dalam kambing misalnya, dan untuk setiap satu dari mereka dua puluh ekor kambing, dan jumlahnya empat puluh ekor, maka menurut beliau tidak wajib zakat pada kambing ini. Mengapa? Karena harta setiap satu secara terpisah tidak mencapai nisab zakat, dan oleh karena itu tidak wajib zakatnya. Dan oleh karena itu sebagaimana kita katakan, yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada pengaruh khultah dalam zakat, tidak dalam kadar yang wajib dan tidak dalam nisab. Dan setiap satu dari mereka—yaitu dari dua sekutu—menzakati hartanya sendiri jika mencapai nisab, maka jika tidak mencapai nisab maka tidak ada zakatnya bahkan jika mencapai nisab dengan menggabungkannya kepada harta yang lain. Tetapi—sebagaimana kita katakan—mazhab jumhur fuqaha mewajibkan zakat dalam hal jika untuk setiap satu dari mereka dua puluh ekor, dan masing-masing ditambahkan kepada yang lain sehingga mencapai empat puluh ekor. Mengapa? Karena mereka—sebagaimana kita katakan—berpendapat bahwa khultah berpengaruh dalam zakat. Dan yang rajih (kuat) adalah mazhab jumhur fuqaha.
Maka hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Tidak dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara yang berkumpul karena takut sedekah”. Dan disyaratkan dalam khultah menurut jumhur bahwa kedua sekutu dari ahli zakat dengan terwujudnya syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya tentang tempat penggembalaan pagi hari, tempat gembalaan, tempat minum, penggembala dan lainnya. Maka jika salah satu dari kedua sekutu bukan Muslim maka khultahnya tidak diperhitungkan, dan tidak ada pengaruhnya dalam nisab di mana diperhitungkan apa yang dimiliki Muslim saja. Maka jika mencapai nisab dizakati sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dalam nisab setiap jenis, jika tidak maka tidak.
Nisab dan berlalunya haul dalam zakat binatang ternak: Terbukti dari yang diriwayatkan dari hadits-hadits bahwa binatang ternak memiliki nisab sebagaimana kita katakan, maka tidak ada zakat padanya di bawah lima ekor unta, dan tidak ada zakat padanya di bawah empat puluh ekor kambing, dan tidak pada kurang dari tiga puluh ekor sapi dan kerbau dan lainnya sama, dan bahwa apa yang di antara batasan-batasan adalah ma’fu (dimaafkan) tidak dihitung zakatnya. Maka apa yang di antara tiga puluh dan empat puluh ekor sapi adalah ma’fu, yaitu tidak wajib zakatnya. Artinya jika memiliki misalnya dari sapi tiga puluh ekor—sebagaimana kita katakan—wajib zakatnya mengeluarkan tabi’, maka jika alih-alih tiga puluh ekor tiga puluh sembilan ekor juga mengeluarkan tabi’ juga.
Jadi yang bertambah dari tiga puluh sampai sebelum empat puluh adalah ma’fu, yaitu tidak ada zakatnya. Maka apa yang di antara tiga puluh dan empat puluh ekor sapi adalah ma’fu. Dan apa yang di antara dua puluh lima dan tiga puluh lima adalah ma’fu, dan telah disebutkan nash tentang itu.
Tidak diragukan lagi bahwa takaran-takaran ini jika dinilai dengan uang di zaman kita akan menjadi jumlah yang besar, dan bahwa hadits-hadits menunjukkan bahwa nilainya lebih rendah dari itu pada masa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menetapkan pengganti dua ekor kambing dengan dua puluh dirham, dan ini mengharuskan bahwa nilai seekor kambing adalah sepuluh dirham, dengan demikian nilai empat puluh ekor kambing secara keseluruhan sekitar empat ratus dirham. Maka jika kita ingin menerapkan zakat di zaman kita, kita melihat takaran-takaran yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tanpa menyimpang darinya, kemudian kita melihat nilainya di zaman kita, maksudnya kita melihat empat ratus dirham itu berapa nilainya dengan pound Mesir atau riyal Saudi dan sebagainya? Maka jika nilai barang-barang ini mencapai nisab, dalam keadaan ini zakat harus dikeluarkan.
Dan Abu Hanifah dari kalangan fuqaha jumhur membolehkan membayar zakat dengan nilainya, maksudnya ketika kita mengatakan: kita menilai atau melihat nilai ini yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang telah menjelaskan bahwa nilai empat puluh ekor kambing secara keseluruhan sekitar empat ratus dirham, kemudian kita melihat berapa nilai empat ratus dirham ini dengan mata uang yang kita gunakan sekarang, dengan pound Mesir atau riyal Saudi sebagai contoh. Maka jika nilai kambing-kambing ini mencapai nisab, zakat harus dikeluarkan.
Ini tentu saja menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan: boleh mengeluarkan nilai dalam zakat, namun tentu saja jumhur fuqaha melarang hal itu, dan mereka mengatakan harus mengeluarkan zakat dari jenis harta yang diwajibkan padanya. Kita katakan bahwa Abu Hanifah dari kalangan fuqaha jumhur membolehkan membayar zakat dengan nilainya, dan kita telah melaksanakan takaran Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam karena nilai harta menggantikan kedudukannya. Bahwa tanpa keraguan, mengambil nilai itu sesuai dengan semangat zaman, dan lebih mendekatkan antara pemilik harta, sebagaimana halnya pada masa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
Maka jika telah terlewatkan pembayaran harta dengan bendanya sendiri, maka tidak akan terlewatkan dari kita memberikan kepada orang fakir nilai-nilainya, dan juga tidak akan terlewatkan dari kita mendekatkan antara modal-modal, dan ini adalah hal yang diperhatikan dalam takaran-takaran Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Di sini kita perhatikan beberapa hal:
Pertama – bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menetapkan nilai seekor kambing dengan sepuluh dirham, dengan demikian nisab zakat mencapai nilainya secara keseluruhan empat ratus dirham, dan bahwa dalam setiap empat puluh ekor kambing ada satu ekor kambing, artinya kadar zakat sama dengan seperempat dari sepersepuluh, yaitu dua setengah persen.
Kedua – bahwa kita harus mengandaikan bahwa nilai lima ekor unta adalah empat ratus dirham, namun zakatnya adalah seekor kambing, yaitu kadarnya sepuluh dirham, maka kadarnya juga 2,5%.
Ketiga – bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menetapkan nisab perak dengan dua ratus dirham, dengan demikian ada perbedaan dari segi nilai antara nisab kambing dan nisab uang, dan selain itu tidak ada yang mewajibkan kesamaan nisab atau nilainya dalam semua hal. Kita katakan ada perbedaan dari segi nilai antara nisab kambing dan nisab uang, namun dalam nisab kambing -sebagaimana kita katakan- empat ratus dirham, dan dalam nisab uang dua ratus dirham. Kita katakan: ada perbedaan dalam nilai, tetapi tidak ada yang mewajibkan kesamaan nisab atau nilainya dalam semua hal.
Dan mungkin hikmah dalam mengurangi nisab, yaitu batas minimal kekayaan untuk uang, adalah bahwa uang dalam kebanyakan keadaannya adalah hasil dan pertumbuhan dari sumber-sumber lain, meskipun ia sendiri layak menjadi jalan menuju sumber-sumber di belakangnya. Adapun kambing, maka ia sendiri adalah sumber dan di dalamnya ada pertumbuhan, dan barang dagangan memiliki pertumbuhan yang lebih jelas daripada pertumbuhan hewan ternak.
Kami cukupkan sampai di sini kuliah ini, dan kami akan melanjutkan -Insya Allah- pada kuliah berikutnya. Saya titipkan kalian kepada Allah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4 – Zakat dalam Uang dan Perhiasan
Lanjutan: Hewan yang Wajib di Dalamnya Zakat, dan Syarat-syarat Zakatnya
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada orang yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, Sayyidina Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita telah membicarakan pada kuliah sebelumnya tentang zakat pada hewan, dan yang kita maksud adalah unta, sapi, dan kambing. Dan kita telah menjelaskan nisab zakat pada setiap jenisnya, dan kadar yang harus dikeluarkan dari nisab ini. Dan kita masih membicarakan tentang zakat pada hewan, maka kita katakan: ada perbedaan dari segi nilai antara nisab kambing dan nisab uang. Telah jelas bagi kita bahwa nisab kambing setelah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa nilai seekor kambing adalah sepuluh dirham, maka nilai nisab kambing yaitu empat puluh ekor setara dengan empat ratus dirham. Ini adalah nisab kambing.
Adapun nisab uang, kita katakan dengan perak adalah dua ratus dirham. Jadi nisab kambing lebih besar dari nisab uang. Nisab kambing empat ratus dirham, dan nisab uang hanyalah seratus dirham. Di sini timbul pertanyaan: mengapa ada perbedaan ini? Kita katakan: tidak ada yang mewajibkan kesamaan nisab atau nilainya dalam semua hal. Dan mungkin hikmah dalam mengurangi nisab, yaitu batas minimal kekayaan untuk uang, adalah bahwa uang dalam kebanyakan keadaannya adalah hasil dan pertumbuhan dari sumber-sumber lain, meskipun ia sendiri layak menjadi jalan menuju sumber-sumber di belakangnya.
Adapun hewan ternak, maka ia sendiri adalah sumber dan di dalamnya ada pertumbuhan. Dan barang dagangan memiliki pertumbuhan yang lebih jelas daripada pertumbuhan hewan ternak. Dan dari pertumbuhan hewan ternak ada yang masuk dalam kebutuhan pokok seperti susunya dan sebagian dagingnya, oleh karena itu nisab padanya lebih besar dari yang lain, yaitu jenis uang. Dan apa yang ada di antara batas-batas dalam takaran-takaran adalah tempat pembebasan.
Kesimpulan dalam perbedaan antara nisab uang dan nisab kambing sebagai contoh adalah bahwa hewan ternak ini termasuk kambing adalah pertumbuhan yang masuk dalam kebutuhan pokok, seperti manusia membutuhkan sebagian manfaatnya, oleh karena itu diperhatikan atau diperhitungkan keadaan mukallaf dalam hal ini. Namun uang pada hakikatnya adalah pertumbuhan dari sumber-sumber lain, oleh karena itu tidak ada yang menghalangi untuk membebankan zakat padanya pada dua ratus dirham.
Dan berputarnya haul (satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat hewan ternak sebagaimana kita katakan. Maka jika haul telah berlalu dan nisab telah berkurang, maka zakat tidak wajib. Artinya jika seseorang memiliki di awal tahun empat puluh ekor kambing, kita katakan nisab telah sempurna. Apakah wajib baginya mengeluarkan zakat sekarang ketika ia memiliki empat puluh ekor kambing yaitu nisab? Kita katakan: tidak, bahkan harus berlalu haul lengkap atas kepemilikannya terhadap nisab ini. Maka jika haul lengkap ini tidak berlalu, dan setelah enam bulan sebagai contoh dari kepemilikannya terhadap nisab ini, nisab tidak ada atau berkurang sedikit hingga akhir tahun, apakah diambil darinya zakat? Tidak diambil darinya zakat; karena syaratnya adalah memiliki nisab, dan haul berlalu atas kepemilikannya terhadap nisab ini. Maka jika haul telah berlalu dan nisab telah berkurang, maka zakat tidak wajib. Dan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu haul padanya.”
Dan jika harta zakat berkurang di tengah haul dari nisab, padahal ia mencapainya di awalnya dan mencapainya di akhirnya, maksudnya nisab ada di awal haul, tetapi tidak mencapai nisab di tengah haul, namun mencapainya di akhir haul, apa yang kita lakukan dalam keadaan ini? Kita katakan: jika harta zakat berkurang di tengah haul dari nisab padahal ia mencapainya di awal dan mencapainya di akhir, kita katakan menurut Abu Hanifah dan Syafi’iyyah tidak ada zakat. Dan menurut Malikiyyah, yang diperhitungkan adalah kesempurnaannya di awal haul dan akhirnya, dan tidak diperhitungkan kekurangannya di tengahnya. Tetapi jika hilang semuanya, nisab dimulai dari awal.
Kita katakan: kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa jika harta atau nisab ada di awal haul, tetapi berkurang di tengah haul, kemudian sempurna di akhir haul, apa yang kita lakukan? Pendapat fuqaha dalam hal ini: Imam Abu Hanifah dan Syafi’iyyah mengatakan tidak ada zakat, seolah-olah mereka mensyaratkan bahwa nisab harus terus berlanjut sepanjang haul secara sempurna. Maka jika berkurang di tengah haul, mereka mengatakan tidak wajib zakat; karena mereka mensyaratkan bahwa nisab harus terus berlanjut sempurna selama haul. Maka jika berkurang di bagian mana pun dari haul, tidak wajib padanya zakat. Namun menurut Malikiyyah tidak mengambil pendapat ini, dan mengatakan yang penting bagi kita dalam hal ini adalah kesempurnaan nisab di awal haul dan di akhir haul, dan tidak diperhitungkan kekurangannya di tengahnya, seolah-olah Malikiyyah menyelisihi Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dalam hal ini.
Kita katakan bahwa Hanafiyyah dan Syafi’iyyah mengatakan bahwa jika nisab berkurang di tengah haul, tetapi sempurna di akhirnya, mereka mengatakan tidak wajib zakat. Mengapa? Mereka mengatakan: karena disyaratkan menurut mereka bahwa nisab harus terus berlanjut sempurna di seluruh masa haul. Namun Malikiyyah mengatakan bahwa yang penting bagi kita adalah adanya nisab di awal haul dan di akhir haul, dan tidak penting bagi kita kekurangan yang terjadi di tengah haul. Dan berdasarkan hal itu, maka zakat wajib menurut Malikiyyah. Tetapi jika hewan ternak bertambah di tengah haul, maksudnya bertambah di tengah haul dengan melahirkan, apakah diambil darinya zakat? Artinya apakah zakat diambil dari pokok nisab dan pertumbuhannya tanpa memperhatikan pertumbuhan itu telah berlalu haul padanya atau belum berlalu haul padanya? Ataukah zakat diambil dari apa yang telah berlalu haul padanya dan tidak diambil sesuatu dari pertumbuhan hingga berlalu haul padanya?
Asumsi yang dibuat fuqaha dalam masalah ini adalah bahwa kita mengandaikan sebagai contoh bahwa di awal haul seseorang memiliki empat puluh ekor kambing. Maka di sini ia memiliki nisab. Dan di tengah haul pertumbuhannya bertambah atau kambing-kambing ini bertambah hingga nisab melebihi itu. Maka fuqaha mengatakan: pertambahan ini yang terjadi, dan mari kita asumsikan di tengah tahun, apakah pertumbuhan ini, atau pertambahan yang terjadi pada nisab, haulnya adalah haul pokok ataukah ia memiliki haul tersendiri dari waktu keberadaannya? Pertambahan yang terjadi di tengah haul pada nisab ini, apakah ia memiliki awal tahun tersendiri ataukah ia ditambahkan ke tahun pokok dan zakatnya adalah zakat pokok? Ini adalah masalah yang diperselisihkan fuqaha.
Pertama – Fuqaha sepakat bahwa pertumbuhan jika tidak tetap dalam kepemilikan orang yang wajib padanya zakat hingga akhir haul, dengan menjualnya atau menyembelihnya sebelum berlalu haul padanya – maka tidak ada zakat padanya. Dan jika tidak demikian, maka fuqaha berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Maksudnya jika ia tidak membuangnya tetapi ia ada, maka apakah -sebagaimana kita katakan- pertumbuhan ini dan pertambahan ini mengambil hukum haul pokok, dan zakatnya adalah zakat pokok dalam hal haul, ataukah kita memulai untuk pertambahan ini haul tersendiri dan ia memiliki haul tersendiri dari haul pokok? Saya katakan: Fuqaha berbeda pendapat dalam hal itu. Syafi’iyyah berpendapat bahwa tidak diambil zakat kecuali pada apa yang telah berlalu haul padanya, dan apa yang bertambah di tengah tahun ditunggu hingga berlalu haul untuknya; karena syarat zakat adalah berputarnya haul dan itu tidak terwujud padanya. Dan mengambil zakatnya padanya akan menyalahi nash; karena Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam meniadakan kewajiban zakat hingga berlalu haul. Maka jika diambil darinya, itu adalah kewajiban tanpa dalil, bahkan bertentangan dengan nash hadits.
Ringkasan Pendapat Mazhab Syafiiyah
Ringkasan pendapat mazhab Syafiiyah dalam hal ini adalah mereka mengatakan bahwa pokok (harta awal) memiliki haulnya sendiri, dan pertambahan atau perkembangan memiliki haul yang mandiri. Artinya ketika haul telah berakhir untuk pokok, kita mengambil zakatnya dan mendistribusikannya, tetapi kita tidak mengambil dari pertambahan ini sampai berlalu haul atas pertambahan ini. Seolah-olah mereka menjadikan untuk pokok ada haul, dan untuk pertambahan ada haul yang mandiri. Karena jika kita mengambil zakat dari pertambahan ini ketika datang haul pokok, berarti pertambahan ini belum dilewati satu tahun penuh, dan dengan demikian kita telah menyelisihi hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menyatakan bahwa zakat tidak diambil kecuali jika telah berlalu haul yang lengkap.
Saya katakan: Mazhab Syafiiyah mengatakan bahwa zakat tidak diambil kecuali dari yang telah berlalu haulnya, yaitu dari kambing atau binatang ternak ini. Adapun yang bertambah di pertengahan tahun ditunggu, artinya tidak dizakati bersama pokoknya, melainkan ditunggu sampai berlalu haul untuknya. Pandangan mereka dalam hal ini atau dalil mereka adalah bahwa syarat zakat adalah berlalunya haul, dan ini belum terwujud untuk pertambahan atau penambahan ini. Oleh karena itu mengambil zakat dari penambahan ini akan menyelisihi nash, yaitu jika kita mengambil darinya zakat saat sempurna haul pokok, seolah-olah kita mengambil darinya sebelum berlalu haul, dan dalam hal itu ada penyelisihan terhadap nash. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meniadakan wajibnya zakat sampai berlalu haul.
Pendapat Kedua: Mazhab Hanabilah dan Malikiyah
Kedua: Sebagian ulama seperti Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa wajib zakat padanya. Mengapa? Jadi Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa zakat wajib pada pertambahan atau penambahan ini. Seolah-olah mereka menjadikan haul penambahan ini adalah haul pokok. Maka jika berlalu haul atas pokok, kita mengambil darinya zakat, dan juga mengambil dari pertambahan yang terjadi di pertengahan haul atau penambahan yang terjadi di pertengahan haul. Pandangan mereka dalam hal ini adalah bahwa ia sejenis dengannya, yaitu penambahan sejenis dengan pokok, maka menjadi tabi’ (mengikuti) pokok, dan digabungkan dengan zakatnya, dan haulnya dihitung dengan haul pokok. Karena ia menyerupai pertambahan yang menyatu seperti gemuk dan sejenisnya. Berdasarkan itu zakat pada penambahan dan pokok bersama-sama, ini menurut Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka penambahan dan pertambahan ditambahkan ke pokok, dan dizakati atau pertambahan atau penambahan ini dizakati bersama haul pokok. Sebagaimana kami katakan bahwa mereka bersandar dalam hal itu kepada bahwa penambahan ini berasal dari jenis pokok, maka menjadi tabi’nya, dan mengambil hukumnya, dan haul penambahan dihitung dengan haul pokok.
Pendapat Ketiga: Abu Hanifah
Pendapat ketiga adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian fuqaha Irak, mereka membedakan dalam hal ini. Mereka berkata: Jika yang besar (induk) atau sebagiannya masih ada meskipun satu ekor, maka wajib zakat padanya. Dan jika tidak tersisa dari yang besar yang telah berlalu haulnya satu ekor pun, maka tidak wajib zakat padanya. Artinya pendapat ketiga yaitu pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan: Kita lihat pokoknya, jika pokok masih ada atau masih tersisa meskipun satu ekor, maka dalam hal ini dizakati pertambahannya bersama pokok. Tetapi misalkan pokok ini tidak ada lagi ketika datang haul, atau tidak tersisa darinya sesuatu, maka dalam hal ini dia berkata: Kita mulai haul baru untuk pertambahan ini.
Dasar yang menjadi landasan pendapat tersebut adalah bahwa jika keluar dari kepemilikannya semua induk, yaitu pokok yang melahirkan penambahan ini, jika keluar dari kepemilikannya semua induk, berarti nishab asli telah hilang di pertengahan tahun. Dan jika pokok hilang maka tidak ada pertimbangan untuk tabi’, dan zakat tidak wajib pada anak (hasil ternak) kecuali karena mengikuti pokok. Selama yang diikuti (pokok) ada dalam bentuk apa pun, maka zakat wajib pada semuanya. Dan jika yang diikuti hilang, hilanglah makna ikut-mengikuti dan wajib zakat pada anak ternak berdasarkan bahwa ia adalah pokok yang berdiri sendiri, artinya akan memiliki haul baru. Ini dari yang dikatakan para fuqaha berkaitan dengan masalah ini, yaitu masalah anak ternak yang terjadi di pertengahan haul, apakah dizakati dengan zakat pokok, dan mengambil hukum pokok dalam zakatnya, dan haulnya adalah haul pokok?
Kami katakan: Para jumhur fuqaha berbeda pendapat dalam hal itu. Sebagian mereka seperti Syafiiyah berkata bahwa pokok memiliki haul yang mandiri, dan tabi’ atau hasil atau pertambahan memiliki haul yang mandiri sendiri agar kita tidak menyelisihi hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun Hanabilah dan Malikiyah mengatakan bahwa pertambahan atau penambahan yang terjadi di pertengahan haul ditambahkan ke pokok, dan dizakati dengan haul pokok. Mengapa? Mereka berkata: Karena penambahan ini berasal dari jenis pokok, maka menjadi tabi’nya, dan zakatnya dengan haulnya sama persis, yaitu haul pokok menjadi haul anak ternak.
Adapun pendapat ketiga yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, dia memiliki pendapat dalam hal ini, dia berkata: Jika kita dapati atau jika tersisa pokok yaitu induk yang melahirkan anak ternak ini, jika tersisa sampai haul yaitu haulnya meskipun hanya satu ekor, maka dalam hal ini anak ternak digabungkan ke pokok, dan haul pokok adalah haul anak ternak, dan zakat dikeluarkan untuk pokok dan pertambahan yaitu penambahan. Adapun jika tidak ada darinya meskipun satu ekor, dia berkata: Dalam hal ini tidak ada hubungan antara pertambahan dengan pokok, dan karenanya penambahan tidak dizakati dengan haul pokok, melainkan memiliki haul yang mandiri.
Masalah Terkait: Kepemilikan yang Belum Mencapai Nishab di Awal Haul
Dari yang berkaitan dengan topik ini ada bentuk yang disebutkan para fuqaha yaitu keadaan di mana jumlah tidak menyempurnakan nishab di awal haul, kemudian sempurna dengan hasil ternak di tengahnya. Apakah haul dihitung dari awal tahun, ataukah dari waktu sempurna nishab dengan anak ternak? Yaitu misalkan seseorang memiliki di awal tahun tiga puluh ekor kambing, kemudian setelah beberapa waktu di pertengahan haul jumlahnya mencapai nishab. Dia memiliki di awal haul tiga puluh ekor kambing, yaitu belum memiliki nishab lengkap. Tetapi setelah beberapa waktu memiliki nishab lengkap. Apakah nishab dihitung dari awal kepemilikan tiga puluh ekor, ataukah dihitung dari waktu sempurna nishab?
Saya katakan: Jumhur fuqaha berkata: Sesungguhnya permulaan haul adalah dari permulaan sempurna nishab. Karena haul belum berlalu atas nishab yang sempurna, dan karena berlalunya haul dalam perdagangan dan uang dimulai dari waktu sempurna nishab, dan tidak ada pertimbangan untuk waktu sebelumnya. Dan karena berlalunya haul untuk menetapkan kekayaan, dan untuk adanya pertumbuhan yang merupakan syarat zakat. Dan karena sebab wajib adalah nishab, maka jika diwajibkan zakat sebelum sempurnanya, itu berarti ada akibat sebelum ada sebab. Berdasarkan itu permulaan haul adalah dari waktu sempurna nishab.
Ini yang dikatakan para fuqaha berkaitan dengan topik apakah haul dihitung sejak sempurna nishab ataukah sejak kepemilikan pokok harta? Sebagaimana kami katakan, jumhur fuqaha mengatakan: Bahwa nishab atau haul tidak dihitung kecuali dari waktu nishab, dan telah disebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan hal itu.
Pelajaran 5: Sisa Jenis-Jenis Zakat Dan Faktor-Faktor Yang Membantu Mewujudkan Keumuman Di Dalamnya
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
- Zakat pada Dua Logam Mulia dan Perhiasan
Zakat pada Emas dan Perak
Kita beralih setelah itu kepada zakat atau pembahasan tentang zakat emas dan perak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Telah aku maafkan untuk kalian dari sedekah kuda dan budak, maka keluarkanlah sedekah perak, dari setiap empat puluh dirham satu dirham, dan tidak ada pada seratus sembilan puluh sesuatu, maka jika mencapai dua ratus maka padanya lima dirham.” Dan diriwayatkan Abu Dawud juga dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Jika engkau memiliki dua ratus dirham, dan berlalu haulnya maka padanya lima dirham, dan tidak wajib atasmu sesuatu—yaitu pada emas—sampai engkau memiliki dua puluh dinar, dan berlalu haulnya maka padanya setengah dinar.” Sesungguhnya dua hadits ini menunjukkan tiga perkara:
Pertama – Bahwa nishab zakat pada dua logam mulia—dan yang kami maksud dengan dua logam mulia adalah emas dan perak—bahwa nishab zakat pada dua logam mulia adalah dua ratus dirham untuk perak, dan dua puluh mitsqal untuk emas. Artinya perak jika mencapai seratus dirham atau lebih maka wajib zakatnya, karena nishabnya dua ratus dirham. Demikian juga emas jika mencapai dua puluh mitsqal atau lebih maka wajib zakatnya, karena nishabnya dua puluh mitsqal emas.
Kedua – Bahwa harus berlalu haul agar harta dapat berkembang dalam masa ini, dan agar dia mencapai tingkat kekayaan yang memiliki kelebihan untuk dikembalikan kepada yang tidak memiliki harta. Berdasarkan itu terwujud sebab wajib yaitu nishab, dan syaratnya adalah berlalunya haul. Jadi artinya hadits menjelaskan pertama nishab emas dan nishab perak. Nishab emas seratus dirham, dan nishab perak dua puluh mitsqal. Juga hadits menjelaskan kepada kita bahwa tidak wajib zakat kecuali jika berlalu haul, dan berlalu haul atas kepemilikannya terhadap nishab ini. Karena berlalunya haul adalah yang mengakibatkan pertumbuhan, bahwa harus berlalu haul agar harta dapat berkembang dalam masa ini. Karena umumnya tidak terjadi pertumbuhan kecuali dengan berlalunya haul. Maka harus berlalu haul ini. Berlalunya haul adalah syarat dari syarat-syarat yang harus terpenuhi agar wajib zakat pada emas dan perak.
Ketiga – Perkara yang ditunjukkan hadits kepada kita: Bahwa pasti di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam nilai dua ratus dirham adalah nilai dua puluh mitsqal emas, karena keduanya satu jenis zakat yang berhadapan dengan binatang ternak, buah-buahan, dan tanaman. Artinya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selama telah menjelaskan kepada kita bahwa nishab perak adalah seratus dirham, dan nishab emas adalah dua puluh mitsqal, berarti nilainya sama atau dua puluh mitsqal senilai dengan dua ratus dirham. Bahwa pasti di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam nilai dua ratus dirham adalah nilai dua puluh mitsqal emas, karena keduanya satu jenis zakat, yaitu zakat dua logam mulia. Artinya dua puluh mitsqal senilai dua ratus dirham, dan dua ratus dirham senilai dua puluh mitsqal.
Jika nilainya satu di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka telah terbukti dalam ekonomi dunia bahwa emas saja yang layak sebagai ukuran untuk menentukan nilai-nilai sesuatu. Oleh karena itu nilainya tidak berubah di berbagai zaman pada umumnya, karena ia timbangan tetap untuk menentukan nilai yang ada pada sesuatu. Dan terbukti bahwa perak tidak demikian. Jika keduanya telah bertemu dalam hal keduanya bersama-sama adalah uang utama di awal Islam, maka nilai perak berbeda dengan berjalannya zaman. Oleh karena itu kita menjadikan emas dalam zakat sebagai satuan penilaian, yaitu selama perak berubah nilainya dan emas tetap, maka dalam hal ini kita harus menganggap bahwa emas adalah satuan penilaian.
Oleh karena itu ketika emas tidak lagi ada dan perak tidak lagi ada, dan emas serta perak tidak lagi menjadi harga barang-barang dan nilai untuk kerusakan, keduanya tidak lagi menjadi uang di zaman ini, dan uang kertas lah yang ada di zaman ini, maka artinya untuk pound Mesir atau riyal Saudi misalnya, orang yang memiliki sejumlah uang ini, pound Mesir atau riyal Saudi, ingin mengeluarkan zakat uang, maka dalam hal ini kita katakan kepadanya: Nilailah yang ada padamu dari harta dengan emas atau dengan perak? Kita katakan: Yang paling tepat dalam hal ini bahwa penilaian dengan emas. Mengapa? Karena emas kokoh nilainya, adapun perak nilainya berubah-ubah. Oleh karena itu sebagaimana kami katakan, seharusnya kita menganggap bahwa emas adalah satuan penilaian di zaman ini.
Tetapi berapa berat dirham yang dianggap dua ratus darinya adalah nishab? Kita dapat memahami itu dari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits lain tentang nishab zakat pada perak. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada pada yang kurang dari lima awaq perak sedekah.” Awaq adalah jamak uqiyah. “Tidak ada pada yang kurang dari lima awaq perak sedekah.” Wariq yang dimaksud adalah perak. Jika semua hadits bertemu mengenai satu makna dalam bab ini, maka kita harus mengatakan: Bahwa lima awaq adalah seratus dirham, artinya satu uqiyah beratnya empat puluh dirham. Dan penentuan nishab dengan berat bukan dengan bilangan. Itu karena di awal Islam tidak ada uang tersendiri untuk bangsa Arab, melainkan mereka menggunakan dirham dan dinar, dan mengambil mata uang negara tetangga. Dan ada tiga jenis dirham, sebagiannya setiap sepuluh dirham beratnya sepuluh dinar, sebagiannya setiap sepuluh dirham beratnya lima dinar yaitu mitsqal, dan sebagiannya setiap sepuluh dirham beratnya tujuh mitsqal. Maka Imam Umar radliyallahu ‘anhu memilih dalam kharaj dan zakat yang berat sepuluh darinya tujuh mitsqal. Mungkin dia memperhatikan bahwa itulah yang berat empat puluhnya satu uqiyah, maka amalnya adalah penerapan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.
Adapun dua puluh mitsqal untuk nishab emas berbeda—sebagaimana kami katakan—kemungkinan di zaman ini kita katakan mencapai rata-rata atau umumnya delapan puluh lima gram emas. Berdasarkan itu yang memiliki uang kertas di zaman ini, baik pound Mesir atau riyal Saudi, sebagaimana kami katakan nishabnya adalah 85 gram emas. Maka jika dia memiliki yang senilai 85 gram emas sebagai nilai mata uang, maka wajib zakat atasnya. Jika yang dimilikinya kurang dari 85 gram emas maka tidak ada zakat atasnya.
Zakat pada Perhiasan yang Diperbolehkan dan yang Diharamkan, serta Pendapat Para Ulama Fikih
Kita berbicara sekarang tentang jenis zakat lain yang berkaitan dengan zakat dua mata uang emas dan perak, yaitu zakat perhiasan. Kita katakan: Para ulama fikih terdahulu dan kemudian sepakat bahwa perhiasan yang diharamkan, yaitu yang terbuat dari emas atau perak untuk laki-laki tanpa keadaan darurat seperti gigi emas, demikian juga bejana-bejana yang diharamkan bagi keduanya (laki-laki dan perempuan), atau perhiasan untuk laki-laki dan perempuan, kita katakan: wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab. Perhiasan yang diharamkan, para ulama fikih sepakat bahwa wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat tentang zakat perhiasan yang diperbolehkan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak?
Laits, mazhab Maliki, mazhab Syafii menurut pendapat yang paling kuat pada mereka, dan mazhab Hanbali dalam zhahir mazhab mereka mengatakan: tidak ada zakat pada perhiasan perempuan yang diperbolehkan baginya berapa pun jumlahnya. Sedangkan mazhab Hanafi, dan ini juga pendapat pada mazhab Syafii, mengatakan: wajib zakat jika telah mencapai nisabnya.
Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama fikih adalah tentang perhiasan yang diperbolehkan, perhiasan dari emas yang diperbolehkan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak wajib? Jumhur (mayoritas) ulama fikih mengatakan bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun mazhab Hanafi dan sebagian ulama fikih mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab perbedaan pendapat para ulama fikih dalam masalah ini adalah karena keraguan tentang perhiasan, apakah ia mirip dengan barang dagangan yang tujuannya adalah manfaat yang diperbolehkan, yang tidak ada zakatnya tanpa perbedaan pendapat, ataukah mirip dengan emas batangan dan emas serta perak yang tujuannya adalah untuk transaksi dalam semua hal, yang wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab tanpa perbedaan pendapat. Maka barangsiapa yang menyerupakan perhiasan dengan barang dagangan yang tujuannya adalah manfaat, ia mengatakan tidak ada zakatnya. Dan barangsiapa yang menyerupakan perhiasan dengan emas batangan dan perak yang tujuannya adalah untuk bertransaksi dengannya, ia mengatakan ada zakatnya. Demikian juga perbedaan pendapat mereka tentang atsar dan nash-nash syariat yang diriwayatkan tentang hal tersebut.
Dalil-Dalil yang Mewajibkan Zakat Perhiasan yang Diperbolehkan
Mereka yang mengatakan wajib zakat pada perhiasan yang diperbolehkan, mereka dan yang sependapat dengan mazhab mereka berdalil dengan nash-nash dan atsar yang mendukung pendapat yang mereka kemukakan. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya: “Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya, dan di tangan anak perempuannya ada dua gelang tebal dari emas—maksudnya gelang yaitu apa yang dipakai perempuan di tangannya untuk berhias, dan bersama perempuan itu ada anak perempuannya, dan di tangan anak perempuannya ada dua gelang tebal dari emas. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: Apakah kamu mengeluarkan zakat ini? Perempuan itu menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Apakah kamu senang Allah memakaimu dengan keduanya dua gelang dari neraka pada hari kiamat? Maka perempuan itu melepaskannya dan melemparkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam seraya berkata: Keduanya untuk Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya.” Hadits ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang berbeda oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasai, dan di dalamnya terdapat sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: “Maka bayarkanlah zakatnya.”
Hadits ini jelas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada perempuan tersebut bahwa zakat itu wajib atas emas yang ada di tangan anak perempuannya, meskipun anak perempuan itu memakainya sebagai perhiasan. Ini jelas bahwa zakat itu wajib—berdasarkan hadits ini—wajib pada perhiasan yang diperbolehkan ini, dengan bukti pernyataan tegas Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu ketika beliau bersabda: “Maka bayarkanlah zakatnya,” artinya keluarkanlah zakat dari emas ini yang ada di tangan anak perempuanmu.
Mereka juga berdalil dengan hadits Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dan melihat di tanganku ada cincin-cincin dari perak. Beliau bertanya: Apa ini wahai Aisyah? Aku menjawab: Aku membuatnya untuk berhias untukmu wahai Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah kamu membayar zakatnya? Aku menjawab: Tidak, atau sekehendak Allah. Beliau bersabda: Itu cukup bagimu dari neraka.” Artinya seakan-akan Nabi shallallahu alaihi wasallam memperingatkan Sayyidah Aisyah—radhiyallahu anha—bahwa jika ia tidak menunaikan zakat, maka ia telah memaparkan dirinya pada neraka jahanam, wal iyadzubillah. Ini jika menunjukkan sesuatu, maka hanya menunjukkan bahwa zakat itu wajib padanya. Ini juga menunjukkan bahwa zakat itu wajib pada perhiasan yang diperbolehkan.
Di antara atsar yang dijadikan dalil oleh yang mengatakan wajib adalah apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dalam masa khilafahnya: bahwa ia menulis kepada Abu Musa Al-Asyari radhiyallahu anhu: “Perintahkan kepada perempuan-perempuan muslimah yang melewati wilayahmu agar menzakati perhiasan mereka, dan jangan menjadikan pinjam-meminjam di antara mereka sebagai tukar-menukar.” Ini juga jelas dan tegas bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Musa Al-Asyari untuk mengambil dari perempuan-perempuan muslimah yang melewatinya zakat perhiasan yang mereka pakai. Ini adalah dalil kewajiban.
Di antaranya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha: “Tidak mengapa memakai perhiasan jika telah dikeluarkan zakatnya.” Dan di antara para tabiin yang diriwayatkan dari mereka pendapat tentang kewajiban adalah: Nakhai, Thawus, Mujahid, Atha, Jabir bin Zaid, Ibnu Sirin, Hasan Bashri, dan lainnya. Inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa zakat itu wajib pada perhiasan yang diperbolehkan.
Dalil-Dalil yang Tidak Mewajibkan Zakat Perhiasan yang Diperbolehkan
Sekarang kita sampai pada dalil-dalil yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan yang diperbolehkan. Penganut mazhab ini, yaitu penduduk Madinah, Malik dan yang sependapat dengan mereka, berdalil dengan hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada perhiasan.” Ini adalah nash dalam masalah ini, bahwa perhiasan yang diperbolehkan ini tidak ada zakatnya.
Penganut mazhab ini juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik rahimahullah dalam Al-Muwaththa dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya: “Bahwa Aisyah radhiyallahu anha memakaikan perhiasan kepada anak-anak perempuan saudaranya, dan mereka adalah anak-anak yatim dalam asuhannya. Ia memakaikan perhiasan kepada mereka tetapi tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan mereka.” Juga di antara dalil yang mereka gunakan adalah bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memakaikan perhiasan kepada anak-anak perempuan saudaranya, namun ia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut. Ini adalah dalil bahwa zakat tidak wajib pada perhiasan yang diperbolehkan, karena seandainya wajib, hal itu tidak akan luput dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ia pasti akan mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai anak-anak perempuan saudaranya.
Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi: “Bahwa Abdullah bin Umar memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak perempuannya dan budak-budak perempuannya, kemudian tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan mereka.” Abdullah bin Umar ini lebih mengetahui tentang syariat, oleh karena itu seandainya ada zakat pada perhiasan yang dipakainya kepada anak-anak perempuannya, niscaya ia akan mengeluarkan zakatnya.
Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibnu Umar bahwa ia menikahkan seorang perempuan dari anak-anak perempuannya dengan mahar sepuluh ribu, lalu ia menjadikan perhiasannya dari jumlah itu empat ribu, maka mereka tidak mengeluarkan zakat darinya.
Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha memakaikan perhiasan emas dan perak kepada anak-anak perempuannya, tetapi tidak menzakatinya senilai kira-kira lima puluh ribu.
Juga dengan apa yang diriwayatkan dari Jabir dan Anas radhiyallahu anhuma bahwa keduanya ditanya tentang perhiasan: apakah ada zakatnya? Keduanya menjawab: Tidak.
Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abu Ubaid dari Qasim bin Muhammad bahwa ia ditanya tentang sedekah perhiasan, lalu ia berkata: “Aku tidak melihat seorang pun yang melakukannya. Aku telah bertanya kepada bibiku yaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka ia berkata: Aku tidak melihat seorang pun yang melakukannya. Sungguh aku memiliki kalung senilai dua belas ratus, tetapi aku tidak menzakatinya.” Artinya aku tidak mengeluarkan zakatnya.
Jadi semua atsar ini—mereka berdalil dengan atsar dan berdalil dengan hadits—semua atsar yang mereka sebutkan dari para sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan bahwa zakat tidak wajib pada perhiasan yang diperbolehkan, karena seandainya wajib, para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui hukum-hukum syariat tidak akan lalai mengeluarkan zakat ini.
Kesimpulan dan Tarjih (Penguatan Pendapat)
Oleh karena itu, setelah menyebutkan mazhab-mazhab dan dalil-dalilnya dalam zakat perhiasan, menjadi jelas bagi kita pertentangan di antara keduanya setelah bantahan dan kritik yang dikemukakan oleh penganut setiap mazhab terhadap dalil-dalil penentang mereka, dan jawaban serta pelemahan terhadapnya. Ketika ada pertentangan antara dalil-dalil, maka tarjih (penguatan) di antara keduanya dilakukan dengan mengompromikan keduanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka dilakukan tarjih antara dalil-dalil, dan diambil yang kuat di antaranya tanpa yang lemah, dan dikuatkan yang paling kuat atas yang kuat, dan seterusnya.
Mengompromikan antara kedua mazhab sekaligus, yaitu yang mengatakan wajib zakat pada perhiasan dan yang mengatakan tidak wajib zakat padanya, aku katakan: mengompromikan kedua mazhab sekaligus tidak mungkin diamalkan karena keduanya bertentangan dalam hukum. Demikian juga karena keseimbangan dalil-dalil pada kedua kelompok dalam keseluruhannya dari segi kekuatan dan kelemahan, maka tidak tersisa kecuali menguatkan salah satu dari dua pendapat atau mazhab atas yang lain.
Karena tarjih dengan makna yang tepat bagi kita dalam konteks ini sulit dicapai mengingat sahihnya dalil-dalil setiap mazhab secara umum, dan pengamalan dengannya di zaman para sahabat, tabiin, dan imam-imam mazhab fikih, maka kita akan cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama fikih dan ulama dalam bidang ini.
Imam Syirazi Asy-Syafii berkata: Tentang perhiasan meskipun untuk pemakaian yang diperbolehkan seperti perhiasan perempuan dan apa yang disediakan untuk mereka, dan cincin perak untuk laki-laki, maka ada dua pendapat: pertama, tidak wajib zakatnya, berdasarkan riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada zakat pada perhiasan.” Dan karena perhiasan disediakan untuk pemakaian yang diperbolehkan, maka tidak wajib zakatnya seperti unta dan sapi yang digunakan untuk bekerja. Maksudnya unta dan sapi yang digunakan manusia untuk pertanian tidak ada zakatnya. Kedua, wajib zakatnya. Imam Syafii beristikharah kepada Allah tentang hal ini dan memilihnya, artinya ia memilih bahwa wajib zakatnya berdasarkan riwayat: “Bahwa seorang perempuan dari Yaman datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya, di tangannya ada dua gelang tebal dari emas. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: Apakah kamu mengeluarkan zakat ini? Perempuan itu menjawab: Tidak. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apakah kamu senang Allah memakaimu dengan keduanya dua gelang dari neraka pada hari kiamat? Maka perempuan itu melepaskannya dan melemparkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam seraya berkata: Keduanya untuk Allah dan Rasul-Nya.” Juga karena perhiasan termasuk jenis harta berharga, maka menyerupai dirham dan dinar.
Ibnu Rusyd berkata setelah menyebutkan atsar Jabir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam “Tidak ada zakat pada perhiasan” sebagai dalil bagi yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan, dan atsar Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya tentang perempuan yang datang bersama anak perempuannya yang di tangan anak perempuannya ada gelang dari emas, maka beliau bertanya kepadanya: “Apakah kamu menunaikan zakat ini?” dan yang telah disebutkan sebelumnya secara lengkap—kedua atsar tersebut lemah, khususnya hadits Jabir.
Al-Mushili berkata dalam bab zakat emas dan perak: Wajib zakat pada emas dan perak yang dicetak, batangannya, perhiasannya, dan bejana-bejananya, baik diniatkan untuk perdagangan atau tidak diniatkan, jika telah mencapai nisab. Allah Taala berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Surah At-Taubah, dari ayat 34) Kewajiban dikaitkan dengan nama emas dan perak, dan ini terdapat dalam semua yang kami sebutkan, karena yang dimaksud dengan menyimpan adalah tidak mengeluarkan zakat. Maka hadits Jabir dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma: “Semua yang tidak kamu tunaikan zakatnya adalah simpanan meskipun tampak, dan apa yang kamu tunaikan zakatnya bukan simpanan meskipun terpendam.” Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata: “Aku memakai gelang-gelang dari emas. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah ini simpanan? Beliau bersabda: Jika kamu tunaikan zakatnya maka bukan simpanan.” Maka dapat ditafsirkan ayat: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat pada keduanya dua gelang dari emas, maka beliau bersabda: “Apakah kalian ingin Allah memakaimu dengan dua gelang dari neraka? Keduanya menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Maka tunaikanlah zakatnya.”
Ini dan bagi mukallaf (orang yang dibebani hukum) untuk memilih apa yang membuat jiwa tenang dari kedua mazhab setelah kita sebutkan nash-nash ini dan dalil-dalil ini secara lengkap, karena masalah ini sangat menyibukkan pikiran kaum muslimin. Kita katakan kepada mukallaf setelah kita menyebutkan dalil-dalil ini, dalil-dalil yang mengatakan wajib dan dalil-dalil yang mengatakan tidak wajib, dan kita sebutkan nash-nash para ulama fikih dalam masalah ini, kita katakan kepada mukallaf: pilihlah apa yang membuat jiwa tenang dari kedua mazhab untuk diamalkan setelah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafii radhiyallahu anhu. Dan barangsiapa yang cenderung untuk mengamalkan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafii setelah istikharahnya, maka itu lebih utama dan lebih baik. Wallahu Tabaraka wa Taala a’lam (Dan Allah Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi lebih mengetahui).
Zakat pada Hasil Pertanian
Jenis Tanaman yang Wajib Dizakati
Kemudian kita beralih kepada zakat hasil pertanian, yaitu apa yang ditumbuhkan bumi dari tanaman. Kita katakan bahwa apa yang ditumbuhkan bumi ada tiga jenis: biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ketiga jenis ini telah dibahas oleh para ulama fikih dari segi kewajiban zakat padanya. Mereka sepakat tentang kewajiban zakat pada sebagian jenis, dan berbeda pendapat pada sebagian lainnya. Setiap kelompok membela pendapat yang dianutnya. Kita akan membahas zakat ini, pertama-tama tentang kewajiban zakat pada biji-bijian.
Para ulama fikih sepakat bahwa zakat wajib pada gandum dan jelai. Yang dimaksud dengan gandum di sini adalah gandum. Ini berdasarkan kesepakatan, artinya mereka mewajibkan zakat pada gandum dan jelai berdasarkan kesepakatan.
Kemudian setelah itu, pandangan mereka berbeda dan pendapat mereka beragam mengenai biji-bijian selain itu. Sebagian berpendapat bahwa zakat wajib pada semua yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan, sementara sebagian lainnya berpendapat wajib pada semua yang ditumbuhkan bumi. Oleh karena itu, kita akan menyebutkan dalil-dalil para ulama fikih dalam hal ini. Seperti yang telah dikatakan, mereka berselisih pendapat setelah sepakat tentang kewajiban zakat pada gandum dan jelai, lalu berbeda pendapat tentang biji-bijian yang wajib dizakati. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib pada semua biji-bijian yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan.
Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan dari biji-bijian. Artinya harus ada dua sifat pada biji-bijian atau tanaman agar kami katakan bahwa zakat wajib padanya. Pertama, harus dapat dijadikan makanan pokok, yaitu manusia dapat memakannya dan hidup darinya. Kedua, dapat disimpan, memungkinkan manusia menyimpannya dan memanfaatkannya sepanjang tahunnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Makanlah dari buahnya ketika berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memanennya.” (Surah Al-An’am, ayat 141)
Sisi pengambilan dalil dari ayat ini, Al-Qarafi dari mazhab Maliki berkata: Para ulama mengatakan ini adalah hukum umum dalam hal-hal ini, dan hukum yang berlaku umum harus didasarkan pada illat (alasan hukum) yang sama, yaitu menurut Malik adalah penyimpanan untuk makanan pokok pada umumnya, karena itu adalah sifat yang sesuai dalam hal makanan pokok untuk menjaga tubuh yang merupakan sebab kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika nikmat besar, maka wajib bersyukur dengan menunaikan zakat. Seolah-olah Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki menjelaskan bahwa diambil dari firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Makanlah dari buahnya ketika berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memanennya”, bahwa itu seharusnya untuk tanaman atau biji-bijian yang dijadikan makanan pokok pada umumnya, karena hal-hal ini menjaga tubuh yang merupakan sebab kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika nikmat besar, maka wajib bersyukur dengan menunaikan zakat. Ini adalah dalil bahwa zakat tidak wajib kecuali pada yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan.
Dari Sunnah, para ulama fikih yang berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan berdalil dengan riwayat dari Abu Said Al-Khudri semoga Allah meridhainya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada sedekah pada biji-bijian dan kurma sampai mencapai lima wasaq, tidak ada sedekah pada kurang dari lima ekor unta, dan tidak ada sedekah pada kurang dari lima uqiyah.” Dalam riwayat Muhammad bin Rafi dari Abdurrazzaq: “Tidak ada pada biji-bijian dan buah-buahan” dengan fathah pada huruf tsa.
Mereka berdalil dengan hadits ini, yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Tidak ada sedekah pada biji-bijian dan kurma sampai mencapai lima wasaq.” Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa sabda Beliau: “Tidak ada sedekah pada biji-bijian dan kurma sampai mencapai lima wasaq” bersifat umum pada semua biji-bijian dan buah-buahan, dan ini hanya berlaku pada yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan. Juga yang mereka jadikan dalil adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Tidak ada sedekah pada sayur-sayuran.” Makna “Tidak ada sedekah pada sayur-sayuran” karena sayur-sayuran tidak dijadikan makanan pokok dan tidak dapat disimpan. Dari ini dipahami bahwa zakat wajib pada yang berkebalikan dengan sayur-sayuran, yaitu yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan bahwa zakat hanya wajib pada yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan saja.
Sebagian ulama fikih lainnya berpendapat bahwa zakat diambil dari semua yang dikeluarkan bumi, tidak ada perbedaan antara jenis yang satu dengan yang lain, tidak antara yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Pada semua yang dikeluarkan bumi ada zakatnya kecuali rumput dan kayu bakar. Namun jika rumput dan kayu bakar ditanam untuk tujuan perdagangan, maka wajib zakat jika mencapai nisab. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi.
Setelah kami paparkan pendapat para ulama fikih mengenai biji-bijian dan apa yang wajib dizakati dari biji-bijian ini dan apa yang tidak—kami berpendapat bahwa pendapat mazhab Hanafi tentang kewajiban zakat pada semua yang dikeluarkan bumi adalah pendapat yang kami pilih, karena keumuman nash dari Al-Quran dan Sunnah mendukungnya, dan sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat. Tidak adil jika zakat diambil dari petani jelai dan gandum tetapi pemilik kebun jeruk, mangga, atau apel dibebaskan darinya, padahal jenis-jenis terakhir ini di masa kini menghasilkan kekayaan yang sangat besar bagi pemiliknya, jauh lebih penting dan lebih besar daripada kekayaan jelai dan gandum. Maka dari keadilan adalah mewajibkan zakat pada jenis-jenis buah-buahan tersebut untuk mewujudkan kesetaraan antara semua orang dalam menanggung kewajiban keuangan umum dalam negara, yang paling penting di antaranya adalah zakat.
Dengan ini kami telah menyelesaikan kuliah ini. Semoga Allah menjaga kalian. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harta Zakat Lainnya dan Harta-harta yang Baru Muncul
Zakat Barang Dagangan, Rikaz, Barang Tambang, dan Hasil Laut
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, junjungan kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kami telah berbicara dalam kuliah sebelumnya tentang keumuman materi dalam zakat, dan kami melanjutkan pembahasan sekarang tentang topik ini.
Dari harta yang wajib dizakati adalah zakat barang dagangan. Jumhur (mayoritas) ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib pada barang dagangan, baik harta itu berupa aset tetap maupun bergerak—yaitu yang dibeli dengan niat berdagang. Kewajiban ini ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, qiyas (analogi), dan ijmak (konsensus).
Dari Al-Quran, firman Allah Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (Surah Al-Baqarah, ayat 267)
Imam Ath-Thabari berkata tentang makna ayat ini: Artinya zakatkanlah dari yang baik-baik dari hasil usahamu, baik melalui perdagangan maupun industri. Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan usaha dalam ayat adalah perdagangan.
Dari Sunnah, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah dari yang kami persiapkan untuk dijual”, yaitu untuk perdagangan.
Juga, qiyas menunjukkan kewajiban zakat pada barang dagangan, karena barang dagangan adalah harta yang dimaksudkan untuk berkembang, maka menyerupai tiga jenis yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan, seperti tanaman, hewan ternak, emas dan perak. Ia menyerupai tanaman dalam penggandaan hasil, dan menyerupai hewan ternak dalam pertambahan melalui keberadaannya. Oleh karena itu, ini adalah yang kami unggulkan, yaitu pendapat jumhur ulama fikih, yaitu wajibnya zakat pada barang dagangan.
Juga dari harta yang wajib dizakati adalah rikaz dan barang tambang. Rikaz adalah apa yang ditimbun oleh orang-orang dahulu dari masa jahiliah di dalam bumi berupa harta dengan berbagai jenisnya. Para ulama fikih berpendapat bahwa di dalamnya ada seperlima. Artinya jika ditemukan oleh seorang muslim, sebagian ulama fikih berpendapat bahwa di dalamnya ada seperlima, yaitu mengeluarkan seperlimanya sebagai zakat, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Pada rikaz seperlima.” Yang ditimbun di dalam bumi adalah rikaz berdasarkan ijmak, karena ia tertimbun di dalamnya.
Mengenai barang tambang, sebagian mendefinisikannya sebagai setiap yang keluar dari bumi dari apa yang diciptakan di dalamnya dari bukan dirinya yang memiliki nilai. Para ulama fikih berselisih tentang kadar yang wajib pada barang tambang. Sebagian berpendapat bahwa yang wajib padanya adalah seperlima, dan sebagian lain berpendapat bahwa yang wajib padanya adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%). Para ulama fikih juga berselisih dalam menentukan barang tambang yang diambil zakatnya sebagai berikut:
Mazhab Syafi’i membatasinya pada emas dan perak. Adapun selain keduanya seperti besi, tembaga, dan timbal, tidak ada zakat padanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua barang tambang yang dikeluarkan dari bumi yang dapat dicetak dengan api memiliki hak wajib. Adapun barang tambang cair atau padat yang tidak dapat dicetak, tidak ada kewajiban di dalamnya menurut mereka.
Mazhab Hambali berpendapat tidak ada perbedaan antara yang dapat dicetak dan yang tidak dapat dicetak dari barang tambang. Barang tambang yang terkait dengan kewajiban adalah setiap yang keluar dari bumi dari apa yang diciptakan di dalamnya dari bukan dirinya yang memiliki nilai, baik padat seperti besi, tembaga, dan timbal, maupun dari barang tambang cair seperti minyak bumi, yaitu petroleum.
Kami berpendapat bahwa pendapat mazhab Hambali tentang kewajiban zakat pada setiap barang tambang yang keluar dari bumi tanpa membedakan antara jenis satu dengan lainnya—kami berpendapat itu lebih layak diterima dan itu yang kami pilih. Karena tidak membedakan antara barang tambang padat dan cair, tidak antara yang dapat dicetak dengan api dan yang tidak dapat dicetak. Ia tidak membedakan antara besi dan timbal dengan minyak bumi. Semuanya adalah harta yang memiliki nilai di kalangan manusia. Maka tidak masuk akal dan bertentangan dengan keadilan untuk membebaskan barang tambang seperti minyak bumi—petroleum—dari zakat, padahal di masa kini telah menjadi salah satu kekayaan terpenting yang dimiliki orang, yang menghasilkan pendapatan jauh melebihi pendapatan dari barang tambang seperti timbal. Barang tambang cair maka wajib dikenakan zakat dengan lebih utama. Pendapat mazhab Hambali menghasilkan pencapaian keumuman materi dalam zakat dengan cara yang paling sempurna, dan dengan demikian mewujudkan kesetaraan penuh antara mereka yang memiliki jenis barang tambang apa pun selama syarat-syarat kewajiban zakat terpenuhi.
Juga dari harta yang diperselisihkan para ulama fikih apakah wajib dizakati atau tidak—zakat hasil laut:
Para ulama fikih berselisih tentang kewajiban zakat pada apa yang dikeluarkan dari laut berupa permata berharga seperti mutiara, marjan, dan wewangian ambar. Sebagian berpendapat tidak ada kewajiban padanya kecuali jika dipersiapkan untuk perdagangan. Jika dipersiapkan untuk perdagangan, maka wajib zakatnya. Sebagian lain berpendapat bahwa apa yang dikeluarkan dari laut memiliki hak wajib. Mereka berselisih tentang kadar kewajiban ini: apakah seperlima seperti perlakuan terhadap rikaz? Atau sepersepuluh seperti perlakuan terhadap tanaman? Atau seperempat dari sepersepuluh seperti perlakuan terhadap dirham dan dinar? Tiga pendapat ulama yang disebutkan Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal halaman 433 dan seterusnya.
Kami mengunggulkan pendapat sebagian ulama bahwa kadar kewajiban ini penentuan kadarnya harus tunduk pada musyawarah ahli pendapat, karena syariat telah membedakan kadar yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan sesuai dengan perbedaan biaya dan usaha dalam mengairi tanaman. Menjadikannya setengah sepersepuluh jika tanaman diairi dengan alat, dan menjadikannya sepersepuluh jika diairi tanpa alat. Demikian pula halnya dengan apa yang dikeluarkan dari laut, seharusnya kadar kewajiban berbeda sesuai dengan perbedaan biaya dan usaha untuk memperolehnya. Menjadi seperlima jika biaya dan usahanya sedikit, dan menjadi sepersepuluh jika biaya dan usahanya banyak.
Kami berpendapat bahwa pendapat yang rajih (kuat) adalah yang mewajibkan hak pada semua yang dikeluarkan dari laut dan itu yang kami pilih, karena bagaimana bisa dibebaskan dari hak wajib ini orang yang mengeluarkan mutiara bernilai sangat tinggi, sementara zakat dibebankan pada saat yang sama pada hasil pertanian yang nilainya relatif rendah jika dibandingkan dengan permata berharga yang dikeluarkan dari laut. Pendapat ini menghasilkan terwujudnya keadilan dan keumuman materi dalam zakat dengan cara yang paling sempurna, dan dengan demikian mewujudkan kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban keuangan umum yang ditetapkan dalam negara.
Juga dari hal-hal yang mereka perselisihkan, mereka berselisih tentang kewajiban zakat pada apa yang dikeluarkan dari laut berupa ikan sebagai berikut:
Sebagian ulama fikih berpendapat tidak ada zakat pada ikan-ikan ini. Sebagian lain berpendapat bahwa apa yang dikeluarkan dari laut berupa ikan memiliki hak wajib jika mencapai nisab, dengan berdalil pada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia menulis kepada pegawainya agar tidak mengambil apa pun dari ikan sampai mencapai dua ratus dirham. Jika mencapai dua ratus dirham, maka ambillah zakatnya. Pendapat-pendapat ini terdapat dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid halaman 434 dan seterusnya.
Pendapat yang rajih: Kami berpendapat bahwa pendapat yang rajih adalah yang mewajibkan zakat pada ikan dan itu yang kami pilih, karena apa yang ditangkap dari ikan bisa mencapai jumlah besar yang diperkirakan dengan harta melimpah. Penangkapan ikan di masa kini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dilengkapi dengan peralatan tercanggih untuk itu. Maka adil bahwa apa yang dikeluarkan dari laut berupa ikan ketika mencapai nisab seharusnya tidak dibebaskan dari hak yang dibebankan padanya. Dengan ini terwujud kesetaraan antara warga negara dalam menanggung kewajiban keuangan umum yang ditetapkan dalam negara.
Zakat atas Harta yang Muncul di Zaman Modern
Salah satu hal yang terkait dengan topik keumuman materi dalam zakat adalah harta-harta yang berkembang dan muncul di zaman modern ini: apakah wajib dikenakan zakat atau tidak? Telah muncul berbagai bentuk kegiatan dan jenis investasi yang tidak ada di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maupun di zaman para Khalifah yang Lurus. Telah muncul perusahaan saham dan bank-bank, aktivitas perdagangan dan keuangan berkembang pesat, pendapatan dari pekerjaan meningkat, ditambah dengan meningkatnya investasi yang menghasilkan pendapatan tinggi di bidang perumahan. Oleh karena itu, sebagian harta tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan pokok yang dibebaskan dari zakat seperti alat-alat industri sederhana dan rumah untuk tempat tinggal, karena pabrik-pabrik dan alat-alat industri itu sendiri telah menjadi modal yang berkembang sehingga perlu dikenakan zakat.
Dalam konteks ini, Syaikh Muhammad Abu Zahrah berkata: Sesungguhnya illat (alasan hukum) kewajiban zakat yang menjadi dasar penetapan wajibnya adalah harta yang berkembang secara aktual atau potensial, yaitu kemampuan untuk mengembangkannya meskipun tidak benar-benar mengusahakannya. Illat ini diambil dari penjelasan para ulama fikih di berbagai tempat, dan dengan menelusuri harta-harta yang wajib dizakati.
Kemudian beliau berkata: Jika di zaman ini muncul harta-harta yang berkembang, yang sebagiannya tidak berkembang di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, zaman para sahabat, maupun para imam mujtahid, apakah kita boleh mewajibkan zakat padanya dengan menerapkan illat yang dirumuskan para ulama fikih untuk hukum kewajiban zakat? Dan jika kita melakukan itu, apakah kita telah melakukan bid’ah dalam hukum syariat? Jawabannya adalah bahwa hal ini boleh bagi kita dan kita dalam hal ini tidak membuat ijtihad baru, tetapi menerapkan illat qiyas. Ini adalah artikel Syaikh Abu Zahrah dalam kumpulan penelitian Muktamar Kedua Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah tahun 1385 H/1965 M dengan judul (Zakat) halaman 179 dan seterusnya.
Kemudian Syaikh berkata: Sesungguhnya menggeneralisasi hukum-hukum khusus zakat pada setiap harta yang memenuhi illatnya akan menghasilkan sesuatu yang benar dan mencegah sesuatu yang zalim, karena hal itu mewujudkan keadilan yang merata di antara manusia. Tidak mungkin zakat diwajibkan pada hasil pertanian pemilik dua feddan (satuan luas tanah), tetapi dibebaskan bagi yang memiliki gedung-gedung mewah yang menghasilkan pendapatan besar setara dengan puluhan feddan, dan dibebaskan pula bagi yang memiliki modal yang diinvestasikan di pabrik yang menghasilkan keuntungan besar. Adapun ketidakadilan yang dicegah dengan mewajibkan zakat pada harta yang menghasilkan banyak uang padahal tidak ada di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah agar orang-orang tidak lari dari harta yang wajib dizakati ke harta yang tidak wajib dizakati, sehingga mayoritas besar berada di satu sisi aktivitas ekonomi dan sedikit di sisi lain, padahal bisa jadi kebutuhan umat lebih mendesak terhadapnya.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditetapkan ini, kami katakan: Setiap harta yang memenuhi kriteria pertumbuhan dan syarat-syarat yang disebutkan ulama fikih, wajib dizakati, meskipun tidak disebutkan dalam nash dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, karena qiyas (analogi) telah ditetapkan dalam fikih Islam, dan penerapan qiyas berlaku di semua masa dan zaman, dan ini adalah bentuk ijtihad yang tidak boleh kosong darinya suatu masa agar dapat merealisasikan illat nash-nash secara ilmiah dan benar.
Sekarang kita akan membahas beberapa harta yang muncul di zaman ini:
- Uang Kertas
Uang kertas tidak dikenal kecuali di zaman-zaman belakangan, di mana ia menjadi dasar transaksi antarmanusia. Mata uang emas dan perak telah hilang dari kehidupan manusia, dan uang kertas telah menjadi pilar kekayaan, alat tukar, dan harga barang. Darinya dibayarkan gaji dan upah, dan berdasarkan jumlah yang dimiliki seseorang dinilai kekayaannya. Uang kertas memiliki kekuatan emas dan perak dalam transaksi dan pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, ia adalah harta yang berkembang atau dapat dikembangkan, sama seperti emas dan perak.
Kesimpulannya adalah bahwa uang kertas wajib dizakati. Untuk masalah ini dapat dirujuk kepada (Fiqh al-Zakah) karya Syaikh al-Qaradawi Jilid 1 halaman 273 dan seterusnya. Perhitungan nisab zakat pada uang kertas dilakukan dengan mengukur nilainya dalam emas, karena itulah ketentuan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berdasarkan itu dilakukan pengumpulan zakat setelah beliau. Dengan mewajibkan zakat pada uang kertas, terwujudlah keumuman materi dalam zakat secara sempurna, dan dengan demikian terwujud kesetaraan di antara warga negara dalam menanggung beban keuangan umum yang ditetapkan dalam negara.
- Hewan Ternak Selain Unta, Sapi, Kambing, dan Kuda
Juga termasuk harta yang menjadi berkembang di zaman ini adalah hewan ternak yang digembalakan selain unta, sapi, kambing, dan kuda. Jika terjadi orang menemukan satu atau beberapa jenis hewan yang mereka gemukkan dan digunakan untuk berkembang dan memperoleh keuntungan darinya, apakah mungkin hewan-hewan itu dikenakan zakat seperti unta, sapi, dan kambing atau tidak? Ada hewan-hewan yang tidak digunakan untuk pertumbuhan harta, tetapi untuk kebutuhan pribadi seperti keledai misalnya, kemudian digunakan untuk pertumbuhan harta setelah itu.
Para ulama Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah (Kelompok Studi Sosial) telah membahas topik ini. Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah adalah lembaga yang berada di bawah Liga Arab. Kami katakan: Para ulama Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah telah membahas topik ini dan menyimpulkan dari riwayat yang shahih dari Umar radhiyallahu ‘anhu tentang qiyas kuda terhadap kambing, di mana beliau berkata: “Apakah kita mengambil satu ekor kambing dari setiap empat puluh ekor kambing, tetapi tidak mengambil apa pun dari kuda?” Maka beliau menetapkan satu dinar untuk kuda.
Kami katakan: Mereka menyimpulkan dari riwayat ini bahwa kita boleh melakukan qiyas dalam masalah zakat. Mereka berkata bahwa riwayat yang shahih dari Umar radhiyallahu ‘anhu membolehkan kita melakukan qiyas dalam masalah zakat, karena nash-nash zakat bukanlah nash yang tidak memiliki illat, melainkan nash-nash yang memiliki illat yang dapat diterapkan. Al-Faruq Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu telah menerapkannya sehingga mewajibkan zakat pada kuda karena terpenuhinya illat yaitu pertumbuhan harta. Abu Hanifah radhiyallahu ‘anhu, guru para ahli fikih qiyas, mengikuti qiyasnya.
Kemudian mereka berkata: Jika Imam Umar radhiyallahu ‘anhu menganggap pertumbuhan harta sebagai illat, dan Abu Hanifah mengikutinya, maka sah untuk menyimpulkan dari metode ini bahwa zakat wajib pada semua hewan yang digunakan untuk pertumbuhan harta dan digembalakan di padang rumput yang mubah, telah mencapai nisab yaitu senilai sepuluh mitsqal emas, maka zakatnya adalah seperempat sepersepuluh (2,5%). Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah li al-Duwal al-‘Arabiyyah halaman 246 dan seterusnya.
Kami berpendapat bahwa dengan mewajibkan zakat pada semua hewan yang digunakan untuk pertumbuhan harta dan keuntungan dari hasilnya, terwujudlah keumuman materi dalam zakat secara sempurna, dan dengan demikian tidak ada ruang untuk membedakan antara harta yang berkembang dengan lainnya. Dengan ini terwujud kesetaraan penuh antara mereka yang memiliki hewan-hewan yang digunakan untuk pertumbuhan harta dan keuntungan dalam menanggung beban keuangan umum yang ditetapkan dalam negara, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
- Pabrik dan Hukum Zakatnya
Para ulama fikih terdahulu membebaskan alat-alat industri sederhana seperti alat tukang kayu yang bekerja dengan tangannya dan alat pandai besi, karena harta-harta ini dianggap sebagai kebutuhan pokok, dan karena tidak dianggap berkembang dengan sendirinya atau berpotensi berkembang.
Di zaman modern, telah muncul harta-harta yang berkembang secara aktual yang tidak dikenal sebagai harta yang berkembang dan dieksploitasi di masa perumusan fikih, yaitu alat-alat industri yang dianggap sebagai modal untuk eksploitasi dan merupakan sarana eksploitasi bagi pemiliknya, seperti pemilik pabrik besar yang mempekerjakan buruh untuk mengelolanya. Modal eksploitasinya adalah alat-alat industri tersebut. Dengan pertimbangan ini, ia dianggap sebagai harta yang berkembang, karena hasil diperoleh dari alat-alat ini, sehingga tidak seperti alat-alat pandai besi yang bekerja dengan tangannya, atau alat-alat tukang kayu yang bekerja dengan tangannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, para ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat wajib pada harta-harta ini karena dianggap sebagai harta yang berkembang, dan bukan termasuk kebutuhan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
Para ulama fikih Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah berkata dalam masalah ini: Jika para ulama fikih tidak mewajibkan zakat pada alat-alat industri di zaman mereka, itu karena alat-alat tersebut adalah alat-alat sederhana yang tidak melampaui kebutuhan pokok untuk industri dan produksi berdasarkan keterampilannya, sehingga tidak dianggap sebagai harta yang berkembang dan produktif. Produksi dalam hal ini adalah milik pekerja. Adapun sekarang, pabrik-pabrik menganggap alat-alat industri itu sendiri sebagai modal yang berkembang. Oleh karena itu, kami katakan: Alat-alat industri yang dimiliki oleh pengrajin yang bekerja seperti alat-alat tukang cukur yang bekerja dengan tangannya dan sejenisnya dibebaskan dari zakat, karena dianggap sebagai kebutuhan pokok baginya. Adapun pabrik-pabrik, zakat wajib padanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini bertentangan dengan pendapat para ulama fikih, karena mereka tidak memutuskan tentangnya karena tidak melihatnya. Seandainya mereka melihatnya, mereka akan berpendapat seperti pendapat kami. Kita sebenarnya tidak keluar dari pendapat mereka, atau menerapkan manat (tempat berlakunya hukum) yang mereka rumuskan dalam fikih mereka radhiyallahu ‘anhum. Lihat Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah li al-Duwal al-‘Arabiyyah halaman 241 dan seterusnya.
Rekomendasi ketiga dari rekomendasi Muktamar Kedua Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah tentang zakat pabrik menyatakan bahwa:
- Tidak wajib zakat pada benda-benda gedung yang dieksploitasi, pabrik-pabrik, kapal-kapal, pesawat-pesawat dan sejenisnya, tetapi wajib zakat pada hasil bersihnya ketika telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun.
- Jumlah persentase yang wajib dikeluarkan adalah seperempat sepersepuluh (2,5%) dari hasil bersih pada akhir tahun. Muktamar Kedua Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah halaman 403, Dar al-Qaumiyyah li al-Thiba’ah wa al-Nasyr 1965.
Kami berpendapat bahwa mewajibkan zakat pada harta yang dikelola pabrik-pabrik mewujudkan keumuman materi dalam zakat secara sempurna, karena bertentangan dengan keadilan jika harta-harta tersebut tetap jauh dari wadah zakat padahal menghasilkan banyak uang bagi pemilik pabrik, sementara yang memiliki nisab dari hasil pertanian dengan nilai finansial yang rendah jika dibandingkan dengan harta yang dikelola pabrik justru dikenakan zakat. Maka kewajiban zakat ini mewujudkan kesetaraan di antara warga negara dalam menanggung beban keuangan umum yang ditetapkan dalam negara.
- Gedung-Gedung dan Hukum Zakatnya
Para ulama fikih terdahulu tidak membahas topik kewajiban zakat pada rumah, karena rumah di zaman mereka tidak dieksploitasi tetapi dikhususkan untuk tempat tinggal pribadi, sehingga dianggap sebagai kebutuhan pokok, dan itu adalah keadilan sosial pada waktu itu.
Adapun sekarang, rumah-rumah dan bangunan-bangunan didirikan untuk mencari pertumbuhan harta, dan menghasilkan keuntungan yang melimpah, maka hasilnya harus dikenakan zakat, karena sebab yang menjadi alasan diwajibkannya zakat pada harta yaitu pertumbuhan telah terpenuhi. Terlebih lagi di zaman kita sekarang, investasi uang di sektor perumahan dengan tujuan eksploitasi telah menjadi salah satu jenis investasi yang paling menguntungkan dan menghasilkan pendapatan besar bagi pemiliknya.
Pendapat untuk mengenakan zakat pada rumah-rumah yang dieksploitasi yaitu gedung-gedung tidak bertentangan dengan pendapat para ulama fikih terdahulu ketika mereka menetapkan bahwa rumah tidak ada zakatnya, karena rumah di zaman mereka tidak dieksploitasi kecuali dalam kasus yang jarang dan langka, tetapi untuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu, mereka tidak memperhatikan yang langka, karena hukum mengikuti yang umum dan lazim, sedangkan yang langka tidak memiliki hukum dalam syariat.
Bahkan Imam Ahmad radhiyallahu ‘anhu memiliki hasil dari toko-toko yang dia sewakan, dan dia mengeluarkan zakatnya meskipun itu satu-satunya sumber penghasilannya untuk hidup. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata: “Saya mengikuti pendapat Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu tentang tanah Sawad, di mana beliau mengeluarkan zakatnya.”
Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah berpendapat untuk mengqiyaskan zakat real estat yang dibangun dengan zakat tanaman dan buah-buahan, karena keduanya dianggap sebagai aset tetap yang menghasilkan pendapatan, maka wajib zakat pada pendapatannya dengan persentase antara 10% dan 5% tergantung pada unsur biaya. Lihat Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah li al-Duwal al-‘Arabiyyah halaman 241 dan seterusnya.
Dalam Rekomendasi ketiga dari rekomendasi Muktamar Kedua Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah disebutkan bahwa:
Tidak wajib zakat pada benda-benda gedung yang dieksploitasi, tetapi wajib zakat pada hasil bersihnya ketika telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun.
Dengan mewajibkan zakat pada gedung-gedung yang digunakan untuk pertumbuhan harta, terwujudlah keumuman materi dalam zakat secara sempurna, karena bukan keadilan jika yang menginvestasikan uangnya di tanah-tanah dikenakan zakat, sedangkan yang menginvestasikan uangnya di gedung-gedung dibebaskan darinya. Ini dianggap sebagai dua hukum yang berbeda untuk dua hal yang sama yaitu investasi di tanah dan investasi di gedung. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu menyebabkan tidak adanya kesetaraan di antara wajib zakat dalam hal ini. Adapun mewajibkan zakat pada gedung-gedung yang dieksploitasi akan mewujudkan kesetaraan yang hilang tersebut.
- Surat Berharga dan Hukum Zakatnya
Perkembangan industri dan perdagangan telah mengenalkan jenis baru modal yang dikenal dengan nama saham dan obligasi, yang merupakan surat berharga yang menjadi dasar transaksi perdagangan di pasar khusus. Surat-surat berharga ini dalam ilmu keuangan disebut “nilai yang dapat dipindahkan” dan pendapatan yang dihasilkannya dikenakan pajak yang disebut pajak atas pendapatan nilai yang dapat dipindahkan.
Bentuk pertumbuhan harta ini tidak ada di zaman para ulama fikih terdahulu, tetapi beberapa ulama fikih kontemporer telah membahas harta-harta tersebut dengan menganggapnya sebagai harta baru yang memenuhi kriteria pertumbuhan di zaman kita, dan oleh karena itu wajib dizakati. Kami akan menjelaskan hal itu sebagai berikut:
Pertama – Saham
Bentuk ini diringkas dalam kepemilikan seseorang atas sebagian dari modal perusahaan yang modalnya dibagi menjadi saham-saham, dan hasil sahamnya ditentukan pada akhir tahun sesuai dengan hasil operasi proyek berupa keuntungan atau kerugian. Ini adalah bentuk yang sah menurut pandangan legislasi Islam.
Pendapat Para Ulama dalam Hal Ini:
Para ulama Halqah al-Dirasat al-Ijtima’iyyah berpendapat bahwa saham jika digunakan untuk perdagangan dan memperoleh keuntungan dari perdagangannya dianggap sebagai barang dagangan, dan dengan demikian dizakati dengan cara yang sama dengan barang dagangan. Adapun jika saham digunakan untuk kepemilikan dan memperoleh keuntungan dari hasilnya bukan dari perdagangannya, maka yang diambil dari perusahaan itu sendiri baik perusahaan industri maupun lainnya sudah mencukupi.
Pendapat ini membedakan antara dua keadaan:
Pertama: Saham dijadikan objek perdagangan, dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dan diperdagangkan di pasar surat berharga. Dalam keadaan ini, wajib zakat padanya sesuai dengan nilainya pada akhir tahun jika telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun.
Keadaan kedua: Saham-saham ini dimiliki dengan tujuan investasi, sehingga menghasilkan keuntungan tahunan. Dalam keadaan ini, zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan sudah mencukupi sebagai pengganti zakat bagi para pemegang saham.
Kedua- Obligasi: Bentuk ini dapat diringkas sebagai berikut: seseorang (pribadi atau badan hukum) memberikan pinjaman kepada orang lain (pribadi atau badan hukum) sejumlah uang tertentu berdasarkan surat obligasi dengan ketentuan bahwa pemberi pinjaman akan menerima bunga tetap tahunan dari peminjam tanpa memandang hasil pemanfaatan uang tersebut oleh peminjam, baik untung maupun rugi. Inilah bentuk riba menurut pandangan Syariat Islam, di mana bunga ditetapkan tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian. Meskipun demikian, kita mendapati bahwa banyak ulama mewajibkan zakat pada obligasi-obligasi tersebut. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam penelitiannya berjudul (Zakat) pada Konferensi Kedua Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah halaman 184 dan seterusnya, mengatakan: Mungkin ada yang berkata: Sesungguhnya bunga yang diambil dari obligasi adalah harta yang haram karena termasuk riba, lalu bagaimana zakat diambil darinya? Kami menjawab dalam hal ini bahwa jika kita membebaskannya dari zakat, hal itu akan menyebabkan orang-orang memilikinya sebagai pengganti saham, dan itu akan membawa manusia untuk meninggalkan yang halal menuju yang haram. Dan karena harta haram jika tidak diketahui pemiliknya, jalan keluarnya adalah sedekah. Maka keharaman cara memperoleh harta menjadi alasan untuk mewajibkan sedekah, bukan untuk membebaskannya dari zakat.
Syekh Mahmoud Shaltout berkata dalam hal ini: Bahkan untuk yang haram secara syariat, menurut saya Syariat Islam menetapkan kewajibannya terhadap pajak. Harta yang diperoleh dari cara haram, tujuannya adalah sedekah. Hal itu karena pada dasarnya pelanggar tidak boleh mendapat manfaat dari pelanggarannya. Dengan membebaskannya dari pajak, ia akan berada dalam posisi yang lebih baik daripada orang yang berpegang pada yang halal, dan Syariat tidak menetapkan menolak bahaya dengan bahaya yang serupa. Bahaya kedua adalah tidak ikut sertanya dalam beban-beban yang diperlukan untuk kepentingan umum ketika dibebaskan dari pajak. Ini terdapat dalam kitab (Fatawi) karya Syekh Muhammad Shaltout halaman 620 dan seterusnya.
Dalam laporan Halaqat ad-Dirasat al-Ijtima’iyyah disebutkan sebagai berikut: Sesungguhnya obligasi-obligasi ini telah menjadi komoditas secara nyata. Jika kita membebaskannya dari zakat karena unsur haram yang melekat padanya, orang-orang akan tertarik membelinya, dan itu akan mengarah pada intensifikasi transaksi dengannya, sehingga hal itu akan mendorong yang haram, bukan memutusnya. Dan karena menyalurkan hasil usaha yang haram untuk sedekah tidaklah terlarang. (Halaqah ad-Dirasat al-Ijtima’iyyah li Jami’ah ad-Duwal al-‘Arabiyyah halaman 373 dan seterusnya).
Doktor Yusuf al-Qaradhawi berpendapat tentang obligasi bahwa obligasi itu berkembang dan mendatangkan keuntungan bagi kreditor meskipun dilarang. Larangan terhadap keuntungan ini tidak menjadi alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari zakat, karena melakukan yang haram tidak memberikan keistimewaan kepada pelakunya dibanding orang lain. Kemudian beliau berkata: Karena itu para fuqaha bersepakat atas kewajiban zakat pada perhiasan yang haram, sementara mereka berbeda pendapat tentang yang mubah. (Fiqh az-Zakah) karya Syekh al-Qaradhawi Jilid Pertama halaman 527 dan seterusnya.
Itulah pendapat para fuqaha yang mewajibkan zakat pada obligasi, dan apa yang dicapai para ulama dalam hal ini serupa dengan yang dijalankan perundang-undangan pajak positif yang menetapkan bahwa tidak ada pertimbangan terhadap keabsahan pendapatan. Jika wajib pajak memperoleh pendapatan yang tidak sah, maka ia tetap dikenai pajak. Seandainya seseorang berdagang narkoba misalnya dan memperoleh pendapatan dari itu, ia akan dikenai pajak keuntungan perdagangan dan industri tanpa mempertimbangkan keabsahan pendapatan atau tidak.
Mengenai cara zakat obligasi ini, sebagian ulama berpendapat bahwa jika digunakan untuk perdagangan, maka ia termasuk barang dagangan, wajib di dalamnya apa yang wajib pada barang dagangan ketika mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Zakat wajib atas seluruh nilainya pada akhir tahun –yaitu modal ditambah bunga– dengan tarif 2,5% per tahun yaitu seperempat dari sepersepuluh. Adapun jika obligasi dimiliki dengan tujuan mendapatkan bunganya, maka zakat dalam hal ini diambil dari bunga saja dengan menganggap bahwa obligasi dalam keadaan ini setara dengan harta tetap, dan tarif yang wajib adalah 10% dari hasil bersihnya karena tidak ada biaya yang berarti untuk menghasilkan pendapatan dalam kasus ini. Kami memilih pendapat yang dikemukakan para fuqaha tentang kewajiban zakat pada obligasi, yaitu dengan justifikasi yang mereka sebutkan.
Keenam- Hasil kerja dan hukum zakatnya: Jika Sunnah Nabawiyyah yang mulia tidak menjelaskan hukum hasil kerja berkaitan dengan zakat, hal itu karena sebagian besar kaum Muslim di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hanya disibukkan oleh jihad. Upah kerja masih terbatas, para budak dan yang semisal mereka melakukan pekerjaan, sehingga tidak mengharuskan pembahasan mengenai kewajiban zakat atas hasil kerja. Lihat dalam hal ini kitab (al-Kharaj) karya al-Qadhi Abu Yusuf halaman 45, penerbit al-Mathba’ah as-Salafiyyah wa Maktabatuha, Kairo.
Namun kita memiliki sandaran pada pemberian (al-‘atha’) untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, kita akan mencoba dalam hal ini mengulas beberapa nash Islam yang menyoroti konsep pemberian, kemudian kami mengomentari nash-nash tersebut.
Pertama- Pemberian di zaman Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq: Abu Yusuf rahimahullah berkata: Ini tercantum dalam kitab (al-Kharaj) halaman 45. Abu Yusuf rahimahullah berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Najih, ia berkata: Datang kepada Abu Bakar radhiyallahu ta’ala ‘anhu sejumlah harta, maka ia berkata: “Barangsiapa yang memiliki janji dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hendaklah datang” –maksudnya siapa yang telah dijanjikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sesuatu dari harta hendaklah datang. Maka datanglah kepadanya Jabir bin Abdullah, lalu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku: “Jika datang harta Bahrain, aku akan memberimu begini dan begini” sambil mengisyaratkan dengan kedua telapak tangannya. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta’ala ‘anhu berkata kepadanya: “Ambillah” maka ia mengambil dengan kedua telapak tangannya, kemudian menghitungnya dan mendapati lima ratus. Lalu ia berkata: “Ambillah seribu lagi” maka ia mengambil seribu. Kemudian ia memberikan kepada setiap orang yang dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan tersisa sebagian dari harta itu, maka ia membaginya kepada manusia secara merata kepada yang kecil dan besar, yang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, sehingga setiap orang mendapat tujuh dirham sepertiga. Ketika tahun berikutnya datang harta yang banyak, lebih banyak dari itu, maka ia membaginya kepada manusia, dan setiap orang mendapat dua puluh dirham. Ia berkata: Lalu datanglah sejumlah kaum Muslim, mereka berkata: Wahai Khalifah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, engkau membagi harta ini lalu menyamakan antara manusia, padahal di antara manusia ada orang-orang yang memiliki keutamaan, pendahuluan, dan kedudukan. Seandainya engkau memberikan keutamaan kepada ahli pendahuluan, kedudukan dan keutamaan sesuai dengan keutamaan mereka. Maka ia berkata: Adapun pendahuluan, kedudukan dan keutamaan yang kalian sebutkan, aku sangat mengetahuinya, dan itu adalah sesuatu yang pahalanya ada pada Allah Jalla Tsana’uhu. Dan ini adalah penghidupan, maka kesamaan di dalamnya lebih baik daripada pembedaan.
Kedua- Pemberian di zaman Khalifah Kedua Umar bin al-Khaththab: Abu Yusuf melanjutkan pembicaraannya dalam hal ini, ia berkata: Ketika masa Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ta’ala ‘anhu dan datang penaklukan-penaklukan, ia memberikan keutamaan dan berkata: Aku tidak akan menjadikan orang yang memerangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seperti orang yang berperang bersamanya. Maka ia menetapkan untuk ahli pendahuluan dan kedudukan dari kaum Muhajirin dan Anshar yang menyaksikan perang Badar lima ribu lima ribu, dan untuk yang tidak menyaksikan Badar empat ribu empat ribu. Dan ia menetapkan untuk yang keislamannya seperti keislaman ahli Badar di bawah itu, ia menempatkan mereka sesuai dengan tingkatan mereka dalam pendahuluan.
Dari nash-nash yang kami sebutkan, kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut:
Pemberian menurut Abu Bakar: Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu menganggap pemberian sebagai penghidupan tetap bagi manusia dalam periodisitasnya setiap kali ada harta, tetapi tidak tetap dalam jumlahnya. Bagian individu –sebagaimana kami sebutkan– pada tahun pertama mencapai tujuh sepertiga dirham, meningkat pada tahun kedua menjadi dua puluh dirham.
Abu Bakar berpendapat untuk menyamakan dalam penghidupan ini, maka ia menyamakan antara yang kecil dan besar, yang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan.
Juga pemberian mencakup di samping penghidupan tetap bagi manusia, hadiah-hadiah yang dijanjikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada sebagian mereka.
Adapun mengenai pemberian menurut Umar, Umar radhiyallahu ‘anhu berpendapat untuk tidak menyamakan antara manusia dalam pemberian –sebagaimana kita lihat. Dan Umar radhiyallahu ‘anhu menjadikan pemberian setiap tahun, yaitu tetap dalam periodisitasnya juga. Beliau berkata: Maka sesungguhnya aku berpendapat untuk menjadikan pemberian setiap tahun, dan mengumpulkan harta karena itu lebih besar keberkahannya.
Juga faktor-faktor yang mewajibkan untuk memberikan keutamaan sebagian manusia atas sebagian lainnya dalam pemberian menurut pandangan Umar adalah faktor-faktor yang berbeda, di antaranya apa yang ia lakukan dari urusan-urusan, apa yang ia kerjakan, untuk memperbaiki penghidupannya, atas kadar keutamaannya atau pendahuluannya atau kedudukannya dalam Islam. Seseorang dan jihadnya dalam Islam, seseorang dan kedudukannya dalam Islam, seseorang dan kekayaannya dalam Islam, dan seseorang dan kebutuhannya dalam Islam.
Umar radhiyallahu ‘anhu juga cenderung kepada kesamaan dalam pemberian jika harta mencukupi untuk itu. Abu ‘Ubaid berkata: Dan pendapat Umar yang pertama adalah memberi keutamaan berdasarkan pendahuluan dan kontribusi kepada Islam, dan inilah yang masyhur dari pendapatnya. Dan pendapat Abu Bakar adalah penyamarataan. Kemudian telah datang dari Umar sesuatu yang menyerupai kembali kepada pendapat Abu Bakar.
Dari sini kita melihat bahwa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu memandang pemberian sebagai penghidupan tetap, sementara Umar bin al-Khaththab memandangnya sebagai balasan kerja atau keutamaan dalam Islam, namun pada akhirnya ia kembali kepada pendapat Abu Bakar.
Pengambilan zakat dari pemberian: Telah terbukti bahwa zakat wajib dikeluarkan dari pemberian pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin. Diriwayatkan dari Hubairah bin Maryam, ia berkata: Abdullah bin Mas’ud memberikan kepada kami pemberian dalam keranjang kecil, kemudian ia mengambil zakat darinya. Dan juga diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khaththab apabila keluar pemberian, ia mengambil zakat dari yang hadir hartanya untuk yang tidak hadir dan yang hadir.
Umar bin Abdul Aziz juga, ketika memberikan upah kepada seseorang, ia mengambil zakat darinya. Ia mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut ketika keluar untuk pemiliknya.
Kami berpendapat bahwa apa yang telah kami sebutkan tentang kewajiban zakat atas pemberian (gaji) memiliki kemiripan dengan yang berjalan dalam perundang-undangan perpajakan dalam hal ini. Jika kita melihat undang-undang perpajakan Mesir misalnya, kita akan mendapati bahwa ia mengenakan pajak atas pendapatan yang dianggap dalam hukum gaji, di mana Pasal 55 dari Undang-Undang nomor 157 tahun 1981 tentang pajak penghasilan menetapkan pemberlakuan undang-undang perpajakan atas pendapatan yang dianggap dalam hukum gaji. Pasal 55 dari Undang-Undang nomor 157 tahun 1981 tentang pajak penghasilan menetapkan pemberlakuan pajak atas gaji dan yang setara dengannya, yang berarti pemberlakuan pajak atas pendapatan yang dibayarkan secara berkala dan teratur meskipun bukan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa di masa sekarang atau masa lalu.
Jika kita menerapkan hal itu pada pemberian (gaji), kita akan mendapati bahwa ia mengambil hukum gaji dalam pengenaan pajak atasnya, meskipun bukan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa dalam hal kita menganggapnya sebagai pensiun tetap sebagaimana pendapat Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Terlebih lagi, pemberian (gaji) mengambil hukum gaji dalam pengenaan pajak atasnya jika kita menganggapnya sebagai balasan atas pekerjaan atau keutamaan dalam Islam sebagaimana pendapat Khalifah Umar bin Al-Khaththab. Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dikatakan untuk membebaskan penghasilan kerja dari zakat, terlebih lagi karena pendapatan ini telah menjadi bagian terbesar dari pendapatan nasional pada masa sekarang, dan pembebasan zakat darinya bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara wajib zakat dalam menanggung beban zakat.
Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer menyerukan kewajiban zakat atas penghasilan kerja. Para ulama Halaqah Dirasat Al-Ijtima’iyyah (Lingkaran Studi Sosial) mengatakan dalam hal ini: Tidak diragukan lagi bahwa jika dikumpulkan darinya, yaitu dari gaji, apa yang setara dengan nishab zakat dan bertahan selama satu tahun penuh, meskipun berkurang di tengah tahun, maka wajib zakat atasnya selama masih utuh di dua ujung tahun, awal dan akhirnya, meskipun berkurang dan tidak habis sama sekali di tengah tahun—sebagaimana mazhab Hanafiyah—karena jika ia bertahan sepanjang tahun tanpa dihabiskan semuanya, maka itu menjadi bukti bahwa ia bukan termasuk kebutuhan pokoknya, dan ia berkembang secara potensial dengan pertimbangan bahwa uang dianggap oleh Islam sebagai harta yang berkembang; karena uang diciptakan untuk digunakan atau dimanfaatkan, bukan untuk ditimbun. Dengan analogi pada hal itu, dapat dikenakan zakat atas penghasilan kerja setiap tahun; karena jarang terhenti sepanjang tahun dan kebanyakan mencapai nishabnya di dua ujung tahun. Dengan analogi ini, benar bahwa kita menganggap penghasilan kerja sebagai wadah zakat dengan pembatasan ini agar terwujud illat (alasan hukum) yang dirumuskan para ulama fikih, dan kami menganggapnya mengikuti nishab yang dianggap sebagai dasar zakat.
Ulama Hanafiyah telah bersikap toleran sehingga cukup dengan melengkapi saldo di awal dan akhir tahun tanpa habis semuanya di tengah tahun. Kita harus memperhatikan hal itu ketika mengenakan zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas untuk mewujudkan batas pemisah antara kaya dan miskin. Lihat Halaqah Dirasat Al-Ijtima’iyyah li Ad-Duwal Al-‘Arabiyyah halaman 243 dan seterusnya.
Dari pendapat ini dapat disimpulkan hal-hal berikut:
- Penghasilan kerja tunduk pada tarif zakat uang sebesar 2,5%, yaitu seperempat sepersepuluh.
- Untuk kewajiban zakat, harus ada nishab di awal tahun dan di akhir tahun serta berlalunya haul (satu tahun).
- Disyaratkan bahwa nishab ini berlebih dari kebutuhan pokok wajib zakat. Jika penghasilan dari kerja dihabiskan semuanya, maka tidak ada zakat atasnya.
Kesimpulannya, dengan mewajibkan zakat atas harta-harta yang baru muncul yang telah kita bicarakan sebelumnya, tercapailah universalitas materi dalam zakat hingga batas maksimal yang mungkin, dan dengan demikian tercapai kesetaraan penuh antara anggota masyarakat yang memiliki nishab zakat dari jenis harta apa pun yang memiliki sifat berkembang, ketika terpenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk kewajiban zakat, yaitu dalam menanggung beban zakat.
Jika kita telah berbicara tentang universalitas materi dalam zakat dan menyebutkan harta-harta yang dikenal pada masa ulama fikih kita terdahulu, kemudian kita berbicara tentang harta-harta yang baru muncul atau harta-harta yang berkembang di era-era belakangan ini, seperti pabrik, gedung-gedung, gaji, dan lain-lain, maka harus ada faktor-faktor yang mewujudkan universalitas ini. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang membantu mewujudkan universalitas dalam zakat.
Kami katakan: Jika kami telah berbicara tentang universalitas materi dalam zakat dan menyebutkan harta-harta yang wajib dizakati dari harta-harta yang dikenal pada masa ulama fikih kita terdahulu, dan harta-harta yang muncul baru di era-era ini dan menjadi harta-harta berkembang yang wajib dizakati, kami katakan: harus ada juga faktor-faktor yang mengarah pada terwujudnya universalitas dalam zakat ini, dan mengarah pada dikeluarkannya zakat dari semua harta yang memenuhi syarat-syarat zakat agar terwujud keadilan di antara anak-anak umat.
Kami cukupkan pada bagian kuliah ini, dan insya Allah akan kami lanjutkan pada kuliah berikutnya. Kami titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian.
3 – Faktor-Faktor yang Membantu Mewujudkan Universalitas dalam Zakat
Menghindari Pengenaan Ganda dalam Pembayaran Zakat, dan Menghindari Retroaktivitas dalam Zakat
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Pemimpin kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan… Amma ba’du:
Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas tentang harta-harta berkembang yang muncul di era-era ini, dan pada kuliah ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang membantu mewujudkan universalitas dalam zakat. Kita katakan:
Kita telah melihat melalui kajian kita tentang ide universalitas dalam zakat bahwa universalitas tersebut telah ditegaskan dengan cara yang paling sempurna. Namun, hukum-hukum khusus tentang zakat tidak cukup dengan universalitas tersebut, bahkan bekerja untuk menjamin terwujudnya. Universalitas mungkin tersedia, tetapi pelaksanaannya bisa mengganggu hal tersebut. Oleh karena itu, kita dapati bahwa hukum-hukum tersebut, di saat yang sama saat memperhatikan penampilan berbagai aspek universalitas ini, bekerja untuk menjauhkan segala yang dapat mengganggunya. Di sini kita dapati bahwa ada beberapa faktor yang membantu menjamin terwujudnya universalitas dalam zakat, dan di antara faktor-faktor terpenting ini adalah:
- Menghindari pengenaan ganda dalam pembayaran zakat
- Menghindari retroaktivitas dalam zakat
- Memerangi penghindaran pembayaran zakat
Kita akan menyoroti setiap faktor dari faktor-faktor ini.
- Menghindari Pengenaan Ganda dalam Pembayaran Zakat
Di antara hal terpenting yang datang dalam menghindari pengenaan ganda dalam pembayaran zakat adalah hukum yang diumumkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: “Tidak ada pengenaan ganda dalam sedekah.” Abu Ubaid berkata: Artinya tidak diambil dari satu tahun dua kali. Berdasarkan itu, fenomena pengenaan ganda zakat terjadi ketika dikenakan zakat yang sama atau zakat dari jenis yang sama dua kali kepada orang yang sama, dan berkenaan dengan harta yang sama, dalam satu haul (tahun).
Ibnu Qudamah dan lainnya menegaskan dengan mengambil dari hadits ini bahwa tidak boleh mewajibkan dua zakat dalam satu haul dengan sebab yang sama. Para ulama fikih telah menyimpulkan beberapa hukum dan prinsip dalam hal ini:
Diantaranya, Abu Hanifah berpendapat bahwa pemilik unta, sapi, atau kambing, jika mengeluarkan zakatnya berupa unta, sapi, atau kambing, kemudian menjualnya setelah itu, maka harga yang ia jual dengannya tidak digabungkan dengan uang yang ada padanya yang mencapai nishab yang ingin ia keluarkan zakatnya; karena harga ini telah dikeluarkan zakatnya melalui unta, sapi, atau kambing. Menggabungkannya dengan uang yang belum dizakati dan mengeluarkan zakatnya bersamanya dianggap sebagai pengenaan ganda, artinya dalam hal ini telah dikeluarkan zakat atas harta yang sama dua kali. Ini dianggap pengenaan ganda dalam zakat karena dalam kondisi ini telah dikeluarkan zakat darinya dua kali, dan pengenaan ganda dinafikan oleh hadits.
Orang yang membayar zakat uangnya, kemudian membeli dengannya unta atau hewan ternak lainnya, sementara ia memiliki hewan ternak dari jenis hewan ternak yang ia beli dengan uang yang telah dizakati itu, maka ia tidak menggabungkannya dengannya, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya ketika genap satu haul hewan ternak yang asli; karena ia merupakan pengganti harta yang telah dibayarkan zakatnya, sehingga tidak wajib lagi untuk kedua kalinya dalam haul yang sama.
Jumhur (mayoritas) ulama fikih berkata tentang unta, sapi, dan hewan pekerja, yaitu yang bekerja untuk membajak, mengairi, dan melayani tanaman, bahwa tidak wajib zakat atasnya. Mereka memberikan alasan bahwa pada gandum ada sedekah, dan gandum itu berasal dari sapi. Abu Ubaid menegaskan makna ini dengan perkataannya: Sesungguhnya jika hewan-hewan itu digunakan untuk mengairi dan membajak, maka biji-bijian yang wajib sedekah atasnya, sesungguhnya proses membajak, mengairi, dan mengiriknya dilakukan dengannya. Jika hewan-hewan itu juga dizakati, yaitu dikeluarkan zakat atasnya bersama biji-bijian, maka sedekah akan menjadi berlipat ganda atas orang-orang, dan ini artinya pengenaan ganda dalam zakat.
Juga, para ulama fikih Hanafiyah, untuk menghindari pengenaan ganda dalam zakat, mengatakan: Tidak diambil usyur (sepersepuluh) dari tanah kharaj, yaitu yang dikenakan atas tanahnya pajak tahunan tetap, agar tidak berkumpul usyur dan kharaj pada satu tanah.
Dengan hukum-hukum ini dan lainnya, pengenaan ganda dalam kewajiban zakat dihindari dengan cara yang membantu agar wajib zakat tidak membayar lebih dari yang wajib atasnya, dan dengan demikian ia setara dengan yang lain dalam tidak membayar zakat atas harta-hartanya kecuali satu kali saja, dan dengan demikian terwujud kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan di negara.
Cara Menghindari Pengenaan Ganda dalam Pemungutan Zakat
Di antara cara terpenting yang mencegah pengenaan ganda dalam zakat yang ditempuh oleh hukum keuangan Islam adalah lokalitas pemungutan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan setelahnya para penguasa Muslim memiliki perangkat-perangkat pusat untuk negara Islam. Datang dalam suratnya shallallahu alaihi wasallam kepada Zur’ah bin Dzi Yazan: “Jika utusan-utusanku datang kepadamu, maka aku perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada mereka: Mu’adz bin Jabal, Abdullah bin Rawahah, Malik bin ‘Ubadah, ‘Utbah bin Niyar, Malik bin Murarah, dan sahabat-sahabat mereka. Kumpulkanlah apa yang ada pada kalian untuk sedekah dan jizyah, lalu sampaikanlah kepada utusan-utusanku, karena pemimpin mereka adalah Mu’adz bin Jabal.” (Al-Amwal oleh Abu Ubaid halaman 259 dan seterusnya)
Makna ini adalah bahwa Zur’ah memiliki perangkat regional untuk pemungutan, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memiliki perangkat pusat untuk pemungutan, yang anggotanya termasuk Mu’adz bin Jabal. Keberadaan perangkat lokal yang khusus untuk pemungutan, tanpa campur tangan dari perangkat-perangkat pusat, mencegah pengambilan zakat dua kali atas harta yang sama dan dalam periode yang sama, sehingga tidak terjadi pengenaan ganda dalam pemungutan zakat.
Pencegahan Pengenaan Ganda dalam Zakat Mewujudkan Kesetaraan antara Wajib Zakat
Asalnya, beban keuangan didistribusikan di antara anggota masyarakat secara adil, sesuai dengan kemampuan keuangan wajib zakat, dan dengan cara tidak membayar jumlah yang wajib atasnya dua kali atas harta yang sama yang dikenakan zakat. Jika terjadi pengenaan ganda dalam zakat, maka orang yang terkena pengenaan ganda ini akan menanggung beban keuangan yang lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh wajib zakat lain yang memiliki kemampuan keuangan yang sama dengan wajib zakat pertama. Dengan demikian, kesetaraan antara yang setara akan hilang, dan dalam hal ini terjadi kegagalan prinsip kesetaraan yang harus berlaku di antara warga negara dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan.
Di sisi lain, orang yang terkena pengenaan ganda akan kehilangan kepercayaan pada perangkat yang bertugas memungut zakat; akibat dari perasaannya akan ketidakadilan yang menimpanya, dan ini dapat membawanya untuk menghindari pembayaran zakat yang wajib atasnya. Penghindaran ini mengabaikan prinsip kesetaraan antara orang-orang dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan. Adapun dalam hal berupaya mencegah pengenaan ganda ini, maka setiap orang akan menanggung dari beban keuangan hanya sejumlah yang sesuai dengan kemampuan keuangannya saja, dan dengan demikian akan terwujud prinsip kesetaraan yang telah disebutkan.
b- Menghindari Sifat Regresif dalam Zakat:
Juga menghindari sifat regresif dalam zakat. Kadang-kadang terjadi bahwa beberapa wajib pajak ketika pajak dibebankan kepadanya berusaha untuk melepaskan diri darinya atau dari sebagiannya dengan cara memindahkannya kepada orang lain, dan kondisi ekonomi masyarakat serta hubungannya dengan anggota masyarakatnya dapat membantunya dalam hal itu, dan dengan demikian ia terbebas dari sebagian beban keuangan yang dibebankan kepadanya.
Pada kenyataannya, sifat regresif pajak dalam sistem-sistem sekuler dianggap sebagai salah satu hambatan mendasar dalam mewujudkan kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan di negara.
Di antara contoh sifat regresif dalam pajak adalah: produsen atau pedagang yang menghitung pajak yang dibayarkannya sebagai bagian dari biaya produksinya atau harga barangnya, dan dengan demikian menambahkannya pada harga jualannya, demikian juga pemilik properti yang menaikkan sewa sesuai dengan pajak properti yang dibebankan kepadanya. Jika demikian kondisi pajak dan sikap banyak wajib pajak yang tidak menghargai kepentingan umum dengan semestinya, maka kedudukan zakat berbeda dengan pajak dalam hal ini, dan pandangan orang terhadapnya berbeda dengan pandangan mereka terhadap pajak. Muslim merasakan bahwa zakat bukanlah hubungan antara dirinya dengan pemerintah atau kantor pemungutan, melainkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya Subhanahu wa Ta’ala sebelum pertimbangan apa pun, dan inilah makna ibadah dalam zakat yang dengan menunaikannya seorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah, dan ia merasakan ketika menunaikannya bahwa ia sedang merealisasikan salah satu rukun Islam, dan dari sinilah menunaikannya merupakan ketaatan dan kebaikan.
Selain itu, seorang Muslim mengetahui dengan baik bahwa zakat adalah hak dari hak-hak Allah yang wajib ditunaikan, dan sudah sewajarnya bahwa apa yang kami sebutkan menimbulkan dalam diri wajib zakat perasaan tidak mungkin untuk melepaskan diri darinya dengan cara apa pun, dan perasaan ini pada kenyataannya adalah syarat dasar untuk menghindari sifat regresif dalam zakat. Yang dimaksud dengan penggelapan dalam bidang perpajakan adalah melepaskan diri dari kewajiban membayar pajak, dan agar terwujud kesetaraan antara individu dalam menanggung beban pajak, pajak harus bersifat umum, dan yang dimaksud dengan keumuman adalah bahwa pajak menyentuh setiap harta dan setiap orang, dan inilah yang dikenal dengan keumuman material dan keumuman personal pajak. Para ahli keuangan publik berpendapat bahwa tidak adanya kesetaraan dalam bidang perpajakan antara para wajib pajak sesungguhnya kembali kepada beberapa faktor, yang terpenting di antaranya adalah penggelapan pajak, di mana dengan keberadaannya hancurlah kaidah keumuman dan kesetaraan; karena penggelapan mengakibatkan para penggelap terbebas dari bagian mereka dalam beban keuangan umum, pada saat yang sama orang-orang yang tidak menggelap tetap berkomitmen dengan bagian tersebut, dan ini mengakibatkan kerugian pada wajib pajak yang menanggung dengan jujur dan ikhlas beban perpajakan, dan demikianlah hancurlah kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban keuangan umum yang ditetapkan di negara.
Adapun mengenai zakat, kita dapati bahwa syariat Islam telah menciptakan cara-cara yang dapat memerangi penggelapan dari menunaikan zakat, dan cara-cara ini dapat dirangkum dalam tiga cara:
- Mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan penggelapan dari menunaikan zakat.
- Mengetahui bentuk-bentuk atau metode-metode yang digunakan wajib zakat untuk melarikan diri dari menunaikan zakat.
- Mengambil tindakan-tindakan yang menjamin pencegahan penggelapan dari menunaikan zakat.
Pertama: Sebab-sebab yang Mengakibatkan Penggelapan dari Zakat:
Sesungguhnya sebab-sebab penggelapan dari menunaikan zakat dapat dirangkum dalam dua sebab utama:
Pertama: Kezaliman administrasi atau para penanggung jawab pemungutan dan pendistribusian zakat. Kedua: Lemahnya kesadaran Islam secara umum, dan kesadaran zakat secara khusus.
Sebab Pertama: Kezaliman Administrasi dalam Pemungutan dan Pendistribusian:
Sesungguhnya kezaliman para pekerja pemungutan zakat terhadap pemilik harta dapat mendorong pemilik harta tersebut untuk menggelapkan pembayarannya kepada administrasi dan para pekerja zakat, sebagaimana juga mendorong orang-orang yang lemah iman untuk menggelapkan pembayaran zakat sama sekali dengan cara apa pun, dan sebab ini mencakup kezaliman dalam pemungutan dan pendistribusian.
Mengenai kezaliman pemungutan, para ahli fikih memutuskan bahwa kezaliman petugas atau administrasi yang bertanggung jawab atas pemungutan zakat merupakan alasan untuk menyembunyikan zakat atau menggelapkannya, maka tidak berhak bagi pihak-pihak ini dalam keadaan ini mengambil tindakan apa pun untuk menghukum atau memberi ta’zir kepada orang yang menyembunyikan atau mencegahnya, melainkan hanya mengambil zakat yang digelapkan atau disembunyikan saja.
Bagaimanapun, kezaliman administrasi atau para penanggung jawab pemungutan zakat merupakan sebab terpenting untuk penggelapan darinya, dan cukuplah kami menunjukkan bahwa salah satu sebab terpenting yang memaksa negara pada masa Sultan Qalawun di Mesir untuk membatalkan sistem pemungutan zakat melalui negara, dan ini menyebabkan diabaikannya pemungutan zakat, adalah kezaliman para pekerja zakat.
Adapun mengenai kezaliman pendistribusian, yang dimaksud dengan itu adalah bahwa hasil zakat dihambur-hamburkan atau dibelanjakan bukan pada tempat-tempat syar’inya, dan di sini muncullah masalah penggunaan hasil zakat pada hal-hal yang dapat meyakinkan wajib zakat, dan masalah ini pada kenyataannya memiliki tingkat kepentingan yang membuat teori modern tentang pajak menjadikannya faktor dasar dalam keberhasilan atau kegagalan pajak apa pun; sebab perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangat bergantung pada cara negara menggunakan hasilnya. Jika kebijakan pengeluaran tidak bijaksana, atau tidak jelas, atau tidak meyakinkan wajib pajak, sehingga ia dapat merasakan dampaknya terhadap layanan yang diberikan kepadanya atau terlaksananya proyek-proyek yang berhasil, maka ia akan berusaha keras untuk melepaskan diri dari kewajiban perpajakannya.
Sebab Kedua: Lemahnya Kesadaran Islam Secara Umum, dan Kesadaran Zakat Secara Khusus:
Sesungguhnya lemahnya kesadaran Islam secara umum, dan kesadaran zakat secara khusus, tidak tersembunyi pengaruhnya bagi siapa pun dalam mengabaikan urusan zakat dan tidak memperhatikan kewajibannya, dan ini serupa dengan apa yang disebutkan para ahli keuangan bahwa semakin meningkat kesadaran keuangan, semakin lemah dorongan untuk menggelapkan, dan sebaliknya semakin lemah kesadaran keuangan semakin kuat dan nyata dorongan untuk menggelapkan pajak.
Berdasarkan ini, semakin kuat kesadaran Islam khususnya berkaitan dengan zakat, semakin sedikit penggelapan darinya, dan demikian ada sebab-sebab lain yang dapat diperhatikan oleh administrasi dan para penanggung jawab urusan zakat, dari waktu ke waktu, sesuai dengan keadaan yang berlaku di masyarakat.
Memerangi Penggelapan dari Menunaikan Zakat
Oleh karena itu, sekarang kita berbicara tentang tindakan-tindakan yang menjamin pencegahan penggelapan dari zakat:
Ada banyak tindakan yang dapat mencegah penggelapan dari zakat, dan di antara tindakan-tindakan terpenting tersebut adalah keadilan administrasi atau para penanggung jawab pemungutan zakat, dan keadilan ini mencakup keadilan dalam pemungutan dan keadilan dalam pendistribusian.
Mengenai keadilan dalam pemungutan, topik ini mengharuskan kami untuk menjelaskan hubungan petugas pemungutan dengan wajib zakat. Hubungan ini kita dapati tunduk pada beberapa hal, yang terpenting di antaranya: sejauh mana wajib zakat menghormati petugas, dan sejauh mana perasaannya bahwa petugas memberikan pelayanan kepadanya lebih daripada sebagai pemungut zakat yang wajib atasnya, dan oleh karenanya masuk akallah bahwa dasar hubungan ini adalah pemilihan petugas itu sendiri. Al-Mawardi telah menyebutkan syarat-syarat yang dipertimbangkan bagi petugas zakat, yang terpenting di antaranya: bahwa petugas harus merdeka, muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat.
Di antara keadilan dalam kebijakan keuangan yang dimiliki pemimpin terhadap siapa yang ia tugaskan untuk mengurus zakat adalah bahwa ia mengawasinya, menghisabnya, menahannya, memberhentikannya, dan menyita apa yang dimilikinya, seluruhnya atau sebagiannya, jika ia mengetahui bahwa ia telah menjadi kaya dari pemungutan harta bukan dengan cara yang benar.
Fikih Islam tidak cukup hanya menentukan syarat-syarat pemilihan petugas zakat, bahkan menekankan tanggung jawab pemungut sedekah di hadapan Allah Azza wa Jalla atas setiap kezaliman yang dilakukannya terhadap wajib zakat. Diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Petugas sedekah yang bekerja dengan benar, seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menghisab para petugasnya atas apa yang ada di tangan mereka dengan penghisaban yang teliti.
Mengenai Pendistribusian Zakat: Jika buruknya pendistribusian hasil pajak dalam sistem-sistem sekuler dapat mengakibatkan wajib pajak menggelapkan pembayaran pajak sebagaimana kami sebutkan, maka kita dapati bahwa zakat telah didistribusikan dengan baik. Al-Quran Al-Karim telah mengkhususkan penggunaan hasil zakat untuk delapan sasaran, menentukannya secara terbatas, yang ditargetkan untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, yang diupayakan syariat Islam dengan seluruh sumbernya untuk meyakinkan para wajib zakat akan pentingnya. Sasaran-sasaran ini disebutkan Allah Tabaraka wa Ta’ala dalam firman-Nya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan” (Surat At-Taubah: sebagian dari ayat 60).
Dari pengkhususan ayat mulia ini sebagian hasil zakat untuk para amil zakat, hal itu menunjukkan bahwa hasil zakat memiliki rekening tersendiri, dan memiliki anggaran tersendiri, dibayarkan dari hasilnya apa yang dibelanjakan untuknya, dan inilah yang membenarkan keberadaan material hasil zakat dalam pandangan wajib zakat, dan menjadikan penggunaannya sebagai hal yang nyata.
Di antara tindakan-tindakan juga yang mencegah penggelapan dari menunaikan zakat:
Pengharaman Penipuan untuk Menggugurkan Zakat: Tindakan ini dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk memerangi penggelapan dari menunaikan zakat. Kita telah melihat melalui pembahasan kami tentang bentuk-bentuk penggelapan dari menunaikan zakat bahwa para ahli fikih bersepakat tentang pengharaman tindakan dengan segala jenisnya terhadap harta setelah wajibnya zakat padanya; sebagai penipuan untuk menggugurkan zakat, dan tidak dianggapnya tindakan ini. Juga kita melihat mayoritas mereka berpendapat tentang pengharaman tindakan terhadap harta sebelum wajibnya zakat padanya dalam waktu singkat seperti sebulan misalnya; sebagai penipuan untuk menggugurkan zakat, dan tidak dianggapnya tindakan ini.
Dalam makna ini Abu Yusuf berkata dalam kitabnya (Al-Kharaj):
Tidak halal bagi seorang lelaki yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir mencegah sedekah, dan tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada kepemilikan kelompok lain; untuk memecahnya dengan itu, sehingga batallah sedekah darinya, dengan menjadikan bagi setiap orang dari unta, sapi, dan kambing jumlah yang tidak wajib sedekah padanya, dan tidak boleh melakukan tipu daya untuk membatalkan sedekah dengan cara dan alasan apa pun.
Juga di antara hal-hal yang mencegah penggelapan dari zakat:
Menetapkan Hukuman Duniawi Berupa Sanksi Keuangan dan Pidana, serta Hukuman Akhirat atas Penggelap:
Di antara sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada penggelap dari menunaikan zakat adalah sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Pada setiap unta penggembalaan, pada setiap empat puluh ekor bintu labun (anak unta betina), tidak dipisah-pisahkan unta dari perhitungannya, dan barangsiapa yang memberikannya dengan mengharap pahala maka baginya pahalanya, dan barangsiapa yang mencegahnya maka sesungguhnya aku akan mengambilnya, dan separuh untanya, azam dari azam Rabb kami Tabaraka wa Ta’ala.” Hadits ini merupakan hujjah dalam pengambilan zakat dari yang enggan, dan jatuhnya pada tempatnya, dan pengambilan separuh unta orang yang enggan, dan dengan ungkapan lain penyitaan separuh hartanya, dianggap sebagai jenis sanksi keuangan yang digunakan pemimpin ketika diperlukan; untuk mendidik dengannya para penggelap, dan ia termasuk sanksi ta’zir yang tunduk kepada pemimpin sesuai dengan apa yang dilihatnya mewujudkan kemaslahatan umum.
Urusan hukuman penggelap dari menunaikan zakat tidak berhenti pada sanksi keuangan saja, bahkan ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penggelap, jika sanksi keuangan tidak berhasil dengannya. Dalam hal ini Imam Al-Mawardi berkata:
Adapun jika seseorang meninggalkan zakat, maka ia tidak dibunuh karenanya, tetapi zakat diambil secara paksa dari hartanya, dan ia diberi hukuman jika menyembunyikannya tanpa ada keraguan. Jika pengambilan zakat tidak memungkinkan karena penolakannya, maka ia diperangi karenanya, dan jika peperangan itu berujung pada kematiannya sampai zakat tersebut diambil darinya, sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Lihat dalam hal ini kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah karya Al-Mawardi halaman 192 dan seterusnya.
Dalam masalah ini juga Ibnu Hazm berkata:
Hukum orang yang menolak membayar zakat adalah bahwa zakat diambil darinya, baik ia suka atau tidak. Jika ia menghalanginya, maka ia adalah orang yang memerangi (negara), dan jika ia mengingkarinya, maka ia adalah orang murtad. Jika ia menyembunyikannya dan tidak menghalanginya, maka ia telah melakukan kemungkaran, sehingga wajib diberi hukuman atau dipukul sampai ia menghadirkannya, atau mati terbunuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam laknat Allah, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya jika ia mampu” dan ini adalah kemungkaran, maka wajib bagi orang yang mampu untuk mengubahnya sebagaimana kami sebutkan.
Maka hukuman bagi orang yang menghindari zakat, sebagaimana tampak dari nash-nash tersebut, tidak terbatas pada denda finansial saja, bahkan dapat melampaui itu hingga hukuman fisik yang sesuai.
Perlu diperhatikan bahwa syariat Islam tidak membatasi hukuman bagi orang yang menghindari pembayaran zakat hanya pada hukuman duniawi berupa finansial dan fisik saja, bahkan ia juga menetapkan hukuman akhirat bagi orang yang menghindarinya. Telah diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa diberi harta oleh Allah dan ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat akan diwujudkan untuknya seekor ular tanduk yang memiliki dua bintik racun, melilit lehernya pada hari kiamat, kemudian menggigit kedua pipinya, lalu berkata: Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini” “Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa (kikir) itu baik bagi mereka. Sebenarnya (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di leher mereka) pada hari kiamat.” (Surah Ali Imran, ayat 180). Diriwayatkan juga dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak dan tidak menunaikan haknya (zakatnya), kecuali pada hari kiamat akan dijadikan lempeng-lempeng dari api untuknya, kemudian dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dengannya lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali dingin, dikembalikan lagi padanya di hari yang lamanya lima puluh ribu tahun, hingga diputuskan (hukuman) di antara para hamba, lalu ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka.”
Hukuman-hukuman yang kami sebutkan baik di dunia maupun akhirat ini, tidak diragukan lagi adalah hukuman-hukuman yang memberikan efek jera yang dapat mencegah setiap orang yang terdorong untuk menghindari pembayaran zakat dari melakukan penghindaran ini. Maka ia adalah pencegah dari akhlak buruk ini, yaitu penghindaran dari pembayaran zakat, dan dengan itu memberantas bahaya paling serius yang mengancam prinsip yang harus menjadi dasar distribusi beban finansial yang ditanggung oleh individu-individu di negara, yaitu kesetaraan di antara mereka dalam menanggung beban. Dengan memberantas bahaya penghindaran ini, prinsip umum ini akan terwujud, dan setiap warga negara akan berkontribusi dalam biaya-biaya umum finansial yang ditetapkan di negara Islam.
Juga dikenal dalam fikih Islam: Pemotongan dari Sumber:
Artinya, kita mengambil pajak sebelum seorang Muslim mengambil hartanya. Maka diterapkan cara pemotongan dari sumber, sebagai prosedur yang mencegah wajib pajak dari menghindari pembayaran zakat. Telah diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila memberikan tunjangan kepada orang-orang -yaitu gaji mereka- ia bertanya kepada seseorang: Apakah engkau memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jika ia berkata: Ya, maka diambil dari tunjangannya sejumlah harta itu, dan jika ia berkata: Tidak, maka diserahkan kepadanya tunjangannya dan tidak diambil darinya sesuatu pun.
Demikian juga Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu, apabila tunjangan dikeluarkan, ia mengambil zakat dari harta yang hadir untuk yang hadir maupun yang tidak hadir. Juga Umar bin Abdul Aziz apabila memberikan kepada seseorang upahnya, yaitu gajinya, ia mengambil darinya zakat, dan apabila mengembalikan harta yang dizalimi, ia mengambil darinya zakat, dan ia mengambil zakat dari tunjangan-tunjangan ketika keluar untuk para penerimanya. Lihat dalam hal ini kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid halaman 526 dan seterusnya.
Pengakuan Kekayaan:
Syariat Islam mewajibkan kepada wajib pajak untuk mengakui harta yang mereka miliki secara jujur kepada petugas zakat, dan tidak menyembunyikannya dari mereka. Yang menunjukkan hal itu adalah dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada anak-anaknya: Wahai anak-anakku, apabila petugas zakat datang kepada kalian, janganlah kalian sembunyikan dari mereka sedikitpun harta ternak kalian. Sesungguhnya jika ia berlaku adil kepada kalian, maka itu adalah kebaikan bagi kalian dan baginya, dan jika ia berlaku zalim kepada kalian, maka itu adalah keburukan baginya dan kebaikan bagi kalian. Diriwayatkan dari Zahir bin Yarbu’ bahwa seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berkata: Apakah aku sembunyikan dari mereka -yaitu petugas zakat- kambing terbaik dari harta bendaku, yaitu kambing yang bagus? Maka ia berkata: Tidak, apabila mereka mendatangi kalian janganlah kalian durhaka kepada mereka, dan apabila mereka pergi janganlah kalian caci mereka, sehingga kalian menjadi orang yang durhaka yang meringankan (beban) orang zalim. Tetapi katakanlah: Ini adalah hartaku, dan ini adalah haknya, maka ambillah haknya dan tinggalkan yang batil. Jika ia mengambilnya dengan berlebihan, dan jika ia melampaui batas ke yang lain, akan dikumpulkan untukmu di timbangan pada hari kiamat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Usaid radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya berkata: Sesungguhnya hak bagi orang-orang apabila petugas zakat datang kepada mereka agar menyambutnya dengan baik, dan mengabarkan kepadanya tentang seluruh harta mereka, dan tidak menyembunyikan darinya sesuatu pun. Jika ia berlaku adil, itulah jalannya, dan jika selain itu dan ia melampaui batas, maka tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri, dan Allah akan menggantinya, yaitu mengganti mereka atas apa yang diambil dari mereka.
Tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam dengan ini, yaitu dengan pengakuan kekayaan, telah mendahului para ahli keuangan publik kontemporer yang menyerukan perlunya bekerja untuk menghilangkan penyebab ketegangan antara wajib pajak dan petugas pajak, agar meningkat kepercayaan dan terwujud kerja sama di antara mereka, karena hubungan antara wajib pajak dan petugas pemungut harus jauh dari segala bentuk permusuhan. Oleh karena itu, pada saat ini administrasi keuangan berupaya keras untuk memperbaiki hubungannya dengan wajib pajak, dan menghilangkan penyebab ketidakpercayaan dan ketegangan antara mereka. Hal itu akan menghasilkan penanggulangan penghindaran pajak.
Juga: Seorang Muslim harus mengetahui bahwa zakat tetap menjadi utang di pundak Muslim, tidak terlepas tanggungannya darinya, dan tidak sah keislamannya kecuali dengan menunaikannya, meskipun bertambah-tambah tahun. Dalam makna ini Imam Ibnu Hazm berkata:
Barangsiapa terkumpul pada hartanya dua zakat atau lebih, dan ia masih hidup, maka ditunaikan semuanya untuk setiap tahun sesuai jumlah yang wajib atasnya setiap tahun, baik itu karena ia melarikan diri dengan hartanya, atau karena keterlambatan petugas, atau karena kebodohannya, atau karena selain itu. Sama saja dalam hal itu (zakat) uang, tanaman, dan ternak, baik zakat itu menghabiskan seluruh hartanya atau tidak, baik hartanya kembali setelah pengambilan zakat darinya kepada (jumlah) yang tidak ada zakatnya atau tidak kembali, dan para pemberi utang tidak mengambil sesuatu pun sampai zakat dipenuhi.
Dengan demikian kita melihat bahwa pendekatan syariat Islam berbeda dari pendekatan perundang-undangan keuangan modern yang mengambil prinsip gugurnya pajak karena kedaluwarsa dengan lewatnya jangka waktu tertentu tanpa tuntutan. Artinya, zakat tidak gugur karena kedaluwarsa.
Inilah prosedur-prosedur terpenting yang menjamin pencegahan penghindaran dari pembayaran zakat, dan mengambilnya -tidak diragukan lagi- akan menjadi penghalang antara orang yang terdorong untuk menghindari pembayaran zakat dengan penghindaran ini. Kita mengetahui bahwa memberantas penghindaran dari pembayaran zakat berarti semua orang berkontribusi dalam biaya-biaya umum finansial yang ditetapkan di negara tanpa terkecuali, dan dengan demikian terwujud kesetaraan penuh antara wajib pajak dalam menanggung biaya-biaya umum finansial di negara, yang terpenting di antaranya adalah zakat.
Di antara hal-hal yang perlu kami perhatikan adalah memperhatikan kondisi wajib pajak, karena -sebagaimana kami katakan- kami mempelajari zakat ini atau sumber-sumber lain dari kas negara, kami mempelajarinya dari sisi kesetaraan dan dari sisi keadilan. Keadilan juga menuntut agar zakat dibebankan dalam jumlah tertentu yang sesuai dengan wajib pajak, dan inilah yang disebut dengan memperhatikan kondisi wajib pajak pembayar zakat.
Kami katakan: Karena tujuan dari pemungutan zakat adalah untuk menyebarkan manfaat, maka tidak seharusnya zakat dibebankan kepada wajib pajak dengan cara yang kaku, tidak memperhatikan kondisi mereka, dan tidak peduli untuk menyediakan keadilan yang dituntut oleh Islam dalam segala urusan kehidupan dalam masyarakat. Keadilan menuntut agar wajib pajak berpartisipasi dalam berkontribusi untuk pembiayaan negara sesuai dengan kemampuan finansialnya, yaitu agar beban-beban finansial umum didistribusikan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan mereka.
Sesungguhnya keumuman dalam zakat meskipun memiliki kepentingan yang sangat besar, tetapi ia harus dipasangkan dengan gagasan lain yaitu sifat personal dari beban zakat itu sendiri. Tidak cukup setiap individu menanggung beban zakat, tetapi harus sesuai beban ini dengan kemampuan finansial wajib pajak dan kondisi pribadinya. Islam telah lebih dahulu mengadopsi gagasan kemampuan finansial wajib pajak. Beban-beban finansial Islam dibebankan atas dasar kapasitas finansial, yaitu kemampuan untuk membayar. Dasar dalam Islam adalah bahwa pembebanan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Dalam hal itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Surah Al-Baqarah, ayat 285). Al-Qur’an telah menentukan kapasitas finansial ini dengan firman-Nya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.'” (Surah Al-Baqarah, ayat 219). Al-‘afw (yang lebih dari keperluan) adalah kelebihan yang mudah didapat yang melebihi kecukupan dan kebutuhan. Ayat Al-Qur’an telah datang menegaskan kewajiban berinfak dari kelebihan yang melebihi kebutuhan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.” (Surah Al-Baqarah, ayat 236).
Jika kami mengatakan perlunya kesetaraan antara kaum muslimin dalam pembebanan zakat, ketika terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk wajibnya zakat, maka itu tidak berarti bahwa jumlah yang dibayarkan setiap individu dari zakat harus sama, bagaimanapun berbedanya kemampuan finansial mereka untuk membayar, karena kesetaraan dalam hal ini adalah kezaliman, karena ia adalah kesetaraan antara yang tidak sama. Adapun jika kemampuan finansial dan kondisi sosial sekelompok wajib pajak setara, maka harus sama jumlah yang diambil dari setiap individu dari kelompok ini dalam zakat. Maka yang dimaksud dengan kesetaraan dalam bidang ini adalah bahwa setiap individu menanggung bagian dari beban-beban finansial yang sesuai dan sebanding dengan kemampuan finansialnya untuk membayar. Semua membayar zakat sesuai dengan jumlah kekayaan mereka, dan setelah memperhatikan kondisi pribadi dan keluarga mereka.
Kami simpulkan dari yang telah dikemukakan bahwa tidak bertentangan dengan kesetaraan dalam bidang ini pembebasan orang yang tidak memiliki nisab dari kewajiban zakat, atau orang yang memiliki nisab yang tidak berlebih dari kebutuhan pokoknya, atau orang yang memiliki utang yang menghabiskan seluruh atau sebagian nisab zakatnya, atau pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk harta yang dikeluarkan zakatnya. Kami akan membicarakan hal itu dengan rincian yang sesuai berikut ini.
Pembebasan (Harta) di Bawah Nisab dari Zakat:
Dari keadilan Islam dalam pemungutan zakat bahwa ia membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat, dan tidak mewajibkannya kecuali pada harta yang mencapai nisab penuh. Itu agar pengambilan zakat dari kelebihan yang mudah bagi jiwa dan tidak menyulitkannya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.'” Al-‘afw ditafsirkan sebagai apa yang melebihi kecukupan dan kebutuhan. Dasar dari pembebasan ini adalah bahwa Islam mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya dari umat, untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Nisab adalah batas minimal kekayaan menurut pandangan syariat. Barangsiapa tidak memiliki nisab ini, ia tidak memiliki kekayaan yang mewajibkan zakat, dan oleh karena itu tidak ada artinya mengambil zakat darinya, karena ia membutuhkan untuk dibantu, bukan untuk membantu. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik sedekah adalah yang (dikeluarkan) dari kelebihan kekayaan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.”
Hikmah Pensyaratan Nishab Tertentu Untuk Wajib Zakat Dan Pembebasan Kebutuhan Pokok Serta Pengurangan Utang Dan Biaya
Hikmah dari disyaratkannya nishab tertentu untuk wajib zakat adalah karena orang kaya merupakan yang dibebani untuk menunaikan zakat, maka perlu ditentukan kadar yang dengannya seseorang dianggap kaya. Jika seseorang tidak memiliki kadar tersebut, maka ia dianggap fakir, tidak hanya dibebaskan dari menunaikan zakat, bahkan ia juga boleh menerima zakat. Karena harta yang kurang dari nishab dianggap sebagai batas minimum yang diperlukan untuk hidup, sehingga jika seseorang tidak mencapai nishab, maka ia berhak menerima zakat.
Islam menetapkan untuk setiap jenis harta nishab tertentu, zakat tidak wajib pada harta yang kurang dari nishab tersebut. Hal ini untuk memperhatikan kondisi mukallaf (orang yang dibebani kewajiban). Kami telah menyebutkan hal itu sebelumnya, kami telah menyebutkan nishab tanaman, buah-buahan, dan lainnya, maka cukuplah apa yang telah kami sebutkan di sana.
Pembebasan batas minimum yang diperlukan untuk hidup:
Sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa nishab harus berlebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan demikian terwujud makna kaya dan makna nikmat, dan dengannya terlaksana pembayaran dengan lapang dada. Karena harta yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok, pemiliknya tidak dianggap kaya darinya, dan tidak dianggap sebagai nikmat. Karena kenikmatan tidak terwujud kecuali dengan kadar yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok, karena itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup dan penopang badan.
Kebutuhan pokok adalah apa yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang membantunya dalam hal itu seperti buku-buku ilmunya, alat-alat pekerjaannya, dan semacamnya. Sebagian ulama Hanafiyah menafsirkan kebutuhan pokok dengan perkataan: yaitu apa yang menolak kebinasaan dari manusia secara nyata seperti nafkah, rumah tempat tinggal, alat-alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menolak panas atau dingin, atau secara perkiraan seperti utang. Karena orang yang berutang membutuhkan untuk melunasinya dengan apa yang ada di tangannya dari nishab, untuk menolak dari dirinya penjara yang seperti kebinasaan. Dan seperti alat-alat pekerjaan, perabotan rumah, hewan tunggangan, buku-buku ilmu untuk ahlinya, karena kebodohan menurutnya seperti kebinasaan. Jika ia memiliki uang yang harus ia belanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan itu, maka uang itu seperti tidak ada.
Yang dipertimbangkan di sini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok mukallaf zakat dan orang yang ia nafkahi dari istri, anak-anak berapa pun jumlah mereka, orang tua, dan kerabat yang wajib ia nafkahi, karena kebutuhan mereka adalah kebutuhannya.
Kebutuhan pokok ini oleh sebagian ulama kontemporer disebut dengan batas kecukupan, yang harus tersedia bagi manusia, karena itu berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang layak. Maksudnya adalah seseorang dianggap fakir jika tidak tersedia baginya kebutuhan-kebutuhannya dengan kadar yang membuatnya hidup berkecukupan dan kaya dari orang lain. Jaminan batas kecukupan dalam Islam adalah perkara suci, karena itu merupakan hak Allah yang lebih tinggi dari semua hak, dan mengingkari atau mengabaikannya merupakan pengingkaran terhadap agama itu sendiri.
Yang menunjukkan pembebasan ini adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Sedekah terbaik adalah dari kelebihan harta, dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu.” Hadits ini menunjukkan bahwa syarat orang yang bersedekah adalah tidak membutuhkan untuk dirinya sendiri atau bagi orang yang wajib ia nafkahi. Hal ini juga ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.” Hadits ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia dan kebutuhan keluarganya yang wajib ia nafkahi, didahulukan atas kebutuhan orang lain.
Pembebasan ini dalam kenyataannya tidak bertentangan dengan prinsip kesamaan antara mukallaf dalam menanggung beban zakat, karena kebutuhan manusia didahulukan atas kebutuhan orang lain. Demikian juga kebutuhan keluarganya, anaknya, dan orang yang ia nafkahi adalah seperti kebutuhan dirinya sendiri. Bagaimana kita meminta darinya zakat dari apa yang ia butuhkan dan hatinya terikat padanya karena sangat membutuhkannya, padahal kita telah melihat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kesamaan dalam bidang ini adalah setiap individu menanggung sebagian beban keuangan yang sesuai dengan kemampuan finansialnya untuk membayar. Tidak diragukan bahwa orang yang sangat membutuhkan harta yang ada padanya, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar. Oleh karena itu, membebaskannya dari zakat tidak bertentangan dengan prinsip kesamaan antara mukallaf dalam menanggung beban-beban umum yang ditetapkan di negara.
PENGURANGAN UTANG:
Di antara perkara yang dipertimbangkan dalam hal mukallaf zakat adalah pengurangan utang. Kemampuan finansial wajib zakat berbeda tergantung apakah ia berutang atau tidak berutang. Oleh karena itu, memperhatikan kemampuan untuk membayar menuntut wajibnya mengurangi beban utang dari harta yang menjadi objek zakat, sebelum mewajibkan zakat padanya. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama fikih, karena mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat atas orang yang memiliki utang yang menghabiskan semua nishab atau sebagiannya, meskipun utang itu bukan dari jenis harta yang dizakati.
Utang menurut mereka menghalangi wajibnya zakat pada seluruh harta. Barangsiapa memiliki harta yang wajib zakatnya dan ia memiliki utang, maka hendaknya ia mengeluarkan darinya kadar untuk melunasinya terlebih dahulu, kemudian ia zakati sisanya jika mencapai nishab. Makna perkataan ulama fikih ini adalah hendaknya ia terlebih dahulu mengurangi utang yang ada padanya, kemudian setelah itu apa yang tersisa setelah utang-utang ini, jika mencapai nishab maka ia zakati, dan jika tidak mencapai nishab maka tidak ada zakat atasnya.
Sebagian ulama berkata dalam masalah ini: Barangsiapa memiliki utang yang menghabiskan hartanya, dan ia memiliki penuntut dari pihak hamba, baik itu untuk Allah Azza wa Jalla seperti zakat, atau untuk manusia seperti pinjaman, harga barang, ganti rugi kerusakan, denda luka, mahar wanita, baik dari uang atau selainnya, baik yang jatuh tempo atau yang ditangguhkan, maka tidak ada zakat atasnya. Karena nishab tersibukkan dengan kebutuhan pokok orang yang berutang, yaitu ia dipersiapkan untuk apa yang menolak kebinasaan darinya secara nyata atau perkiraan, karena ia membutuhkannya untuk melunasi utangnya.
Ada banyak riwayat yang mendukung pengurangan utang: di antaranya apa yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa ia berkata: Ini adalah bulan zakat kalian, barangsiapa memiliki utang hendaknya ia lunasi agar kalian mengeluarkan zakat harta kalian. (Riwayat-riwayat ini terdapat dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid halaman 534 dan seterusnya), agar diketahui apa yang tersisa dari harta setelah melunasi utang, lalu mengeluarkan zakatnya jika mencapai nishab.
Juga apa yang diriwayatkan dari Maimun bin Mihran bahwa ia berkata: Jika tiba waktumu berzakat, maka lihatlah semua hartamu, kemudian kurangi darinya apa yang menjadi utangmu, kemudian zakati apa yang tersisa.
Dan apa yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki harta dan memiliki utang, apakah ada zakat atasnya? Ia menjawab: Tidak, ini jika apa yang tersisa dari harta setelah melunasi utang tidak mencapai nishab.
Pengurangan utang dari harta yang dipersiapkan untuk zakat sejalan dengan ruh syariat Islam. Zakat tidak disyariatkan kecuali dari kelebihan harta, sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita tentang itu. Tidak ada kekayaan pada orang yang berutang, dan ia membutuhkan untuk melunasi utangnya, seperti kebutuhan orang fakir atau lebih. Tidak bijaksana menelantarkan kebutuhan pemilik untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
Dari apa yang telah disebutkan, kita melihat bahwa utang yang menghabiskan semua nishab atau sebagiannya, menghalangi wajibnya zakat pada seluruh harta, karena zakat dibebankan berdasarkan kemampuan dan kelapangan mukallaf. Kemampuan ini ditentukan berdasarkan bebasnya tanggungan mukallaf dari utang. Selain itu, zakat diambil dari orang kaya untuk dikembalikan kepada orang fakir, dan orang yang berutang tidak mungkin diambil darinya zakat, karena ia termasuk orang yang terlilit utang yang berhak menerima zakat.
Ini yang ditetapkan oleh Abu Ubaid dengan perkataannya: Jika utang itu benar dan telah diketahui bahwa itu menjadi tanggungan pemilik tanah, maka tidak ada sedekah atasnya, tetapi itu gugur darinya karena utangnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Thawus, Atha’, dan Makhul. Dengan pendapat mereka juga bahwa itu sesuai dengan mengikuti Sunnah, tidakkah engkau lihat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mensyariatkan agar sedekah diambil dari orang kaya lalu dikembalikan kepada orang fakir. Orang yang memiliki utang yang menghabiskan hartanya, tidak memiliki harta, dan ia termasuk ahli sedekah (penerima sedekah). Bagaimana mungkin diambil darinya sedekah sementara ia termasuk ahlinya, atau bagaimana mungkin ia kaya sekaligus fakir dalam satu keadaan? Selain itu, ia termasuk orang yang terlilit utang, salah satu dari delapan golongan, maka ia berhak menerimanya dari dua sisi. (Lihat dalam hal itu Al-Amwal karya Abu Ubaid halaman 612 dan seterusnya).
Pembebasan orang yang memiliki utang yang menghabiskan semua nishab atau sebagiannya dari menunaikan zakat, menurut keyakinan kami tidak bertentangan dengan prinsip kesamaan antara mukallaf dalam menanggung beban zakat, karena orang yang berutang telah terpengaruh kemampuan finansialnya untuk menunaikan zakat. Zakat tidak dibebankan kecuali berdasarkan kemampuan dan usaha – sebagaimana kita lihat. Dan juga orang yang berutang karena adanya utang padanya menjadi berhak menerima zakat dengan sifat orang yang terlilit utang yang termasuk golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan. Dan juga ia berhak menerimanya dengan sifat kefakiran, karena orang yang berutang bukanlah orang kaya.
Kita simpulkan dari itu bahwa pembebasan orang yang berutang dari menunaikan zakat tidak bertentangan dengan prinsip kesamaan antara mukallaf dalam menanggung beban-beban umum keuangan yang ditetapkan di negara, termasuk zakat.
PENGURANGAN NAFKAH DAN BIAYA:
Di antara perkara yang kita perhatikan dalam hal mukallaf zakat adalah pengurangan nafkah dan biaya. Pembuat hukum Islam mengambil dengan mewajibkan zakat pada pendapatan bersih. Dalam zakat tanaman dan buah-buahan, sebagian ulama fikih berpendapat mengurangi utang yang dipinjam oleh pemilik tanaman dan buah-buahan untuk membiayai tanaman. Yang menunjukkan hal itu adalah riwayat-riwayat berikut:
Apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa ia berkata tentang laki-laki yang berutang lalu membiayai keluarganya dan tanahnya, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Ia melunasi apa yang ia biayakan untuk tanahnya. Dan Ibnu Umar berkata: Ia melunasi apa yang ia biayakan untuk tanahnya dan keluarganya. Artinya ia mengurangi nafkah-nafkah ini dari harta terlebih dahulu, jika tersisa harta yang mencapai nishab maka wajib zakatnya, dan jika tidak mencapai nishab maka tidak ada zakat atasnya. Diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dengan perkataannya: Ibnu Umar berkata: Ia dahulukan apa yang ia pinjam lalu melunasinya, dan zakati apa yang tersisa. Dan Ibnu Abbas berkata: Ia lunasi apa yang ia biayakan untuk buah-buahan, kemudian zakati apa yang tersisa. (Ini terdapat dalam Al-Kharaj karya Yahya bin Adam Al-Qurasy halaman 162 dan seterusnya).
Diriwayatkan bahwa Syarik ditanya tentang laki-laki yang menyewa tanah dari tanah ‘usyur dengan makanan tertentu lalu ia menanaminya dengan makanan, ia berkata: Ia sisihkan apa yang menjadi kewajibannya dari makanan, kemudian zakati apa yang tersisa.
Dari ini jelas bahwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Syarik, telah sepakat bahwa utang yang dibiayakan untuk tanah dan buah-buahan, dikurangi sebelum menunaikan zakat.
Diriwayatkan dari Makhul bahwa ia berkata tentang pemilik tanaman yang berutang: Tidak diambil darinya zakat hingga ia melunasi utangnya, dan apa yang tersisa setelah itu ia zakati jika termasuk yang wajib zakat padanya. (Riwayat-riwayat ini juga terdapat dalam Al-Amwal karya Abu Ubaid halaman 611 dan seterusnya).
Kita lihat dari yang telah disebutkan bahwa zakat hanya pada pendapatan atau kekayaan bersih. Petani boleh mengurangi apa yang ia biayakan untuk tanamannya kemudian zakati apa yang tersisa jika mencapai nishab. Artinya pemilik tanaman jika berutang untuk membiayai tanaman dan buah-buahan, seperti membeli pupuk atau membeli apa yang ia gunakan untuk melawan hama pertanian, maka itu dikurangi dan tidak dihitung apa yang wajib zakatnya, kecuali setelah mengurangi apa yang ia biayakan untuk pertumbuhan tanaman dari pupuk dan apa yang ia biayakan untuk melindunginya dari hama.
Dan diqiyaskan pada tanaman yang lainnya seperti pendapatan pabrik, bangunan, dan semacamnya. Adapun mengenai harta perniagaan, maka nafkah-nafkah dikurangi secara nyata, karena zakat hanya diambil dari apa yang tersisa dari modal dan keuntungan sampai akhir haul (satu tahun). Apa yang berupa nafkah telah habis, kecuali jika masih ada dinar, seperti sewa tempat yang belum dibayar maka dikurangi, dan zakati sisanya.
Adapun mengenai hewan ternak, maka apa yang dibiayakan untuknya dikurangi dari nishab zakat, seperti tanaman dan harta perniagaan.
Dengan ini kita telah selesai dari kuliah ini. Saya titipkan kalian kepada Allah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelajaran 6: Jizyah, Kharaj, dan Usyur
1 – Dari Sumber-Sumber Keuangan: “Jizyah”
Keumuman dalam Jizyah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu junjungan kami Muhammad, beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita melanjutkan pembicaraan kita dalam kuliah ini tentang sumber-sumber keuangan dalam Islam, maka kita katakan:
Syariat Islam mewajibkan kepada orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam beberapa kewajiban keuangan yang terwujud dalam jizyah, kharaj, dan usyur. Hal itu bukanlah—sebagaimana dikatakan oleh sebagian orientalis—bukan sebagai hukuman bagi mereka karena tidak memeluk Islam, melainkan beban-beban keuangan tersebut adalah pajak-pajak yang adil sepenuhnya dalam segala bentuknya. Kehidupan dalam setiap masyarakat, di setiap zaman, berdiri atas dasar hak dan kewajiban. Orang-orang non-Muslim di negara Islam telah menikmati banyak hak, dan setiap hak pasti ada kewajiban yang mengimbanginya. Orang-orang non-Muslim yang tinggal di masyarakat Islam memiliki kebebasan, perdagangan, dan mu’amalah (transaksi) yang sama seperti kita. Sebagai imbalannya, mereka wajib memberikan sebagian dari harta mereka kepada perbendaharaan umum—yaitu Baitul Mal—sebagaimana kaum Muslim menanggung banyak beban keuangan seperti zakat dan lainnya. Mereka harus menanggung bagian mereka dari beban-beban umum, yaitu dalam bentuk jizyah, kharaj, dan usyur, agar mereka ikut berkontribusi dalam pembangunan negara dan pengeluaran-pengeluaran umumnya. Untuk topik ini dapat merujuk kepada buku (Islam dan Ahli Dzimmah) karya Dr. Ali Hasan Al-Kharbuthli, Komite Ta’rif bil Islam, diterbitkan oleh Majelis Tinggi Urusan-Urusan Islam, buku nomor 49 tahun 1969 halaman 67.
Ini disamping bahwa kewajiban-kewajiban keuangan umum tersebut hanyalah bagian kecil dibandingkan dengan apa yang menjadi kewajiban pemerintah Islam dalam mempertahankan orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam, dan membantu para tentara yang melindungi mereka dari siapa saja yang menyerang mereka. Kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban keuangan umum yang menjadi tanggung jawab orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam.
Dan kita mulai dengan jizyah:
Jizyah dalam bahasa adalah bentuk fi’lah (kata benda) dari kata al-jaza’ (balasan/ganti rugi), jamaknya jizi, seperti lihyah (jenggot) dan lihi. Ia adalah apa yang diambil dari ahli dzimmah, yaitu berupa harta yang dengan itu orang kafir Kitabi (Ahli Kitab) mendapat jaminan perlindungan (dzimmah).
Jizyah secara syariat adalah: kewajiban yang diambil dari orang kafir sebagai imbalan tinggalnya di Darul Islam setiap tahun.
Sejarah Jizyah
Sesungguhnya jizyah bukanlah hal baru dalam Islam, bahkan sudah ada sejak awal peradaban kuno. Jizyah telah diberlakukan oleh orang-orang Yunani Athena terhadap penduduk pantai Asia Kecil, sekitar abad kelima Sebelum Masehi, sebagai imbalan perlindungan mereka dari serangan orang-orang Fenisia. Fenisia pada masa itu adalah wilayah yang tunduk kepada negeri Persia. Maka mudahlah bagi penduduk pantai-pantai tersebut membayar harta sebagai imbalan perlindungan itu. Bangsa Romawi memberlakukan jizyah kepada bangsa-bangsa yang mereka taklukkan di bawah kekuasaan mereka. Bangsa Persia juga memungut jizyah dari rakyat-rakyat mereka. Dapat merujuk dalam hal ini kepada buku (Sejarah Peradaban Islam) Juz 1 halaman 169 dan selanjutnya, karya Profesor Jurji Zaidan, cetakan 1902 Percetakan Al-Hilal Mesir.
Alasan-Alasan Pemberlakuan Jizyah
Sesungguhnya alasan yang menjadi dasar disyariatkannya jizyah menjadi pokok perbedaan pendapat di antara para fuqaha sebagai berikut:
Pertama: Sebagian berpendapat jizyah sebagai pengganti perlindungan:
Sebagian berpendapat bahwa jizyah diwajibkan kepada ahli dzimmah sebagai pengganti perlindungan, dan mereka dibebaskan darinya ketika tidak ada perlindungan. Mereka berdalil dengan apa yang tercantum dalam surat (Khalid bin Walid) kepada Shalubah bin Nastunah, ketika ia masuk ke Furat, yang isinya: “Sesungguhnya aku telah memberikan jaminan kepada kalian dengan jizyah dan perlindungan, maka bagi kalian jaminan perlindungan dan perlindungan. Selama kami melindungi kalian maka kami berhak atas jizyah, jika tidak maka tidak ada jizyah.” Artinya dalam hal ini ia menjelaskan bahwa ia mengambil jizyah dari mereka sebagai imbalan perlindungannya dari setiap serangan.
Al-Mawardi berkata dalam kitabnya (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah): Dan diwajibkan bagi mereka dengan membayarnya—yaitu jizyah—dua hak: pertama, tidak menyerang mereka, dan kedua melindungi mereka, agar mereka dengan tidak diserang menjadi aman, dan dengan perlindungan menjadi terjaga.
Jizyah sebagai pengganti dukungan (nushrah):
Sebagian berpendapat bahwa jizyah wajib atas ahli dzimmah sebagai pengganti dukungan yang tidak ada karena mereka bersikeras tetap kafir, karena siapa yang termasuk ahli Darul Islam wajib baginya mendukung negeri, dan badan mereka tidak layak untuk dukungan ini karena mereka condong kepada ahli negeri yang memusuhi. Maka diambil dari mereka harta untuk dibelanjakan kepada para pejuang yang melaksanakan dukungan terhadap negeri.
Jizyah sebagai pengganti jaminan keamanan dan penghormatan darah:
Sebagian berpendapat bahwa jizyah wajib atas ahli dzimmah sebagai balasan atas jaminan keamanan kaum Muslim bagi mereka dan penghormatan darah mereka.
Jizyah sebagai pengganti tempat tinggal:
Sebagian juga berpendapat bahwa kewajiban yang diambil dari orang kafir sebagai imbalan tinggalnya di Darul Islam setiap tahun, artinya sebagai imbalan memungkinkan mereka menetap di Darul Islam.
Jizyah sebagai Sarana untuk Mewujudkan Kesetaraan antara Warga Negara di Negara Islam
Pada dasarnya setiap orang yang menikmati fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh negara, wajib baginya menanggung sebagian dari beban-beban umum yang ditetapkan di negara, sesuai dengan kemampuan finansialnya, berdasarkan kaidah “keuntungan sebanding dengan kerugian” (al-ghunmu bil ghurmi). Karena tidak dapat diterima bahwa seseorang menikmati hak-hak umum dan khusus, menikmati fasilitas-fasilitas umum di negara, dan pada saat yang sama terlepas dari menunaikan bagiannya dari kewajiban-kewajiban dan beban-beban umum di negara yang ia nikmati kebaikan-kebaikannya. Dari sudut pandang ini kita lihat bahwa dasar pemberlakuan jizyah adalah bahwa ia merupakan sarana untuk mewujudkan kesetaraan di antara rakyat negara Islam. Maka wajib bagi setiap individu yang termasuk rakyat ini untuk berkontribusi dalam beban-beban keuangan umum di negara, agar sebagai imbalannya ia dapat menikmati hak-hak umum dan khusus, serta menikmati fasilitas-fasilitas umum di negara. Jika individu ini seorang Muslim maka yang wajib atasnya adalah membayar zakat—sebagaimana telah kita lihat—dari hartanya. Dan jika ia dari kalangan non-Muslim, yaitu ahli dzimmah, maka yang wajib atasnya adalah membayar jizyah. Dengan demikian terwujudlah kesetaraan antara rakyat-rakyat ini dalam menikmati hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka jizyah adalah bagian orang non-Muslim dari kewajiban-kewajiban keuangan umum yang dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat dalam fasilitas-fasilitas umum dan membantu orang-orang miskin non-Muslim.
Keumuman dalam Jizyah
Sesungguhnya keumuman dalam jizyah berarti bahwa jizyah harus dibayar oleh semua orang yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Maka tidak ada seorang pun yang dibebaskan dari membayarnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan juga keumuman berarti bahwa jizyah dikenakan atas semua harta yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya jizyah. Maksudnya bahwa keumuman dalam jizyah menggabungkan antara aspek pribadi dan aspek materiil. Oleh karena itu kita akan membahas tentang keumuman pribadi dan keumuman materiil dalam jizyah.
Mengenai Keumuman Pribadi, kita katakan:
Sesungguhnya orang yang dikenai jizyah harus terpenuhi padanya beberapa syarat, yang terpenting di antaranya:
Pertama: Bahwa ia laki-laki, karena jizyah hanya wajib atas laki-laki karena ia termasuk ahli perang. Adapun perempuan maka tidak ada jizyah atasnya karena ia bukan termasuk ahli perang.
Syarat kedua: Bahwa ia baligh (dewasa), maka jizyah tidak wajib atas anak-anak karena mereka tidak boleh dibunuh jika kaum Muslim menguasai mereka.
Syarat ketiga: Bahwa ia berakal, maka jizyah tidak wajib atas orang gila karena ia bukan termasuk ahli kewajiban.
Syarat keempat: Kemampuan untuk membayarnya, maka jizyah tidak wajib atas orang miskin yang tidak mampu membayarnya.
Dan juga disyaratkan bahwa pembayar jizyah sehat, maka ia tidak wajib atas orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, tidak atas orang tua renta, tidak atas orang lumpuh, dan tidak atas orang buta, karena ketidakmampuan mereka berperang.
Ini adalah syarat-syarat terpenting wajibnya jizyah, kami sebutkan secara ringkas dan terburu-buru, meskipun para fuqaha berbeda pendapat dalam sebagian syarat-syarat ini, dan mereka memiliki rincian-rincian yang berbeda yang tidak perlu disebutkan di sini karena bukan inti pembahasan.
Dan jika legislasi Islam telah menjadikan kewajiban zakat sebagai kewajiban umum dan menyeluruh bagi semua orang kaya Muslim—sebagaimana telah kita lihat—maka kita dapati bahwa legislasi yang sama mewajibkan jizyah kepada laki-laki yang mampu dan sehat. Maka ia bersifat umum bagi mereka, dan tidak ada seorang pun yang dibebaskan darinya karena kedudukan sosialnya atau keanggotaannya pada kelas tertentu. Maka prinsip kesetaraan dalam menunaikan jizyah terwujud bagi orang-orang yang dibebani membayarnya. Dan penerapan-penerapan praktis adalah bukti terbesar atas hal itu.
Di antara bukti-bukti pasti tentang terwujudnya kesetaraan antara pembayar jizyah adalah apa yang tercantum dalam surat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada penduduk Najran dan seluruh orang-orang Nasrani. Dalam surat ini disebutkan: “Dan tidak ada kharaj dan tidak ada jizyah kecuali atas orang yang di tangannya ada warisan dari warisan tanah, dari orang yang wajib baginya kepada penguasa suatu hak, maka ia menunaikan itu sebagaimana yang ditunaikan oleh orang yang semisal dengannya. Dan ia tidak dizalimi dan tidak diambil darinya kecuali sesuai kemampuan dan kekuatannya untuk menggarap tanah dan memakmurkannya serta memperoleh hasilnya. Dan ia tidak dibebani secara berlebihan dan tidak dilampaui batas hingga para pemilik kharaj dari orang-orang yang semisal dengannya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam surat ini memerintahkan kesetaraan antara orang-orang yang dibebani, dan tidak membedakan antara seorang dengan yang lain dalam jizyah atau kharaj, selama kondisi mereka sama, dan tidak membebani wajib pajak melebihi kemampuannya.
Di antara bukti-bukti atas hal itu juga adalah bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu tidak membebaskan orang-orang Nasrani Bani Taghlib dari jizyah, dan mereka adalah orang-orang Arab yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ia berdamai dengan mereka dengan mengambil dua kali lipat zakat dari mereka. Dapat dirujuk dalam hal ini (Al-Amwal) karya Abu Ubaid halaman 36 dan selanjutnya. Ini adalah bukti—yaitu apa yang diwajibkan Umar kepada orang-orang Nasrani Bani Taghlib—yang kuat bahwa siapa yang wajib atasnya jizyah tidak dibebaskan darinya, apapun kedudukan sosialnya.
Di antara bukti-bukti juga bahwa ketika terjadi perdamaian antara Amr bin Ash dengan Al-Muqauqis di Mesir, mereka bersepakat untuk mewajibkan kepada semua orang yang ada di Mesir bagian atas dan bawahnya, dari orang-orang Qibthi, dua dinar untuk setiap jiwa, baik orang mulia maupun orang biasa, dari siapa yang telah baligh. Maka jizyah diwajibkan kepada semua orang yang mampu di Mesir, berbeda dengan apa yang berlaku di sana pada masa Romawi, di mana orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan dibebaskan dari pajak. Tetapi kita dapati bahwa Amr bin Ash tidak membedakan dalam mengambil jizyah antara orang mulia dan orang biasa, ia mengambilnya atau menyamakan antara manusia dalam mengambilnya dari mereka.
Dan untuk mewujudkan kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban jizyah, dihapuskanlah hak-hak istimewa penduduk Iskandariah dan kelas-kelas bangsawan yang mereka nikmati di bawah pemerintahan Bizantium, dan diterapkanlah jizyah Islam kepada mereka. Untuk rincian lebih lanjut tentang hal itu dapat merujuk kepada buku (Sistem Keuangan Perbandingan dalam Islam) karya Dr. Badawi Abdul Lathif, cetakan 1962 halaman 88 dan selanjutnya.
Di antara bukti-bukti juga bahwa diriwayatkan bahwa Jabalah bin Al-Aiham ketika bangsa Romawi kalah dari Yarmuk, pergi ke tempat tinggalnya bersama sekelompok kaumnya. Yazid bin Abi Sufyan mengirim utusan kepadanya meminta kharaj tanahnya dan kharaj kepalanya—yaitu jizyah. Jabalah tidak menolak membayar pajak tanah, tetapi ia merasa gengsi dan tidak rela dengan jizyah kepala seraya berkata: “Sesungguhnya yang membayar jizyah adalah rakyat jelata, yaitu individu-individu atau masyarakat umum, sedangkan aku adalah laki-laki dari bangsa Arab.” Ia memang dibebaskan dari jizyah di masa Romawi. Dan ketika ia melihat desakan kaum Muslim untuk mengambil jizyah darinya agar ia disamakan dengan yang lain dalam hal ini, ia meninggalkan negeri dan pindah ke negeri Romawi, agar tidak membayar jizyah kepada kaum Muslim.
Demikianlah kita lihat bahwa agama kita yang menyerukan kesetaraan antara manusia tidak berpihak kepada raja Ghassan, yaitu Jabalah bin Al-Aiham, dan tidak membebaskannya dari jizyah, meskipun ia adalah orang yang terhormat di kaumnya dan terhormat di sisi Romawi. Mereka membebaskannya dari jizyah. Maka logika Romawi adalah logika yang zalim dalam menetapkan jizyah, di mana mereka mengambilnya dari petani dan membebaskan orang-orang yang mampu darinya karena kedekatan mereka dengan kaisar dan karena kedudukan mereka di masyarakat. Logika ini tidak diakui oleh Islam. Jizyah wajib atas setiap orang yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya, apapun kedudukan sosialnya. Oleh karena itu penguasa-penguasa Muslim meminta jizyah dari raja Ghassan sebagaimana kita lihat.
Dalam makna ini, Abu Yusuf berkata dalam kitabnya (Al-Kharaj):
“Dan tidak halal bagi wali (penguasa) untuk membiarkan seorang pun dari orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Shabiin, dan Samiriyyah, kecuali ia mengambil jizyah dari mereka. Dan ia tidak boleh memberi keringanan kepada seorang pun dari mereka untuk meninggalkan sesuatu dari itu. Dan tidak halal ia membiarkan seseorang dan mengambil dari yang lain. Dan hal itu tidak diperbolehkan, karena darah dan harta mereka sesungguhnya terjaga dengan menunaikan jizyah.”
Dari hal ini kita melihat bahwa prinsip kesetaraan antara orang-orang yang dikenai jizyah telah terwujud dengan sempurna, dan makna dari hal ini adalah bahwa sifat umum personal (menyeluruh dari segi subjek) berkaitan dengan jizyah telah terealisasi hingga tingkat maksimal yang mungkin.
Adapun mengenai sifat umum materiil dalam jizyah, kami katakan:
Jika jizyah diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal dan mampu membayarnya -sebagaimana telah kami sebutkan- maka disyaratkan bahwa ia memiliki harta untuk membayar jizyah yang diwajibkan kepadanya. Jizyah itu wajib dari harta, oleh karena itu orang buta, lumpuh, fakir, dan miskin dibebaskan darinya. Hal ini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Hingga mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Surah At-Taubah: ayat 29), dan pembayaran tentu dari harta yang ada dalam kepemilikan individu, baik dengan membayar langsung atau dengan jaminan. Oleh karena itu, Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu membedakan jumlah jizyah sesuai dengan besarnya harta yang dimiliki wajib pajak. Jika hartanya banyak, maka jumlahnya ditambah, dan jika hartanya sedikit, maka jumlahnya dikurangi. Dia telah menetapkan kenaikan jizyah kepada penduduk Syam dan Irak karena kekayaan mereka, dan menurunkannya untuk penduduk Yaman karena sedikitnya sumber keuangan mereka.
Meskipun jizyah pada dasarnya berupa dirham, dinar, dan makanan, namun dibolehkan mengambil barang dagangan dan hewan sebagai pengganti uang. Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu pernah menerima unta sebagai jizyah, dan datang kepadanya dari Syam banyak hewan ternak dari jizyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambilnya dari setiap pemilik keahlian, dari pemilik jarum berupa jarum, dari pemilik alat pemotong berupa alat pemotong, dan dari pemilik tali berupa tali. Artinya mereka memperhatikan kondisi wajib pajak dan tidak menyulitkan mereka.
Faktor-faktor yang Membantu Mewujudkan Sifat Umum dalam Jizyah
Sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor yang membantu mewujudkan sifat umum dalam jizyah:
Kita telah melihat bagaimana syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya sifat umum dalam jizyah, baik sifat umum personal maupun sifat umum materiil. Namun syariat tidak cukup hanya menegaskan hal ini, melainkan bekerja untuk menjamin terwujudnya hal tersebut. Sifat umum mungkin tersedia, tetapi pelaksanaannya bisa merusaknya. Oleh karena itu, kita dapati syariat Islam pada saat yang sama memperhatikan penampakan berbagai aspek dari sifat umum ini, juga bekerja keras untuk menjauhkan segala sesuatu yang dapat merusaknya. Ada beberapa faktor yang membantu menjamin terwujudnya sifat umum dalam jizyah, di antaranya yang terpenting adalah: mencegah pemungutan ganda dalam jizyah, menghindari penerapan surut dalam jizyah, dan memerangi penggelapan jizyah.
Mengenai pencegahan pemungutan ganda dalam jizyah:
Disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang perdamaian Najran bahwa mereka dikenakan dua ribu helai pakaian dari pakaian uqiyah, pada setiap bulan Rajab seribu helai, dan pada setiap bulan Safar seribu helai, dengan setiap helai pakaian senilai satu uqiyah perak. Apa yang lebih dari kharaj atau kurang dari uqiyah, maka dihitung. Dengan demikian Sunnah yang suci telah menunjukkan bahwa pemungutan ganda dalam jizyah adalah kezaliman, oleh karena itu tidak ada pemungutan ganda di dalamnya. Hal itu ditunjukkan dengan bahwa apa yang lebih dari kharaj dari perdamaian orang-orang Nasrani Najran dihitung, maka selisihnya dikembalikan kepada mereka atau diperhitungkan dari jizyah tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Ketahuilah, barangsiapa menzalimi orang yang memiliki perjanjian, atau membebaninya melebihi kemampuannya, atau mengurangi haknya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku adalah lawannya pada hari kiamat.”
Sebagai penerapan tidak adanya pemungutan ganda dalam jizyah, leher orang-orang yang dikenai jizyah dicap pada waktu pemungutan, hingga selesai pendataan mereka, kemudian cap-cap itu dilepas, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Hunaif terhadap mereka jika mereka meminta untuk melepasnya. Demikian juga apa yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu bahwa ia menulis kepada para pegawainya untuk mencap leher ahlul dzimmah. Hal itu untuk memperketat ketelitian dalam pemungutan, agar tidak ada yang lolos dari pajak yang telah ditetapkan kepadanya, dan agar tidak terjadi pemungutan ganda dalam jizyah.
Cara pembayaran pajak telah diatur, di mana penguasa memerintahkan para pemungut pajak untuk memberikan wajib pajak bukti bahwa mereka telah membayar kewajiban mereka, agar itu menjadi bukti bagi mereka yang mencegah penagihan lagi pada tahun yang sama atas harta yang sama. Mengenai pencegahan pemungutan ganda dalam jizyah, kami katakan: pada dasarnya beban jizyah harus didistribusikan kepada orang-orang yang dikenai jizyah secara adil, sesuai dengan kemampuan finansial wajib pajak, dan wajib pajak tidak boleh membayar jumlah yang wajib kepadanya dua kali dalam satu tahun yang sama. Jika terjadi pemungutan ganda dalam pembayaran jizyah, maka orang yang terkena pemungutan ganda ini akan menanggung beban finansial yang lebih besar dari beban yang ditanggung wajib pajak lain yang memiliki kemampuan finansial yang sama dengan wajib pajak pertama. Dengan demikian, kesetaraan antara orang-orang yang setara menjadi hilang, dan ini berarti pengabaian terhadap prinsip kesetaraan yang harus berlaku di antara orang-orang yang dikenai jizyah. Di sisi lain, orang yang terkena pemungutan ganda akan kehilangan kepercayaan kepada sistem yang mengurus pemungutan jizyah sebagai akibat dari perasaannya bahwa kezaliman telah menimpanya, dan ini dapat menyebabkan penggelapan jizyah yang wajib atasnya. Penggelapan -sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya- merusak prinsip kesetaraan antara wajib pajak dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan. Adapun dalam kondisi upaya pencegahan pemungutan ganda ini, maka setiap wajib pajak akan menanggung sebagian dari beban keuangan yang sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan dengan demikian prinsip kesetaraan antara warga negara dalam menanggung beban jizyah akan terwujud.
Mengenai topik menghindari penerapan surut dalam jizyah, kami katakan:
Jizyah ditetapkan atas ahlul dzimmah, dan ditentukan jumlahnya serta orang-orang yang dikenakan. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil dari setiap orang dewasa satu dinar atau yang setara dari kain Ma’afir. Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu juga menentukan jumlah jizyah dan membuatnya bertingkat. Ia mewajibkan kepada orang kaya jizyah sebesar 48 dirham per tahun, kepada orang menengah 24 dirham per tahun, dan kepada pekerja 12 dirham per tahun. Waktu pembayaran jizyah ditentukan sesuai dengan kepentingan wajib pajak, dan itu berbeda-beda menurut daerah dan negeri. Biasanya diambil pada akhir musim pertanian dan saat penjualan hasil panen untuk memudahkan pembayarnya. Jizyah ini jumlahnya tetap dan tidak boleh diubah oleh pihak manapun yang terikat perjanjian. Adapun jika jumlah jizyah tidak disebutkan dalam perjanjian perdamaian, maka penguasa dapat menetapkan jizyah kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka membayar pajak. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu mengambil dari orang-orang yang berdamai dengannya dari ahlul ahdi sesuai dengan apa yang mereka sepakati, tidak mengurangi sedikitpun dan tidak menambah kepada mereka. Barangsiapa yang menerima jizyah tanpa menyebutkan jumlah tertentu, Umar mempertimbangkan kondisi mereka. Jika mereka membutuhkan, ia meringankan mereka, dan jika mereka kaya, ia menambah kepada mereka sesuai dengan kekayaan mereka.
Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa syariat Islam dalam mengatur hukum-hukum yang mengatur jizyah memperhatikan agar hukum-hukum tersebut tidak banyak, dan membuatnya jelas dan tegas, tidak menimbulkan penipuan apapun. Dengan demikian, pintu ditutup untuk penafsiran dan ijtihad yang berbeda-beda terhadap hukum-hukum ini, sehingga celah-celah yang melaluinya wajib pajak jizyah dapat memindahkan beban jizyah yang ia tanggung kepada wajib pajak lainnya dapat dihilangkan. Ini berarti menghindari penerapan surut dalam jizyah, dan dengan menghindari penerapan surut tersebut, kesetaraan antara wajib pajak dalam menanggung beban jizyah dapat terwujud, masing-masing sesuai dengan kemampuan finansialnya.
Mengenai memerangi penggelapan pembayaran jizyah, kami katakan:
Kaum muslimin bekerja untuk memerangi penggelapan pembayaran jizyah. Dalam perjanjian yang dilakukan antara Habib bin Maslamah dengan beberapa negeri yang ia taklukkan disebutkan: jaminan keamanan untuk kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, harta kalian, biara-biara kalian, gereja-gereja kalian, agama kalian, dan ibadah kalian, dengan pengakuan akan kerendahan dengan jizyah, atas setiap keluarga satu dinar penuh. Kalian tidak boleh menggabungkan keluarga-keluarga yang terpisah untuk mengecilkan jizyah, dan kami tidak boleh memisahkan yang sudah bersatu untuk memperbanyak jizyah. Artinya ia mewajibkan kepada mereka, kepada setiap rumah satu dinar, tetapi meminta mereka agar tidak menggabungkan rumah-rumah kepada satu sama lain sehingga hanya membayar satu dinar saja. Juga ia menjelaskan kepada mereka bahwa kami tidak akan menzalimi mereka dan hanya akan mengambil dari setiap rumah satu dinar saja. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan keluarga-keluarga yang terpisah dengan maksud manipulasi untuk mengurangi jizyah, karena setiap rumah dituntut membayar satu dinar. Jika mereka menggabungkan dua keluarga atau lebih menjadi satu keluarga, maka jumlah yang wajib atas mereka akan berkurang.
Juga Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu menulis kepada para pegawainya yang mengurus jizyah untuk mencap leher ahlul dzimmah. Hal itu untuk memperketat ketelitian dalam pemungutan, agar tidak ada yang lolos dari pajak -yaitu menggelapkannya- yang telah ditetapkan kepadanya.
Cara-cara Memerangi Penggelapan Jizyah:
Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mencegah penggelapan pembayaran jizyah. Di antara yang terpenting kami sebutkan:
Pertama: Keadilan Petugas Pemungut
Salah satu penyebab terpenting yang mendorong wajib pajak untuk menggelapkan kewajiban finansial mereka adalah kezaliman petugas pemungut. Kebaikan kepada wajib pajak -sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun- akan meningkatkan hasil pajak, dan kezaliman menguranginya, bahkan dapat menyebabkan kehancuran negeri. Juga keberpihakan kepada sebagian wajib pajak dengan perlakuan baik dari pihak petugas pemungut dapat mendorong wajib pajak yang tidak dipihaki untuk menggelapkan jizyah yang wajib atas mereka, karena perbedaan perlakuan antara mereka dengan yang lain dari pihak petugas pemungut. Oleh karena itu, kita dapati bahwa ajaran Islam mengajak agar petugas pemungut berlaku adil dalam memperlakukan wajib pajak dan bersikap baik kepada mereka. Pemungut tidak boleh membedakan antara muslim dan non-muslim, tidak boleh membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan, tidak boleh memukulnya, tidak boleh memenjarakannya, tidak boleh melakukan sesuatu pada tubuh wajib pajak yang mereka benci, tetapi harus bersikap baik kepada mereka. Diriwayatkan dari Hisyam bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa ia melewati sekelompok orang yang disiksa karena jizyah di Palestina, maka Hisyam berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah akan menyiksa pada hari kiamat orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.”
Para khalifah sering berwasiat kepada petugas jizyah untuk memperhatikan keadilan dalam memungutnya, memperlakukan wajib pajak dengan baik, dan tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Di antara buktinya adalah apa yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu didatangi harta yang banyak dari jizyah, maka ia berkata kepada petugas jizyah: Aku khawatir kalian telah membinasakan orang-orang. Mereka berkata: Tidak demi Allah, kami hanya mengambil dari kelebihannya saja. Ia berkata: Tidak ada suara dan tidak ada pukulan? Maksudnya: kalian tidak memukul orang-orang? Mereka berkata: Benar. Ia berkata: Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan hal itu terjadi melalui tanganku dan bukan dalam kekuasaanku. Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu khawatir ketika melihat harta yang banyak yang mereka bawa, khawatir bahwa itu karena mereka mengambil apa yang tidak seharusnya dari ahlul dzimmah, dan ia memastikan bahwa mereka tidak menzalimi ahlul dzimmah, sehingga ia memuji Allah Tabaraka wa Ta’ala bahwa tidak ada kezaliman terhadap ahlul dzimmah di masa pemerintahannya.
Di antara bukti yang menunjukkan bahwa syariat Islam tidak mengizinkan petugas jizyah menzalimi wajib pajak, bahkan memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada wajib pajak ini dan mewujudkan kesetaraan penuh di antara mereka, adalah apa yang tertulis dalam perintah yang ditemukan di antara lembaran papirus Yunani yang tersimpan di Museum Inggris, yang dipindahkan kepada kita oleh Dr. Tritton dalam bukunya (Ahlul Dzimmah dalam Islam). Ia telah memindahkan kepada kita ucapan dari perintah ini yang ditujukan dari penguasa kaum muslimin kepada yang menangani urusan jizyah yang menyatakan:
Dan janganlah engkau membuat kami mengetahui bahwa engkau telah menyelesaikan urusan penduduk wilayahmu—yaitu negerimu—dengan cara apa pun dalam masalah pajak yang engkau tugaskan untuk mengumpulkannya, atau bahwa engkau telah berpihak dan menzalimi seseorang dalam pengumpulannya; karena kami tahu bahwa orang-orang yang ditugaskan membayarnya pasti tidak akan mematuhi sebagian perintahmu. Jika engkau mendapati bahwa mereka—yaitu para petugas jizyah—telah memperlakukan seseorang dengan kelonggaran berlebihan akibat keberpihakan mereka kepadanya, atau membebaninya secara berlebihan karena kebencian mereka kepadanya, maka kami akan menghukum mereka pada diri dan harta mereka sebagai pelaksanaan syariat. Kemudian kami memperingatkan, mengingatkan, dan memberitahu mereka agar tidak memberatkan pekerja dan tidak membebankan kepadanya sesuatu yang tidak mampu dia pikul, meskipun dia jauh dari mereka atau bukan dari kelompok mereka, dalam pengumpulan pajak. Tetapi semua orang harus diperlakukan dengan adil, dan mengambil sesuatu dari setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah perkataan yang dinukil dari non-Muslim yang bersaksi tentang keadilan kaum Muslim. Perkataan ini tercantum dalam buku (Ahlu Dzimmah fi al-Islam) karya Dr. Tirton, terjemahan Hasan Habasy, Cetakan Kedua 1967, Penerbit Dar al-Ma’arif Mesir, halaman 163 dan seterusnya.
Dan nukilan dari buku Tirton dalam bukunya (Ahlu Dzimmah) ini menjelaskan bahwa para penguasa memerintahkan orang-orang yang menangani urusan pemungutan jizyah dan kharaj agar mengawasi petugas pemungutan dan meminta mereka untuk tidak menzalimi siapa pun, bahkan jika orang itu jauh dari mereka, bukan dalam kelompok mereka, tidak berjalan bersama mereka, dan sebagainya. Ini adalah kesaksian dari non-Muslim tentang keadilan kaum Muslim dalam pemungutan jizyah mereka.
Demikianlah kita dapati bahwa Islam memerintahkan petugas jizyah untuk mewujudkan keadilan penuh terhadap orang-orang yang dikenai jizyah. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan memberikan dampak baik dalam jiwa para wajib pajak tersebut, yang membuat mereka sama sekali tidak berpikir untuk menghindari pembayaran jumlah yang wajib mereka bayar dari pajak ini. Hal yang pada akhirnya akan mewujudkan persamaan penuh antara para wajib jizyah, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
Berkenaan dengan pendataan wajib pajak yang membantu mencegah penghindaran pembayaran jizyah, kami katakan:
Sesungguhnya pendataan wajib pajak dan harta mereka akan menghasilkan kemungkinan untuk memperkirakan dan memungut jizyah dengan sangat teliti, dan dengan demikian mencegah penghindaran pembayaran jizyah. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Umar bin Khaththab memerintahkan untuk mendata penduduk Sawad, maka mereka didata dan jizyah dikenakan kepada mereka. Demikian pula yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan, ketika dia mengutus kepada gubernurnya di Jazirah, Adh-Dhahhak bin Abdurrahman al-Asy’ari, dan memerintahkannya untuk mendata kepala—yaitu manusia—dan menjadikan semua orang sebagai pekerja dengan tangan mereka. Dia menghitung apa yang diperoleh pekerja dalam setahun penuh, kemudian mengurangi dari itu biaya hidupnya untuk makanan, lauk pauk, dan pakaian, serta mengurangi hari-hari raya dalam setahun penuh. Maka dia mendapati yang tersisa setelah itu dalam setahun untuk setiap orang adalah empat dinar, lalu dia mewajibkan mereka membayarnya. Artinya dia memperhatikan kepentingan pribadi mereka, memperhatikan apa yang mereka butuhkan, dan tidak mengenakan jizyah kecuali pada jumlah yang tersisa dari kebutuhan mereka. Ini menunjukkan perhatian terhadap keadilan yang dijalankan kaum Muslim terhadap ahlu dzimmah.
Pelaksanaan terhadap Harta Orang yang Menunggak Pembayaran Jizyah:
Di antara cara-cara yang dapat mencegah penghindaran pembayaran jizyah adalah pelaksanaan paksa terhadap harta orang-orang yang menunggak pembayaran jizyah. Jika ahlu dzimmah menolak membayar jizyah, maka sebagian ulama menganggap hal itu sebagai pelanggaran perjanjian mereka, dan jizyah diambil dari mereka secara paksa seperti utang. Kami katakan, di antara cara-cara yang dapat mencegah penghindaran pembayaran jizyah adalah menahan orang yang menghindari pembayarannya hingga dia membayarnya. Dalam makna ini Abu Yusuf berkata: Ahlu dzimmah ditahan hingga mereka membayar apa yang menjadi kewajiban mereka, dan mereka tidak dikeluarkan dari tahanan hingga jizyah dipungut secara penuh dari mereka.
Inilah cara-cara terpenting yang menjamin pencegahan penghindaran pembayaran jizyah. Mengambil cara-cara ini—tanpa diragukan—akan menjadi penghalang antara orang yang tergoda untuk menghindari pembayaran jizyah dengan penghindaran tersebut. Kita tahu bahwa memberantas penghindaran pembayaran jizyah berarti semua ahlu dzimmah yang memenuhi syarat wajib jizyah harus berkontribusi dalam beban keuangan yang ditetapkan bagi mereka dalam negara tanpa pengecualian, dan dengan demikian terwujud persamaan penuh antara wajib jizyah dalam menanggung bebannya.
Memperhatikan Kondisi Wajib Jizyah
Kami ingin membahas tentang memperhatikan kondisi wajib jizyah, maka kami katakan:
Laki-laki dewasa yang berakal sehat dan mampu dari kalangan ahlu dzimmah yang dikenai kewajiban membayar jizyah, sesungguhnya mereka berkontribusi dalam beban keuangan melalui pembayaran jizyah, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya. Pembebanan harus sesuai dengan kemampuan dan daya; karena Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Oleh karena itu tidak boleh menzalimi mereka dalam hal itu; berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: “Ketahuilah, barang siapa menzalimi orang yang telah membuat perjanjian, atau mengurangi haknya, atau membebaninya melebihi kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan menjadi penuntutnya pada hari kiamat.” Jumlah yang diambil dari mereka dalam jizyah harus memperhatikan kemampuan keuangan mereka dan seluruh kondisi keluarga mereka. Jumlah ini berbeda dari satu orang ke orang lain, bahkan berbeda untuk satu orang dari satu waktu ke waktu lain, sebagaimana berbeda mengikuti lingkungan. Oleh karena itu tidak sepatutnya menentukan jumlah tertentu. Jika harta wajib pajak bertambah, maka jumlah jizyah ditambah padanya, dan jika hartanya berkurang, maka jumlahnya dikurangi. Kita dapati hal itu jelas dalam apa yang disarankan Mu’adz bin Jabal kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perdamaian Ar-Ruha, ketika dia berkata:
Sesungguhnya jika engkau memberikan perdamaian kepada mereka dengan sesuatu yang ditentukan namun mereka tidak mampu membayarnya, maka engkau tidak boleh membunuh mereka, dan kita tidak menemukan jalan lain selain membatalkan apa yang disyaratkan kepada mereka dari penentuan tersebut. Jika mereka berkecukupan, mereka membayarnya tanpa kehinaan yang diperintahkan Allah tentangnya. Maka terimalah perdamaian dari mereka dan berikan itu kepada mereka dengan syarat mereka membayar sesuai kemampuan, yaitu sesuai dengan apa yang mereka mampu dan sesuai kemampuan keuangan wajib pajak. Jika mereka berkecukupan atau kesulitan, maka engkau tidak berhak atas mereka kecuali apa yang mereka mampu, dan syaratmu terpenuhi serta tidak batal. Maka Abu Ubaidah menerima hal itu.
Ini menunjukkan bahwa lebih baik jizyah tidak ditentukan dengan jumlah tertentu setiap tahun untuk semua orang, tetapi seharusnya berbeda mengikuti perbedaan setiap orang, sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.
Juga kita dapati bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu membedakan jumlah jizyah sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki wajib pajak. Jika hartanya banyak, maka jumlahnya ditambah, dan jika hartanya sedikit, maka jumlahnya dikurangi. Dia menambah jumlah ini untuk penduduk Syam dan penduduk Irak karena kekayaan mereka, dan mengurangi jumlah ini untuk penduduk Yaman karena keterbatasan kemampuan keuangan mereka.
Perbedaan jumlah jizyah sesuai dengan kemampuan pembayaran wajib pajak dianggap sebagai salah satu prinsip paling maju yang ingin dicapai oleh sistem keuangan modern berkenaan dengan pajak, yaitu keadilan dalam pajak. Perbedaan jumlah yang wajib akan memperhatikan kemampuan pembayaran wajib pajak dan merupakan dasar ide persamaan yang memperhatikan keadilan; karena persamaan antara yang tidak sama adalah kezaliman.
Kondisi wajib jizyah telah diperhatikan dalam berbagai aspek, kami akan membahas yang terpenting sebagai berikut:
Pembebasan Orang yang Tidak Mampu dari Pembayaran Jizyah:
Jika kita telah melihat melalui pembahasan tentang persamaan dalam zakat bahwa yang kurang dari nisab dibebaskan dari zakat, maka hal itu tidak berbeda untuk jizyah. Jizyah tidak diambil dari setiap harta, tetapi dibebaskan dari harta sedikit yang tidak menghilangkan sifat miskin dari pemiliknya dan tidak menetapkan baginya sifat kaya. Jizyah diambil dari kelebihan harta ahlu dzimmah. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas berkata: Tidak ada (yang diambil) dari harta ahlu dzimmah kecuali kelebihannya, yaitu apa yang melebihi kebutuhan mereka. Jika yang diambil adalah kelebihannya, yaitu apa yang lebih dari kebutuhan pokok, maka akibatnya adalah pembebasan orang yang tidak mampu yang kemampuannya tidak memungkinkan untuk dikenai jizyah. Yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan dalam surat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada penduduk Najran dan semua orang Nasrani, bahwa tidak ada kharaj dan tidak ada jizyah kecuali atas orang yang memiliki warisan dari warisan tanah, yang wajib baginya hak penguasa, maka dia membayar itu seperti yang dibayar orang sejenisnya. Dia tidak boleh dizalimi, dan tidak diambil darinya kecuali sesuai kemampuan dan kekuatannya untuk menggarap tanah dan memakmurkannya serta memanen hasilnya. Dia tidak boleh dibebani secara berlebihan, dan tidak boleh melampaui batas para pembayar kharaj dari orang-orang sejenisnya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hal ini memerintahkan persamaan antara wajib pajak ketika kondisi mereka sama, tidak membebani wajib pajak melebihi kemampuannya, dan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan membayar jizyah dibebaskan darinya. Yang menunjukkan hal itu adalah apa yang tercantum dalam surat: Tidak ada kharaj dan tidak ada jizyah kecuali atas orang yang memiliki warisan dari warisan tanah. Ini artinya pembebasan orang yang tidak mampu dari pembayaran jizyah.
Yang juga menunjukkan hal itu adalah bahwa Umar bin Khaththab membatalkan jizyah selama dua puluh empat bulan untuk orang-orang Nasrani Najran ketika dia memindahkan mereka ke Irak, hingga mereka menetap dan mulai berproduksi.
Jelas dari itu bahwa periode antara pemindahan dan dimulainya produksi, yaitu dua puluh empat bulan, penduduk Najran tidak memiliki harta yang cukup untuk menjadi objek jizyah, dan dengan demikian tidak terpenuhi bagi mereka sifat kaya yang merupakan syarat wajib jizyah. Oleh karena itu Umar bin Khaththab membebaskan mereka dari jizyah pada periode tersebut.
Kami cukupkan dengan pembahasan ini untuk kuliah kali ini. Aku titipkan kalian kepada Allah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 – Lanjutan: Jizyah, kemudian Pembahasan tentang Kharaj
Lanjutan: Memperhatikan Kondisi Wajib Jizyah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Kami melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syariat memperhatikan kondisi orang-orang yang dikenai jizyah ini dan membebaskan yang tidak mampu darinya, maka kami katakan:
Di antara dalil-dalilnya adalah apa yang diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu wa ardhaahu membatalkan jizyah dari orang miskin yang menerima sedekah. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu melewati pintu suatu kaum dan di sana ada pengemis meminta-minta, seorang tua yang buta. Maka dia menepuk pundaknya dari belakang dan berkata: Dari ahli kitab mana engkau? Dia menjawab: Yahudi. Dia berkata: Apa yang memaksamu pada apa yang aku lihat ini? Dia menjawab: Aku meminta jizyah, kebutuhan, dan usia tua. Maka Umar memegang tangannya dan pergi bersamanya ke rumahnya, lalu memberikan sesuatu dari rumah—yaitu memberikan sesuatu kepadanya—kemudian mengirim kepada bendahara baitul mal dan berkata kepadanya: Perhatikanlah orang ini dan orang-orang sejenisnya. Demi Allah, kami tidak berlaku adil kepadanya jika kami memanfaatkan masa mudanya kemudian mengabaikannya saat tua. Kemudian dia berkata: “Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin” (Surat At-Taubah, ayat 60). Orang fakir adalah kaum Muslim, dan orang ini termasuk orang miskin dari ahli kitab, dan dia membatalkan jizyah darinya dan dari orang-orang sejenisnya. Dirujuk dalam (Al-Kharaj) karya Abu Yusuf.
Di antara dalil-dalilnya juga, telah tercantum dalam perjanjian perdamaian Hirah: Siapa saja orang tua yang lemah dalam bekerja atau tertimpa suatu musibah dari berbagai musibah atau pernah kaya lalu menjadi miskin, dan penduduk agamanya bersedekah kepadanya, maka jizya-nya dihapuskan—yaitu jizyah tidak akan diambil darinya—dan dia dinafkahi dari baitul mal kaum Muslim beserta keluarganya selama dia tinggal di negeri Islam. Artinya jika dia tertimpa musibah kemiskinan, jizyah tidak diambil darinya, dan juga dia diberi dari baitul mal kaum Muslim apa yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya.
Juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menulis surat kepada gubernurnya Adi bin Artha’ah yang berisi: Kemudian perhatikanlah ahlu dzimmah yang ada di wilayahmu yang telah bertambah usianya dan kemampuan mencari nafkahnya hilang, maka berilah dia nafkah dari baitul mal kaum Muslim yang dapat memperbaiki keadaannya. Perhatikanlah siapa yang ada di wilayahmu yang sudah menjadi tua dari ahlu dzimmah dan tidak mampu mencari harta, maka berilah dia dari baitul mal kaum Muslim. Seandainya seorang Muslim memiliki budak yang sudah tua, kekuatannya lemah dan kemampuan mencari nafkahnya hilang, maka menjadi kewajiban baginya untuk menafkahinya hingga kematian atau pembebasan memisahkan antara keduanya. Dirujuk dalam (Ahkamu Ahli Dzimmah) karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Bagian Pertama: halaman 37 dan seterusnya, Cetakan Pertama yang Ditahkik 1961.
Juga apa yang diriwayatkan bahwa Utsman bin Hunaif telah membagi wajib pajak menjadi kelompok-kelompok sesuai kemampuan keuangan masing-masing, dan mengenakan kepada setiap kelompok jumlah tertentu sebagai berikut:
Kelompok Yang Dibebaskan dari Jizyah
Kelompok-kelompok yang tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan dibebaskan dari jizyah.
Pekerja manual seperti penjahit dikenakan dua belas dirham per tahun.
Kelompok menengah dari kalangan pedagang dan pengrajin dikenakan dua puluh empat dirham.
Orang-orang kaya dari kalangan pedagang dan pengrajin, setiap orang dikenakan empat puluh delapan dirham per tahun.
Dari hal tersebut kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang tidak mampu yaitu orang-orang fakir dibebaskan dari jizyah karena mereka tidak mampu membayarnya, dan tidak ada kewajiban dalam keadaan tidak mampu. Pembebasan orang-orang yang tidak mampu dari membayar jizyah dapat kita anggap sebagai padanan dari pembebasan harta yang belum mencapai nisab dalam zakat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembebasan ini menurut keyakinan kami tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara para wajib pajak dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan dalam negara, karena pembebanan hanya dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, dan orang fakir tidak memiliki kapasitas keuangan, sehingga pembebasannya dari membayar jizyah tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara para wajib pajak dalam menanggung kewajiban jizyah.
Di antara hal-hal yang diperhatikan berkaitan dengan kondisi wajib pajak adalah pembebasan kebutuhan minimum yang diperlukan untuk penghidupan dari jizyah. Sesungguhnya jaminan batas kecukupan yang telah disebutkan sebelumnya ketika membahas kesetaraan dalam zakat harus tersedia bagi setiap warga negara yang hidup dalam masyarakat Islam apa pun agamanya dan apa pun jenis kelaminnya. Hal ini telah dibahas secara rinci oleh Dr. Muhammad Syauqi Al-Fanjari dalam bukunya (Islam dan Masalah Ekonomi) halaman 67 dan seterusnya.
Sebagai penerapannya, kita dapati bahwa para penguasa Muslim menaksir jizyah dengan mempertimbangkan apa yang tersisa di tangan rakyat dari penghasilan mereka setelah pengeluaran mereka, sebagaimana yang terjadi di negeri Irak dan Jazirah. Para penakluk menetapkan satu dinar untuk setiap kepala, namun ketika Khalifah Abdul Hakam bin Marwan berkuasa dia menganggapnya terlalu sedikit, maka dia mengutus kepada gubernurnya di sana untuk mendata rakyat dan menghitung penghasilan pekerja dalam satu tahun penuh, lalu mengurangi dari itu pengeluaran untuk makanan, lauk-pauk, dan pakaiannya, serta mengurangi hari-hari raya dalam setahun, maka dia menemukan bahwa yang tersisa setelah itu adalah empat dinar untuk setiap orang, lalu dia mewajibkan mereka membayarnya. Pengurangan pengeluaran untuk makanan dan pakaian dapat kita anggap sebagai kebutuhan pokok wajib pajak, dan ini berarti bahwa yang wajib dibayar oleh wajib jizyah seharusnya adalah dari kelebihan kebutuhan pokoknya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi, sebagaimana halnya dengan zakat seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Pembebasan ini menurut keyakinan kami tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hal ini, karena kebutuhan seseorang didahulukan dari kebutuhan orang lain, demikian pula kebutuhan keluarga, anak, dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya seperti kebutuhan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita meminta jizyah dari wajib pajak yang membutuhkan apa yang ada padanya dan hatinya terikat dengannya karena sangat membutuhkannya? Kita telah melihat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan dalam hal ini adalah bahwa setiap individu menanggung sejumlah beban keuangan yang sesuai dengan kemampuan keuangannya untuk membayar. Tidak diragukan bahwa orang yang sangat membutuhkan uang yang ada padanya tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar jizyah, dan dengan demikian pembebasannya darinya tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara para wajib jizyah dalam menanggung pembayarannya, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa jizyah tidak lagi ada di zaman modern. Sebagian ulama berpendapat bahwa jizyah wajib atas ahlu dzimmah sebagai pengganti dari ketidakikutsertaan mereka dalam membela negara Islam, karena mereka tidak layak untuk membelanya disebabkan kekafiran mereka, karena mereka mungkin berpihak kepada orang yang memerangi kaum Muslim karena persatuan agama dengan mereka. Jizyah diambil dari mereka untuk membiayai tentara yang membela negara Islam. Namun jika terbukti kelayakan ahlu dzimmah untuk membela tanah air bersama kaum Muslim dengan kesetiaan mereka kepada kaum Muslim dan kesiapan mereka untuk membela negara Islam dan benar-benar bergabung dengan tentara Islam, maka jizyah gugur dari mereka. Oleh karena itu kita dapati bahwa di zaman sekarang, kebanyakan negara Islam memiliki dzimmi dan mereka tidak membayar jizyah. Hal ini dapat dijelaskan karena mereka bergabung dalam tentara yang membela negara Islam, dan partisipasi dalam kewajiban ini yaitu membela tanah air Islam menggugurkan jizyah dari mereka sebagaimana telah disebutkan.
Dengan demikian kita telah selesai membahas kewajiban jizyah sebagai salah satu sumber keuangan dalam negara Islam.
Sejarah Kharaj dan Sifat Umumnya
Sekarang kita berbicara tentang kharaj. Kharaj adalah upeti yang diambil dari harta manusia dan merupakan sesuatu yang dikeluarkan kaum dalam setahun dari harta mereka dengan jumlah yang telah ditentukan. Kharaj secara syariat adalah apa yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan kaum Muslim secara paksa atau damai. Jadi: apa yang diambil wali urusan (penguasa) dari hasil tanah. Juga didefinisikan sebagai apa yang dikenakan atas tanah berupa hak-hak yang harus dibayarkan darinya.
Sejarah Kharaj
Kharaj bukanlah hal baru dalam Islam, bahkan sudah ada sebelum Islam, karena merupakan salah satu jenis pajak tertua yang dikenal dalam sejarah. Ditemukan pada zaman Firaun, Ptolemeus, Romawi, dan Persia, namun sistemnya tidak sama di antara bangsa-bangsa tersebut, melainkan berbeda dalam jumlah dan cara pemungutannya.
Sifat Umum dalam Kharaj
Sifat umum dalam kharaj berarti bahwa semua orang yang memenuhi syarat-syarat kewajiban kharaj harus membayar jumlah yang telah ditentukan dan dikenakan kepadanya dari kharaj ini, sehingga tidak ada seorang pun yang dibebaskan dari membayarnya tanpa alasan yang jelas. Sifat umum tersebut juga berarti bahwa kharaj dikenakan pada semua tanah yang memenuhi syarat-syarat kewajiban kharaj. Artinya sifat umum dalam kharaj menggabungkan antara aspek pribadi dan material. Oleh karena itu kita akan membahas sifat umum pribadi dan material dalam kharaj.
Sifat Umum Pribadi
Berkenaan dengan sifat umum pribadi, kharaj dianggap sebagai pajak atas hasil tanah, dan merupakan salah satu sumber keuangan yang baru diberlakukan pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mewajibkannya sebagai wali urusan kaum Muslim dan menolak permintaan sebagian sahabatnya untuk membagi tanah Sawad sebagaimana harta rampasan perang dibagi. Beliau membacakan ayat-ayat tentang fai dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan kuda dan tidak (pula) unta” (Surah Al-Hasyr ayat 6) hingga firman-Nya: “Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang” (Surah Al-Hasyr ayat 10). Kemudian beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyertakan orang-orang yang datang sesudah kalian dalam fai ini, maka jika aku membaginya tidak akan tersisa apa pun bagi yang datang sesudah kalian.”
Abu Ubaid dalam penafsirannya terhadap apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menetapkan sistem kharaj dan mewajibkannya kepada ahlinya, menyatakan bahwa beliau menjadikannya menyeluruh dan umum bagi setiap orang yang tanah tersebut berada di tangannya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun mukatab atau budak, sehingga mereka sama dalam hal ini. Beliau tidak mengecualikan seorang pun. Yang menunjukkan hal itu adalah perkataan Umar tentang seorang dahqanah (bangsawan perempuan) Nahrul Malik ketika dia masuk Islam: “Biarkan dia di tanahnya dan dia membayar kharajnya”. Maka beliau mewajibkan kepadanya apa yang beliau wajibkan kepada laki-laki.
Jadi berkenaan dengan sifat umum pribadi, cakupannya lebih luas pada kharaj daripada jizyah sebagaimana telah disebutkan. Dengan demikian, semua orang yang tanah kharaj berada di tangan mereka berkewajiban membayar kharaj. Dari sini kita melihat bahwa prinsip kesetaraan antara para wajib kharaj dalam menanggung bebannya telah terwujud dengan sempurna. Artinya juga bahwa sifat umum pribadi terhadap pajak kharaj telah terwujud sampai tingkat maksimal yang mungkin.
Apakah Kharaj Wajib atas Muslim?
Di sini muncul pertanyaan: apakah kharaj wajib atas Muslim? Selama kita berbicara tentang sifat umum pribadi dalam kharaj, maka patut kita jelaskan masalah apakah kharaj wajib atas Muslim, untuk melengkapi pembahasan topik ini. Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:
Pendapat Pertama: Jumhur ulama berpendapat wajibnya kharaj atas Muslim, baik dia dahulu dzimmi kemudian masuk Islam dan tanah kharaj bersamanya, atau seorang Muslim membeli tanah kharaj dari dzimmi. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata: Umar bin Khattab menulis kepadaku tentang dahqanah Nahrul Malik setelah dia masuk Islam: “Serahkan kepadanya tanahnya dan dia membayar kharajnya”. Artinya dia masuk Islam namun tetap dikenakan kharaj, berarti kharaj wajib atas Muslim juga.
Pendapat Kedua: Sebagian ulama berpendapat bahwa kharaj tidak wajib atas Muslim. Mereka mengqiyaskan kharaj tanah dengan kharaj kepala yaitu jizyah. Sebagaimana jizyah tidak wajib atas Muslim setelah masuk Islam, demikian pula tidak wajib kharaj setelah masuk Islam.
Sifat Umum Material
Berkenaan dengan sifat umum material dalam kharaj, kharaj wajib pada setiap tanah yang ditaklukkan secara paksa atau penduduknya berdamai dengan syarat mereka tetap di dalamnya dan membayar kharajnya, dan pada setiap tanah yang dijangkau air kharaj. Lihat pembahasan ini dalam (Al-Amwal) karya Abu Ubaid halaman 92 dan seterusnya.
Tanah yang dikenakan kharaj sejak awal jika berada di bawah tangan dzimmi adalah:
- Tanah yang ditaklukkan secara paksa dan dengan kekuatan jika imam memberikan jaminan keamanan kepada pemiliknya dan membiarkannya di tangan mereka sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab terhadap tanah Mesir dan tanah Sawad dan lainnya.
- Tanah yang penduduknya berdamai dengan kewajiban tertentu yang harus mereka bayar, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bahwa beliau jika berdamai dengan suatu kaum, mensyaratkan kepada mereka untuk membayar kharaj sekian dan sekian.
- Tanah usyuriyah (tanah yang dikenakan usyur/zakat 10%) jika dimiliki dzimmi, menurut Abu Hanifah menjadi tanah kharaj, karena tidak wajib usyur atasnya karena dia bukan termasuk orang yang wajib atasnya, dan harus ada usyur atau kharaj, maka wajib kharaj.
Sebagian ulama berpendapat bahwa tanah yang diairi dengan air kharaj meskipun tanah usyuriyah tetap dikenakan kharaj, karena pengairan dengan air kharaj adalah bukti komitmennya.
Pajak kharaj mencakup tanah pertanian dan tanah yang dapat ditanami. Setiap tanah yang dijangkau air maka layak untuk ditanami dan wajib kharaj atasnya. Setiap tanah yang mungkin ditanami wajib kharaj, meskipun pemiliknya tidak dapat menanamnya karena kelalaiannya. Dari uraian di atas jelas bahwa kharaj dikenakan pada setiap tanah kharaj yang benar-benar ditanami atau yang layak untuk ditanami meskipun belum ditanami. Dalam hal ini terwujud sifat umum material dalam kharaj sampai batas maksimal, yang berakibat pada terwujudnya kesetaraan antara para wajib kharaj dalam menanggung bebannya.
Faktor-Faktor yang Membantu Mewujudkan Sifat Umum dalam Kharaj
Sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor yang membantu mewujudkan sifat umum dalam kharaj. Kita telah melihat bagaimana syariat Islam peduli untuk mewujudkan sifat umum dalam kharaj, baik sifat umum pribadi maupun material. Namun tidak cukup dengan itu saja, bahkan bekerja keras untuk menjamin terwujudnya, karena sifat umum mungkin tersedia tetapi pelaksanaannya dapat mengganggunya. Oleh karena itu kita dapati syariat Islam pada waktu yang sama memperhatikan untuk menampakkan berbagai aspek sifat umum ini, juga bekerja untuk menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggunya. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menjamin terwujudnya sifat umum dalam kharaj, di antaranya yang terpenting:
Mencegah Pajak Berganda dalam Kharaj
Dalam upaya mencegah pajak berganda dalam kharaj, mazhab Hanafi berpendapat bahwa Muslim yang memiliki tanah kharaj hanya diwajibkan kharaj saja, dan gugur darinya usyur (zakat 10%), karena tidak boleh berkumpul usyur dan kharaj bersama-sama. Mereka menjelaskan bahwa sebab keduanya yaitu usyur dan kharaj adalah sama yaitu biaya tanah kharaj. Dengan demikian tidak boleh berkumpul dua hak pada tanah yaitu usyur dan kharaj. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan para wali dan imam yang tidak menggabungkan usyur dan kharaj, dan tidak dinukil dari salah seorang pun di antara mereka penggabungan keduanya meskipun banyak Muslim yang memiliki tanah kharaj, sehingga hal ini seperti ijma yang tidak boleh dilanggar. Menurut pendapat Hanafiyah, mengambil usyur bersama kharaj merupakan pajak berganda dalam hak yang wajib.
Adapun jumhur ulama berpendapat wajibnya penggabungan usyur dan kharaj dalam kasus ini, karena sebab yang mewajibkan salah satunya berbeda. Zakat atau usyur wajib pada tanah kharaj karena sebabnya adalah harta yang berkembang dan pertumbuhan telah terwujud. Jika sebab terwujud maka akibat pun terwujud. Kharaj wajib pada tanah kharaj karena merupakan sewa tanah. Jika sebabnya berbeda maka tidak ada pajak berganda.
Syariat Islam telah mengatur cara penetapan pajak termasuk kharaj. Para penguasa memerintahkan pemungut pajak untuk memberikan kepada wajib pajak bukti bahwa mereka telah membayar pajak, agar hal itu menjadi bukti bagi mereka yang mencegah penagihan kembali dalam tahun yang sama atas harta yang sama. Dapat dilihat lebih lanjut dalam hal ini pada kitab (Al-Amwal) karya Abu Ubaid halaman 641 dan seterusnya.
Kami katakan bahwa pencegahan pajak berganda dalam kharaj mewujudkan kesetaraan antara para wajib pembayarannya. Pada dasarnya beban pajak kharaj didistribusikan kepada para wajib pajak dengan distribusi yang adil sesuai dengan kemampuan keuangan wajib pajak, dan agar wajib pajak tidak membayar jumlah yang wajib atasnya dua kali dalam tahun yang sama. Jika terjadi pajak berganda dalam pembayaran kharaj, maka orang yang terkena pajak berganda ini telah menanggung beban keuangan yang lebih besar dari beban yang ditanggung wajib pajak lain yang memiliki kemampuan keuangan yang sama dengan wajib pajak pertama. Dengan demikian kesetaraan antara yang setara menjadi tidak ada, dan ini merusak prinsip kesetaraan yang harus berlaku di antara para wajib kharaj.
Di sisi lain, orang yang terkena pengenaan pajak ganda akan kehilangan kepercayaan terhadap para petugas pemungut kharaj akibat perasaan ketidakadilan yang menimpanya, dan hal ini dapat mendorongnya untuk menghindari pembayaran kharaj yang menjadi kewajibannya. Penghindaran pajak sebagaimana kita ketahui akan merusak prinsip kesetaraan di antara para wajib pajak dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan di negara.
Adapun dalam hal upaya mencegah pengenaan pajak ganda ini, setiap wajib pajak akan menanggung sejumlah beban keuangan yang sesuai dengan kemampuan keuangannya saja, dan dengan demikian akan terwujud prinsip kesetaraan di antara para pembayar pajak dalam menanggung kewajiban kharaj. Berkenaan dengan menghindari pemberlakuan surut dalam kharaj, kami katakan: bahwa besaran kharaj sudah diketahui, baik berdasarkan luas tanah jika kharaj tersebut merupakan kharaj wadzifah (pajak tetap), atau berdasarkan persentase tertentu dari hasil tanah jika kharaj tersebut merupakan kharaj muqasamah (bagi hasil). Dalam kedua jenis ini, besaran kharaj sudah jelas, dan pembayaran kharaj dilakukan setahun sekali jika berupa kharaj wadzifah dan dilakukan setiap kali panen dalam hal kharaj muqasamah. Umar bin Khaththab menenangkan masyarakat dalam salah satu khutbahnya bahwa dia tidak akan mengambil kharaj dari mereka kecuali sesuai dengan yang menjadi hak mereka, dan tidak akan mengejutkan mereka dengan jumlah uang yang tidak diwajibkan kepada mereka. Beliau berkata: “Dan kalian memiliki hak atas diriku wahai manusia, beberapa hal yang akan kusebutkan untuk kalian, maka tuntutlah aku dengannya. Hak kalian atas diriku adalah aku tidak akan mengambil sesuatu pun dari kharaj kalian atau dari harta rampasan yang Allah berikan kepada kalian kecuali dari sumbernya yang benar.” Dapat dirujuk dalam kitab (Al-Kharaj) karya Abu Yusuf halaman 127 dan seterusnya. Bagaimanapun, kestabilan pajak yang relatif terlihat jelas dalam pajak kharaj. Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa apabila penetapan kharaj pada sebidang tanah telah mantap, maka hal itu menjadi kekal, dan tidak boleh ditambah atau dikurangi selama tanah tersebut dalam keadaan tetap dari segi pengairannya dan perbaikannya. Dari uraian di atas, terlihat jelas bagi kita bahwa syariat Islam dalam mengatur hukum-hukum yang mengatur kharaj telah memperhatikan agar hukum-hukum tersebut tidak banyak dan menjadikannya jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan penipuan apa pun. Dengan demikian menutup pintu bagi tafsiran dan ijtihad yang berbeda-beda mengenai hukum-hukum tersebut, dan akibatnya menghilangkan celah-celah yang melaluinya wajib pajak kharaj dapat memindahkan beban kharaj yang dikenakan kepadanya kepada wajib pajak lain. Ini berarti menghindari pemberlakuan surut dalam kharaj, dan dengan menghindari pemberlakuan surut tersebut, tercapailah kesetaraan penuh di antara para wajib pajak kharaj dalam menanggung beban pajak tersebut, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
Penghindaran Pembayaran Kharaj
Syariat Islam juga berupaya memerangi penghindaran pembayaran kharaj. Kaum Muslim berupaya memerangi penghindaran pembayaran kharaj agar terwujud kesetaraan di antara para wajib pembayar kharaj. Telah kita lihat sebelumnya bahwa penghindaran pembayaran jumlah yang wajib dari beban keuangan menyebabkan hilangnya kesetaraan di antara para wajib pajak dalam hal ini. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memerangi penghindaran pembayaran kharaj, di antaranya yang terpenting:
Pertama: Keadilan petugas pemungut pajak. Di antara penyebab terpenting yang dapat mendorong para pembayar pajak untuk menghindari kewajiban mereka adalah kezaliman petugas pemungut. Jika kezaliman terjadi dari para petugas ini terhadap para pembayar pajak, maka hasil pemungutan pajak akan berkurang, bahkan dapat menyebabkan kehancuran negeri. Juga, ketidaksetaraan di antara para wajib pajak dalam perlakuan dari pihak petugas pemungut, seperti memihak sebagian wajib pajak tanpa yang lain, hal tersebut akan mendorong mereka yang tidak dipihaki untuk menghindari jumlah kharaj yang wajib atas mereka. Untuk menghindari hal tersebut di atas, kita dapati bahwa ajaran Islam menyerukan agar petugas pemungut bersikap adil kepada para pembayar pajak dan lemah lembut kepada mereka. Umar bin Khaththab menerapkan ajaran tersebut dengan sangat teliti, di mana beliau tidak hanya memilih para sahabat terbaik untuk mengelola kharaj, tetapi juga kembali kepada para pembayar pajak sendiri agar mereka meyakinkan beliau bahwa mereka tidak dizalimi dalam pembayaran kharaj. Diriwayatkan bahwa beliau memungut dari Irak setiap tahun seratus ribu ribu uqiyah, kemudian sepuluh orang dari penduduk Kufah dan sepuluh orang dari penduduk Bashrah datang kepadanya, bersaksi dengan empat kesaksian demi Allah bahwa itu dari yang baik, tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap Muslim maupun orang yang memiliki perjanjian. Dua puluh orang yang mewakili para pembayar pajak bersaksi demi Allah dengan empat kesaksian bahwa harta ini telah diambil dengan benar dan tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap Muslim maupun orang yang memiliki perjanjian dari para pembayar pajak, dan mereka tidak akan bersumpah kecuali jika mereka yakin dengan apa yang mereka sumpahkan. Dari kepentingan mereka dan kepentingan orang yang mereka wakili adalah mengatakan yang benar. Ini tidak diragukan lagi merupakan cara yang berhasil untuk mengawasi pengelola kharaj melalui para pembayar pajak sendiri.
Abu Yusuf menyebutkan syarat-syarat orang yang melakukan pemungutan kharaj dalam perkataannya kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid: “Aku berpendapat -semoga Allah menjaga Amirul Mukminin- hendaknya engkau mengangkat orang-orang dari kalangan orang saleh, beragama, dan amanah, lalu tugaskan mereka mengelola kharaj.” Kemudian beliau berkata: “Dan pesankanlah kepada orang yang engkau angkat agar tidak sewenang-wenang terhadap penduduk wilayahnya, tidak meremehkan mereka, dan tidak merendahkan mereka, tetapi hendaknya mengenakan kepada mereka pakaian kelembutan yang dipadukan dengan sedikit ketegasan, dan ketelitian tanpa menzalimi mereka atau membebankan apa yang tidak wajib atas mereka. Lemah lembut kepada Muslim, tegas kepada orang fasik, adil kepada ahli dzimmah, membela orang yang terzalimi, tegas kepada orang zalim, dan memaafkan manusia. Sesungguhnya hal itu akan mendorong mereka untuk taat. Dan hendaknya pemungutan kharajnya dilakukan sebagaimana yang ditetapkan baginya, meninggalkan pembaruan dalam apa yang dia perlakukan kepada mereka, dan menyamakan di antara mereka dalam majelis dan wajahnya, sehingga yang dekat dan yang jauh, yang mulia dan yang rendah, sama di sisinya dalam kebenaran.” Disebutkan dalam kitab (Al-Kharaj) karya Abu Yusuf: halaman 115 dan seterusnya.
Para fuqaha tidak cukup dengan menetapkan syarat-syarat tertentu bagi petugas kharaj agar terwujud keadilan dalam penerapan, tetapi menambahkan kepada itu perlunya pengawasan terhadap para petugas ini, sebagai jaminan agar mereka tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan bagi mereka. Dalam pengertian ini, Abu Yusuf menasihati Harun Ar-Rasyid tentang perlunya mengawasi petugas kharaj, yaitu dengan mengirim di belakang para petugasnya orang-orang yang saleh dan suci yang dapat dipercaya agama dan amanahnya, untuk menanyakan tentang perilaku para petugas dan apa yang mereka lakukan di negeri-negeri, dan bagaimana mereka memungut kharaj sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan sesuai dengan apa yang ditetapkan atas para wajib kharaj dan telah mantap? Jika hal itu telah terbukti di sisimu dan benar, ambillah dari mereka apa yang mereka ambil secara berlebihan dengan pengambilan yang sangat keras setelah hukuman yang menyakitkan dan pelajaran, sehingga mereka tidak melampaui apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang diamanahkan kepada mereka di dalamnya. Jika kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan pengelola kharaj itu, maka diasumsikan bahwa dia telah diperintahkan melakukannya, padahal dia diperintahkan sebaliknya. Jika engkau menjatuhkan hukuman yang menyakitkan kepada salah satu dari mereka, yang lain akan berhenti, takut, dan khawatir. Jika engkau tidak melakukan ini kepada mereka, mereka akan melampaui batas terhadap para wajib kharaj, berani menzalimi mereka, sewenang-wenang kepada mereka, dan mengambil dari mereka apa yang tidak wajib atas mereka. (Al-Kharaj) karya Abu Yusuf: halaman 120 dan seterusnya.
Abu Yusuf menjelaskan hasil-hasil besar yang akan diperoleh dari terwujudnya keadilan dalam penerapan, beliau berkata: “Sesungguhnya keadilan, membela orang yang terzalimi, dan menghindari kezaliman, di samping pahala yang terkandung di dalamnya, akan menambah kharaj dan memperbanyak kemakmuran negeri. Berkah akan ada bersama keadilan, dan berkah hilang bersama kezaliman. Kharaj yang diambil dengan kezaliman akan mengurangi dan merusak negeri.” Demikianlah kita dapati bahwa syariat Islam memerintahkan petugas kharaj untuk berupaya mewujudkan keadilan penuh dalam perlakuan mereka terhadap para wajib kharaj. Tidak diragukan lagi bahwa perlakuan baik terhadap para wajib pajak ini akan meninggalkan kesan baik di hati mereka, yang akan membuat mereka sama sekali tidak berpikir untuk menghindari pembayaran jumlah yang wajib atas mereka dari pajak ini. Hal yang pada akhirnya akan mewujudkan kesetaraan penuh di antara para wajib pajak ini dalam menanggung kewajiban kharaj.
Kedua: Di antara cara memerangi penghindaran pembayaran kharaj adalah bahwa pemilik tanah jika menunda-nunda pembayaran kharaj yang wajib atasnya padahal dia mampu secara finansial, dia akan ditahan sebagai pembayaran utangnya, kecuali jika dia memiliki harta maka dijual atas namanya untuk kharajnya sebagaimana orang yang berutang. Jika dia tidak memiliki selain tanah kharaj, maka penguasa memiliki pilihan dalam membolehkan penjualannya, lalu menjual darinya sejumlah kharajnya, atau menyewakannya dan mengambil kharaj dari penyewanya. Jika sewanya bertambah maka kelebihan itu untuknya, dan jika kurang maka kekurangannya menjadi tanggungannya. Dapat dirujuk dalam (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) karya Al-Mawardi halaman 132 dan seterusnya. Hukuman finansial dan fisik ini akan mencegah orang yang tergiur untuk menghindari pembayaran jumlah yang wajib atasnya dari kharaj, sehingga dia tidak menghindarinya, dan dengan demikian terwujud kesetaraan penuh di antara para wajib pajak dalam menanggung kewajiban kharaj, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
Ketiga: Di antara cara yang juga mencegah penghindaran pembayaran kharaj adalah pendataan para pembayar pajak dan harta mereka untuk mengetahui besaran pajak dan memungutnya secara lengkap. Umar bin Khaththab memerintahkan pengukuran Sawad (wilayah Irak) dan mencapai tiga puluh enam ribu ribu jarib, lalu menetapkan kharaj atasnya. Dapat dirujuk dalam (Al-Kharaj) karya Abu Yusuf halaman 38 dan seterusnya.
Keempat: Di antara cara yang juga mencegah penghindaran kharaj adalah bahwa pemilik tanah jika mengklaim bahwa dia telah membayar kharaj, perkataannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Kharaj adalah hak yang statusnya seperti utang, dan ini adalah penerapan asas umum dalam pembuktian yaitu bukti atas orang yang mengklaim dan sumpah atas orang yang mengingkari. Dia telah mengklaim pembayaran kharaj maka bukti menjadi kewajibannya untuk memastikan pembayarannya atas pajak kharaj. Dalam hal ini boleh merujuk kepada catatan negara yang mencatat pembayaran kharaj agar tidak dituntut lagi.
Kelima: Di antara cara yang juga mencegah penghindaran pembayaran kharaj adalah cara pembelanjaan kharaj. Kharaj dibelanjakan untuk kepentingan umat di tempat pemungutannya. Jika tersisa sesuatu darinya, dikirim ke Baitul Mal untuk dibelanjakan dalam fasilitas umum negara. Yang menegaskan hal itu adalah bahwa Amr bin Al-Ash menerapkan di Mesir cara terbaik dalam pemungutan dan pembelanjaan kharaj. Beliau membelanjakan kharaj untuk menggali kanal-kanal Mesir, mendirikan bendungan-bendungannya, dan membangun jembatan-jembatannya, kemudian mengirimkan sisanya setelah itu kepada Amirul Mukminin di Madinah. Pada pokoknya, asalnya adalah menggunakan hasil kharaj di negeri tempat dikumpulkan, untuk menampakkan penggunaan ini dan mengumumkannya. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut akan memiliki dampak baik pada jiwa para wajib kharaj, membantu mereka mengeluarkan yang wajib atas mereka dengan jiwa yang rela, dan sama sekali tidak berpikir untuk menghindari pembayarannya karena keyakinan mereka bahwa apa yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dengan manfaat. Semua ini pada akhirnya akan mewujudkan kesetaraan di antara para wajib pajak dalam menanggung kewajiban kharaj, masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
Inilah cara-cara terpenting yang menjamin pencegahan penghindaran pembayaran kharaj. Mengambil cara-cara tersebut tidak diragukan lagi akan menjadi penghalang antara orang yang tergiur untuk menghindari pembayaran kharaj dengan penghindaran ini. Kita mengetahui bahwa memberantas penghindaran pembayaran kharaj berarti semua wajib kharaj berkontribusi dalam beban keuangan yang ditetapkan atasnya di negara tanpa pengecualian, dan dengan demikian terwujud kesetaraan di antara mereka dalam hal ini.
Memperhatikan Kondisi Pembayar Pajak dalam Kharaj
Kita perlu membahas tentang memperhatikan kondisi pembayar pajak dalam kharaj, maka kami katakan: karena tujuan dari penetapan kharaj adalah mewujudkan kesetaraan di antara semua warga dalam menanggung beban keuangan yang ditetapkan di negara, maka hal itu tidak berarti bahwa kharaj dibebankan kepada para wajib pajak dengan cara yang kaku tanpa memperhatikan kondisi mereka. Keadilan menuntut agar wajib pajak berkontribusi dalam pengeluaran umum negara sesuai dengan kemampuan keuangannya. Beban keuangan didistribusikan kepada para wajib pajak sesuai dengan kemudahan mereka. Mewujudkan keumuman dalam kharaj, meskipun memiliki kepentingan yang besar, tetapi harus dibarengi dengan gagasan lain yaitu bahwa beban kharaj yang ditanggung wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan keuangan dan kondisinya. Syariat Islam dalam menetapkan kharaj tidak menempuh jalan yang kaku, bahkan memperhatikan dalam hal itu kemampuan taklifi wajib pajak. Buktinya adalah bahwa Umar bin Khaththab radiyallahu ‘anhu memperhatikan agar pajak kharaj didasarkan pada kapasitas tanah, dan mempertimbangkan perbedaan tanah dari segi kesuburan yang menambah hasil panennya atau keburukannya yang mengurangi hasilnya, perbedaan tanaman dari segi jenis karena di antaranya ada yang harganya tinggi, perbedaan pengairan karena yang diairi dengan alat pengangkat air dan timba tidak dapat menanggung kharaj sebesar yang diairi dengan aliran air dan hujan, dengan ketentuan bahwa kharaj ditetapkan tanpa ketidakadilan kepada pemilik dan tanpa merugikan petani.
Bukti hal itu adalah bahwa Umar bin Khaththab bertanya kepada kedua petugasnya untuk kharaj, Hudzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunaif, untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak membebani para pembayar pajak melebihi kemampuan mereka. Mereka berdua menjawabnya bahwa mereka berdua membebankan kepada tanah apa yang mampu ditanggungnya. Jika ditambah masih sanggup, tetapi mereka berdua menyisakan kelebihan untuk rakyat. Utsman berkata: “Sungguh aku telah meninggalkan setengahnya, dan jika aku mau, aku bisa mengambilnya.” Pembahasan Umar dengan kedua petugasnya tentang besaran kharaj yang mereka tetapkan atas tanah menunjukkan keadilan Umar yang diambil dari keadilan Islam dan toleransinya terhadap non-Muslim.
Maka kharaj ditentukan jumlahnya sesuai dengan kapasitas tanah, dan karena itulah datang berbagai riwayat yang berbeda dari Umar tentang jumlah kharaj, yang berbeda-beda menurut perbedaan tanah dari segi kesuburan dan banyaknya hasil, sehingga ia tidak menetapkan jumlah yang sama untuk semua tanah tanpa perbedaan, melainkan memperhatikan untuk setiap tanah apa yang mampu ditanggungnya, dan ini mewujudkan keadilan di antara manusia. Umar menetapkan pada sebagian wilayah Sawad (Irak) setiap jarib (satuan luas) satu qafiz (satuan takaran) dan satu dirham, dan menetapkan pada wilayah lain dengan jumlah yang berbeda.
Sesungguhnya keadilan dalam kebijakan keuangan menuntut dari penguasa agar tidak membebankan pajak yang membebani pundak manusia dan memberatkan mereka, atau tidak sesuai dengan tingkat kekayaan dan perbedaan manusia dalam kemudahan, dengan kata lain ia harus memperhatikan keadaan manusia dan kesiapan mereka untuk menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka. Jika manusia menjadi tidak mampu menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka, maka wajib bagi penguasa untuk meringankan kepada apa yang mereka mampu. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa salah seorang khalifah Abbasiyah beralih dari kharaj tetap yang telah ditetapkan pada Sawad Irak sejak masa Umar, kepada kharaj bagi hasil ketika ia melihat bahwa tanah tidak lagi memenuhi apa yang telah ditetapkan padanya sebelumnya, maka tidaklah adil jika penduduk Sawad terus dibebani menunaikan apa yang ditetapkan pada tanah mereka sementara tanah itu tidak menghasilkan bagi mereka apa yang memungkinkan mereka menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka. Dapat dirujuk dalam hal itu (As-Siyasah Asy-Syar’iyyah wa Al-Fiqh Al-Islami) karya Syekh Abdurrahman Taj halaman 40 dan seterusnya, cetakan pertama 1953, percetakan Dar At-Ta’lif di Mesir.
Dan kehati-hatian dalam mendistribusikan beban kharaj kepada semua orang melalui memperhatikan apa yang telah disebutkan adalah cita-cita orang Prancis yang tidak terwujud bagi mereka kecuali pada pertengahan abad kesembilan belas, dan cara ini dalam menentukan jumlah kharaj yang telah dijelaskan sebelumnya adalah cara modern dalam menetapkan pajak properti, dan perbedaan jumlah yang wajib dalam kharaj menurut kapasitas tanah dianggap sebagai dasar gagasan persamaan yang memperhatikan keadilan; karena persamaan antara orang yang tidak sama dalam kemampuan finansial adalah kezaliman sebagaimana telah kami jelaskan menurut pandangan kami, dan telah diperhatikan kondisi orang yang dikenai kharaj dalam beberapa hal yang penting di antaranya kami sebutkan:
Pertama: Pembebasan orang yang tidak mampu dari pajak kharaj. Sebagaimana kharaj wajib atas orang yang dikenai jika tanah mampu menanggungnya, maka kharaj ini gugur dalam banyak keadaan yang paling penting di antaranya: jika tanaman terkena bencana maka kharaj gugur dari yang dikenai; karena ia adalah orang yang tertimpa bencana yang layak mendapat pertolongan, dan jika kharaj diambil darinya maka itu adalah penghancuran hartanya. Jika terjadi penurunan hasil dari tanah yang tidak disebabkan oleh pembayar pajak seperti jebolnya bendungan atau terputusnya sungai maka kharaj gugur. Jika tanah tidak dapat ditanami setiap tahun sehingga harus diistirahatkan pada satu tahun dan ditanami pada tahun lain, diperhatikan kondisinya pada awal penetapan kharaj padanya dengan mengukur setiap dua jarib sebagai satu jarib sehingga yang satu untuk yang ditanami dan yang lain untuk yang ditinggalkan, dan artinya adalah menggugurkan kharaj dari tanah pada tahun yang tidak ditanami. Dan pembebasan dari menunaikan kharaj ini menurut kami dapat dianggap sebagai padanan pembebasan yang di bawah nishab dari zakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan pembebasan ini menurut pendapat kami tidak bertentangan dengan prinsip persamaan antara orang yang dikenai dalam menanggung beban pajak tersebut, karena beban ini terkait dengan kemampuan finansial orang yang dikenai, dan selama kemampuan itu tidak ada maka tidak ada tempat untuk pembebanan, artinya pembebasan ini tidak bertentangan dengan prinsip persamaan antara orang yang dikenai dalam menanggung beban umum yang ditetapkan di negara.
Dan termasuk pertimbangan juga adalah pembebasan batas minimum yang diperlukan untuk penghidupan. Sesungguhnya jaminan batas kecukupan yang telah disebutkan sebelumnya ketika berbicara tentang pembebanan zakat dan jizyah harus tersedia bagi setiap warga negara yang hidup dalam masyarakat Islam apa pun agamanya dan apa pun jenis kelaminnya, dan pembebasan batas minimum yang diperlukan untuk penghidupan atau batas kecukupan sebagaimana sebagian orang menyebutnya adalah disepakati atau terwujud dalam pajak kharaj, yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut:
Dibebaskan dari kharaj tempat tinggal dan rumah yang menjadi tempat tinggal orang yang dikenai, karena tidak ditetapkan padanya sesuatu, maka apa yang tidak dapat dihindari dari bangunannya untuk tempat tinggal orang yang dikenai di tanah kharaj untuk mengolahnya digugurkan kharajnya; karena ia tidak dapat tinggal kecuali dengan tempat tinggal yang ia tempati, dan tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan untuk kehidupan orang yang dikenai, dan apa yang termasuk kebutuhan pokok dibebaskan dari kharaj, yang menunjukkan hal itu adalah perkataan Al-Mawardi: dan apa yang melebihi kadar kebutuhan diambil kharajnya, dan maknanya adalah bahwa apa yang tidak melebihi kadar kebutuhan dibebaskan dari kharaj.
Juga sesungguhnya syariat Islam membebaskan dari kharaj pakaian, makanan dan hewan tunggangan dengan menganggap hal-hal ini sebagai kebutuhan pokok, yang menunjukkan hal itu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib kepada pegawainya untuk kharaj: Jika engkau mendatangi mereka yaitu: orang yang dikenai kharaj, maka jangan menjual bagi mereka pakaian musim dingin dan musim panas, dan bukan rezeki yang mereka makan, dan bukan hewan yang mereka kerjakan, dan jangan menjual bagi salah seorang dari mereka barang dalam sesuatu dari kharaj. Dirujuk dalam hal itu kepada (Al-Amwal) karya Abu Ubaid halaman 55 dan seterusnya. Dan pembebasan yang ditetapkan untuk batas minimum yang diperlukan untuk penghidupan ini tidak bertentangan menurut pandangan kami dengan prinsip persamaan antara orang yang dikenai pajak kharaj dalam menanggung pajak tersebut, dan itu karena kebutuhan manusia dan kebutuhan keluarganya dan anaknya dan orang yang wajib dinafkahinya didahulukan atas kebutuhan orang lain, maka bagaimana kharaj dituntut dari orang yang dikenai yang berada dalam kebutuhan mendesak terhadap harta yang ada padanya, dan kita telah melihat sebelumnya bahwa persamaan dalam bidang ini dimaksudkan bahwa setiap individu menanggung sejumlah beban keuangan yang ditetapkan di negara yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas finansialnya, dan tidak diragukan bahwa orang yang dikenai yang berada dalam kebutuhan mendesak terhadap harta yang ada padanya tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan kharaj, dan dengan demikian pembebasannya dari menunaikan kharaj tidak bertentangan dengan prinsip persamaan antara orang yang dikenai dalam menanggung beban kharaj masing-masing sesuai kapasitas finansialnya.
Dan termasuk yang juga diperhatikan adalah perbedaan jumlah yang wajib dari kharaj menurut perbedaan usaha yang dilakukan. Fikih Islam membedakan antara hasil dari tanah kharaj sehingga membedakan jumlah yang wajib dengan perbedaan usaha yang dilakukan, maka apa yang dicurahkan dalam produksinya usaha dan kesulitan yang besar maka sedikit jumlah yang wajib padanya, dan apa yang dicurahkan dalam produksinya usaha dan kesulitan yang lebih sedikit atau tidak dicurahkan sama sekali maka lebih banyak jumlah yang wajib padanya.
Dan dengan ini kita telah selesai dari kuliah ini, kita cukupkan sampai di sini, saya titipkan kalian kepada Allah, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah kepada kalian.
3 – Usyur, dan Konsep Politik serta Landasan-landasannya dalam Islam dan Sumber-sumber Hukum Politik dalam Sistem Islam
Dari Sumber-sumber Keuangan Negara Islam: Usyur
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga shalawat dan salam tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, pemimpin kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Maka kita telah berbicara dalam kuliah-kuliah sebelumnya tentang sistem keuangan dalam Islam, dan kita telah berbicara tentang sumber-sumber keuangan yang paling penting dalam Islam, yaitu: zakat, jizyah, dan kharaj, dan pembicaraan kita dalam sumber-sumber ini adalah tentang bagaimana mewujudkan persamaan dan keadilan antara orang yang dikenai sumber-sumber ini, namun seharusnya kita menambahkan kepada sumber-sumber ini sumber lain, yaitu usyur.
Maka kami katakan: berlalu masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan negara Islam tidak memerlukan harta; karena sedikitnya fasilitas dan tidak adanya kebutuhan; hingga masa Umar radhiyallahu anhu maka meluaslah negara Islam -dengan apa yang Allah bukakan bagi kaum muslimin dari negeri-negeri- maka kebutuhan mengajak untuk menetapkan pajak; untuk memenuhi kebutuhan; oleh karena itu Umar menetapkan usyur. Maka sistem usyur kembali kepada masa Umar bin Khaththab; telah diriwayatkan bahwa Abu Musa Al-Asy’ari menulis kepada Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu bahwa para pedagang dari pihak kami dari kaum muslimin datang ke negeri perang; maka mereka mengambil dari mereka setengah usyur; maka Umar menulis kepadanya berkata: Ambillah engkau dari mereka sebagaimana mereka mengambil dari pedagang kaum muslimin, dan ambillah dari ahli dzimmah setengah usyur, dan dari kaum muslimin dari setiap empat puluh dirham satu dirham -yaitu: seperempat usyur- dan tidak ada pada yang kurang dari dua ratus sesuatu, maka jika dua ratus maka padanya lima dirham, dan apa yang bertambah maka menurut perhitungannya.
Dan dari ini menjadi jelas bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu menjadikan manusia dalam usyur pada tiga tingkatan: kaum muslimin, diambil dari mereka seperempat usyur, dan dzimmi, diambil dari mereka setengah usyur, dan harbi (kafir yang berperang), diambil dari mereka sebagaimana mereka mengambil dari kaum muslimin; karena urusan antara mereka dan kaum muslimin dibangun atas perlakuan yang sama, dan atas imam untuk menambah dari usyur, atau mengurangi darinya hingga setengah usyur, atau menghapus itu dari mereka jika ia melihat dalam hal itu kemaslahatan, dan tidak bertambah apa yang diambil dari satu kali dari setiap yang datang dengan perdagangan setiap tahun, meskipun kedatangannya berulang, dan pajak ini tidak diambil dari pedagang kecuali jika ia berpindah dari negerinya ke negeri lain, dan inilah yang kita sebut pada waktu sekarang: dengan pajak bea cukai.
Dan mengenai pajak usyur dapat dirujuk kepada kitab (An-Nizham Al-Mali) dalam Islam karya Dr. Abdul Khaliq An-Nawawi halaman 117 dan seterusnya, dan kitab (An-Nuzum Al-Islamiyyah) karya Dr. Hasan Ibrahim halaman 239 dan seterusnya.
PELAJARAN: 7 SISTEM POLITIK ISLAM
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Pajak Perdagangan, Konsep Politik dan Pilar-pilarnya dalam Islam serta Sumber-sumber Hukum Politik dalam Sistem Islam
Istilah Politik sejak Awal Negara Islam
Kita mulai sekarang membahas tentang sistem politik dalam Islam, maka kita katakan -dan dengan pertolongan Allah-:
Ada orang yang meragukan keberadaan apa yang disebut politik sebagai ilmu pada kaum muslimin; karena mengira bahwa ilmu tersebut termasuk hal-hal baru dari zaman ini, atau merupakan istilah yang hanya berlaku di kalangan non-muslim; karena bagaimana mungkin kaum muslimin mengenalnya, atau memasuki kedalaman permasalahannya, apa urusan mereka dengan politik, padahal mereka lebih dekat dengan fitrah, dan hanya sejengkal atau lebih dekat dari kebeduinan yang akan membawa pemiliknya pada kebinasaan; karena perkataan yang muncul begitu saja, atau perilaku spontan; karena jauhnya mereka dari sikap waspada dan toleransi, serta kekerasan hati mereka pada sikap kasar dan keras, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan dari itu, dan ini serta lainnya jauh dari pemahaman politik dan konsepnya.
Artinya ada orang yang meragukan bahwa kaum muslimin dahulu mengenal politik dengan makna modern, dan mengatakan bahwa bangsa Arab adalah penduduk padang pasir yang fanatik, maka bagaimana mereka mencapai jenis politik yang merupakan bentuk toleransi? Namun kami katakan kepada mereka: Sesungguhnya pernyataan ini secara mutlak bertentangan dengan kenyataan; karena orang-orang yang mengatakan hal ini -dan betapa banyaknya mereka- adalah kaum yang memiliki tujuan yang dikenal, dan maksud-maksud yang terkenal dan familiar, mungkin yang terpenting di antaranya adalah menyingkirkan Islam dari pemerintahan manusia, dan mengarahkan jalannya kehidupan mereka; agar mereka menjauh dari komitmen terhadap hukum-hukumnya; sehingga terwujud bagi mereka pemuasan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang tidak dibenarkan oleh syariat, apalagi melarangnya, dan memperingatkan dari terjebak di dalamnya, atau mendekatinya. Sesungguhnya mereka yang mengklaim bahwa kaum muslimin tidak mengenal politik di masa mereka, mereka memiliki maksud-maksud buruk dalam klaim ini, mereka ingin menjauhkan Islam dari arena pemerintahan, dan ini adalah kezaliman.
Jika engkau ingin mengungkap kebenaran dalam masalah ini; maka ketahuilah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para khalifah beliau memiliki politik yang mereka gunakan untuk mengatur bangsa Arab di Jazirah, dan bangsa-bangsa lain yang tunduk kepada Islam, dan dikuasai oleh pemerintahan kaum muslimin, yaitu bangsa-bangsa yang membentuk mayoritas dunia yang ada saat itu. Bagaimana mungkin dikatakan sebaliknya, padahal berbagai ras yang berbeda -Romawi, Persia, Habasyah, dan Arab- telah memeluk Islam, dan hidup berdampingan dalam naungan negara yang bersatu yang semua orang memberikan kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Apakah masuk akal dan dapat diterima bahwa semua ras ini memeluk Islam, dan bahwa kelompok-kelompok campuran yang berbeda dalam akar, adat istiadat, budaya, bahasa, dan filosofi mereka dapat hidup berdampingan tanpa politik yang mengarahkan kehidupan mereka?
Sesungguhnya hal itu -jika benar- bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pergaulan manusia yang paling sederhana; dan oleh karena itu pernyataan bahwa semuanya telah hidup dalam naungan politik yang berasal dari syariat -yang mewujudkan kepentingan mereka- lebih dekat kepada akal dan logika, dibuktikan dengan berdirinya negara Islam dengan kekuatannya, dan luasnya wilayahnya sepanjang zaman yang panjang di era Nabi, era Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah.
Pernyataan sebelumnya mengharuskan penjelasan kebenaran tentang apa yang dimaksud dengan politik, dan apa yang dituju olehnya. Politik diambil dari kata sasa, dikatakan: sasa ar-ra’iyyah yasusuha siyasatan, dan dikatakan: sasa al-amra yasusuhu siyasatan -artinya: mengurusnya.
Ibnu Qayyim telah mengemukakan definisi politik dengan perkataannya: Politik adalah perbuatan yang dengannya manusia lebih dekat kepada perbaikan, dan lebih jauh dari kerusakan -meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tidak turun dengannya wahyu. Maksud dari ini: bahwa politik adalah perwujudan dari kaidah Islam yang dikenal: menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, tanpa terikat dengan nash-nash dalam Kitab dan Sunnah, melainkan mencari apa yang bermanfaat bagi manusia, dan menjauhkan mereka dari kerusakan dalam cahaya Kitab dan Sunnah, ruh syariat, dan tujuan-tujuannya.
Dan politik -menurut pendapat sebagian ahli modern- berarti: pengaturan urusan-urusan umum negara Islam dengan cara yang menjamin terwujudnya kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan, yang tidak melampaui batas-batas syariat, dan prinsip-prinsip umumnya -meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
Pilar-pilar Politik dalam Islam
Sesungguhnya makna yang harus dipegang oleh negara Islam dalam hal pengurusan urusan-urusan politiknya adalah: tidak dapat dipisahkan antara pengarahan politiknya dengan identitas Islamnya. Politik di dalamnya termasuk dalam agama, dan berada dalam lindungannya. Mungkin kebenaran ini tampak jelas dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta’ala berfirman: “Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus” (Yusuf: sebagian dari ayat 40) dan firman-Nya Ta’ala: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Al-Maidah: sebagian dari ayat 50).
Dan makna ini adalah yang terus mendominasi pengarahan politik di negara Islam sepanjang periode ketika kaum muslimin memiliki kejayaan dan keagungan. Jika kita merenungkan pilar-pilar politik agama Islam; akan tampak bagi kita sebagai berikut:
Pertama: Beriman pada Ide dan Kesetiaan pada Persatuan: Sesungguhnya pilar ini -meskipun mengandung dua unsur, yaitu beriman pada ide, kemudian kesetiaan pada persatuan- namun masing-masing sangat erat kaitannya dengan yang lain. Kita katakan pertama: Beriman pada ide: kandungannya adalah bahwa negara harus menganut satu ide yang terangkum dalam bersatu di sekitar Islam sebagai akidah dan syariat, dan menganggap keislaman adalah kewarganegaraan yang mewakili ikatan politik dan hukum antara muslim dan negara dalam Islam, dan dalam kerangkanya kesetiaan bagi muslim adalah mengorbankan semua yang dimilikinya demi Islamnya dan agamanya, dan meninggikannya di atas segala ikatan. Dengan demikian muslim menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta’ala dengan firman-Nya: “Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam” (Al-An’am: ayat 162) dan firman-Nya ‘Azza wa Jalla: “Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan” (Al-An’am: 79).
Dan konsekuensi dari itu adalah tidak ada tempat dalam naungan beriman pada ide bagi negara yang di dalamnya fanatisme kesukuan saling berperang, atau menonjolnya nasionalisme, atau bangsa-bangsa yang saling meninggikan diri; karena sesungguhnya politik agama telah melebur semua fanatisme ini dalam akidahnya, dan menjadikan semua kaum muslimin mengibarkan bendera tauhid dalam keyakinan mereka, dan beriman kepada para nabi semuanya, dan bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam adalah penutup para rasul, dan bahwa risalah Islam adalah risalah umum untuk semua, dan bahwa mereka mengarahkan politik mereka dengan orang lain sesuai dengan kebenaran ini.
Dan hal itu tidak berarti bahwa muslim tidak merasakan kasih sayang dan rahmat terhadap anak-anak bangsanya, atau rasnya, melainkan berarti: bahwa hal itu tidak mengalahkan kesetiaannya pada Islamnya, dan menganggap persaudaraan adalah ukuran yang menghubungkan antara dirinya dengan semua kaum muslimin, baik mereka dari anak-anak bangsanya maupun dari selainnya. Sebagaimana tidak berarti: mengarahkan politik negara dengan Islam terhadap non-muslim bahwa memaksakan akidah Islam kepada mereka, karena ini adalah yang ditolak oleh Islam berdasarkan nash yang muhkam dalam firman-Nya Ta’ala: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat” (Al-Baqarah: sebagian dari ayat 256) dan firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus: sebagian dari ayat 99).
Berkenaan dengan kesetiaan pada persatuan, kita dapati bahwa persatuan adalah pilar dari pilar-pilar politik Islam yang mengumpulkan kaum muslimin pada prinsip dan tujuan, dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Setiap politik yang tidak menjadikan hal itu sebagai keputusannya adalah politik yang menyimpang dari jalan Islam; karena kaum muslimin meskipun ada perbedaan di antara mereka dalam orientasi, adat istiadat, dan ras, mereka adalah saudara dalam agama, dan ini adalah tuntutan Islam, yang diperintahkan oleh nash-nash, dan mendorong untuk itu, dan ini melampaui pemikiran teoritis menuju aspek praktis; Allah Ta’ala berfirman: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” (Ali Imran: sebagian dari ayat 103) dan Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya (agama) umat ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku” (Al-Anbiya: 92).
Dalam hadits, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mendatangi kalian sedangkan urusan kalian terkumpul di bawah satu orang, ia ingin memecah tongkat kalian atau memecah jamaah kalian, maka bunuhlah dia”. Dalam dalil-dalil ini terdapat isyarat wajibnya persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin; karena ia adalah sumber kekuatan dan ketangguhan, dan pondasinya, dan ia adalah sarana dari sarana-sarana terpenting yang menjaga keberadaan mereka, kewibawaannya, dan meluncurkan mereka menuju pencapaian tujuan-tujuan agama dan duniawi mereka.
Oleh karena itu, imam penguasa dianggap satu; karena yang dimaksud adalah terwujudnya pemimpin yang berpendapat dan ditaati yang mengumpulkan berbagai pendapat yang berbeda, dan menghalangi antara kaum muslimin dengan jalan-jalan perselisihan dan perpecahan, dan membawa mereka kepada kemaslahatan kehidupan dan akhirat; maka seandainya lebih dari satu imam bangkit untuk urusan ini, dan masing-masing dari mereka mengambil para pembantu, dan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan; maka dengan demikian kepentingan kaum muslimin akan terancam, dan kekacauan akan merata; oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa imam harus satu.
Yang dapat diamati dari realitas politik kaum muslimin adalah bahwa ia bertentangan dengan pandangan ini, yaitu persatuan. Jika banyak sebab yang melatarbelakangi realitas ini, mulai dari munculnya perselisihan kesukuan dan kedaerahan, cinta kekuasaan, kecenderungan pada individualitas dan dominasi, dominasi Eropa, dan serangan pemikiran yang dialami kaum muslimin, serta sebab-sebab lainnya; maka ada prinsip umum -yang harus mendominasi politik di kalangan kaum muslimin di timur dan barat bumi- yaitu bahwa ia harus berjalan dalam lingkup Islam, dan bersumber darinya dalam prinsip-prinsipnya. Pernyataan ini tidak membelenggu pemikiran Islam; karena kaum muslimin dituntut untuk meneliti dan melihat, serta menciptakan cara-cara yang sesuai dengan kondisi mereka yang berubah-ubah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syara’, sebagaimana mereka harus memberi manfaat kepada orang lain, dan mengambil manfaat dari mereka; karena persoalan-persoalan politik termasuk hal-hal yang di dalamnya pandangan berbeda, dan perkataan beragam, dan ini termasuk cara memperkaya pemikiran politik; karena ia adalah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan kejadian dan peristiwa.
Dan dari hasil hal itu adalah bahwa metode-metode yang menangani tuntutan realitas khusus bagi setiap wilayah dari wilayah-wilayah Islam akan berbeda, dan tidak ada yang memalukan dalam hal ini, dan tidak ada pertentangan di dalamnya dengan nash-nash, atau kaidah-kaidah Islam; karena wajar jika setiap negara berbeda dalam adat istiadatnya, kondisi sosial, ekonomi, pembangunan, dan budayanya, dan politik yang dirancang untuk wilayah atau negara tersebut mendominasi semua itu, yang bertujuan mengetahui cara-cara terbaik yang dengannya dapat terwujud kebangkitan dan kemajuan bagi wilayah dalam kerangka musyawarah, tukar pendapat, dan kerjasama antara anak-anak agama dan tanah air yang satu.
Sesungguhnya dalam mencari sebab-sebab, atau metode-metode yang mewujudkan tujuan dalam kemuliaan wilayah dan kebangkitannya ada yang mewajibkan memberi kesempatan bagi semua pendapat, dan semua arah, dan menganggap hal itu sebagai ukuran yang benar untuk memahami pandangan-pandangan yang berbeda, dan terkadang bertentangan untuk mengambil yang terbaik darinya, dan mewajibkan semua orang dengan apa yang diputuskan oleh pendapat, tanpa mengurangi, atau merendahkan pendapat yang berbeda.
Namun kebebasan berpikir, kewajiban musyawarah, dan pembolehan kemandirian setiap wilayah dengan politik khusus untuknya; hanyalah membentuk beberapa manifestasi dari politik umum yang bersatu yang mengatur semua kaum muslimin, kandungannya: kesatuan unsur-unsur yang mengutamakan kepentingan semua, dan bahwa mereka menjadi satu barisan. Ini mengharuskan adanya cara-cara yang kepadanya wilayah-wilayah ini berpaling ketika ada perbedaan; untuk menjamin bantuan bagi setiap wilayah dalam mengurus urusannya, dan agar kepentingan khusus tidak melampaui kepentingan umum, atau bertentangan dengannya, dan agar terwujud komitmen pada garis Islam.
Dan dari pilar-pilar juga yang seharusnya politik dibangun di atasnya di negara Islam, harus dipraktikkan politik agama -dalam naungan hukum Islam- karena ia adalah patokan yang sesuai dengannya politik digambarkan bahwa ia benar, atau salah. Oleh karena itu politik dalam Islam bukan termasuk politik mutlak, karena hal itu berarti: bahwa negara, para penguasa, dan individu tidak terikat dengan nash-nash syariat, dan mengikuti apa yang tampak baginya sebagai kemaslahatan dari logika manusia semata, dan yang menjadi pembimbingnya dalam hal itu adalah kehendak rakyatnya, dan penguasanya, tanpa melihat kepada agama dan kebenaran, dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam.
Untuk menjelaskan hal itu dapat dibedakan antara dua perkara:
Perkara Pertama: Bahwa prinsip-prinsip politik -yang disebutkan oleh nash-nash agama dalam Kitab dan Sunnah, atau terjadi mengenainya ijma’- prinsip-prinsip ini wajib dipegang dan tidak ada ruang untuk melepaskan diri darinya, atau melanggarnya. Seperti hukum dengan adil, dan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (An-Nisa: sebagian dari ayat 58). Seperti juga metode musyawarah, dan tukar pendapat, ini adalah prinsip-prinsip politik, Allah Ta’ala berfirman: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah” (Ali Imran: 159).
Dan seperti ketaatan kepada penguasa selama dia tidak memerintahkan kemaksiatan, karena sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik”. Dan seperti persamaan di antara manusia; diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Manusia itu sama seperti gigi sisir”.
Atau dalam hal yang ditetapkan berdasarkan ijmak seperti baiat kepada imam; maka prinsip-prinsip ini dan yang serupa dengannya—prinsip-prinsip yang telah kami sebutkan seperti hukum dengan keadilan, seperti musyawarah, seperti ketaatan kepada imam dalam hal yang bukan maksiat, seperti mewujudkan keadilan dan persamaan di antara manusia.
Kami katakan: prinsip-prinsip ini dan yang serupa dengannya merupakan pilar-pilar politik Islam yang tidak ada ruang untuk ragu dalam mengambilnya, dan tidak dianggap pendapat umat atau penguasa jika bertentangan dengannya. Sebab keterikatan dengan pilar-pilar seperti ini adalah tidak ada jalan untuk menegakkan pemerintahan yang baik dan menjalankan politik yang kuat tanpa bergantung atau bersandar kepadanya. Jika kamu ragu tentang hal itu, maka lihatlah jejak bangsa-bangsa besar di masa lalu dan sekarang; kamu akan mendapati bahwa di antara sebab-sebab mereka mencapai puncak kejayaan adalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini dan lainnya yang tidak ada jalan untuk kemajuan tanpanya.
Oleh karena itu, Syariat datang dengan tegas tentang kewajiban terikat pada kaidah-kaidah ini. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Surat Al-Maidah: 49) Dan firman-Nya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Surat Al-Jasiyah: 18).
Jika demikian halnya, maka masalah keterikatan dengan nash-nash menjadi dari perkara-perkara yang bukan tempat untuk khilaf atau menimbulkan perdebatan tentangnya. Dan semua yang mungkin dilakukan umat atau penguasa dalam bidang ini adalah penafsiran, dan memperhatikan keadaan umat serta perubahan zaman dalam lingkup rincian-rincian yang berkaitan dengan prinsip, dan mengemukakan gambaran-gambaran yang menjadi dasar penerapan tanpa hal itu menyentuh prinsip itu sendiri.
Perkara kedua: bahwa kaidah-kaidah politik dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan yang tidak disebutkan dalam Kitab atau Sunnah tunduk pada kaidah-kaidah umum dalam Syariat, seperti: pengangkatan penguasa melalui referendum, dan masa jabatan penguasa dibatasi dengan waktu tertentu, serta mengambil sistem majelis perwakilan; maka perkara-perkara ini dan yang serupanya dapat dirujuk kepada kaidah-kaidah untuk memutuskan pengambilan atau tidak mengambilnya. Dan kami ingatkan dalam hal ini bahwa berhukum kepada kaidah-kaidah adalah dengan menampilkan hukum-hukum ini pada kaidah-kaidah Syariat dan pada preseden-preseden politik Islam; jika merupakan penerapan dari suatu kaidah atau mengikuti suatu preseden, maka diambil. Demikian pula jika hukum-hukum dan sistem-sistem politik dalam kerangka kaidah-kaidah Islam atau tidak bertentangan dengan salah satunya, maka diambil juga.
Dari itu jelaslah bahwa bidang komitmen terhadap kaidah-kaidah umum Syariat tidak naik ke tingkat sistem-sistem dan hukum-hukum yang diucapkan oleh nash-nash Al-Quran dan Sunnah, atau yang menjadi tempat ijmak. Namun unsur komitmen terhadapnya ada; dan karenanya wajib terikat dengannya khususnya jika mewujudkan kemaslahatan vital bagi negara Islam.
Sesungguhnya landasan komitmen terhadap kaidah-kaidah umum dalam syariah bersumber dari kenyataan bahwa ia memenuhi salah satu kebutuhan Islam yang dapat dikenali seiring perkembangan zaman dan penciptaan sistem-sistem baru untuk meningkatkan sistem-sistem politik. Dan pentingnya hal itu terletak pada tidak merincikan bentuk-bentuk pemerintahan dan membatasi semua prinsip yang harus dipatuhi negara Islam dalam bidang pemerintahan dan politik dalam Al-Quran, atau Sunnah, atau Ijmak, yaitu sumber-sumber kewajiban dalam sistem Islam yang tidak ada tempat untuk menyimpang darinya.
Dan dalam aspek ini, umat Islam memiliki peran yang dilakukannya untuk meningkatkan sistem pemerintahan di dalamnya dan menjadikannya lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan umat, agar terwujud stabilitas politik di dalamnya, dan agar hubungan baik antara penguasa dan yang dikuasai merata; dimana dapat dikurangi—jika bukan mengakhiri—konflik-konflik politik seputar kekuasaan.
Jika itu terbukti, maka tidak benar apa yang disebutkan Montesquieu dalam bukunya (Ruh Undang-undang) yang mencap dan menggambarkan negara Islam sebagai negara mutlak; ketika ia berkata: Sesungguhnya kerajaan-kerajaan ini—ia maksudkan yang mutlak—kita dapati agama di dalamnya memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruhnya di kerajaan-kerajaan lain, dan ia di dalamnya adalah ketakutan atas ketakutan; maka di kerajaan-kerajaan Islam kamu dapati bahwa penghormatan yang luar biasa terhadap raja dari rakyat adalah dasar agama.
Kemudian ia memberi contoh tentang itu pada apa yang terjadi di Turki, dan berkata: bahwa orang-orang hanya mengagungkan raja sangat banyak, dan itu sebabnya adalah agama; jadi makna itu adalah ia menjelaskan bahwa negara Islam adalah negara yang tidak mengenal musyawarah, dan dibangun atas ketakutan terhadap agama, dan bahwa agama menakuti orang-orang dan mencegah mereka dari menghadapi penguasa; bahkan jika ia zalim. Dan ini adalah ilusi—besar. Kami menjawab Montesquieu dan berkata kepadanya: apa yang engkau katakan ini adalah ilusi besar—bahwa penggambaran negara Islam sebagai mutlak adalah yang paling jauh dari sifat negara ini; ia adalah negara manhaj Ilahi yang diridhai Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkan khalifah manusia di bumi; dan karenanya ia harus terikat dengan batasan-batasan manhaj ini, manhaj itu yang bersandar pada keadilan, menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, dan kebebasan manusia terhadap saudaranya manusia; sebagai ketaatan kepada penghambaan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Dan tidak benar cap Montesquieu atau penggambarannya terhadap agama Islam bahwa ia menambah umat Islam ketakutan atas ketakutan; sesungguhnya Islam adalah agama akal dan keyakinan, bukan agama pemaksaan dan penindasan. Dan kaum muslim menyembah Allah dan berkomitmen dengan syariatnya sesuai dengan kebenaran ini, dan dengan makna yang lebih tepat maka ini adalah karena keinginan dan ketakutan; maka bukan targhib (dorongan) saja atau tarhib (ancaman) saja yang cukup dalam hal itu, meskipun keinginan mendahului ketakutan dan mendahuluinya. Dan ini membatalkan klaimnya tentang ide ketakutan yang timbul dari agama, yang ia anggap sebagai sebab kenyataan bahwa negara Islam termasuk kerajaan-kerajaan mutlak.
Dan akhirnya, tidak ada tempat untuk penghormatan yang luar biasa itu yang ia klaim untuk imam, yang sandarannya adalah agama. Dimana ini dari hak kritik yang diletakkan Abu Bakar dalam ucapannya: “Jika aku berbuat baik maka tolonglah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku.” Dan rakyat menyatakannya di hadapan Umar dalam ucapan salah seorang muslim kepadanya: “Demi Allah, jika kami dapati padamu kebengkokan niscaya kami luruskan dengan pedang kami.” Bukankah lebih pantas bagi Montesquieu—dan ia adalah peneliti yang teliti—untuk tidak memasukkan agama dalam ilusi yang tampak baginya, atau sesungguhnya hujahnya dengan perbuatan Turki tidak ada nilainya dan bukan sesuatu; karena mereka bukan hujah atas Islam—meskipun mereka dari kaum muslim—karena mereka mengambil dari Islam bentuk Khilafah dan membuang isinya ke samping; karena sebab-sebab politik dan positivis murni yang tidak ada hubungannya dengan agama.
Kami simpulkan dari itu bahwa politik negara Islam adalah politik yang terikat dengan hukum Syariat Islam, keterikatan itu yang tidak mengarah pada pengabaian nash atau keluar darinya atau menyimpang dari suatu kaidah dari kaidah-kaidah Islam.
Sumber-sumber Hukum Politik dalam Sistem Islam: Pertama Al-Quran Al-Karim
Kita berbicara sekarang tentang sumber-sumber sistem politik dalam Islam. Sistem politik dan konstitusional dalam Islam adalah bagian dari kumpulan hukum-hukum syar’i yang membentuk dalam keseluruhannya apa yang dikenal dengan Fikih Islam; oleh karena itu wajib bagi yang ingin menjelaskan sumber-sumber sistem politik dalam Islam untuk berbicara tentang sumber-sumber fikih secara umum; karena sumber-sumber tasyri’ Islam adalah satu, baik itu dalam bidang tasyri’ perdata, atau tasyri’ internasional, atau tasyri’ ekonomi, atau tasyri’ politik, atau bahkan dalam bidang ibadah; maka semua pengaturan ini mengambil hukum-hukumnya dari mata air yang satu yaitu: sumber-sumber Fikih Islam, atau dalil-dalil hukum yang diteliti ulama Ushul Fikih dengan bentuk yang tidak ada tambahan lagi.
Namun ini tidak mencegah kita tentu saja untuk mengenal sumber-sumber ini; untuk melihat bagaimana kita dapat mengambil darinya hukum-hukum politik dan konstitusional dalam sistem Islam. Dan diketahui bahwa sumber-sumber Fikih Islam terbagi menjadi: sumber-sumber naqli (tekstual) yang terwakili dalam Kitab dan Sunnah; karena keduanya dinukil kepada mereka melalui wahyu, dan tidak ada bagi akal bidang dalam meletakkannya, meskipun harus menggunakan akal dalam memahaminya dan mengambil hukum-hukum darinya. Dan terbagi juga menjadi sumber-sumber lain yang aqli (rasional), yang mencakup semua sumber-sumber itu yang dilakukan melalui ijtihad—dengan maknanya yang luas—dan dari ulama Ushul ada yang membagi sumber-sumber ini menjadi: sumber-sumber asli yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan lainnya tabi’i (turunan) yang ditunjukkan oleh nash-nash dan dianggap dalam pengambilan atau pendirian hukum-hukum atasnya—ketika tidak ada nash—dan itu seperti Ijmak, Qiyas, Mashalih Mursalah, dan semacamnya.
Oleh karena itu kita akan menjadikan kajian kita dalam hal ini mencakup sumber-sumber sistem politik Islam, baik yang asli maupun turunan; maka kita berbicara pertama tentang Al-Quran Al-Karim sebagai sumber hukum-hukum politik dan konstitusional.
Al-Quran Al-Karim: adalah Kalam Allah Subhanahu wa Ta’ala yang diturunkan dengannya Jibril yang Amin Alaihissalam kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ia adalah apa yang dinukil kepada kita di antara dua sampul Mushaf secara mutawatir. Dan telah perhatian Sahabat Radhiyallahu Anhum dengan menukil dan memurnikannya dari selainnya, dan mereka berlebihan dalam hal itu; sehingga mereka tidak suka tasykil dan titik; agar tidak bercampur dengan Al-Quran selainnya. Maka yang tertulis di antara dua sampul Mushaf adalah Al-Quran lengkap tidak kurang; karena mustahil dalam kebiasaan—dengan tersedianya pendorong-pendorong untuk menjaga Al-Quran dan menukil—bahwa diabaikan sebagiannya sehingga tidak dinukil, atau dicampur dengannya apa yang bukan darinya.
Dan telah dimulai turunnya Al-Quran kepada Nabi Yang Mulia Shallallahu Alaihi wa Sallam di Makkah Al-Mukarramah tahun 610 Masehi, yaitu pada hari ketujuh belas Ramadhan tahun keempat puluh satu dari kelahirannya Shallallahu Alaihi wa Sallam—dan terus turunnya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga tanggal sembilan Dzulhijjah hari Haji Akbar tahun kesepuluh Hijriah, dan tahun keenam puluh tiga dari kelahirannya Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan Al-Quran Al-Karim turun secara berangsur-angsur terpisah; untuk meneguhkan dengannya hati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan agar menyertai peristiwa-peristiwa yang dilalui masyarakat Islam dari awal bi’tsah hingga akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah.
Dan Al-Quran Al-Karim telah melalui—dalam turunnya—dua periode yang berbeda: yaitu periode Makkiyah—dan di dalamnya turun sebagian besar Al-Quran—dan disebut pada ayat-ayat dan surat-surat yang turun di Makkah: Al-Quran Makki. Dan ciri khas ayat-ayat dan surat-surat ini adalah bertujuan untuk membentuk akidah yang benar dan membersihkannya dari khurafat dan kesesatan lama melalui hujah dan logika.
Kemudian periode Madaniyah, dan membentang dari Hijrah hingga wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan di dalamnya sempurna tasyri’, dan disebut pada ayat-ayat dan surat-surat yang turun dalam periode ini: Al-Quran Madani. Dan ciri khas tasyri’ dalam periode ini adalah penjelasan hukum-hukum dan taklif-taklif syar’i setelah mukallaf telah siap untuk itu dengan perbaikan akidah mereka dalam periode Makkiyah.
Dan tidak dikumpulkan Al-Quran Al-Karim pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi tertulis dalam lembaran-lembaran dan terhafal di dada Sahabat. Dan orang pertama yang melakukan pengumpulannya adalah Abu Bakar Radhiyallahu Anhu ketika ia menjabat khilafah kaum muslim, dan terbunuh sejumlah besar penghafal Kitabullah Ta’ala dalam pertempuran Yamamah.
Kemudian ketika meluaslah wilayah negara Islam dan berpencar Sahabat di negeri-negeri yang ditaklukkan; khawatir Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa kaum muslim berbeda dalam Al-Quran; maka ia melakukan setelah bermusyawarah dengan Sahabat pengumpulannya untuk kedua kalinya, bergantung dalam hal itu pada usaha-usaha Abu Bakar sebelumnya, dan menulis salinan-salinan berbeda dari Mushaf dan membagikannya ke negeri-negeri Islam yang berbeda, dan membakar selainnya; agar kaum muslim tidak berbeda dalam Al-Quran. Dan jumlah surat-surat Al-Quran 114 surat, dan jumlah ayat-ayatnya: 6341. Dan ayat-ayat dan surat-surat ini tersusun, dan kebanyakan ahli ilmu bahwa susunannya adalah tauqifi, tidak ada pendapat Sahabat di dalamnya. Kemudian berlanjut usaha-usaha kaum muslim setelah itu—dan hingga Allah mewarisi bumi dan siapa yang ada di atasnya—atas perhatian terhadap Mushaf Syarif penulisan, percetakan, hafalan, dan penjelasan. Dan benar Allah Yang Maha Agung yang berfirman: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Surat Al-Hijr: 9).
Dan terbagi hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim menjadi: hukum-hukum i’tiqadiyah (akidah) yang bertujuan untuk memperbaiki akidah manusia dari sisi imannya kepada Allah Ta’ala dan dengan apa yang datang dari sisi-Nya dari apa yang dikhabarkan Rasul-rasul Alaihimush Shalatu was Salam.
Dan juga hukum-hukum khuluqiyah (akhlak) yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amal dan kebaikan-kebaikan akhlak.
Dan ada juga—ketiga—hukum-hukum amaliyah (praktis) yang berkaitan dengan penjelasan hukum Allah Ta’ala dalam apa yang keluar dari mukallaf dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan tindakan-tindakan, dan ia adalah apa yang disebut dengan nama: Fikih, atau Tasyri’ Islam.
Ringkasan ini bahwa hukum-hukum yang mencakup Al-Quran Al-Karim terbagi menjadi tiga bagian: hukum-hukum i’tiqadiyah (akidah), hukum-hukum khuluqiyah (akhlak), dan hukum-hukum amaliyah (praktis).
Dan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran tidak lebih dari lima ratus ayat, dan terbagi menjadi hukum-hukum ibadah, dimaksudkan dengannya pengaturan hubungan antara manusia dan Tuhannya, dan mencakup 140 ayat. Dan hukum-hukum muamalah, yaitu yang berkaitan dengan penjelasan pengaturan tasyri’ untuk seluruh hubungan individu-individu—di antara mereka, atau di antara mereka dan penguasa, atau di antara mereka dan negara-negara lain—dan telah disebutkan Syaikh Abdul Wahhab Khallaf bahwa jenis hukum ini terbagi menjadi beberapa bagian:
- Hukum-hukum Ahwal Syakhsiyah atau hukum keluarga, yang mencakup hukum pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, dan pengampuan (hajr), meliputi sekitar 70 ayat.
- Hukum-hukum perdata, yaitu yang berkaitan dengan muamalat individu dan transaksi mereka seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, jaminan, perserikatan, dan sebagainya, meliputi sekitar 70 ayat.
- Hukum-hukum pidana (jinayah), yaitu yang berkaitan dengan penjelasan tentang kejahatan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang terbebani hukum) dan hukuman yang pantas dijatuhkan atasnya, meliputi sekitar 30 ayat.
- Hukum-hukum acara peradilan (murafaat), yaitu yang berkaitan dengan pengaturan prosedur yang ditempuh pengadilan untuk mempertimbangkan hak-hak manusia, dan penjelasan tentang hukum gugatan dan pembuktian, meliputi sekitar 13 ayat.
- Hukum-hukum konstitusi (dusturiyah), yaitu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan dasar-dasarnya—yakni: penentuan hubungan antara penguasa dan rakyat, dan penjelasan tentang hak masing-masing pihak serta kewajibannya, meliputi sekitar 10 ayat.
- Hukum-hukum internasional (duwaliyah), berkaitan dengan penjelasan hubungan negara Islam dengan negara lain dalam keadaan damai maupun perang, ayat-ayatnya meliputi sekitar 25 ayat.
- Dan akhirnya hukum-hukum ekonomi dan keuangan, yaitu yang mengatur hubungan finansial dari segi sumber pendapatan dan cara pengeluaran dan sebagainya, meliputi sekitar 10 ayat.
Yang penting bagi kita dalam hal ini adalah menetapkan bahwa Al-Quran—sebagai sumber pertama syariat—telah memberikan perhatian pada penetapan banyak hukum konstitusi dan politik. Ayat-ayatnya yang mulia berbicara tentang pemerintahan, kepemimpinan, kerajaan, kekuasaan, wilayah, kedaulatan, peradilan, perang, perdamaian, perjanjian, hak-hak individu dan kebebasan mereka, hak penguasa, hak ahli dzimmah (non-Muslim yang dilindungi) dari kalangan warga negara, atau yang dikenal dengan status orang asing dan minoritas dalam hukum internasional modern. Al-Quran juga berbicara tentang syura (musyawarah) sebagai sistem pemerintahan, dan berbagai masalah pokok konstitusi dan politik lainnya yang disebutkan Al-Quran dan terpelihara serta terdokumentasi sebelum negara-negara modern mengenal konsep konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum politik dan konstitusi mereka. Hal ini menjadikan syariat yang agung sebagai perintis dalam bidang ini.
Namun harus diperhatikan bahwa penjelasan Al-Quran tentang hukum politik dan konstitusi hanya terbatas pada kaidah-kaidah umum dan pemikiran global saja. Al-Quran tidak membahas hal-hal detail dan rincian tata cara kecuali sedikit, karena hal itu akan mengurangi keindahan bahasa Al-Quran dan sifatnya sebagai kitab yang seperti konstitusi bagi seluruh hukum syariat. Maka pendekatan penjelasan seperti ini mengandung dorongan semangat untuk memahami kaidah-kaidah universal tersebut dan menerapkannya dalam berbagai bentuk yang dimungkinkan oleh nash dan tidak bertentangan dengannya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran tentang nash syura politik tanpa menentukan bentuk khusus untuknya. Dengan demikian ia mencakup setiap sistem pemerintahan yang mewujudkan keadilan dan menghindari kezaliman, kesewenang-wenangan, dan pendapat satu orang, tanpa memandang apakah sistem tersebut republik, kerajaan, khilafah, atau lainnya yang tidak ada monopoli kekuasaan oleh satu orang atau kelompok sesuai dengan yang ditentukan kemaslahatan umum masyarakat.
Kesimpulan dalam hal ini: bahwa Al-Quran—berkaitan dengan masalah pemerintahan dan sistem konstitusi—hanya terbatas pada hukum-hukum umum. Adapun rinciannya, maka Al-Quran tidak merincikannya. Mengapa? Karena syariat Islam adalah syariat penutup—penutup semua syariat—dan oleh karena itu akan tetap ada hingga hari kiamat dan sampai Allah mewarisi bumi dan seisinya. Oleh karena itu, Al-Quran bersungguh-sungguh meninggalkan ruang berpikir bagi manusia—terutama dengan perkembangan masyarakat dan banyaknya peristiwa dan kejadian baru—dan oleh karena itu Al-Quran meninggalkan rincian kepada mereka dan menetapkan batasan-batasan untuk sistem pemerintahan baik dari segi konstitusi maupun lainnya, kemudian meninggalkan rincian kepada mereka. Mereka boleh merinci hal-hal baru yang muncul sesuai dengan batasan-batasan syariat dan sesuai dengan hukum-hukum universal yang disebutkan dalam Al-Quran.
Kita berikan contoh dengan syura. Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (Surat Asy-Syura, sebagian dari ayat 38) dan berfirman juga: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Surat Ali Imran, sebagian dari ayat 159). Al-Quran telah menetapkan kaidah syura, tetapi tidak menjelaskan kepada kita bagaimana cara pelaksanaan syura tersebut. Oleh karena itu, rincian ini diserahkan kepada individu-individu, dan rincian ini akan berbeda dari satu zaman ke zaman lain dan dari satu tempat ke tempat lain. Yang penting adalah bahwa hal itu dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan umum yang ditetapkan Al-Quran.
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menetapkan bahwa Al-Quran adalah sumber pertama sistem politik Islam, dan sedikitnya ayat-ayat yang membahas penjelasan hukum masalah-masalah ini—adalah karena Al-Quran hanya terbatas pada penjelasan kaidah-kaidah universal saja, dan meninggalkan rincian dan hal-hal detail untuk kondisi setiap masyarakat sesuai dengan perkembangan baru dan peristiwa yang terjadi dengan tidak keluar dari dasar-dasar syariat dan tujuan-tujuannya. Dan ini bukan karena kurangnya perhatian Pembuat Syariat terhadap hukum-hukum ini—sebagaimana yang dicoba dipahami secara keliru oleh sebagian penulis modern, atau karena maksud baik darinya karena terpengaruh oleh pendekatan positivis di satu sisi, dan kurangnya latihan dan keakrabannya dengan kaidah-kaidah syariat Islam dan karakteristiknya di sisi lain. Benar firman Allah Yang Maha Agung tentang kitab-Nya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu” (Surat An-Nahl, sebagian dari ayat 89).
Demikian, semoga Allah memberikan taufik. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagian 2: Lanjutan – Sumber-Sumber Hukum Politik dalam Sistem Islam
Sunnah
Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, shalawat dan salam semoga tercurah kepada utusan yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, junjungan kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma badu:
Pada perkuliahan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep politik dalam Islam dan tentang Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum konstitusi dalam Islam. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang sumber kedua, yaitu Sunnah Nabi yang mulia.
Sunnah secara bahasa adalah: jalan dan perilaku. Ada yang berpendapat bahwa sunnah diambil dari kata “sanna” yang berarti menjelaskan. Sunnah dinamakan demikian karena ia menjelaskan Al-Quran. Adapun sunnah secara istilah yang dimaksud adalah perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, dan penetapannya (taqrir).
Sunnah qauliyah (perkataan) adalah apa yang keluar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, dan ini adalah bagian terbesar dari sunnah. Contohnya: sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya”, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya”, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat”, dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa, hendaklah dia shalat ketika mengingatnya”.
Sunnah fi’liyah (perbuatan) adalah perbuatan-perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dinukil darinya, seperti shalatnya shallallahu alaihi wasallam dan hajinya. Beliau alaihi shalatu wassalam shalat dan bersabda: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat”. Beliau shallallahu alaihi wasallam berhaji dan bersabda: “Ambillah dariku manasik haji kalian”. Termasuk juga apa yang dilakukan beliau shallallahu alaihi wasallam seperti keputusan hukumnya dengan sumpah dan satu saksi, dan apa yang dilakukan beliau shallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Semua itu dianggap sunnah karena perbuatannya shallallahu alaihi wasallam.
Adapun sunnah taqririyah (penetapan): yaitu Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat suatu perbuatan atau mendengar perkataan lalu membenarkannya. Mungkin terjadi dari para sahabat di hadapan beliau shallallahu alaihi wasallam perkataan dan perbuatan, namun beliau tidak mengingkarinya, dan dalam hal itu terdapat penetapan (pembenaran). Contohnya: diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, bertanya kepadanya: “Dengan apa engkau akan memutuskan hukum?” Dia menjawab: “Saya memutuskan dengan Kitabullah (Al-Quran)”. Beliau bertanya: “Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?” Dia menjawab: “Maka dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bertanya: “Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah?” Dia menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan bermalas-malasan”. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menepuk (dada Muadz) dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk apa yang diridhai Rasulullah”. Termasuk juga: penetapan beliau shallallahu alaihi wasallam terhadap Ali radhiyallahu anhu dalam banyak keputusan hukumnya, dan penetapan beliau shallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat yang bertayamum untuk shalat ketika tidak menemukan air, kemudian menemukan air setelah shalat namun mereka tidak berwudhu dan tidak mengulangi shalatnya. Semua itu adalah penetapan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ini dianggap sunnah. Jadi sunnah adalah sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah, dan sunnah taqririyah.
Sunnah yang suci dianggap sebagai sumber kedua legislasi Islam setelah Al-Quran, karena Allah Taala telah memerintahkan untuk mentaati Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dan mengaitkan ketaatan ini dengan ketaatan kepada-Nya Subhanahu wa Taala. Firman Allah Azza wa Jalla: “Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” (Surat Al-Hasyr, ayat 7). Dan berfirman Subhanahu wa Taala: “Barangsiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah” (Surat An-Nisa, sebagian dari ayat 80). Asy-Syaukani berkata: “Di dalamnya terdapat bahwa ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, dan dalam hal ini terkandung pemberitaan tentang kemuliaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tingginya kedudukan dan martabatnya yang tidak dapat diukur kadarnya dan tidak dapat dicapai batasnya. Alasannya adalah bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kecuali apa yang diperintahkan Allah, dan tidak melarang kecuali apa yang dilarang Allah”. Atas dasar ini kaum muslimin telah bersepakat sejak awal Islam hingga hari ini tentang kewajiban mengambil sunnah dan menganggapnya sebagai sumber utama dari sumber-sumber legislasi Islam, terutama karena sebagian hukum telah dijelaskan secara global dalam Al-Quran, seperti kewajiban shalat, zakat, dan haji, dan kita tidak dapat memahami hukum-hukum ini kecuali dengan merujuk kepada penjelasan sunnah tentangnya. Seandainya sunnah bukan merupakan sumber legislatif, niscaya tidak mungkin kita mengetahui maksud Al-Quran dan sunnah.
Sunnah yang suci terbagi dari segi ketetapan (tsubut) kepada: sunnah mutawatir, sunnah masyhur, dan sunnah ahad. Sunnah mutawatir adalah apa yang diriwayatkan dari Rasul shallallahu alaihi wasallam sampai akhir sanad oleh sejumlah perawi yang mustahil menurut kebiasaan mereka bersepakat untuk berdusta, dengan syarat jumlah perawi ini ada di setiap tingkatan sanad. Karena kebiasaan mustahil jumlah perawi ini berkumpul di setiap tingkatan sanad dari awal hingga akhirnya. Kita katakan: kebiasaan mustahil jumlah perawi ini bersepakat berdusta karena banyaknya jumlah mereka, perbedaan lingkungan dan latar belakang mereka. Contoh jenis sunnah mutawatir ini adalah apa yang dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang tata cara pelaksanaan shalat, manasik haji, kadar-kadar zakat, tata cara adzan, dan sebagainya yang dinukil kepada kita secara mutawatir sejak zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita ini. Ini mengenai sunnah mutawatir.
Adapun sunnah masyhur: yaitu apa yang diriwayatkan dari Rasul shallallahu alaihi wasallam oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai tingkat mutawatir, kemudian jumlah perawi ini menjadi mutawatir setelah itu. Jadi kemutawatiran dalam sunnah masyhur tidak terjadi pada tahap pertama dari sunnah, dan inilah yang membedakannya dari sunnah mutawatir yang memenuhi syarat mutawatir dari awal sanad hingga akhirnya sebagaimana telah kami sebutkan.
Dan sunnah masyhur menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya memberikan ilmu yang yakin, tetapi tingkatannya di bawah ilmu yang diperoleh dari sunnah mutawatir, dan mereka terkadang menyebutnya dengan ilmu tuma’ninah (ketenangan hati) yang tidak mencapai tingkat keyakinan meskipun menyerupainya. Oleh karena itu, kita dapati bahwa mazhab Hanafi mewajibkan beramal dengan jenis sunnah ini, dan mereka mengikat dengannya hukum-hukum yang bersifat mutlak dalam Al-Qur’an dan mengkhususkan dengannya hukum-hukum yang bersifat umum dan semacamnya.
Dan kita sampai pada jenis ketiga, yaitu sunnah ahad: Sunnah ahad adalah setiap berita yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir atau masyhur menurut istilah Hanafiyah. Sunnah ahad memberikan dugaan yang kuat (ghalabatuzh zhann), dan tidak memberikan ilmu yang qath’i (pasti), karena sambungan sanadnya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masih diragukan.
Sebagian ulama mengatakan bahwa sambungan padanya terdapat keraguan secara lafal dan makna. Adapun penetapan keraguan secara lafal, karena sambungan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak terbukti secara pasti. Adapun secara makna, karena umat menerimanya dalam penerimaan, yaitu pada generasi yang mengikuti para tabi’in. Karena keraguan ini dalam sanad sunnah ahad, para ulama memutuskan bahwa wajib beramal dengannya jika tidak ada yang menentangnya, tetapi tidak diambil untuk masalah akidah, karena maknanya adalah kepastian dan keyakinan. Maksudnya, akidah bergantung pada kepastian dan keyakinan, sedangkan sunnah ahad berdiri atau memberikan dugaan yang kuat. Oleh karena itu tidak diambil untuk masalah akidah, karena akidah -sebagaimana telah kita katakan- dibangun di atas kepastian dan keyakinan, dan tidak cukup padanya dengan dugaan yang kuat yang diberikan oleh sunnah ahad, karena dugaan dalam akidah tidak dapat menggantikan kebenaran sedikitpun.
Dan disyaratkan untuk beramal dengan khabar wahid (berita yang diriwayatkan seorang perawi) menurut Abu Hanifah -selain kepercayaan terhadap perawi dan keadilannya- adalah agar perawi tidak bertentangan perbuatannya dengan apa yang diriwayatkannya. Artinya, agar perawi tidak menyalahi hadits yang diriwayatkannya. Di antara contohnya adalah apa yang diriwayatkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan berita: “Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah,” maka sesungguhnya Abu Hanifah tidak mengambilnya, artinya tidak mensyaratkan tujuh kali. Mengapa? Mereka berkata: karena Abu Hurairah sendiri -yang merupakan perawi berita tersebut- tidak mengamalkannya, karena ia cukup dengan mencuci tiga kali. Maka ini menjadi tanda kelemahan dalam periwayatan, dalam kebenaran penisbatannya kepada perawi itu sendiri.
Dan Malik radhiyallahu ‘anhu mensyaratkan untuk beramal dengan sunnah ahad: agar tidak bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah, karena dari mazhabnya bahwa apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah dalam urusan agama adalah periwayatan yang terkenal dan tersebar luas sehingga tidak tersembunyi bagi siapapun.
Syaikh Abu Zahrah mengatakan dalam hal ini: Malik dalam hal ini seperti gurunya Rabi’ah ar-Ra’yi, berpendapat bahwa amalan penduduk Madinah dalam urusan agama adalah periwayatan ribuan dari ribuan hingga sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka jika bertentangan dengannya khabar ahad, maka lemah penisbatannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga didahulukan atasnya. Maka pendahuluan amalan penduduk Madinah atas sunnah ahad menurut Malik adalah pendahuluan yang masyhur, tersebar luas, dan mutawatir atas khabar wahid, dan bukan penolakan semata terhadap khabar ahad. Artinya, Imam Malik tidak menolak khabar ahad, tetapi khabar ahad jika bertentangan dengan amalan penduduk Madinah menurut Imam Malik, maka ia mendahulukan amalan penduduk Madinah, tetapi ini tidak berarti bahwa ia menolak beramal dengan khabar ahad.
Kita kembali setelah pendahuluan ini kepada topik asal kita, yaitu: sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai sumber dari sumber-sumber hukum konstitusional dan politik dalam sistem Islam.
Kehujjahan Sunnah dengan Segala Jenisnya
Dan ketika kita telah menetapkan bahwa sunnah adalah sumber legislatif yang diakui dalam semua hukum syar’i dan bahwa hukum-hukum politik dan konstitusional dalam sistem Islam adalah bagian dari hukum-hukum syar’i praktis, maka kita menetapkan dalam hal ini dengan kepuasan penuh bahwa sunnah dianggap sebagai sumber bagi hukum-hukum ini seperti hukum-hukum lainnya sama sekali, tanpa perbedaan dalam hal ini antara sunnah mutawatir, sunnah masyhur, dan sunnah ahad. Hal ini tampak dalam dokumen tertulis yang dikenal dengan nama Konstitusi Madinah, atau yang disebut ash-Shahifah yang merupakan dasar dalam tahap pertama pembentukan negara Islam dalam hak-hak penguasa dan hak-hak rakyat serta pengaturan masyarakat dan negara. Demikian juga berulang dalam nash-nash sunnah yang suci kata-kata: pemimpin (ar-ra’i), rakyat (ar-ra’iyyah), bai’at, kepemimpinan, ketaatan kepada pemimpin. Dan di dalamnya terdapat perundang-undangan tentang hak-hak penguasa dan tanggung jawabnya, hak-hak individu, kebebasan mereka, kedaulatan, perdamaian, peperangan, perjanjian, peradilan, musyawarah, kedudukan minoritas agama, dan lain-lain yang masuk dalam inti hukum-hukum konstitusional dan politik dengan istilah kontemporer. Makna dari itu semua adalah bahwa sunnah juga seperti Al-Qur’an yang mulia dianggap sebagai sumber dari sumber-sumber hukum konstitusional dan politik dalam negara Islam, karena sebagaimana telah kita katakan: disebutkan urusan-urusan yang merupakan inti aspek-aspek konstitusional dan politik -sebagaimana telah kita katakan- seperti: kepemimpinan, ketaatan kepada pemimpin dan lain-lain, hak-hak individu dan kebebasan mereka, serta hubungan kaum muslimin dengan orang lain dalam perdamaian dan peperangan dan lain-lain.
Oleh karena itu, kita sangat heran dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang penulis modern tentang tidak berdalil dengan sunnah ahad dalam bidang hukum-hukum politik dan konstitusional. Kita telah mengatakan bahwa sunnah, baik sunnah mutawatir, sunnah masyhur, atau sunnah ahad adalah sumber bagi hukum-hukum konstitusional dan politik dalam negara Islam. Namun sebagian penulis modern di masa sekarang mulai menentang hal ini dan berpendapat bahwa sunnah ahad tidak bisa atau tidak layak menjadi sumber bagi hukum-hukum konstitusional dan politik dalam negara Islam.
Kita katakan: kita sangat heran dengan apa yang dikemukakan oleh sebagian ini tentang tidak berdalil dengan sunnah ahad dalam bidang hukum-hukum politik dan konstitusional. Namun jika kita mencari alasan bagi penulis ini karena ia bukan dari kalangan yang ahli dalam ilmu hadits dan sunnah atau yang terlatih dalam kajian-kajian Islam, oleh karena itu ucapannya tidak lebih dari sekadar pendapat pribadinya, maka mungkin urusan berakhir di sini. Namun ini tidak menghalangi kita bagaimanapun untuk mengajukan beberapa pemikiran penulis hukum yang terkenal ini bernama Dr. Abdul Hamid Mutawalli, dan ia adalah doktor dalam ilmu hukum konstitusional di fakultas-fakultas hukum. Kita katakan: kita harus meninjau beberapa pemikirannya untuk mengetahui apa yang terdapat dalam pemikiran-pemikiran ini dari kerancuan dan meluruskan apa yang harus diluruskan darinya.
Dan ringkasan pendapat doktor dalam hal ini, dan doktor menulis itu Dr. Abdul Hamid Mutawalli dalam buku yang ia beri nama (Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan dalam Islam) halaman 188 dan seterusnya.
Ringkasan Pendapat Dr. Abdul Hamid Mutawalli dan Pembahasan Terhadapnya:
Profesor Dr. Abdul Hamid Mutawalli berpendapat bahwa dalam kedudukan hukum konstitusional tidak boleh kita mengambil sunnah ahad ketika berdiri sendiri, artinya ketika datang dengan hukum-hukum atau prinsip-prinsip baru yang tidak dinashkan dalam Al-Qur’an, dan itu karena dua pertimbangan berikut:
- Pentingnya hukum-hukum konstitusional dan keberatihannya.
- Bahwa sunnah ahad tidak bersifat yakin.
Dr. Abdul Hamid Mutawalli tidak mengambil sunnah ahad terkait hukum-hukum konstitusional, dan ia membenarkan tidak mengambilnya dengan sunnah ahad terkait hukum-hukum konstitusional ini dengan mengatakan: pentingnya hukum-hukum konstitusional dan keberatihannya. Artinya, karena kepentingan dan kebertihan ini, maka tidak layak ditetapkan dengan sunnah ahad. Dan juga ia mengatakan bahwa sunnah ahad tidak bersifat yakin.
Kemudian profesor melanjutkan pembicaraannya dan menjelaskan permasalahan dengan mengatakan: Sesungguhnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum konstitusional berada pada tingkat kepentingan dan kebertihan yang besar, karena berkaitan dengan sistem politik negara, yaitu sistem pemerintahan di dalamnya, dan penjelasan kebebasan individu dan hak-hak dasar mereka di hadapan negara. Oleh karena itu, tidak dapat diterima bahwa kita mengambil sunnah dalam hal ini kecuali jika bersifat yakin, yaitu mutawatir atau setidaknya sunnah masyhur.
Dalam hal-hal seperti ini yang mengandung kepentingan dan kebertihan semacam itu, ketidakterkenalan sunnah dianggap sebagai indikasi kuat tentang ketidaksahihannya, yaitu tentang tidak benar-benar berasal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Inilah nash ucapan Dr. Abdul Hamid Mutawalli. Dan yang ingin kita bahas dengan profesor yang terhormat adalah: Apakah hukum-hukum konstitusional dan politik keluar dari menjadi hukum-hukum syar’i yang berdalil dalam persoalannya dengan apa yang berdalil dengannya dalam hukum-hukum lainnya? Dan di antara itu -tentu saja- sunnah ahad ketika sahih penisbatannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit dari yang semisal dengannya hingga ujungnya, dan haditsnya tidak syaz (menyendiri) dan tidak ber’illat dengan ‘illat yang mencacatnya.
Artinya, selama kita berdalil dengan sunnah ahad dalam hukum-hukum lain yang bukan konstitusional, maka kita harus berdalil dengannya dalam hukum-hukum konstitusional juga, dan menjadi sumber bagi hukum-hukum konstitusional juga, selama yang meriwayatkannya memiliki sifat keadilan dan kedhabitan. Dan apa yang dikemukakan oleh profesor yang terhormat tidak sahih dalam kedudukan syariat Islam yang tidak menganggap ada keistimewaan bagi hukum-hukum hukum publik atas hukum-hukum hukum privat. Setiap hukum syar’i yang telah berdiri dalil tentang tuntutannya -dengan cara apapun- harus dipatuhi. Dan para fuqaha yang mensyaratkan dalam sunnah ahad syarat-syarat khusus untuk beramal dengannya seperti Malikiyah dan Hanafiyah sebagaimana telah kita sebutkan, bukanlah akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat ini dalam pandangan mereka adalah penolakan sunnah ahad secara keseluruhan dan terperinci. Mereka tetap berdalil dengan sunnah ahad dalam banyak hukum kecuali beberapa hadits yang sedikit dan langka yang bertentangan dengan apa yang mereka syaratkan dalam beramal dengan sunnah ini.
Dan apakah hukum-hukum hukum politik dan konstitusional dalam keberatihannya mencapai tingkat akidah-akidah yang menurut ulama ushul dan fiqh: tidak cukup untuk menetapkannya dengan dugaan yang kuat yang diberikan oleh sunnah ahad, tetapi harus dalil penetapan akidah bersifat yakin, karena dugaan dalam hal ini tidak dapat menggantikan kebenaran sedikitpun?
Saya yakin bahwa hukum-hukum hukum politik dan konstitusional tidak mencapai tingkat akidah sehingga kita mensyaratkan untuknya hadits-hadits yang memberikan keyakinan seperti hadits-hadits mutawatir.
Kita catat bahwa: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan pemilik syariat dan pendiri negara kaum muslimin telah mutawatir darinya pengutusan para utusan, qadhi, dan pemimpin ke berbagai daerah dan ke negara-negara tetangga, dan mereka dengan itu adalah orang-orang yang sendirian (ahad), dan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa pengutusan ini tidak sahih. Bahkan penduduk negara-negara yang berbeda berkomitmen dengan hukum-hukum yang disampaikan kepada mereka oleh para utusan, pemimpin, dan qadhi dari pihak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan seandainya khabar wahid bukan hujjah yang mengikat, mereka tidak akan berkomitmen dengan itu.
Dan juga, Asy-Syafi’i telah menyebutkan dalam (Ar-Risalah) apa yang menunjukkan berdalil dengan khabar wahid dari hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda: “Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar perkataanku lalu menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Karena banyak pembawa ilmu fiqh namun ia bukan ahli fiqh, dan banyak pembawa ilmu fiqh kepada orang yang lebih ahli fiqh darinya.” Asy-Syafi’i berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan untuk mendengarkan perkataannya, menghafalnya, dan menyampaikannya dari seorang hamba yang seorang, ini menunjukkan bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk disampaikan dari beliau kecuali apa yang menjadi hujjah atas orang yang disampaikan kepadanya. Jadi, makna dari itu adalah bahwa hadits-hadits ini -hadits-hadits ahad- dijelaskan kepada kita oleh Imam Asy-Syafi’i bahwa ia berdalil dengannya. Bukankah amalan-amalan ini seperti mengutus para utusan, pemimpin, dan qadhi, dan semacamnya adalah inti dari masalah-masalah konstitusional dan politik yang diklaim oleh Dr. Abdul Hamid Mutawalli bahwa ia berada pada tingkat kebertihan dan kepentingan yang besar, dan karena itu ia sampai pada kesimpulan bahwa tidak cukup dalam menetapkannya dengan sunnah ahad karena tidak bersifat yakin?
Kita katakan: pengutus para utusan, pemimpin, dan qadhi yang dianggap dari masalah-masalah konstitusional dan politik bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Hamid Mutawalli. Dengan demikian ia tidak benar dalam apa yang dikemukakan tentang tidak mengandalkan -atau tidak mengambil- sunnah ahad dalam hukum-hukum konstitusional.
Sesungguhnya kita menyebutkan di sini atau mengingatkan di sini tentang apa yang telah kita isyaratkan sebelumnya bahwa hukum-hukum syar’i yang tidak berhubungan dengan akidah cukup dalam persoalannya dengan dugaan yang kuat saja. Oleh karena itu wajib beramal dengan hukum-hukum ini pada saat itu, agar tidak terhenti hukum-hukum karena langkanya dalil-dalil yang qath’i dan sedikitnya jalan-jalan keyakinan. Para ulama hanya mensyaratkan dalam bidang akidah bahwa dalil penetapannya harus yakin, karena dugaan tidak dapat menggantikan dalam bidang ini sebagaimana telah kita sebutkan.
Dan agar dalil penetapan akidah-akidah diketahui dari agama dengan darurat, sehingga kekufuran terjadi ketika menolaknya atau tidak beramal dengannya. Oleh karena itu para ulama memutuskan: bahwa barangsiapa mengingkari sunnah mutawatir yang qath’i dalam dalalah-nya, maka ia telah mengingkari yang diketahui dari agama dengan darurat, dan karena itu dihukumi kafir, karena ia memberikan kepastian dan keyakinan dalam kebenaran penisbatannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan barangsiapa mengingkari sunnah ahad atau mengingkarinya maka ia adalah orang yang bermaksiat dan bukan kafir, karena ia memberikan dugaan yang kuat dalam penisbatannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan tidak ada seorangpun -secara mutlak- dari ahli ilmu yang diakui yang mengatakan bahwa sunnah ahad tidak layak untuk membangun jenis apapun dari hukum-hukum syar’i atasnya selain akidah sebagaimana telah kita sebutkan.
Inilah yang telah diputuskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika beliau menyebutkan dalam kitab (Al-Mustashfa) bahwa khabar ahad tidak dapat menetapkan ushul (pokok-pokok), yakni: pokok-pokok agama dan akidah-akidahnya. Maka ini tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil qath’i (pasti) dari Al-Quran atau Sunnah mutawatir.
Adapun selain itu, maka Sunnah ahad dianggap sebagai sumber legislasi dalam semua muamalat tanpa kecuali, termasuk di dalamnya masalah-masalah siyasah syar’iyyah (politik syariah) atau hukum-hukum politik dan konstitusional.
Berdasarkan hal tersebut: maka tidaklah benar apa yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Hamid Mutawalli berupa pemahaman yang keliru terhadap ungkapan Al-Ghazali seakan-akan bermakna: bahwa khabar ahad tidak dapat menetapkan ushul, yakni: pokok-pokok hukum syariah secara mutlak, yaitu: sumber-sumbernya. Maka Sunnah ahad -dengan demikian- menurut logika Dr. Mutawalli bukanlah termasuk di antara sumber-sumber hukum syariah. Dan tidak membantunya dalam hal itu apa yang ia nukil dari Al-Ghazali yang ia salah pahami ungkapannya, pertama, dan kedua: karena Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya yang berbeda seringkali berdalil dengan Sunnah ahad, dan terkadang ia berdalil dengan hadits-hadits dhaif dari Sunnah ini, dan mendahulukannya daripada mengambil pendapat (ra’yu).
Dan juga tidaklah benar apa yang dikemukakan oleh Dr. Mutawalli tentang: bahwa tidak boleh beramal dengan Sunnah ahad dalam ranah hukum konstitusional; karena Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak mengambil hadits dalam ranah legislasi, meskipun legislasi biasa yakni non-konstitusional, jika perawi hadits adalah seorang sahabat saja. Bahkan masing-masing dari keduanya meminta demi keyakinan akan kebenaran hadits, saksi yang menyertai perawi. Oleh karena itu, adalah wajar dan perlu bahwa kita mengambil sikap kehati-hatian dan keyakinan dalam legislasi konstitusional yang jauh lebih besar daripada yang kita ambil dalam legislasi biasa, terlebih setelah berlalu banyak abad dari masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan masuknya banyak kebohongan dan penyimpangan dalam periwayatan hadits. Ini adalah perkataan Dr. Abdul Hamid dalam bukunya (Mabadi Nizham Al-Hukm fi Al-Islam) hal. 190 dan seterusnya.
Ia menyandarkan hal itu pada bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar -ridhwanullahu tabaraka wa ta’ala anhuma- tidak mengambil hadits jika disampaikan oleh seorang sahabat saja, bahkan mereka menanyakan kepada orang-orang lain, mungkin mereka mendengar hadits ini. Maka ia berkata: selama Abu Bakar dan Umar tidak bergantung dan tidak mengambil hadits ini kecuali dengan merujuk dan bertanya tentang sejauh mana kebenaran hadits kepada selain yang mengatakannya, ia berkata: dengan qiyas (analogi) terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar dan apa yang dilakukan Umar, sepatutnya kita tidak mengambil Sunnah ahad dalam perkara-perkara penting, seperti hukum-hukum konstitusional dalam pemerintahan.
Tanggapan terhadap hal itu, kami katakan: apa yang dikemukakan oleh penulis yang terhormat itu tidak benar; karena yang diketahui tentang para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa mereka: jika hadits telah tetap pada mereka maka mereka berdalil dengannya, dan mereka beramal dengan khabar wahid (periwayat tunggal), dan hal itu mutawatir pada mereka. Dan hadits-hadits yang mereka tolak atau mereka tahan, maka itu karena hal-hal yang mengharuskan demikian berupa adanya pertentangan atau hilangnya syarat, bukan karena mereka menolak beramal dengan Sunnah ahad pada asalnya sebagaimana yang salah dipahami oleh penulis tersebut yang membayangkan bahwa hadits ahad adalah yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Dan ini tentu saja menunjukkan kebodohan yang memalukan tentang Sunnah ahad yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat mutawatir atau syuhrah (kemashuran) menurut istilah Hanafiyah.
Bagaimanapun: jelas dari ini bahwa Doktor tidak memahami makna Sunnah ahad; oleh karena itu ia memandang bahwa terkadang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika salah seorang sahabat mengabarkan kepada mereka sebuah hadits, mereka tidak yakin dengan itu dan bertanya kepada para sahabat lainnya: apakah kalian mendengar hadits ini atau tidak? Yang dilakukan oleh kedua imam mulia itu hanyalah karena adanya pertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits ini, mereka hanya ingin memastikan hal itu, dan ingin menghilangkan pertentangan ini. Namun ketika mereka memastikan kebenaran hadits ini, bukan berarti: mereka tidak mengambil Sunnah ahad. Mereka mengambil Sunnah ahad, dan Sunnah ahad tidak mesti diriwayatkan oleh satu orang sebagaimana dipahami oleh Dr. Abdul Hamid Mutawalli, tetapi bisa jadi satu atau dua atau tiga orang. Yang penting: mereka tidak mencapai derajat mutawatir yang mustahil atau mustahil menurut adat atau adat memustahilkan kesepakatan mereka untuk berdusta.
Dan juga tidaklah benar apa yang dikemukakan oleh Dr. Mutawalli tentang tidak berdalil dengan Sunnah ahad dalam ranah hukum konstitusional; karena Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak menerima hadits-hadits ahad, karena beliau tidak menerima kecuali hadits-hadits masyhur, dan itu karena menyebarnya pemalsuan dalam hadits. Artinya: Imam atau Dr. Mutawalli berkata: kita tidak mengambil Sunnah ahad dan ia berdalil dengan hal itu bahwa Imam Abu Hanifah tidak menerima hadits-hadits ahad. Karena Imam Abu Hanifah tidak mengambil hadits-hadits ahad -Dr. Mutawalli mengatakan ini- ia berkata: selama Imam Abu Hanifah tidak menerima hadits-hadits ahad.
Maka kami juga berkata: dengan qiyas terhadap apa yang dikemukakan beliau, kita juga tidak mengambil hadits-hadits ini. Kami katakan: pertama: nukilan ini tentang Imam Abu Hanifah, yaitu: bahwa beliau tidak menerima hadits-hadits ahad, adalah nukilan yang aneh tentang Abu Hanifah yang tidak dikatakan oleh seorang ulama pun. Karena yang diputuskan oleh para ulama dalam bidang berdalil dengan khabar wahid adalah sebagai berikut:
Kaum Khawarij dan Muktazilah berpendapat tidak berdalil dengan khabar wahid; karena tidak memberikan pengetahuan yang pasti. Dan Dawud Adz-Dzahiri berpendapat mengambil hadits-hadits ahad dan bahwa ia memberikan ilmu dan amal sekaligus. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm dan ia sangat membelanya dalam bukunya (Al-Ahkam). Ini juga dinukil dari: Malik dan Ahmad, dan ini adalah pendapat banyak ulama hadits; karena hukum yang mewajibkan beramal dengannya mewajibkan ilmu yang yakin. Dan jumhur fuqaha dari para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat: wajib beramal dengan khabar wahid meskipun hanya memberikan dzhan rajih (dugaan kuat) saja, karena tidak ada keharusan antara wajib beramal dan memberikan ilmu, dan karena dzhan rajih sudah cukup dalam perkara-perkara praktis.
Maka dengan demikian: kita menemukan -maka- kaum Ahnaf bersama jumhur fuqaha yang mengatakan wajib beramal dengan khabar wahid. Artinya: nukilan Dr. Abdul Hamid Mutawalli dari Imam Abu Hanifah, bahwa beliau tidak mengambil Sunnah ahad, nukilan ini diragukan dan tidak benar.
Demikian pula yang dinukil dari Hanafiyah dalam kitab-kitab mereka: bahwa mereka menjadikan Sunnah dalam urutan kedua setelah Al-Quran, maka ia adalah sumber kedua legislasi, baik mutawatir, masyhur, atau ahad jika datang sesuai syarat-syarat mereka. Dan mereka tidak menggunakan ra’yu dan qiyas kecuali jika tidak menemukan hadits dalam masalah tersebut. Bahkan yang diketahui dari Hanafiyah adalah bahwa mereka mendahulukan hadits dhaif daripada ra’yu dan qiyas, dan juga mereka mendahulkan perkataan sahabat daripada ra’yu dan qiyas. Maka apakah disangka terhadap orang yang ushul-ushulnya dalam istinbath hukum seperti ini: bahwa ia menolak Sunnah ahad secara keseluruhan sebagaimana yang salah dipahami oleh Dr. Mutawalli? Ini adalah perkara yang tidak benar.
Dan ada syubhat (keraguan) terakhir yang disebutkan oleh Dr. Abdul Hamid Mutawalli, yaitu: bahwa Shahih Bukhari telah mengalami kritik dari sebagian ulama hadits, seperti Imam Ahmad yang tidak memberikan kesahihan terhadap empat hadits dari yang dikumpulkan oleh Bukhari. Demikian juga para ulama lain mengkritik seratus sepuluh hadits Bukhari. Dan Imam Muslim tidak menyetujui Bukhari atas semua yang ia kumpulkan dari hadits-hadits, bahkan berbeda pendapat dengannya. Dan para ulama berpendapat: bahwa Shahih Bukhari hanya memberikan dzhan saja.
Dan ini adalah perkataan yang mengandung generalisasi yang tidak sesuai dengan sifat penelitian ilmiah, apalagi sebagiannya sama sekali tidak benar. Penjelasannya dari dua sisi: Pertama: yang pasti adalah bahwa hadits-hadits Bukhari shahih, dan di antaranya ada yang mutawatir, masyhur, dan Sunnah ahad. Dan jika sebagian ulama mengkritik Bukhari dalam apa yang ia kumpulkan dari sebagian hadits, maka ini tidak berarti mencela kesahihan hadits-hadits ini, tetapi maknanya: bahwa mereka berbeda pendapat dalam sejauh mana penilaian mereka terhadap Sunnah dan sejauh mana pendapat mereka tentang para perawi sanad ini. Maka ini adalah perkara yang kembali kepada perbedaan standar kedhabitan dan keshahihan yang bervariasi di kalangan ulama hadits. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bukhari misalnya: berbeda dari yang ditetapkan oleh Muslim. Dan ini adalah perkara-perkara yang tidak mengurangi nilai Shahih Bukhari atau Shahih Muslim. Bahkan para ulama telah memutuskan bahwa derajat tertinggi keshahihan dalam hadits adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
Dan Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi telah mengumpulkan dari hadits-hadits ini apa yang ia namakan dengan kitab (Al-Lu’lu wal Marjan fima Ittafaqa alaihi asy-Syaikhani). Maka hadits-hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu ada pada derajat keshahihan tertinggi, kemudian yang diriwayatkan sendirian oleh Bukhari, kemudian yang diriwayatkan sendirian oleh Muslim, kemudian yang sesuai syarat keduanya, namun tidak mereka keluarkan.
Kedua: mengenai masalah dzhan dan qath’i dalam Shahih Bukhari, maka ini bukan hukum yang disampaikan begitu saja secara sembarangan; karena yang diputuskan oleh para ahli ilmu bahwa yang memberikan kepastian dari Sunnah adalah hadits mutawatir, baik dalam Shahih Bukhari atau selainnya. Adapun hadits masyhur maka ia memberikan dzhan yang mendekati ketenteraman dan tidak naik ke tingkat keyakinan yang diberikan oleh hadits mutawatir. Adapun yang memberikan dzhan adalah Sunnah ahad, baik dalam (Shahih Bukhari) atau selainnya. Dan bagaimanapun ia cukup untuk wajib beramal selain dalam bidang akidah; karena tidak ada keharusan sebagaimana kami sebutkan antara wajib beramal dan wajib beramal, bahkan cukup dzhan akan kejujuran perawi sehingga terrajihkan adanya perintah Allah Ta’ala dan perintah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam; maka menjadi kehati-hatian beramal dengan yang rajih.
Ijma’
Dan kita berpindah sekarang kepada sumber lain dari sumber-sumber hukum konstitusional dalam sistem Islam, yaitu Ijma:
Ijma dalam bahasa adalah: kesepakatan. Dikatakan: jamaah sepakat tentang sesuatu jika mereka sepakat tentangnya. Dan digunakan dengan makna kesungguhan tekad. Dikatakan: fulan mengumpulkan pendapatnya tentang sesuatu jika ia menetapkan tekadnya. Allah Ta’ala berfirman: “Maka bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu” (Yunus: 71).
Dan makna Ijma dalam syariat: kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa dari masa-masa setelah wafat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariat. Dan para ulama yang kesepakatan mereka dianggap dalam Ijma adalah para mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mengistinbathkan hukum dari sumber-sumbernya.
Oleh karena itu: maka tidak masuk dalam hal ini kesepakatan orang awam; karena mereka bukan dari ahli ijtihad. Dan ahli ijtihad diketahui dan terkenal di setiap masa, sehingga dapat diketahui pendapat-pendapat mereka dari berbagai penjuru. Dan tidak mungkin terjadi Ijma dalam kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena jika mereka menyetujui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
Maka hujjah ada pada perkataan dan perbuatan beliau alaihish-shalatu was-salam dan itu termasuk Sunnah. Dan jika mereka menyelisihi beliau, maka tidak ada pertimbangan bagi penyelisihan mereka selama shallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka menjelaskan dari Allah Ta’ala apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan harus kesepakatan para mujtahid tentang hukum dari hukum-hukum syariah untuk mengeluarkan hukum-hukum akal, bahasa, atau adat, maka kesepakatan tentangnya tidak dinamakan Ijma.
Dan di sini muncul pertanyaan: Apakah mungkin terjadi Ijma di zaman ini?
Sebagian ulama berpendapat mustahil terjadi Ijma, dalam arti: kesepakatan semua mujtahid dalam suatu masa dari masa-masa tentang hukum dari hukum-hukum; mengingat berpencarnya para mujtahid di berbagai negeri, dan tidak bertemunya para fuqaha sehingga menjadikan sulit untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka, dan tidak diketahuinya mujtahid dari bukan mujtahid; mengingat terjadinya perbedaan di antara fuqaha ahli setiap negeri dari kota-kota Islam. Oleh karena itu mustahil semua mujtahid sepakat tentang hukum syariah yang diperselisihkan. Namun jumhur ulama berpendapat: bahwa Ijma mungkin secara akal, dan keberadaannya tergambar; karena umat sepakat tentang wajibnya shalat lima waktu, dan seluruh rukun Islam. Dan bagaimana kita mencegah tergambarnya Ijma, sedangkan seluruh umat terikat dengan nash-nash, dan dalil-dalil qath’i yang terancam hukuman dengan menyelisihinya. Dan sebagaimana tidak mustahil kesepakatan mereka tentang makan dan minum, tidak mustahil kesepakatan mereka tentang perkara dari perkara agama.
Dan jika diperbolehkan persepakatan orang-orang Yahudi dengan jumlah mereka yang banyak atas kebatilan, maka mengapa tidak diperbolehkan persepakatan ahli kebenaran atas kebenaran? Yaitu: atas kebenaran. Dan ijma’ telah terjadi secara nyata, dan terwujud pada masa sahabat, seperti ijma’ mereka bahwa: nenek mendapat seperenam, yang diambil sendiri oleh satu orang nenek dan diambil bersama-sama jika lebih dari satu nenek, dan ijma’ mereka tentang tidak bolehnya menikahi seorang wanita bersama bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu, dan ijma’ mereka bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah menggantikan kedudukan saudara sekandung jika tidak ada saudara sekandung, dan ijma’ mereka tentang batalnya pernikahan wanita muslimah dengan non-muslim dan lain-lain yang panjang jika dihitung dan dirinci. Dalam hal ini dapat dirujuk Syaikh Abu Zahrah dalam (Ushul Fiqh) halaman 159 dan seterusnya.
Dan yang kami lihat dalam hal ini: bahwa terbentuknya ijma’ menurut pandangan ushul sangat sulit terwujud dalam kenyataan. Jika mungkin ijma’ ini terwujud pada masa sahabat karena jumlah mereka yang sedikit, berkumpulnya mereka di Madinah, saling mengenal, dan ketenaran mereka, yang memudahkan untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka, dan Umar radiallahuanhu pernah melarang para sahabat senior dan ahli pendapat untuk meninggalkan Madinah menuju negeri-negeri yang telah ditaklukkan kecuali dalam keadaan darurat.
Kami katakan: jika ini mungkin terjadi pada masa sahabat, maka hal itu tidak mungkin pada masa tabiin dan sesudah mereka setelah para ulama dan mujtahid tersebar di berbagai negeri dan wilayah yang telah ditaklukkan dan menetap di sana, dengan jumlah mereka yang banyak, dan masing-masing mandiri dengan ijtihadnya di negerinya, dan inilah yang membuat ijtihad berciri individual.
Dari sinilah terbentuknya ijma’ menjadi sulit, dan tidak mudah terjadi, dan inilah yang membuat Ibnu Hambal dan Asy-Syafi’i juga lebih memilih untuk menggunakan ungkapan daripada ijma’, yaitu mengatakan: kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Maksudnya: Imam Asy-Syafi’i dan Ibnu Hambal lebih memilih mengungkapkan ijma’ dengan perkataan mereka: kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, tetapi mereka tidak mengungkapkannya dengan kata ijma’, mengapa? Seolah-olah mereka berpendapat: ijma’ tidak terwujud.
Dan bahwa orang yang mengklaim adanya ijma’ mereka menganggapnya pendusta, karena bisa jadi orang-orang berbeda pendapat. Mungkin bermanfaat jika kita menyerukan bersama sebagian pihak dalam hal ini pentingnya memberikan perhatian kepada majelis-majelis fiqh pada masa ini yang mengumpulkan semua fuqaha di dunia Islam, di mana majelis-majelis ini memiliki tempat-tempat yang dikenal, tersedia kesempatan yang tepat dan kemungkinan yang diperlukan, mudah berkomunikasi di antara mereka, dan berkumpul pada waktu-waktu tertentu secara berkala, kemudian disodorkan kepada mereka masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa baru untuk dipelajari, dan menampakkan hukum syariat di dalamnya, kemudian dipublikasikan hukum-hukum ini melalui radio atau majalah atau buku-buku berkala; agar orang-orang mengetahuinya dan ahli ilmu di antara mereka menyampaikan pendapat mereka di dalamnya; karena kemungkinan tidak semua fuqaha dapat bergabung dengan majelis-majelis ini, kemudian majelis-majelis fiqh memperhatikan berbagai pendapat yang berbeda dari anggota-anggota resminya, dan dari mereka yang di luarnya, dan jika pendapat-pendapat majelis-majelis ini sepakat atas suatu hukum -setelah itu- maka hal ini bisa menjadi contoh dari apa yang dapat disebut ijtihad kolektif yang mendekati ijma’ yang dibicarakan oleh para ushuliyyun. Dan sesungguhnya kita menemukan dalam Hai’ah Kibar Al-Ulama di Mesir sebelum dibubarkan dan dalam Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyyah sekarang apa yang mewakili inti untuk mewujudkan gagasan ini yang kita serukan.
Kehujjahan Ijma’:
Dalil kehujjahan ijma’ adalah seperti firman Allah Tabaraka Wata’ala: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisa: 115) Ayat ini mewajibkan mengikuti jalan orang-orang mukmin, dan mengharamkan menyelisihi mereka. Dan tidak dikatakan dalam hal ini: bahwa sesungguhnya ancaman ditujukan kepada orang yang menentang Rasul, dan meninggalkan mengikuti jalan orang-orang mukmin bersamanya, maka orang yang meninggalkan salah satu dari keduanya secara terpisah tidak mendapat ancaman. Tidak dikatakan demikian; karena ancaman atas dua hal menunjukkan bahwa ancaman itu berlaku untuk masing-masing dari keduanya secara terpisah atau keduanya secara bersama-sama, dan tidak boleh mengkhususkan ancaman pada salah satunya tanpa yang lain.
Dan dalam Sunnah ada yang menjadi bukti kehujjahan ijma’ seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan” dan dalam riwayat: “Allah tidak akan mengumpulkan umat ini atas kesalahan” dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk maka ia buruk di sisi Allah” dan beliau juga bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya” dan beliau juga bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah maka ia mati dengan kematian jahiliyyah”.
Maka hadits-hadits ini senantiasa jelas dan masyhur di kalangan sahabat dan tabiin, tidak ada seorang pun dari salaf dan khalaf yang menolaknya. Dan meskipun hadits-hadits tersebut secara individual tidak mutawatir, namun dengan keseluruhannya memberi kita pengetahuan yang pasti: bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengagungkan kedudukan umat ini dan menjelaskan perlindungannya dari kesalahan. Dan dari sisi lain bahwa hadits-hadits ini senantiasa masyhur di kalangan sahabat dan tabiin, mereka berpegang teguh dengannya dalam menetapkan ijma’, dan tidak tampak ada perbedaan pendapat dari siapa pun.
Mungkin muncul pertanyaan di sini, yaitu: apakah ijma’ menjadi sumber hukum-hukum konstitusional dan politik? Sesungguhnya jawaban atas pertanyaan ini hampir terlihat jelas tidak ada kesulitan di dalamnya, jika kita mengetahui -sebagaimana kita katakan berkali-kali-: bahwa hukum-hukum ini adalah bagian dari hukum-hukum syariat secara umum, dan sumber-sumber syariat yang di antaranya ijma’ digali darinya hukum-hukum syariat secara mutlak, baik hukum-hukum ini termasuk undang-undang biasa dengan bahasa ahli hukum maupun termasuk undang-undang politik dan konstitusional. Maka tidak ada dalam syariat ruang untuk mengklasifikasikan hukum-hukum seperti yang ditetapkan dalam hukum menjadi: hukum-hukum hukum privat yang mengatur hubungan-hubungan individu di antara mereka, dan hukum-hukum hukum publik yang mengatur hubungan individu dengan negara yang memerintah mereka. Dan tentu saja jenis yang terakhir memiliki beberapa kepentingan dari segi urgensi masalah-masalah yang ditanganinya, dan inilah yang menyebabkan sebagian orang mengatakan bahwa ijma’ tidak menjadi sumber dari sumber-sumber yang digali darinya hukum-hukum konstitusional dan politik.
Tetapi ijma’ dengan kedudukannya sebagai sumber syar’i dapat digunakan untuk menetapkan semua hukum syariat dengannya. Dan para sahabat telah berijma’ setelah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang wajibnya imamah, dan itu adalah masalah dari kekhususan paling khusus dalam hukum konstitusional dan politik. Maka Ibnu Khaldun menyebutkan dalam (Al-Muqaddimah) bahwa menegakkan imam adalah wajib, telah diketahui wajibnya dalam syariat dengan ijma’ sahabat dan tabiin; karena para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam segera membaiat Abu Bakar radiallahuanhu dan menyerahkan pengelolaan kepada beliau dalam urusan-urusan mereka, demikian juga di setiap masa setelah itu, dan tidak dibiarkan manusia dalam keadaan kacau di suatu masa pun, dan hal itu menjadi ijma’ tentang wajibnya menegakkan imam.
Dan meskipun kita menyetujui sulitnya terbentuknya ijma’ setelah masa sahabat -sebagaimana kita sebutkan sebelumnya- para ulama menyebutkan bahwa imamah selama diperoleh dengan pemilihan dan baiat; maka ia tidak memerlukan ijma’ dari semua ahlu al-halli wal-aqdi, bahkan cukup dalam hal itu pendapat satu atau dua orang dari mereka, seperti pengangkatan Umar untuk Abu Bakar, dan pengangkatan Abdurrahman bin Auf untuk Utsman. Sebagaimana para sahabat berijma’ tentang baiat sebagai cara untuk menyerahkan kekuasaan kepada kepala negara, seperti yang terjadi dalam membaiat Abu Bakar. Dan mereka berijma’ juga untuk memerangi orang-orang murtad pada masa Abu Bakar. Dan semua ini adalah masalah-masalah politik dan konstitusional dengan bahasa ahli hukum, atau dari masalah-masalah siyasah syar’iyyah dengan bahasa fuqaha kaum muslimin. Semua ini adalah dalil bahwa ijma’ adalah sumber dari sumber-sumber hukum politik dalam negara Islam.
Demikian dan dengan pertolongan Allah, kita cukupkan sampai di sini, dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
3 – Lanjutan: Sumber-sumber Hukum Politik dalam Sistem Islam dan Kaidah-kaidah Sistem Politik dalam Islam (1)
Qiyas
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, yaitu junjungan kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Pada kuliah sebelumnya kita telah memulai pembahasan tentang sumber-sumber hukum politik dalam negara Islam dan kita sebutkan di antaranya: Al-Qur’an Al-Karim sebagai sumber dari sumber-sumber ini, dan Sunnah Nabawiyyah yang mulia sebagai sumber dari sumber-sumber ini, dan kita telah membahas tentang ijma’.
Kemudian kita membahas setelah itu tentang: sumber lain dari sumber-sumber yang digali darinya hukum-hukum politik dalam negara Islam, maka kita membahas tentang ijtihad dengan ra’yu sebagai sumber hukum-hukum konstitusional dan politik.
Dan yang kami maksud dengan ungkapan ijtihad dengan ra’yu dalam hal ini: apa yang lebih umum dari qiyas, sehingga mencakupnya dan mencakup selain qiyas seperti istihsan, mashalih mursalah, dan ‘urf. Oleh karena itu kita akan mendefinisikan masing-masing dari sumber-sumber ini kemudian kita jelaskan apakah layak menjadi sumber hukum-hukum politik atau tidak?
Pertama Qiyas:
Qiyas menurut bahasa adalah takdir (pengukuran). Adapun qiyas menurut syariat: yaitu membawa cabang kepada asal dalam hukum dengan adanya persamaan di antara keduanya. Dan dikatakan: yaitu menghukumi cabang dengan seperti apa yang engkau hukumi pada asal; karena keduanya sama dalam ‘illat yang menuntut hal itu pada asal. Dan dikatakan: yaitu membawa sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam menetapkan hukum untuk keduanya atau meniadakannya dari keduanya dengan adanya persamaan di antara keduanya dari penetapan hukum atau sifat untuk keduanya atau meniadakannya dari keduanya.
Dan makna-makna batasan dan definisi-definisi ini berdekatan, maka semuanya adalah ungkapan tentang penjelasan hukum suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya, dengan menggabungkannya pada perkara yang diketahui hukumnya dengan adanya nash tentangnya dalam Al-Qur’an atau Sunnah. Maka ia adalah ungkapan tentang menggabungkan perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan perkara lain yang ada nash tentang hukumnya karena kesamaan di antara keduanya dalam ‘illat hukum.
Dan rukun qiyas ada empat, yaitu: al-maqis (yang diqiyaskan) yaitu: cabang yang tidak ada nash tentang hukumnya, dan al-maqis ‘alaihi yaitu: asal yang ada nash tentang hukumnya, dan hukum asal yang disebutkan nashnya.
Dan kita bisa memberikan contoh yang menjelaskan hal itu: kita punya khamr -sebagai contoh- yang disebutkan nashnya dalam Al-Qur’an Al-Karim tentang keharamannya, dalam firman Allah Tabaraka Wata’ala: “Sesungguhnya khamr, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah: 90) Maka ayat ini menyebutkan tentang haramnya khamr. Jika kita punya nabidz yang dibuat dari kurma -sebagai contoh- hingga menjadi memabukkan, yaitu: jika manusia meminumnya maka ia mabuk, maka apa hukum nabidz ini? Nabidz ini tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur’an atau Sunnah secara tegas, tetapi yang disebutkan secara tegas adalah hukum khamr.
Maka dalam hal ini melalui qiyas kita mengqiyaskan nabidz pada khamr, dan hukum khamr adalah haram, maka kita berikan kepada nabidz keharaman jika ia menjadi memabukkan, dan ‘illat di antara keduanya adalah memabukkan. Maka seolah-olah kita punya asal yaitu khamr, dan cabang yaitu nabidz, dan hukum asal yaitu haram, dan ‘illat yaitu memabukkan yang terwujud dalam al-maqis dan al-maqis ‘alaihi atau dalam asal dan cabang.
Inilah makna qiyas, dan oleh karena itu -sebagaimana kita katakan-: ia memiliki empat rukun yaitu al-maqis, dan al-maqis ‘alaihi yaitu asal yang ada nash tentang hukumnya, dan hukum asal yang disebutkan nashnya, dan ‘illat.
Dan ‘illat adalah apa yang dibangun di atasnya hukum pada asal dan terwujud dalam cabang. Dan ia adalah dalil syar’i, yaitu: bahwa qiyas adalah dalil syar’i yang mu’tabar menurut mayoritas ulama fiqh Islam; karena nash-nash itu terbatas, sedangkan kejadian-kejadian tidak terbatas, dan peristiwa-peristiwa manusia selalu baru, maka oleh karena itu tidak mungkin dapat mengabaikan qiyas sebagai sumber syar’i yang memberikan kepada hukum-hukum baru hukum syar’inya, dan menempatkannya pada kedudukan yang layak melalui ijtihad dengan ra’yu yang menggabungkan cabang-cabang kepada pokok-pokoknya yang bersifat kully.
Oleh karena itu Umar bin Al-Khaththab berkata kepada Abu Musa Al-Asy’ari: Pahamilah, pahamilah apa yang ganjil di dadamu dari apa yang tidak ada di kitab dan tidak di sunnah, kemudian ketahuilah hal-hal yang serupa dan contoh-contohnya, lalu qiyaskanlah perkara-perkara pada saat itu dengan yang serupa dengannya, dan pilih yang paling dekat kepada Allah dan paling serupa dengan kebenaran.
Dan qiyas adalah sumber keempat dari sumber-sumber syariat yang mulia. Sumber pertama adalah Al-Qur’an dan Sunnah dan ijma’, kemudian datang setelah itu qiyas.
Dan karena qiyas adalah sumber ijtihadiyyah sebagaimana kita sebutkan, maka ia tidak dianggap mengikat secara khusus menurut mujtahid-mujtahid lainnya; karena ‘illat yang menjadi tempat bergantung qiyas dan berpusat padanya tidak sama menurut pandangan semua mujtahid; oleh karena itu perbedaan dalam ‘illat adalah sebab perbedaan mujtahid dalam pendapat-pendapat fiqh yang mereka keluarkan.
Maka qiyas dengan demikian adalah sumber tafsiri yang berbeda menurut mujtahid-mujtahid.
Tetapi apakah qiyas dianggap sebagai sumber hukum-hukum politik dan konstitusional dalam syariat Islam?
Kita katakan qiyas -dengan kedudukannya sebagai sumber syar’i yang digunakan oleh mujtahid ketika ingin menggabungkan cabang yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan asal yang ada nash tentangnya atau tentang hukumnya karena kesamaan di antara keduanya dalam ‘illat hukum menurut mujtahid- maka dengan demikian ia layak menjadi sumber untuk semua hukum-hukum syariat, baik konstitusional maupun non-konstitusional.
Istihsan
Kedua: Istihsan:
Dan istihsan sebagai sumber hukum-hukum politik dan konstitusional dalam sistem Islam adalah dari sumber-sumber tabi’iyyah (tambahan) bagi syariat Islam, dan ia adalah jenis dari qiyas, dan kadang-kadang disebut qiyas khafiy (qiyas tersembunyi).
Dan Abu Al-Hasan Al-Karkhi -dari kalangan Hanafiyyah- mendefinisikannya, ia berkata: yaitu bahwa mujtahid berpaling dari menghukumi suatu masalah dengan seperti apa yang ia hukumi dalam masalah-masalah yang serupa dengannya karena adanya alasan yang lebih kuat yang menuntut berpaling dari yang pertama.
Maka hukum dalam istihsan datang bertentangan dengan kaidah yang berlaku umum karena ada alasan yang membuat keluar dari kaidah lebih dekat kepada syariat daripada berpegang teguh pada kaidah, maka menyandarkan kepadanya lebih kuat sebagai dalil dalam masalah tersebut daripada qiyas.
Dan istihsan telah diingkari oleh sebagian ulama seperti Imam Asy-Syafi’i, dan ia berkata: barangsiapa yang beristihsan maka ia telah membuat syariat, yaitu: menjadikan dirinya pembuat syariat tanpa Allah. Maka Asy-Syafi’i menganggapnya sebagai jenis pembuatan syariat dengan hawa nafsu dan pendapat tanpa dalil. Dan tidak diragukan bahwa apa yang demikian itu tercela menurut semua pihak. Adapun apa yang bukan demikian -tetapi alasan berpaling dari kaidah lebih kuat daripada berpegang teguh padanya- maka itu adalah ijtihad yang terpuji tidak ada keharaman di dalamnya.
Dan istihsan terbagi menjadi dua bagian:
Istihsan qiyasiy, maksudnya: bahwa mujtahid berpaling dari tuntutan qiyas zhahir kepada qiyas khafiy yang dituntut oleh maslahat.
Dan juga: istihsan karena darurat, dengan pengertian: menyalahi hukum qiyas karena darurat atau kemaslahatan untuk menolak kesulitan dan memenuhi kebutuhan, dan hal ini terjadi ketika penerapan kaidah-kaidah qiyas umum akan menyebabkan kesulitan dan kesusahan.
Contohnya adalah bahwa orang yang diamanati atau penyimpan barang titipan tidak menanggung kerusakan barang yang ada di tangannya tanpa kelalaian, begitu pula orang yang meminjam, penyewa, dan pekerja. Namun Hanafiyah membedakan antara pekerja khusus dan pekerja umum. Pekerja khusus adalah yang bekerja pada individu tertentu, sedangkan pekerja umum adalah yang bekerja pada sejumlah individu.
Kami katakan bahwa Hanafiyah membedakan antara pekerja khusus dan pekerja umum, dan mereka menjadikan pekerja umum seperti tukang celup, tukang roti, penjahit dan semacamnya, mereka menjadikannya menanggung apa yang ada di tangannya. Mengapa?
Meskipun hal itu bertentangan dengan kaidah yang mengatakan: bahwa penyewa dan pekerja itu adalah orang yang dipercaya, mereka menyalahi kaidah ini dengan istihsan; agar pekerja ini tidak mengabaikan pekerjaannya dan hal itu menyebabkan rusaknya barang dagangan, kecuali jika kerusakan atau kehilangan itu karena sesuatu yang tidak ada campur tangannya di dalamnya dan tidak mungkin baginya untuk berhati-hati darinya seperti kebakaran dan semacamnya.
Dan jika telah tetap bagi kita bahwa istihsan adalah sumber syariat yang diakui berdasarkan pengertian yang telah kita kemukakan, maka ia mengandung jenis kemaslahatan; karena seringkali penerapan kaidah-kaidah qiyas umum menyebabkan terabaikannya sebagian kemaslahatan atau menyalahi sebagian prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan. Maka pada saat itu istihsan menjadi sangat penting untuk keluar dari kebuntuan ini; untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat dan menghormati kemaslahatan-kemaslahatan yang dipelihara, tanpa perbedaan dalam hal ini antara hukum yang diambil dengan istihsan termasuk dalam hukum-hukum konstitusional dan politik atau yang lainnya; karena syariat sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya tidak mengenal perbedaan seperti ini antara satu hukum syariat dengan hukum syariat lainnya, dan selama sumbernya sah sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah dan darinya dapat diambil hukum, maka sama saja dalam hal itu semua hukum. Bahkan kita perhatikan: bahwa mengandalkan istihsan dalam bidang-bidang politik mungkin lebih sesuai dengan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan yang berubah yang berbeda dengan perbedaan zaman, dan kadang-kadang penerapan kaidah-kaidah qiyas menyebabkan terabaikannya sebagian kemaslahatan-kemaslahatan yang diakui ini, sebagaimana disebutkan.
Maslahah Mursalah
Dan di antara sumber-sumber ini -juga yang bergantung pada pendapat- dari sumber-sumber ini adalah maslahah mursalah.
Dan maslahah mursalah sebagai sumber hukum-hukum politik dan konstitusional dalam sistem Islam.
Pertama: Maslahah adalah ungkapan tentang mendatangkan manfaat atau menolak kerusakan, dan ia terbagi menjadi tiga bagian: bagian yang syariat menyaksikan pengakuannya, dan dikenal dengan maslahah mu’tabarah (kemaslahatan yang diakui), yaitu ungkapan tentang pengambilan hukum dari yang dapat dipahami dari nash atau ijma’. Bagian yang syariat menyaksikan kebatalannya, dan inilah yang dikenal dengan maslahah mulghah (kemaslahatan yang dibatalkan), seperti mewajibkan puasa karena bersetubuh di bulan Ramadan bagi raja-raja dan penguasa; karena memerdekakan budak itu mudah bagi mereka, sehingga mereka tidak akan jera dengannya, padahal kafarat itu ditetapkan untuk membuat jera. Maka ini adalah kemaslahatan yang batil; karena menyalahi nash yang tegas. Artinya: kemaslahatan ini -mereka yang mengatakan demikian atau sebagian dari mereka yang mengatakan demikian- melihat bahwa jika seseorang itu kaya dan menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan, mereka berkata: ia wajib mengqadha dan membayar kafarat, dan kafarat di sini berjenjang. Kafarat dimulai dengan memerdekakan budak. Maka sebagian fuqaha berkata: jika kita mewajibkan orang kaya ini memerdekakan budak, sementara ia memiliki banyak budak, maka ia tidak akan jera dari ini. Oleh karena itu mereka berkata: kemaslahatan menuntut agar kita mewajibkannya berpuasa supaya ia merasakan hukuman lebih dari mewajibkannya memerdekakan budak yang tidak memberatkannya. Kemaslahatan yang mereka lihat ini adalah kemaslahatan yang dibatalkan, tidak diakui oleh pembuat syariat. Mengapa pembuat syariat tidak mengakuinya? Karena bertentangan dengan nash. Nash menjelaskan bahwa yang pertama dari kafarat-kafarat ini adalah memerdekakan budak, dan tidak memandang kepada apakah orang yang melakukan perbuatan yang mewajibkan kafarat -yaitu menyetubuhi istri- pembuat syariat tidak memandang kepada: apakah ia kaya atau miskin. Oleh karena itu kemaslahatan yang dituju oleh para fuqaha ini dianggap kemaslahatan yang dibatalkan, tidak ada pengakuan terhadapnya dalam syariat; karena menyalahi nash.
Adapun bagian ketiga adalah yang tidak ada kesaksian syariat untuk mengakuinya atau membatalkannya, dan inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah (kemaslahatan yang terlepas). Ia adalah jenis kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pembuat syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang menyaksikan pengakuan atau pembatalannya.
Dan yang mengusung bendera jenis kemaslahatan ini adalah Imam Malik rahimahullah Tabaraka wa Ta’ala sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
Dan maslahah mursalah dengan demikian dianggap sebagai sumber dasar dari sumber-sumber kaidah konstitusional secara khusus; karena kebanyakan kaidah-kaidah ini tidak disebutkan dalam nash syariat; maka pintu kemaslahatan terbuka di hadapan mujtahid untuk mengambil apa yang dituntut oleh kemaslahatan ini, dan ini mendekati apa yang dikenal oleh para ahli hukum dengan gagasan hukum alam dan kaidah-kaidah keadilan yang diandalkan oleh para pengulas hukum-hukum positif berkaitan dengan topik-topik yang tidak disebutkan hukumnya.
Dan di antara yang menunjukkan bolehnya mengambil kemaslahatan ini dalam hukum-hukum konstitusional dan politik adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam (Muqaddimah) bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif berdasarkan kemaslahatan, meskipun tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhaahu.
Umar bin Khattab melakukan itu yaitu: ia memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Mengapa? Berdasarkan kemaslahatan; karena banyaknya kesibukan imam dalam bidang eksekutif yang dengannya ia tidak mampu untuk mengadili dan memutuskan dalam perselisihan.
Ibnu Khaldun berkata: Adapun peradilan, maka ia termasuk tugas-tugas yang masuk di bawah khilafah; karena ia adalah jabatan pemisah antara manusia dalam perselisihan untuk menghentikan gugatan dan memutuskan pertengkaran, kecuali bahwa ia dengan hukum-hukum cabang yang diambil dari Kitab dan Sunnah. Maka karena itu ia termasuk tugas-tugas khilafah dan masuk dalam keumumannya. Para khalifah pada awal Islam menanganinya sendiri dan tidak menjadikan peradilan kepada selain mereka. Orang pertama yang menyerahkannya kepada selainnya dan mewakilkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia mengangkat Abu Darda bersamanya di Madinah, mengangkat Syuraih di Bashrah, mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari di Kufah, dan menuliskan untuknya dalam hal itu surat yang terkenal yang menjadi poros hukum-hukum peradilan.
Kemudian Ibnu Khaldun berkata di tempat lain: Bahwa para khalifah menyerahkan peradilan kepada selain mereka, meskipun itu termasuk yang berkaitan dengan mereka karena mereka menjalankan politik umum dan banyaknya kesibukan-kesibukannya seperti jihad, penaklukan, menutup celah, melindungi negeri, dan mereka mengangkat wakil dalam hal itu orang yang menjalankannya untuk meringankan diri mereka. Dan inilah makna perkataan ini yang kami nukil dari Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, sesungguhnya menjelaskan kepada kita: bahwa setelah Umar bin Khattab mensyariatkan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, pemisahan ini berlanjut setelahnya radhiyallahu anhu di negara Islam, dan menjadi ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Umar bin Khattab melakukan itu -sebagaimana telah kami katakan- karena kemaslahatan menuntut demikian.
Maka pemisahan perselisihan antara manusia membutuhkan orang-orang yang khusus, sedangkan khalifah sudah tidak mampu menjalankan tugas-tugas khilafah dan tugas-tugas peradilan. Oleh karena itu Sayyidina Umar mendapati bahwa kemaslahatan menuntut pemisahan antara khilafah dan mengurus pekerjaan-pekerjaan peradilan, dan inilah yang kita ambil dari maslahah mursalah.
Maka mengambil -dengan demikian- dengan maslahah mursalah di dalamnya ada perwujudan kemaslahatan masyarakat Islam, dan ini masuk dalam lingkup hukum-hukum politik.
‘Urf (Kebiasaan)
Juga di antara hal-hal yang dianggap sebagai sumber hukum-hukum politik dan konstitusional adalah ‘urf, dan ‘urf adalah ungkapan tentang: apa yang menjadi kebiasaan manusia dalam suatu perkara, dan dengannya urusan-urusan mereka berjalan lurus, dan ia berbeda dengan adat. Adat lebih umum daripada ‘urf, karena ia digunakan untuk setiap perkara yang berulang yang bersumber dari individu atau dari kelompok, sedangkan ‘urf adalah kebiasaan mayoritas manusia dalam perkataan atau perbuatan. Ia adalah kebiasaan yang umum pada banyak manusia, dan ia adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip fikih Islam ketika tidak ada nash syariat.
Maka yang ditetapkan menurut para ulama terutama Malikiyah dan Hanafiyah: bahwa yang tetap dengan ‘urf seperti yang tetap dengan nash.
Dan Syaikh Abu Zahrah berkata: Dan barangkali maknanya: bahwa yang tetap dengan ‘urf itu tetap dengan dalil yang dapat diandalkan seperti nash, dimana tidak ada nash. Artinya: selama tidak ada nash, dan tidak ada pengakuan terhadap ‘urf jika menyalahi nash dari Kitab atau Sunnah, seperti jika manusia saling menganggap biasa pada sebagian waktu mengonsumsi sebagian yang haram seperti khamar, zina, memakan riba dan semacam itu, maka ini adalah ‘urf yang rusak, pengakuannya menyebabkan pengabaian nash-nash syariat dan mengikuti hawa nafsu, dan itu adalah kerusakan-kerusakan yang tidak datang syariat untuk hal sepertinya selamanya.
Maka berdasarkan ini, ‘urf menjadi dua bagian:
‘Urf shahih (kebiasaan yang benar): tidak bertentangan dengan nash syariat, maka diambil dengannya selama tidak ada nash.
Dan ‘urf fasid (kebiasaan yang rusak): maka tidak boleh ditempuh, dan ia adalah yang menyalahi nash qath’i dari nash-nash syariat Islam.
Dan disyaratkan untuk beramal dengan ‘urf sebagai prinsip syariat ketika tidak ada nash yaitu sebagai berikut:
Bahwa ‘urf itu harus mapan dan umum, artinya: bahwa manusia mengamalkannya dalam kebanyakan keadaan. Jika ‘urf tidak demikian maka ia tidak mapan, dan cukup jika diamalkan oleh mayoritas manusia baik itu ‘urf umum atau khusus.
Syarat kedua dari syarat-syarat beramal dengan ‘urf: bahwa ‘urf itu ada pada waktu lahirnya tindakan-tindakan yang hendak dihukumi dengannya, maka ia harus mendahului atau bersamaan dengannya. Adapun jika ‘urf itu lahir setelah akad atau tindakan, maka dalam keadaan ini tidak boleh mengambil dengannya.
Di antara syarat-syarat lainnya adalah: adat kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan pernyataan yang berlawanan dengannya. Apabila kedua pihak yang melakukan akad menyatakan keinginan mereka untuk melakukan transaksi dengan cara tertentu, maka keinginan mereka tersebut harus dihormati dan didahulukan atas adat kebiasaan, karena akad adalah syariat bagi pihak-pihak yang berakad, dan mereka telah menyatakan keinginan mereka dengan cara tertentu sebagaimana kami sebutkan, sehingga tidak ada pertimbangan terhadap petunjuk (adat) di hadapan pernyataan tegas.
Di antara syarat-syarat lainnya adalah: pelaksanaan adat kebiasaan tidak boleh mengakibatkan pelanggaran terhadap nash yang pasti dalam syariat, karena tidak ada ruang bagi pertentangan antara nash-nash syariat dengan adat kebiasaan. Jika hal itu terjadi, maka adat tersebut dianggap rusak dan tidak dapat diterima.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan dari apa yang telah dijelaskan: bahwa ketika tidak ada nash dalam suatu masalah, maka adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum dalam masalah tersebut dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Oleh karena itu, setiap faqih yang berwenang mengeluarkan fatwa harus memiliki pengetahuan tentang adat kebiasaan agar dapat berfatwa sesuai dengannya jika diperlukan.
Pelajaran: 8 – Kaidah-Kaidah Sistem Politik Islam
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Lanjutan: Sumber-Sumber Hukum Politik dalam Sistem Islam dan Kaidah-Kaidah Sistem Politik dalam Islam (1)
Kaidah-Kaidah Sistem Politik Islam: Pertama – Hakimiyyah (Kedaulatan Hukum) Milik Allah
Setelah selesai membahas tentang sumber-sumber hukum politik dalam sistem Islam atau dalam sistem politik Islam, sekarang kita akan membahas tentang kaidah-kaidah sistem politik Islam.
Sistem politik Islam memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus menjadi pondasinya. Kaidah adalah sesuatu yang tanpanya sesuatu itu tidak akan ada; oleh karena itu, setiap kaidah dari kaidah-kaidah ini harus ada dan terwujud.
Di antara kaidah pertama yang menjadi pondasi sistem politik dalam Islam adalah: kaidah hakimiyyah (kedaulatan hukum) milik Allah.
Di antara hal-hal yang pasti dalam sistem Islam adalah bahwa seluruh alam semesta—beserta siapa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di atasnya—adalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana firman-Nya: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Surah Al-Maidah: Ayat 17). Maha Suci Dia dan Maha Tinggi: “Dan katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya'” (Surah Al-Isra: Sebagian dari Ayat 111).
Jika Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah Pemilik dan tidak ada sekutu bagi-Nya, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dengan apa yang telah Dia syariatkan kepada kita dari agama ini, karena merupakan kontradiksi jika Pemilik tidak mengelola milik-Nya. Maka penetapan hukum (tasyri’), yang merupakan pengelolaan terhadap makhluk sebagai ujian dan cobaan, adalah konsekuensi dari uluhiyyah (sifat ketuhanan) dan kepemilikan. Allah sendirilah yang dalam kerajaan-Nya menghalalkan dan mengharamkan. Kebenaran ini telah ditetapkan oleh seruan tauhid yang disampaikan oleh para rasul ‘alaihimus salam sejak Nabi Adam ‘alaihis salam hingga Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan Aku'” (Surah Al-Anbiya: 25).
Sebagaimana diketahui: sesungguhnya rukun aqidah dalam Islam adalah syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah, yang artinya—sebagaimana telah kami sebutkan—bahwa tidak ada pencipta alam semesta ini—dengan segala yang ada di dalamnya dan siapa yang ada di dalamnya, yang diketahui oleh ilmu kita maupun yang tidak diketahui, tidak ada penciptanya—kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagai cabang dari hal itu: maka tidak ada di alam semesta ini yang wajib disembah dan dipatuh dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala. Pengakuan terhadap kepemilikan Allah atas alam semesta tanpa mengakui bahwa Dia sendirilah yang berhak memiliki otoritas hukum di dalamnya mengandung, sebagaimana telah kami sebutkan, semacam kontradiksi.
Almarhum Ustadz Sayyid Quthb telah mencoba menggambarkan hal itu, ia berkata: Dari sisi kenyataan, kita menemukan bahwa orang-orang musyrik tidak hanya menyekutukan Allah dengan berhala dan patung saja, tetapi mereka juga menyekutukan-Nya dengan jin, malaikat, dan manusia. Mereka menyekutukan manusia hanya dalam hal memberikan hak penetapan hukum bagi masyarakat dan individu, di mana mereka menetapkan aturan-aturan bagi mereka, meletakkan tradisi-tradisi bagi mereka, dan memutuskan perkara di antara mereka dalam persengketaan mereka sesuai dengan adat dan pendapat. Islam menganggap ini sebagai kesyirikan, dan menganggap bahwa penghakiman manusia dalam urusan manusia adalah penguluhanan terhadap mereka dan menjadikan mereka tandingan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang hal itu sebagaimana larangan-Nya bersujud kepada berhala dan patung. Keduanya dalam pandangan Islam adalah sama, yaitu kesyirikan kepada Allah dan menjadikan tandingan selain Allah.
Al-Qur’an Al-Karim telah mencela umat-umat terdahulu karena mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: “Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan” (Surah At-Taubah: 31).
Para mufassir menyebutkan bahwa maknanya adalah: mereka menjadikan pendeta dan rahib sebagai tuhan lalu mereka menaati mereka dalam perintah mereka untuk bermaksiat, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana tuhan-tuhan ditaati dalam perintah-perintah mereka.
Di zaman modern, kita menemukan bahwa hukum-hukum buatan manusia (positivisme) menempati kedudukan di sisi para pendukungnya dan pembelanya yang mirip dengan kedudukan berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hukum-hukum itu bagi mereka berkedudukan seperti nash-nash agama, bahkan mungkin terkadang berada pada tingkat yang lebih tinggi darinya. Ini mengandung pengakuan terhadap hak penetapan hukum bagi selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang tidak boleh ada dalam masyarakat Islam atau masyarakat Timur kita kecuali sejauh yang dituntut oleh kebutuhan hidup dalam hal-hal yang tidak dibahas oleh Syari’ (Allah) baik dengan pengakuan maupun penolakan. Adapun apa yang diakui oleh Syari’, maka itulah kebenaran yang wajib diikuti, dan kita tidak boleh menggantikannya dengan yang lain. Demikian pula apa yang ditolak-Nya wajib kita hindari, meskipun semua penghuni bumi melakukannya.
Jika manusia membela kebatilan mereka dan bangga dengannya, bukankah seharusnya kita berpegang teguh pada kebenaran yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala dan membelanya?!
Dalam Al-Qur’an Al-Karim terdapat penegasan yang tegas tentang kekhususan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan hakimiyyah dalam masyarakat Islam, bahkan dalam seluruh alam semesta. Dalam Surah Al-Maidah, ayat-ayat mulia dari ayat (44) hingga ayat (47) ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”, kemudian: “Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”, kemudian: “Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.
Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu ‘anhuma dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” dan “orang-orang yang zalim” dan “orang-orang yang fasik”, bahwa barangsiapa mengingkari hukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan maka ia telah kafir, dan barangsiapa mengakuinya tetapi tidak memutuskan dengannya maka ia adalah zalim dan fasik, dan bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, tetapi ini adalah kekufuran yang lebih rendah, yaitu kufur di bawah kufur, kezaliman di bawah kezaliman, dan kefasikan di bawah kefasikan.
Jelas bagi kita—dengan demikian—bahwa sistem Islam berdiri atas pengakuan terhadap hak hakimiyyah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala yang tidak ada seorang pun yang berbagi dalam hal itu. Ini tentu saja akan membawa kepada kestabilan masyarakat dan kepatuhan mereka dengan rela terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal-hal yang ditentukan-Nya, dan mengambil inspirasi dari kaidah-kaidah wahyu dan tujuan-tujuannya dalam hal-hal yang tidak ditentukan-Nya. Adapun ketika kaidah ini terpecah-belah dan otoritas penetapan hukum terbagi-bagi dalam masyarakat, maka saat itulah kekuasaan menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hati nurani dan ibadah ritual, sementara kekuasaan menjadi milik selain-Nya dalam undang-undang dan syariat. Dan ketika kekuasaan menjadi milik Allah dalam pembalasan akhirat, sementara kekuasaan menjadi milik selain-Nya dalam hukuman dunia—saat itulah—jiwa dan masyarakat terkoyak di antara dua kekuasaan yang berbeda dan di antara dua manhaj yang berbeda. Saat itulah kehidupan manusia menjadi rusak, kerusakan yang ditunjukkan oleh firman Al-Haq Tabaraka wa Ta’ala: “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa” (Surah Al-Anbiya: 22), dan firman-Nya Subhanahu: “Dan seandainya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi” (Surah Al-Mu’minun: Ayat 71), dan firman-Nya ‘Azza wa Jalla: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Surah Al-Jatsiyah: 18).
Seandainya kaum muslimin dalam masyarakat mereka mendirikan negara mereka atas kaidah hakimiyyah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka: hal itu akan mengakibatkan penghormatan terhadap kaidah-kaidah syariat atau hukum dalam negara-negara yang bertumpu pada prinsip ini, baik dari pihak penguasa maupun yang diperintah, karena semua sama di hadapan hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mereka menaati dan mengharap pahala serta takut akan hukuman, dan senantiasa mengawasi hati nurani mereka karena Allah melihat mereka dan mengetahui keadaan mereka. Dia Subhanahu wa Ta’ala mengetahui orang yang merusak dan orang yang memperbaiki.
Ini tentu saja akan menonjolkan otoritas dan wibawa hukum dalam negara, karena nilai suatu syariat diukur dari seberapa besar ketaatan dan penghormatan yang dimilikinya dalam jiwa individu. Ini adalah hal yang tidak pernah dicapai oleh syariat buatan manusia mana pun pada tingkat Syariat Islam.
Juga, kekhususan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan hak hakimiyyah dalam masyarakat Islam akan membawa kepada keteguhan dan kestabilan sistem sebagaimana telah kami isyaratkan sebelumnya, karena bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda seperti republik atau monarki akan senantiasa terikat dengan agama yang tidak berubah dan tidak berganti, yang diyakini oleh setiap penguasa dan digunakan oleh setiap sistem. Ketika umat mengetahui bahwa perubahan bentuk pemerintahan tidak akan mempengaruhi hukum dan sistem mereka, karena hukum dan sistem tersebut berada di atas pemerintahan dan di atas individu, dan semua harus menghormatinya, ketika umat mengetahui itu maka mereka akan melangkah dalam kehidupan dengan penuh keyakinan, teguh dalam tekad, dan tenang terhadap masa depan mereka. Adapun umat yang urusan mereka tidak didasarkan pada hal itu, maka mereka akan hidup dalam kegelisahan, keguncangan, kebingungan, kehati-hatian, dan kewaspadaan terhadap perubahan pemerintahan yang berbeda pandangannya tentang keadilan dan kebenaran sesuai dengan afiliasi dan hawa nafsu mereka.
Inilah kaidah pertama dari kaidah-kaidah sistem atau sistem politik dalam Islam, yaitu kaidah hakimiyyah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Kaidah-Kaidah Sistem Politik Islam: Kedua – Syura (Musyawarah)
Adapun kaidah kedua yang menjadi pondasi sistem politik dalam Islam adalah kaidah syura (musyawarah). Syura termasuk kaidah-kaidah pokok yang menjadi landasan sistem politik Islam, dan merupakan salah satu pokok syariat serta termasuk keputusan-keputusan yang pasti di dalamnya. Dengan makna ini, syura tidak hanya terbatas pada kaidah dasar sistem politik Islam saja, tetapi juga mewakili kerangka umum dan ruang lingkup di mana semua otoritas penguasa dalam negara Islam harus bekerja di dalam batas-batasnya, baik otoritas legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Dengan demikian, syura mencegah kesewenang-wenangan dalam berpendapat atau memonopoli pendapat, hal yang akan membawa kepada tercapainya pendapat yang benar dan terwujudnya persatuan umat serta persatuan hati di antara anggota-anggotanya.
Syura, sebagai salah satu pilar dasar sistem konstitusional Islam, memberikan hak kepada umat untuk mengelola urusan-urusan umum mereka, dan mewakili salah satu jaminan dasar yang mencegah pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan, karena keputusan yang akan diambil oleh otoritas penguasa tidak akan keluar ke ranah pelaksanaan kecuali setelah penelitian, penyelidikan, pencarian kemaslahatan umum, dan musyawarah dengan para ahli dalam masalah tersebut.
Dengan makna ini, syura termasuk hak-hak dasar yang dijamin oleh Syari’ Islam bagi seluruh kaum muslimin, sehingga mewakili landasan utama di antara kebebasan-kebebasan politik yang dinikmati oleh kaum muslimin dalam negara Islam. Selain itu, syura menjamin bagi umat peran yang mendasar dan efektif dalam mengelola urusan-urusan umum mereka sesuai dengan yang ditetapkan oleh Syariat Islam.
Kita akan membahas beberapa poin dalam topik syura:
Poin Pertama: Dasar Keabsahan dan Kewajiban Syura
Dasar kewajiban kaidah syura bersumber dari sumber-sumber keabsahan Islam. Al-Qur’an Al-Karim telah menganjurkannya, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menganjurkannya serta menjadikannya sebagai syariat dan manhaj baginya dalam banyak urusan, di samping itu para sahabat radiyallahu ‘anhum dan para khalifah rasyidin beramal dengannya dan mengikutinya dalam banyak urusan.
Kita akan membahas setiap dalil dari dalil-dalil keabsahan Islam yang menganjurkan syura dan mewajibkannya atas umat Islam sebagai berikut:
Al-Qur’an Al-Karim: Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal” (Surah Ali Imran: 159). Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Surah Asy-Syura: 38).
Beberapa ahli fiqih menegaskan: bahwa keberadaan sebuah surat dalam Kitabullah Ta’ala, yaitu Surah Asy-Syura yang dinamai dengan nama prinsip ini, dan menjadikan syura (musyawarah) sebagai salah satu sifat orang-orang mukmin, kemudian perintah secara tegas dalam surat yang lain, sesungguhnya merupakan bukti atas perhatian pembuat syariat terhadap musyawarah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang menjadi landasan sistem pemerintahan dalam Islam dan yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan Islam.
Pendapat ini juga menyatakan bahwa petunjuk ayat pertama: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Ali Imran: 159) lebih kuat dalam menunjukkan musyawarah dan ajakan untuk menggunakannya daripada ayat kedua yaitu: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” (Asy-Syura: 38), karena ayat pertama adalah perintah kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, sementara ayat kedua hanya menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu sifat terpuji dari orang-orang mukmin.
Syekh Rasyid Ridha menegaskan bahwa Imam Muhammad Abduh berpendapat: bahwa dalam Surah Ali Imran terdapat ayat lain yang lebih kuat dalam menunjukkan kewajiban musyawarah dan tegaknya pemerintahan atasnya daripada ayat: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” dari surat yang sama, dan ayat ini adalah firman Allah Ta’ala: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104).
Kuatnya petunjuk ayat ini sebagaimana dikatakan Imam Muhammad Abduh dibandingkan dengan petunjuk ayat yang disebutkan dalam Surah Asy-Syura: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” adalah karena petunjuk ayat yang terakhir ini, yaitu firman Allah Ta’ala: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” hanya berarti: bahwa musyawarah adalah sifat informatif tentang keadaan kelompok tertentu, lebih dari menunjukkan bahwa hal ini terpuji pada dirinya sendiri dan terpuji di sisi Allah Tabaraka wa Ta’ala. Dan petunjuknya lebih kuat dari petunjuk firman Allah Ta’ala: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”, karena petunjuk yang terakhir ini, yaitu firman Allah Ta’ala: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” hanya berarti: kewajiban bermusyawarah atas pemimpin, tetapi jika tidak ada penjamin yang menjamin kepatuhannya terhadap kewajiban ini, maka bagaimana jika ia meninggalkannya dan tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat? Sementara ayat ini, yaitu firman Allah Ta’ala: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar”, kami katakan: sementara ayat ini mewajibkan agar di tengah-tengah manusia ada kelompok yang bersungguh-sungguh dan kuat yang mengemban tugas dakwah kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan kewajiban ini bersifat umum dan mengikat para penguasa dan rakyat secara pasti.
Sunnah Nabawiyyah dan Sikapnya terhadap Musyawarah:
Agar kita dapat memahami sikap Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terkait penerapan kaidah ini, yaitu kaidah musyawarah, dan sejauh mana komitmennya terhadap perintah yang terdapat dalam ayat mulia “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”, maka perlu kita menentukan sejauh mana komitmen Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam dalam bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam hal-hal yang akan beliau lakukan.
Dan jika Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam memang wajib bermusyawarah, maka perlu kita jelaskan poin-poin atau ruang lingkup komitmen ini.
Pentingnya menjelaskan hal ini adalah: bahwa jika Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam memang wajib bermusyawarah, maka komitmen ini berlaku lebih-lebih lagi sebagai kewajiban mutlak bagi para khalifah dan penguasa sesudah beliau.
Untuk menjelaskan hal-hal ini, kita perlu menyebutkan beberapa kejadian yang terjadi pada masa kenabian, dan berdasarkan kejadian-kejadian tersebut dapat ditentukan ruang lingkup kewajiban ini dan batasannya. Kita akan melihat: bahwa kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bermusyawarah dalam segala hal yang tidak ada nash tentangnya dalam Alquran Karim.
Kita akan menjelaskan -pertama- beberapa kejadian pada masa kenabian, kemudian membahas sejauh mana komitmen Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap musyawarah dan ruang lingkup komitmen ini, dan pada akhirnya menjelaskan sejauh mana komitmen Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh ahli musyawarah.
Pertama: Kejadian-kejadian Musyawarah pada Masa Kenabian
Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat ketika mendengar kabar keluarnya pasukan Quraisy untuk melindungi kafilah mereka, dan beliau memberitahukan mereka tentang apa yang akan dilakukan Quraisy. Maka berdirilah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu dan berbicara dengan baik, disusul Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu, kemudian berdirilah Al-Miqdad radhiyallahu ‘anhu dan berkata: Wahai Rasulullah! Teruslah pada apa yang Allah tunjukkan kepadamu, kami bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Musa alaihissalam: “Pergilah kamu bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, kami akan duduk menunggu di sini” (Al-Ma’idah: 24), tetapi pergilah kamu bersama Tuhanmu lalu berperanglah, sesungguhnya kami akan ikut berperang bersama kalian. Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, seandainya engkau membawa kami ke Bark Al-Ghimad (tempat yang sangat jauh), niscaya kami akan berjuang bersamamu sampai engkau mencapainya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendoakannya dengan kebaikan. Kemudian Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam menanyakan pendapat kaum Anshar, dan berkata: “Berilah aku nasihat wahai sekalian manusia”. Maka berkatalah Sa’d bin Mu’adz radhiyallahu ‘anhu: Demi Allah, seolah-olah engkau menginginkan kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Benar.” Sa’d berkata: Sungguh kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran, dan kami telah memberikan kepadamu atas hal itu janji dan perjanjian kami untuk taat dan patuh. Maka lakukanlah wahai Rasulullah apa yang engkau inginkan, kami bersamamu. Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, seandainya engkau menerjang laut ini dan menceburkan diri, kami akan ikut menerjang bersamamu, tak seorang pun dari kami yang akan tertinggal.
Demikianlah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebelum melakukan hal ini bermusyawarah dengan para sahabat -semoga Allah Tabaraka wa Ta’ala meridhai mereka- dan ketika beliau mendapati mereka menyetujui apa yang ingin beliau lakukan, beliau menyetujui mereka dan melanjutkan dengan berkah Allah Tabaraka wa Ta’ala.
Dalam Perang Badar -juga- pasukan Quraisy turun di sisi lembah yang jauh, dan keluarlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendahului mereka menuju sumber air, hingga ketika sampai di sumber air Badar yang terdekat, beliau turun di sana. Maka datanglah Al-Hubab bin Al-Mundzir radhiyallahu ‘anhu dan berkata: Wahai Rasulullah, tempat ini, apakah tempat yang Allah tetapkan untukmu sehingga kita tidak boleh maju atau mundur darinya, ataukah ini adalah pendapat, perang, dan strategi? Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ini adalah pendapat, perang, dan strategi.” Maka Al-Hubab berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ini bukan tempat yang baik, beranjlah dengan pasukan hingga kita sampai ke sumber air yang terdekat dari musuh, lalu kita turun di sana, kemudian kita tutup sumber air di belakangnya, lalu kita bangun kolam di atasnya dan kita isi dengan air, kemudian kita berperang dengan musuh, kita minum sementara mereka tidak dapat minum. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh engkau telah memberikan saran yang baik.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan apa yang disarankan Al-Hubab.
Ibnu Sa’d menambahkan pada riwayat ini bahwa wahyu turun kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: “Pendapat yang benar adalah apa yang disarankan Al-Hubab bin Al-Mundzir.” Dari riwayat ini kita dapat melihat: bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bermusyawarah dan mengamalkan pendapat orang yang bermusyawarah dengannya.
Dalam Perang Uhud, Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaum muslimin, dan setelah beliau menceritakan kepada mereka mimpi yang beliau lihat yang menunjukkan kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya, beliau bersabda: “Jika kalian berpendapat untuk tinggal di Madinah dan membiarkan mereka di tempat mereka turun, jika mereka tinggal, mereka tinggal di tempat yang buruk, dan jika mereka masuk ke Madinah, kita perangi mereka di dalamnya.” Maka kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama: menginginkan keluar menemui Quraisy karena keinginan untuk syahid, karena sebagian mereka ketinggalan menghadapi musuh di Badar, dan kelompok lain berpendapat tidak keluar dan tinggal di Madinah sebagaimana pendapat beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam melihat bahwa mayoritas berpendapat keluar menghadapi musuh, beliau mengikuti pendapat mayoritas.
Dan ketika mereka mencoba mengurungkan niat beliau untuk keluar setelah mereka menyadari bahwa mereka telah memaksa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam untuk itu, beliau bersabda kepada mereka: “Tidak pantas bagi seorang nabi jika telah memakai baju zirahnya untuk melepasnya hingga ia berperang.”
Wahai saudara-saudara, kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya -insya Allah-. Saya titipkan kalian kepada Allah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 – Kaidah-kaidah Sistem Politik dalam Islam (2)
Lanjutan: Dalil-dalil Musyawarah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam kepada yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, junjungan kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Kita telah membahas pada perkuliahan sebelumnya tentang sisa sumber-sumber hukum politik dalam Islam, kemudian kita beralih membahas tentang kaidah-kaidah sistem politik dalam Islam. Kita telah membahas kaidah pertama yaitu hakimiyyah (kedaulatan) hanya milik Allah semata, kemudian kita memulai pembahasan tentang kaidah kedua yang terwujud dalam musyawarah dalam Islam, dan kita sebutkan dalilnya dari Alquran. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang dalilnya dari Sunnah, maka kita katakan:
Dalam Perang Uhud, Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaum muslimin dan setelah beliau menceritakan kepada mereka mimpi yang beliau lihat yang menunjukkan kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya, beliau bersabda: “Jika kalian berpendapat untuk tinggal di Madinah dan membiarkan mereka di tempat mereka turun, jika mereka tinggal, mereka tinggal di tempat yang buruk, dan jika mereka masuk ke Madinah, kita perangi mereka di dalamnya.”
Maka kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama: menginginkan keluar menemui Quraisy karena keinginan untuk syahid, karena sebagian mereka ketinggalan menghadapi musuh di Badar, dan kelompok lain berpendapat tidak keluar dan tinggal di Madinah, sebagaimana pendapat beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam melihat bahwa mayoritas berpendapat keluar menghadapi musuh, beliau mengikuti pendapat mayoritas. Dan ketika mereka mencoba mengurungkan niat beliau untuk keluar setelah mereka menyadari bahwa mereka telah memaksa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam untuk itu, beliau bersabda kepada mereka: “Tidak pantas bagi seorang nabi jika telah memakai baju zirahnya untuk melepasnya hingga ia berperang.”
Sebagian orang mengomentari hal ini, mereka berkata tentang apa yang terjadi dalam Perang Uhud: bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam walaupun berpendapat bahwa yang terbaik bagi kaum muslimin sebagaimana ditunjukkan oleh kejadian-kejadian setelahnya adalah tidak keluar menghadapi Quraisy yang jumlah dan persenjataannya melebihi mereka di medan perang terbuka, dan agar mereka berkemah di Madinah dan mempertahankannya jika diserang, namun ketika mayoritas berpendapat berbeda dengan apa yang dipandang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan minoritas yang sependapat dengan beliau, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengikuti pendapat mayoritas. Dari kejadian ini kita juga melihat bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkomitmen pada apa yang diputuskan oleh para peserta musyawarah meskipun pendapat pribadi beliau berbeda dengan pendapat mereka, di mana beliau berpendapat bahwa lebih baik tinggal di Madinah dan berlindung di dalamnya. Ini adalah penerapan prinsip musyawarah dalam Islam pada tingkat tertinggi.
Ada kejadian yang terjadi pada masa kenabian yang memberikan penegasan pasti terhadap sikap Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terkait musyawarah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan ahli fiqih lainnya. Ringkasan kisahnya adalah bahwa utusan dari suku Hawazin datang kepada beliau, yaitu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, meminta agar beliau mengembalikan kepada mereka harta dan tawanan mereka, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerangi mereka dan mengambil harta dan tawanan dari mereka, dan mereka ingin mendapatkan kembali hal-hal tersebut. Ketika mereka datang kepada beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan meminta agar beliau mengembalikan kepada mereka harta dan tawanan mereka, beliau berkata kepada mereka: “Bersamaku ada orang-orang yang kalian lihat.” Maksudnya: seakan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada mereka: bersamaku ada para sahabat, saya akan mengambil pendapat mereka dalam masalah ini, dan saya tidak dapat memberikan pendapat tanpa merujuk kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka: “Bersamaku ada orang-orang yang kalian lihat, dan ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, maka pilihlah salah satu dari dua kelompok, antara tawanan atau harta.”
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada mereka: kalian tidak akan mendapat tawanan dan harta sekaligus, tetapi pilihlah antara tawanan atau harta, dan beliau berkata kepada mereka: “Aku telah menunggu kalian.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada mereka selama lebih dari sepuluh hari ketika beliau kembali dari Thaif. Ketika jelas bagi mereka bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua kelompok, mereka memilih tawanan. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan berkata: “Amma ba’du: sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang dalam keadaan bertaubat, dan aku memutuskan untuk mengembalikan kepada mereka tawanan mereka. Barangsiapa di antara kalian yang suka untuk merelakan hal itu, maka lakukanlah.” Artinya: barangsiapa di antara kalian yang suka mengembalikan tawanan yang diambilnya kepada mereka, maka lakukanlah -yaitu kembalikan kepada mereka, dan baginya pahala dari Allah Tabaraka wa Ta’ala-. “Dan barangsiapa di antara kalian yang ingin tetap memiliki bagiannya hingga kami memberinya dari harta rampasan pertama yang Allah berikan kepada kami, maka lakukanlah.”
Yakni: bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, barang siapa yang memiliki sesuatu dari para tawanan perang, jika ia memilih untuk mengembalikannya kepada kaum tersebut, yaitu kepada orang-orang Yahudi tanpa imbalan maka silakan ia lakukan, adapun barang siapa yang memiliki sesuatu dari para tawanan perang dan tidak ingin mengembalikannya tanpa imbalan maka hendaklah ia mengembalikannya dan kami akan memberinya imbalan ketika Allah memberikan harta rampasan perang kepada kami, yaitu ketika Allah memberikan karunia harta kepada kami, maka orang-orang berkata: “Kami ridha dengan itu wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.”
Artinya: kami setuju wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan apa yang engkau katakan dan kami akan mengembalikan para tawanan ini tanpa imbalan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kami tidak tahu siapa di antara kalian yang mengizinkan hal itu dan siapa yang tidak mengizinkan,” yaitu: seakan-akan beliau shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka: aku belum yakin siapa yang mengizinkan dan ridha, dan siapa yang tidak mengizinkan dan tidak ridha, maka kembalilah kalian hingga para pemuka kalian menyampaikan urusan kalian kepada kami.
Peristiwa ini menunjukkan dari satu sisi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam berbagai peristiwa dan kejadian yang dihadapkan kepadanya, dan dari sisi lain hal ini menunjukkan pengambilan sistem perwakilan dan perwalian, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “hingga para pemuka kalian menyampaikan urusan kalian kepada kami,” yaitu orang-orang yang kalian pilih untuk menyampaikan urusan kalian kepada kami.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak hanya bermusyawarah dalam urusan-urusan umum dan penting yang menyangkut semua kaum muslimin, bahkan beliau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan pribadinya yang paling khusus, sebagaimana yang terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior mengenai tindakan apa yang akan diambil terhadap Ummul Mukminin Aisyah, ketika orang-orang munafik penebar fitnah menuduhnya dengan tuduhan yang batil, dan tujuan dari itu adalah untuk menyakiti Islam dan kaum muslimin sebagaimana diketahui dalam kisah yang terkenal dengan kisah Ifki (tuduhan palsu), dan karena keputusan dalam masalah seperti ini memiliki pengaruh besar terhadap jiwa kaum muslimin, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memutuskannya sendiri, melainkan mengajukan masalah tersebut kepada kaum mukminin untuk mengambil pendapat mereka, dan Al-Quran kemudian turun membuktikan kesucian Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Juga, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memuji musyawarah dan mendorong kaum muslimin untuk melaksanakannya serta bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam sebagian besar urusan yang dihadapkan kepadanya sebagaimana telah kami jelaskan, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan hal itu dengan perkataannya: “Tidak ada seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.”
Para fuqaha meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang musyawarah, di antaranya: “Orang yang dimintai nasihat adalah orang yang dipercaya,” dan di antaranya: “Apabila pemimpin kalian adalah orang-orang terbaik kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang dermawan, dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka permukaan bumi lebih baik bagi kalian daripada perutnya (kubur).” Beliau juga bersabda: “Tidaklah suatu kaum bermusyawarah melainkan mereka diberi petunjuk kepada urusan mereka yang paling tepat,” dan beliau bersabda: “Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan gagal orang yang beristikharah,” dan beliau bersabda: “Tidaklah celaka seorang hamba karena musyawarah,” dan beliau juga bersabda: “Musyawarah adalah benteng dari penyesalan, dan jaminan dari celaan,” dan beliau juga bersabda: “Barang siapa yang menghendaki suatu urusan lalu bermusyawarah di dalamnya dengan seorang muslim, maka Allah memberinya taufik kepada urusan yang paling tepat,” dan beliau bersabda: “Puncak akal setelah beriman kepada Allah adalah menjalin keakraban dengan manusia,” dan beliau bersabda: “Tidaklah merasa cukup orang yang menyendiri dengan pendapatnya, dan tidaklah binasa seseorang karena musyawarah,” dan dalam riwayat lain: “Dan tidaklah merasa cukup seseorang tanpa musyawarah,” dan beliau bersabda: “Ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak memerlukan hal itu” –yaitu musyawarah– “tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi umatku, maka barang siapa di antara mereka yang bermusyawarah tidak akan kehilangan petunjuk, dan barang siapa yang meninggalkannya tidak akan luput dari kesesatan.” Syaikh Rasyid Ridha berkomentar tentang hal itu dengan perkataannya: yaitu Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkannya untuk mewujudkan petunjuk dalam berbagai kemaslahatan dan mencegah kerusakan; karena kesesatan adalah kerusakan dan kesesatan, dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mintalah pertolongan untuk urusan-urusan kalian dengan musyawarah.”
Dalam banyak urusan duniawi, beliau shallallahu alaihi wasallam kembali kepada kaum muslimin, dan dalam lingkup ini diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam sabdanya: “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian,” dan sabdanya: “Apa yang termasuk urusan agama kalian maka kembalilah kepadaku, dan apa yang termasuk urusan dunia kalian maka kalian lebih mengetahuinya.” Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tunduk pada pendapat mereka dalam urusan dunia. Setelah memaparkan preseden-preseden yang terjadi di masa kenabian ini, maka kita sampai pada jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan di awal pembahasan kita tentang musyawarah, yaitu apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan yang hendak beliau lakukan.
Sejauh mana kewajiban Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam bermusyawarah: Para fuqaha berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah ini tidak mengikat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan yang terjadi padanya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah ini tidak mengikat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kewajiban melainkan dalam bentuk anjuran; untuk menenangkan hati kaum muslimin dan menarik hati mereka, dan karena itu lebih menyayangi mereka dan menghilangkan kedengkian mereka, sebagaimana hal itu merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mereka serta untuk menarik hati mereka pada agama mereka, meskipun Allah Subhanahu wa Taala telah mencukupinya dari musyawarah ini dengan mengatur urusan-urusannya dan memimpinnya.
Arah kedua berpendapat bahwa perintah yang terdapat dalam ayat mulia tersebut adalah dalam bentuk kewajiban, dalam hal yang tidak turun wahyu di dalamnya, karena mungkin kaum muslimin memiliki sesuatu yang bermanfaat, oleh karena itu wajib kembali kepada mereka. Menurut pendapat ini, musyawarah di sini adalah dalam bentuk kewajiban, sebagaimana kami melalui preseden-preseden nabawi yang telah kami sebutkan sebagiannya memastikan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari apa yang telah disepakati oleh para peserta musyawarah.
Jika kita kembali kepada lingkup kewajiban ini, maka apa lingkup kewajiban ini? Yaitu jika Nabi shallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan, apakah beliau bermusyawarah dengan mereka dalam semua urusan, baik urusan agama atau urusan dunia atau urusan peperangan atau ekonomi atau bagaimana? Inilah yang dikenal dengan lingkup kewajiban ini. Kami katakan: Adapun lingkup kewajiban ini, yaitu kewajiban bermusyawarah, maka di dalamnya tidak disepakati pendapat-pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu terbatas pada masalah-masalah duniawi seperti urusan perang dan lainnya, adapun masalah-masalah agama maka keluar dari lingkup musyawarah, dan Rasulullah tidak wajib bermusyawarah dengan kaum muslimin di dalamnya, bahkan dalam urusan-urusan yang belum turun wahyu kepada beliau shallallahu alaihi wasallam di dalamnya; karena urusan-urusan ini rujukannya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dengan semua bagiannya: kewajiban, anjuran, kebolehan, kemakruhan, dan keharaman, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak wajib bermusyawarah dalam hukum-hukum agama ini; karena pendapat di dalamnya adalah milik Allah Azza wa Jalla semata melalui wahyu; oleh karena itu sebagian fuqaha menafsirkan lafazh yang terdapat dalam ayat musyawarah, yaitu firman-Nya Taala: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka” (Surat Asy-Syura: sebagian dari ayat 38) dan lafazh yang terdapat dalam Surat Ali Imran: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Surat Ali Imran: sebagian dari ayat 159) bahwa yang dimaksud adalah urusan duniawi yang biasanya dilakukan oleh para penguasa, bukan urusan agama murni yang porosnya adalah wahyu bukan pendapat.
Karena seandainya masalah-masalah agama seperti akidah, ibadah, halal dan haram termasuk yang diputuskan dengan musyawarah, niscaya agama adalah buatan manusia, dan ini mustahil dan batil, melainkan ia adalah buatan ilahi, tidak ada seorang pun yang memiliki pendapat di dalamnya baik di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun setelah masa beliau shallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu kita melihat para sahabat radhiyallahu alaihim tidak mengemukakan pendapat mereka kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali setelah mereka memastikan bahwa apa yang mereka kemukakan kepadanya dari pendapat adalah termasuk urusan yang belum turun wahyu di dalamnya, dan ini jelas dari diskusi yang terjadi antara beliau shallallahu alaihi wasallam dengan Al-Hubab bin Al-Mundzir pada hari perang Badar, ketika Al-Hubab berkata kepadanya saat beliau turun di suatu tempat: “Apakah tempat ini diturunkan oleh Allah kepadamu sehingga tidak boleh bagi kami untuk maju atau mundur darinya, ataukah ini adalah pendapat, strategi perang, dan taktik?”
Maksud perkataan Al-Hubab bin Al-Mundzir adalah bahwa pendapat ini jika Allah yang membuat engkau berhenti di dalamnya maka tidak boleh bagi kami untuk memberikan pendapat, adapun jika ini urusan duniawi dan urusan perang dan sebagainya maka kami memberikan pendapat kami, ini artinya bahwa para sahabat dalam urusan agama tidak memberikan pendapat dan mereka bertanya terlebih dahulu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam apakah urusan ini berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan urusan dunia, jika berkaitan dengan urusan agama mereka tidak memberikan pendapat, adapun jika berkaitan dengan urusan dunia seperti perang misalnya maka mereka memberikan pendapat mereka dalam hal itu, dan di antara yang mengatakan demikian berpendapat bahwa istisyarah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah agama, meskipun bukan dalam bentuk hukum dan kewajiban, namun itu adalah untuk menenangkan jiwa kaum muslimin, dan ini tidak bertentangan dengan bahwa rujukan urusan agama adalah wahyu.
Artinya: meskipun kami mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya bermusyawarah dengan mereka dalam urusan dunia saja, namun sesungguhnya beliau shallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka dalam sebagian urusan atau bermusyawarah dengan mereka dalam sebagian urusan duniawi, maka ini bukan kewajiban atas beliau, melainkan hanya dari segi menenangkan jiwa saja.
Inilah pendapat pertama yang mengatakan bahwa musyawarah tidak dilakukan dalam urusan agama melainkan hanya dilakukan dalam urusan duniawi saja.
Sebagian yang lain berpendapat bahwa lingkup musyawarah mencakup masalah-masalah duniawi sebagaimana juga mencakup masalah-masalah agama, dalam hal yang belum turun wahyu di dalamnya, dan wahyu membenarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terakhir, jika para peserta musyawarah keliru, namun hal ini bukan berarti bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membutuhkan musyawarah, melainkan ini adalah peringatan dari Pembuat Syariat Yang Maha Bijaksana akan keutamaan yang ada dalam musyawarah dan agar umat mengikutinya setelah beliau, inilah pendapat kedua, dan kami berpendapat bahwa arah yang melihat bahwa musyawarah mengikat dan membatasi lingkupnya pada masalah-masalah duniawi yang tidak ada nash di dalamnya adalah pendapat yang lebih layak diterima dan yang rajih menurut kami, karena masalah-masalah agama keluar dari lingkup musyawarah; karena dasarnya dan rujukan di dalamnya adalah kepada wahyu, baik dengan cara langsung, yaitu apa yang diturunkan oleh wahyu dari nash-nash Al-Quran atau dengan cara tidak langsung dalam apa yang disunnahkan kepada mereka oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum; karena beliau shallallahu alaihi wasallam ketaatannya wajib atas seluruh makhluk dalam apa yang mereka sukai atau mereka benci dan tidak boleh diberikan hak kepada kaum muslimin dalam musyawarah yang keluar dari lingkup masalah-masalah ini, oleh karena itu kita temukan sebagian mufassir menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau membaca ayat yang terdapat dalam Surat Ali Imran: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebagian urusan, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah,” adapun jumhur maka mereka tidak mengambil tambahan ini, namun melihat bahwa urusan di sini tidak disebutkan dalam bentuk umum karena tidak bermusyawarah dalam menghalalkan dan mengharamkan, dan arah ini sesuai dengan logika, akal, dan dasar syariat Islam.
Dan mendukungnya adalah bahwa masalah-masalah yang terjadi musyawarah di dalamnya di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah-masalah duniawi seperti masalah perang, dan apa yang berkaitan dengan muamalah yang berlaku di antara manusia, kemudian kita membahas topik lain yaitu sejauh mana kewajiban Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang disimpulkan oleh para peserta musyawarah. Jika kita mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam kembali kepada para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan, kemudian jika mereka sepakat pada suatu pendapat tertentu, apakah beliau mengambil pendapat ini ataukah hak beliau untuk menyelisihi pendapat ini dan mengambil pendapat yang beliau anggap benar? Kami katakan: masih tersisa satu pertanyaan terakhir terkait dengan perintah yang ditujukan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dan maksudnya, apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meskipun wajib bermusyawarah dengan perincian yang telah kami jelaskan? Apakah beliau harus mengamalkan apa yang disimpulkan oleh mayoritas peserta musyawarah? Yaitu: apakah beliau wajib mengamalkan apa yang disimpulkan oleh pendapat mayoritas atau tidak? Kami katakan para fuqaha tidak sepakat pada jawaban yang pasti mengenai pertanyaan ini dan sebab yang menyebabkan ketidakpastian pada jawaban yang pasti adalah ketidaksepakatan mereka dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” (Surat Ali Imran: sebagian dari ayat 159). Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah yang terdapat dalam ayat ditujukan kepada kewajiban bermusyawarah, kemudian jika telah selesai dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membulatkan tekad pada suatu urusan dari urusan-urusan maka boleh baginya untuk melaksanakannya dan bertawakal kepada Allah Taala bukan kepada musyawarah mereka, yaitu bahwa musyawarah wajib pada awalnya bukan pada akhirnya. Yaitu bahwa beliau bermusyawarah dengan mereka pada awal urusan tetapi hasil musyawarah tidak mengikat Nabi shallallahu alaihi wasallam.
Sementara itu, pendapat lain berpandangan bahwa syura bersifat mengikat sejak awal hingga akhir, dengan pengertian bahwa syura wajib dilaksanakan ketika hendak memutuskan suatu perkara dari perkara-perkara duniawi, dan tidak boleh melakukan suatu perkara yang tidak ada wahyu mengenainya kecuali dengan mengikuti musyawarah. Apabila para peserta musyawarah telah sampai pada suatu pendapat, maka pendapat tersebut wajib dilaksanakan. Hal ini disimpulkan dari sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan Umar: “Seandainya kalian berdua bersepakat dalam suatu musyawarah, niscaya aku tidak akan menyelisihi kalian berdua”. Dan apa yang diriwayatkan dari Ali yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ketegasan, beliau bersabda: “Musyawarah dengan ahli pendapat kemudian mengikuti mereka”.
Dalam rangka membandingkan kedua kecenderungan dan dua pendapat ini, kami berpandangan bahwa apa yang diriwayatkan oleh mereka yang berpendapat bahwa musyawarah bersifat mengikat sejak awal hingga akhir—yaitu bahwa wajib mengamalkan pendapat yang telah disepakati oleh para peserta musyawarah—adalah yang lebih layak diterima dan lebih kuat. Jika kecenderungan pertama sesuai dengan masa kenabian karena beliau shallallahu alaihi wasallam terpelihara dari kesalahan dan terhindar dari hawa nafsu, sehingga jika beliau memutuskan suatu pendapat meskipun bertentangan dengan kesepakatan para peserta musyawarah, maka itulah pendapat yang benar. Dan jika bukan demikian, maka wahyu akan membimbing Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun setelah masa kenabian dan berakhirnya wahyu, maka pendapat yang menyatakan bahwa musyawarah itu wajib di awal namun tidak wajib di akhir—sehingga penguasa boleh bertekad pada suatu pendapat meskipun bertentangan dengan kesepakatan para peserta musyawarah—kami katakan adalah pendapat yang tidak kami terima. Karena dari satu sisi, hal ini menjadikan syura sebagai sesuatu yang bersifat formal dan semu, sehingga penguasa telah memenuhi kewajiban ini hanya dengan melakukan musyawarah, meskipun ia telah bertekad sebelumnya pada pendapat tertentu yang bertentangan dengan pendapat mayoritas umat.
Dari sisi lain, pendapat ini akan mengakibatkan kesewenang-wenangan dan tirani, karena pada akhirnya tidak memberikan nilai atau bobot apa pun terhadap pendapat ahli syura yang merupakan ulama umat dan ahli hal wal aqd di dalamnya. Sudah pasti bahwa syariat Islam sama sekali tidak membolehkan tirani dan kesewenang-wenangan, dan dilarang bagi penguasa untuk menjadi thaghut yang menginginkan kesombongan atas manusia. Sebaliknya, ia harus tunduk pada kesimpulan para ahli ijtihad dan mengikuti pendapat mereka. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ali dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: Aku bertanya: “Ya Rasulullah! Suatu perkara terjadi pada kami yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan tidak ada sunnah darimu mengenainya.” Beliau bersabda: “Kumpulkanlah untuk itu para alim” atau beliau bersabda: “Para ahli ibadah dari kalangan mukmin, lalu jadikanlah itu sebagai musyawarah di antara kalian, dan janganlah kalian memutuskan dengan satu pendapat saja”. Karena jika keputusan hasil syura tidak mengikat, maka hal itu akan membatasi penerapan dan pengamalan syura, yang berakibat pada hilangnya kewajiban ini sama sekali.
Sekarang kita berbicara tentang penerapan syura pada masa Khulafaur Rasyidin:
Ketika kita meninjau prinsip ini setelah masa kenabian, kita mendapati sebagian fuqaha memperluas cakupan syura dan menjadikannya wajib dalam semua masalah yang tidak ada wahyu mengenainya, setelah mengeluarkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan akidah, karena nash-nash telah menjelaskannya secara terbatas dan tidak ada ruang untuk musyawarah di dalamnya.
Adapun selain masalah-masalah ini, baik terkait dengan masalah peperangan maupun masalah lain yang masuk dalam lingkup kekuasaan politik atau terkait dengan hukum-hukum, maka syura di dalamnya wajib sejak awal menurut satu pendapat, dan wajib sejak awal hingga akhir menurut pendapat lain, sesuai dengan rincian yang telah kami jelaskan tentang syura di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini menemukan dasarnya dalam preseden-preseden yang terjadi di masa para Sahabat. Mereka bermusyawarah tentang khalifah dan apa yang harus diikuti dalam menghadapi ahli riddah (orang yang murtad), bermusyawarah tentang kakek dan warisannya, tentang hukuman arak dan jumlahnya, bermusyawarah dalam masalah peperangan dan lain-lain. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika suatu masalah diajukan kepadanya, ia mencari hukumnya pertama kali dalam Al-Quran Al-Karim. Jika ia menemukan apa yang dapat diputuskan dengannya, maka ia memutuskan dengannya. Jika tidak ada dalam Al-Quran hukum untuk masalah tersebut, ia merujuk pada Sunnah. Jika ia menemukan solusi di dalamnya, maka ia memutuskan dengannya. Jika ia tidak mampu mencapai hukum masalah tersebut dari Al-Quran atau Sunnah, ia bertanya kepada orang-orang: “Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memutuskan mengenainya dengan suatu keputusan?” Jika salah seorang dari mereka menunjukkan kepadanya suatu hukum dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut, ia memutuskan dengannya. Jika tidak, ia mengumpulkan orang-orang dan meminta pendapat mereka. Jika mereka bersepakat pada suatu pendapat, ia memutuskan dengannya.
Metode yang sama juga diikuti oleh Umar bin Khaththab, hanya saja ia menambahkan pada Al-Quran dan Sunnah apa yang telah ditempuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia tidak menemukan hukum untuk masalah tersebut dalam sumber-sumber ini, ia meminta pendapat orang-orang dan mengikuti kesimpulan para peserta musyawarah. Ia menolak untuk menyendiri dalam berpendapat pada masalah apa pun yang dihadapkan kepadanya. Sebaliknya, ia mengumpulkan para sahabat senior dari kalangan ahli Badar dan meminta pendapat mereka.
Utsman radhiyallahu anhu juga mengikuti metode ini. Syura memiliki kedudukannya selama enam tahun masa khilafahnya hingga Bani Umayyah menguasai kendali perkara pada masanya, yang mengakibatkan tidak diperhatikannya kewajiban ini. Keadaan terus demikian hingga Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Setelah ia syahid dan Ali mengambil alih khalifah berdasarkan bai’at umum dari kaum muslimin, syura kembali pada kedudukannya, dan ia bekerja untuk menjamin kewajiban ini.
Penentuan Ahli Syura dan Syarat-Syarat yang Harus Terpenuhi di Dalamnya
Sekarang kita berbicara tentang penentuan ahli syura dan syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya. Kami katakan bahwa ahli syura harus memenuhi sejumlah syarat. Para fuqaha telah menjelaskan syarat-syarat ini ketika mereka berbicara tentang ahli hal wal aqd dan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada mereka. Di antara syarat-syarat terpenting adalah:
- Islam, dan ini adalah syarat mutlak karena negara Islam didirikan atas dasar kesatuan akidah. Tidak boleh berpartisipasi dalam menjalankan urusan-urusannya atau dalam menjamin pencapaian maksud-maksud Syari’ (pembuat hukum) terhadap makhluk, orang yang tidak beriman kepada Islam. Syarat ini disepakati dan termasuk syarat yang terkait dengan sistem umum dalam negara Islam.
- Akal, dan ini adalah syarat yang jelas dalam semua taklif (beban kewajiban) syariat, sebagaimana ia adalah syarat untuk semua wilayah (kekuasaan) umum atau khusus.
- Jenis kelamin: Jumhur fuqaha berpandangan bahwa disyaratkan laki-laki dalam ahli hal wal aqd, termasuk ahli syura. Namun kami tidak berpandangan demikian, karena larangan hanya terbatas pada jabatan khalifah dan tidak berlaku untuk semua wilayah.
- Ilmu: Artinya harus tersedia pada ahli syura tingkat ilmu tertentu yang memenuhi syarat mereka untuk menjadi ahli syura dan memberikan mereka kemampuan untuk membedakan berbagai pendapat dalam lingkup perkara yang dimusyawarahkan.
- Pendapat dan hikmah: Selain ilmu, harus tersedia pada ahli syura pendapat dan hikmah agar ia dapat mencapai keputusan-keputusan yang paling sesuai yang mewujudkan maksud Syari’ dan kemaslahatan masyarakat Islam.
- Keadilan: Yaitu takwa dan wara’ yang terwujud dengan istiqamah, amanah, menjaga syiar-syiar Islam, dan berpegang teguh pada tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, Al-Qurthubi mengutip dari Sufyan Ats-Tsauri tentang perlunya takwa dan amanah pada ahli syura. Namun perlu diperhatikan bahwa bukan berarti mewajibkan syura bahwa ia harus dilaksanakan dalam setiap masalah apa pun sifatnya, sehingga harus meminta pendapat semua ahli hal wal aqd. Sebaliknya, kewajiban tertuju pada musyawarah dengan para ahli dalam masalah yang diajukan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi yang menyebutkan pendapat bahwa para penguasa wajib meminta pendapat para ulama dalam hal yang tidak mereka ketahui dan apa yang membingungkan mereka dari urusan agama, para ahli dalam urusan militer dan peperangan dalam masalah-masalah kemiliteran, dan para ahli dalam bidang-bidang administratif dalam masalah-masalah yang terkait dengannya.
Al-Qurthubi berkata: Wajib bagi para penguasa meminta pendapat para ulama dalam hal yang tidak mereka ketahui dan apa yang membingungkan mereka dari urusan agama, para tokoh militer dalam hal yang terkait dengan peperangan, tokoh-tokoh masyarakat dalam hal yang terkait dengan kemaslahatan, tokoh-tokoh penulis, menteri, dan pegawai dalam hal yang terkait dengan kemaslahatan negara dan pemakmurannnya. Al-Qurthubi juga menetapkan bahwa sifat orang yang dimintai pendapat dalam urusan dunia adalah berakal, berpengalaman, dan mencintai orang yang meminta pendapat. Ia juga harus ahli fatwa, amanah. Para fuqaha biasa meminta bantuan majelis-majelis yang terdiri dari para ulama dalam fikih, filsafat, ilmu pengetahuan, sejarah, dan ahli dalam berbagai bidang.
Adapun jika masalah yang menjadi objek syura terkait dengan semua kaum muslimin dan tidak memerlukan jenis keahlian dan spesialisasi dalam bidang tertentu, maka tidak ada pilihan selain merujuk kepada seluruh kaum muslimin. Lingkaran orang yang dimintai pendapat meluas cakupannya setiap kali objek syura terkait dengan masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan pokok dari kemaslahatan kaum muslimin. Pendapat ini menemukan dasarnya dalam apa yang ditempuh oleh Umar radhiyallahu anhu ketika ia meminta pendapat kaum Muhajirin dan Anshar tentang pembagian apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin dari tanah Irak dan Syam.
Pertanyaannya sekarang: Apakah disyaratkan Islam pada ahli syura? Kami telah merangkum sebelumnya syarat-syarat yang harus terpenuhi pada ahli syura dan kami katakan: Bahwa sudah pasti bahwa syarat Islam adalah salah satu syarat yang diperlukan yang harus terpenuhi pada ahli hal wal aqd, sebagaimana ia juga merupakan syarat mutlak yang diperlukan bagi setiap orang yang menjalankan wilayah umum dalam negara Islam. Namun, mungkin diperlukan untuk meminta bantuan keahlian asing. Apakah hal itu dianggap pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum Islam? Di sini kita harus membedakan antara dua hal:
Pertama: Dalam bidang legislasi (pembuatan undang-undang), maka syarat Islam adalah salah satu syarat yang diperlukan dan mutlak yang harus terpenuhi pada ahli syura karena syarat ini terkait dengan sistem dasar negara Islam. Oleh karena itu, tidak boleh non-muslim berpartisipasi dalam lingkup syura yang tujuan pelaksanaannya adalah menetapkan kaidah-kaidah hukum, yaitu dalam keadaan di mana tidak ada nash, karena tidak ada ijtihad dengan adanya nash. Maka dari itu, non-muslim dikecualikan dari lingkup syura dalam masalah-masalah legislatif.
Kedua: Adapun dalam bidang pelaksanaan, terutama dalam lingkup masalah-masalah teknis murni, mungkin diperlukan meminta bantuan non-muslim. Hal ini menurut kami tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam, selama wewenang penilaian dan keselarasan keputusan dengan kemaslahatan masyarakat Islam tetap berada di tangan otoritas umum dalam negara Islam. Meminta pendapat non-muslim, meskipun kami berpandangan bahwa itu adalah perkara yang boleh, namun tidak bersifat mengikat, sehingga wajib diamalkan. Karena pendapat ini memberikan kepada non-muslim hak wilayah umum atas kaum muslimin, yang dilarang berdasarkan nash Syari’, karena menyentuh sistem umum dalam negara Islam. Sebaliknya, ia termasuk perkara-perkara yang bersifat pertimbangan yang tunduk pada pertimbangan kelayakan dan apa yang sesuai dengan kemaslahatan umum umat Islam.
Cara Melaksanakan Kewajiban Syura dan Cara Memilih Ahli Syura
Sekarang kita berbicara tentang cara melaksanakan kewajiban syura:
Adapun bagaimana menerapkan kewajiban syura yang telah diwajibkan oleh Syari’ Islam, maka untuk menjelaskan hal itu, kita harus membedakan antara kewajiban prinsip ini dan keharusan menjaminnya, dan antara metode pelaksanaannya. Kita harus membedakan antara prinsip dan metode pelaksanaannya. Jika Islam telah mewajibkan syura dan menjamin dengan kewajiban tersebut hak umat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam memutuskan urusan-urusan umumnya, serta memerintahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengannya, dan karenanya para khalifahnya setelah beliau wajib melaksanakannya, di samping menjadikannya sebagai sifat dari orang-orang yang beriman dengan syariatNya dan berkomitmen dengan hukum-hukumNya, maka hal ini sama sekali tidak mengharuskan kita mencampuradukkan antara kaidah yang menetapkan prinsip yang jelas dan tegas ini—yang merupakan pilar dasar dari pilar-pilar yang menjadi dasar sistem politik Islam—dengan metode pelaksanaan dan bentuk penerapan yang dihasilkan dari pelaksanaan prinsip ini. Syariat Islam telah menghindari rincian-rincian yang diperlukan untuk pelaksanaan prinsip syura, dan ini adalah pendekatan yang diperlukan oleh keluhuran syariat dan kecocokannya untuk menghadapi semua perkembangan yang diperlukan oleh kondisi waktu dan tempat.
Karena bentuk-bentuk penerapan terikat erat dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Seandainya syariat Islam mengambil pendekatan rinci dalam bentuk-bentuk penerapan, maka ia akan tampak di hadapan para peneliti sebagai kaku dan tidak mampu bertahan dalam menghadapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, kaidah yang sesuai dengan masa tertentu tidak dapat dikatakan cocok untuk setiap masa. Yang cocok untuk muslimin pertama dengan kesederhanaan dan kemurnian lingkungan mereka, tidak mungkin cocok untuk diterapkan setelah Islam tumbuh, berkembang, dan menghadapi kondisi dan keadaan yang berbeda sama sekali dengan kondisi yang dihadapi kaum muslimin pada awalnya. Dari sinilah Al-Quran Al-Karim cukup dengan menetapkan kewajiban prinsip dan kemutlakannya, yaitu prinsip syura. Demikian pula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau meletakkan kaidah-kaidah untuk syura sesuai dengan apa yang cocok dengan lingkungan dan kondisi masanya, maka kaum muslimin akan menjadikannya agama dan mencoba mengamalkannya di setiap waktu dan tempat, padahal itu bukan urusan agama. Maka yang lebih bijaksana dan lebih baik adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan penetapan rincian-rincian khusus tentang prinsip syura kepada umat, agar mereka menetapkan darinya dalam setiap keadaan apa yang sesuai dengan mereka dan baik bagi mereka.
Dan jalan untuk mencapai itu tidak dapat terwujud kecuali dengan menerapkan prinsip syura (musyawarah). Cara-cara yang digunakan dalam bentuk dan rincian syura dapat selalu ditinjau kembali, sesuai dengan kondisi zaman dan tuntutan masa, tanpa menyentuh esensi dasar syura itu sendiri. Sebab, kaidah-kaidah yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah dalam lingkup ini tidak dapat diubah, karena kaidah-kaidah tersebut mewakili prinsip umum dan dasar yang luas yang tidak berubah karena perbedaan zaman atau tempat.
Oleh karena itu, upaya untuk merendahkan Syariat Islam karena tidak menetapkan aturan-aturan yang terperinci dan model-model detail untuk bentuk dan penerapan syura, menunjukkan ketidaktahuan yang mencolok tentang hakikat dan sifat sistem Islam. Karena kita harus membedakan antara prinsip dan cara serta bentuk penerapan prinsip tersebut. Allah Azza wa Jalla menghendaki agar Islam menjadi dakwah yang abadi dan risalah yang kekal untuk seluruh manusia. Maka diperlukan, bahkan sangat penting, bahwa Syariat dalam lingkup muamalat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat hanya menetapkan kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip menyeluruh yang tetap, yang tidak berubah dan tidak berganti. Namun dalam hal pelaksanaan dan bentuk penerapannya, syariat memungkinkan penyesuaian dengan setiap perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Syariat tidak terbatas pada satu cara pelaksanaan yang tidak dapat diganti dengan cara lain, melainkan meletakkan kaidah umum dan prinsip luas yang senantiasa memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inilah yang kita temukan dalam ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh pembuat Syariat (Allah) berkaitan dengan pengaturan masyarakat dalam kondisi politik, ekonomi, dan internasionalnya.
Pembuat Syariat (Allah) cukup dengan meletakkan arahan-arahan umum yang datang dalam bentuk kaidah-kaidah menyeluruh yang tidak terperinci, agar generasi-generasi tidak terikat dengan rincian dan penerapan tersebut. Pembuat Syariat menyerahkannya kepada umat agar bebas menetapkan apa yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat, selama masih dalam lingkup kaidah dan hukum yang telah digariskan oleh Syariat. Dari pendekatan Syariat dalam hal ini, timbul dua perkara:
Perkara pertama: Ajaran-ajaran yang dibawa oleh pembuat Syariat dalam lingkup pengaturan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan dalam negara Islam, bukanlah ajaran yang dituangkan dalam cetakan yang kaku yang tidak dapat diterapkan kecuali dengan satu cara saja. Sebaliknya, tujuannya jelas dan pasti, dan tidak ada ruang untuk mengubah atau menggantinya. Adapun cara pelaksanaan dan bentuk penerapannya dapat berubah dan berkembang. Setiap generasi wajib memahami tujuan tersebut, kemudian memilih cara yang sesuai dengannya berdasarkan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman, dengan memanfaatkan semua yang telah dikembangkan oleh ilmu pengetahuan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk mengeksplorasi cakrawala-cakrawalanya, dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi negara Islam. Setiap generasi di masa mana pun akan selalu menemukan bahwa nash-nash (teks) syariat cukup luas untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baru dan perkembangan yang dicapai.
Perkara kedua: Kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok menyeluruh yang dibawa oleh Syariat tetap menjadi kewajiban yang mengikat dan tugas-tugas yang pasti, yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun, karena kaidah-kaidah tersebut mewakili kerangka umum sistem Islam yang tidak menerima perubahan dan penggantian.
Jadi, prinsipnya tetap dan tidak ada pendapat siapa pun yang dapat mengubahnya, dan umat tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya. Adapun cara-cara pelaksanaan dan bentuk-bentuk penerapan bersifat berubah dan berkembang tanpa bertentangan dengan isi atau menambahnya. Umat berhak kapan saja, sesuai dengan kepentingannya, untuk meninjau kembali penerapannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
Kini kita perlu menentukan cara pemilihan ahli syura berdasarkan apa yang telah kita jelaskan tentang perlunya membedakan antara prinsip dan cara pelaksanaannya. Syura telah menegaskan hak umat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam mengelola urusan-urusan umumnya, dan membangun hubungan erat antara dua pihak dalam masyarakat: para penguasa di satu sisi dan yang diperintah di sisi lain, dengan menetapkan prinsip tersebut. Maka wajar jika seluruh rakyat ikut serta dalam mengelola urusan umumnya. Namun, hal itu tidak dapat terwujud karena dua alasan:
Pertama: Islam tidak mementingkan jumlah banyak, melainkan kualitas iman, ketakwaan, ilmu, budaya, dan pemahaman mereka terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, pendapat sekelompok kecil ulama mungkin lebih baik daripada pendapat mayoritas yang tidak berilmu. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla: “Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk menarik hatimu” (Al-Maidah: 100). As-Sarakhsi menyebutkan bahwa Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahwa penguatan pendapat berdasarkan jumlah terbanyak yang sepakat. As-Sarakhsi menentang pendapat Muhammad bin Al-Hasan dengan mengatakan: Ini bertentangan dengan mazhab yang jelas dari para ulama kami dalam hal penguatan pendapat, bahwa penguatan tidak berdasarkan banyaknya jumlah. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Taala: “Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal saleh” (Hud: 11), dan firman-Nya: “Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Yusuf: 21), dan firman-Nya: “Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya” (Yusuf: 103).
Kedua: Mustahil dalam kenyataan bahwa semua Muslim ikut serta dalam musyawarah untuk setiap persoalan, bahkan jika kita mengabaikan alasan pertama. Karena dari satu sisi, mustahil secara materi untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat untuk bermusyawarah dan mencapai keputusan. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Hazm ketika dia menentang pendapat yang mensyaratkan sahnya pemilihan khalifah harus disetujui oleh orang-orang utama umat di seluruh wilayah negara Islam, karena menurutnya itu adalah pembebanan yang tidak mungkin dilakukan dan tidak dalam kemampuan, dan pasti akan menyebabkan hilangnya urusan-urusan kaum Muslim sebelum dapat mengumpulkan sebagian dari seratus orang utama dari negeri-negeri tersebut. Di sisi lain, bahkan jika kita menerima bahwa tidak mustahil mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat, jika hal itu terwujud akan menyebabkan mustahilnya mencapai keputusan karena beragamnya pendapat dan perbedaan kecenderungan seluruh individu rakyat. Apalagi persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah teknis murni yang mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, sia-sia merujuk kepada mereka semua. Karena semua itu, perwakilan dalam pembentukan ahli syura merupakan cara paling aman untuk memilih mereka.
Sebelumnya telah kami singgung ketika membahas preseden-preseden yang terjadi di masa kenabian, bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menunjukkan kepada kaum untuk kembali kepada para pemimpin mereka, yakni orang-orang yang dikenal di antara mereka, agar mereka menyampaikan persoalan kepada beliau, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seluruh rakyat harus ikut serta dalam pemilihan ahli syura, karena lafal: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (Asy-Syura: 38) menunjuk kepada seluruh masyarakat, dan pembuat Syariat tidak mengkhususkan satu kelompok tertentu tanpa yang lain dalam melaksanakan tuntutan syura. Urusan yang dimaksud di sini adalah urusan kaum Muslim yang dinisbahkan kepada mereka. Oleh karena itu, setiap Muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, harus ikut serta dalam proses pemilihan ahli syura yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kaum Muslim sama dalam hak memberikan suara dan menyatakan pendapat.
Kewajiban bermusyawarah seperti semua kewajiban yang difardukan oleh pembuat Syariat tidak ada ruang untuk fanatisme atau fanatik terhadap suatu pendapat, kecuali jika dia yakin bahwa itu adalah pendapat yang benar. Harus tunduk pada keputusan mayoritas dan berhenti di mana jamaah berhenti. Dalam majelis syura, tidak ada tempat untuk partisan dan sektarianisme, karena Islam menolak agar ahli syura berkelompok dan bersama kelompok mereka bersikeras pada pendapat yang batil. Yang dituntut oleh sistem Islam adalah mereka berputar mengikuti kebenaran di mana pun ia berada dan tidak menyimpang darinya. Seseorang harus meninggalkan pendapatnya jika ternyata itu tidak benar dan menyalahi (kebenaran). Tidak ada celaan bagi majelis syura jika mencapai suatu keputusan kemudian berubah darinya jika kemudian ternyata pendapat itu keliru. Namun, tunduk pada pendapat mayoritas tidak wajib jika bertentangan dengan nash atau kaidah umum dari kaidah-kaidah Syariat atau dalil apa pun dari dalil-dalil syariat, kecuali sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah syariat Islam dalam hal ini.
Kita cukupkan sampai di sini. Aku titipkan kalian kepada Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3 – Kaidah-Kaidah Sistem Politik dalam Islam (3)
Sejauh Mana Keterikatan dengan Pendapat Ahli Syura, dan Penjelasan Pendapat Para Fuqaha tentang Hal Itu
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada orang yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Pada kuliah sebelumnya, kita telah membahas kaidah-kaidah sistem politik dalam Islam. Kita mulai membahas kaidah pertama, yaitu hakimiyah (kedaulatan) milik Allah Subhanahu wa Taala, kemudian kita mulai membahas kaidah kedua, yaitu syura dalam Islam. Kita telah menjelaskan dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabawiyah yang mulia, dan dari preseden-preseden sejarah di masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para Khalifah Rasyidin setelah beliau.
Kita melanjutkan pembahasan tentang syura dalam Islam. Sekarang kita membahas tentang lingkup kewajiban umat dalam syura. Kita katakan: Syura dalam Syariat Islam merupakan kewajiban yang pasti bagi penguasa dan yang diperintah secara sama. Oleh karena itu, syura memberikan hak kepada para ulama umat, sebagaimana telah kami singgung, untuk berpartisipasi dalam mengelola urusan negara, dalam hal-hal yang tidak ada dalilnya dari dalil-dalil syarak. Syura dalam pengertian ini berfungsi untuk mengangkat tanggung jawab kekuasaan umum. Berikut rinciannya:
Pertama: Syura wajib bagi penguasa dan yang diperintah secara sama. Kewajiban bermusyawarah tidak terbatas pada khalifah dan para wali serta penguasa saja, tetapi juga mengikat kaum Muslim. Di satu sisi, syura merupakan salah satu hak dasar mereka, dan di sisi lain merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hal ini: “Jika salah seorang dari kalian dimintai nasihat oleh saudaranya, hendaklah dia menasihatinya”, dan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: “Sesungguhnya di antara hak Muslim atas Muslim lainnya adalah jika dimintai nasihat, hendaklah dia menasihatinya”.
Di samping itu, pembuat Syariat menganggapnya sebagai sifat yang wajib dimiliki oleh orang-orang beriman kepada risalah-Nya. Orang-orang beriman ini yang memenuhi panggilan-Nya, menegakkan rukun-rukun agama-Nya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Maka pembuat Syariat memuji mereka karena mereka tidak menyendiri dengan pendapat, bahkan apa yang tidak mereka sepakati tidak mereka lakukan. Pembuat Syariat dengan ini menjelaskan bagaimana seharusnya pemeluk agama ini, sebagaimana kewajiban ini juga dibebankan kepada khalifah dan para penguasa dan wali lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh ayat mulia: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Ali Imran: 159). Karena jika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang merupakan Nabi yang terjaga dari hawa nafsu dan terbebas dari kesalahan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermusyawarah, maka lebih-lebih lagi para penguasa setelah beliau wajib terikat dengan kewajiban ini. Keterikatan mereka lebih kuat dan lebih tegas karena tidak ada sifat maksum pada mereka dan kemungkinan mereka jatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu, para fuqaha menegaskan bahwa perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk bermusyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada mereka keutamaan musyawarah dan agar umat mengikuti beliau setelahnya. Namun kewajiban timbal balik dalam syura antara penguasa dan yang diperintah ini tidak boleh berakhir dengan melanggar kaidah yang disebutkan dalam Syariat Islam atau kaidah umumnya. Keputusan dalam hal ini adalah batal, yakni dalam hal ada pelanggaran terhadap kaidah yang disebutkan dalam Syariat, dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Ketika ada nash yang qath’i (pasti) atau kaidah umum, maka tidak boleh penerapan pendapat dan musyawarah mengakibatkan pelanggaran terhadapnya.
Kemudian kita berbicara sekarang tentang peran Umat Islam dalam mewujudkan kewajiban syura. Sebelumnya telah kami singgung bahwa syura wajib bagi penguasa dan yang diperintah secara sama. Kita menyimpulkan bahwa syura dengan pengertian ini memberikan kepada para ulama umat dan para mujtahid dari ahlul halli wal aqdi (orang-orang yang berhak memutuskan dan mengikat) dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan mereka peran dalam mengatur segala urusan umat, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu, Umat Islam dalam menjalankan peran ini melalui para mujtahid dan ulamanya dari ahlul halli wal aqdi, tidak terbatas dalam bidang legislasi pada pemberian nasihat kepada khalifah, melainkan menjalankan peran utama dan efektif melalui mereka. Jika mereka bersepakat (ijma’) atas suatu hukum dari hukum-hukum praktis, maka hukum tersebut wajib diterapkan dan mengikat bagi kekuasaan umum. Tidak seorang pun dari mereka yang menjalankan kekuasaan negara dapat turut serta dengan umat dalam mengeluarkan legislasi ini kecuali jika dia adalah seorang mujtahid, dengan terpenuhinya syarat-syarat khusus ijtihad padanya.
Adapun dalam bidang pelaksanaan, umat Islam juga memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan nasihat yang diperlukan kepada penguasa dalam hal-hal yang ingin mereka laksanakan. Oleh karena itu, Pembuat Syariat (Allah) Yang Mahaperkasa dan Mahaagung menjadikan musyawarah sebagai salah satu sifat orang-orang yang beriman kepada risalah-Nya, yaitu mereka yang tidak bertindak sewenang-wenang dalam berpendapat. Maka dari itu, Pembuat Syariat Yang Mahabijaksana memuji sifat ini pada mereka, dan pujian dari Pembuat Syariat berarti bahwa musyawarah merupakan perkara wajib yang harus dijamin dalam negara Islam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Asy-Syura: 38)
Dan kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban yang pasti sebelum mengambil keputusan dalam masalah-masalah penting dan berbahaya yang berkaitan dengan kewenangannya dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya, berdasarkan kedudukannya sebagai khalifah (pengganti) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kami katakan: kekuasaan eksekutif ini wajib memiliki kewajiban yang pasti untuk meminta nasihat dari umat yang diwakili oleh ahlul halli wal ‘aqdi (ahli yang berhak memutuskan) dalam perkara yang akan diputuskan. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapat dan menjelaskan pandangan mereka berdasarkan kaidah-kaidah syariat dalam setiap masalah penting yang berkaitan dengan umat Islam. Artinya, mereka yang menjalankan musyawarah wajib melaksanakan musyawarah ini, karena ini adalah kewajiban yang terletak di pundak mereka.
Karena musyawarah dianggap sebagai kewajiban yang mengikat bagi khalifah dan seluruh penguasa dalam negara Islam, maka sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa wali (pemimpin) yang bertindak sewenang-wenang dengan pendapatnya sendiri dan mengabaikan musyawarah, maka pemimpin seperti itu wajib diberhentikan. Bahkan pendapat ini menyatakan bahwa pemberhentian dalam kasus ini merupakan perkara yang telah disepakati (ijma’).
Ketika kita berbicara tentang musyawarah dan tanggung jawab kekuasaan umum, kami katakan: sebelumnya telah kami sampaikan bahwa dalam lingkup peran yang dilakukan oleh umat dalam penetapan hukum, kekuasaan umum wajib mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh para mujtahid umat, sehingga tidak ada anggota kekuasaan umum yang boleh berpartisipasi dalam hak ini kecuali jika ia adalah seorang mujtahid, dan ia beserta mujtahid-mujtahid umat lainnya menyepakati suatu hukum syariat.
Oleh karena itu, peran umat dalam penetapan hukum dalam fiqih Islam bukan hanya untuk penguasa saja, dan penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau memonopolinya, melainkan peran itu untuk umat, sesuai dengan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang telah kami jelaskan sebelumnya.
Adapun dalam bidang pelaksanaan, kewajiban kekuasaan umum untuk melaksanakan tugas ini bersifat mutlak, baik dalam tahap pengambilan keputusan maupun dalam tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Hal ini karena pada umumnya keputusan tersebut adalah benar. Al-Qurthubi menukil dari Al-Hasan bahwa ia berkata: “Tidaklah suatu kaum bermusyawarah di antara mereka, kecuali Allah akan membimbing mereka kepada yang terbaik dari apa yang ada pada mereka.” Jika umat berkomitmen pada musyawarah dan ikhlas dalam niat untuk mencapai kebenaran dan kebenaran, dan itu adalah tujuan utama ahli musyawarah tanpa condong pada hawa nafsu dan tanpa menyimpang dari kebenaran, maka Allah akan membimbing langkah mereka kepada kebenaran dan memberikan taufik kepada mereka untuk mencapainya. Ini karena musyawarah dengan para fuqaha dan ulama lebih jauh dari bahaya.
Dan bahaya yang mengancam umat jika mereka tidak diberi hak ini dan hak itu dimonopoli oleh salah satu anggota kekuasaan umum—hal ini akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan kediktatoran. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa penguasa yang merampas hak umat ini—yaitu hak musyawarah—dan tidak berkomitmen padanya serta bertindak sewenang-wenang dengan pendapatnya, maka ia wajib diberhentikan—inilah pendapat yang benar. Maka dari itu, musyawarah merupakan salah satu jaminan dasar yang ditetapkan oleh syariat untuk mencegah pelanggaran terhadap kaidah-kaidah syariat, atau kesewenang-wenangan dengan kekuasaan dan penyimpangan dari kepentingan-kepentingan dasar yang diinginkan dan dituju.
Ahli Musyawarah dan Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi pada Mereka
Preseden-preseden yang menjelaskan penerapan prinsip ini pada masa kenabian di satu sisi, dan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama di sisi lain, telah menjelaskan tanpa keraguan sedikitpun bahwa bekerja dengan hasil musyawarah adalah wajib dan tidak boleh dilanggar. Dan dalam kasus-kasus langka di mana pendapat minoritas diambil, terdapat alasan serius dan kuat yang membenarkan hal tersebut, seperti yang terjadi pada masa Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu dalam memerangi orang-orang yang murtad. Ia bermusyawarah dengan para sahabat tentang apa yang harus dilakukan, dan pendapat mayoritas adalah untuk tidak memerangi mereka, sedangkan pendapatnya radhiyallahu ‘anhu berbeda karena mereka telah kehilangan sifat dasar yang tanpanya syarat Islam tidak terpenuhi, yaitu pengingkaran mereka terhadap zakat dan tidak membayarnya. Peristiwa-peristiwa selanjutnya membuktikan kebenaran pandangannya dan menegaskan kebenaran keputusannya. Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu yang termasuk di antara yang menentang Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu dalam memerangi orang-orang murtad ini, mengakui kesalahan pendapat yang menentang.
Khalifah dan seluruh anggota kekuasaan umum berkewajiban sebagai prinsip umum untuk mengikuti hasil musyawarah yang diberikan oleh kaum muslimin selama tidak ada alasan serius dan kuat yang menyebabkan pengabaian hasil musyawarah tersebut. Khalifahlah yang memutuskan adanya alasan yang menyebabkan pengabaian ini, dan ia sendirilah yang menanggung akibat dari keputusan yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ini. Di sisi lain, ia juga tidak wajib mengikuti pendapat minoritas, kecuali jika ia memiliki alasan kuat bahwa pendapat minoritas adalah pendapat yang sesuai dengan kepentingan umum masyarakat Islam. Dan jika khalifah mengambil pendapat minoritas, maka ia juga yang menanggung sendiri tanggung jawab atas pelanggaran terhadap pendapat mayoritas, jika kemudian ternyata ia keliru dalam mengikuti pendapat tersebut. Dan jika khalifah mengambil pendapat mayoritas, maka ia tidak bertanggung jawab jika kemudian ternyata pendapat tersebut tidak benar, karena kesalahan di sini tidak ditanggung oleh khalifah, melainkan ditanggung oleh seluruh umat. Jika mereka—yaitu ahli musyawarah—keliru, maka merekalah yang keliru, dan jika benar, maka merekalah yang benar. Secara logika tidak boleh khalifah atau siapapun yang menjalankan kekuasaan umum menanggung kesalahan mayoritas ahli musyawarah, yang menurut sifat syarat-syarat yang harus dipenuhi pada mereka adalah para ulama dan orang-orang terbaik umat.
Al-Qurthubi menukil pendapat yang dinisbatkan kepada salah seorang cendekiawan yang berkata: Seorang cendekiawan berkata: “Aku tidak pernah salah jika suatu urusan menarik perhatianku, aku bermusyawarah dengan kaumku, lalu aku melakukan apa yang mereka lihat. Jika benar, maka merekalah yang benar, dan jika salah, maka merekalah yang salah.” Al-Qurthubi meriwayatkan di tempat lain: Seorang Arab Badui berkata: “Aku tidak pernah rugi sehingga kaumku rugi.” Ditanya: “Bagaimana itu?” Ia menjawab: “Aku tidak melakukan sesuatu sampai aku bermusyawarah dengan mereka.” Oleh karena itu dikatakan bahwa kesalahan dengan musyawarah lebih baik daripada kebenaran dengan bertindak sendiri dan sewenang-wenang.
Di samping kewajiban khalifah untuk mengikuti hasil musyawarah, hal ini selain mengangkat tanggung jawab khalifah, pada saat yang sama juga mendidik umat dengan pendidikan politik yang benar dan membuat mereka menyadari kesalahan ini di masa depan. Ini jauh lebih baik daripada bekerja dengan pendapat penguasa meskipun benar, karena menjadikan pendapat hanya milik penguasa sendiri adalah pembenaran untuk kesewenang-wenangan dan kediktatoran yang tidak diakui oleh fiqih Islam. Terlebih lagi, kesalahan umat dalam hal ini adalah perkara langka yang jarang terjadi, karena sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan,” dan sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka ia baik di sisi Allah,” sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Ikutilah sawad al-a’zham (mayoritas terbesar),” dan sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hendaklah kalian berpegang pada jama’ah dan ‘ammah (masyarakat umum).”
Maka dari itu, komitmen pada pendapat ulama dan fuqaha umat akan selalu dan selamanya mengarah pada pendapat yang benar dalam sebagian besar urusan.
Musyawarah dan Prinsip Kedaulatan Umat
Kini kita berbicara tentang musyawarah dan prinsip kedaulatan umat. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa prinsip musyawarah dalam Islam mengandung pengambilan prinsip kedaulatan umat. Mereka mendasarkan pendapat ini pada beberapa dalil dan ayat-ayat Al-Qur’an yang mereka yakini dapat diambil kesimpulan dari maknanya untuk mendukung pendapat mereka. Berikut ini akan kami sebutkan berbagai dalil yang mereka gunakan, kemudian kami akan mengomentari dan membahasnya:
Pertama: Para ulama tersebut mengatakan bahwa umat dalam Islam adalah pemilik hak untuk mengangkat kepala negara, dan mereka juga memiliki hak untuk memberhentikannya dari jabatannya jika mereka melihat kemaslahatan umum dalam hal itu. Ini berarti bahwa kepala negara memperoleh kekuasaannya dari umat, dan umat dengan demikian dianggap sebagai sumber kekuasaan dan pemilik kedaulatan. Hubungan antara umat dan kepala negara yang mereka pilih adalah hubungan kontraktual, yaitu didasarkan pada ide kontrak sosial. Hubungan kontraktual ini terlihat dalam perwakilan ahlul halli wal ‘aqdi atas umat dalam membaiat kepala negara. Ahlul halli wal ‘aqdi pada kenyataannya mewakili umat yang merupakan pemilik kedaulatan.
Kedua: Para ulama ini berhujjah dengan beberapa ayat Al-Qur’an dan beberapa hadits Nabi yang mulia yang mereka anggap dapat diambil dalil darinya bahwa Islam mengambil prinsip kedaulatan umat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (An-Nisa: 135) Seolah-olah Allah Tabaraka wa Ta’ala menyeru umat: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.” Dan firman-Nya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Ma’idah: 2) Mereka mengambil kesimpulan dari ayat-ayat ini bahwa Allah Tabaraka wa Ta’ala menyeru seluruh kaum muslimin, dan mereka menyimpulkan dari itu bahwa umat adalah dasar kekuasaan sebagaimana yang mereka katakan.
Di samping kedua ayat ini, dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat lain yang kita dapati seruan di dalamnya ditujukan kepada umat Islam, yang darinya kita dapat mengambil dalil bahwa umat itulah yang memikul tanggung jawab untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala, memelihara kepentingan-kepentingan umum, dan dengan demikian umat dianggap sebagai sumber kedaulatan dan dasar kekuasaan dari sudut pandang Islam.
Ustadz besar Abul A’la Al-Maududi mengaitkan antara prinsip musyawarah dalam Islam dengan prinsip kedaulatan umat secara penuh. Kita lihat ia berkata: “Prinsip kedaulatan umat yang dinyatakan oleh Islam dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: ‘Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu’ dan dalam firman-Nya: ‘Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka’ adalah prinsip yang dicapai oleh kemanusiaan setelah perjuangan panjang. Oleh karena itu, prinsip ini harus terus berlanjut dalam naungan negara Islam.” Ustadz Al-Maududi juga berkata: “Keberadaan parlemen sebagai otoritas pengawasan di samping fakta bahwa penguasa sendiri dipilih melalui rakyat dalam negara Muslim, menjamin kedaulatan umat.”
Adapun hadits-hadits Nabi yang mulia, mereka menyebutkan—yaitu mereka yang mengaitkan antara musyawarah dengan prinsip kedaulatan umat—kami katakan mereka menyebutkan dari hadits-hadits dalam hal ini sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.” Hadits mulia ini menunjukkan menurut pendapat mereka bahwa umat Islam ketika bersepakat pada suatu pendapat tertentu, maka itu adalah kebenaran dan harus diambil, karena ia dikeluarkan oleh pemilik hak kedaulatan, yaitu umat.
Bantahan terhadap Pendapat yang Mengaitkan Musyawarah dengan Prinsip Kedaulatan Umat
Kami katakan: Upaya untuk mengaitkan antara prinsip musyawarah sebagaimana yang dibawa oleh Islam dengan prinsip atau teori kedaulatan umat dengan pengertiannya yang dikenal dalam fiqih konstitusional modern, tidak lain adalah upaya untuk menciptakan masalah fiqih yang sangat rumit. Tampak bagi kami bahwa yang mendorong para ulama tersebut untuk mencoba mengaitkan kedua prinsip tersebut—yaitu musyawarah dan kedaulatan umat—adalah upaya peniruan dan kecenderungan terpengaruh oleh pendapat para ulama dan fuqaha Barat, serta kekhawatiran para ulama tersebut bahwa pemikiran fiqih Islam akan dikritik karena tidak ada tempat bagi setiap teori politik atau konstitusional kuno atau modern. Seolah-olah dengan itu mereka mengikuti istilah-istilah yang datang kepada kita dari para ahli hukum Barat.
Namun upaya untuk menghubungkan antara kedua prinsip tersebut dan menciptakan hubungan di antara keduanya sebenarnya adalah upaya yang tidak didasarkan pada fondasi ilmiah yang kuat, dan dapat dijawab terhadap dasar-dasar yang telah dikemukakan sebelumnya untuk membenarkannya dengan hal-hal berikut:
Pertama: bahwa prinsip kedaulatan rakyat adalah buah dari teori yang baru muncul, berasal dari Prancis. Philippo orang Prancis adalah pemikir pertama yang berbicara tentang ide kedaulatan rakyat, yaitu pada tahun 1414 Masehi, ketika ia menyatakan di hadapan badan perwakilan yang mewakili kelas-kelas sosial pada periode sebelum Revolusi Prancis, dan itu ketika membahas masalah perwalian terhadap Raja Charles VIII yang masih di bawah umur, ia menyatakan bahwa rakyat Prancis sendiri yang berdaulat, dan merekalah yang memberikan hak ini kepada raja. Selama raja masih di bawah umur, maka rakyat Prancis atau majelis perwakilan yang mewakili mereka berhak untuk menjadi wali atasnya. Ini dengan catatan bahwa para pangeran Prancis pada saat itu menganggap bahwa mereka sendirilah yang berhak mengatur perwalian terhadap raja yang masih di bawah umur, bukan rakyat Prancis. Ketika Revolusi Prancis terjadi, ia menetapkan bahwa kedaulatan hanya untuk rakyat. Maka tidak benar pendapat jika kita mencoba mengembalikan akar teori tersebut kepada hukum-hukum Islam dan pemikiran Islam klasik. Kita tidak menemukan dalam karya-karya para fuqaha dan pemikir Muslim klasik satupun rujukan tentang teori kedaulatan rakyat, atau mengandalkan konsep atau akibat-akibatnya. Kita juga tidak menemukan pada mereka upaya untuk menghubungkan antara prinsip musyawarah dengan prinsip kedaulatan rakyat, seperti yang dilakukan oleh para ulama modern di zaman kita sekarang.
Kenyataannya kita menemukan bahwa konsep modern tentang prinsip kedaulatan rakyat tidak jelas kecuali dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis, yaitu deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Nasional pada 26 Agustus 1789, dan pasal ketiganya menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan tempat kedudukannya. Prinsip kedaulatan rakyat telah diulang dalam konstitusi 1791, kemudian disebutkan setelah itu dalam konstitusi tahun ketiga pada 1795. Demikianlah Revolusi Prancis menjadikan teori kedaulatan rakyat sebagai kaidah konstitusional umum yang mulai tersebar dan meluas di sebagian besar negara.
Kedua: bahwa konsep umat dalam Islam sangat berbeda dengan konsep umat dalam fikih konstitusional modern. Sementara fikih ini mendefinisikannya sebagai sekelompok orang yang menetap di wilayah tertentu di bumi, dan antar individu-individunya terdapat keinginan bersama untuk hidup bersama, maka kita menemukan bahwa umat dalam Islam memiliki makna lain yang berbeda dari konsep tersebut. Terkadang yang dimaksud dengan lafaz umat hanya sebagian individunya saja, bukan semua individu, dan itu jelas dari firman Allah Ta’ala: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104). Di sini kita menemukan bahwa firman Allah Ta’ala: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang” dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan umat bukanlah semua individu Muslim, melainkan ditujukan kepada sebagian dari mereka saja, dengan bukti adanya lafaz “di antara kamu”.
Pendapat yang rajih menurut para ulama tafsir bahwa kelompok dari umat yang Allah kehendaki untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang mungkar adalah kelompok orang-orang mukmin. Jelas bahwa umat dengan makna ini, yaitu sebagai bagian saja dari kelompok manusia, adalah hal yang tidak sesuai dengan konsep umat yang dikenal dalam teori kedaulatan rakyat dalam hukum positif dengan makna fikihnya yang modern. Bahkan untuk ayat yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa Islam mengambil prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip musyawarah, yaitu firman Allah Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu” (An-Nisa: dari ayat 135), kita menemukan bahwa khitab dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dan mereka adalah sedikit dari kaum Muslim, bukan semua individu umat dengan makna yang dikenal.
Di antara bantahan juga terhadap teori ini yang menghubungkan antara musyawarah dengan prinsip kedaulatan rakyat, kami katakan: bahkan untuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari prinsip kedaulatan rakyat, kita menemukan perbedaan besar antara pemikiran Islam dan pemikiran konstitusional tentang masalah ini. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah kehendak umat memiliki kekuasaan umum atau kedaulatan yang tidak ada kekuasaan tertinggi lain yang lebih tinggi darinya. Wujud dari kekuasaan tersebut adalah undang-undang yang mengekspresikan kedaulatan rakyat. Tetapi bagaimana kita menerapkan itu dalam Islam? Apakah bisa legislasi dalam Islam adalah ekspresi dari kehendak umat yang mayoritas individunya hanya Muslim secara nama saja? Ataukah sebaliknya, legislasi justru pertama-tama mengekspresikan hukum-hukum syariat Islam dalam Islam, dan bahwa hukum-hukum inilah yang harus memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi? Oleh karena itu kita menemukan bahwa sungguh aneh beberapa ulama dan pemikir kita mencoba memasukkan di bawah bendera Islam teori yang asing baginya, pada saat kita menemukan beberapa ahli fikih konstitusional terkemuka di sini dan di Barat menyerang teori tersebut, yaitu teori kedaulatan rakyat, dan berpendapat bahwa kondisi historis yang menyebabkan penurunannya telah menjadi bagian dari sejarah, artinya kita tidak lagi membutuhkannya di zaman kita sekarang, selain itu bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang sebagai ancaman bagi kebebasan.
Kesimpulannya, tidak benar menghubungkan antara prinsip musyawarah dalam Islam dengan prinsip atau teori kedaulatan rakyat. Sesungguhnya Islam tidak membutuhkan pembangkitan masalah atau problem tersebut yang pembahasannya tidak menghasilkan solusi dari masalah-masalah dalam pemikiran Islam, melainkan justru menciptakan masalah baru yang tidak dibutuhkan oleh pemikiran tersebut.
Kita berbicara sekarang juga tentang prinsip musyawarah dan sistem pemilihan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam mengandung pengambilan sistem pemilihan umum, yaitu pendapat ini berpandangan bahwa prinsip musyawarah mengakibatkan kewajiban mengambil sistem pemilihan umum. Sebagian ulama berpendapat bahwa prinsip musyawarah dalam Islam mengandung pengambilan sistem pemilihan umum, dan dalam hal ini mereka mendasarkan pada beberapa hujjah dan dasar, serta ayat-ayat dari Al-Quran dan hadits-hadits dari Sunnah yang mulia. Kami akan menanggapi pendapat ini setelah kami paparkan terlebih dahulu dengan dalil-dalil dan dasarnya.
Profesor besar Abul A’la Al-Maududi membedakan antara hak memilih dengan hak mencalonkan diri. Adapun kelayakan untuk melaksanakan hak memilih, ia berpendapat bahwa setiap penduduk negara yang jumlahnya mencapai jutaan dan ratusan juta memilikinya, dan ia tidak mensyaratkan untuk kelayakan ini hal yang menghalangi penerapan prinsip pemilihan umum. Ia menyebutkan bahwa beberapa pasal konstitusi praktis cukup untuk menjelaskan kriteria dan syarat kelayakan tersebut.
Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah Allah Ta’ala tentang musyawarah dalam Al-Quran dalam dua ayat “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” dan firman-Nya: “dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” (Asy-Syura: dari ayat 38), serta apa yang Allah perintahkan tentang amar makruf dan nahi mungkar dalam ayat ini: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah” (Ali Imran: dari ayat 110), kemudian dalam firman-Nya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104), mereka berpendapat bahwa ayat-ayat ini semua dapat diambil darinya dalil bahwa Islam ketika menetapkan prinsip musyawarah, telah menjadikan akibat dari prinsip ini pengambilan sistem pemilihan umum. Karena khitab Allah Ta’ala dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa ditujukan kepada seluruh umat. Musyawarah adalah di antara semua individunya, karena firman-Nya: “dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka”, dan amar makruf nahi mungkar dikhususkan untuk umat dengan semua individunya.
Tetapi kami tanggapi pendapat ini dan kami katakan, menurut pendapat kami bahwa itu adalah pendapat yang tidak tepat, karena beberapa alasan:
Pertama: telah kami sebutkan sebelumnya bahwa perintah Allah Ta’ala tentang musyawarah tidak harus menghasilkan bahwa musyawarah untuk semua individu umat atau seluruh kaum Muslim. Kita telah melihat bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para Khalifah Rasyidin setelah beliau bermusyawarah dengan unsur-unsur dan golongan tertentu. Seseorang biasanya tidak bermusyawarah kecuali dengan orang yang layak memberikan pendapat yang benar. Al-Quran kita temukan telah berulang di dalamnya ayat-ayat yang menyatakan bahwa pendapat, keutamaan, dan ilmu bukanlah sifat kebanyakan manusia secara umum. Maka tidak benar jika musyawarah untuk mayoritas manusia, melainkan kita harus kembali dalam musyawarah kepada ahli pendapat dan hikmah, dengan dalil firman Allah Ta’ala: “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)” (An-Nisa: dari ayat 83). Dan Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah: ‘Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'” (Az-Zumar: dari ayat 9).
Kedua: di antara bantahan kepada mereka juga kami katakan kepada mereka: adapun tentang dalil Profesor Al-Maududi dan lainnya dengan firman Allah Ta’ala: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” bahwa ayat itu mewajibkan pengambilan sistem pemilihan umum, maka itu adalah dalil yang tidak tepat. Hukum dalam hal itu adalah tafsir ayat ini dan apa yang dituju seperti yang disebutkan para mufassir. Oleh karena itu kami katakan kepada yang berdalil demikian bahwa mazhab Muktazilah didasarkan pada lima prinsip dasar yang dikenal, salah satunya: amar makruf dan nahi mungkar. Meskipun demikian, kita tidak menemukan para Muktazilah itu menafsirkan ayat ini dengan cara yang menjadikan amar makruf dan nahi mungkar wajib bagi semua orang, dengan bukti bahwa kita menemukan seorang ulama besar dari para mufassir mereka, yaitu Imam Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat ini dengan tafsir yang sama sekali jauh dari makna yang dijadikan dasar oleh yang berdalil dengannya atas kewajiban Islam untuk sistem pemilihan umum. Ia berkata: sesungguhnya nahi mungkar termasuk fardhu kifayah bukan fardhu ‘ain, karena tidak layak untuk itu kecuali orang yang mengetahui bagaimana mengatur urusan dalam menegakkannya dan bagaimana melaksanakannya. Kemudian sesungguhnya melihat ayat ini tidak memberikan petunjuk pada keumuman dan kemutlakan. Yang melakukan makruf dan nahi mungkar, ayat ini berkata: “Dan hendaklah di antara kamu ada”, dan “di antara kamu” berarti sebagian, bukan seluruh umat atau semua orang. Kalau Allah Ta’ala menghendaki amar makruf dan nahi mungkar wajib bagi semua orang, pasti disebutkan.
Dan jika semua orang akan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, lalu siapa yang akan mereka suruh, dan siapa yang akan berhenti? Kita menemukan pendapat seperti ini juga pada Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, dia berkata dalam tafsir ayat yang sama: Sesungguhnya tugas menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan kewajiban setiap individu menurut kemampuannya, yaitu menurut kesanggupannya. Namun yang dimaksud dengan ayat ini adalah khususnya para sahabat, dan khususnya para perawi yaitu para mujtahid dan ulama.
Dari uraian di atas kita melihat kekeliruan pendapat sebagian ulama yang berpandangan bahwa Islam mewajibkan penerapan sistem pemilihan umum, karena dianggap sebagai konsekuensi atau hasil dari prinsip syura yang diwajibkan Islam. Yang perlu diperhatikan adalah jika dalam Alquran dan Sunah tidak ada yang mewajibkan penerapan sistem pemilihan umum, maka tidak ada hal yang menghalangi negara Islam untuk menerapkan sistem ini jika kemaslahatan menghendakinya. Karena perincian sistem-sistem ketatanegaraan dan cara-cara pelaksanaan syura adalah termasuk perkara yang berbeda sesuai perbedaan kondisi sosial umat. Maka merupakan hikmah dan kemudahan bagi manusia bahwa kita dapati Islam setelah menetapkan syura telah menyerahkan kepada setiap umat untuk menyusun sistem-sistem perinciannya sesuai dengan keadaan mereka dan selaras dengan kemaslahatan mereka.
Maka ada perbedaan besar antara pendapat yang kami tentang, yaitu yang menyatakan wajibnya sistem pemilihan umum di setiap zaman dan tempat, dengan pendapat yang kami sebutkan bahwa tidak ada yang menghalangi kaum muslimin untuk menerapkan sistem pemilihan umum jika mereka melihat kemaslahatan di dalamnya.
Pendapat yang kami kemukakan menjadikan sistem pemilihan umum sebagai masalah agama yang wajib, adapun yang kami dukung adalah menganggap sistem ini sebagai masalah sosial politik. Dengan demikian sifat kaku terlepas dari syariat Islam, dan jelas esensinya yang dalam hal muamalat bercirikan fleksibilitas, mengikuti perkembangan dan memperhatikan kemaslahatan.
Akhirnya, jika kita mengedepankan kebenaran dan ketepatan, maka kita akan menemukan bahwa sistem yang paling dekat dengan prinsip syura dalam Islam adalah sistem pemilihan yang disebut pemilihan terbatas, bukan sistem pemilihan umum. Arah ini didukung oleh sejumlah ulama dan peneliti dalam masalah-masalah ketatanegaraan dan Islam. Profesor besar Barthelemy berpandangan bahwa penyerahan urusan umat kepada elite pilihan dari putra-putranya tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan antar warga negara, bahkan hal itu sesuai dengan definisi yang dikenal dari Aristoteles. Dia berkata: Kesetaraan adalah tidak menempatkan dua hal yang tidak setara pada kedudukan yang sama.
Kita telah melihat dalam pembahasan tentang syura dalam Islam bahwa yang diperhatikan dalam menentukan ahli syura adalah sifat-sifat mereka, bukan jumlah mereka, dan bahwa banyaknya bilangan dan mayoritas tidak berarti keunggulan sepenuhnya. Sebagaimana kata Profesor besar Abu A’la Al-Maududi: Sesungguhnya Islam tidak menjadikan banyaknya jumlah sebagai timbangan kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Katakanlah: ‘Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu.'” (Surah Al-Maidah: 100). Bahkan sebaliknya kita dapati Alquran Al-Karim selalu memperingatkan kita dari pendapat mayoritas, karena tidak selalu benar bahkan bisa mengarah pada kesesatan dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (Surah Al-An’am: 116).
Namun perlu diperhatikan bahwa satu-satunya pembatasan yang diakui Islam berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak politik seperti pemilihan adalah pembatasan kecakapan semata, tanpa memandang sama sekali pembatasan lain seperti asal-usul, profesi atau harta.
Kami cukupkan sampai di sini, saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah atas kalian.
Pelajaran 9: Kaidah-kaidah Lain Sistem Islam yaitu Keadilan, Tanggung Jawab Penguasa, Hak dan Kebebasan, Kekuasaan Umat dalam Mengawasi Penguasa
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Kaidah-kaidah Sistem Politik dalam Islam (4)
Keadilan
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, pemimpin kami Muhammad, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas tentang syura dalam Islam sebagai kaidah dari kaidah-kaidah sistem politik dalam Islam, dan telah kami jelaskan tingkat keterkaitannya dengan teori kedaulatan umat, dan tingkat keterkaitannya dengan prinsip kewajiban pemilihan umum bagi semua orang.
Setelah selesai membahas syura, kita akan membahas kaidah lain dari kaidah-kaidah sistem politik dalam Islam, yaitu keadilan. Keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan maka akan tegak, meskipun pemiliknya tidak memiliki bagian di akhirat. Dan kapan pun tidak ditegakkan dengan keadilan maka tidak akan tegak, meskipun pemiliknya memiliki iman yang akan dibalas dengannya di akhirat. Oleh karena itu peringatan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firman-Nya: “Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Surah An-Nisa: 58). Teks ini datang dalam konteks kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, taat kepada Rasul – semoga shalawat dan salam Allah atasnya – dan ulil amri dari para wali dan penguasa kaum muslimin. Maka ini adalah teks yang tegas dalam masalah yang harus dipatuhi dan diwujudkan dalam semua aspek pemerintahan dan politik Islam, sehingga tidak boleh meninggalkannya atau melanggarnya.
Oleh karena itu ada dorongan untuk itu dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (Surah An-Nahl: 90) dan firman-Nya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Surah Al-Maidah: 8). Sesungguhnya maksudnya adalah bahwa penguasa diperintahkan untuk memerintah di antara semua manusia dengan adil, sama saja dalam hal itu antara yang kuat dan lemah, kaya dan miskin, muslim dan non-muslim, teman dan musuh. Mengingat pentingnya hal ini dalam kelurusan kehidupan bangsa-bangsa dan masyarakat, serta sistem pemerintahan dan politik apa pun jenisnya, dikatakan: Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan yang zalim meskipun muslim. Dan dikatakan: Dunia bertahan dengan keadilan dan kekafiran, dan tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam.
Jika engkau memahami hal itu, engkau akan yakin bahwa banyak keburukan yang menimpa negara-negara adalah akibat dari bencana kezaliman yang menyebabkan hilangnya hak-hak dan kehilangan kepercayaan antara penguasa dan yang diperintah, serta merebaknya manifestasi negatif dan penyakit-penyakit sosial yang terkait dengan kekuasaan yang rusak, seperti suap, pengkhianatan amanah, berdagang dengan kepentingan rakyat, dominasi frustasi dan keputusasaan atas jiwa-jiwa. Dan ini bisa membuka jalan agar masyarakat berada di ambang kehancuran, dan menjadi ajang yang siap untuk terjadinya fitnah dan meletusnya pertumpahan darah di antara anak-anak agama dan tanah air yang satu.
Mungkin salah satu manifestasi keadilan yang paling menonjol adalah penerapan keadilan dalam hubungan penguasa dengan yang diperintah. Ini adalah salah satu bukti terkuat komitmen terhadap keadilan. Jika negara menerapkan hal itu dan menetapkannya dalam kebijakannya, tidak diragukan lagi bahwa mudah untuk menyimpulkan bahwa negara ini adalah negara yang adil dalam semua aspek kebijakannya. Karena komitmen terhadap berlakunya keadilan antara pemimpin dan salah satu anggota rakyat adalah bukti nyata tentang berlakunya hal itu di tingkat-tingkat yang lebih rendah pada tingkat negara.
Keadilan telah menempati aspek penting dari aspek-aspek manhaj Islam di tingkat atas dan bawah. Tidak ada bukti yang lebih jelas dari penerapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hal itu pada dirinya sendiri. Diriwayatkan dari beliau: “Bahwa beliau keluar saat sakit yang menyebabkan wafatnya, keluar di antara Al-Fadhl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib hingga duduk di atas mimbar, kemudian berkata: Wahai manusia, barangsiapa yang punggungnya telah aku cambuk, maka ini punggungku maka hendaklah dia mengqishash dariku. Dan barangsiapa yang kehormatannya telah aku caci, maka ini kehormatanku maka hendaklah dia mengqishash dariku. Dan barangsiapa yang hartanya telah aku ambil, maka ini hartaku maka hendaklah dia mengambil darinya. Dan janganlah takut akan kebencian dariku, karena itu bukan dari perilakuku. Ketahuilah bahwa orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang mengambil dariku hak jika memang ada haknya, atau memaafkanku sehingga aku bertemu Tuhanku dalam keadaan jiwa yang tenang. Kemudian beliau turun, shalat Zhuhur, kemudian kembali ke mimbar dan mengulangi perkataannya yang pertama.” Sesungguhnya analisis perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ini dan penjelasan aspek-aspek keadilan di dalamnya menunjukkan kepadamu bahwa keadilan itu menyeluruh, bukan khusus pada aspek tertentu dalam hubungan penguasa dengan salah satu anggota rakyatnya. Keadilan mencakup aspek-aspek berikut:
1 – Hukuman badan, dan ini jelas dalam sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam: “Barangsiapa yang punggungnya telah aku cambuk, maka ini punggungku maka hendaklah dia mengqishash dariku.”
2 – Hukuman yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat, dan ini dipahami dari sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam: “Dan barangsiapa yang kehormatannya telah aku caci, maka ini kehormatanku maka hendaklah dia mengqishash dariku.”
3 – Hukuman harta, dan itu dalam sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam: “Dan barangsiapa yang hartanya telah aku ambil, maka ini hartaku maka hendaklah dia mengambil darinya.”
Kemudian engkau memahami dari perkataan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam puncak ketaatan dalam menunaikan kewajiban keadilan, yang terlihat jelas dalam sabda beliau: “Ketahuilah bahwa orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang mengambil dariku hak jika memang ada haknya, atau memaafkanku sehingga aku bertemu Tuhanku dalam keadaan jiwa yang tenang.” Dan ini membuat seseorang yakin bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam menekankan kewajiban kaum muslimin untuk menuntut hak-hak mereka atau memaafkannya jika jiwa mereka rela dengan itu.
Mengingat nilai-nilai luhur yang ditanamkan keadilan pada pemimpin dan rakyat, maka para khalifah kaum muslimin adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam menerapkan keadilan di antara orang-orang yang mereka pimpin. Mereka berusaha keras dalam hal itu dengan menyelisihi dorongan hawa nafsu dan mengikuti bisikan jiwa manusiawi kepada manusia untuk menzalimi orang yang dibencinya, serta berlebihan dalam bersikap ramah kepada orang yang dicintainya, dan keduanya menyimpang dari keadilan. Carilah hal itu dalam riwayat hidup mereka, engkau akan mendapatinya jelas dan nyata tanpa kesamaran, dan bahwa modal mereka dalam berusaha mencari keadilan dan berpegang teguh padanya melampaui modal negara-negara lain secara keseluruhan.
Diriwayatkan dalam hal itu bahwa Umar bin Al-Khaththab berkata kepada Abu Maryam As-Sululi, dan dia adalah orang yang membunuh saudaranya Zaid bin Al-Khaththab: Demi Allah, aku tidak mencintaimu. Maka orang itu berkata kepadanya: Apakah hal itu menghalangiku dari hak? Maksudnya: ketidakcintaanmu kepadaku apakah menjadi sebab engkau mencegahku dari hak yang telah ditetapkan Islam untukku? Apakah hal itu menghalangiku dari hak? Maka dia berkata: Tidak. Maksudnya: kebencianku kepadamu dan ketidakcintaanku kepadamu tidak berpengaruh sama sekali terhadap hak-hak yang telah ditetapkan Islam untukmu. Maka orang itu berkata kepadanya: Tidak masalah kalau begitu, hanya wanita yang bersedih karena cinta. Dalam kisah ini kita dapati bahwa penguasa meskipun dia dirugikan dan tertekan karena pembunuhan saudaranya, dan meskipun ada dendam dalam dadanya terhadapnya, namun orang itu tidak peduli dengan semua itu. Dia merasa tenang dengan keadilan sebagai salah satu sifat manhaj Islam. Penguasa tidak bisa tidak kecuali berdiri di hadapannya dengan sikap orang yang beribadah di mihrabnya, taat kepada perintah-perintahnya. Dan orang yang lain tidak perlu menunggu lama untuk menjawab khalifah yang memiliki kekuasaan di tangannya ketika dia terus terang mengatakan bahwa dia membencinya, dia menjawabnya dengan nada orang yang yakin bahwa penegakan keadilan lebih terjamin baginya daripada kekuatan dan kekuasaan khalifah. Oleh karena itu jawabannya dengan sederhana “tidak masalah” artinya tidak takut dari itu. Dan bahaya apa dari rakyat yang mengetahui manhaj kebenaran dan penguasa yang paling bersemangat dalam menerapkan dan berkomitmen padanya.
Keadilan dianggap sebagai tujuan umum bagi semua legislasi yang dibuat manusia untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, dan hikmah utama yang mengelilinginya berbagai undang-undang. Oleh karena itu dikatakan: Bahwa setiap undang-undang harus dan pasti bersandar pada sesuatu dari keadilan.
Kita menemukan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum disebut sebagai lembaga keadilan. Pengadilan disebut sebagai rumah keadilan, dan dikatakan menteri kehakiman, bukan menteri hukum. Meskipun pengadilan menerapkan hukum, tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Dari sini, hukum pada akhirnya hanyalah sarana untuk mewujudkan keadilan. Jika terjadi penerapan hukum yang bertentangan dengan keadilan karena satu dan lain hal, maka hakim harus melakukan intervensi untuk meringankan beban putusan hukum atau melengkapi kekurangannya atau bahkan mengenyampingkannya dalam beberapa kasus, dan menetapkan solusi yang sesuai dengan keadilan.
Perkara ini berbeda dalam Syariat Islam dibandingkan dengan perundang-undangan buatan manusia, terkait dengan penetapan keadilan sebagai tujuan yang tidak dipengaruhi oleh politik, tidak dipengaruhi oleh kepentingan, dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu pribadi para penguasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan diri-Nya untuk berlaku adil kepada makhluk-Nya, dan mewajibkan mereka untuk berlaku adil dalam interaksi mereka satu sama lain. Oleh karena itu, kemukjizatan Al-Quran terwujud dalam ayat-ayat mulia yang membicarakan tentang keadilan, menjadikannya nilai suci yang harus selalu dicapai, apa pun kerugian yang diduga akan terjadi darinya.
Syekh Abu Zahrah berkata dalam pengertian ini: Sesungguhnya ciri Islam adalah keadilan. Artinya: di antara hal-hal yang menjadi sifat Islam adalah keadilan. Setiap koordinasi sosial yang tidak berdiri di atas keadilan akan runtuh, betapa pun kuatnya organisasi di dalamnya, karena keadilan adalah pilar, sistem, dan koordinasi yang benar bagi setiap bangunan. Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memperlakukan manusia pada hari kiamat dengan keadilan sempurna, dan tidak akan meninggalkan sesuatu pun tanpa perhitungan. Dia akan membalas orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat dengan adil, berdasarkan firman-Nya: “Dan Kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (balasan)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.” (Surat Al-Anbiya: 47). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (Surat Az-Zalzalah: 7-8). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala mewasiatkan kepada para rasul-Nya dan hamba-hamba-Nya agar menegakkan keadilan di bumi, maka Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (keadilan) karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.” (Surat Al-Maidah: 8). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Surat An-Nahl: 90). Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, maka berlaku adillah sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Surat Al-An’am: 152).
Demikianlah ayat-ayat sebelumnya menampilkan keadilan sebagai nilai moral yang luhur, yang harus diikuti dalam kehidupan, dalam muamalat, dan dalam penetapan hukum secara umum. Allah Tabaraka wa Ta’ala mengingatkan kita tentang pentingnya memutuskan dengan adil dalam perselisihan dan perkara dalam banyak ayat lainnya, seperti firman-Nya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (Surat An-Nisa: 58). Dan Dia juga berfirman: “Dan jika kamu memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Surat Al-Maidah: 42).
Dalam bidang hubungan antara negara Islam dan negara-negara lain, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Surat Al-Mumtahanah: 8).
Bentuk-bentuk Keadilan dalam Al-Quran
Kenyataannya, menghitung semua yang disebutkan dalam Al-Quran tentang keadilan dan pentingnya mencapainya dalam setiap sistem perundang-undangan adalah hal yang sulit. Saya tidak berlebihan jika mengatakan: bahwa semua ayat mulia yang menggambarkan gaya hidup bagi manusia dan menetapkan metode untuk berusaha di bumi terkait dengan keadilan dan menjadikannya tujuan utama. Oleh karena itu, kita cukup menyebutkan contoh-contoh dari ayat-ayat ini yang disebutkan terkait beberapa bentuk muamalat.
Mari kita berbicara tentang keadilan sosial. Pembagian keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan kompensasi atau pertukaran adalah pembagian terpenting yang ditetapkan untuk keadilan. Kita memiliki keadilan distributif dan keadilan kompensasi atau pertukaran. Bentuk pertama terwujud dalam distribusi kedudukan dan harta, dan semua yang dapat dibagi di antara mereka yang diakui oleh konstitusi. Harus ada semacam distribusi proporsional untuk keuntungan sosial dan juga beban kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan tingkat kontribusi mereka dalam menanggung beban masyarakat.
Kita menemukan Al-Quran mengekspresikan bentuk keadilan ini dalam banyak ayat mulia, di antaranya firman Allah Ta’ala: “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.” (Surat Al-Hasyr: 7). Berdasarkan ayat ini, Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu melarang pembagian tanah-tanah yang telah ditaklukkan kepada para penakluk.
Rinciannya adalah ketika negara Islam berkembang dan banyak wilayah baru bergabung melalui penaklukan, Umar radhiyallahu anhu berbeda pendapat dengan para sahabat tentang cara pengelolaan tanah, yaitu tanah yang direbut oleh kaum muslimin. Sementara mayoritas cenderung membaginya di antara para penakluk sesuai dengan ayat tentang ghanimah (rampasan perang): “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.” (Surat Al-Anfal: 41). Ayat ghanimah ini berarti seperlima untuk Allah dan Rasul, dan empat perlima untuk yang merebut. Ini adalah ayat ghanimah. Kita katakan: mayoritas cenderung membagi tanah-tanah ini di antara para penakluk sesuai dengan ayat ghanimah yang telah kita sebutkan. Namun dia, yaitu Umar bin Al-Khaththab, berpendapat bahwa tanah tidak boleh dibagikan kepada para penakluk atau pejuang, tetapi harus tetap di tangan pemiliknya dan mereka membayar kharaj (pajak tanah) agar menjadi sumber keuangan bagi negara Islam yang dapat digunakan untuk belanja umum negara Islam.
Kita katakan: dia mendasarkan pendapatnya pada ayat-ayat mulia yang telah kita sebutkan, dan menolak pembagian serta menetapkan kaidah yang intinya adalah membiarkan tanah untuk pemiliknya dan mengenakan kharaj padanya agar dapat dimanfaatkan untuk membiayai fasilitas umum bagi seluruh kaum muslimin. Dia radhiyallahu anhu memahami nash ini sebagai mengutamakan kepentingan umat Islam yang menghendaki agar tidak ada sekelompok orang yang menguasai kepemilikan tanah, karena itu bertentangan dengan keadilan dan nash Al-Quran: “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Dan nash Al-Quran yang melengkapi ayat yang disebutkannya ketika menyebutkan kelompok-kelompok yang berhak, dan menyebut di akhir mereka: “dan orang-orang yang datang sesudah mereka.” Umar bin Al-Khaththab terus membela pandangannya bahwa tanah harus tetap di tangan pemiliknya dan dikenakan kharaj seperti yang telah kita katakan. Dia membela pandangannya dengan mengatakan: “Bagaimana menurut kalian dengan benteng-benteng ini, harus ada orang-orang yang menjaganya?” Benteng berarti tempat-tempat di mana para tentara berada untuk membela negara Islam. “Bagaimana menurut kalian dengan kota-kota besar seperti Syam, Mesir, dan Kufah, harus ada pasukan yang mengisinya dan mengalirkan pemberian kepada mereka. Dari mana akan diberikan kepada mereka jika tanah-tanah dibagi?” Artinya jika dibagi di antara yang merebut. Demikianlah Umar bin Al-Khaththab menerapkan kaidah keadilan distributif, atau yang sekarang disebut keadilan sosial. Dia melihat perlunya umat Islam mendapatkan sumber daya yang dibelanjakan untuk yang membutuhkan di antara mereka, untuk mengurus kepentingan umum, dan mengelola fasilitas negara Islam. Dia mengutamakan kepentingan ini daripada kepentingan segelintir penakluk dan anak-anak mereka yang hasil tanah ini semuanya akan pergi kepada mereka tanpa sisa kaum muslimin. Dari sini dapat dikatakan bahwa kita menghadapi nash yang muhkam yang menetapkan perlunya semua orang mendapat manfaat dari harta publik, bukan hanya mereka yang ada saat pembentukannya, tetapi juga mereka yang datang sesudah mereka. Dapatkah kita membayangkan ada nash buatan manusia yang memperhatikan hal itu sekarang?
Sejujurnya saya tidak berpikir demikian. Kita juga melihat penerapan yang menunjukkan kejeniusan dini dan kemampuan untuk menembus hikmah dari hikmah-hikmah syariat Islam di masa ketika tidak ada sekolah, lembaga, atau universitas, tetapi itu adalah universitas Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan madrasah Al-Quran.
Mengenai bentuk keadilan lainnya, yaitu keadilan kompensasi atau pertukaran, ia memainkan peran korektif dalam hubungan yang terjadi antara individu dan menuntut agar tidak ada yang mengambil dalam kontrak dan transaksi lebih dari yang seharusnya. Berdasarkan ini dirumuskan perlunya keseimbangan finansial dan ekonomi dalam kontrak dan transaksi. Kita melihat tujuan ini juga jelas secara mengagumkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mulia.
Al-Quran melarang segala bentuk eksploitasi dalam transaksi dan mewajibkan kontrak berdiri di atas dasar yang seimbang. Tidak diragukan bahwa perhatian Al-Quran terhadap kesehatan transaksi dan keseimbangan antara pihak-pihaknya tidak tertandingi oleh perhatian proyek lain dalam hukum mana pun. Kita tidak akan lama membahas perundang-undangan Islam dalam hal ini, tetapi saya akan cukup dengan apa yang disebutkan tentang riba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Surat Al-Baqarah: 275). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala mempertegas celaan terhadap orang-orang yang memakan riba, maka Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Surat Al-Baqarah: 278-279).
Al-Quran membawa manusia ke puncak tanggung jawab dalam bidang ini, sehingga tidak membuat uang menghasilkan uang dalam hal keterlambatan pembayaran karena uzur, maka Dia berfirman: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan bertakwalah pada hari (ketika) kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).” (Surat Al-Baqarah: 280-281).
Dan ini berarti bahwa keadilan yang dituju oleh Islam adalah keadilan dalam semua bidang, keadilan dari sisi pemerintahan, keadilan dari sisi ekonomi dalam semua bidang. Islam sangat bersemangat agar ada keadilan di antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, mereka yang melakukan transaksi riba tidak ada keadilan di dalamnya, karena rentenir memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan tidak ada keadilan dalam apa yang dia ambil dan dalam apa yang dia berikan. Karena itu, kita dapati sikap Islam tegas demi mewujudkan keadilan tersebut dalam segala bentuknya, baik dalam ekonomi maupun dalam pemerintahan.
Tanggung Jawab Para Penguasa
Kemudian kita beralih sekarang untuk membahas kaidah lain dari kaidah-kaidah yang menjadi dasar sistem politik dalam Islam, yaitu tanggung jawab penguasa. Maka kita katakan: Sistem politik Islam berbeda dari semua sistem politik lainnya dengan menetapkan prinsip “tanggung jawab”, di mana tidak ada dalam Islam seseorang yang dapat terhindar dari tanggung jawab tersebut. Hal itu karena ketidakbertanggungjawaban berarti: bahwa orang yang tidak bertanggung jawab menempati posisi yang suci, atau karena dia maksum (terjaga dari kesalahan), dan tidak ada dalam Islam yang menempati kedudukan ini selain para Nabi dan Rasul.
Dan setiap Muslim bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya, baik tindakan dan perbuatan tersebut berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wajib yang telah dibebankan oleh pembuat syariat Islam kepada setiap mukallaf (orang yang dibebani hukum), dan mengharuskannya untuk melaksanakannya, atau berkaitan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Dalam semua kondisi ini, seorang Muslim bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala di akhirat, di samping dia bertanggung jawab di dunia di hadapan hati nuraninya dari satu sisi, dan dari sisi lain di hadapan masyarakat Islam.
Dan kami, jika kami menerima bersama Yang Mulia Syaikh Ahmad Huraidi prinsip ini, karena ia termasuk kaidah-kaidah yang qath’i (pasti) dalam fikih Islam, namun kami tidak menerima perkataannya bahwa tanggung jawab individu terkadang muncul di hadapan dirinya dan hati nuraninya, terkadang di hadapan Tuhannya Subhanahu wa Ta’ala, dan terkadang di hadapan manusia dan masyarakat. Karena perkataan ini mengisyaratkan bahwa dalam beberapa kasus seseorang dapat bertanggung jawab di hadapan dirinya dan hati nuraninya, atau bertanggung jawab di hadapan masyarakat, namun tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan ini yang tidak kami terima, dan kami yakin bahwa Syaikh tidak menentang hal itu. Karena tanggung jawab ditentukan pertama-tama dan sebelum segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan dalam semua keadaan.
Oleh karena itu, kita akan membahas sekarang tentang dasar legitimasi tanggung jawab. Kita katakan: Sumber-sumber legitimasi Islam menunjukkan penetapan kaidah tanggung jawab dan keumumannya, untuk mencakup semua tindakan dan semua orang yang dikenai hukum syariat, baik penguasa maupun yang dikuasai secara sama. Hal ini jelas dari Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabawiyah, dan penerapan praktis pada masa Khulafaur Rasyidin.
Dasar legitimasi tanggung jawab dalam Islam menunjukkan dari sumber-sumber legitimasi dalam Islam tentang kaidah syura (musyawarah) sebagai bangunan kokoh yang menjadi dasar bukan hanya sistem politik Islam, melainkan seluruh sistem Islam. Hal itu jelas dari nash-nash Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabawiyah, penerapan praktis pada masa Khulafaur Rasyidin, dan apa yang telah disepakati oleh para ulama umat.
Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Surat Az-Zalzalah: 7-6). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan jika (amal itu) seberat biji sawi, niscaya Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.” (Surat Al-Anbiya: dari ayat 47). Dan Allah Subhanahu berfirman: “Tiap-tiap diri terikat dengan apa yang telah diperbuatnya.” (Surat Al-Muddatstsir: 38). Dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Surat Al-Anfal: 27). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman: “Dan agar dibalas tiap-tiap diri dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dianiaya.” (Surat Al-Jatsiyah: 22). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Surat At-Taubah: 105). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (Surat Ath-Thur: dari ayat 21). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan (di hadapannya), begitu (pula) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh.” (Surat Ali Imran: dari ayat 30).
Semua ayat-ayat ini menetapkan dengan nash-nash yang qath’i kaidah tanggung jawab, sehingga tanggung jawab itu mencakup tanggung jawab di dunia dan tanggung jawab di akhirat.
Dan dari Sunnah Nabawiyah yang mulia, kami sebutkan apa yang diriwayatkan dari Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (pemimpin) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka yang dipimpinnya. Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Budak seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” Oleh karena itu, tidak ada dalam Islam seseorang yang dapat terhindar dari tanggung jawab, sehingga tanggung jawab itu berjenjang sejajar dengan kekuasaan, mulai dari kepala negara hingga budak atas harta tuannya.
Dan juga apa yang datang dalam Khutbah Wada’ dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian hingga kalian menemui Tuhan kalian, seperti keharaman hari kalian ini dan seperti keharaman bulan kalian ini. Dan sesungguhnya kalian akan menemui Tuhan kalian, maka Dia akan menanyai kalian tentang amal-amal kalian. Dan aku telah menyampaikan, maka barangsiapa yang memiliki amanah, hendaklah dia menyerahkannya kepada orang yang mengamanahkannya kepadanya.” Dan juga apa yang diriwayatkan oleh para sejarawan: “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dalam sakitnya yang terakhir dari kamar Sayyidah Aisyah di antara Al-Fadhl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bershalawat untuk para sahabat Uhud, dan memperbanyak serta memohonkan ampun untuk mereka, dan bersabda: Wahai manusia, barangsiapa yang telah aku pukul punggungnya, maka ini punggungku, hendaklah dia mengqishash dariku. Dan barangsiapa yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku, hendaklah dia mengambil darinya. Dan janganlah takut akan kedengkian dariku, karena sesungguhnya itu bukan kebiasaanku. Ketahuilah, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang mengambil hak dariku jika dia memilikinya, atau membebaskanku.”
Dan prinsip tanggung jawab bukanlah prinsip teoritis dalam fikih Islam pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam atau pada masa Khulafaur Rasyidin, melainkan telah mengambil tempatnya dalam penerapan seperti nash-nash hukum lainnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang adalah Nabi yang diutus, maksum, yang suci dari kesalahan dan hawa nafsu, menerima qishash. Dan kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d: “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menusuk Sawad bin Ghaziyyah dengan ranting siwak, lalu mengenai perutnya -artinya: meninggalkan bekas di perutnya- maka Sawad meminta qishash -yaitu: orang yang ditusuk Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meminta qishash dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan ketika kaum Anshar mengingkari hal itu dari Sawad, dia segera menjawab mereka dengan perkataannya: Tidak ada kelebihan manusia atas manusia. Dan ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyingkap tubuhnya yang suci agar di-qishash darinya, Sawad berkata: Aku tinggalkan ini agar menjadi syafaat untukku pada hari kiamat wahai Rasulullah.”
Dan jika kita ingin menyebutkan preseden untuk tanggung jawab ini pada masa Khulafaur Rasyidin, maka kita katakan: Preseden-preseden menunjukkan secara pasti bahwa para khalifah yang pertama semoga Allah Tabaraka wa Ta’ala meridhainya mereka, bekerja dengan prinsip ini dan menetapkan tanggung jawab mereka atas segala yang timbul dari pelaksanaan kekuasaan umum.
Dan kami akan meringkas jalan para khalifah yang pertama dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana mereka menjamin penerapan prinsip ini, yaitu tanggung jawab penguasa. Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu berkata dalam khutbah pertamanya setelah menjabat sebagai khalifah: Taatilah aku selama aku menaati Allah terhadap kalian, maka jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Dan seolah-olah dia mengisyaratkan dengan itu kepada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq.” Dan dia juga berkata: Maka jika kalian melihatku lurus, ikutilah aku, dan jika aku menyimpang, luruskanlah aku. Dan meluruskan khalifah tidak akan diakui sebagai kaidah yang ditetapkan kecuali jika prinsip tanggung jawab mengambil tempatnya dalam sistem Islam. Hal itu karena pelurusan tidak terwujud kecuali karena khalifah bertanggung jawab dan harus tunduk pada hukum undang-undang. Dan Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu berpandangan bahwa dia bertanggung jawab bukan hanya atas tindakan-tindakan pribadinya, melainkan atas tindakan-tindakan para pegawai dan gubernurnya. Dan sebagai penerapan dari apa yang dipandang Umar dalam tanggung jawab penguasa, maka cakupan tanggung jawab meluas dalam metodenya dalam pemerintahan untuk mencakup berbagai aktivitas, tempat, dan bidang dalam masyarakat.
Dan kami tidak melihat seorang penguasa di Timur atau Barat yang menggambarkan tanggung jawab seperti yang digambarkan Umar. Dan di antara yang diriwayatkan darinya radhiyallahu ‘anhu bahwa dia berkata: Gubernur mana pun yang aku angkat yang menzalimi seseorang, lalu kezaliman itu sampai kepadaku namun aku tidak mengubahnya, maka akulah yang menzaliminya. Dan karena dia menganggap bahwa dia bertanggung jawab atas para pegawai dan gubernurnya, maka dia sangat ketat dalam memilih para gubernur, dan tidak memilih salah satu dari mereka untuk pekerjaan apa pun, kecuali jika telah terpenuhi padanya syarat-syarat yang dituntut oleh pekerjaan itu pada orang yang melaksanakannya, dan dipercaya amanah dan ketakwaannya. Oleh karena itu, dia menangani sendiri urusan-urusan dengan dirinya sendiri, dan apa yang tidak dapat diangkat kepadanya dari masalah-masalah wilayah dan provinsi yang berbeda, maka dia memilih untuk itu orang-orang yang kuat dan amanah. Dan di antara yang diriwayatkan darinya radhiyallahu ‘anhu perkataannya: Barangsiapa yang berada di hadapan kami, kami tangani dengan diri kami sendiri. Dia berbicara tentang para pegawai. Dan barangsiapa yang tidak hadir dari kami, kami angkat untuknya orang-orang yang kuat dan amanah. Demi Allah, tidak ada urusan kalian yang hadir padaku lalu ditangani orang lain selain aku, dan tidak ada yang tidak hadir dariku maka aku lalai dalam hal kekuatan dan amanah. Dan demi jika mereka berbuat baik, sungguh aku akan berbuat baik kepada mereka, dan demi jika mereka berbuat buruk, sungguh aku akan memberikan hukuman kepada mereka. Dia berbicara tentang para pegawainya dan seolah-olah dia bersumpah dan berkata: Demi jika mereka berbuat baik, yaitu: berbuat baik kepada rakyat, dan memperlakukan mereka dengan kelembutan, kebaikan, dan keadilan, sungguh aku akan berbuat baik kepada mereka, dan demi jika mereka berbuat buruk, sungguh aku akan memberikan hukuman kepada mereka. Dan karena dia bertanggung jawab atas para pegawainya, maka dia ketat dalam mengawasi dan menghitung mereka atas tindakan-tindakan mereka. Dan dia menegaskan dalam surat-suratnya yang banyak kepada mereka, atau dalam pertemuan-pertemuan tahunan yang dia adakan pada musim haji: Jangan memukul kaum Muslim sehingga kalian menghinakan mereka, jangan mengharamkan kepada mereka sehingga kalian mengkafirkan mereka, dan jangan memaksa mereka sehingga kalian memfitnah mereka. Dan setiap orang yang melanggar prinsip ini, maka dia dihukum dengan hukuman yang sesuai yang sepadan dengan kerugian yang menimpa kaum Muslim. Ibnu Sa’d meriwayatkan dari Amr bin Al-Ash yang berkata kepada Umar radhiyallahu ‘anhu: Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu jika seorang amir mendidik seorang laki-laki dari rakyatnya, apakah engkau meng-qishash darinya? Maka Umar berkata: Mengapa aku tidak meng-qishash darinya! Aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meng-qishash dari dirinya sendiri. Yang dipahami dari riwayat ini adalah bahwa tanggung jawab bukan atas pendidikan yang merupakan akibat dari pelanggaran seseorang terhadap kaidah-kaidah syariat, melainkan tanggung jawab tertuju kepada kasus jika gubernur mendidik seorang laki-laki dari rakyat tanpa alasan -yaitu: tanpa sebab- atau pendidikan ini telah melampaui batas kewenangan oleh amir, dengan tercapainya ketidaksesuaian antara perbuatan yang melanggar hukum dengan cara pendidikan. Dalam kedua kasus ini bukan merupakan pendidikan, melainkan merupakan kezaliman yang tidak dibenarkan syariat, dan harus di-qishash sebagai pembalasannya. Dan inilah yang dipahami dari kelanjutan kisah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d.
Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu memerintahkan para pegawainya agar menemaninya pada musim haji, yaitu: musim haji, yaitu: datang kepadanya pada musim haji. Maka jika mereka berkumpul, dia berkata: Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak mengutus para pegawaiku atas kalian agar mereka mengambil dari kulit dan harta kalian, melainkan aku mengutus mereka agar mereka membatasi di antara kalian dan membagi fai’ kalian di antara kalian. Maka barangsiapa yang diperlakukan dengan selain itu, hendaklah dia berdiri. Maka tidak ada yang berdiri kecuali seorang laki-laki saja. Maka dia berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya pegawaimu si fulan -maksudnya Amr bin Al-Ash- memukulku seratus kali cambuk. Dia berkata: Mengapa dia memukulmu wahai Amr? Dan ketika Umar yakin bahwa dia memukulnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dia berkata kepada laki-laki itu: Berdirilah dan qishash darinya, yaitu: qishash dari Amr bin Al-Ash. Maka Amr bin Al-Ash berkata: Wahai Amirul Mukminin, jika engkau melakukan ini, akan banyak atasmu, dan akan menjadi sunnah yang diambil oleh orang-orang setelahmu. Maka dia berkata: Mengapa aku tidak meng-qishash, padahal aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meng-qishash dari dirinya sendiri. Amr bin Al-Ash berkata: Maka biarkanlah kami, mari kita ridhai dia. Dia berkata: Terserah kalian, maka ridhaikan dia. Maka dia menebus darinya dengan dua ratus dinar, setiap cambuk dengan dua dinar.
Demikianlah Umar bersikap tegas dalam memperlakukan atau dalam mengawasi para pejabatnya, hingga ia ingin menjadikan seorang dari kalangan rakyat biasa, dari rakyat jelata, mengqishash (membalas) dari gubernur Amr bin Ash. Dan ini jika menunjukkan, maka sesungguhnya menunjukkan sejauh mana keadilan yang dijaga oleh Umar bin Khaththab terhadap rakyat. Sungguh Umar bersikap tegas dalam tanggung jawab para gubernur atas tindakan-tindakan mereka, dan ia berpandangan bahwa ia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka sepanjang masa pemerintahannya.
Dan ia berpandangan bahwa ia bertanggung jawab atas segala sesuatu di negara Islam; oleh karena itu ia biasa meraba unta dan berkata: Sesungguhnya aku takut akan ditanya tentang apa yang menimpamu. Dan ia radhiyallahu anhu berkata: Andai seekor unta tersesat di tepi sungai Furat, niscaya aku khawatir Allah akan menanyakan kepadaku tentangnya; karena negara tidak menyediakan jalan untuknya. Maka ia takut jika seekor unta tersesat, maka ia akan bertanggung jawab atas hal itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta’ala.
Dan jika ini adalah sikap Umar, maka ada sikap yang berlawanan dengannya, yaitu sikap yang diperintah. Mereka berpandangan bahwa khalifah bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakannya di samping tanggung jawabnya terhadap mereka.
Ibnu al-Jauzi meriwayatkan: Bahwa Umar bin Khaththab berkata dalam khutbah pertamanya: Jika kalian melihat kecenderungan pada diriku, maka luruskanlah aku. Dan seorang Muslim menanggapi Umar dengan perkataannya: Demi Allah, jika kami melihat kecenderungan padamu niscaya kami akan meluruskannya dengan ujung pedang. Dan Umar menanggapi dengan perkataannya: Segala puji bagi Allah yang menjadikan di kalangan kaum Muslimin orang yang meluruskan Umar dengan ujung pedang.
Dan seorang Muslimah menggambarkan pemahaman Islam tentang batasan-batasan dan cakupan tanggung jawab khalifah dengan cara yang tidak dikenal dalam masa lalu maupun masa kini oleh perundang-undangan buatan manusia mana pun. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab melewati malam hari seorang wanita Arab pedalaman, dan ia menghibur anak-anaknya yang kecil dengan tungku api yang telah ia letakkan di atasnya panci berisi air murni tanpa isi apa pun; karena ia tidak memiliki makanan untuk memberi makan anak-anaknya. Dan ia menghibur anak-anaknya yang kecil dengan tungku api. Dan ketika Sayyidina Umar mendekat dan bertanya kepadanya: Apa yang sedang kau lakukan wahai wanita? Dan mengapa anak-anak ini menangis tersedu-sedu? Ia menjawabnya bahwa mereka kelaparan—yaitu: menangis karena sangat lapar—dan ia menghibur mereka—yaitu: seolah-olah ia menipu mereka hingga mereka tidur, mengira bahwa ia sedang memasak sesuatu untuk mereka, padahal tidak ada di dalam panci kecuali air saja. Maka ia berkata kepadanya: Mengapa kau tidak pergi kepada Umar—dan ia tidak tahu bahwa dialah yang berbicara, ia tidak tahu bahwa ia adalah Umar—agar membantu memberi mereka makan? Maka ia berkata: Allah (menjadi hakim) antara kami dan dia. Maka Umar sangat cemas, sangat takut, dan berkata kepadanya—dan kecemasan serta kesedihan telah menguasainya—: Dan apa yang membuat Umar tahu tentang kalian?—yaitu: apa yang membuat Umar tahu tentang keadaan kalian, ia tidak tahu tentang itu. Maka ia berkata: Ia mengurusi urusan kami, tetapi ia lengah terhadap kami.
Dan kisah ini meskipun sederhana, menggambarkan bagaimana kaum Muslimin pertama, penguasa dan yang diperintah. Dan Umar berpandangan bahwa karena ia bertanggung jawab lebih besar kedudukannya dan lebih berbahaya daripada para gubernur dan penguasa lainnya, maka sudah seharusnya dari logika keadilan Umar bahwa ia dan keluarganya menjadi teladan puncak bagi individu-individu masyarakat Islam; oleh karena itu ia melipatgandakan hukuman terhadap keluarganya jika mereka melakukan apa yang bertentangan dengan perintah dan larangan syariat, dan apa yang diperintahkan Umar kepada rakyat. Dalam hal ini Umar berkata: Kalian telah mendengar apa yang aku larang, dan sesungguhnya aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalian yang melakukan sesuatu yang aku larang kecuali aku akan melipatgandakan siksanya dua kali lipat.
Aku titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya atas kalian.
2 – Hak dan Kebebasan dalam Sistem Islam
Lanjutan: Kaidah Sistem Politik dalam Islam: “Tanggung Jawab Penguasa”
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan shalawat serta salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, junjungan kami Muhammad, atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kami telah memulai pembicaraan tentang kaidah keempat yaitu tanggung jawab penguasa, dan kami telah menyebutkan dalil tanggung jawab ini dari Al-Quran, kemudian dalilnya dari Sunnah, kemudian dalilnya dari preseden sejarah di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan kami melanjutkan pembicaraan dengan menyebutkan penerapan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhahu, maka kami katakan:
Adapun di masa Utsman bin Affan, maka sesungguhnya ia radhiyallahu anhu meskipun perilaku pribadinya, kejujurannya, amanahnya, ketakwaannya, dan pengorbanannya demi meninggikan Islam dan kaum Muslimin tidak diragukan lagi, namun ia radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid karena mayoritas pemberontak menganggapnya bertanggung jawab atas dominasi Bani Umayyah terhadap pundak kaum Muslimin; dan karena ia lalai dalam hak mereka, dan ia mengangkat kerabat-kerabatnya untuk jabatan-jabatan yang berbeda… dan lain-lain dari kritik-kritik yang dikemukakan oleh para pemberontak kepadanya, yang menjadi penyebab kesyahidannya. Dan penyebab-penyebab ini meskipun tidak mencela ketakwaan Utsman radhiyallahu anhu, ketakwaannya, dan amanahnya, dan tidak mengurangi peran besar yang dilakukan Utsman, namun tanpa diragukan lagi hal itu mengarah pada kesimpulan penting, yaitu bahwa khalifah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan gubernurnya, pejabatnya, dan wakilnya di wilayah-wilayah yang berbeda. Di samping bahwa ia radhiyallahu anhu tidak mengingkari hak kaum Muslimin untuk meminta pertanggungjawabannya; maka diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu perkataannya: “Jika kalian menemukan dalam Kitab Allah untuk memasang belenggu pada kakiku maka pasanglah.”
Dan Ali radhiyallahu anhu berpandangan bahwa khalifah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diakibatkan oleh pelaksanaan kekuasaan umum. Ibnu Hazm meriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu bahwa Umar mengirim kepada seorang wanita tertentu yang didatangi orang—yaitu didatangi oleh sebagian orang—maka ia mengingkarinya. Lalu dikatakan kepadanya: Datanglah menghadap Umar. Maka ia berkata: Celakalah dia! Apa urusannya dengan Umar? Maka sementara ia di jalan, ia ketakutan, maka datanglah kontraksi persalinan, lalu ia masuk rumah dan melahirkan anaknya. Maka bayi itu berteriak sekali lalu meninggal. Yaitu bahwa ia ketakutan ketika mengetahui bahwa ia akan menghadap dan hadir di hadapan Umar bin Khaththab, dan ketakutan ini menjadi penyebab kontraksi persalinan datang bukan pada waktunya; dan akibatnya ia melahirkan anak dan anak itu meninggal. Maka Umar meminta nasihat para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, meminta nasihat mereka sebagaimana kebiasaannya—radhwanullahu Tabaraka wa Ta’ala alaihi—yaitu meminta nasihat mereka tentang sikapnya terhadap bayi yang meninggal ini yang disebabkan oleh ketakutan yang dialami wanita itu. Maka sebagian dari mereka menyarankan kepadanya bahwa tidak ada tanggungan apa pun atasmu, yaitu sebagian berkata: Tidak ada tanggungan apa pun atasmu wahai Amirul Mukminin karena hal itu, sesungguhnya engkau hanyalah gubernur dan pendidik. Ia berkata: Dan Ali—yaitu Ali bin Abi Thalib—diam. Maka Umar menghadap kepadanya dan berkata: Apa pendapatmu? Yaitu apa pendapatmu wahai Ali tentang peristiwa ini? Dan apakah aku bertanggung jawab atas kematian bayi ini atau tidak? Maka ia berkata: Wahai Amirul Mukminin, jika mereka berkata dengan pendapat mereka—yaitu orang-orang yang menyarankan kepadamu bahwa tidak ada tanggungan apa pun atasmu—maka pendapat mereka salah, dan jika mereka berkata sesuai keinginanmu, maka mereka tidak memberikan nasihat yang baik kepadamu. Aku berpendapat bahwa diyatnya adalah tanggunganmu; karena engkau yang membuatnya ketakutan dan anaknya dalam urusanmu. Maka ia memerintahkan Ali untuk membagikan diyat (tebusan darah) kepada Quraisy—yaitu diyat yaitu diyat bayi ini kepada Quraisy—dan mereka adalah yang menanggung diyat untuk Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu wa ardhahu.
Dan terlepas dari pendapat kami tentang tanggung jawab khalifah atas peristiwa ini, hal ini mengungkapkan dengan cara yang pasti bahwa Ali radhiyallahu anhu berpandangan bahwa khalifah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan umum.
Dan dari kajian nash-nash dalam Al-Quran, Sunnah, dan penerapan praktis di masa Khulafaur Rasyidin; kita memahami bahwa khalifah bertanggung jawab:
Pertama: Dalam kedudukannya sebagai salah satu dari individu kaum Muslimin, dan tanggung jawabnya dalam hal ini seperti tanggung jawab mereka sepenuhnya sama rata.
Dan kedua: Bertanggung jawab atas pelaksanaan pribadinya terhadap kewajiban-kewajiban kekuasaan umum.
Dan ketiga: Ia bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan pemegangnya, dan semua jabatan lain bercabang dari jabatan umumnya. Maka hal ini mengharuskan bahwa ia bertanggung jawab atas semua tindakan gubernurnya, para menterinya, dan wakilnya di semua penjuru dan negeri Islam.
Maka kekuasaan khalifah dan penguasa lainnya dibatasi dengan batasan yang tepat dalam fikih Islam. Dan jika seseorang dari mereka yang memegang kendali kekuasaan umum berani melanggar hukum Islam, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau menyimpang darinya dari kepentingan umum masyarakat Islam; maka ia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di hadapan Allah dari satu sisi, dan dari sisi lain di hadapan hukum dan di hadapan opini publik Islam. Dan dari sinilah kaidah-kaidah tanggung jawab berlaku kepada khalifah dan seluruh penguasa seperti mereka, dalam hal ini seperti seluruh kaum Muslimin. Hal itu karena jabatan adalah amanah dalam Islam, dan setiap orang yang diberi amanah bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya; oleh karena itu khalifah bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya dari hak-hak umat. Akan tetapi tanggung jawab khalifah lebih luas cakupannya dan lebih luas jangkauannya daripada tanggung jawab individu-individu semua; karena ia berat, sebesar beratnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada pundaknya dan keberagamannya. Maka ia juga mencakup tanggung jawabnya untuk menjamin semua yang pokok dan vital bagi semua kaum Muslimin; dan oleh karena itu nash-nash menegaskan bahwa orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim; dan oleh karena itu kita dapati bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu melipatgandakan tanggung jawab keluarganya atas pelanggaran terhadap apa yang disyariatkan untuk kaum Muslimin dari perintah-perintah.
Dan dalam hal ini Ibnu Sa’d meriwayatkan dari Abdullah bin Umar: Umar jika ingin melarang manusia dari sesuatu, ia mendahului keluarganya dan berkata: Jangan sampai aku mengetahui seorang pun yang terlibat dalam sesuatu yang aku larang kecuali aku akan melipatgandakan hukumannya. Dan itu tidak lain karena Umar menganggap khalifah adalah teladan yang baik bagi semua kaum Muslimin. Dan jika khalifah dan keluarganya bukan orang pertama yang menghormati hukum dan patuh kepadanya; maka hal itu akan menyebabkan pengabaian semua kaum Muslimin terhadap kaidah-kaidah hukum. Dan itu sesuai dengan perkataannya radhiyallahu anhu: “Sesungguhnya manusia tetap lurus selama pemimpin dan pembimbing mereka lurus bagi mereka.” Perkataannya: “Rakyat taat kepada pemimpin selama pemimpin taat kepada Allah, maka jika pemimpin melakukan kemaksiatan, maka mereka pun bermaksiat.” Yaitu bahwa jika ia taat kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala maka rakyat taat kepadanya, dan jika ia bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala maka rakyat bermaksiat kepadanya. Maka sesuai dengan kebaikan pemimpin dan penghormatan terhadap nash-nash hukum dan kepatuhannya kepadanya, demikian pula rakyat; oleh karena itu sesungguhnya Syariat Islam memperketat dalam menetapkan tanggung jawab penguasa; karena dalam hal ketidakhormatan terhadap hukum dan berani melanggarnya dari pihak penguasa; maka hal ini menyebabkan rusaknya semua perangkat dalam negara, dan merajalelanya kerusakan di negeri, dan ketidakpatuhan rakyat terhadap hukum.
Pendahuluan tentang Hak dan Kebebasan dalam Sistem Islam
Dan kami beralih sekarang—anak-anakku dan anak-anakku perempuan mahasiswa pascasarjana—kepada rukun lain, atau kepada kaidah lain dari kaidah-kaidah yang menjadi dasar sistem politik dalam Islam. Dan kaidah ini adalah hak dan kebebasan dalam sistem Islam:
Negara-negara modern berusaha melindungi individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan dan penyerangannya terhadap hak-hak mereka, yaitu dengan menetapkan sejumlah hak dan kebebasan individu, yang dianggap sebagai penghalang kuat di hadapan kekuasaan negara, tidak boleh baginya menerobos atau melampauinya, jika tidak maka ia adalah negara yang dicap dengan kesewenang-wenangan dan ketidakabsahan atau ketidakkonstitusionalan.
Dan patut dicatat bahwa pembicaraan tentang hak dan kebebasan individu di negara-negara modern tidak dikenal kecuali sejak berdirinya Revolusi Prancis, dan mengeluarkan apa yang disebut dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan di dalamnya pengakuannya terhadap hak-hak alamiah manusia, yang melekat padanya karena statusnya sebagai manusia, yang ada bersamanya sebelum adanya negara; dan oleh karena itu tidak boleh bagi negara melangkahi atau melampaui hak-hak ini—sebagaimana kami sebutkan.
Dan sungguh konsep hak dan kebebasan individu di negara-negara modern berbeda sesuai dengan sistem individual atau kolektif yang mereka anut; dan oleh karena itu hak-hak ini terbagi menjadi:
- Hak-hak individual tradisional yang ditetapkan untuk manusia dalam statusnya sebagai makhluk yang abstrak.
- Dan hak-hak lain yang bersifat sosial dan ekonomi yang ditetapkan untuk individu dalam status mereka sebagai anggota dalam kelompok yang terorganisir, dan negara harus berkomitmen secara positif dalam menghadapi individu, untuk menjaga hak-hak ini, dan tidak cukup dengan komitmen negatif yang membatasi kegiatannya hanya pada menjaga umat, mempertahankan tanah air, dan melindungi kepentingan individu dari serangan terhadapnya.
Dan konsep kebebasan dalam pemikiran individualistik yang disuarakan oleh sejumlah filsuf, seperti “Jean Jacques Rousseau” dan “John Locke” dan “Voltaire”… dan lain-lain, konsep ini berbeda darinya sepenuhnya dalam pemikiran sosialis, yang benderanya dinaikkan oleh “Karl Marx” dan orang-orang yang mengikuti jejaknya; karena kebebasan menurut pandangan pemilik pemikiran sosialis tidak dapat dijamin kecuali dalam kondisi lingkungan tertentu, dan masyarakat sosialis yang negara mewujudkannya; dan dari sinilah datang percobaan komunis di Rusia untuk menerapkan teori-teori yang dibawa oleh pelopor pemikiran sosialis.
Adapun dalam sistem Islam maka hak-hak individu ditetapkan atas dasar spiritual, yaitu: bahwa manusia semuanya dimuliakan oleh Sang Pencipta Subhanahu wa Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman: “Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Surat Al-Isra: 70) Dan mereka semua, penguasa dan yang diperintah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Surat Adz-Dzariyat: 56) Dan ibadah berarti ketundukan yang dipilih kepada kekuasaan Allah yang mutlak, dan mengatur urusan individu atau kelompok sesuai dengan apa yang dirinci—Subhanahu—dalam syariat-Nya. Maka hak dan kebebasan individual atau kolektif dalam sistem Islam dasarnya adalah akidah, dan sistemnya adalah syariat, dan ia adalah pemberian ilahi dari Sang Pencipta Subhanahu wa Ta’ala yang memuliakan ras, dan melebihkannya atas banyak makhluk yang diciptakan dengan kelebihan yang sempurna; dan dengan ini Islam menyatukan tujuan bagi individu dan negara, yaitu beribadah kepada Allah dan tunduk kepada kekuasaan-Nya, dengan melaksanakan syariat-Nya dalam hak dan kebebasan; dan oleh karena itu kita tidak menemukan dalam sistem Islam penyerangan terhadap hak apa pun meskipun sifatnya bagaimana pun. Maka hak-hak individu dan kebebasan mereka dilindungi dan dipelihara, tetapi bukan dengan mengorbankan kelompok, demikian juga sebaliknya, tetapi tanpa kesewenang-wenangan atau tirani yang menyebabkan terkuburnya kepentingan individu. Maka ada keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, sehingga tidak ada satu kepentingan yang mendominasi yang lain.
Dan yang harus diperingatkan dalam hal ini adalah bahwa hak dan kebebasan dalam sistem Islam tidaklah mutlak tanpa batasan apapun. Selain dari apa yang telah kami sebutkan mengenai keseimbangan antara kepentingan khusus dan kepentingan umum, harus selalu ditanggung bahaya yang lebih ringan demi menghilangkan bahaya yang lebih besar -sebagaimana dinyatakan oleh kaidah-kaidah fikih-. Misalnya, jika syariat menetapkan hak kepemilikan bagi individu, maka hal itu dibatasi dengan keharusan bahwa kepemilikan tersebut timbul dari sebab yang sah menurut syariat, seperti penguasaan atas barang-barang mubah, atau akad-akad dan transaksi: seperti jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, syirkah (persekutuan)… dan semacamnya, dengan syarat bahwa akad-akad tersebut memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan kepemilikan dapat timbul dari warisan, yang dalam hal ini merupakan kepemilikan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan syariat dan bukan atas kehendak ahli waris maupun pewaris. Demikian pula Islam telah menetapkan cara-cara investasi dan pengembangan harta, dengan cara yang menjauhkan masyarakat dari kotoran riba, atau terbenam dalam kubangan perolehan yang tidak sah melalui perdagangan barang-barang haram, seperti narkotika, minuman keras… dan sejenisnya, yang memenuhi masyarakat-masyarakat modern yang berbicara besar tentang kebebasan dengan mulut penuh namun tidak memiliki hubungan dengan kebebasan tersebut.
Demikian pula syariat mengizinkan pemanfaatan harta tanpa pemborosan dan tanpa kikir, dan hendaknya pengeluaran dilakukan pada hal-hal yang diakui secara syariat.
Dalam sistem Islam diperbolehkan pencabutan kepemilikan pribadi untuk perluasan jalan umum, atau pembuatan aliran sungai… dan semacamnya dari manfaat-manfaat umum.
Sebagaimana diperbolehkan penjualan kepemilikan secara paksa kepada pemiliknya untuk melunasi utang-utangnya. Maka semua itu adalah batasan-batasan yang ditetapkan terhadap hak individu dalam kepemilikan; agar hak tersebut berada dalam lingkup individu dan kolektif yang telah ditetapkan oleh syariat, dan tidak menjadi sarana untuk kesewenang-wenangan, atau kezaliman, atau merugikan orang lain. Setelah pembagian ini, kami memandang bahwa tepat untuk menunjukkan bahwa kami akan mengikuti pembagian yang ditempuh oleh para ahli hukum, dalam menetapkan daftar hak dan membaginya menjadi hak individual dan hak sosial; hal itu untuk kemudahan perbandingan. Oleh karena itu, kami akan mengkaji dalam hal ini beberapa hal:
Pertama: Daftar khusus mengenai hak dan kebebasan individual dalam sistem Islam.
Kedua: Hak dan kebebasan sosial dalam sistem ini.
Pertama: Hak dan Kebebasan Individual dalam Sistem Islam:
Kelompok hak dan kebebasan ini dalam fikih konstitusi modern mencakup: kebebasan-kebebasan pribadi, kebebasan-kebebasan pemikiran, kemudian kebebasan-kebebasan berkumpul, dan kebebasan-kebebasan ekonomi.
Kebebasan-Kebebasan Pribadi
Pertama: Kebebasan-Kebebasan Pribadi:
Jenis kebebasan ini dianggap sebagai salah satu hal terpenting yang harus dinikmati oleh individu; karena berkaitan dengan martabat kemanusiaannya yang dijamin oleh Sang Pencipta, Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Kebebasan-kebebasan ini dalam fikih konstitusi meliputi hal-hal berikut:
1 – Kebebasan Berpindah:
Artinya individu bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain, keluar dari negara dan kembali ke negara tanpa pembatasan kebebasannya dalam hal itu, kecuali apa yang dituntut oleh sistem dan hukum. Dan ini adalah hak individu yang telah diakui oleh sistem Islam yang mengajak manusia untuk berusaha di muka bumi, dan berjalan di penjuru-penjurunya; untuk mencari rezeki, dan mengambil pelajaran dari nasib umat-umat terdahulu. Diriwayatkan dari Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab semoga Allah meridhainya bahwa beliau melarang beberapa sahabat senior keluar dari Madinah; agar beliau dapat kembali kepada mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan negara. Dan ini dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpindah untuk kepentingan umum jika imam memandangnya perlu. Bagaimanapun, kebebasan berusaha di muka bumi sebagai hak individual tidak patut dan tidak boleh dibatasi kecuali untuk kepentingan yang lebih tinggi darinya. Adapun membatasinya hanya karena keinginan untuk membalas dendam kepada individu, sebagaimana terjadi di dunia saat ini, adalah tindakan yang tidak diakui oleh sistem Islam, yang di dalamnya kebutuhan selalu diukur sesuai kadarnya.
2 – Hak Keamanan:
Yang dimaksud dengan hak ini dalam fikih konstitusi adalah: tidak bolehnya penangkapan terhadap seseorang, atau penahanan, atau pemenjaraannya, kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam undang-undang, dan setelah mengambil semua prosedur dan jaminan yang ditentukan oleh undang-undang. Juga berarti kekebalan pribadinya -yaitu perlindungan pribadi dari setiap serangan terhadapnya-. Dalam sistem Islam tentu saja tidak boleh menangkap seseorang dan menakut-nakutinya serta memenjarakannya, kecuali karena alasan syar’i yang mengharuskan hal itu. Dan hukuman-hukuman dalam Islam tentu saja pintunya dipersempit, maka tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa nash, dan hukuman-hukuman tidak ditetapkan hanya dengan pendapat dan ijtihad semata; karena hukuman-hukuman hudud dihapuskan dengan keraguan sebagaimana diketahui, dan asalnya adalah praduga tak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, sistem Islam menganggap serangan terhadap hak keamanan manusia, baik dalam tubuhnya maupun dalam kehidupan umumnya, sebagai bentuk kezaliman, dan mengancamnya dengan hukuman yang sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta’ala menganggap barang siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah dia telah membunuh semua manusia, dan barang siapa yang menghidupkannya maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Allah mengancam pembunuh yang disengaja dengan kekal di neraka. Dan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan semua (hak) Muslim atas Muslim adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dalam khutbah Haji Wada’ beliau ‘alaihish-shalaatu was-salaam bersabda: “Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram atas kalian, seperti keharaman hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, sungguh telah aku sampaikan. Ya Allah saksikanlah.”
3 – Kehormatan Tempat Tinggal:
Artinya tidak boleh menyerbu atau menggeledah tempat tinggal seseorang kecuali dalam kasus-kasus dan sesuai prosedur yang disebutkan oleh undang-undang. Nama tempat tinggal diberikan pada tempat yang ditempati individu secara permanen atau sementara. Maka tempat tinggal pribadi memiliki kehormatan yang tidak boleh dilanggar kecuali dalam keadaan darurat. Dan tidak perlu disebutkan bahwa hak ini ditetapkan dengan nash-nash yang jelas dalam Kitab Allah Tabaraka wa Ta’ala dalam “Surah An-Nur” di mana ayat 27 dan 28 dari surah tersebut menyebutkan firman Yang Hak Tabaraka wa Ta’ala: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemukan seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: ‘Kembali (saja)lah,’ maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah An-Nur: ayat 27).
Maka kehormatan tempat tinggal telah ditetapkan dengan nash yang mulia ini; sehingga tidak boleh bagi seseorang memasuki rumah selain rumahnya kecuali setelah meminta izin, bahkan meminta ketenangan, dan memberi salam kepada penghuninya. Tidak boleh memasuki tempat tinggal seseorang saat ketidakhadirannya kecuali dengan izinnya. Dan ketika tidak ada izin untuk masuk maka wajib kembali; hal itu lebih suci dan lebih bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan Dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada dari menjaga kehormatan masjid, atau keinginan untuk melanggarnya dan melihat aurat orang.
4 – Kerahasiaan Surat-Menyurat:
Artinya tidak bolehnya penyitaan atau pembunuhan kerahasiaan surat-menyurat antara individu; karena hal itu mengandung serangan terhadap hak kepemilikan surat-surat yang mengandung surat-menyurat tersebut; dan karena dalam hal itu terdapat pelanggaran terhadap kebebasan berpikir. Dalam sistem Islam tidak boleh menyerang kerahasiaan surat-menyurat; karena surat-menyurat tersebut dimiliki oleh pemiliknya, maka serangan terhadapnya adalah serangan terhadap hak orang lain, dan hal itu tidak diperbolehkan secara syar’i kecuali dengan izin dan kerelaan pemilik hak. Juga surat dianggap sebagai titipan sampai sampai kepada orang yang dituju. Dan diketahui bahwa titipan adalah amanah, dan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan untuk menunaikannya kepada ahlinya; karena itu tidak boleh menyentuhnya atau bertindak terhadapnya dari pihak yang dititipi; karena hal itu mengandung mata-mata dan mengikuti aurat, yang telah dilarang dan diingatkan kepada kita oleh syariat. Bagaimanapun, kita harus selalu memperhatikan bahwa kebebasan-kebebasan ini tidak boleh sama sekali menyentuh kepentingan-kepentingan umum masyarakat; oleh karena itu, sudah menjadi hal yang wajar bahwa negara memiliki kewenangan membatasi kebebasan-kebebasan pribadi ini dengan beberapa batasan demi kepentingan masyarakat, terutama ketika keegoisan individual merajalela, kerusakan meluas, integritas melemah, dan hati nurani melemah. Dalam kondisi ini, otoritas yang sah dan adil memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan dan batasan-batasan yang menolak bahaya, menyediakan keamanan, dan mewujudkan kepentingan masyarakat.
Kebebasan Intelektual
Kedua: Kebebasan Intelektual:
Yang dimaksud dengan kebebasan ini dalam pemikiran konstitusi modern adalah:
- Kebebasan keyakinan.
- Dan kebebasan berpendapat dan berpikir.
- Dan kebebasan mengajar dan belajar.
Dalam sistem Islam, kebebasan intelektual dengan berbagai kandungannya dianggap sebagai salah satu kebebasan terpenting yang bergantung padanya kehidupan manusia sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Jika kebebasan-kebebasan pribadi -yang telah saya sebutkan sebelumnya- melindungi sisi material dalam diri manusia, maka kebebasan-kebebasan intelektual melindungi sisi-sisi maknawi, dan ini lebih penting bagi manusia daripada sisi-sisi material. Oleh karena itu, ayat-ayat datang secara tegas dalam Kitab Allah Subhanahu wa Ta’ala menetapkan kebebasan intelektual manusia, dan mendorongnya untuk menggunakan akalnya yang dengannya Allah telah membedakannya dari seluruh makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya Ta’ala: “Katakanlah: ‘Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan.'” (Surah Saba’: ayat 46).
Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Surah Al-Jatsiyah: ayat 13).
Dan firman-Nya Subhanahu: “Katakanlah: ‘Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat?’ Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?” (Surah Al-An’am: ayat 50). Dan selain itu banyak dalam ayat-ayat Kitab yang mulia yang mendorong untuk berpikir tentang ciptaan Allah, dan mencela penonaktifan akal dari fungsi-fungsinya, mengikuti bapak-bapak (leluhur), dan taklid buta. Dan pendahulu kami -wahai kaum muslimin- telah mempraktikkan kebebasan intelektual sebaik-baiknya; oleh karena itu diwarisi dari mereka hasil pemikiran mereka dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna. Contoh paling menonjol dari hal itu adalah madzhab-madzhab fikih yang berbeda, yang ditetapkan dalam fikih Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dan ushul yang diterima oleh para imam madzhab dalam istinbath (penggalian hukum). Kami akan menyebutkan kandungan kebebasan intelektual ini sesuai dengan pembagian yang berlaku dalam fikih konstitusi modern; agar kita mengetahui apa yang datang dalam sistem Islam mengenai hal ini:
1 – Kebebasan Keyakinan:
Yang dimaksud dengannya dalam fikih konstitusi positif adalah kebebasan seseorang untuk memeluk agama atau prinsip yang diinginkannya, dan kebebasannya untuk tidak memeluk agama atau prinsip yang diinginkannya, dan kebebasannya untuk mempraktikkan syiar-syiar agama tersebut, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, dan kebebasannya untuk tidak berkeyakinan dengan agama apapun, dan kebebasannya untuk tidak dipaksakan padanya agama tertentu, atau dipaksa untuk melakukan manifestasi-manifestasi lahiriah atau berpartisipasi dalam ritual-ritual berbagai agama, dan kebebasannya untuk mengubah agamanya. Semua ini dalam batas-batas ketertiban umum dan akhlak. Demikianlah mengenai hukum-hukum positif dan penafsirannya terhadap kebebasan keyakinan.
Pada kenyataannya, kemanusiaan tidak sampai pada penetapan kebebasan ini kecuali sejak masa yang dekat; karena seringkali individu-individu dipaksa untuk memeluk keyakinan-keyakinan tertentu. Dan kita masih mendapati hingga hari ini bahwa kebebasan keyakinan tidak tersedia di banyak negara kontemporer; karena banyak individu dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, atau tidak diizinkan untuk mendirikan syiar-syiar agama mereka, dan mereka menghadapi banyak kekerasan dan penganiayaan karena mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka yang mereka imani.
Adapun sistem politik Islam, ia telah mengumumkan sejak awal kemunculannya tentang kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala: “Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat” (Surat Al-Baqarah, ayat 256).
Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam menyapa Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam: “Maka apakah engkau (Muhammad) yang memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Surat Yunus, ayat 99).
Asy-Syaukani berkata dalam tafsirnya: Artinya bukan itu yang ada dalam kemampuanmu wahai Muhammad, dan tidak termasuk dalam kekuasaanmu, dan dalam hal ini merupakan penghiburan baginya shallallahu alaihi wasallam dan menolak apa yang menyempitkan dadanya dari permintaan kebaikan semua orang, yang seandainya itu terjadi, tidaklah menjadi kebaikan yang pasti, bahkan akan lebih dekat kepada kerusakan karena hikmah yang diketahui oleh Allah Tabaraka Wataala. Maka dalam Islam tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk mengganti keyakinannya dan menganut Islam sebagai gantinya. Memang benar dalam Islam ada ajakan kepada agama sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik” (Surat An-Nahl, ayat 125).
Namun ajakan adalah satu hal dan paksaan untuk masuk agama adalah hal lain. Yang telah ditetapkan dalam Islam adalah kita membiarkan mereka dengan agama mereka, maka negara Islam tidak mengganggu orang non-Muslim dalam keyakinan dan ibadahnya. Dan yang telah ditetapkan dalam sistem Islam adalah legitimasi perang untuk membela kebebasan berkeyakinan; karena orang-orang musyrik dahulu menghadang kaum muslimin, lalu mencegah mereka dari melaksanakan syiar-syiar mereka, dan menganiaya mereka karena hal itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, ‘Tuhan kami ialah Allah.’ Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa” (Surat Al-Hajj, ayat 39-40).
Dan jika kita kembali kepada sejarah ahlul dzimmah (non-Muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam) yang hidup dalam naungan negara Islam; kita akan mendapati bahwa mereka diperlakukan dengan perlakuan yang mulia, tidak ada penganiayaan dan tidak ada paksaan di dalamnya. Dan seringkali para khalifah Muslim mendekatkan mereka kepada diri mereka dalam banyak urusan, dan memperlakukan mereka dengan baik, dan menyerahkan kepada mereka jabatan-jabatan penting dalam negara. Bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid menempatkan semua sekolah di bawah pengawasan “Yuhanna bin Masawaih”, dan ini adalah bukti bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Berdasarkan hal itu, maka apa yang kadang terjadi berupa penganiayaan terhadap non-Muslim, atau memperlakukan mereka tanpa kemuliaan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam dan keluar dari ajaran Islam, dan itu kembali pada tempat pertama kepada sebab-sebab politik bukan agama; karena Eropa Kristen sendirilah yang memulai dan membangkitkan kemarahan kaum muslimin sejak perang-perang penghancuran yang mereka selenggarakan di bawah panji Salib, dan melanggar dengan itu kehormatan kaum muslimin dan tempat-tempat suci mereka.
Masih tersisa satu masalah penting yang harus kita bahas dalam hal ini, yaitu pengkriminalan murtad dari Islam, dan penetapan hukuman mengenainya; yang membuat sebagian musuh Islam menuduhnya dengan fanatisme.
Dan pada kenyataannya sesungguhnya kebebasan berkeyakinan sebagai prinsip telah ditetapkan dalam Islam sejak awal kemunculannya -sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya- dan tidak ada paksaan untuk masuk agama dengan nash Al-Quran. Namun ketika sebagian orang masuk agama dengan penipuan dan keluar darinya untuk menimbulkan bahaya, maka apa yang diharapkan dari Islam? Apa yang diharapkan dari Islam untuk dilakukan terhadap mereka kecuali memukul tangan mereka? Sebab, kita telah melihat bahwa Islam menjamin bagi dzimmi dan lainnya dalam negaranya dari orang-orang yang memilih tinggal dalam naungan kaum muslimin, menjamin mereka tingkat hak yang luar biasa; sehingga mereka memiliki apa yang dimiliki kaum muslimin dan kewajiban mereka adalah apa yang menjadi kewajiban kaum muslimin. Maka mengapa mereka meninggalkan agama mereka dan masuk Islam kemudian keluar darinya setelah itu?! Sesungguhnya logika mengharuskan tentu saja bahwa tujuan dari hal itu adalah menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin, dan menyakiti negara dan agama mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala: “Dan segolongan dari ahli kitab berkata, ‘Berimanlah kamu pada pagi hari terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman (kaum muslimin), dan ingkarilah pada akhir siang, agar mereka (kaum muslimin) kembali (kepada kekafiran)'” (Surat Ali Imran, ayat 72). Ibnu Abbas berkata tentang maknanya: Mereka bersama kaum muslimin pada awal siang, dan duduk bersama mereka, dan berbicara dengan mereka, kemudian ketika sore tiba dan tiba waktu shalat, mereka mengingkarinya dan meninggalkannya.
Apakah Islam berdiri dengan tangan terkunci dan membiarkan musuh-musuhnya atas nama kebebasan berkeyakinan yang telah ia tegakkan sedangkan mereka menyalahgunakan penggunaannya?
Apakah Islam membiarkan mereka dengan hal itu: untuk menyakitinya, dan menghina keyakinannya, dan menipu syariatnya, dan menimbulkan fitnah di antara para pengikutnya?!
Oleh karena itu ditetapkan dalam sistem Islam hukuman riddah (murtad), dan bahwa hukumannya adalah dibunuh setelah ditawari untuk bertobat; untuk menolak bahaya yang menimpa jamaah Islam karenanya. Dan sungguh hukuman ini didasarkan dalam sistem Islam atas dasar bahwa orang yang murtad dengan keluar dari Islam melanggar komitmen yang telah ia bebankan pada dirinya sendiri, dengan pilihan dan kemauan sendiri, dan menyakiti negara dalam keyakinan dan sistemnya; oleh karena itu ia layak dibunuh sebagai balasan atas pelanggaran komitmen ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat-syariat samawi dan syariat buatan manusia sama saja. Dan jika musuh-musuh Islam menuduh kaum muslimin dengan fanatisme agama, maka sejarah yang tercatat dan tetap menegaskan kepada kita dengan bentuk yang pasti bahwa non-Muslim diperlakukan dalam negara Islam dengan perlakuan yang paling mulia, dan diakui hak-hak mereka, sehingga kebebasan agama dan pemikiran mereka terjaga, pada saat dimana Eropa Kristen di Andalusia (Spanyol) menimpakan kepada kaum muslimin berbagai jenis siksaan, dan menganiaya mereka dengan jenis penganiayaan yang paling keji, dan memaksa mereka untuk meninggalkan agama mereka dan masuk Nasrani, dan menyiksa dengan berbagai jenis siksaan yang paling kejam siapa yang menolak mereka maka ia tetap pada keislamannya; hingga berubah -yakni bertransformasi- negeri Andalusia dalam periode singkat di bawah cambuk penyiksaan dan penindasan Kristen, bertransformasi menjadi negeri Kristen yang tidak tersisa di dalamnya seorang Muslim pun. Dan tidak pernah terjadi sama sekali bahwa kaum muslimin memaksa seseorang untuk meninggalkan agamanya, atau menganiaya dia karena keyakinannya. Dan bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan Allah Subhanahu Wataala berfirman: “Tidak ada paksaan dalam agama”. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: Artinya jangan memaksa seorang pun untuk masuk dalam agama Islam; karena sesungguhnya ia jelas, terang, nyata dalil-dalil dan bukti-buktinya, tidak memerlukan untuk memaksa seseorang untuk masuk di dalamnya. Bahkan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wataala kepada Islam, dan dilapangkan dadanya, dan diterangi mata batinnya, ia masuk ke dalamnya dengan jelas. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wataala, dan dikunci pendengaran dan penglihatannya; maka sesungguhnya tidak bermanfaat baginya masuk agama dalam keadaan dipaksa dan terpaksa.
Dan berkata sebagian mufassirin: Artinya Allah Subhanahu Wataala tidak menjadikan urusan iman atas pemaksaan dan keharusan, tetapi atas pemberdayaan dan pilihan dan semacamnya. Allah Subhanahu Wataala berfirman: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang yang di bumi beriman semuanya. Maka apakah engkau (Muhammad) yang memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” Artinya seandainya Dia menghendaki, niscaya memaksa mereka atas keimanan, tetapi Dia tidak melakukan itu dan membangun urusan atas pilihan.
2 – Kebebasan Berpendapat dan Berpikir:
Yang telah ditetapkan dalam sistem Islam bahwa yang paling agung yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya adalah akal; oleh karena itu kita temukan Al-Quran Al-Karim mendorong manusia untuk menggunakan akal secara terus menerus; agar menuntun mereka kepada kebenaran dan kebenaran. Dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali muncul ungkapan-ungkapan: “berakal” (Surat Al-Ankabut, ayat 35), “berpikir” (Surat Ar-Rum, ayat 21), “mengetahui” (Surat Al-Baqarah, ayat 230), “merenungkan” (Surat An-Nisa, ayat 82), “memahami” (Surat Al-An’am, ayat 65), “sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal” (Surat Az-Zumar, ayat 21).
Dan Al-Quran Al-Karim dengan hal itu sesungguhnya ingin menegakkan kehidupan manusia selalu atas dasar ilmu dan pengetahuan, yang didasarkan pada penelitian dan penggalian, dan pemikiran terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wataala di langit dan bumi; oleh karena itu kebebasan berpikir bagi manusia dijamin dalam Islam sejak awal kemunculannya, selama ia berlindung dengan pagar agama dan syariat selalu. Dan benar bahwa hak ini selalu dijamin bagi manusia dalam dua abad pertama dan kedua Hijriah. Dan meskipun setelah itu mengalami beberapa jenis penganiayaan, dan khususnya pada masa Bani Abbas; dimana Imam Ahmad bin Hanbal dianiaya karena menentang Al-Makmun dalam masalah penciptaan Al-Quran, dan Imam Malik dianiaya pada masa Abu Ja’far Al-Manshur; karena fatwanya tentang tidak sahnya jual beli orang yang dipaksa, dan Imam Abu Hanifah dianiaya; karena tidak mau menjadi hakim, dan Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm dianiaya… dan lainnya. Namun bagaimanapun juga, penganiayaan pemikiran ini tidak mewakili pendapat Islam, ia adalah kejadian yang keliru, yang didorong oleh beberapa hawa nafsu, dan tidak boleh dijadikan hujjah terhadap Islam.
Dan di antara hal-hal yang dialami oleh kebebasan berpikir dalam sistem Islam, dan khususnya dalam bidang fikih: penutupan pintu ijtihad, dan melarang ulama untuk melaksanakannya. Dan ini merupakan pendahuluan bagi periode kejumudan yang dialami oleh pemikiran Islam setelah abad keenam Hijriah; dimana pekerjaan para ulama dan fuqaha terbatas pada sekadar mengulang perkataan orang-orang terdahulu, atau mentakhrijnya, dan membuat catatan kaki atasnya, tanpa para fuqaha membebankan diri mereka dengan bantuan penelitian dan kajian untuk menggali hukum-hukum kejadian-kejadian yang baru; oleh karena itu maka pantas bahwa kebebasan intelektual dipraktikkan, terutama dalam bidang fikih, bagi setiap orang yang mampu melakukan hal itu; agar pemikiran Islam mampu mengikuti peristiwa-peristiwa yang berkembang. Namun harus selalu tidak boleh melakukan ijtihad kecuali orang yang memiliki syarat-syarat syariat yang dikenal dalam ilmu ushul; agar tidak terbuka medan bagi orang-orang bodoh untuk bermain-main dengan hukum syariat.
Tetapi kebebasan berpendapat dalam sistem Islam harus dibatasi dengan hal-hal berikut:
a- Bahwa tujuan dari hal itu adalah nasihat kepada Allah Subhanahu Wataala, kepada Rasul-Nya, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sebagaimana telah shahih dalam Sunnah; dalam hadits syarif: “Agama itu nasihat. Kami berkata: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh rakyatnya.”
Adapun jika menyampaikan pendapat hanya untuk mempermalukan para penguasa, dan menyakiti mereka, dan membalas dendam kepada mereka, dan membawa orang-orang untuk berani kepada mereka… dan semacam itu dari tujuan-tujuan yang tidak benar, yang tidak dimaksudkan dengannya wajah Allah Subhanahu Wataala, dan tidak kebaikan bagi orang yang dinasihati, dan tidak mewujudkan kemaslahatan umum, maka itu adalah sesuatu yang bukan dari agama, bahkan itu adalah jatuh dalam kehormatan manusia yang telah diharamkan oleh agama dan memperingatkan darinya.
Juga harus secara terus menerus kita mencari udzur bagi orang yang menyelisihi dalam apa yang merupakan medan perbedaan; karena pendapat kita tidak lebih layak dari pendapatnya, selama masalahnya adalah ijtihadiyyah. Berdasarkan hal itu maka bukan dari Islam juga membawa manusia dan membatasi mereka untuk mengikuti sebagian pendapat dan keyakinan pribadi. Maka tidak ada keharusan kecuali dengan hukum syariat, dan tidak mampu seorang individu siapa pun untuk mewajibkan dengan pendapatnya jika bertentangan dengan hukum syariat. Maka hendaklah memperhatikan hal ini; karena sesungguhnya itu termasuk kesalahan yang terjatuh di dalamnya sebagian orang kadang-kadang dengan niat baik.
Juga harus seseorang ketika ia menyampaikan pendapatnya selalu berakhlak dengan akhlak Islam dan adabnya, maka tidak menjelekkan kehormatan manusia, dan tidak mencaci mereka, atau melengketkan kekurangan kepada mereka, dengan dalih kebebasannya dalam menyampaikan pendapatnya. Maka manusia bebas selalu selama kebebasannya tidak berubah menjadi kerusakan dan bahaya; agar kebebasan menjadi membangun; agar menimbulkan akibatnya, dan tidak berbalik urusan menjadi terbalik.
3 – Kebebasan Mengajar dan Belajar:
Yang dimaksud dengan kebebasan ini dalam fikih konstitusi dan politik modern: hak individu untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan haknya untuk menerima sejumlah pendidikan, dan haknya untuk memilih dari para guru siapa yang ia kehendaki. Dan dalam sistem Islam, Islam mendorong ilmu, dan menganjurkannya, dan menyeru kepadanya. Allah Subhanahu Wataala berfirman: “Katakanlah, ‘Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'” (Surat Az-Zumar, ayat 9).
Para mufassirin berkata: Artinya orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wataala berupa kebangkitan dan pahala dan siksa adalah benar, dan orang-orang yang tidak mengetahui hal itu. Atau orang-orang yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wataala turunkan kepada para rasul-Nya dan orang-orang yang tidak mengetahui hal itu. Atau yang dimaksud adalah para ulama dan orang-orang bodoh. Dan diketahui bagi setiap orang yang memiliki akal bahwa tidak ada kesamaan antara ilmu dan kebodohan, dan tidak ada kesamaan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh.
Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama” (Faathir: ayat 28). Maknanya: sesungguhnya yang takut kepada-Nya yang Maha Suci dengan gaib adalah orang-orang yang berilmu tentang-Nya, dan tentang sifat-sifat-Nya yang mulia serta perbuatan-perbuatan-Nya yang indah. Maka para ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada-Nya Subhanahu Wataala dan mengagungkan kekuasaan-Nya.
Dan dalam Sunnah ada yang menegaskan hal itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang menempuh jalan untuk mencari ilmu melainkan Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Keutamaan orang berilmu atas orang yang beribadah adalah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang.”
Islam telah menjadikan ilmu terkadang sebagai tuntutan syariat, dan bukan sekadar hak yang boleh ditinggalkan oleh manusia. Allah Azza Wajalla berfirman: “Maka mengapa tidak pergi dari setiap kelompok di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka dapat menjaga diri” (At-Taubah: ayat 122).
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini bukan merupakan bagian dari sisa hukum-hukum jihad, melainkan hukum yang berdiri sendiri tentang pensyariatan keluar untuk menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama. Allah Taala menjadikannya terhubung dengan yang menunjukkan kewajiban keluar untuk berjihad, sehingga safar (perjalanan) menjadi dua jenis:
Pertama: safar untuk jihad.
Kedua: safar untuk menuntut ilmu.
Tidak diragukan lagi bahwa wajibnya keluar untuk menuntut ilmu adalah ketika penuntut ilmu tidak menemukan orang yang dapat ia pelajari darinya di tempat tinggalnya tanpa harus melakukan perjalanan. Dan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat.
Saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepada kalian.
3 – Lanjutan Hak-Hak dan Kebebasan dalam Sistem Islam dan Beberapa Kaidah Sistem Politik dalam Islam
Lanjutan: Hak-Hak dan Kebebasan Individu dalam Sistem Islam: Kebebasan Berkumpul
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu pemimpin kami Muhammad, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Sekarang kita berbicara tentang kebebasan berkumpul. Kita katakan:
Kebebasan-kebebasan ini dalam fiqih politik dan konstitusional positif mencakup:
- Kebebasan pertemuan. – Dan kebebasan membentuk perkumpulan.
Yang dimaksud dengan kebebasan pertemuan adalah: hak individu untuk berkumpul di suatu tempat dalam periode waktu tertentu untuk menyampaikan pendapat mereka, baik dalam bentuk pidato, diskusi panel, ceramah, debat, dan sebagainya.
Adapun kebebasan membentuk perkumpulan yang dimaksud adalah: membentuk kelompok-kelompok terorganisir yang memiliki keberadaan berkelanjutan, bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan memiliki aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Kebebasan ini mencakup seseorang memiliki kebebasan untuk bergabung dengan perkumpulan apa pun yang ia kehendaki, selama tujuannya baik, dan tidak boleh dipaksa untuk bergabung dengan perkumpulan tertentu. Tidak ada halangan dalam sistem Islam, tentu saja, untuk menetapkan kebebasan-kebebasan ini bagi individu, selama tujuannya tidak bertentangan dengan tata tertib umum, karena bertabrakan dengan nash syariat atau kaidah kulliyah dalam syariat. Jika berkumpul untuk tujuan agama, seperti melaksanakan Jumat, Ied, atau shalat berjamaah dan semacamnya, maka ia mengambil hukum dari tujuan yang ingin dicapai. Dan jika berkumpul untuk tujuan yang tidak diakui secara syariat, seperti berjudi atau bersepakat untuk berbuat jahat dan semacamnya, maka itu haram karena bertentangan dengan tata tertib umum Islam, sebagaimana yang telah kami sebutkan.
Kebebasan Ekonomi
Keempat: Kebebasan Ekonomi:
Dalam sistem konstitusional, yang dimaksud dengan ini adalah: kebebasan bekerja dan mencari nafkah, dan kebebasan memiliki. Kebebasan-kebebasan ini ditetapkan untuk manusia agar ia dapat bergerak dengan segala usaha dan kemampuannya untuk bekerja yang membangun dan berbuah, yang manfaatnya kembali kepadanya dan kepada masyarakat tempat ia tinggal.
1 – Kebebasan Bekerja dan Mencari Nafkah:
Islam adalah agama kerja. Ia mengajak manusia kepadanya dan mendorong mereka kepadanya, serta tidak membedakan antara satu pekerjaan dengan yang lain selama dalam bingkai yang diperbolehkan. Allah Taala berfirman: “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Al-Mulk: 15).
Allah Subhanahu Wataala telah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikan bumi bagi mereka mudah dan lembut agar mereka dapat menetap di atasnya, dan Dia tidak menjadikannya kasar sehingga mereka tidak mampu tinggal di dalamnya dan berjalan di atasnya. Kemudian Dia memerintahkan untuk berjalan di bumi, dalam makna kebolehan, agar manusia dapat makan dari apa yang Allah rizkikan dan ciptakan untuknya di bumi.
Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang mukmin yang profesional.” Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam daripada hasil kerja tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya.” Dan sabda beliau Alaihi Salam: “Barangsiapa yang bermalam dalam keadaan lelah mencari yang halal, maka ia bermalam dalam keadaan diampuni.” Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: “Biarkanlah manusia, Allah memberikan rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain.”
Jika Islam telah mengajak manusia untuk bekerja dengan cara ini, maka ia telah memberikan kepada setiap individu kebebasan mutlak dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengannya, karena manusia berbeda-beda dalam hal itu, dan apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Setiap individu boleh memilih untuk dirinya pekerjaan yang manfaatnya kembali kepadanya. Dan negara tentu saja boleh memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu dalam memilih pekerjaan mereka untuk menjamin pelestarian kepentingan umum dalam masyarakat. Negara dapat mengatur pertanian dengan tujuan menanam beberapa tanaman yang menghasilkan keuntungan sehingga ekonomi negara berkembang, atau tanaman yang dibutuhkan umat untuk makanan mereka dan semacamnya. Dan negara boleh melarang penanaman tanaman yang merugikan kepentingan umum, seperti menanam ganja, khat, dan semacamnya. Negara boleh mengatur industri dengan cara ini, demikian juga perdagangan. Dan bukan hanya itu, bahkan negara wajib menyediakan bagi individu kesempatan kerja yang sesuai, memudahkan bagi mereka sebab-sebab kehidupan yang layak, memberantas pengangguran, dan melindungi masyarakat dari kejahatan mereka.
2 – Kebebasan Memiliki:
Sementara kita dapati paham individualisme memberikan kebebasan penuh kepada kepemilikan pribadi dan membolehkan pemilik untuk bertindak dalam kepemilikannya sesuka hatinya tanpa batasan atau batas, meskipun hal itu menyebabkan kerugian bagi orang lain, dengan mengandalkan kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hak kepemilikan kepada pemiliknya, kita menemukan di sisi lain yang berlawanan, paham kolektivisme yang menghapus kepemilikan pribadi secara mutlak, dan menganggap yang mengelolanya hanya sebagai pegawai negara yang bertindak di dalamnya sebagai wakil dari yang mewakilkannya.
Adapun dalam sistem Islam, ada keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif, karena Islam yang mengakui kepemilikan pribadi dan mengakuinya dengan nash-nashnya yang tegas, telah meletakkan batasan dan pembatasan untuk kepentingan masyarakat. Kepemilikan pribadi tidak boleh tumbuh dengan cara yang merugikan kepentingan kolektif, seperti monopoli, penipuan, eksploitasi, dan semacamnya yang diharamkan Islam, dan menjadikannya sebagai batasan-batasan yang dapat membatasi kebebasan mutlak pemilik dalam kepemilikannya, di samping hak-hak lain yang dijadikan untuk fakir miskin dalam harta orang-orang kaya.
Adapun yang berkaitan dengan pengakuan Islam terhadap kepemilikan pribadi, itu adalah perkara yang hampir diketahui dari agama secara pasti, dan hal itu terlihat jelas dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan hadits-hadits Nabi yang mulia, yang menisbatkan kepemilikan kepada manusia, seperti firman Allah Taala: “Dan jika kamu beriman dan bertakwa, niscaya Dia memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu” (Muhammad: ayat 36). Dan firman-Nya Subhanahu Wataala: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Al-Ma’arij: ayat 24-25). Dalam Sunnah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Wada’: “Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian dan Dia menanyakan kalian tentang amal-amal kalian. Ketahuilah, hendaknya yang paling dekat menyampaikan kepada yang paling jauh.”
Adapun pengakuan Syariat Islam terhadap kepemilikan kolektif, kita menemukan manifestasi paling jelas dalam masjid-masjid. Masjid adalah milik Allah Taala dengan nash Al-Quran Al-Karim: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah” (Al-Jinn: ayat 18).
Dan penisbahan kepemilikan kepada Allah Subhanahu Wataala berarti bahwa ia adalah milik jamaah kaum muslimin, tempat mereka melaksanakan ibadah dan syiar-syiar mereka.
Demikian juga makna kepemilikan kolektif tampak dalam sistem wakaf, yang merupakan ibadah khusus bagi kaum muslimin, di mana benda wakaf ditahan sebagai milik Allah Taala – yaitu untuk jamaah kaum muslimin – dan hak orang yang diwakafkan kepadanya terbatas hanya pada memetik hasil atau buah saja, tanpa bertindak dalam benda yang diwakafkan.
Makna kepemilikan kolektif juga tampak dalam apa yang dilindungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tanah untuk kuda-kuda kaum muslimin yang mereka tunggangi ketika mereka berperang di jalan Allah Taala, dan ini adalah kondisi fai’ dan ghanimah sebelum dibagikan kepada manusia.
Adapun pembatasan Syariat terhadap hak kepemilikan pribadi, dengan menjamin pelaksanaan fungsi sosialnya, dalam memberi manfaat kepada pemiliknya dan tidak merugikan orang lain, maka Syariat Islam telah membebankan batasan-batasan ini. Jika Syariat mengakui hak kepemilikan, namun hak ini tidak mutlak, melainkan dibatasi dengan batasan-batasan. Batasan-batasan ini bertujuan agar pemilik tidak keluar dari batasan-batasan syariat, dan tindakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat.
Hak Dan Kebebasan Sosial Dalam Sistem Islam
Kemudian kita akan berbicara sekarang tentang hak dan kebebasan sosial dalam sistem Islam, maka kita katakan:
Setelah terjadinya Revolusi Industri di Eropa pada akhir abad kedelapan belas, dan munculnya kapitalisme yang besar, dan berdirinya proyek-proyek besar, serta menonjolnya kesenjangan antara kelas pemilik dan kelas buruh, maka sudah semestinya negara modern melakukan intervensi untuk melindungi para pekerja dan orang-orang yang lemah secara ekonomi terhadap para pemilik dan majikan, dengan cara yang menjamin tercapainya tingkat kehidupan yang layak bagi para pekerja ini, terutama pada masa-masa sakit mereka, ketidakmampuan mereka, dan pengangguran mereka. Konstitusi-konstitusi modern menyebut kelompok hak ini dengan nama “Hak-hak Sosial”. Kelompok hak ini telah mendapat perhatian dari Pembuat Syariat Islam sejak awal kemunculan Islam, dan sebelum konstitusi-konstitusi modern mengenalnya ratusan tahun; hal itu karena syariat Islam adalah syariat yang sempurna, yang mengikuti peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan baru, maka ia mensyariatkan sejak hampir satu setengah abad yang lalu apa yang baru ditemukan umat manusia hari ini. Daftar hak-hak sosial dalam sistem Islam didasarkan pada pertimbangan bahwa kaum mukminin semuanya seperti satu tubuh, maka oleh karena itu masyarakat mereka harus saling bersaudara, saling berbelas kasih, saling mencintai, saling menyayangi, yang dipenuhi dengan keadilan sosial dan ekonomi, dan berinteraksi dengan akhlak dan nilai-nilai luhur, dan dipenuhi dengan ikatan keimanan di antara individu-individunya, dan bertanggung jawab baik individu maupun negara terhadap setiap individu di dalamnya yang sakit, atau lapar, atau telanjang, atau tidak mampu bekerja, atau tertimpa kezaliman ekonomi atau sosial apa pun, baik dia muslim maupun non-muslim, selama dia manusia yang tinggal di negara kaum muslimin.
Dan kita akan menyebutkan beberapa model berikut ini yang mewujudkan bidang-bidang keadilan sosial dalam sistem Islam:
1 – Jaminan Negara terhadap Individu-individu:
Dengan arti bahwa individu menemukan jaminan umum dari negara ketika mengalami kemiskinan atau penyakit, maka tidak ada individu yang binasa di negara kaum muslimin, sementara mereka melihatnya dan mengetahui kebutuhan dan kekurangannya; karena hal itu bertentangan dengan tujuan Pembuat Syariat yang menjadikan kaum mukminin seperti satu tubuh -sebagaimana telah kita sebutkan- dan yang mendorong untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Surat Al-Maidah: ayat 2).
Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menyebutkan dalam Surat Al-Baqarah tafsiran makna kebaikan, maka Dia Yang Maha Mulia berfirman: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat” (Surat Al-Baqarah: ayat 177).
Dan dalam penyebutan Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang zakat setelah apa yang mendahuluinya; terdapat petunjuk bahwa pemberian yang sebelumnya adalah dari kategori sunnah; karena diketahui bahwa zakat adalah rukun dari rukun Islam, dan di dalamnya terdapat upaya memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, dan kekurangan orang-orang yang berkekurangan. Maka seandainya semua manusia menunaikan zakat yang menjadi kewajiban mereka; maka tidak akan ada di masyarakat kaum muslimin orang yang dirugikan oleh kelaparan, atau terbakar oleh api kekurangan dan kebutuhan, apalagi jika mereka beramal sunnah dan beramal dalam mewujudkan kebaikan?!
Dan dalam Sunnah juga terdapat banyak nash yang menegaskan makna ini, dan mendorong kaum muslimin untuk saling berbelas kasih dan saling menyayangi di antara mereka, seperti sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Orang yang berusaha (membantu) janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berdiri (shalat) di malam hari dan berpuasa di siang hari”. Dan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Barangsiapa memiliki kelebihan kendaraan maka hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memiliki kendaraan, dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memiliki bekal”.
Dan jika ini adalah maksud Pembuat Syariat Islam dalam masyarakat kaum muslimin, maka umat baik individu maupun negara bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mewujudkan maksud ini; karena negara dalam Islam mewakili umat dan menggantikannya; maka wajib atasnya melaksanakan apa yang telah ditunjukkan oleh syariat, tentang kewajiban saling menyayangi dan saling berbelas kasih di antara anggota masyarakat, yang harus seperti satu tubuh.
Namun perlu diisyaratkan dalam konteks ini bahwa negara ketika menjamin hak ini bagi individu-individu, harus selalu tidak mendorong pada kemalasan, atau pengangguran, atau pengemisan, bahkan wajib atasnya selalu menyediakan kesempatan kerja bagi orang-orang yang mampu; karena itu lebih baik daripada memberikan nafkah kepada mereka, dan menjadikan mereka beban bagi baitul mal jika mereka mampu bekerja. Tetapi jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena usia lanjut, atau ketidakmampuan, atau penyakit; maka dalam keadaan ini wajib membantunya dan memberi nafkah kepadanya, baik dari kerabatnya yang wajib menanggung nafkahnya secara syar’i, atau dari baitul mal kaum muslimin. Diperbolehkan memberikan nafkah kepada orang-orang fakir dari harta zakat, maka jika semua itu tidak mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, maka sebagian ulama fiqih menegaskan bahwa wajib atas orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri untuk menanggung orang-orang fakir mereka, dan penguasa memaksa mereka untuk itu jika zakat tidak mencukupi mereka, maka diberikan kepada mereka makanan pokok yang tidak bisa ditinggalkan, dan pakaian untuk musim dingin dan panas seperti itu, dan tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, dan panas musim panas, dan matahari, dan mata penyakit.
Dari semua yang telah dikemukakan kita dapat melihat: bagaimana Islam bekerja untuk memampukan individu-individu menikmati hak sosial mereka dalam jaminan negara bagi mereka, terutama dalam keadaan ketidakmampuan dan kekurangan; dan dengan demikian hak ini dalam sistem Islam lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan dalam hukum-hukum positif, yang hanya sekadar jaminan negara untuk hak bekerja, yang merupakan puncak hak-hak sosial dalam fiqih hukum konstitusi.
Kewenangan Umat Dalam Pengawasan Terhadap Penguasa
Kita beralih sekarang kepada kaidah lain dari kaidah-kaidah sistem politik dalam Islam, yaitu kewenangan umat dalam pengawasan terhadap penguasa, maka kita katakan:
Syariat Islam tidak cukup dengan nash-nash atau dengan menetapkan kaidah musyawarah sebagai jaminan dari jaminan-jaminan pokok, yang dinikmati dan juga dipatuhi oleh umat dalam negara Islam; untuk mencegah kesewenang-wenangan lembaga-lembaga penguasa terhadap kekuasaan, atau penyimpangannya dari kepentingan umum masyarakat Islam, atau penyalahgunaan penggunaannya, tetapi menetapkan kaidah lain yang tidak kalah pentingnya, bahayanya, dan perlunya jaminannya, dari kaidah musyawarah. Kaidah ini terwujud dalam hak umat Islam untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbuatan dan tindakan penguasa-penguasanya. Dan telah kita lihat sebelumnya dalam lingkup kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan umum, bahwa ia memiliki kewenangan-kewenangan diskresi yang luas, dan dari pelaksanaannya terhadap kewenangan-kewenangan ini dapat meniadakan semua pengaruh dan efektivitas dari setiap kaidah hukum yang ada sebelumnya, yang tujuan dari penetapannya adalah membatasi kesewenang-wenangannya terhadap kekuasaan, atau mencegahnya dari melanggar hukum Islam jika tidak disertai dengan kaidah ini pengawasan yang terus-menerus dan berkelanjutan terhadap berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penguasa, dan terhadap khalifah dalam negara Islam.
Dan pengawasan tujuannya adalah mewujudkan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum-hukum syariat Islam, dan adab-adabnya yang umum, yaitu mewujudkan supremasi syariat Islam, dan bekerja untuk berpegang teguh pada tujuan-tujuannya, baik itu dari penguasa atau yang diperintah; karena kewajiban ini adalah dari kewajiban-kewajiban timbal balik antara umat di satu sisi, dan berbagai kekuasaan di sisi lain. Para ulama fiqih telah membahas pengawasan dengan istilah “Hisbah” dan orang yang melaksanakan pengawasan ini disebut “Muhtasib” baik ia mewakili kekuasaan umum, atau salah satu dari individu kaum muslimin, atau masyarakat Islam.
Bismillahirrahmanirrahim
1 – Lanjutan Hak dan Kebebasan dalam Sistem Islam dan Beberapa Kaidah Sistem Politik dalam Islam
TANGGUNG JAWAB PENGUASA DI HADAPAN UMAT ISLAM “Legalitas Tanggung Jawab”
Dan kita berbicara sekarang tentang dasar legalitas kewajiban umat dalam pengawasan, maka kita katakan:
Nash-nash dalam fiqih Islam telah bergabung untuk menegaskan kewajiban umat, dan kewenangannya dalam pengawasan terhadap penguasa, sebagaimana ijma’ telah sepakat atas kewajiban ketetapan ini, di samping bahwa penerapan praktis pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama telah menjamin hak ini. Dan dari nash-nash ini dan penerapan-penerapan tersebut terlihat jelas bagi kita dengan terang dan jelas:
Bahwa hak umat dalam pengawasan terhadap penguasa bukanlah hak bagi umat Islam, yang memiliki kebebasan untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, sebagaimana ia bukan sunnah yang baik dilakukan dan tidak ditinggalkan, tetapi ia adalah dari kewajiban-kewajiban yang pasti, yaitu bahwa pengawasan terhadap kekuasaan adalah dari kewajiban-kewajiban yang pasti yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan, dan tidak boleh bagi umat Islam meninggalkannya atau mengabaikannya. Dan ini kita temukan dasarnya atau sandarannya dalam Al-Quran Al-Karim, maka Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Surat Ali Imran: ayat 104).
Dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman melalui lisan Luqman: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan” (Surat Luqman: ayat 17).
Dan Allah Ta’ala berfirman: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar” (Surat Ali Imran: ayat 110).
Dan Dia Maha Suci berfirman: “Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak dihalangi (menerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa” (Surat Ali Imran: 113-115).
Dan juga jika kita kembali kepada Sunnah Nabawiyah, maka kita akan menemukan bahwa para ulama fiqih menyebutkan banyak hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mewajibkan amar ma’ruf dan nahi munkar, di antaranya sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Barangsiapa menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; maka ia adalah khalifah Allah di bumi-Nya, dan khalifah Rasul-Nya, dan khalifah kitab-Nya”.
Dan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah berfirman: Hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma’ruf, dan hendaklah kalian mencegah dari yang munkar, sebelum kalian berdoa maka tidak dikabulkan untuk kalian”.
Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman”.
Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab orang-orang khusus karena dosa-dosa orang umum, sampai mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka dan mereka mampu mengingkarinya namun mereka tidak mengingkarinya”.
Dan para ulama fiqih telah bersepakat atas kewajiban menjamin amar ma’ruf dan nahi munkar, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi dalam hal itu.
Dan di samping nash-nash yang mewajibkan amar ma’ruf dan nahi munkar, yang telah kita sebutkan dari Kitab dan dari Sunnah, yang darinya kita menyimpulkan penetapan syariat Islam terhadap kewenangan umat dalam pengawasan terhadap perbuatan kekuasaan-kekuasaan penguasa, maka penerapan praktis pada masa Khilafah Rasyidah telah menjamin aspek ini:
Maka ini Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu menegaskan hak umat dalam pengawasan terhadapnya, dan mempertanyakannya dengan cara yang tegas dan jelas, maka beliau radhiyallahu ‘anhu berkata: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin atas kalian dan aku bukan yang terbaik di antara kalian, maka jika kalian melihat aku di atas kebenaran maka bantulah aku, dan jika kalian melihat aku di atas kebatilan maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku menaati Allah terhadap kalian, maka jika aku bermaksiat kepada-Nya maka tidak ada ketaatan bagiku atas kalian”.
Dan beliau radhiyallahu ‘anhu berkata: “Sesungguhnya aku hanya pengikut dan bukan pembuat bidah, maka jika aku lurus maka ikutilah aku, dan jika aku menyimpang maka luruskanlah aku”.
Dan sebagaimana Abu Bakar menempuh jalan dalam mengakui umat dengan kewenangan pengawasan terhadap khalifah jika ia menyimpang dari kebenaran, atau melanggar hukum Islam, demikian pula Umar radhiyallahu ‘anhu menempuh jalan tersebut, maka ia mengakui hak umat dalam melaksanakan pengawasan terhadapnya. Dan dalam lingkup ini diriwayatkan dari beliau radhiyallahu ‘anhu: “Ketahuilah jika kalian melihat pada diriku kecenderungan maka luruskanlah aku”. Dan salah seorang kaum muslimin menjawabnya dengan berkata kepadanya: “Demi Allah, seandainya kami melihat padamu kecenderungan niscaya kami akan meluruskannya dengan pedang-pedang kami”. Dan Umar mengomentari hal itu dengan berkata: “Segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara kaum muslimin orang yang meluruskan Umar dengan ujung pedang”.
Sebagaimana Umar mendorong umat untuk melakukan pengawasan terhadap para penguasa, ia memutuskan bahwa orang yang paling dicintainya adalah orang yang menyampaikan kepadanya tentang kekurangan-kekurangannya. Pernah seorang muslim berkata kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah wahai Amirul Mukminin!” Ketika salah seorang yang hadir keberatan dengan apa yang dikatakan orang tersebut kepada khalifah yang paling agung dan paling adil, dengan mengatakan kepadanya: “Apakah kamu berkata kepada Amirul Mukminin: bertakwalah kepada Allah?!” Saat itu Umar membentak orang ini dan berkata kepadanya: “Ya, bagus apa yang ia katakan; tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mengatakannya, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mendengarnya.”
Umar menganggap dirinya seperti rakyat biasa, hanya saja ia berbeda dari mereka dalam besarnya tanggung jawab, dan bahwa ia adalah orang yang paling berat bebannya. Jika salah seorang rakyat berbicara dengannya tentang suatu masalah, atau Umar menempuh suatu cara yang disangka sebagian orang bertentangan dengan syariat, maka ia melapangkan dadanya untuk kritik atau pertanggungjawaban apa pun dari setiap individu muslim.
Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab mendapat kain-kain jenis burud (sejenis pakaian) dari Yaman, lalu membagikannya secara merata kepada kaum muslimin. Setiap orang muslim mendapat satu helai kain darinya, dan Umar juga mengambil bagiannya dari kain-kain ini seperti muslim lainnya. Ketika Umar mengenakan baju gamis dan naik ke mimbar menyeru orang-orang untuk berjihad dan meminta dari mereka untuk mendengar dan taat, salah seorang muslim berdiri dan berkata: “Tidak ada pendengaran dan tidak ada ketaatan!” Umar berkata: “Mengapa demikian?” Ia berkata: “Karena Anda mengutamakan diri sendiri atas kami.” Umar berkata: “Dalam hal apa aku mengutamakan diriku?” Ia berkata: “Sesungguhnya kain-kain Yaman—maksudnya pakaian yang datang kepada kami dan Anda bagikan—ketika Anda membagikannya, setiap muslim mendapat satu kain, dan Anda juga mendapat—maksudnya Anda juga mengambil seperti kami—tetapi satu kain tidak cukup untuk menjadi pakaian Anda, dan kami melihat Anda telah menjahitnya menjadi gamis yang sempurna, sedangkan Anda adalah orang yang tinggi, jadi seandainya Anda tidak mengambil lebih dari itu tidak mungkin menjadi gamis untuk Anda.”
Seolah-olah orang ini keberatan kepada Umar bin Khaththab dan berkata kepadanya: Anda mengambil seperti kami satu gamis, setiap orang Anda bagikan kepadanya satu gamis, dan seharusnya Anda mengambil gamis seperti kami, tetapi gamis yang Anda ambil tidak cukup untuk Anda: bagaimana Anda memakainya sekarang? Artinya Anda mengambil lebih dari kami, ia menuduh Umar bin Khaththab dengan itu, padahal ia hanyalah individu biasa dari kaum muslimin. Di sini Umar menoleh kepada putranya Abdullah dan berkata: “Wahai Abdullah, jawablah perkataannya.” Maksudnya bantahlah orang yang menuduhku bahwa aku mengambil dari kain lebih darinya dan lebih dari kaum muslimin. “Wahai Abdullah, jawablah perkataannya.” Maka Abdullah berdiri dan berkata: “Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar ketika ingin menjahit satu kain tidak cukup untuknya, maka aku memberikan kepadanya dari kainku apa yang menyempurnakannya.” Artinya aku memberikan kepada ayahku Umar sebagian dari kain yang menjadi bagianku; karena itu menjadi gamis lengkap untuknya. Di sini orang itu berkata: “Sekarang ada pendengaran dan ketaatan.”
Kaum muslimin telah mempraktikkan semua bentuk pengawasan, dan Utsman sendiri mengakui hak kaum muslimin dalam hal itu—sebagaimana kita lihat sebelumnya. Akibat dari pelaksanaan pengawasan ini oleh para ulama umat adalah banyak di antara mereka yang mengalami pembunuhan dan penyiksaan. Pembunuhan itu hanyalah akibat dari pelaksanaan mereka terhadap kewajiban pengawasan, dan apa yang mereka katakan, serta apa yang mereka laksanakan dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada mereka oleh pembuat syariat. Artinya pekerjaan ini—yaitu pengawasan terhadap penguasa—kami katakan: kaum muslimin tidak mundur dari melaksanakannya, meskipun pelaksanaan mereka terhadap kewajiban pengawasan mendatangkan bahaya kepada mereka. Sebagian dari mereka dibunuh karena pengawasan ini, karena keberatan mereka terhadap tindakan penguasa yang bertentangan dengan syariat, sebagian dipenjara, sebagian dipukuli, tetapi meskipun demikian mereka tidak berhenti melakukan pengawasan ini; atas dasar bahwa pengawasan ini adalah termasuk perkara yang wajib bagi mereka.
Di sini kita ingin membicarakan tentang syarat-syarat orang yang melakukan pengawasan. Jadi, kita telah mengatakan bahwa pengawasan adalah termasuk perkara yang wajib bagi kaum muslimin, tetapi: apakah ada syarat-syarat bagi yang melakukan pengawasan ini?
Ya; harus ada syarat-syarat bagi yang melakukan pengawasan ini. Para fuqaha mensyaratkan pada muhtasib (pengawas) atau yang melakukan pengawasan, beberapa syarat, di antaranya:
- Islam:
Artinya harus muslim. Kewajiban ini termasuk dari kewajiban-kewajiban agama yang diwajibkan oleh pembuat syariat kepada muslim; dengan tujuan meninggikan syiar-syiar Islam, menerapkan hukum-hukumnya, dan menjauhi apa yang dilarang-Nya; oleh karena itu tidak boleh bagi non-muslim melaksanakannya. Artinya kewajiban pengawasan adalah salah satu syiar Islam, dan karena ia adalah syiar Islam maka diketahui bahwa yang melakukannya dan yang menjaga syiar-syiar ini hanyalah muslim; karena itu disyaratkan pada muhtasib atau yang melakukan pengawasan untuk menjadi muslim.
- Syarat kedua: Baligh dan berakal:
Harus terpenuhi pada orang yang melakukan kewajiban pengawasan untuk menjadi baligh dan berakal, dan ini syarat yang jelas; karena yang tidak baligh atau tidak berakal tidak terkena kewajiban perintah dan larangan; berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Pena diangkat dari tiga orang (di antaranya disebutkan): anak kecil sampai ia baligh atau bermimpi basah, dan orang gila sampai ia sadar.” Mereka ini tidak bertanggung jawab; karena itu tidak ditujukan kepada mereka kewajiban untuk melakukan pengawasan.
- Syarat lain dari syarat-syarat orang yang melakukan pengawasan: Keadilan (adalat):
Syarat keadilan adalah hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha:
Sebagian berpendapat perlu terpenuhi pada orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran syarat ini. Artinya sebagian fuqaha mengatakan bahwa harus terpenuhi keadilan pada orang yang melakukan pengawasan; oleh karena itu muhtasib atau yang melakukan pengawasan harus menjauhi apa yang dilarang oleh pembuat syariat dan tidak tercemar dengannya, dan inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash dalam Alquran dan Sunnah. Adapun dari sisi nash-nash yang mewajibkan hal itu dalam Alquran seperti firman Allah Azza wa Jalla: “Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?” (Surat Al-Baqarah: 44) Dan firman Allah Azza wa Jalla: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (Surat Ash-Shaff: 2-3).
Inilah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan pengawasan atau muhtasib harus adil, dalam arti tidak melakukan kemungkaran yang ia ingin melarangnya.
Adapun pendapat kedua dari para ulama berpendapat tidak mensyaratkan syarat ini. Artinya sebagian fuqaha tidak mensyaratkan pada muhtasib untuk menjadi adil. Syaikh Al-Ghazali memutuskan bahwa semua yang mereka sebutkan adalah khayalan, orang fasik berhak melakukan kewajiban ini; karena merampas haknya dari hak ini, dan tidak memperbolehkan pelaksanaannya oleh orang fasik, berarti yang melaksanakannya harus maksum (terpelihara) dari maksiat, dan jika dikatakan demikian; maka ucapan ini bertentangan dengan ijmak yang menyepakati tidak adanya kemasuman; para sahabat tidak maksum, sebagaimana para nabi juga diperselisihkan tentang kemasuman mereka, di samping itu nash-nash umum mewajibkan amar makruf nahi munkar kepada orang fasik dan orang adil.
Jadi masalahnya khilafiyah (diperselisihkan)—sebagaimana kita katakan—sebagian fuqaha mengatakan bahwa disyaratkan pada muhtasib atau yang melakukan pengawasan untuk menjadi adil, dan mereka berdalil dengan ayat-ayat yang telah kami sebutkan, di antaranya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” Dan ini berlaku bagi yang tidak adil jika ia ingin melarang orang lain dari dosanya. Dan kita menemukan pendapat kedua, dan di antara penganut pendapat ini adalah Imam Al-Ghazali, dan ia telah menyebutkan itu secara rinci dalam kitabnya (Ihya Ulumuddin) dan ia menjelaskan bahwa kewajiban pengawasan atau muhtasib tidak disyaratkan keadilan padanya… Mengapa? Ia berkata bahwa nash-nash datang secara umum, nash-nash yang meminta dari muslim untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran datang secara umum, tidak membedakan antara fasik dan bukan fasik, tidak membedakan antara adil dan tidak adil, ini di samping bahwa jika kita mensyaratkan keadilan padanya maka artinya kita mensyaratkan kemasuman dari kesalahan, dan ini tidak ada yang mengatakannya.
Kita katakan: Al-Ghazali memutuskan bahwa ijmak menyepakati kewajiban hisbah (pengawasan) atas setiap muslim, dan pendapat ini juga dianut oleh sebagian fuqaha; mereka berpendapat tidak disyaratkan pada muhtasib untuk menjadi sempurna keadaannya, melaksanakan apa yang ia perintahkan, menjauhi apa yang ia larang, bahkan kewajibannya tetap ada meskipun ia lalai dalam apa yang ia perintahkan, dan dalam keadaan ini muhtasib memiliki dua kewajiban:
Pertama: bahwa ia memerintahkan dirinya terlebih dahulu dengan kebaikan dan melarangnya dari melakukan kemungkaran.
Kedua: bahwa ia memerintahkan orang lain dan melarangnya dari hal itu juga.
Jika ia lalai dalam salah satunya maka tidak pantas mengatakan menggugurkan kewajiban yang lain.
Sebagian berpendapat bahwa pendapat kedua, yaitu yang mengatakan tidak disyaratkan keadilan, sebagian berpendapat bahwa pendapat ini yang benar; karena kuatnya dalil-dalilnya, dan lemahnya dalil-dalil pendapat yang mensyaratkan keadilan. Pendapat ini juga mengatakan bahwa dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh penganut pendapat pertama tidak layak menjadi hujjah dalam tidak bolehnya orang fasik melakukan amar makruf nahi munkar; karena ayat pertama: “Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?” mengingkari mereka meninggalkan amar makruf nahi munkar, tetapi tidak menghalangi mereka melakukannya. Artinya seolah mereka berkata: ayat ini tidak tegas dalam melarang orang fasik dari amar makruf nahi munkar. Demikian juga ayat kedua: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” Ia berkata: yang dimaksud dengannya adalah janji dusta, bukan maksudnya memerintahkan orang lain dan meninggalkan perbuatan.
Kami tidak menerima pendapat yang tidak mensyaratkan keadilan pada orang yang melakukan hisbah dan pengawasan, dan pandangan kami dalam mengambil pendapat yang mensyaratkan keadilan pada yang melakukan kewajiban ini adalah sebagai berikut:
- Bahwa Imam Al-Ghazali keberatan terhadap tidak memberikan hak ini kepada orang fasik; karena pelarangan darinya membawa kepada mensyaratkan kemasuman pada yang melakukan kewajiban ini. Artinya Imam Al-Ghazali ketika berkata: “tidak disyaratkan keadilan” berdalil dengan bahwa jika kita mensyaratkan keadilan, maka artinya kita mensyaratkan padanya untuk maksum, dan ini tidak ada yang mengatakannya. Kami berpendapat bahwa itu tidak benar; mensyaratkan keadilan sama sekali tidak berarti bahwa yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran harus maksum dari kesalahan, kemasuman dari kesalahan adalah satu hal dan mensyaratkan keadilan adalah hal lain, dan tidak ada seorang pun dari penganut pendapat yang mensyaratkan keadilan yang mengatakan perlunya orang yang melakukan kewajiban ini maksum dari kesalahan.
Kedua: bahwa jika kita memperbolehkan memberikan hak ini—yaitu pengawasan terhadap manusia dan penguasa—kepada orang fasik, untuk memerintahkan orang lain yang sepertinya dengan amar makruf nahi munkar; maka ini—menurut kami—membawa kepada hilangnya kewajiban ini sepenuhnya. Jika orang ini melakukan perintah kepada kebaikan yang tidak ia lakukan, atau melarang kemungkaran yang ia tercemar dengan perbuatannya dan tidak menjauhinya; maka keduanya—muhtasib (yang mengawasi) dan muhtasab alaihi (yang diawasi)—akan berhak—jika kita menerima pendapat ini—melakukan kekuasaan itu terhadap yang lain, dan setiap dari keduanya akan menjadi muhtasib dan muhtasab alaihi sekaligus, dan kewajiban sebelum setiap dari keduanya melakukan kekuasaan ini terhadap orang lain adalah ia harus menghentikan dirinya terlebih dahulu dari apa yang dilarang oleh pembuat syariat, dan melaksanakan perintah-Nya; agar ia menjadi tempat keteladanan.
Bukan berarti kami mengatakan bahwa muhtasib harus selamat dari kesalahan sepenuhnya; karena mustahil demikian; manusia adalah manusia, dan setiap manusia rawan kesalahan, tetapi kami mengatakan—sebagaimana ditetapkan sebagian—bahwa muhtasib harus menjauhi apa yang dilarang, menjauhi perbuatannya; agar orang lain tidak berhak melakukan kekuasaan ini padanya.
Kesimpulan bantahan ini terhadap Al-Ghazali yang tidak mensyaratkan keadilan:
Bahwa jika kita memperbolehkan orang fasik melakukan tugas ini—yaitu pengawasan—maka artinya jika ia sendiri membutuhkan orang yang mengawasinya dan melarangnya dari perbuatan yang ia lakukan, bagaimana ia bisa menjadi muhtasib dan muhtasab alaihi sekaligus? Dan bagaimana orang lain bisa meneladaninya? Penyair berkata:
Jangan melarang dari suatu akhlak dan kamu melakukan yang serupa… Aib bagimu jika kamu melakukan yang besar
Selama ia tidak mematuhi hukum-hukum agama, selama ia tidak adil… bagaimana dakwahnya akan berpengaruh terhadap orang yang ia dakwahi kepada kebaikan?
Tidak diragukan ia tidak bisa diteladani, dan tidak diragukan itu akan sia-sia ketika kita memutuskan baginya untuk melakukan pengawasan ini.
Ketiga: bahwa berhujjah dengan keumuman nash-nash untuk memberikan orang fasik hak ini atau kekuasaan itu terhadap orang lain, tidak cukup menjadi dalil untuk menetapkan hal itu; karena kewajiban ini seperti semua kewajiban yang ditetapkan syariat memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun, dan dari syarat-syaratnya menurut kami adalah orang itu harus adil. Jika terpenuhi pada kaidah syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka ia berlaku untuk setiap orang yang terpenuhi padanya, sehingga keluar dari lingkup penerapannya orang yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat dan rukun-rukun ini, tanpa hal itu mempengaruhi keumuman kaidah.
Keempat: bahwa kewajiban ini mengandung makna wilayah (kekuasaan) terhadap orang lain. Kewajiban—dan kami maksudkan dengannya pengawasan—mengandung makna wilayah terhadap orang lain, dan seperti wilayah apa pun disyaratkan pada yang melakukannya untuk menjadi adil, dan orang fasik menurut fuqaha Syafiiyah dan yang mengikuti mereka tidak memiliki wilayah… bagaimana kita bisa memberikan kepadanya kekuasaan wilayah terhadap orang lain sedangkan ia sendiri layak untuk orang lain melakukan kekuasaan ini padanya?!
Kelima: Sebagaimana kami tidak menerima penafsiran terhadap nash-nash yang dijadikan dalil oleh mereka yang mensyaratkan keadilan bahwa nash-nash tersebut bermakna bahwa hukuman merupakan akibat dari meninggalkan kebaikan dan melakukan kemungkaran, tanpa menghalangi mereka untuk melaksanakannya; karena -sebagaimana telah kami tegaskan sebelumnya- kami sama sekali tidak mengakui bahwa hak diberikan kepada orang yang tidak menjaminnya, dan kekuasaan diberikan kepada orang yang seharusnya kekuasaan dipraktikkan atasnya, dan bahwa kami membolehkan seseorang untuk menjamin penerapan hukum padahal dia sendiri yang melanggar hukum dan menerjangnya.
Keenam: Dan bahwa kewajiban ini, karena telah dikaitkan oleh syariat dengan keimanan, bahkan syariat mendahulukannya atas keimanan karena pentingnya dan perlunya menjamin kewajiban ini dalam umat, maka kewajiban ini -yaitu amar makruf nahi mungkar- didahulukan oleh Allah Tabaraka wa Ta’ala atas keimanan, dan Allah menjadikannya sebagai salah satu sifat orang-orang mukmin yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana ia merupakan sifat yang membedakan umat ini dari umat-umat non-Islam lainnya; oleh karena itu, semua ini mengharuskan bahwa orang yang mempraktikkan hak ini harus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh syariat, dan menjauhi apa yang dilarang-Nya; karena Islam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan barangsiapa yang melarang suatu perbuatan maka lebih layak baginya untuk melarang dirinya terlebih dahulu dan menahan diri darinya, dan sebelum memerintah orang lain maka lebih layak untuk memulai dengan memerintah dirinya sendiri.
Syarat keempat dari syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orang yang mempraktikkan hisbah atau melakukan pengawasan: Kemampuan:
Disyaratkan bagi orang yang melakukan pengawasan hisbah bahwa ia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempraktikkan kewajiban ini, dengan cara yang tidak mengakibatkan kerusakan besar pada dirinya, hartanya, atau keluarganya. Hadits yang mulia telah menjelaskan batasan kemampuan manusia dengan cara yang menjamin kewajiban ini dan kemustahilan keluarnya dari batasan kemampuan manusia, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.”
Barangsiapa yang tidak mampu mengingkari dengan tangan, maka di hadapannya ada cara untuk mewujudkan kewajiban ini dengan pengingkaran melalui perkataan, dan barangsiapa yang tidak mampu mengingkari dengan cara terakhir ini, maka tidak ada hisbah atasnya dengan tangan atau lisan; karena ia tidak mampu mewujudkannya dengan kedua cara tersebut, dan orang yang tidak mampu tidak dibebani untuk menjamin apa yang ia tidak mampu mewujudkannya, namun masih ada cara lain di hadapannya yaitu pengingkaran dengan hati, dan cara ini selalu dan selamanya masuk dalam batasan kemampuan dan kekuatan manusia; karena kaitannya dengan perasaan dan hati nurani orang yang dibebani, dan tidak ada campur tangan kekuasaan apapun terhadap gejolak jiwa dan apa yang bergulir dalam hati nurani dan kata hati.
Syarat kelima dari syarat-syarat yang disyaratkan terpenuhi pada orang yang melakukan pengawasan: Ilmu:
Syarat ilmu berbeda kewajibannya tergantung pada apakah perbuatan yang melanggar hukum itu jelas dan nyata, sehingga tidak memerlukan pengetahuan tentang sejauh mana pelanggarannya terhadap hukum dengan keharusan terpenuhinya sifat mujtahid pada orang yang melaksanakan kewajiban ini, ataukah termasuk perbuatan-perbuatan yang rumit dan berkaitan dengan ijtihad; sehingga memerlukan pengetahuan tentang pelanggarannya terhadap hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat ijtihad pada orang yang melaksanakannya. Artinya: apakah disyaratkan bahwa orang yang melakukan pengawasan harus seorang alim mujtahid atau tidak?
Kami katakan: Ini tergantung pada jenis pelanggaran. Jika pelanggaran ini sangat jelas, maka dalam hal ini berarti tidak disyaratkan -yaitu tidak disyaratkan ijtihad-. Namun jika memerlukan pemahaman fikih, dan termasuk perkara yang diperselisihkan, maka dalam hal ini memerlukan ilmu. Jika perbuatan itu termasuk jenis pertama -yaitu yang jelas- maka hak untuk mengingkari dan melawannya adalah bagi setiap muslim, setiap orang, bagi setiap muslim dan orang-orang khusus, dan pelaksanaannya tidak bergantung pada syarat lain, selain syarat Islam, baligh, berakal, adil, dan mampu, baik orang ini seorang imam, hakim, fakih, atau salah satu dari kaum muslimin. Adapun jika perbuatan itu menuntut pengetahuan tentang pelanggarannya terhadap hukum dengan terpenuhinya syarat ijtihad karena termasuk perbuatan dan perkataan yang rumit, maka orang awam tidak memiliki hak dalam pengawasan dan pengingkaran terhadap perbuatan-perbuatan ini; karena mereka mungkin mengingkari suatu perbuatan padahal kenyataannya sebaliknya. Bahkan hak ini hanya diberikan kepada para fuqaha yang memahami nash-nash dan tujuan-tujuan syariat, dan mereka juga kewenangan mereka dalam pengingkaran tergantung pada apakah perbuatan itu telah disepakati hukumnya yang spesifik, ataukah perbuatan ini termasuk masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para fuqaha.
Syarat keenam: Mendapatkan izin terlebih dahulu dari penguasa:
Syarat ini termasuk syarat yang tidak disepakati oleh pendapat-pendapat dalam fikih Islam. Satu pendapat berpendapat bahwa tidak boleh mempraktikkan kewajiban ini -yaitu kewenangan pengawasan- kecuali jika penguasa mengizinkan pelaksanaannya, dan dalih mereka yang berpendapat demikian adalah bahwa pelaksanaan hak ini menuntut penetapan kekuasaan dan wewenang atas orang yang dihukumi; oleh karena itu tidak boleh hak ini diberikan atau ditetapkan pelaksanaan kewajiban ini oleh seorang muslim, kecuali jika penguasa memberikan wewenang kepadanya, dan yang menuntut mendapatkan izin terlebih dahulu dari penguasa adalah tidak bolehnya pelaksanaan kewajiban ini oleh orang kafir atas muslim, dengan pertimbangan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah hak.
Al-Ghazali membantah mereka yang mensyaratkan syarat ini. Ia setelah menetapkan bahwa ini termasuk syarat-syarat yang rusak; karena nash-nash dalam Al-Quran atau Sunnah menunjukkan bahwa setiap orang yang melihat kemungkaran atau diam dari mengingkarinya, maka ia melalaikan kewajiban yang diwajibkan oleh nash-nash untuk mengingkarinya di mana pun ia melihatnya dan bagaimana pun ia melihatnya; oleh karena itu pendapat tentang syarat ini -yang kami maksud adalah mendapatkan izin dari penguasa- adalah kesewenang-wenangan yang tidak memiliki dasar dari syariat. Di sisi lain, tidak bolehnya memberikan hak ini kepada non-muslim atau pelaksanaan kewajiban ini olehnya, kembali pada bahwa non-muslim tidak boleh mempraktikkan kekuasaan atau wewenang apapun atas muslim, di samping bahwa muslim menikmati hak ini, dan wajib atasnya melaksanakan kewajiban ini dengan statusnya sebagai muslim, maka ia berhak atas penghormatan ini dari syariat dan dari agama; karena ini termasuk kewajiban-kewajiban agama, dan seperti kewajiban agama lainnya, pelaksanaannya terbatas pada orang-orang yang beriman pada risalah tanpa yang lain; karena di dalamnya terdapat kekuasaan atas kaum muslimin.
Kami cukupkan sampai di sini, kami titipkan kalian kepada Allah, dan semoga kesejahteraan, rahmat, dan berkah Allah atas kalian.
2 – Pemerintahan di Kalangan Arab Sebelum Islam dan Penjelasan bahwa Imamah adalah Bahasan Fikih
Pemerintahan di Kalangan Arab Sebelum Islam
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, junjungan kami Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kami telah menyelesaikan dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya pembahasan tentang kaidah-kaidah yang menjadi landasan sistem politik dalam Islam yaitu: kaidah hakimiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, kaidah syura dalam Islam, kaidah hak-hak dan kebebasan-kebebasan umum dalam sistem Islam, kaidah tanggung jawab penguasa di hadapan seluruh umat, dan kaidah pengawasan umat terhadap penguasa. Kami mulai dalam perkuliahan ini membahas tentang sistem pemerintahan dalam Islam.
Pembahasan tentang sistem pemerintahan dalam Islam menuntut kami untuk terlebih dahulu melihat sistem pemerintahan di kalangan Arab sebelum Islam, maka kami katakan -dan hanya kepada Allah kami memohon petunjuk-:
Arab sebelum Islam tidak memiliki pemerintahan dalam pengertian yang kita kenal tentang pemerintahan sekarang. Mereka tidak memiliki administrasi yang terorganisir yang memiliki kekuasaan yang dipatuhi oleh manusia dan bekerja untuk menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya serta mencegah perbuatan saling melampaui batas di antara manusia. Mereka adalah bangsa badui atau semi badui yang hidup dalam suku-suku yang beragam dan terpencar. Anggota setiap suku dikumpulkan oleh ikatan darah yang menjadi objek penghormatan dari setiap orang Arab yang hidup di Jazirah Arab. Ikatan ini -yaitu ikatan darah- yang jika ada, baik dalam kenyataan maupun dalam klaim mereka, dianggap sebagai satu kesatuan yang mewajibkan anggota suku mendapat perlindungan penuh di bawah naungannya, dan memberikan setiap individu di dalamnya hak untuk meminta pertolongan darinya, dan suku berkewajiban membela dirinya sebagaimana ia berkewajiban tunduk mutlak pada adat dan agamanya. Suku tersebut menjalani sebagian besar hidupnya dalam konflik dengan suku-suku lain, sehingga terpaksa membuat persekutuan dengan yang lain untuk menangkis serangan atau untuk menyerang persekutuan-persekutuan lain atau untuk tujuan-tujuan lainnya. Jika suku-suku bersekutu dalam persiapan untuk perang dan mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka semua, mereka mengundi di antara para pemimpin. Artinya: mereka melakukan undian di antara orang-orang yang layak menjadi pemimpin, maka siapa yang keluar undiannya dialah pemimpin mereka.
Jika kita melihat sistem-sistem politik yang hidup bersama Arab sebelum Islam, kita dapati sebagian hidup bersama badui di daerah-daerah gurun seperti Najd dan pinggiran Hijaz, di mana suku sekecil apapun adalah kesatuan politik, anggota-anggotanya terikat oleh ikatan darah dan fanatisme kesukuan, dan mereka tidak tunduk pada kekuasaan apa pun bahkan tidak pada kekuasaan kepala suku yang putusannya dapat ditolak oleh setiap individu dalam suku, dan ia hanya bisa mengandalkan kekuatannya jika ia memiliki kekuatan, atau meninggalkan seluruh suku jika ia merasa takut darinya dan bergabung dengan suku lain. Salah satu dari mereka tidak menganggap kepemimpinan atau kekuasaan kepala sukunya kecuali sebagai simbol dari ide umum yang kebetulan ia mengambil bagian darinya. Bahkan ia memiliki kebebasan mutlak untuk menolak apa yang disepakati oleh pendapat mayoritas dari anggota sukunya. Namun ini tidak menghalangi kami untuk mengatakan bahwa beberapa suku, pemerintahan pemimpin-pemimpin mereka terhadap mereka adalah jenis kelaliman dan kezaliman, hingga mereka menghinakan manusia dengan penghinaan yang tidak dihapuskan kecuali dengan munculnya agama samawi yang baru yang dibawa oleh Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Mengingat bahwa suku-suku dianggap sebagai kesatuan-kesatuan yang independen, negeri terbagi menjadi wilayah-wilayah pengaruh yang beragam, setiap wilayah dikuasai oleh suku yang memiliki dominasi atas wilayah tersebut. Suku dipimpin oleh salah satu anggotanya yang diandalkan dalam kepemimpinannya dalam berbagai pertempuran yang dihadapinya melawan suku lain untuk merampas apa yang dimilikinya atau mengembalikan hak yang dirampas oleh yang lain darinya. Kepala suku dipilih dari mereka yang memenuhi syarat-syarat khusus seperti banyaknya harta, besarnya pengaruh, dan menikmati kehormatan dari anggota suku; karena keberaniannya, keteguhan pendapatnya, kesempurnaan pengalamannya dengan usia tuanya dan fanatisme kesukuannya. Pemilihan kepala suku atau syaikhnya tidak dilakukan dengan cara-cara yang kita kenal sekarang dalam pemilihan kepala negara, tetapi dipilih secara spontan jika syarat-syarat yang mereka minta selalu terpenuhi pada pemimpin mereka. Mereka tidak memiliki sistem tertentu untuk pengalihan kekuasaan kepala suku. Jika suku tersebut membesar dan bercabang menjadi banyak cabang yang masing-masing menikmati kehidupan terpisah dan keberadaan independen, dan tidak bersatu kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa untuk bersama-sama membela suku atau melakukan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Kepemimpinan dapat menjadi banyak dalam satu keluarga selama ia memiliki sebab-sebab dominasi dan fanatisme kesukuan, sehingga berpindah dari yang kuat kepada yang kuat yang menguasai anggota sukunya. Kepala suku mungkin memiliki cucu yang setara dengannya dalam kehormatan, kedudukan, dan kekuasaan, dan dalam hal ini ia dapat menempati posisi kepemimpinan dari ayahnya, namun jarang terjadi bahwa kepemimpinan dan kekuasaan diwariskan oleh tiga orang dari satu suku.
Kepala suku dibantu oleh dewan yang disebut masyayikh (para tetua) suku yang mewakili pendapat umum dalam suku dan yang anggotanya dipilih dari mereka yang menonjol dalam pendapat dan bakat-bakat yang dibanggakan oleh suku-suku. Di antara anggotanya ada penyair suku yang diandalkan untuk menampakkan kemuliaan-kemuliaannya dan menyanyikan kepahlawanan-kepahlawanannya. Dewan ini mencakup hakim-hakim suku dari orang-orang terhormat yang terkenal di antara manusia karena kejujuran, amanah, pengalaman, keteguhan pendapat, dan usia tua yang memiliki ketenaran di antara manusia karena kemampuan untuk memutuskan perselisihan mereka dalam masalah-masalah nasab, pembagian, warisan, dan darah. Para hakim ini tidak memutuskan berdasarkan hukum tertulis atau kaidah-kaidah yang dikenal, tetapi mereka merujuk pada adat dan tradisi mereka yang dibentuk oleh pengalaman mereka kadang-kadang, dan apa yang sampai kepada mereka melalui orang-orang Yahudi kadang-kadang yang lain. Hukum jahiliyah ini yang didasarkan pada adat dan tradisi tidak memiliki sanksi, dan orang-orang yang berselisih tidak diwajibkan untuk berhukum kepadanya dan tunduk pada putusannya. Jika mereka berhukum kepadanya, baiklah, dan jika tidak, maka tidak. Jika putusan dikeluarkan, ia mematuhinya jika ia mau.
Dewan ini juga mencakup di antara anggotanya orang-orang berani yang terkenal karena keperkasaannya, dan beberapa individu dari kedudukan-kedudukan khusus seperti peramal dan dukun, ini di samping para syaikh kabilah dan mereka yang memperoleh pengalaman dari kehidupan karena usia tua mereka. Mereka semua mewakili masyayikh suku yang diandalkan oleh kepala suku dalam mengendalikan kemudi sukunya, dan ia tidak dapat melancarkan perang atau membuat perdamaian atau mengambil keputusan-keputusan lain yang mempengaruhi kehidupan suku kecuali setelah mengambil pendapat dewan ini. Pemerintahan suku tidak berjalan dengan nash-nash hukum yang mengaturnya dan mengatur hubungan manusia satu sama lain sebagaimana yang kita kenal dalam hukum-hukum yang mengatur kita saat ini, tetapi pemerintahan di dalamnya berjalan dengan bimbingan naluri dan fitrah, mereka menyetujui sistem yang sesuai dengan pemahaman mereka yang sederhana, sehingga dengan berlalunya tahun-tahun menjadi adat yang tidak dapat diubah oleh seorang individu dengan mudah. Baik dalam hal ini Arab yang hidup di gurun seperti Najd dan pinggiran Hijaz maupun Arab yang mengambil sebagian dari peradaban yang mendiami kota-kota seperti Mekah dan Madinah atau di pinggiran Jazirah Arab seperti kerajaan-kerajaan Yaman di Selatan, kerajaan Hirah di Timur Laut, dan negara Ghassaniyah di Barat Laut.
Dan setiap kabilah memiliki adat dan tradisi khusus yang mungkin berbeda dengan apa yang dimiliki kabilah-kabilah lain, atau mungkin sejalan dengannya dalam banyak hal atau sedikit. Di tengah-tengah Jazirah Arab dan di antara sistem pemerintahan kesukuan, terdapat satu kerajaan yang tidak mampu bertahan kecuali sekitar lima puluh tahun, yaitu Kerajaan Kindah yang dihancurkan oleh raja-raja Hirah dan yang dinisbatkan kepadanya Imru’ul Qais, salah satu penyair Mu’allaqat yang terkenal.
Dan jika kita meninggalkan tengah-tengah Semenanjung Jazirah Arab dan berpindah ke Hijaz, kita menemukan kota-kota yang memiliki kehidupan politik khusus. Setiap kota dari kota-kota Hijaz mengatur dirinya sendiri dan sepenuhnya independen dari yang lain. Demikianlah keadaannya di Mekah, di Madinah, dan di Thaif. Kita menemukan setiap kota juga dikuasai oleh roh kesukuan yang menguasainya secara penuh. Bahkan kita menemukan orang Arab, meskipun berada di kota-kota, tidak mengenal penisbatan kepada kota-kota tersebut, melainkan hanya menisbatkan diri kepada kabilahnya. Orang Arab tidak mengenal penisbatan kepada kota-kota kecuali pada abad kedua Hijriyah.
Mekah, yang memiliki kedudukan paling agung di antara kota-kota Hijaz, tidak diperintah oleh seorang raja. Pemerintahan di sana disandarkan kepada beberapa orang dari keluarga-keluarga besar yang membagi urusan-urusan umum di antara mereka. Telah ditetapkan kesepakatan bahwa yang tertua usianya adalah yang memimpin dan mereka menjulukinya sebagai pemimpin kaum. Yang tertua—maksudnya yang paling tua usianya—pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Abbas bin Abdul Muththalib.
Di Yatsrib (Madinah), kepemimpinan diperebutkan oleh dua kelompok, yaitu Aus dan Khazraj. Peperangan terjadi di antara keduanya dan perselisihan berlangsung lama hingga mereka menetapkan bahwa pemerintahan dilakukan secara bergiliran. Kota Madinah dipimpin oleh seorang pemimpin dari salah satu kelompok dengan ketentuan bahwa pemimpin pada tahun berikutnya adalah dari pemimpin kelompok yang lain.
Di pinggiran Semenanjung Jazirah Arab muncul kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah-pisah. Kita melihat kerajaan-kerajaan Yaman di selatan seperti Kerajaan Saba yang memiliki ketenaran luas, khususnya setelah Al-Qur’an Al-Karim membicarakannya dan menceritakan kisah ratunya Balqis dengan Nabi Sulaiman ‘alaihissalam. Perlu dicatat bahwa di Yaman berdiri sistem politik yang berbeda dengan sistem yang berlaku di kota-kota Hijaz. Sementara kita menemukan di kota-kota ini tidak berdiri sistem kerajaan, kita melihat bahwa sistem kerajaan telah berdiri di Yaman karena alasan-alasan ekonomi dan sejarah yang jelas pengaruhnya. Tidak ada di antara kota-kota Hijaz ikatan-ikatan ekonomi yang mengharuskan kepatuhan mereka kepada satu sistem sebagaimana yang terjadi di Yaman. Di Yaman telah berdiri ikatan-ikatan ekonomi yang mengharuskan adanya aturan-aturan umum yang dihormati semua orang dan mereka terapkan dalam pemerintahan di antara mereka. Selain itu, Yaman telah dilanda penjajahan Habsyi (Ethiopia) dan Persia. Penjajahan berkepentingan agar penguasaannya atas negeri itu lengkap, maka orang-orang Habsyi dan Persia mendirikan seorang penguasa untuk negeri yang seluruhnya tunduk kepada kekuasaannya dengan kekuatan jika mereka tidak tunduk dengan kerelaan dan pilihan. Hijaz tidak dilanda penjajahan seperti Yaman.
Dari semua itu kita melihat bahwa ide kesukuan adalah yang menguasai Semenanjung Jazirah Arab dan merupakan tiang kehidupan secara politik dan sosial. Tidak ada pemerintahan pusat yang menguasai negeri-negeri Arab sebelum Islam dan memperkuat sisi hukum serta bekerja untuk menegakkan ketertiban di negeri. Hukum tidak memiliki kekuatan yang melindungi dan menjaganya, bahkan pemilik hak harus berusaha meraihnya dengan fanatisme kesukuan dan kekuatannya.
Kemunculan agama Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah pertanda berakhirnya masa kesewenang-wenangan, dominasi, dan kekacauan yang dialami Jazirah Arab. Islam memiliki keutamaan tertinggi bagi massa rakyat yang diselamatkannya dari kehidupan penindasan dan kesewenang-wenangan serta berakhirnya kesewenang-wenangan penguasa terhadap yang dikuasai. Jazirah Arab sebelum Islam telah mengenal berbagai bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan yang tidak kurang dari bentuk-bentuknya yang terkenal pada bangsa-bangsa lain. Beberapa kabilah badui dan kota telah dikuasai oleh para pemimpin yang mengukur kemuliaan mereka dengan sejauh mana kemampuan mereka menghinakan orang lain. Barangkali kitab-kitab sejarah dan peribahasa memberikan gambaran tentang keadaan beberapa penguasa Arab yang zalim pada masa Jahiliyah. Telah dikatakan tentang sebab peribahasa yang mengatakan: “Tidak ada orang merdeka di lembah Auf,” bahwa ia menindas siapa saja yang tinggal di lembahnya. Setiap orang di sana seperti budak baginya karena ketaatan mereka kepadanya. Kesewenang-wenangan salah seorang dari mereka sampai pada tingkat ia memerintahkan agar tidak ada gadis yang diarak kepada suaminya sebelum diarak kepadanya terlebih dahulu.
Keutamaan Islam jelas dalam mengangkat orang-orang ini dari jurang kemerosotan ke kehidupan yang mulia dan cakrawala kemuliaan yang luas yang tidak akan mereka capai kecuali dengan kemunculan agama baru yang dikabarkan oleh Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Imamah adalah Pembahasan Fikih
Sekarang kita beralih kepada pembicaraan tentang Imamah Kubra (kepemimpinan tertinggi) dan meneliti: apakah ia merupakan pembahasan fikih, ataukah termasuk pembahasan ilmu kalam? Dengan kata lain: apakah ia diteliti dalam akidah, ataukah diteliti dalam hukum-hukum praktis seperti ilmu fikih?
Ini adalah masalah dari masalah-masalah yang para fukaha berselisih padanya. Imamah Kubra atau kepemimpinan negara termasuk masalah yang menimbulkan perhatian sangat besar dalam massa umat Islam, dan perselisihan yang pada beberapa kesempatan mencapai tingkat bertemunya pedang-pedang yang dipikul di kedua sisi oleh tangan-tangan kaum muslimin. Barangkali inilah yang mendorong salah seorang ahli sejarah besar tentang kelompok-kelompok Islam untuk mengatakan: Perselisihan terbesar di antara umat adalah perselisihan tentang imamah, karena tidak pernah terhunus pedang dalam Islam atas dasar kaidah agama seperti terhunusnya pedang atas imamah pada setiap masa. Ini adalah pendapat Asy-Syahrastani dalam (Al-Milal wan-Nihal) jilid pertama halaman 21.
Asy-Syahrastani mengatakan: Perselisihan terbesar di antara umat adalah perselisihan tentang imamah, dan ia menjelaskan bahwa pedang-pedang tidak diangkat dan kaum muslimin tidak saling membunuh kecuali atas dasar kaidah agama seperti imamah. Artinya, seakan-akan imamah adalah di antara perkara-perkara yang paling banyak menyebabkan terhunusnya pedang karenanya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa ungkapan Asy-Syahrastani ini mengandung sedikit berlebihan, karena ia menggeneralisasi hukumnya pada setiap masa. Ia mengatakan: Karena tidak pernah terhunus pedang dalam Islam atas dasar kaidah agama seperti terhunusnya pedang atas imamah pada setiap masa. Maka ia menggeneralisasi hukumnya pada setiap masa, memutuskan bahwa perselisihan yang muncul dari imamah adalah perselisihan terbesar dengan senjata.
Kita menjawabnya dan mengatakan: Tidak terjadi perselisihan di antara individu-individu umat tentang imamah pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tidak dengan pedang atau tanpa pedang. Pedang-pedang tidak terhunus pada masa mereka tentang sesuatu dari agama kecuali apa yang terjadi pada zaman Abu Bakar berupa pertemuan dengan pedang antara kaum muslimin dan orang-orang murtad serta para penolak zakat. Apa yang terjadi pada hari Saqifah sebelum pembaitan Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin tidak dianggap sebagai perselisihan antara dua kelompok kaum muslimin yang bersenjata atau tidak bersenjata. Itu hanyalah diskusi dan dialog antara dua kelompok yang masing-masing memiliki pendapat yang mereka yakini wajib untuk disampaikan. Ketika salah satunya melihat bahwa kebenaran ada pada pihak yang berhadapan dengannya, ia rela dengan sukarela terhadap hal itu. Hal seperti ini terjadi dalam setiap situasi serupa pada setiap umat yang mengalami angin perubahan.
Senjata juga tidak diangkat dalam masa kekhalifahan Umar. Senjata yang diangkat terhadap Utsman dan menyebabkan kematiannya bukanlah didorong oleh perselisihan tentang kekhalifahan, melainkan dari orang-orang yang meyakini kesalahannya radhiyallahu ‘anhu dalam perkara-perkara yang mereka nisbatkan kepadanya. Bahkan pertempuran yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dan orang-orang yang mengangkat senjata kepadanya tidaklah seperti yang dibayangkan sebagian orang. Itu bukanlah perselisihan bersenjata tentang imamah. Orang-orang yang memeranginya dalam Perang Jamal, Shiffin, dan Nahrawan tidak mengklaim bahwa mereka berperang karena meyakini imamah selain Ali. Kita menemukan banyak dari para Sahabat yang hidup sezaman dengan peperangan-peperangan ini dan banyak dari para ulama menganggap apa yang terjadi sebagai fitnah yang menimpa kaum muslimin, hingga sebagian yang menyaksikannya menyendiri dari manusia dan tidak berperang, tidak bersama kelompok ini maupun kelompok itu. Pertempuran antara Ali dan lainnya adalah pertempuran antara ahli keadilan dan ahli pemberontakan, bukan pertempuran atas dasar kaidah agama. Pedang pertama yang terhunus atas perselisihan dalam kaidah-kaidah agama adalah pedang Khawarij dan pertempuran mereka termasuk pertempuran paling besar. Merekalah yang menciptakan perkataan-perkataan yang dengan itu mereka menyelisihi para Sahabat dan berperang karenanya.
Tidak terjadi pertempuran antara Ali radhiyallahu ‘anhu dan orang-orang yang mengklaim ketidaksahan imamahnya. Tidak terbukti bahwa ada seorang pun yang mengatakan pada masa kekhalifahan Ali bahwa ia lebih berhak atas kekhalifahan darinya. Bahkan umat mengakui keutamaan Ali dan haknya dalam mengambil alih urusan setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu ‘anhu wa ardhahu. Sementara kita menemukan bahwa banyak dari kaum muslimin di Madinah telah membaiat Ali radhiyallahu ‘anhu, kita menemukan bahwa Thalhah dan Zubair tidak dibaiat oleh seorang pun dan tidak meminta pembaitan dari seorang pun. Artinya: jika Thalhah dan Zubair menentang Ali, maka peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara mereka dan Ali bukanlah karena mereka mengklaim lebih berhak atas kekhalifahan darinya, melainkan karena perkara-perkara lain. Hal-hal yang telah kita uraikan ini menunjukkan bahwa imamah bukanlah sebab kaum muslimin saling membunuh. Oleh karena itu, ia tidak dianggap termasuk akidah, melainkan dianggap dari perkara-perkara praktis yang diteliti oleh ilmu fikih.
Meskipun terdapat berlebihan dalam ungkapan Asy-Syahrastani sebagaimana telah kita jelaskan, namun hal itu tidak menghalangi pernyataan bahwa kepemimpinan negara atau Imamah Kubra mengambil perhatian dari massa umat dalam kadar yang tidak tersedia sepertinya kecuali untuk sedikit dari masalah-masalah; perhatian yang mencapai tingkat perselisihan yang sampai pada beberapa kesempatan—sebagaimana kita katakan—ke tingkat bertemunya pedang-pedang di antara kaum muslimin. Ia menimbulkan perselisihan politik dan pemikiran di antara kelompok-kelompok umat yang di dalamnya pedang memainkan perannya pada beberapa kesempatan, dan lisan serta pena memainkan perannya pada banyak kesempatan. Imamah Kubra atau kepemimpinan negara telah menjadi masalah terbesar yang menjadi putar penelitian-penelitian politik Islam sepanjang era-era yang berbeda, dan menjadi poros yang tidak terpisah darinya pemikiran-pemikiran para peneliti dalam bidang berbahaya ini.
Syiah adalah yang Pertama Menulis tentang Imamah Kubra
Imamah Kubra telah memiliki peran berbahaya dalam medan penelitian-penelitian ilmiah yang dasarnya diletakkan oleh Syiah Ali radhiyallahu ‘anhu dan orang lain menambahkan kepadanya hasil-hasil penelitian dan pemikiran mereka. Pendapat-pendapat khusus tentang Imamah Kubra diriwayatkan dengan cara lisan yang mengambil bentuk perdebatan atau ditulis dalam surat-surat yang dipertukarkan di antara orang-orang yang menaruh perhatian padanya, atau kadang mengambil bentuk pengajian. Namun penulisan dan penulisan yang terorganisir tidak muncul kecuali pada masa Abbasiyah pertama.
Syiah adalah yang pertama menulis tentang Imamah Kubra dengan tulisan-tulisan ilmiah terorganisir yang muncul sebagai akibat perselisihan yang terjadi antara mereka dan penentang mereka dari Khawarij, Mu’tazilah, dan Ahlus Sunnah. Ketika masa ini adalah masa kejayaan ilmu, ilmu-ilmu berkembang di dalamnya dan perdebatan-perdebatan serta argumentasi-argumentasi tersebar. Kelompok-kelompok lain dari Mu’tazilah dan Khawarij mulai terlibat dengan Syiah dalam perdebatan ilmiah yang dengan itu mereka membantah persoalan-persoalan yang dimunculkan Syiah. Akibatnya muncul hasil pemikiran yang subur yang ditambahkan kepada ilmu-ilmu yang dimiliki kaum muslimin.
Sementara perdebatan berlangsung antara Syiah dan lainnya dari Khawarij dan Mu’tazilah, ada kelompok lain yang jauh dari perdebatan yang berlangsung tentang masalah-masalah ilmu kalam, yaitu kelompok ahli hadits atau Ahlus Sunnah yang enggan masuk dalam pembahasan masalah-masalah ilmu kalam dan menyibukkan diri mereka dengan menggali hukum-hukum fikih dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penelitian-penelitian Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan topik Imamah Kubra datang terlambat dari penelitian-penelitian kelompok-kelompok lain. Yang pertama menghadapi Syiah adalah Mu’tazilah yang merintis jalan bagi Ahlus Sunnah yang pada gilirannya mulai memberikan kontribusi mereka dalam bidang baru ini.
Ketika Syiah—sebagaimana telah kita sampaikan—adalah yang pertama berbicara tentang Imamah Kubra, maka mereka memasukkan penelitian-penelitian mereka yang berkaitan dengannya ke dalam ilmu kalam, karena mereka mengklaim bahwa iman kepada para imam adalah bagian dari iman dan seseorang tidak menjadi mukmin hingga ia beriman kepada imam. Pemikiran yang menguasai mereka inilah yang membuat mereka berbicara tentang imamah dan meneliti nya dalam ilmu kalam yang merupakan ilmu tauhid jika boleh dikatakan demikian. Jadi, mereka menjadikannya dari akidah dan menelitinya sebagai akidah, bukan dari hukum-hukum cabang (furu’).
Bahkan sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah tidak menciptakan makhluk-Nya kecuali karena para imam mereka. Sebagian dari mereka mengatakan: Kami meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta’ala menciptakan seluruh apa yang Dia ciptakan untuk Ahlul Bait ‘alaihimus salam, dan bahwa kalau bukan karena mereka, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi, tidak juga surga dan neraka, tidak pula Adam dan Hawa, tidak pula malaikat-malaikat, tidak pula sesuatu dari apa yang diciptakan, shalawatullah ‘alaihim ajma’in. Sebagian dari mereka mengatakan: Seorang hamba tidak menjadi mukmin hingga ia mengenal Allah, Rasul-Nya, para imam ‘alaihimus salam, dan imam zamannya. Dan perkataan-perkataan lain yang menunjukkan bahwa mereka menjadikan iman kepada imam sebagai bagian dari iman kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala. Semua itu menunjukkan kepada kita sejauh mana yang dicapai Syiah dalam iman mereka kepada imamah dan para imam.
Sebagai akibat dari hal ini—sebagaimana kita katakan—Syiah memasukkan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan imamah ke dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang di dalamnya diteliti hal-hal yang seseorang tidak menjadi mukmin kecuali dengannya, seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan seterusnya, atau yang kita sebut ilmu tauhid. Ilmu kalam meneliti akidah-akidah. Syiah meneliti imamah dalam ilmu kalam dengan menganggapnya sebagai ilmu yang membahas akidah, dan tidak ada akidah bagi seorang mukmin hingga ia beriman kepada para imam sebagaimana pendapat mereka.
Meskipun ada keanehan yang jelas dalam klaim Syiah bahwa imamah merupakan salah satu pokok keimanan yang menyimpang dari ijmak umat, karena yang dikenal dalam agama Islam adalah bahwa orang kafir jika meyakini bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah serta menunaikan hak-hak kalimat ini, maka dengan itu ia menjadi mukmin. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam.” Dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyebutkan keimanan kepada para imam. Dan Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Apabila telah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu menemuinya, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan awasilah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka.” (Surat At-Taubah, ayat 5) dan tidak disebutkan juga dalam ayat ini keimanan kepada para imam. Dan Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama.” (Surat At-Taubah, ayat 11) Dan tidak disebutkan dalam semua itu tentang imamah baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dan imamah tidak disebutkan dalam rukun-rukun iman, dalam hadits yang disepakati yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dalam bentuk seorang Arab Badui dan bertanya kepadanya tentang Islam, iman, dan ihsan, maka beliau bersabda kepadanya: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah,” dan beliau tidak menyebutkan dalam itu tentang imam. “Dan iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari Akhir, kebangkitan setelah kematian, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya,” dan beliau tidak menyebutkan imam. Beliau bersabda: “Dan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu,” dan ini adalah hadits yang disepakati yang telah disepakati kesahihannya oleh para ulama. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan hakikat orang-orang mukmin dan menggambarkan mereka dengan petunjuk tanpa sedikit pun isyarat tentang imamah, artinya bahwa imamah bukanlah bagian dari keimanan sebagaimana yang diyakini oleh Syiah. Perhatikan firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka sajalah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Mereka memperoleh derajat-derajat di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia.” (Surat Al-Anfal, ayat 2-4) Dalam ayat-ayat ini Allah Tabaraka Wata’ala tidak menyebutkan keimanan kepada imamah. Dan firman-Nya Subhanahu Wata’ala: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Surat Al-Hujurat, ayat 15) Dan Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Surat Al-Baqarah, ayat 177) Firman-Nya Subhanahu Wata’ala: “Alif Lam Mim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada (Al-Quran) yang diturunkan kepadamu dan (kitab-kitab) yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Surat Al-Baqarah, ayat 1-5).
Dalam semua ayat-ayat yang telah kami sebutkan ini, dimana Allah Tabaraka Wata’ala menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin, Dia tidak menyebutkan di antara sifat-sifat ini bahwa mereka beriman kepada imamah dan bahwa imamah adalah rukun dari keimanan. Adapun yang mungkin bisa menjadi syubhat bagi mereka dalam klaim mereka, yaitu bagi Syiah yang mengatakan bahwa keimanan kepada imamah adalah syarat, kita tidak menemukan syubhat bagi mereka dalam klaim mereka kecuali hadits yang mereka nisbatkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yaitu “barangsiapa mati dan tidak mengenal imam zamannya maka ia mati dalam keadaan jahiliyah”. Para ulama telah menolak hadits ini. Sebagian dari mereka berkata dalam bantahan: siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan lafal ini? Artinya: di mana perawinya? Dan hadits tidak diterima kecuali dengan perawi, dan di mana sanad hadits? Dan bagaimana boleh berdalil dengan nukilan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tanpa penjelasan jalan yang dengannya terbukti bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakannya? Artinya: tidak diterima hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali jika kami jelaskan sanadnya, kami jelaskan jalan yang menyampaikan hadits ini kepada kami. Jika sanad ini tidak dijelaskan maka hadits ini tidak dianggap. Ini jika hadits tersebut majhul (tidak diketahui keadaannya) di kalangan ahli ilmu hadits, apalagi hadits ini dengan lafal ini tidak dikenal? Karena para ulama dan di kepala mereka Ibnu Taimiyyah mengingkari hadits ini secara keseluruhan. Pertama, ia mengatakan bahwa hadits ini tidak memiliki sanad, dan di mana para perawi hadits ini, selama tidak memiliki perawi maka hadits ini tidak diterima. Bahkan ia mengatakan bahwa hadits ini sama sekali tidak dikenal di kalangan ahli ilmu hadits. Tetapi ada yang mungkin mendekati ini, yaitu yang di dalamnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan maka ia akan bertemu Allah pada hari Kiamat tidak memiliki hujah, dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tidak ada bai’ah (janji setia) maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.” Hadits ini tidak menunjukkan bahwa imamah adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan dengan hadits ini bahwa wajib atas seorang muslim untuk taat kepada imam atau taat kepada penguasa selama penguasa ini tidak memerintahkan kemaksiatan, berdasarkan sabdanya shallallahu ‘alaihi wasallam: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik.” Kemudian jika terjadi bahwa penguasa ini menjadi zalim, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga melarang kita untuk memberontak terhadapnya jika dalam pemberontakan terhadapnya terdapat kerusakan yang lebih besar daripada keberadaannya dalam pemerintahan. Inilah makna hadits tersebut dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan imamah dan apakah ia termasuk pembahasan ilmu tauhid dan kalam atau termasuk pembahasan cabang-cabang. Jadi hadits ini tidak menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung bahwa imamah atau keimanan kepada imamah adalah bagian dari keimanan.
Kami katakan: meskipun mereka menyimpang dari ijmak umat Islam dalam klaim mereka bahwa imamah kubra (kepemimpinan besar) adalah bagian dari keimanan yang telah terbukti kebatilannya dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka tidak puas dengan itu, bahkan mereka menambah bid’ah-bid’ah dan menampakkan berbagai macam kesesatan. Syiah telah menjelaskan dalam tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian mereka tentang imamah berbagai macam bid’ah dan penyimpangan seperti perkataan mereka tentang ishmah (kemakshuman) para imam dari kesalahan, dan mencela tiga khalifah pertama: Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Dan pencacatan terhadap tiga khalifah pertama yang mencapai tingkat tuduhan menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, bahkan mencela seluruh sahabat dan setiap orang yang tidak menyetujui mereka dalam apa yang mereka yakini. Adalah wajar bahwa kelompok-kelompok lain dari kaum muslimin dari Ahlussunnah dan lainnya menjawab mereka dalam bidang penelitian mereka, dan mereka telah meneliti itu dalam ilmu kalam, maka yang lebih tepat dan lebih bermanfaat adalah para ulama menjawab mereka tentang apa yang mereka yakini dalam ilmu kalam juga. Dikatakan: adalah wajar bahwa kelompok-kelompok lain dari kaum muslimin dari Ahlussunnah dan lainnya menjawab mereka di tempat penelitian mereka dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan mereka dalam ilmu yang mereka masukkan kesesatan-kesesatan mereka di dalamnya, agar orang-orang yang membaca klaim-klaim mereka dapat mengetahui jawaban-jawaban para ulama terhadapnya, terutama karena mereka mengklaim bahwa kesesatan ini termasuk rukun akidah. Kenyataannya adalah bahwa pembahasan imamah bukanlah termasuk rukun akidah sedikitpun sebagaimana telah dijelaskan, tetapi ia adalah cabang dari cabang-cabang yang dibawa oleh syariat Islam. Jabatan kepala negara atau imam tidak lebih dari fardhu kifayah yang jika telah dilakukan oleh sebagian maka gugur dari yang lainnya. Adapun ushul ad-din (pokok-pokok agama) bukanlah dari jenis ini, tetapi ia termasuk fardhu ‘ain yang tidak gugur dari satu pun dari mukallaf. Bahkan kami melihat para ulama menegaskan bahwa orang yang jauh dari membahas masalah-masalah imamah lebih selamat agamanya daripada orang yang membahasnya. Ini artinya bahwa imamah bukanlah termasuk rukun akidah, tetapi ia adalah cabang dari cabang-cabang sebagaimana kami katakan. Dan sesungguhnya kami menemukan para ulama menegaskan bahwa tempat alamiah pembahasan imamah bukanlah ilmu kalam.
Tetapi tempat alamiahnya adalah ilmu fikih. Sebagian dari mereka mengatakan: tidak ada perselisihan bahwa pembahasan imamah lebih tepat dengan ilmu furu’ (cabang), karena kembalinya kepada bahwa melakukan imamah dan mengangkat imam yang memiliki sifat-sifat khusus termasuk fardhu kifayah, yaitu urusan-urusan kulli (umum) yang berkaitan dengannya kemaslahatan-kemaslahatan agama atau dunia yang tidak teratur urusan kecuali dengan terwujudnya, maka syariat bermaksud mewujudkannya secara umum tanpa bermaksud terwujudnya dari setiap individu. Tidak tersembunyi bahwa itu termasuk hukum-hukum amaliah bukan akidah. Tetapi karena telah tersebar di antara manusia dalam bab imamah keyakinan-keyakinan yang rusak dan perselisihan-perselisihan bahkan kebohongan-kebohongan yang dingin, terutama dari kelompok-kelompok Rafidah dan Khawarij, dan setiap kelompok cenderung kepada fanatisme yang hampir mengakibatkan penolakan banyak kaidah-kaidah Islam dan kritik terhadap akidah-akidah kaum muslimin serta mencela para khalifah rasyidin, dengan keyakinan bahwa penelitian tentang keadaan-keadaan mereka, kelayakan mereka, dan keutamaan mereka tidak terlalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, para mutakallimin (ahli kalam) memasukkan bab ini ke dalam bab-bab kalam.
Perkataan ini dari para peneliti dalam topik imamah menjelaskan bahwa imamah, pembahasannya adalah dalam ilmu furu’ (cabang) dan bukan dalam akidah, bukan dalam ilmu kalam tetapi dalam ilmu fikih. Kemudian dijelaskan bahwa para fuqaha ingin menjawab Syiah yang menjadikannya sebagai bagian dari akidah, mereka menjawab mereka, maka jawaban yang tepat adalah mereka menjawab mereka dalam akidah yang mereka tulis di dalamnya agar manusia dapat membedakan yang hak dari yang sesat.
Kami cukupkan sampai di sini. Aku titipkan kalian kepada Allah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3 – Makna Khilafah dan Imamah, serta Hukum Mengangkat Imam
Makna: Khilafah, Amirul Mukminin, dan Imam
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada orang yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kini kita akan membahas tentang makna khalifah dan imamah, serta berbagai masalah lain yang berkaitan dengan keduanya. Maka kami katakan – dan dengan pertolongan Allah lah kesuksesan:
Sebelum membahas tentang mazhab-mazhab Islam mengenai pengangkatan kepala negara tertinggi, pertama-tama kita akan menjelaskan gelar-gelar yang biasa disematkan kepada orang yang mengurus urusan kaum muslimin. Gelar-gelar: Khalifah, Amirul Mukminin, dan Imam, adalah gelar yang disematkan kepada orang yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi dalam negara Islam. Masing-masing gelar memiliki kondisi dan latar belakang sejarah yang menyebabkan kemunculan dan penyematan gelar tersebut kepada kepala negara.
Khilafah:
Pada asalnya adalah bentuk mashdar dari kata “khalafa”. Dikatakan: Si fulan menggantikan si fulan di kalangan kaumnya, ia menggantikannya dengan penggantian (khilafah), maka ia adalah khalifah. Pengarang kamus Al-Qamus dan penjelasannya berkata: “Dan ia menggantikannya di kalangan kaumnya dengan khilafah.” Dan kaidah mengharuskan hal itu karena maknanya adalah kepemimpinan. Dalam kitab-kitab bahasa terdapat penjelasan bahwa kata kerja “khalafa” menunjukkan berdirinya seseorang menggantikan orang lain dalam hal yang dulunya dikerjakan oleh orang pertama, baik orang pertama itulah yang mengangkatnya sebagai pengganti, maupun orang kedua datang setelahnya tanpa diangkat oleh orang pertama sebagai pengganti. Dalam Ash-Shihah dikatakan: Si fulan menggantikan si fulan, jika ia menjadi penggantinya. Dikatakan: Ia menggantikannya di kalangan kaumnya dengan khilafah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala: “Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: ‘Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku'” (Surat At-Taubah, sebagian dari ayat 142). Dan “khalaftuhu” juga berarti: jika engkau datang setelahnya. Dalam Mukhtar Ash-Shihah: Si fulan menggantikan si fulan, jika ia menjadi penggantinya. Dikatakan: Ia menggantikannya di kalangan kaumnya, sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku”, dan khalafahu juga berarti: datang setelahnya.
Dari sini jelaslah bahwa lafaz “khilafah” pada asalnya adalah bentuk mashdar dari “khalafa”, kemudian setelah itu dalam penggunaan umum diterapkan untuk kepemimpinan tertinggi, yaitu kekuasaan umum atas seluruh individu umat, dan mengurus kepentingan mereka, serta melaksanakan segala sesuatu yang mewujudkan kemaslahatan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pembuat Syariat Tabaraka wa Ta’ala.
Siapa yang Berhak Disebut dengan Nama Khalifah?
Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak dari orang-orang yang memegang kepemimpinan negara untuk diberi gelar khalifah:
- Sebagian imam salaf – di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu – berpendapat makruh menyebut nama khalifah kepada orang yang datang setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Pendukung pendapat ini berdalil dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Khilafah dalam umatku adalah tiga puluh tahun, kemudian setelah itu adalah kerajaan.”
- Sebagian salaf lainnya berpendapat bahwa nama khalifah juga disematkan kepada siapa saja setelah Hasan bin Ali jika ia memegang kepemimpinan umat, namun disyaratkan dalam penyematan ini bahwa orang yang memegang jabatan tersebut menjalankannya berdasarkan metode keadilan dan jalan kebenaran, dengan berdalil pada riwayat bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu bertanya kepada Thalhah, Az-Zubair, Ka’ab, dan Salman tentang perbedaan antara khalifah dan raja. Maka Thalhah dan Az-Zubair menjawab: Kami tidak tahu. Dan Salman berkata: Khalifah adalah orang yang berlaku adil kepada rakyat, membagi di antara mereka dengan sama rata, menyayangi mereka seperti kasih sayang seorang laki-laki kepada keluarganya dan orang tua kepada anaknya, serta memutuskan perkara di antara mereka dengan Kitab Allah Ta’ala. Maka Ka’ab berkata: Aku tidak menyangka bahwa di majelis ini ada orang yang membedakan antara khalifah dan raja, tetapi Allah Ta’ala telah mengilhami Salman hikmah dan ilmu.
Namun kebiasaan umum berlaku sejak awal Islam bahwa nama khalifah disematkan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin secara umum. Dan dapat dijawab mengenai dalil hadits: “Khilafah dalam umatku tiga puluh tahun…” bahwa yang dimaksud adalah khilafah sempurna, bukan khilafah secara mutlak.
Pengganti Siapakah Khalifah Itu?
Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang digantikan oleh khalifah menjadi empat pendapat:
Pertama: Bahwa khilafah adalah pengganti Allah Ta’ala, maka dikatakan untuk kepala negara tertinggi: Khalifah Allah; karena imam agung mengurus hak-hak Allah Ta’ala terhadap makhluk-Nya. Mereka berdalil dengan firman-Nya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi” (Surat Al-An’am, sebagian dari ayat 164).
Kedua: Bahwa tidak boleh dikatakan untuk seseorang bahwa ia khalifah Allah kecuali Adam dan Daud alaihimassalam, karena firman Allah subhanahu dalam hal Adam: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah” (Surat Al-Baqarah, sebagian dari ayat 30) dan firman-Nya tentang Daud: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di bumi” (Surat Shaad, sebagian dari ayat 26).
Ketiga: Pendapat yang menyatakan bahwa boleh menyematkan nama khalifah Allah kepada seluruh nabi alaihimussalam.
Keempat – dan ini pendapat jumhur fuqaha: Bahwa tidak boleh (menyebut) khalifah Allah, dan mereka menganggap orang yang mengatakan hal itu sebagai orang fasik. Hanya boleh dikatakan: “Al-Khalifah” secara mutlak, atau khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun mengatakan: khalifah Allah, karena sesungguhnya pengangkatan pengganti itu terjadi dalam keadaan kematian atau ketidakhadiran, sedangkan Allah subhanahu kekal selamanya, tidak mengalami kematian, dan tidak mungkin tidak hadir. Adapun dikatakan kepadanya: khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena ia telah menggantikannya di kalangan umatnya dalam kepemimpinan umumnya dalam urusan agama dan dunia sekaligus.
Pendapat ini – yang kami anggap sebagai pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat jumhur yang menyatakan bahwa tidak boleh mengatakan khalifah Allah, tetapi dikatakan: Al-Khalifah secara mutlak, artinya tanpa menisbatkannya kepada sesuatu, atau kita katakan bahwa ia khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam – didukung oleh riwayat Ibnu Mulaikah: bahwa seseorang berkata kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu: Wahai khalifah Allah. Maka Abu Bakar mengingkarinya dan berkata: Aku bukan khalifah Allah, tetapi khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu: Wahai khalifah Allah. Umar berkata kepadanya: Celakalah engkau! Sungguh engkau telah mengambil jangkauan yang jauh. Sesungguhnya ibuku menamaiku Umar, jika engkau memanggilku dengan nama ini aku terima. Kemudian aku dewasa dan diberi kunyah Abu Hafsh, jika engkau memanggilku dengannya aku terima. Kemudian kalian menjadikanku pemimpin urusan kalian dan kalian menamaiku Amirul Mukminin, jika engkau memanggilku dengan itu sudah cukup bagimu.
Dari sini jelaslah bahwa tidak layak menyematkan kepada siapa pun, apapun statusnya, baik rasul maupun bukan rasul, (gelar) khalifah Allah; karena jika kita perhatikan alasan bahwa yang diangkat sebagai pengganti hanyalah orang yang meninggal atau tidak hadir, sedangkan Allah subhanahu suci dari kematian dan ketidakhadiran, maka kita pahami bahwa hal itu juga tidak mungkin untuk Adam dan Daud serta rasul-rasul lainnya alaihimussalam. Dua ayat yang dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat boleh menyebut khalifah Allah untuk Adam dan Daud alaihimassalam tidak mengandung penyematan khalifah Allah kepada keduanya. Yang disebutkan dalam kedua ayat hanyalah kata “khalifah” yang terlepas dari penambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak diragukan bahwa boleh menyematkan kata “khalifah” kepada setiap orang yang memegang imamah kubra (kepemimpinan tertinggi). Seandainya kita anggap bahwa dalil telah tegak bahwa boleh menyematkan khalifah Allah kepada keduanya – yaitu Adam dan Daud alaihimassalam – maka dalam keadaan ini penambahan tersebut tidak lain hanya untuk pengagungan dengan anggapan bahwa ia berdiri untuk melaksanakan hukum-hukum Allah terhadap hamba-hamba-Nya.
Gelar Amirul Mukminin:
Setelah Abu Bakar dibai’at untuk khilafah, orang-orang mulai memanggilnya khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka terus memanggilnya demikian hingga Allah Tabaraka wa Ta’ala mewafatkannya. Ketika Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu dibai’at setelah Abu Bakar mencalonkannya untuk khilafah, mereka memanggilnya khalifah khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus seperti itu untuk beberapa waktu. Tampaknya mereka merasa berat dengan hal itu, karena akan menyebabkan kepanjangan dan beruntun penambahan seiring bergantinya pemimpin. Segera setelah muncul gelar lain selain khalifah, mereka menganggapnya baik dan menjadikannya gelar untuk imam agung atau kepala negara. Gelar ini adalah Amirul Mukminin. Orang pertama yang diberi gelar ini dari para pemimpin menurut kesepakatan adalah Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu. Umar menulis kepada gubernurnya di Irak: “Utuslah kepadaku dua orang yang kuat dan terhormat agar aku bertanya kepada mereka tentang Irak dan penduduknya.” Maka ia mengutus kepadanya Labid bin Rabi’ah dan Adi bin Hatim Ath-Tha’i. Ketika keduanya sampai di Madinah, mereka menambatkan unta mereka di halaman masjid dan masuk ke masjid. Di sana mereka bertemu Amr bin Al-Ash. Keduanya berkata kepadanya: Mintakan izin untuk kami kepada Amirul Mukminin. Maka Amr berkata: Demi Allah, kalian berdua telah menemukan namanya yang tepat; kami adalah kaum beriman dan ia adalah pemimpin kami. Maka panggilah ia dengan itu. Gelar itu menjadi gelar baginya di kalangan masyarakat dan diwariskan oleh para khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu.
Kemudian kaum Syiah menyematkan kepada Ali bin Abi Thalib gelar Al-Imam, sebagai sindiran terhadap pendapat mereka bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi imam shalat daripada Abu Bakar – yaitu lebih berhak atas imamah kubra (kepemimpinan tertinggi) daripadanya. Mereka mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar, sehingga ia lebih berhak atas imamah – yaitu khilafah – daripadanya. Maka mereka mengkhususkan Ali dengan gelar Al-Imam, dan menyematkannya kepada setiap orang setelahnya yang mereka yakini berhak atas jabatan ini. Mereka memanggilnya Al-Imam selama mereka berdoa untuknya secara sembunyi-sembunyi. Jika mereka berhasil menguasai negara, mereka mengubah gelar orang setelahnya menjadi Amirul Mukminin, sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Bani Abbas. Mereka terus memanggil para imam mereka dengan Al-Imam hingga Ibrahim yang mereka nyatakan secara terang-terangan doa untuknya dan mengadakan perang atas perintahnya. Ketika ia meninggal, saudaranya As-Saffah dipanggil dengan Amirul Mukminin.
Lafaz Imam dan Imamah:
Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan topik kepemimpinan negara tidak terkenal dalam kajian kalam atau fikih dengan nama pembahasan khilafah atau imarah mukminin, tetapi terkenal dengan nama pembahasan imamah. Meskipun khilafah, imarah mukminin, dan imamah semuanya menunjuk kepada satu makna yaitu kepemimpinan negara Islam, namun ada sebab yang menyebabkan tersebarnya pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dengan nama pembahasan imamah, yaitu – sebagaimana telah kami katakan sebelumnya – bahwa kaum Syiah adalah orang pertama yang membahas topik imamah kubra. Sebagaimana mereka menamai orang yang mengurus urusan kaum muslimin dengan Al-Imam, mereka juga menamai pembahasan yang berkaitan dengan jabatan ini dengan pembahasan imamah. Ketika lawan-lawan mereka berdebat dengan mereka tentang masalah ini, mereka tidak menemukan halangan untuk menggunakan istilah yang sama dengan mereka, terlebih lagi karena imamah shalat dianggap sebagai jabatan keagamaan tertinggi. Maka dialog berlangsung antara Syiah dan lawan-lawan mereka dengan bahasa yang sama yang diciptakan oleh Syiah. Ini menjadi tradisi yang diikuti oleh setiap orang yang membahas topik ini, dan tidak ada yang mendorong untuk mengubahnya. Juga karena lafaz “imam” telah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan hadits-hadits mulia; Allah menamai Ibrahim dan lainnya sebagai imam dalam firman-Nya subhanahu: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menunaikannya. Dia (Allah) berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi manusia'” (Surat Al-Baqarah, sebagian dari ayat 124). Dan firman-Nya subhanahu: “Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing Kami jadikan orang-orang saleh. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin (imam) yang memberi petunjuk dengan perintah Kami” (Surat Al-Anbiya, ayat 72-73).
Makna Bahasa Kata “Imam”:
Al-Fairuzabadi berkata: Al-Imam adalah apa yang diikuti, baik berupa pemimpin atau lainnya, tali yang ditarik di atas bangunan lalu dibangun mengikutinya, jalan, pengurus perkara yang memperbaikinya, Al-Quran, Nabi shallallahu alaihi wasallam, khalifah, panglima pasukan, apa yang dipelajari anak setiap hari, apa yang dibuat sesuai dengan model, dalil dan keadaan.
Dalam Ash-Shihah: Al-Imam adalah kayu bangunan yang digunakan sebagai patokan untuk meluruskan bangunan. Al-Imam adalah daratan yang luas – yaitu bagian dari tanah atau tempat dari tanah – dan jalan. Firman Allah Ta’ala: “Dan sesungguhnya keduanya benar-benar di jalan yang nyata” (Surat Al-Hijr, sebagian dari ayat 79). Dan Al-Imam: orang yang diikuti petunjuknya.
Ibnu Manzhur berkata dalam bab “amma”: Al-Amm dengan fathah artinya maksud, ammahu amman jika ia bermaksud kepadanya. Dalam hadits Ka’ab bin Malik: “Kemudian diperintahkan untuk menutup pintu terhadap penghuni neraka, maka tidak keluar darinya kesedihan selamanya” artinya dimaksudkan lalu ditutup atas mereka. Dan tayammamtu ash-sha’id untuk shalat. Kemudian ia berkata: Amma al-qauma wa amma bihim: memimpin mereka, dan itu adalah imamah. Al-Imam: setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka di jalan yang lurus maupun mereka dalam kesesatan. Al-Imam adalah orang yang diikuti, baik pemimpin maupun lainnya. Jamaknya adalah a’immah. Dalam Al-Quran: “Maka perangilah pemimpin-pemimpin (a’immah) orang-orang kafir” (Surat At-Taubah, sebagian dari ayat 12) artinya perangilah para pemimpin kekufuran dan para panglima mereka yang orang-orang lemah adalah pengikut mereka.
Dari semua yang telah disebutkan, jelaslah bahwa kata “imam” telah digunakan dalam bahasa untuk berbagai makna, di antaranya: teladan, kepemimpinan, petunjuk, bimbingan, untuk sesuatu yang menjadi model, untuk manusia yang menjadi contoh untuk diteladani, dan berada dalam posisi mengurus perkara dan memimpin manusia.
Dan kepemimpinan (imamah) adalah kata dasar dari “amma”, dikatakan: fulan memimpin orang-orang, yaitu ketika dia menjadi pemimpin mereka yang mereka ikuti. Jika pengikutan itu dalam shalat maka itu yang dikenal dengan kepemimpinan kecil (imamah sughra), dan jika pengikutan itu dalam perintah dan larangan maka itu adalah kepemimpinan besar (imamah kubra), yaitu kepemimpinan negara. Dan harus diperhatikan bahwa jika kata “kepemimpinan” disebutkan secara mutlak untuk seorang muslim maka tidak boleh dipahami kecuali dengan makna kepemimpinan besar. Adapun jika yang dimaksud adalah menggambarkan seseorang sebagai pemimpin dalam suatu cabang ilmu atau selainnya, maka harus ada penambahan kata, misalnya dikatakan: Al-Bukhari adalah imam hadits, Abu Hanifah adalah imam fikih, dan fulan adalah imam Bani Fulan. Dan sebagaimana tidak boleh menggunakan kata kepemimpinan secara mutlak kecuali untuk pemimpin tertinggi negara, demikian pula khilafah dan amirul mukminin (pemimpin orang-orang beriman).
Adapun apa yang diriwayatkan bahwa setiap orang yang diangkat oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk memimpin suatu wilayah, atau pasukan kecil, atau tentara, seperti Abdullah bin Jahsy dan Usamah bin Zaid -maula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam- dapat dikatakan: bahwa ketika mereka menyebut imarah (kepemimpinan) orang-orang beriman untuk orang-orang ini, maka “al” yang ada dalam kata “al-mukminin” (orang-orang beriman) adalah untuk menunjukkan yang diketahui secara khusus, yaitu orang-orang beriman yang bersama masing-masing dari mereka, karena setiap orang dari mereka dalam kenyataannya bukanlah pemimpin bagi semua orang beriman, melainkan pemimpin bagi sebagian mereka. Oleh karena itu kita dapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyapa Usamah bin Zaid dengan berkata: “Assalamu alaikum wahai sang pemimpin.” Dan dia tidak berkata: “Assalamu alaikum wahai amirul mukminin.” Lalu Usamah menjawabnya: “Semoga Allah mengampunimu wahai amirul mukminin, kamu berkata demikian kepadaku?” Maka Umar berkata: “Aku akan terus memanggilmu dengan sebutan pemimpin selama aku hidup, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan kamu adalah pemimpinku.”
Makna Kepemimpinan Besar (Imamah Kubra)
Setelah itu, telah jelas dari apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kaum muslimin dalam periode waktu yang berbeda, dan karena kondisi khusus, memberikan gelar kepada kepala negara dengan gelar-gelar: khalifah, amirul mukminin, dan imam. Tetapi apakah ini berarti bahwa pemimpin tertinggi negara dalam Islam harus diberi gelar dengan salah satu dari gelar-gelar ini agar jabatan ini menjadi islami?
Tidak diragukan lagi bahwa yang mengatakan demikian adalah memaksakan penilaian terhadap masalah-masalah, karena yang penting dalam hal ini adalah bahwa kaum muslimin dan pemimpin mereka tunduk pada hukum Islam, sehingga sistem tersebut dapat disifati sebagai sistem islami, terlepas dari gelar-gelar yang dapat diberikan kepada pemimpin ini, apakah gelarnya khalifah rasulillah, atau amirul mukminin, atau imam agung mereka. Islam tidak peduli dengan gelar-gelar, melainkan peduli dengan apa yang ada di balik gelar tersebut dari hakikat sistem itu sendiri. Jika kaum muslimin pada suatu masa memberikan gelar kepada pemimpin mereka, atau dia sendiri yang memberikan gelar kepada dirinya: khalifah rasulillah shallallahu alaihi wasallam, namun inti sistem yang dia wakili jauh dari komitmen terhadap prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam, maka sistem ini dalam hakikatnya adalah sistem non-islami, meskipun ada gelar “khalifah rasulillah”. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu masyarakat dan pemimpinnya tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum Islam, dan pemimpin ini tidak diberi gelar dari gelar-gelar khilafah, atau amirul mukminin, atau imamah, melainkan diberi gelar lain seperti presiden republik, atau kepala negara misalnya, maka dalam hal ini sistem negara tersebut adalah sistem islami yang tidak dapat dicela oleh siapa pun.
Kesimpulan dalam hal ini: bahwa Islam tidak memandang nama-nama, sebutlah apa yang kamu mau: khalifah, amirul mukminin, imam, yang penting dalam masalah ini adalah bahwa khalifah ini berkomitmen pada hukum-hukum Islam dan sistem Islam.
Definisi Istilah Kepemimpinan Besar (Imamah Kubra)
Setelah kita selesai menjelaskan makna-makna bahasa dan keadaan sejarah yang melingkupi khilafah, amirul mukminin, dan imamah, kita mendefinisikan imamah kubra:
Definisi Al-Mawardi tentangnya: Dipahami dari perkataan Imam Al-Mawardi dalam kitab (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) tentang imamah kubra bahwa: penggantian kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.
Dan diperhatikan bahwa definisi ini menunjukkan beberapa hal penting:
Pertama: bahwa kepemimpinan negara Islam dalam hakikatnya adalah penggantian (perwakilan) dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa kepala negara atau imam agung harus menjadi teladan tertinggi bagi individu-individu umat dalam komitmen penuh terhadap prinsip-prinsip Islam.
Kedua dan ketiga: penjelasan fungsi pemimpin tertinggi negara Islam yang dalam hal ini dia mewakili Rasul shallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama berusaha agar agama tetap terjaga dari segala sesuatu yang merugikannya, dan setelah itu berusaha mengambil semua tindakan yang menjamin kemaslahatan duniawi bagi individu-individu umat.
Telah jelas bagi kita dari apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa imamah kubra dalam hakikatnya adalah kepemimpinan negara Islam, yang tunduk pada hukum Islam, dan berjalan di atas petunjuknya dalam mengatur kemaslahatan umat dalam agama dan dunia; karena tidak ada artinya sebagai penggantian dari Rasul shallallahu alaihi wasallam kecuali bahwa dia dipercayakan dengan garis yang jelas yang telah digambarkan untuknya oleh beliau alaihish shalatu wassalam sebagai pembawa risalah dari Allah tabaraka wa ta’ala. Maka ini bukanlah pemerintahan yang berjalan sesuai dengan hukum positif menurut kemaslahatan dunianya saja, tanpa memandang pada apa yang ada setelah kehidupan dunia, melainkan ini adalah pemerintahan yang mewakili Rasul shallallahu alaihi wasallam. Dan karena kepemimpinan Rasul shallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan hukum Allah dalam segala jenis perilaku manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia, maka demikian pula halnya dengan pemerintahan yang mewakilinya, yaitu berkomitmen untuk menjaga agama, dan berjalan dalam kebijakan duniawinya di atas petunjuk yang jelas yang telah dijelaskan oleh syariat yang mulia. Karena makhluk bukanlah dimaksudkan untuk dunia mereka saja, karena semuanya adalah sia-sia dan batil, karena tujuan akhirnya adalah kematian dan kepunahan. Dan Allah berfirman: “Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara sia-sia” (Al-Mu’minun: 115). Maka yang dimaksudkan dengan mereka sesungguhnya adalah agama mereka yang membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat mereka: “(Yaitu) jalan Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi” (Asy-Syura: 53).
Maka inilah hakikat imamah kubra sebagaimana dijelaskan oleh para ulama muslimin. Maka ini bukanlah kerajaan (monarki), karena raja bergantung dalam mengatur urusan kerajaan pada hukum-hukum yang sering kali zalim terhadap kebenaran, dan tujuannya pada umumnya adalah agar cengkeramannya tetap menguasai seluruh wilayah kerajaannya, tanpa memandang pada apa yang mungkin mengotori pemerintahannya berupa penindasan dan dominasi. Dan imamah kubra tidak memiliki makna ini baik dari dekat maupun jauh, melainkan ia berjalan dengan hukum-hukum dari Pembuat Syariat Yang Maha Bijaksana, yang menjelaskan apa yang harus diikuti dalam perilaku individu-individu satu sama lain, dan dalam hubungan mereka semua dengan Allah tabaraka wa ta’ala. Dan ini juga bukanlah kepemimpinan yang dituntut hanya oleh kebutuhan berkumpulnya manusia, di mana mereka tunduk di bawahnya pada aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka, menurut kemaslahatan politik yang mengatakan tentang manfaat bagi mereka semua; karena hukum seperti ini melihat tanpa cahaya Allah: “Dan barangsiapa yang tidak dijadikan Allah baginya cahaya maka tidak ada cahaya baginya” (An-Nur: 40), karena Pembuat Syariat lebih mengetahui kemaslahatan semua orang dalam apa yang ghaib bagi mereka dari urusan akhirat mereka, dan semua perbuatan manusia akan kembali kepada mereka di tempat kembali mereka baik raja maupun lainnya. Oleh karena itu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian yang dikembalikan kepada kalian”. Dan hukum-hukum politik hanya melihat kemaslahatan dunia saja: “Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia” (Ar-Rum: 7).
Hukum Mengangkat Imam
Posisi Para Ulama tentang Mengangkat Kepala Negara
Penjelasan pendapat para ulama tentang apakah harus didirikan kepemimpinan ini atau tidak harus, yaitu apakah kaum muslimin wajib mengangkat seorang imam untuk mereka ataukah hal itu bukan termasuk perkara yang wajib?
Para ulama umat berbeda pendapat tentang mengangkat imam agung atau kepala negara, apakah wajib atau tidak wajib, menjadi empat madzhab:
Madzhab pertama: berpendapat wajib mengangkat imam secara mutlak, yaitu baik dalam keadaan aman dan stabil, maupun dalam keadaan munculnya fitnah dan pergolakan.
Madzhab kedua: berpendapat tidak wajib mengangkatnya secara mutlak.
Madzhab ketiga: berpendapat wajib mengangkatnya dalam keadaan fitnah dan pergolakan, dan tidak berpendapat wajib dalam keadaan aman dan stabil.
Madzhab keempat: bahwa wajib mengangkat imam dalam keadaan aman, dan tidak berpendapat wajib dalam keadaan munculnya fitnah.
Yang berpendapat wajib mengangkat pemimpin tertinggi negara adalah jumhur (mayoritas terbesar) dari ulama umat; karena itu adalah pendapat Ahlus Sunnah seluruhnya, pendapat Murji’ah seluruhnya, kebanyakan Mu’tazilah dan Khawarij kecuali Najdat dari mereka, dan pendapat Syiah seluruhnya. Namun kita harus memperhatikan beberapa hal:
Hal pertama: bahwa mereka ini dengan kesepakatan mereka semua tentang pernyataan wajib mengangkat imam secara mutlak -yaitu dalam setiap keadaan- baik keadaan aman dan tidak ada pergolakan dan fitnah, maupun keadaan pergolakan dan fitnah, namun mereka berbeda pendapat tentang jalan yang mengarah pada kewajiban: apakah itu syara’ ataukah akal?
Ahlus Sunnah berkata: Sesungguhnya dalil-dalil sam’iyyah (yang didengar dari syara’) adalah yang menunjukkan wajib mengangkat imam, dan tidak ada peran akal dalam hal itu, bertolak dari prinsip yang mereka pegang, yaitu bahwa hukum-hukum hanya diambil dari syara’; dan karena imam dimaksudkan untuk menjalankan urusan-urusan syar’i, seperti menegakkan had (hukuman), dan memenuhi hak-hak. Adapun Zaidiyyah, dan kebanyakan Mu’tazilah, dan Itsna ‘Asyariyyah, mereka berkata: Sesungguhnya akal adalah yang menunjukkan wajib mengangkat imam. Kemudian yang berpendapat bahwa akal adalah yang menunjukkan wajib mengangkat imam, mereka terbagi dari segi arah kewajiban: apakah ditujukan kepada manusia ataukah ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta’ala?
Hal kedua: bahwa jumhur atau mayoritas fuqaha yang berkata: “Sesungguhnya mengetahui wajib mengangkat imam tidak ada jalannya kecuali syara'”, jumhur ini telah menjelaskan bahwa maksud mereka dengan kewajiban di sini adalah kewajiban kifai bukan kewajiban ‘aini (individual), dalam arti bahwa wajib atas umat untuk mengangkat seorang imam untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia, dan kewajiban ini ditujukan kepada semua ahlul halli wal aqdi (orang-orang yang berhak memutuskan dan mengikat) dan orang-orang yang layak untuk menjabat posisi ini. Jika sebagian ahlul halli wal aqdi telah menjalankan kewajiban ini, maka gugur kewajiban dari sisanya. Adapun jika tidak ada seorang pun yang menjalankan kewajiban ini, maka semua ahlul halli wal aqdi berdosa, dan tidak berdosa selain mereka dari anggota umat yang tidak memenuhi syarat-syarat ahlul halli wal aqdi. Maka bukan maksud jumhur di sini dengan kewajiban adalah wajib ‘aini; karena mereka tidak mengatakan bahwa wajib atas setiap individu dari individu-individu umat untuk ikut serta dalam mengangkat imam. Oleh karena itu Qadhi Abu Ya’la berkata -berbicara tentang imamah-: Dan ia adalah fardhu kifayah, yang dikenakan kepada dua kelompok manusia: Salah satunya: ahlul ijtihad sampai mereka memilih. Dan yang kedua: orang yang ada padanya syarat-syarat imamah sampai salah satu dari mereka berdiri untuk imamah. Dan tidak ada atas selain kedua kelompok ini dari umat dalam penundaan imamah dosa dan tidak pula kesalahan.
Kemudian setelah itu kita berbicara tentang dalil-dalil atau bukti-bukti dari mazhab yang mewajibkan, yaitu mazhab yang berpendapat bahwa wajib mengangkat imam – dan mereka sebagaimana kita katakan: mayoritas ulama – kita katakan: ketika kewajiban mengangkat imam telah dinyatakan oleh mayoritas umat Islam dari Ahlussunnah dan selain mereka – sebagaimana telah kita jelaskan – dan ketika Ahlussunnah berdalil atas klaim mereka dengan dalil-dalil yang berbeda dari dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh selain mereka, dan ketika ada sekelompok dari yang berpendapat wajib mengangkat imam yang berpandangan bahwa kewajiban di sini bukan ditujukan kepada makhluk tetapi ditujukan kepada Sang Pencipta – Yang Maha Agung – maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menjelaskan dalil-dalil setiap kelompok dari kelompok-kelompok yang berpendapat wajib mengangkat imam satu per satu; sehingga pandangan semuanya tampak jelas dan terang terhadap jabatan penting ini:
Dalil Pertama
Dalil pertama dari dalil-dalil Ahlussunnah bahwa mengangkat imam adalah termasuk perkara-perkara yang wajib:
Pemilik pendapat ini berdalil dengan ijmak, dan ijmak di sini merupakan salah satu dalil terkuat menurut Ahlussunnah dan yang menyetujui mazhab mereka, tentang wajibnya mengangkat imam secara syar’i, bahkan ia adalah yang terkuat secara mutlak, dan ia adalah ijmak umat Islam bahwa wajib mengangkat kepala negara tertinggi; hal itu karena para sahabat Radiyallahu Anhum telah berijmak tentang wajibnya mengangkat pemimpin bagi mereka untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurus urusan-urusan umat, dalam menegakkan penjagaan agama dan mengatur urusan dunia, maka mereka mengangkat Abu Bakar Radiyallahu Anhu sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Saqifah Bani Sa’idah, setelah diskusi dan dialog sengit antara Muhajirin dan Anshar, yang berakhir dengan keyakinan Anshar bahwa kepemimpinan tertinggi harus berada di Quraisy, dan mereka menyetujui pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam – dan pada hari berikutnya tindakan yang diambil oleh orang-orang musyrik di halaman itu, mendapat persetujuan para sahabat yang tidak hadir dalam pertemuan ini, kemudian para sahabat meskipun mereka berbeda pendapat pada awalnya dalam menentukan pribadi imam, namun ini tidak mengurangi kesepakatan mereka semua tentang wajibnya mengangkatnya, dan Abu Bakar Radiyallahu Anhu telah berkhutbah kepada manusia setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum dibaiat sebagai khalifah dengan mengatakan: “Wahai manusia, barangsiapa menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barangsiapa menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hidup tidak akan mati: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? (Ali Imran: 144) kemudian berkata: “Dan sesungguhnya Muhammad telah pergi menuju jalannya, dan tidak ada jalan lain bagi urusan ini kecuali ada pemimpin yang mengurusnya, maka lihatlah dan kemukalah pendapat-pendapat kalian – semoga Allah merahmati kalian – maka orang-orang menyeru kepadanya dari setiap penjuru: Benar wahai Abu Bakar, tetapi kita menunggu pagi untuk mempertimbangkan urusan ini, dan memilih orang yang akan mengurusnya, dan tidak ditemukan dari para sahabat yang berkata: Sesungguhnya urusan ini baik tanpa ada yang mengurusnya.
Dalil Kedua
Mengangkat imam di dalamnya terdapat penolakan bahaya yang diperkirakan, pemilik pendapat ini berkata: Sesungguhnya dalam mengangkat imam terdapat penolakan terhadap bahaya yang diperkirakan dengan tidak mengangkatnya, dan menolak bahaya yang diperkirakan adalah wajib berdasarkan ijmak; maka kesimpulannya mengangkat imam adalah wajib. Adapun penjelasan mengangkat imam di dalamnya terdapat penolakan bahaya yang diperkirakan, maka sesungguhnya manusia tidak mampu hidup sendiri-sendiri; karena manusia itu makhluk sosial secara alami, tidak mampu hidup sempurna jauh dari individu-individu sejenisnya, dan jika manusia tidak mampu hidup kecuali berkumpul, dan mereka – sebagaimana dikatakan ulama – dengan perbedaan hawa nafsu, dan tercerai-berainya pendapat, dan apa yang ada di antara mereka dari permusuhan, jarang sebagian mereka tunduk kepada sebagian yang lain, maka itu mengakibatkan perselisihan, dan mungkin mengarah kepada kebinasaan mereka semua, dan dibuktikan oleh pengalaman dan fitnah-fitnah yang terjadi ketika wafatnya para penguasa ke tempat lain, sehingga jika berlanjut akan mengganggu penghidupan dan setiap orang menjadi sibuk dengan menjaga hartanya dan dirinya di bawah pedangnya sendiri; dan itu mengarah kepada hilangnya agama dan binasanya seluruh kaum muslimin, maka dalam mengangkat imam terdapat penolakan bahaya yang tidak terbayangkan lebih besar darinya. Dan adapun bahwa menolak bahaya itu wajib; maka ini disepakati di antara semua orang berakal, dan kita lihat para ulama setelah mereka menetapkan dalil seperti ini mereka menjawab apa yang mungkin diajukan oleh pembantah, maka pembantah berkata: Sesungguhnya kalian berkata: Sesungguhnya mengangkat imam di dalamnya terdapat penolakan bahaya yang diperkirakan, dan kami katakan: Bahkan dalam mengangkat imam terdapat bahaya yang diperkirakan, dan itu ditolak dengan sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan” dan penjelasan bahwa dalam mengangkat imam terdapat bahaya-bahaya dari tiga segi, yaitu bahwa mereka menjelaskan atau bahwa mayoritas fuqaha mengatakan bahwa mengangkat imam di dalamnya terdapat penolakan terhadap bahaya yang diperkirakan; karena manusia tidak mampu hidup dalam masyarakat kecuali jika ada yang mengurus urusan mereka, dan mencegah kezaliman – yaitu kezaliman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain – dan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya.
Ada keberatan dari mereka yang mengatakan bahwa tidak wajib mengangkat imam, dan keberatan ini tertuju pada bahwa mungkin dalam mengangkat imam terdapat bahaya, dan mereka jelaskan itu dari beberapa segi:
- Mereka berkata bahwa manusia jika ditunjuk orang lain atasnya dalam perkara-perkara yang dia pahami, dan perkara-perkara yang tidak dia pahami, di dalamnya terdapat bahaya yang jelas, yaitu bahwa manusia secara alami tidak menginginkan dipimpin.
- Juga bahwa sebagian manusia mungkin enggan dipimpin oleh orang lain, sebagaimana kebiasaan manusia, dan ini mengarah kepada perselisihan dan terjadinya fitnah di antara individu-individu umat.
- Dan juga karena imam dapat terkena bahaya maka mungkin terjadi kefasikan, bahkan mungkin terjadi darinya kekufuran, jika umat tidak melakukan pemecatannya maka dia membahayakan dengan kefasikan dan kekufurannya, dan jika dipecat maka itu mengarah kepada memicu fitnah dan kekacauan.
Kami katakan: Ini yang mungkin diajukan oleh pembantah terhadap dalil ini, tetapi pemilik pendapat pertama – yaitu mayoritas fuqaha – menjawab ini bahwa bahaya yang muncul dari meninggalkan pengangkatan imam jauh lebih banyak daripada bahaya yang terjadi dari mengangkatnya; oleh karena itu dikatakan: “Enam puluh tahun dengan imam yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa” dan tidak diragukan bahwa menolak bahaya yang lebih besar itu wajib; maka mengangkat imam adalah wajib.
Fakhruddin ar-Razi berkata menjawab bahwa bahaya-bahaya ini dan sejenisnya mungkin terjadi: Tidak ada perselisihan bahwa larangan-larangan ini mungkin terjadi, tetapi setiap orang berakal mengetahui bahwa jika dibandingkan kerusakan yang terjadi dari tidak adanya pemimpin yang ditaati dengan kerusakan yang terjadi dari keberadaannya, maka kerusakan yang terjadi dari ketiadaannya jauh lebih banyak daripada kerusakan yang terjadi dari keberadaannya, dan ketika terjadi pertentangan maka yang menjadi pertimbangan adalah yang lebih kuat, maka sesungguhnya meninggalkan kebaikan yang banyak karena keburukan yang sedikit adalah keburukan yang banyak, yaitu artinya menanggung bahaya yang lebih kecil demi menolak bahaya yang lebih besar.
Dalil Ketiga
Dan dari dalil-dalil juga tentang wajibnya mengangkat imam:
Bahwa mengangkat imam tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, dan penjelasan itu bahwa diketahui bahwa Syari’ Tabaraka wa Ta’ala memerintahkan menegakkan hukuman-hukuman atas yang berhak, dan mempersiapkan pasukan untuk jihad, dan menutup celah-celah, dan menjaga kehormatan Islam, dan itu tidak dapat dilakukan oleh individu atau individu-individu, tetapi dilakukan oleh kekuasaan tertinggi yang memiliki kemampuan luas, dan hak ketaatan atas keseluruhan umat, dan memiliki kekuatan pengarahan, yang membantunya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, dan kekuasaan tertinggi ini terwujud dalam imamah agung, maka dengannya dapat dilakukan semua kewajiban-kewajiban ini, dan apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka ia wajib, maka mengangkat imam adalah wajib; oleh karena itu sebagian orang berkata: Dan kaum muslimin tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali imam yang melaksanakan hukum-hukum mereka, dan menegakkan hukuman-hukuman mereka, dan menutup celah-celah mereka, mempersiapkan pasukan-pasukan mereka, dan mengambil sedekah-sedekah mereka, dan mengalahkan para perampas dan pencuri dan perampok jalanan, dan menegakkan jumat dan hari raya, dan memutuskan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara hamba-hamba Allah, dan menerima kesaksian-kesaksian yang menegakkan hak-hak, dan menikahkan anak kecil laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki wali, dan membagi ghanimah … semua itu membutuhkan imam, jika tidak ada imam maka terbengkalaialah semua ini.
Dalil Keempat
Tentang wajibnya mengangkat imam: Bahwa para sahabat bersegera mengangkat imam sebelum mereka melakukan penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pemilik pendapat ini yang mengatakan wajib mengangkat imam berkata bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian terhadap urusan khilafah, dan bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan – sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan sesungguhnya para sahabat bersegera mengangkat imam sebelum mereka melakukan penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu karena para sahabat telah berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah untuk memilih yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertemuan mereka berakhir dengan pemilihan Abu Bakar Radiyallahu Anhu dan itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum mereka menguburkannya; yang menunjukkan bahwa mereka menganggap mengangkat imam sebagai kewajiban yang paling penting, jika tidak maka mereka tidak akan rela menguburkan Rasul Yang Paling Agung Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendahulukan pengangkatan imamah atasnya.
Ini adalah dalil-dalil pemilik pendapat pertama, yaitu mayoritas fuqaha dan mayoritas Ahlussunnah yang berpendapat: Bahwa wajib mengangkat imam, dan mereka berdalil dengan empat dalil yang telah kami sebutkan, tetapi dalil-dalil ini tidak luput dari keberatan terhadapnya, dan tidak luput dari pembahasan, maka dari titik tolak ini kami katakan:
Meskipun ijmak – ini adalah ijmak dalil pertama yang dijadikan dalil oleh mayoritas fuqaha tentang wajibnya mengangkat imam – dianggap dalil terkuat dari dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah dan yang menyetujui apa yang mereka pandang tentang wajibnya mengangkat kepala tertinggi atas umat, namun kita dapati bahwa sebagian orang telah memicu perdebatan seputar dalil ini, mencoba mencari kemungkinan bahwa para sahabat telah bersegera mengangkat imam ketika wafatnya setiap pemimpin, mengingat kondisi khusus yang mengharuskan kesegeraan mereka ini. Maka sebagian pembantah berkata: Sesungguhnya itu menunjukkan – jika memang menunjukkan – kepada baiknya menegakkan imam, dan bolehnya mengangkatnya, dan tidak menunjukkan wajibnya itu di setiap masa dan zaman; karena tidak mustahil bahwa para pengangkat Abu Bakar dan yang berkumpul untuk syura, hanya bersegera kepada apa yang mereka segerakan dan bersemangat padanya; karena keadaan mengharuskannya – yaitu kondisi-kondisi yang mengharuskan itu, dan mungkin jika tidak ada kondisi-kondisi ini mereka tidak melakukannya – dan karena yang menguasai prasangka mereka bahwa mengabaikan pengangkatan di dalamnya terdapat kerusakan dan kekacauan, dan tidak ada di antara yang menyelisihi dalam wajibnya imamah dalam setiap keadaan yang menafikan baiknya, dan menolak bahwa mengharuskan sebagian keadaan lari kepadanya; oleh karena itu pembantah ini berkata: Sesungguhnya imam mungkin boleh tidak dibutuhkan dalam sebagian keadaan, yang menguasai prasangka bahwa manusia di dalamnya menetapi kebaikan dan ketepatan dalam kebanyakan hal, keberatan ini tertuju pada bahwa ijmak yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah, atau mayoritas fuqaha, dan mayoritas ulama, tentang wajibnya mengangkat imam, yaitu ijmak, dan yaitu bahwa para sahabat telah berijmak atas khilafah Abu Bakar, pembantah membalas itu dan berkata: Mungkin yang mendorong kaum muslimin kepada itu kondisi-kondisi tertentu, tetapi jika tidak ada kondisi-kondisi di sebagian waktu maka itu tidak berarti wajib mengangkat imam. Maka jenis ini meragukan ijmak.
Tetapi para fuqaha membalas itu, maka kami katakan membantah ini: Bahwa yang zahir dari perbuatan para sahabat dari pendirian mereka imam baru ketika wafatnya setiap imam, dan berulangnya itu dari mereka dalam keadaan-keadaan yang banyak, bahwa itu karena adanya pendorong dalam setiap keadaan untuk menegakkan imam ini. Maka balasan atasnya atau atas pembantah ijmak ini adalah kami katakan kepadanya: Pendorong ini ada di setiap waktu; oleh karena itu wajib mengangkat imam.
Semoga Allah menjaga kalian, dan assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4 – Lanjutan Masalah Pengangkatan Imam, dan Syarat-syarat Kepala Negara
Yang Berpendapat Tidak Wajib Mengangkat Imam di Setiap Keadaan atau Keadaan Tertentu Tanpa Keadaan Lain
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam Sayyidina Muhammad, dan atas keluarganya, dan para sahabatnya, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan, amma ba’du:
Maka kita telah mulai berbicara dalam kuliah sebelumnya tentang masalah apakah wajib mengangkat imam atau tidak? Dan telah jelas bagi kita bahwa ada empat pendapat dalam masalah ini; pertama – yaitu pendapat mayoritas ulama – dan berkata: wajib mengangkat imam secara mutlak, yaitu: dalam keadaan aman, dan dalam keadaan kacau, dan kedua dan berpendapat: tidak wajib mengangkat imam secara mutlak, yaitu: dalam keadaan aman dan dalam keadaan kacau, dan ketiga dan berpendapat: tidak wajib mengangkat imam dalam keadaan aman dan wajib mengangkatnya dalam keadaan kacau, dan keempat dan berkata: wajib mengangkat imam dalam keadaan kacau tanpa keadaan aman.
Dan kita telah menyebutkan dalil-dalil pemilik pendapat pertama yaitu mayoritas ulama yang berpendapat wajib mengangkat imam dalam setiap keadaan, baik keadaan itu keadaan aman atau keadaan fitnah dan kekacauan.
Dan kita mulai sekarang dalam menjelaskan pendapat-pendapat lain, dan menjelaskan dalil-dalilnya maka kami katakan:
Sesungguhnya berkenaan dengan pendapat kedua yang berpendapat tidak wajib mengangkat imam secara mutlak, maka sesungguhnya mereka berdalil dengan yang berikut:
Dalil Pertama
Mereka berkata: Sesungguhnya mengangkat imam memicu fitnah, yaitu mengakibatkan fitnah, dan setiap yang demikian maka ia tidak wajib secara syar’i, maka jadi mengangkat imam tidak wajib secara syar’i. Adapun bahwa mengangkat imam memicu fitnah, maka penjelasannya bahwa hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka mungkin sekelompok manusia ingin memilih satu orang untuk imamah; karena dalam pandangan mereka dia adalah orang yang paling baik dalam hal itu, dan kelompok lain ingin mengangkat yang lain bagi mereka, maka terjadilah saling berebut dan bertengkar di antara massa umat karena itu, dan pengalaman-pengalaman yang banyak mendukung apa yang kami katakan. Dan adapun bahwa setiap yang memicu fitnah tidak wajib secara syar’i maka ia perkara yang jelas dan tidak membutuhkan dalil.
Dalil Kedua
Dan dari dalil-dalil mereka juga: Bahwa agama manusia dan tabiat-tabiat mereka adalah yang mendorong mereka untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka yang agamis dan duniawi, maka tidak ada kebutuhan mereka jadi untuk mengangkat yang menghukumi atas mereka dalam apa yang mereka kuasai, tidakkah engkau melihat teraturnya keadaan-keadaan orang Arab dan pedalaman dalam kehidupan duniawi mereka dan keadaan-keadaan agamis mereka, padahal mereka keluar dari hukum penguasa, tidak menghukumi mereka imam, ini adalah dalil kedua dari dalil-dalil yang berpendapat bahwa tidak wajib mengangkat imam secara mutlak, tidak dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan kacau, dan isi dalil ini bahwa tabiat-tabiat manusia mendorong mereka untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka yang agamis dan duniawi, dan artinya bahwa tidak ada kebutuhan mereka untuk mengangkat imam yang menghukumi atas mereka dalam perkara-perkara yang mereka kuasai, dan mereka bersandar dalam itu atau mengqiyaskan dalam itu kepada keadaan-keadaan orang Arab dan pedalaman, yaitu suku-suku nomaden yang tidak memiliki pemerintahan yang mereka masuki di bawah kekuasaannya.
Namun dalil-dalil yang dijadikan argumen oleh penganut pendapat kedua -yang menyatakan bahwa tidak wajib mengangkat imam secara mutlak- dapat dibantah:
Mereka berkata -sebagaimana kami sebutkan dalam dalil pertama- bahwa pengangkatan imam menimbulkan fitnah di antara manusia, tetapi kami katakan kepada mereka: bahwa keadaan manusia ketika hendak mengangkat imam tidak lepas dari salah satu dari dua hal: yaitu kesepakatan terhadap orang tertentu yang mereka pandang lebih unggul daripada yang lain karena sifat-sifat yang menjadikannya berbeda dari para pesaingnya dalam jabatan ini, atau terjadi perselisihan di antara mereka. Adapun keadaan pertama -yaitu keadaan mereka bersepakat tentang pribadi imam- maka tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa hal itu menimbulkan fitnah di antara manusia, bahkan justru merupakan salah satu cara memadamkan fitnah. Sedangkan keadaan yang lain -yaitu keadaan mereka berselisih dalam menentukan pribadi imam- maka Syariat yang Bijaksana tidak membiarkan permasalahan tanpa aturan-aturan yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan perselisihan ini, melainkan kami katakan: dalam keadaan ini wajib bagi ahli hal dan ikad dalam umat untuk mendahulukan orang yang paling berilmu di antara para calon untuk imamah, jika sama dalam ilmu maka wajib mendahulukan yang paling wara’, jika sama maka wajib mendahulukan yang paling tua usianya, dan semua itu dapat menghilangkan fitnah dan perselisihan. Dengan bantahan ini dapat kita pahami bahwa apa yang dijadikan dalil oleh penganut pendapat kedua yang mengatakan tidak wajib mengangkat imam tidak memiliki tempat dalam dalil ini, dan dalil mereka gugur sehingga tidak dapat diandalkan.
Adapun pernyataan mereka -yaitu yang mengatakan tidak wajib mengangkat imam- bahwa agama dan tabiat manusia mendorong mereka untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia mereka. Kami katakan: bahwa hal ini walau mungkin secara akal, namun mustahil menurut kebiasaan, dan tidak ada bukti yang lebih jelas dari itu selain menyebarnya fitnah dan perselisihan di antara manusia ketika para sultan dan penguasa meninggal, dan klaim bahwa keadaan padang pasir dan pedalaman Arab teratur adalah klaim yang tidak dapat diterima karena kita melihat mereka seperti serigala liar dan singa buas, sebagian tidak membiarkan sebagian yang lain. Maka ini juga dalil yang gugur bagi mereka yang mengatakan tidak wajib mengangkat imam karena perkataan mereka bahwa tabiat manusia membawa mereka untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia mereka, kami katakan: ini persoalan yang tidak dapat diterima karena kenyataan menyelisihi itu, dan ini tampak ketika suatu sistem atau pemimpin jatuh, terjadi perselisihan dan pertikaian di antara manusia, dan tidak dapat mengqiyaskan dengan keadaan padang pasir karena keadaan mereka menyelisihi itu.
Kita sekarang sampai pada mereka yang mengatakan wajib mengangkat imam dalam keadaan tertentu tanpa keadaan lain:
Kami jelaskan dalil mereka dan bantahan terhadap mereka, ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib mengangkat imam ketika keadilan muncul, dan tidak wajib mengangkatnya ketika fitnah muncul, dan kita lihat sebagian pendapat melihat kebalikan dari apa yang dilihat pendapat ini -yaitu wajib mengangkat imam ketika kezaliman muncul, dan tidak wajib mengangkatnya ketika keadilan dan keinsafan muncul- jadi pendapat ketiga dan pendapat keempat masing-masing bertentangan dengan yang lain.
Dan telah berdalil mereka yang berpendapat wajib mengangkat imam ketika fitnah muncul, dan tidak wajib ketika keadilan muncul dan manusia berlaku insaf satu sama lain; bahwa terjadinya fitnah dan kezaliman di antara manusia di dalamnya terdapat bahaya, dan setiap bahaya wajib dihilangkan, maka kesimpulannya terjadinya fitnah dan kezaliman di antara manusia wajib dihilangkan, kemudian tidak mungkin menghilangkan itu kecuali dengan kekuasaan yang kuat dan umum, yang memiliki hak memerintah dan melarang manusia, yaitu kekuasaan imamah, maka wajib menegakkan imamah ketika kezaliman dan fitnah muncul, adapun ketika keadilan dan keinsafan di antara manusia muncul, maka tidak ada bahaya yang terjadi di antara manusia sehingga kita mengatakan wajib menghilangkannya.
Dan dapat kita bantah dalil mereka yang mengatakan wajib mengangkat imam ketika keadilan muncul, dan tidak wajib mengangkatnya ketika fitnah muncul, bahwa sebaliknya dari apa yang kalian katakan; sesungguhnya terjadinya fitnah di antara manusia merupakan pendorong dari pendorong-pendorong terbesar untuk munculnya kekuasaan yang kuat, yang mampu mengembalikan kebenaran ke tempatnya, dan mencegah fitnah, sehingga keadilan merata, dan keamanan tersebar; karena tidak adanya imam dalam keadaan ini merupakan hal yang mendorong para pelaku fitnah untuk terus-menerus dalam kesesatan dan kezaliman mereka, tidak ditakuti oleh kekuatan apapun, dan tidak digentar oleh penguasa, tetapi yang wajib dalam keadaan ini adalah mengangkat pemimpin, dan berkumpulnya massa umat di sekitarnya sehingga ia mampu dengan bantuan orang-orang adil untuk menegakkan hukum Allah, dan memberantas sebab-sebab fitnah dan perselisihan. Ini adalah bantahan terhadap mereka yang mengatakan wajib mengangkat imam ketika keadilan muncul, dan tidak wajib mengangkatnya ketika fitnah muncul.
Dan dapat kita bantah juga terhadap mereka yang mengklaim wajib mengangkat imam ketika fitnah muncul, dan tidak wajib mengangkatnya ketika keadilan muncul dan manusia berlaku insaf satu sama lain, bahwa dalil-dalil yang shahih telah berdiri atas kewajiban mengangkat imam secara mutlak, dan tidak membedakan antara keadaan aman dan fitnah, maka pembedaan antara keadaan aman dan fitnah adalah pembedaan tanpa dalil; karena bahaya sebagaimana terjadi dalam keadaan fitnah juga terjadi dalam keadaan aman, maka kezaliman manusia tidak mungkin ada yang mengklaim bahwa itu terbatas pada keadaan terjadinya fitnah di antara manusia; karena kezaliman manusia terhadap satu sama lain terjadi terus-menerus dalam setiap keadaan, tidak ada perbedaan antara keadaan aman dan keadaan tidak aman, ini kenyataan -kezaliman manusia terhadap satu sama lain terjadi- terus-menerus dalam setiap keadaan, sebagaimana didukung oleh berjalannya kebiasaan mereka sepanjang masa, dan ketika kezaliman terjadi dalam keadaan keamanan tersebar di antara manusia, dibutuhkan imam untuk mengangkatnya; karena ia bahaya yang wajib dihilangkan; dan karena wajah-wajah kebutuhan terhadap imam tidak terbatas pada keadaan terjadinya fitnah; karena sesungguhnya imam dibutuhkan untuk memperhatikan kemaslahatan manusia, dan memutuskan di antara mereka dengan kebenaran; dan untuk menegakkan hukuman mereka, dan mempersiapkan pasukan mereka, dan itu tidak terbatas pada keadaan tertentu tanpa keadaan lain, melainkan umum dalam semua keadaan. Kemudian apakah mungkin ada yang mengklaim bahwa keadaan di mana para sahabat semoga Allah meridhoi mereka bersepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah keadaan terjadinya fitnah di antara manusia?! Jawabannya tentu saja tidak; karena tidak ada pada saat itu di antara mereka perang saudara dan menyebarnya fitnah sehingga dapat dikatakan sebaliknya, dan ketika jelas bahwa keadaan para sahabat pada saat itu bukan keadaan terjadinya fitnah, dan mereka telah bersepakat di dalamnya untuk mengangkat imam; hal itu menunjukkan bahwa pengangkatan imam tidak khusus dalam keadaan fitnah saja, melainkan pengangkatannya wajib dalam setiap keadaan, tidak ada perbedaan antara keadaan fitnah dan keadaan aman dan stabil.
Pendapat yang Rajih:
Dan sekarang setelah kita mengetahui permasalahan pengangkatan pemimpin tertinggi negara, dan dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat-pendapat ini, dan bantahan Ahlussunnah terhadap mereka yang menyelisihi dari penganut mazhab-mazhab lain: kita lihat bahwa pendapat yang paling berhak untuk diterima dan dirajihkan adalah pendapat Ahlussunnah, yang mengatakan wajib mengangkat pemimpin tertinggi negara, dan bahwa kewajiban ini sumbernya adalah syariat, bukan akal sebagaimana diklaim sebagian orang, karena pembicaraan di sini -sebagaimana dikatakan Ahlussunnah- dengan kewajiban, dalam arti berhak mendapat pahala ketika melakukan dan siksa ketika meninggalkan; dan karena imam hanya dikehendaki untuk urusan-urusan syar’i, seperti menegakkan hukuman -yaitu sanksi-sanksi yang telah ditentukan syariat- seperti memotong tangan pencuri… dan selainnya, dan melaksanakan hukum-hukum dan yang serupa dengannya, dan jika apa yang dikehendaki untuknya imam tidak ada campur tangan akal di dalamnya; maka tidak ada campur tangan baginya dalam menetapkan imam adalah dari pintu yang lebih utama.
Jika kita memilih mazhab Ahlussunnah yang mengatakan wajib -yaitu wajib mengangkat imam dalam setiap keadaan- maka itu berarti bahwa kita mengatakan wajib secara mutlak, yaitu bahwa hukum wajib berdiri mengikat kaum muslimin dalam setiap keadaan, baik itu keadaan aman maupun keadaan munculnya fitnah di antara manusia.
Pelajaran: 11 Syarat-syarat Imamah Kubra
Bismillahirrahmanirrahim
1 – Lanjutan masalah pengangkatan imam, dan syarat-syarat kepala negara
Syarat-syarat Imamah Kubra
Dan setelah kita selesai dari topik ini -yaitu masalah pengangkatan imam, dan apakah ini urusan wajib atau tidak wajib, sebagaimana telah kami jelaskan secara rinci- kita beralih sekarang ke topik lain, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi pada kepala negara, kami katakan:
Para ulama umat Islam telah bersepakat bahwa jabatan pemimpin tertinggi negara tidak diwariskan, dan bahwa harus ada sifat-sifat tertentu pada orang yang dicalonkan untuk memegang jabatan penting ini, kecuali kelompok Imamiyah; karena mereka menyimpang dari ijma’ umat, dan berpendapat dengan pewarisan di dalamnya, dan inilah pendapat yang akan kita bahas ketika berbicara tentang cara-cara terbentuknya kepemimpinan, adapun selain mereka dari mayoritas umat Islam maka tidak membolehkan pewarisan menjadi jalan untuk memegang jabatan ini.
Dan ada urusan penting yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa syarat-syarat yang dipersyaratkan para ulama pada orang yang akan ditunjuk memimpin negara Islam, adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam keadaan di mana sifat pilihan tersedia bagi umat, maka wajib baginya dalam keadaan ini untuk tidak menyerahkan urusannya kecuali kepada orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat ini, adapun jika tidak ada keadaan pilihan, dan umat terpaksa dalam keadaan tidak ada pilihan baginya, seperti pemaksaan sebagian yang tidak pantas untuk imamah kubra dengan kudeta militer, maka para ulama dalam keadaan ini menjelaskan bahwa berpegang pada syarat-syarat yang wajib di sini dapat membawa kepada fitnah yang wajib dijaga umat dari masuk dalam kejahatan-kejahatannya, dan pada saat itu dibolehkan secara syariat mengakui keadaan ini untuk sementara sampai datang kesempatan perubahan kepada yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut, dan akan kami jelaskan syarat-syarat ini dan sudut pandang dalam mensyaratkannya sebagai berikut:
Syarat pertama dari syarat-syarat yang harus terpenuhi pada imam adalah syarat: Islam:
Sebagian berkata: para ulama bersepakat bahwa imamah tidak terjalin bagi orang kafir, dan bahwa jika kekafiran terjadi padanya -yaitu setelah memegang khilafah- ia terlepas, demikian juga jika ia meninggalkan penegakan shalat dan seruan kepadanya; karena Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Surah An-Nisa, sebagian dari ayat: 141) Dan adakah jalan yang lebih besar dari kekuasaan imam yang agung? Dan juga karena Allah Subhanahu Wata’ala memerintahkan untuk memerangi non-Muslim sampai mereka masuk Islam atau membayar jizyah, maka bagaimana mungkin non-Muslim memimpin dan mengendalikan perang yang dilancarkan kaum muslimin terhadap non-Muslim; dan atas dasar ini maka tidak boleh mengadakan kepemimpinan negara bagi orang kafir asli atau murtad; karena makna pendirian negara Islam adalah ia berkomitmen dengan hukum Islam, menerapkannya, dan menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran-ajarannya, dan hukum Islam ini tidak dapat dibayangkan penerapannya kecuali oleh orang-orang yang menganut kesetiaan dan ketundukan total kepada hukum ini, sesungguhnya sistem apapun -apapun jenisnya- tidak mungkin dapat menerima menyerahkan posisi pertama di dalamnya -atau posisi penting apapun- kecuali kepada orang yang beriman dengan sepenuh keimanan terhadap sistem ini dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menolongnya.
Syarat kedua dari syarat-syarat yang harus terpenuhi pada imam atau kepala negara, adalah syarat yang juga disepakati umat: yaitu baligh (dewasa), kecuali Imamiyah karena mereka menyimpang dari ijma’ ini, dan membolehkan imam adalah anak kecil, tetapi perkataan ini dari Imamiyah hanyalah perkataan yang tidak dapat diandalkan, dan ijma’ tetap berdiri bahwa tidak boleh mengangkat kepemimpinan negara untuk yang belum baligh.
Di sini mungkin muncul pertanyaan: apa hukumnya jika anak yang belum baligh dipaksakan menjabat dalam keadaan darurat? Maksudnya: jika para ahli fikih telah sepakat bahwa tidak boleh seorang anak yang belum baligh memangku jabatan kepala negara atau imamah kubra (kepemimpinan tertinggi), lalu jika diandaikan anak ini dipaksakan kepada mereka untuk menjadi imam tertinggi atau menjadi khalifah… maka apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Apa hukumnya jika anak ini dipaksakan dalam keadaan darurat? Yaitu ketika tidak ada kerelaan dari rakyat, tetapi ia dipaksakan kepada mereka secara paksa dan paksaan, seperti rakyat dipaksa oleh pengikut ayahnya yang menguasai kekuasaan dan alat-alat untuk memaksa umat?
Jawabannya adalah: ini memang merupakan keadaan darurat, dan dalam kondisi demikian wajib bagi ahli hal dan aqad (pemimpin dan tokoh masyarakat) dalam umat untuk mengumumkan bahwa ini adalah perkara yang tidak sah menurut syariat, dan wajib bagi umat untuk mendukung mereka dalam hal ini, serta menuntut agar yang memenuhi syarat yang menjabat. Jika pemaksaan anak kecil ini kepada umat tetap berlanjut, maka dalam kondisi ini tidak dapat dibayangkan menghentikan kepentingan-kepentingan umat, maka wajib mengangkat seorang wali -sebagaimana yang dikatakan mazhab Hanafi- untuk anak kecil ini, tetapi harus memenuhi syarat-syarat imamah. Jika mereka yang memiliki kemampuan memaksakan anak kecil ini terus memaksa dan mengangkat wali yang tidak memenuhi syarat, maka ini juga merupakan keadaan darurat yang umat tunduk kepadanya untuk sementara waktu; agar tidak terhenti kepentingan-kepentingan agama dan dunia individu-individu rakyat, tetapi umat tidak boleh rela dengan kondisi ini sebagai kondisi yang harus terus berlanjut, bahkan umat -terutama ahli hal dan aqad- harus memanfaatkan setiap kesempatan yang dapat membantu mengubah kondisi ini, dan menjadikan yang memenuhi syarat menjabat, jika tidak ada fitnah dari upaya perubahan ini. Adapun jika rakyat rela dan sepakat untuk mengangkat anak kecil imam sebagai pengganti ayahnya tanpa paksaan dan tekanan dari penguasa, maka ini bukan keadaan darurat, dan inilah kesalahan yang tidak ada pembenarnya.
Kemudian kita beralih sekarang ke syarat ketiga dari syarat-syarat imam: yaitu akal sehat:
Ini adalah syarat yang jelas, maka tidak sah kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila atau lainnya seperti kepikunan; karena orang yang hilang akal membutuhkan wali untuk dirinya sendiri untuk mengurus urusannya, maka bagaimana urusan orang lain dapat diserahkan kepadanya?! Dan jika anak kecil dilarang memegang jabatan ini karena alasan ini, maka orang yang hilang akal terlebih lagi.
Imam Al-Mawardi telah membagi dalam kitabnya (Al-Ahkam As-Sulthaniyah) menjadi dua sebab:
Pertama: yang diharapkan akan hilang seperti pingsan.
Kedua: yang tidak diharapkan hilang seperti kegilaan.
Adapun yang pertama -yaitu yang diharapkan akan hilang seperti pingsan-: ini tidak menghalangi terbentuknya imamah, dan juga tidak menghalangi kelanjutannya; karena ini adalah penyakit yang sebentar dan cepat hilang. Adapun yang kedua yaitu yang menetap -maksudnya kegilaan menetap yang tidak diharapkan hilang seperti kegilaan dan kepikunan-: ini ada dua bagian:
Salah satunya: jika terus-menerus tanpa diselingi kesadaran, maka ini menghalangi terbentuknya imamah, dan jika menimpa imam setelah memegang jabatannya, maksudnya jika kegilaan ini menimpanya setelah memegang jabatannya, maka layak untuk diturunkan jika kita yakin adanya penyakit ini dan memastikannya padanya.
Bagian kedua dari yang menetap -maksudnya penyakit menetap yang menyertai seseorang- yang diharapkan akan hilang, adalah jika penyakit itu tidak menyertainya sepanjang waktu, tetapi diselingi waktu-waktu sadar di mana ia kembali ke kondisi sehatnya, dan dalam kondisi ini perlu dilihat; jika waktu sakit lebih lama dari waktu sadar, maka ini seperti penyakit permanen yang menghalangi terbentuknya imamah, dan jika menimpa imam setelah imamah terbentuk untuknya dalam keadaan sehat, maka layak untuk diturunkan karenanya. Dan jika sebaliknya yaitu yang terjadi, maksudnya waktu sadar lebih lama dari waktu sakit, maka para ulama sepakat tentang sahnya imamah dengannya, dan mereka berbeda pendapat jika penyakit ini menimpa imam setelah ia memegang jabatannya: apakah menghalangi kelanjutannya atau tidak?
Ada dua pendapat dalam masalah ini:
Pendapat pertama mengatakan: bahwa hal itu menghalangi kelanjutannya -yaitu kelanjutan imamah- sebagaimana menghalangi permulaannya; karena kewajiban imam adalah mengurus kepentingan umat, dan penyakit ini dengan berulangnya merusak kewajiban ini.
Pendapat kedua: melihat bahwa hal itu tidak menghalangi kelanjutan imamah, meskipun menghalangi terbentuknya di awal; karena yang diminta saat akad imamah adalah kesehatan sempurna, dan saat keluar darinya adalah cacat sempurna.
Kami melihat bahwa pendapat pertama lebih layak untuk dipertimbangkan; karena mungkin serangan penyakit datang pada waktu umat membutuhkan pendapat imam, dan keputusannya dalam masalah-masalah penting, seperti urusan perang misalnya, dan tidak dapat dibayangkan bahwa masalah-masalah seperti ini terhenti hingga imam sadar. Imam Al-Mawardi telah menjelaskan dalam kitabnya (Al-Ahkam As-Sulthaniyah) ketika berbicara tentang syarat-syarat yang harus ada pada orang yang menjadi hakim -termasuk akal sehat-: bahwa harus ada kecerdasan padanya, dan tidak cukup dengan akal yang berkaitan dengannya taklif (pembebanan hukum) dari pengetahuannya tentang hal-hal yang dharuriyyat (pasti); agar ia sehat dalam membedakan, baik dalam kecerdasan, jauh dari lupa dan lengah, dapat mencapai dengan kecerdasannya penjelasan apa yang rumit, dan memisahkan apa yang sulit. Dan jika ini adalah syarat dalam mempertimbangkan sifat akal pada hakim, maka imam tertinggi terlebih lagi. Maka Imam Al-Mawardi menjelaskan kepada kita bahwa tidak cukup dengan hanya akal yang dengannya pemiliknya membedakan antara hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya, bahkan harus memiliki kecerdasan yang baik, maksudnya akal jenis khusus, memiliki kecerdasan dan kecerdikan. Jika Imam Al-Mawardi mensyaratkan itu pada hakim; maka seharusnya disyaratkan pada imam tertinggi terlebih lagi.
Syarat keempat dari syarat-syarat imam: kemerdekaan:
Maka tidak sah imamah budak, baik ia budak murni -maksudnya tidak ada unsur kemerdekaan padanya- atau setengah merdeka -maksudnya sebagian merdeka dan sebagian budak- atau kemerekdekaannya digantungkan pada sifat; karena yang seharusnya bagi budak menurut syariat adalah bahwa seluruh waktu dan usahanya dalam pelayanan tuannya, dan ia diwajibkan menaati perintah-perintah yang dikeluarkan kepadanya dari tuan ini selama dalam kemampuannya, dan jika urusannya berjalan dengan perintah orang lain: maka bagaimana urusan umat dapat diserahkan kepadanya? Sebagian orang mengatakan: agar pelayanan kepada tuan tidak menyibukkannya dari tugas-tugas imamah, dan agar tidak diremehkan sehingga dibangkang, karena orang-orang merdeka meremehkan budak dan enggan menaati mereka. Dan sebagian orang mengatakan sebagai alasan mengapa kemerdekaan disyaratkan dalam imamah kubra, menjelaskan hal itu dengan ucapannya: bahwa budak tidak memiliki wilayah (kewenangan) atas dirinya sendiri, maka bagaimana ia dapat memiliki wilayah atas orang lain? Dan wilayah yang melampaui adalah cabang dari wilayah yang ada? Ini adalah syarat yang disyaratkan -sebagaimana telah kami katakan- oleh jumhur ulama.
Syarat kelima dari syarat-syarat yang harus ada pada imam tertinggi atau kepala negara: laki-laki:
Para ulama telah mensyaratkannya dengan ijmak (kesepakatan) bagi orang yang dicalonkan untuk memegang jabatan kepala negara. Sebagian orang mengatakan: maka tidak sah imamah untuk perempuan, meskipun ia memiliki semua sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemandirian, dan bagaimana perempuan dapat dicalonkan untuk jabatan imamah padahal ia tidak memiliki jabatan qadha (peradilan), dan tidak pula jabatan kesaksian dalam kebanyakan hukum. Para ulama telah berdalil tentang hal itu dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abu Bakrah radhiallahu anhu bahwa ia berkata: Allah memberi manfaat kepadaku dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada masa (perang) Jamal, setelah aku hampir bergabung dengan pasukan Jamal dan berperang bersama mereka, ia berkata: ketika sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka -yaitu menjadikannya ratu- Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Ini adalah hadits shahih dan maknanya adalah bahwa imam tidak bisa tidak bercampur dengan laki-laki dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan, maksudnya makna yang menjadi alasan bahwa tidak boleh perempuan menjadi kepala negara, maknanya adalah bahwa imam tidak bisa tidak bercampur dengan laki-laki dan bermusyawarah dalam urusan-urusan, dan perempuan dilarang dari hal itu; dan karena perempuan kurang dalam urusan dirinya sendiri, sehingga tidak memiliki kewenangan pernikahan, maka tidak diberikan kepadanya wilayah atas orang lain.
Sebagian orang mengatakan sebagai alasan mengapa perempuan tidak layak untuk imamah kubra atau kepala negara, menjelaskan hal itu dengan ucapannya: bahwa perempuan diperintahkan untuk tinggal di rumah-rumah, sehingga dasar kondisi mereka adalah tertutup, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya ketika bersabda: “Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan” dan persyaratan laki-laki untuk menjelaskan bahwa imamah perempuan tidak sah; karena perempuan kurang akal dan agama, sebagaimana ditetapkan dalam hadits shahih, mereka dilarang keluar ke tempat-tempat hukum dan medan perang. Dan meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perempuan memegang peradilan, sebagian dari mereka melarangnya secara mutlak, sebagian membolehkannya berperkara dalam urusan-urusan yang ia menjadi saksi di dalamnya, dan sebagian membolehkannya berperkara secara mutlak, kami katakan: meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini -yaitu masalah mengangkat perempuan sebagai hakim- tetapi mereka telah bersepakat tentang tidak bolehnya mengangkatnya untuk jabatan kepala negara, dan ini bukan fanatisme dari para imam fikih Islam; bahkan karena sifat alami perempuan dan pembentukannya secara jasmani bertentangan dengan pelaksanaannya beban jabatan berbahaya ini; karena mungkin diminta dari kepala negara untuk memimpin pasukan sendiri, ikut serta dalam perang, dan menanggung kengerian-kengeriannnya… dan lain-lain dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus, dan kecakapan jasmani tertentu, dan ini tidak sesuai dengan sifat alami perempuan. Yang diperhatikan bahwa pendapat ini adalah yang sesuai -maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh perempuan memegang kepala negara- sesuai dengan sifat alami perempuan secara jasmani, kejiwaan, dan akal, dan tidak ada bukti yang lebih jelas tentang itu selain penelitian kondisi manusia di semua masa lama dan barunya. Dan memperhatikan bahwa orang-orang yang menonjol dalam memegang kepemimpinan umum di semua bangsa, mayoritas besar dari mereka adalah laki-laki, dan ketonjolan perempuan dalam memimpin bangsa-bangsa tidak muncul kecuali dalam kondisi langka, dan karena sebab-sebab yang tidak sering terulang, dan tidak benar mengembalikan hal itu kepada bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam bidang ini dengan menggunakan kekuatannya yang ia unggul dari perempuan di dalamnya; yang memberikan kesempatan-kesempatan kepadanya yang perempuan tidak mendapatkannya, atau karena ia mencegahnya dari pendidikan bertahun-tahun sehingga membuatnya puas dengan peran pengikut laki-laki, tidak benar mengatakan ini; karena penggunaan laki-laki kekuatannya dalam menonjolkan sisi keunggulan, jika itu adalah jalan biasa yang ditempuh di masa-masa lalu, maka jalan ini telah hilang -atau hampir hilang- di masa modern, dan meskipun demikian kepemimpinan-kepemimpinan masih di tangan laki-laki kecuali yang jarang, di waktu yang tersedia bagi perempuan kesempatan belajar yang tersedia bagi laki-laki. Dan begitu juga tidak benar mengembalikan kepemimpinan lebih banyak bagi laki-laki kepada banyaknya jumlah laki-laki dibanding perempuan; karena di beberapa negara yang menunjukkan dalam statistik tentang banyaknya jumlah di sisi perempuan, seperti yang terjadi di Jerman setelah Perang Dunia, maka jumlah laki-laki sedikit dibandingkan jumlah perempuan; karena perang telah membinasakan laki-laki lebih banyak, dan meskipun demikian, dan meskipun kesempatan tersedia bagi perempuan untuk membuktikan keunggulannya atas laki-laki, maka ketonjolan kepemimpinan, pemikiran dan ilmiah di semua bidang terwujud di sisi laki-laki lebih banyak darinya di sisi perempuan, meskipun perempuan di Jerman setelah perang tidak ada penghalang apapun menghalangi keterbukaan mereka pada semua cakrawala pengetahuan, dan penjelasan satu-satunya untuk keunggulan laki-laki atas perempuan dalam bidang kepemimpinan, politik, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, hanyalah pembentukan sifat alami masing-masing dari laki-laki dan perempuan, dan bukan cacat bahwa manusia menuntut urusan-urusan yang sesuai dengan sifat alami dan kesiapannya, tetapi cacatnya adalah bahwa ia menuntut apa yang bertentangan dengan hal itu.
Syarat keenam dari syarat-syarat yang wajib ada pada imam tertinggi: adalah ijtihad:
Kami katakan: jumhur ulama berpendapat bahwa syarat ini harus ada pada orang yang dicalonkan untuk imamah kubra, jumhur berpendapat bahwa ahli imamah dan yang berhak atasnya adalah orang yang mujtahid dalam ushul dan furu’; agar ia dapat melaksanakan urusan-urusan agama, mampu menegakkan hujjah dan menyelesaikan syubhat dalam akidah-akidah agama, mandiri dalam fatwa dalam peristiwa-peristiwa dan hukum-hukum kejadian dengan nash dan istinbath; karena tujuan terpenting imamah adalah menjaga akidah-akidah, memutuskan pemerintahan-pemerintahan, dan mengangkat perselisihan-perselisihan, dan hal itu tidak akan sempurna tanpa syarat ini, yaitu ijtihad.
Mazhab Hanafi berpendapat tidak mensyaratkan ijtihad pada imam, maka kita melihat mereka ketika menjelaskan syarat-syarat imamah kubra tidak menghitung darinya syarat ijtihad, dan ini adalah pendapat yang mewakili mazhab Hanafi, meskipun sebagian ulama Hanafiyah -seperti Kamaluddin Ibnu Humam, dan ia dari imam-imam Hanafiyah- menghitung ilmu, maksudnya menjadikan ilmu sebagai syarat dari syarat-syarat wajib dalam imamah kubra, tetapi ia tidak bermaksud dengannya ilmu mujtahid sebagaimana yang dimaksud dengannya pada kebanyakan ulama, ketika mereka mengungkapkan syarat ijtihad dengan ilmu, maka jumhur ulama jika mereka menyebutkan ilmu dari antara syarat-syarat wajib ada pada imamah, mereka menjelaskan bahwa maksud mereka dengan hal itu adalah ilmu mujtahid, maka sama saja mereka mengungkapkan dengan mujtahid atau mengungkapkan dengan ilmu sama pada mereka, maka kata ilmu sama dengan mujtahid, dan ini berbeda dengan Hanafiyah yang menjadikan ilmu sesuatu dan ijtihad sesuatu yang lain; oleh karena itu kami katakan: pendapat yang diamalkan pada mereka bahwa mereka tidak mensyaratkan pada imam tertinggi atau kepala negara bahwa ia harus mujtahid. Kami katakan maka ulama yang menghitung ijtihad sebagai syarat dari syarat-syarat imamah, terkadang mereka mengungkapkan syarat ini dengan ijtihad, dan terkadang mereka menyebutkan ilmu dan bermaksud dengannya ilmu mujtahid -sebagaimana kami jelaskan- adapun Kamaluddin Ibnu Humam -dan ia dari imam-imam fikih Hanafi- maka tidak bermaksud dengannya ilmu mujtahid, bahkan bermaksud dengannya ilmu yang mahir dalam ushul dan furu’, dan ini adalah perbedaan antara ilmu dan ijtihad pada mereka.
Kemudian sesungguhnya jumhur ulama dengan mensyaratkan mereka ijtihad pada imam, maka mereka bermaksud dengan hal itu bahwa harus terwujud padanya hal-hal berikut setelah terpenuhi syarat Islam, maksudnya harus ada hal-hal berikut sehingga kita mengatakan tentang imam bahwa ia mujtahid:
Pertama: bahwa ia harus mengetahui bahasa Arab sejumlah yang dengannya ia dapat memahami ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya; hal itu karena Al-Quran dan Sunnah -dan keduanya adalah dua sumber pertama hukum-hukum syariat- keduanya dalam bahasa Arab- dan mujtahid tidak dapat memahami dalil-dalil kecuali jika ia mengetahui bahasa Arab.
Kedua: bahwa ia harus mengetahui ayat-ayat hukum, maka ia mengetahui maknanya, dan apa yang berkaitan dengannya dari umum dan khusus, mujmal dan terperinci, mutlak dan muqayyad, hakikat dan majaz, nasikh dan mansukh… dan lain-lain, harus mengetahui ayat-ayat ini.
Para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuannya tentang ayat-ayat hukum bukanlah harus menghafalnya di luar kepala, melainkan yang mereka maksudkan adalah ia harus memiliki pengetahuan tentang cara merujuk kepada ayat-ayat tersebut ketika ia ingin menetapkan suatu hukum dari berbagai hukum.
Ketiga: Ia harus memiliki ilmu tentang hadis-hadis hukum, sehingga ia mengetahui sanadnya dari: mutawatir, ahad, dan masyhur, dan ia harus mengetahui keadaan perawi hadis dari segi jarh (cacat) dan ta’dil (keadilan); sehingga ia dapat membedakan hadis-hadis yang sahih dari lainnya. Karena jarak waktu yang panjang antara kita sekarang dengan para perawi tersebut, maka para ulama telah mencukupkan diri dengan penilaian ta’dil dari imam-imam besar yang memiliki kepercayaan dalam ilmu hadis, seperti al-Bukhari dan Muslim … dan ulama hadis lainnya, artinya cukup bagi mujtahid ini untuk merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Jika ia membuka Sahih al-Bukhari dan kitab itu menyatakan: perawi si fulan adalah adil, maka cukup dengan itu, dan tidak dituntut dari dia untuk meneliti riwayat hidup perawi ini. Maka seharusnya kita membatasi diri pada hal ini; agar tidak menimbulkan kesulitan, artinya jika kita membatasi diri pada kitab-kitab sahih ini dalam penilaian ta’dil mereka terhadap para perawi maka hal itu sudah cukup dan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Dan juga mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang matan hadis-hadis hukum, dari segi-segi yang telah disebutkan sebelumnya, seperti umum dan khusus, ijmal (global) dan tafsil (terperinci) … dan lain sebagainya.
Keempat: Mengingat bahwa penetapan hukum membutuhkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah ushul yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum-hukum tersebut; maka ia harus menjadi orang yang berilmu tentang kaidah-kaidah ushul fikih.
Kelima: Ia harus menjadi orang yang berilmu tentang masalah-masalah yang telah disepakati oleh para fuqaha (ahli fikih); agar ia tidak menyalahi dengan ijtihadnya apa yang telah disepakati oleh para ulama dalam salah satu masalah, sehingga menyebabkan ia melakukan perbuatan yang haram; karena menyalahi ijma (konsensus) para ulama adalah perkara yang diharamkan secara syariat. Dan kita harus mengetahui bahwa jika suatu sifat ada pada seorang imam, kemudian ia menderita sakit setelah memegang jabatannya yang menyebabkan ia kehilangan sifat tersebut, maka dalam keadaan ini ia berhak untuk dipecat menurut pendapat mereka yang mensyaratkan sifat ilmu pada imam.
Dalil Jumhur dan Penentangnya tentang Pendapat yang Mereka Anut: Telah kami katakan bahwa jumhur fuqaha mensyaratkan pada imam agar menjadi mujtahid, dan kita telah mengetahui hal-hal yang dengannya ia menjadi mujtahid, yaitu pengetahuannya tentang bahasa Arab, ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, ilmu ushul fikih, dan hal-hal lain yang telah kami sebutkan, tetapi apa dalil-dalil yang dijadikan hujah oleh jumhur fuqaha bahwa imam harus menjadi mujtahid? Atau apa dalil-dalil mereka tentang syarat ijtihad pada imam?
Kami katakan: Jumhur ulama dalam pendapat mereka tentang wajibnya ijtihad bagi imam agung, berdasarkan pada dua aspek: Pertama: Qiyas (analogi), dan Kedua: Sifat pekerjaan yang diserahkan kepada imam agung, dan apa yang dituntut darinya berupa sifat-sifat khusus agar dapat dilaksanakan sesuai dengan cara yang diwajibkan oleh pembuat syariat. Adapun yang berkaitan dengan aspek pertama -yaitu qiyas- mereka mengqiyaskan jabatan imamah kubra (kepemimpinan tertinggi) dengan jabatan peradilan. Jika qadhi (hakim) disyaratkan harus menjadi mujtahid maka demikian juga imam, bahkan lebih utama lagi, sehingga sebagian orang setelah menghitung ijtihad sebagai salah satu syarat yang wajib pada imam mengatakan: Karena qadhi yang diangkat oleh imam membutuhkan hal itu, maka imam lebih utama. Artinya seolah-olah jumhur fuqaha mengqiyaskan imam kepada qadhi, jika disyaratkan pada qadhi harus menjadi mujtahid maka lebih utama lagi disyaratkan pada imam agung harus menjadi mujtahid, karena imam agung adalah yang mengangkat qadhi, dan disyaratkan pada qadhi harus menjadi mujtahid, maka lebih utama lagi wajib pada imam agung harus menjadi mujtahid. Adapun yang berkaitan dengan aspek kedua, sebagian ulama mengatakan: Karena ia membutuhkan untuk mengelola urusan-urusan pada jalan yang lurus, dan menjalankannya pada jalan yang benar, dan agar ia mengetahui had (hukuman), menunaikan hak-hak, dan memutuskan sengketa di antara manusia, dan jika ia tidak berilmu dan tidak mujtahid maka ia tidak mampu melakukan hal itu.
Sebagian ulama mengatakan: Ijtihad disyaratkan pada imam; agar dengan itu ia mampu menegakkan hujah dan memecahkan syubhat (keraguan) dalam akidah agama, dan mandiri dalam berfatwa tentang kejadian-kejadian dan hukum peristiwa-peristiwa secara nash (teks) maupun istinbath (penggalian hukum); karena tujuan terpenting dari imamah adalah menjaga akidah, memutuskan pemerintahan, dan mengangkat sengketa.
Adapun mereka yang berpendapat tidak wajibnya syarat ini -yaitu Hanafiyah sebagaimana telah kami katakan- mereka membangun pendapat mereka atas dasar bahwa berkumpulnya syarat ini dengan syarat-syarat lain yang diperlukan pada satu orang adalah perkara yang langka, dan ia dapat mewakilkan kepada mujtahid lain untuk memutuskan dalam perkara-perkara yang memerlukan ijtihad, atau ia memutuskan setelah meminta fatwa para ulama. Maka mereka ini adalah Hanafiyah yang tidak mensyaratkan pada imam harus menjadi mujtahid, tetapi mereka mengatakan: Cukup baginya untuk bertanya kepada ahli ilmu atau ahli ijtihad tentang masalah apa pun yang dihadapkan kepadanya, dan ia membangun putusannya berdasarkan hal itu; karena mungkin syarat ini tidak terpenuhi bersama syarat-syarat lain, dan mensyaratkannya termasuk perkara yang memberatkan; oleh karena itu mereka mencukupkan dengan mengatakan bahwa ia merujuk kepada ahlinya; dan dengan demikian mereka tidak mensyaratkan pada imam agung harus menjadi mujtahid.
Saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah melimpah kepada kalian.
2 – Syarat-Syarat Kepala Negara (2)
Keadilan
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu pemimpin kami Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat … Amma ba’du:
Kita telah memulai pembahasan dalam kuliah yang lalu tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pada imam agung, atau kepala negara, dan kami sebutkan bahwa disyaratkan pada imam agung harus baligh (dewasa), berakal, muslim, merdeka, laki-laki, mujtahid, dan kami sebutkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di antara para fuqaha dalam syarat-syarat ini, dan kami jelaskan pendapat yang rajih (kuat) di antaranya, dan sekarang kami melanjutkan pembahasan tentang sisa syarat-syarat ini, kami katakan:
Syarat ketujuh dari syarat-syarat imam agung atau kepala negara: Adalah ia harus adil, dan keadilan adalah sifat dalam jiwa yang mencegah pemiliknya dari melakukan dosa besar dan bersikeras pada dosa kecil. Para ulama berbeda dalam menyebutkan syarat ini, kebanyakan mengungkapkannya dengan keadilan, sebagian menyebutnya dengan kesalehan dalam agama, dan sebagian menyebutnya dengan wara’ (sikap hati-hati dari yang haram), dan al-Mawardi mensyaratkan beberapa syarat agar keadilan yang diperlukan dapat terwujud, ia berkata dalam kitab (Wilayah al-Qadha):
Dan keadilan adalah ia harus jujur ucapannya, nyata amanahnya, menjaga diri dari yang haram, menghindari dosa-dosa, jauh dari keraguan, dapat dipercaya dalam keadaan ridha maupun marah, mengamalkan muru’ah (sikap kesatria) yang sesuai dengan posisinya dalam agama dan dunianya.
Mensyaratkan keadilan pada imam adalah pendapat jumhur ulama umat; karena syarat ini diperlukan pada saksi dan qadhi, artinya disyaratkan pada saksi agar kesaksiannya diterima ia harus adil, dan disyaratkan pada qadhi agar putusannya berlaku ia harus adil. Jika hal itu diperlukan pada saksi dan qadhi, maka seharusnya lebih utama lagi diperlukan pada orang yang memegang imamah kubra; karena imamah kubra lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dan peradilan, dan kefasikan adalah lawan dari keadilan. Jika hal ini menjadi penghalang dari memegang jabatan peradilan dan kesaksian, yaitu kefasikan, maka lebih utama lagi menjadi penghalang dari memegang imamah kubra. Dan jika dituntut dari imam untuk memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin, maka bagaimana hal itu dapat terwujud sedangkan dengan kefasikannya ia tidak memperhatikan urusan dirinya sendiri.
Sebagian ulama mengatakan: Dan orang fasik tidak layak untuk urusan agama, dan tidak dapat dipercaya perintah dan larangannya, dan orang zalim akan kacau dengannya urusan agama dan dunia, dan bagaimana ia layak untuk memegang kekuasaan, sedangkan pemimpin itu hanya untuk menolak kejahatannya.
Tidak ada yang menyalahi jumhur dalam mengatakan mensyaratkan keadilan pada imam kecuali Hanafiyah, mereka tidak menghitungnya sebagai salah satu syarat yang wajib, dan mereka membolehkan orang fasik memegang urusan umat, tetapi mereka memakruhkan hal itu. Mereka berdasarkan pada pendapat mereka yang mengatakan bahwa keadilan bukan syarat pada imam agung, bahwa telah terbukti para sahabat shalat di belakang imam-imam yang zalim dari Bani Umayyah, dan ridha dengan kepemimpinan negara mereka. Jawaban terhadap hal itu adalah bahwa mereka adalah raja-raja yang menguasai umat dengan paksa, mereka memegang jabatan ini dengan kekerasan, bukan dengan ridha dan pilihan, dan keadaan penguasaan dengan paksa adalah keadaan darurat, maka tidak sah berdalil dengannya. Dan jika kita mengatakan tidak sahnya kepemimpinan orang yang berkuasa dengan paksa yang tidak adil maka akan terhenti kemaslahatan umat yang bersifat agama dan dunia, seperti memutuskan sengketa, berjihad melawan orang-orang kafir, dan lain sebagainya.
Sebagian ulama mengatakan: Dan bukan termasuk syarat sahnya shalat di belakang imam adalah keadilannya, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah: “Jihad wajib atas kalian bersama setiap amir, baik ia berbuat baik maupun jahat, dan shalat wajib atas kalian di belakang setiap muslim, baik ia berbuat baik maupun jahat, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar” Dan hikmah bahwa keadilan tidak disyaratkan dalam imamah shalat, tetapi disyaratkan dalam imamah kubra, adalah bahwa shalat tidak berkaitan dengan hak orang lain, berbeda dengan imamah, karena ia berkaitan dengan hak orang lain.
Sebagian ulama mengatakan: Dan hak imam adalah melaksanakan hak-hak seperti had, hukum-hukum, berbuat adil, membela, mengambil harta dari tempatnya, dan menyalurkannya pada haknya, dan orang fasik tidak dapat dipercaya untuk hal itu. Maka mengqiyaskan imamah kubra kepada imamah shalat adalah qiyas ma’al fariq (analogi dengan perbedaan), dan oleh karena itu gugur apa yang dijadikan dalil oleh Hanafiyah bahwa keadilan tidak disyaratkan pada imam agung atau kepala negara.
Imam al-Mawardi dalam kitab (al-Ahkam as-Sulthaniyyah) membagi kefasikan yang menghilangkan keadilan menjadi dua bagian: Pertama: Apa yang dengannya ia mengikuti syahwatnya, Kedua: Apa yang berkaitan dengan syubhat (keraguan).
Adapun yang pertama: yaitu apa yang dengannya ia mengikuti syahwatnya, terjadi dengan keberaniannya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga ia melakukan hal-hal yang terlarang tanpa mempedulikan ancaman Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka ini adalah kefasikan yang -menurut al-Mawardi- menghalangi terbentuknya imamah baginya, dan jika terjadi setelah imamah terbentuk untuknya maka ia -menurut al-Mawardi- telah keluar dari imamah. Adapun yang kedua dari dua bagian kefasikan: yaitu apa yang berkaitan dengan keyakinan yang menyalahi kebenaran, karena adanya syubhat. Para ulama telah berbeda pendapat dalam hal itu, sebagian berpendapat bahwa hal itu menghalangi terbentuknya imamah, dan jika terjadi pada orang yang telah ditetapkan imamahnya maka ia berhak dipecat karenanya, dan mereka memberikan alasan bahwa karena hukum kekufuran sama baik dengan takwil maupun tanpa takwil, maka wajib sama juga keadaan kefasikan baik dengan takwil maupun tanpa takwil. Dan al-Mawardi menyebutkan bahwa banyak ulama Bashrah berpendapat bahwa hal itu tidak menghalangi terbentuknya imamah, dan jika terjadi padanya setelah ia memegang imamah maka ia tidak keluar dari imamah karenanya, sebagaimana hal itu tidak menghalangi memegang jabatan peradilan dan diterimanya kesaksian.
Kemudian kefasikan yang menghilangkan keadilan terkadang bersifat zhahir (nyata), dalam arti diketahui oleh orang-orang dengan tersebar di antara mereka, atau dengan kesaksian orang-orang adil atas hal itu, dan terkadang seseorang secara zhahir adil, tetapi secara batin fasik, kebalikan dari apa yang diyakini orang-orang. Jika ia menyembunyikan kefasikan, dan dipilih oleh ahlu al-halli wa al-‘aqdi (ahli ikatan dan pelepasan/lembaga pembentuk konstitusi) untuk imamah, apakah halal baginya menerima jabatan ini, ataukah wajib baginya menolaknya?
Sebagian ulama mengatakan: Wajib baginya untuk bertaubat dari apa yang ia lakukan, dan dari apa yang ia ketahui dari dirinya, dan menerima jabatan ini dengan syarat ia yakin akan perbaikan dan istiqamahnya, dan tidak kembalinya ia kepada apa yang merusak keadilannya. Jika ia tidak yakin akan hal itu maka wajib baginya menampakkan keadaannya secara umum, dan wajib atas ahlu al-halli wa al-‘aqdi menerima hal itu darinya, dan mencalonkan orang lain untuk imamah.
Namun apa hukumnya jika sulit menemukan keadilan?
Sulitnya keadilan dalam diri imam dapat terjadi karena dua hal: pertama, dikuasainya jabatan ini oleh orang yang tidak memiliki keadilan dengan cara paksa, sehingga ahli halli wal aqdi (para pembuat keputusan) tidak memiliki pilihan dalam penguasaannya atas kepemimpinan. Kedua, tidak ditemukannya keadilan pada orang-orang yang dipertimbangkan oleh ahli halli wal aqdi yang memiliki syarat-syarat lainnya dan layak untuk memegang jabatan ini, namun keadilan tidak terwujud pada diri mereka. Kedua hal ini mengandung makna darurat. Maksud kami adalah hal pertama, yaitu seseorang yang tidak adil menguasai kepemimpinan, dan hal kedua yaitu ahli halli wal aqdi tidak menemukan syarat keadilan pada orang-orang yang layak untuk kepemimpinan. Kami katakan: kedua hal ini mengandung makna darurat, karena tidak ada cara untuk memaksa yang pertama yang menguasai kekuasaan dengan paksa, tidak ada cara untuk memaksanya melepaskan kepemimpinan kecuali dengan menggunakan kekerasan, dan ini akan menyebabkan terjadinya fitnah dan menyebarnya kerusakan, yang merupakan kondisi yang tidak diridhai oleh syariat. Maka pada saat itu dilihat mana yang lebih ringan mudharatnya: mudharat adanya pemimpin tertinggi umat yang tidak adil, atau mudharat menyebarnya fitnah di antara manusia ketika mencoba menyingkirkannya dengan kekerasan. Maka ditolerir mudharat yang lebih ringan, yaitu keberadaan orang yang tidak adil sampai datang kesempatan untuk menyingkirkannya ketika fitnah sudah aman dan tidak ada mudharat.
Sebagian orang mengatakan: jika sulit menemukan ilmu dan keadilan pada orang yang menguasai kepemimpinan, yaitu orang yang menguasainya adalah orang bodoh terhadap hukum-hukum atau orang fasik, dan dalam menyingkirkannya akan menimbulkan fitnah yang tidak tertahankan, maka kami memutuskan sahnya kepemimpinannya, agar dalam menyingkirkannya dan menimbulkan fitnah yang tidak tertahankan, kami tidak seperti orang yang membangun istana tetapi menghancurkan kota. Para fuqaha menjelaskan bahwa selama kami memutuskan sahnya keputusan-keputusan yang diputuskan oleh hakim-hakim pemberontak di wilayah mereka yang dikuasai kembali oleh orang-orang yang adil, karena kebutuhan manusia untuk melaksanakan keputusan-keputusan ini, maka kita harus memutuskan sahnya kepemimpinan orang yang kehilangan syarat tersebut. Jika tidak, akan terjadi kekacauan di antara manusia dan tidak sahnya keputusan hakim-hakim mereka berdasarkan pengangkatan mereka sebagai hakim dari imam. Demikian juga keadaan kedua: yaitu keadaan di mana orang yang tidak adil tidak menguasai kepemimpinan dengan paksa, tetapi ahli halli wal aqdi dalam meneliti keadaan orang-orang yang layak untuk kepemimpinan ketika mereka ingin memilih imam, tidak menemukan orang yang memiliki syarat keadilan. Kami katakan: keadaan ini juga keadaan darurat, para fuqaha memfatwakan bolehnya kepemimpinan orang fasik, namun harus diperhatikan kewajiban mendahulukan yang paling baik, artinya yang paling sedikit kefasikannya didahulukan daripada yang lain, demikian seterusnya.
Dan di sini muncul pertanyaan: apakah imam harus maksum dari kesalahan dan dosa?
Kami katakan: dari uraian sebelumnya kita mengetahui bahwa disyaratkan terpenuhinya sifat keadilan pada imam, artinya orang tersebut tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Maka kesalahan-kesalahan kecil tidak mempengaruhi keadilan imam, selama ia tidak terus-menerus melakukannya. Berdasarkan itu, tidak wajib maksum dari kesalahan dan dosa, yang wajib adalah keadilan zahirnya. Jika keadilan ini tampak darinya maka kepemimpinannya sah, dan ketika ia menyimpang dari itu maka umat harus berdiri menunjukkan kesalahannya. Inilah yang dikatakan oleh mayoritas besar Umat Islam, dari Ahlussunnah, Muktazilah, Zaidiyah, dan Khawarij. Sedangkan Syi’ah Itsna Asy’ariyah (Dua Belas Imam) dan Ismailiyah menyimpang dengan mengatakan wajibnya imam maksum dari dosa.
Makna Ismah (Kemaksuman)
Sebelum kami sebutkan syubhat (keraguan/argumentasi keliru) mereka dalam hal itu, yaitu syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa imam harus maksum dari dosa, sebelum kami sebutkan syubhat-syubhat ini dan bantahan Ahlussunnah beserta yang bersama mereka terhadapnya, kami jelaskan dulu makna ismah. Kami katakan:
Sebagian orang menafsirkan ismah sebagai sifat khusus dalam diri seseorang atau dalam badannya yang dengannya tidak mungkin terjadinya dosa darinya. Sebagian lain juga menafsirkannya dengan: Allah tidak menciptakan dosa pada hamba, dengan tetap adanya kemampuan dan pilihannya.
Syi’ah Itsna Asy’ariyah dan Ismailiyah—sebagaimana kami sebutkan—mewajibkan ismah bagi para imam dengan makna bahwa mereka suci dari segala kotoran, bahwa mereka tidak berdosa baik dosa kecil maupun besar, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan mereka menyamakan para imam dengan para nabi dan rasul dalam ismah ini. Perbedaan antara imam dan nabi menurut mereka adalah bahwa nabi menerima wahyu sedangkan imam tidak menerima wahyu. Bahkan kami melihat sebagian Syi’ah berlebih-lebihan dalam hal itu, mereka membolehkan kesalahan pada Rasul shallallahu alaihi wasallam pada waktu mereka tidak membolehkan kesalahan pada imam. Menurut mereka Rasul shallallahu alaihi wasallam boleh bermaksiat kepada Allah, dan bahwa Nabi telah bermaksiat dalam mengambil tebusan pada perang Badar. Adapun para imam maka tidak boleh hal itu pada mereka, karena Rasul jika bermaksiat maka wahyu datang kepadanya dari Allah, sedangkan para imam tidak menerima wahyu dan para malaikat tidak turun kepada mereka, dan mereka maksum, maka tidak boleh mereka lupa atau salah, meskipun boleh bagi Rasul bermaksiat. Inilah keyakinan-keyakinan mereka, Itsna Asy’ariyah dan Ismailiyah.
Syubhat yang Mereka Jadikan Dalil dan Bantahannya
Kami sebutkan syubhat-syubhat yang mereka jadikan sandaran dalam hal ini, yaitu syubhat yang mereka klaim untuk mewajibkan ismah bagi para imam:
Syubhat Pertama
Mereka berdalil dengan wajibnya ismah bagi para imam dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata: Dan (juga) dari keturunanku? Allah berfirman: Janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.” (Surat Al-Baqarah: 124). Ayat mulia ini menunjukkan bahwa janji kepemimpinan tidak sampai kepada orang yang zalim, dan setiap orang yang melakukan dosa maka ia zalim, perhatikan firman-Nya: “Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri” (Surat Fathir: 32). Jika demikian halnya maka ayat ini tegas bahwa barangsiapa melakukan dosa, baik dosa zahir maupun batin, maka ia tidak berhak menjadi imam. Maka terbukti bahwa imam harus maksum.
Dapat kami jawab kepada mereka dalam hal ini: bahwa ayat mulia tersebut menunjukkan bahwa imam harus tidak sibuk dengan dosa. Adapun mengenai wajibnya maksum, tidak ada dalil dalam ayat tentang hal itu. Demikianlah para fuqaha menjawab syubhat ini dengan mengatakan: kami tidak mengakui bahwa zalim adalah orang yang tidak maksum, tetapi ia adalah orang yang melakukan maksiat yang menggugurkan keadilan, tanpa bertaubat dan memperbaiki diri.
Syubhat Kedua
Di antara syubhat yang mereka jadikan sandaran, mereka mengatakan: telah terbukti dengan dalil bahwa ismah wajib bagi kenabian, maka dengan qiyas (analogi) kepada kenabian kami mengatakan wajibnya ismah bagi para imam dengan illah (alasan) bahwa semuanya menegakkan syariat dan melaksanakan hukum-hukum Allah Ta’ala. Inilah syubhat lain yang mereka jadikan sandaran untuk menetapkan ismah bagi para imam, dan mereka mengqiyaskan para imam dengan kenabian dengan illah bahwa semuanya menegakkan syariat dan melaksanakan hukum-hukum Allah Ta’ala.
Jawaban atas syubhat ini:
Pertama: bahwa perbedaan jelas antara nabi dan imam. Sesungguhnya nabi diutus dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, didukung oleh-Nya dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kemaksuman mereka dari kebohongan dan segala perkara yang bertentangan dengan kenabian dan kedudukan risalah. Imam tidak demikian, ia hanya diberi kepemimpinan melalui cara manusia, yang tidak dapat mengetahui kemaksuman dan kelurusan batinnya, maka tidak ada alasan untuk mensyaratkannya.
Kedua: bahwa nabi datang dengan syariat yang manusia tidak mengetahui tentangnya apa pun kecuali dari dirinya. Jika ia tidak maksum dari kebohongan dalam menyampaikannya dan melakukan maksiat, padahal kita diperintahkan untuk mengikutinya dalam perintah dan larangannya, dan meyakini bahwa apa yang datang darinya berupa perbuatan adalah mubah, niscaya mukjizat yang ditegakkan Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk membenarkannya dalam mengklaim risalah dan baiknya urusan dunia dan akhirat akan menyebabkan melakukan maksiat dan rusaknya keadaan dunia dan akhirat. Artinya ada perbedaan, mereka mengqiyaskan kepemimpinan dengan kenabian, tetapi para fuqaha menjawab mereka bahwa ada perbedaan jelas antara nabi dan imam. Oleh karena itu ini adalah qiyas ma’al fariq (qiyas dengan adanya perbedaan mendasar). Nabi diutus dari Allah Subhanahu wa Ta’ala didukung oleh-Nya dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kemaksuman, sedangkan imam tidak demikian. Yang mengangkat imam adalah manusia atau ahli halli wal aqdi, dan ini berbeda dengan kenabian. Demikian juga Nabi shallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat yang kita tidak mengetahui apa pun tentangnya. Jika ia tidak maksum maka hal itu dapat menyebabkan terjerumus dalam maksiat dan dosa, dan Allah menolak hal itu.
Syubhat Ketiga
Di antara syubhat yang mereka jadikan sandaran, mereka mengatakan: sesungguhnya menaati imam adalah wajib berdasarkan nash dan ijmak. Allah Ta’ala berfirman: “Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (para pemimpin) di antara kalian” (Surat An-Nisa: 60). Dan setiap orang yang wajib ditaati adalah wajib maksum, jika tidak maka jika ia tidak wajib maksum, maka boleh ia berdusta dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan memerintahkan kemungkaran serta melarang ketaatan. Karena menaatinya wajib maka menjadi wajib meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Konsekuensi ini batil maka batil pula yang menyebabkannya yaitu tidak wajibnya maksum, maka terbukti kebalikannya yaitu wajibnya maksum.
Tetapi dijawab kepada mereka juga dalam hal ini bahwa imam hanya wajib ditaati dalam hal yang tidak melanggar syariat. Adapun jika melanggar syariat maka tidak wajib menaatinya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul” (Surat An-Nisa: 59). Dan dapat diterima klaim wajibnya ismah jika menaatinya wajib hanya karena perkataannya saja, tetapi perkaranya tidak demikian, karena menaatinya wajib karena itu adalah hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika demikian halnya maka cukup dengan tidak bohongnya dalam menjelaskan hukum-hukum dengan mensyaratkan Islam dan keadilan, seperti halnya hakim dan wali terhadap manusia, dan saksi terhadap hakim, dan mufti terhadap muqallid (pengikut), dan sejenisnya.
Syubhat Keempat
Di antara syubhat yang mereka jadikan sandaran juga bahwa imam adalah pemelihara syariat, jika kita membolehkan kesalahan padanya maka ia akan merusak syariat bukan memeliharanya, maka membatalkan kedudukannya sendiri.
Dijawab kepada mereka dalam hal ini bahwa imam bukan pemelihara syariat dengan dirinya sendiri, tetapi dengan Al-Quran, Sunnah, ijmak umat, dan ijtihadnya yang benar. Jika ia salah dalam ijtihadnya atau melakukan salah satu maksiat maka para mujtahid dari umat memperbaiki ijtihadnya, dan para penyuruh kepada kebaikan dan pencegah kemungkaran menghentikan kesesatannya. Dan jika mereka tidak melakukannya, dengan asumsi demikian, maka tidak ada pembatalan syariat.
Kesimpulan
Setelah ini jelaslah rusaknya apa yang dijadikan dalil oleh Syi’ah Itsna Asy’ariyah dan Ismailiyah tentang wajibnya ismah bagi para imam.
Yang penting bagi kita sekarang untuk menunjukkan bahwa pendorong mereka untuk mewajibkan sifat ini pada para imam mereka adalah karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menguduskan mereka sampai tingkat yang membawa mereka ke derajat di atas derajat manusia pada umumnya, dan mendekatkan mereka ke derajat para rasul dengan memunculkan mukjizat di tangan mereka dan kemaksuman mereka dari dosa. Mereka tidak membedakan antara para imam dan para rasul kecuali bahwa rasul menerima wahyu sedangkan imam tidak menerima wahyu. Sebab dari pemberian kesucian ini kepada para imam adalah masuknya kelompok-kelompok besar orang Persia ke dalam agama Islam setelah penaklukan, yang meyakini kesucian raja-raja mereka, dan keyakinan ini menyertai mereka setelah masuk ke agama baru. Maka mereka mengelilingi Ali radhiyallahu anhu dengan lingkaran kesucian dan keagungan sebagaimana nenek moyang mereka telah terbiasa mengelilingi raja-raja mereka dengannya. Sebagaimana nenek moyang mereka terbiasa memberi gelar kepada Kisra sebagai raja suci putra langit, dan menyifatinya dalam kitab-kitab mereka sebagai tuan dan pembimbing, demikian juga orang-orang yang memeluk Islam ini memberi gelar kepada Ali sebagai imam. Meskipun gelarnya sederhana, keagungan maknanya jelas nyata, karena menunjukkan bahwa pemiliknya telah menggabungkan dua sisi penting yaitu kekuasaan duniawi dan bimbingan akal. Meskipun Syi’ah karena berlebih-lebihan dalam menguduskan para imam mereka telah mensucikan mereka dari kebohongan, dengan mengatakan kemaksuman mereka darinya, namun kami melihat mereka bertentangan dengan prinsip ini dengan membolehkan imam jika ia takut terhadap dirinya untuk mengatakan: “Aku bukan imam” padahal ia adalah imam. Inilah makna taqiyah (menyembunyikan keyakinan). Seharusnya jika kemaksuman dari kebohongan tetap baginya, ia tidak boleh pada sebagian keadaannya jujur dan pada sebagian lainnya bohong, tetapi kejujuran harus melekat padanya dalam semua keadaannya.
Dengan syubhat-syubhat mereka yang telah disebutkan, kami dapati mereka terkadang memaksakan dalam memberikan dalil terhadap apa yang mereka katakan tentang ismah.
Inilah syubhat-syubhat Syi’ah Itsna Asy’ariyah dan Ismailiyah tentang ismah bagi para imam, dan kami telah menjelaskan syubhat-syubhat ini serta membantahnya.
Kebenaran Pendapat dalam Politik, Administrasi, dan Perang
Kita beralih sekarang kepada syarat kedelapan dari syarat-syarat kepala negara, yaitu kebenaran pendapat dalam politik, administrasi, dan perang. Kami katakan:
Karena di antara pekerjaan terpenting pemimpin tertinggi negara adalah memutuskan perkara-perkara penting yang menyangkut kepentingan umat, maka para ahli fikih menganggap bahwa di antara syarat yang paling wajib adalah seorang imam harus memiliki kemampuan besar dalam kebenaran pendapat, dan pengetahuan tentang urusan politik dan perang, serta memiliki kecakapan tinggi dalam mengelola urusan negara. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan pendapat yang mengarah kepada mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan, sebagaimana diungkapkan Al-Mawardi, atau sebagaimana sebagian mereka berkata: memiliki pendapat dan kebijaksanaan dalam mengelola perang dan perdamaian, mengatur pasukan, dan menjaga perbatasan agar dapat menjalankan urusan kekuasaan. Sebagian lain menjelaskan persyaratan pendapat dengan ucapannya: agar dia dapat mengatur rakyat dengannya, dan mengelola kepentingan-kepentingan agama dan dunia mereka. Berdasarkan hal ini, jika imam tidak memiliki kebenaran pendapat yang memadai dalam bidang politik, administrasi, dan perang, maka menurut pandangan jumhur ahli fikih, dia tidak layak untuk memangku jabatan penting ini. Oleh karena itu sebagian berkata: tidak sah kepemimpinan orang yang lemah pendapatnya, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri Islam akan dilaporkan kepadanya, dan dia tidak akan dapat mengetahui jalan kemaslahatan kecuali jika dia memiliki pendapat yang benar dan pengelolaan yang tepat. Inilah pandangan jumhur ulama tentang kewajiban memiliki kebijaksanaan dalam mengelola urusan perang dan perdamaian, ahli dalam mengorganisir pasukan dan melindungi wilayah negara, serta mengetahui bagaimana rakyat diatur dan kepentingan-kepentingan dikelola.
Namun ada di antara ulama yang mensyaratkan syarat ini dengan membolehkan mencukupkan dengan imam berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pendapat tepat dalam semua urusan penting yang perlu diputuskan, dengan alasan bahwa jarang sekali syarat ini terpenuhi bersama syarat-syarat lain yang diperlukan dalam kepemimpinan seperti ijtihad dan lain-lain.
Kami berpendapat bahwa mensyaratkan pemimpin harus memiliki pendapat yang tepat, dalam arti bahwa dia harus menguasai urusan perang seperti para komandannya, dan spesialis dalam politik seperti salah satu ahlinya, di dalamnya terdapat sedikit berlebihan; karena hal ini meskipun mudah didapatkan pada sebagian individu di masa-masa lampau sebelum berbagai ilmu merumitkan berbagai bidang kehidupan, namun sekarang tidak semudah itu. Mewajibkan pemimpin memiliki pengalaman dan pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidang politik, bidang administrasi, dan urusan perang, sulit sekali berkumpul pada satu orang di zaman ini; karena masalah-masalah politik dan perang tidak lagi sesederhana dulu di masa lampau. Setiap bidang dari bidang-bidang ini membutuhkan pengerahan banyak kelompok yang memiliki kepercayaan tinggi dalam berbagai cabang ilmu, dan perlu kerja sama para spesialis dalam mempelajari satu masalah dari masalah-masalah politik, atau perang, atau administrasi, dan menyiapkan penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang berkaitan dengannya.
Jika mensyaratkan pendapat dengan makna di atas di dalamnya terdapat sedikit berlebihan, maka kami tidak mengatakan -sebagaimana yang dikatakan sebagian orang- untuk meninggalkan syarat ini sepenuhnya, dan mencukupkan dengan berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pendapat tepat; karena pemimpin dalam segala hal dituntut untuk menjalankan prinsip syura (musyawarah). Konsultasi adalah kewajibannya yang dibebankan kepadanya. Bahkan kami katakan: pemimpin harus memiliki sifat pendapat dalam arti bahwa dia harus memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat ketika masalah-masalah politik, perang, dan administrasi jelas di hadapannya, yaitu setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang fokus pada masalah-masalah ini dari para ahli perang, administrasi, dan politik, dan setelah melihat semua penelitian yang berkaitan dengan suatu masalah dari masalah-masalah yang dihadapi umat.
Yang terlihat sekarang bahwa urusan-urusan negara berjalan secara alami dengan pemimpin-pemimpin mereka memanfaatkan berbagai lembaga dalam berbagai bidang administrasi dan perang, dan pemimpin tertinggi setelah itu memiliki keputusan akhir setelah apa yang berkaitan dengan suatu masalah jelas di hadapannya. Sama saja dalam hal ini negara-negara yang sekarang berada di puncak peradaban manusia, maupun negara-negara yang masih merangkak di jalan peradaban dan kemajuan. Tidak ada pelanggaran dalam pendapat ini terhadap kaidah syariat, atau terhadap hukum yang ditetapkan dari syariat; karena syarat-syarat kepemimpinan tidak ada di dalamnya syarat yang dinashkan oleh syariat kecuali satu syarat yaitu syarat Quraisy. Selain syarat ini, para ulama mensyaratkannya karena melihat keperluan terhadapnya, dan berbeda sudut pandang dalam apakah keperluan itu mendesak atau tidak. Oleh karena itu terjadi perbedaan dalam mensyaratkan sebagian syarat antara sebagian Ahlussunnah dengan sebagian yang lain.
Kemudian kita harus mengingatkan bahwa ini bukan berarti tidak mensyaratkan syarat ini dengan makna yang ditentukan para ahli fikih, yaitu memiliki pendapat dan kebijaksanaan dalam mengelola perang dan perdamaian, mengatur pasukan, dan menjaga perbatasan. Bahkan kami tegaskan bahwa jika ada seseorang yang terpenuhi padanya syarat ini dengan makna ini bersama syarat-syarat lain yang diperlukan dalam kepemimpinan, maka tidak boleh berpaling darinya kepada orang lain yang tidak terpenuhi padanya syarat ini dengan makna ini; sesuai dengan kaidah yang paling baik kemudian yang paling baik. Adapun jika tidak ada yang terpenuhi padanya makna ini, maka yang kami lihat bahwa dia harus memiliki kemampuan memutuskan dengan tepat dalam urusan-urusan, setelah jelasnya pendapat-pendapat yang diberikan kepadanya oleh para spesialis dalam berbagai bidang. Adapun pendapat untuk meninggalkan persyaratan pendapat tepat dalam kepemimpinan, dan mencukupkan dengan berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pendapat tepat, kami tidak mengatakannya.
Kecakapan Jasmani dan Kecakapan Jiwa
Kita beralih sekarang kepada syarat kesembilan dari syarat-syarat kepemimpinan besar, atau syarat-syarat yang harus terpenuhi pada khalifah, atau imam tertinggi, atau kepala negara, yaitu kecakapan jasmani:
Yang dimaksud dengan syarat ini adalah kesehatan indra dan anggota badan, dari apa yang mempengaruhi pendapat dan kerja. Dari sisi kesehatan indra, para ulama mensyaratkan harus dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Tidak sah kepemimpinan orang tuli; karena ketulianannya menghalanginya dari mendengar kepentingan rakyat, dan karena jika itu menghalangi dari menjabat hakim maka kepemimpinan lebih-lebih lagi. Tidak sah kepemimpinan orang buta. Al-Mawardi berkata: Hilangnya penglihatan dari akad kepemimpinan dan kelanjutannya, jika itu datang kemudian maka batallah dengannya kepemimpinan; karena ketika itu membatalkan jabatan hakim dan menghalangi kebolehan kesaksian, maka lebih patut menghalangi sahnya kepemimpinan. Kemudian Al-Mawardi berkata: Adapun rabun senja yaitu tidak dapat melihat saat malam masuk, maka tidak menghalangi dari akad kepemimpinan baik dalam akad maupun kelanjutan; karena itu adalah penyakit pada waktu istirahat yang diharapkan hilang. Demikian juga orang bisu tidak sah kepemimpinannya; karena kebisuannya menghentikan kepentingan-kepentingan umat.
Para ulama berbeda pendapat tentang datangnya kebisuan atau ketulian pada imam, yaitu datang kepadanya setelah dia memegang kepemimpinan. Segolongan berpendapat wajib keluarnya imam dari kepemimpinan jika datang kepadanya kebisuan atau ketulian, sebagaimana dia keluar jika kehilangan penglihatannya; karena baik kebisuan maupun ketulian memiliki pengaruhnya terhadap pengelolaan dan kerja. Golongan lain berkata: tidak keluar dengan datangnya ketulian atau kebisuan dari kepemimpinan; karena isyarat menggantikannya. Golongan ketiga berkata: jika dia pandai menulis tidak keluar, dan jika tidak pandai maka keluar dari kepemimpinan; karena tulisan dapat dipahami, sedangkan isyarat samar.
Al-Mawardi setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini mengoreksi pendapat pertama, yaitu wajib keluarnya imam dari kepemimpinan jika datang kepadanya salah satunya.
Tidak mengapa pendengaran yang berat dan penglihatan yang lemah jika tidak menghalanginya dari membedakan orang-orang dari terjadinya kepemimpinan atau kelanjutannya.
Adapun dari sisi kesehatan anggota badan, Al-Mawardi membagi kehilangan anggota badan menjadi empat bagian:
Bagian pertama: apa yang tidak menghalangi sahnya akad kepemimpinan, dan tidak dari kelanjutannya, yaitu apa yang kehilangannya tidak mempengaruhi pendapat, kerja, aktivitas, dan tidak cacat dalam penampilan, seperti terputusnya kemaluan atau buah zakar. Keduanya tidak ada sangkut pautnya dengan pendapat, dan tidak ada pengaruhnya kecuali dalam keturunan, maka itu berjalan seperti impotensi. Orang impoten adalah yang tidak mampu mendatangi wanita. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuji Nabi-Nya Yahya bin Zakaria alaihimassalam, Dia berfirman: “Dan menjadi pemimpin, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang Nabi dari orang-orang yang saleh” (Surah Ali Imran: 39). Dalam makna hashuran (menahan diri) ada dua pendapat: pertama, bahwa dia adalah orang impoten yang tidak mampu mendatangi wanita; kedua, bahwa dia tidak memiliki kemaluan untuk menggauli wanita, atau memiliki kemaluan seperti biji kurma.
Bagian kedua: apa yang menghalangi akad kepemimpinan dan kelanjutannya, yaitu kehilangan apa yang memiliki pengaruh dalam kerja, seperti kehilangan kedua tangan, atau memiliki pengaruh dalam aktivitas seperti kehilangan kedua kaki. Itu mengarah kepada ketidakmampuannya melaksanakan hak-hak umat dalam kerja atau aktivitas, dan dengan itu menjadi penghalang dari akad kepemimpinan sejak awal, dan dari kelanjutannya jika itu terjadi setelah dia memegang kepemimpinan.
Bagian ketiga: apa yang menghalangi sebagian kerja atau sebagian aktivitas, seperti kehilangan sebagian tangan atau salah satu kaki, dan itu menghalangi akad kepemimpinan sejak awal; karena dia tidak mampu melakukan tindakan sempurna dalam urusan-urusan umat. Imam Al-Mawardi tidak menyebutkan pendapat yang menyelisihi itu.
Adapun jika itu datang pada imam setelah terjadinya kepemimpinan untuknya maka ada dua pendapat. Pertama: menghalangi kelanjutannya; karena itu adalah kecacatan yang menghalangi dari awalnya, maka demikian juga menghalangi kelanjutannya. Kedua: tidak mempengaruhi kelanjutannya meskipun menghalangi terjadinya sejak awal; karena yang dipertimbangkan dalam terjadinya adalah kesempurnaan kesehatan, dan dalam keluar darinya adalah kesempurnaan kecacatan.
Bagian keempat: apa yang kehilangannya tidak menghalangi kelanjutannya -yaitu kepemimpinan- dan diperselisihkan dalam menghalanginya sejak awal, yaitu apa yang cacat dan jelek namun tidak ada pengaruhnya dalam pendapat, aktivitas, atau kerja, seperti terpotongnya hidung atau tercopot salah satu mata. Para ulama sepakat bahwa itu tidak menghalangi kelanjutan kepemimpinan; karena tidak ada pengaruhnya dalam sesuatu dari hak-haknya. Mereka berbeda pendapat dalam apakah itu menghalangi akad kepemimpinan sejak awal dengan dua pendapat:
Pertama: bahwa itu tidak mempengaruhi akad kepemimpinan sejak awal; karena tidak mengganggu sesuatu dari hak-hak kepemimpinan.
Kedua: bahwa itu menghalangi akad kepemimpinan, dan kesehatan di dalamnya adalah syarat dalam sahnya akad kepemimpinan; agar para imam selamat dari setiap cacat yang mengurangi kesempurnaan wibawa yang kekurangannya mengarah kepada enggan mematuhi. Dan apa yang mengarah kepada ini maka itu adalah kekurangan dalam hak-hak umat.
Kita beralih setelah itu kepada syarat kesepuluh dari syarat-syarat kepemimpinan besar, atau syarat-syarat yang harus terpenuhi pada kepala negara, dan syarat ini adalah kecakapan jiwa. Kami katakan:
Para ulama berbeda ungkapan dalam syarat ini. Sementara kita dapati sebagian dari mereka mengungkapkan syarat ini dengan keberanian, kita dapati sebagian lain mengungkapkannya dengan kecakapan. Bagaimanapun, syarat ini baik diungkapkan dengan keberanian, atau digabungkan dengannya dengan kebenaran pendapat dan diungkapkan keduanya dengan kecakapan, telah disyaratkan oleh jumhur ahli fikih pada imam. Mereka menjelaskannya -sebagaimana telah lewat- bahwa di antara kewajiban imam adalah menegakkan hudud kepada yang berhak, dan jika dia penakut maka kepenakutannya akan menghalanginya dari menegakkannya, dan agar dia dapat menerobos peperangan dan menyiapkan pasukan. Jadi jumhur ahli fikih berpendapat syarat keberanian atau kecakapan pada imam tertinggi atau yang memegang khilafah atau kepala negara. Mengapa? Mereka berkata: karena jika dia penakut maka dia akan menjadi tidak mampu menegakkan hudud, dan akan menjadi tidak mampu menerobos peperangan dan menyiapkan pasukan, dan ini akan membahayakan negara Islam.
Sebagian ulama menyelisihi dalam hal itu, mereka berkata tidak disyaratkan sifat keberanian pada imam, dengan alasan bahwa jarang terkumpul sifat ini dengan sifat-sifat lain yang diperlukan pada imam, dan dapat diwakilkan konsekuensi-konsekuensi keberanian -yaitu urusan-urusan yang mengharuskan imam harus berani seperti qishas, menegakkan hudud, dan memimpin pasukan menghadapi musuh kepada orang lain. Maksudnya sebagian ahli fikih atau sebagian ulama tidak mensyaratkan syarat ini, tidak mensyaratkan pada imam harus berani, bahkan mereka berkata dicukupkan dengan dia mewakilkan orang lain dalam melaksanakan urusan-urusan ini, baik berkaitan dengan pelaksanaan hukum, atau penegakan hudud, atau memimpin pasukan, dan menyiapkan pasukan dan lain-lain. Mereka berkata: dicukupkan dengan itu, yaitu imam mewakilkan orang lain dalam urusan-urusan ini yang bergantung pada keberanian, dan tidak mengapa tidak adanya syarat ini pada imam. Mereka berkata bahwa jarang kita temukan syarat ini bersama syarat-syarat lain.
Kenyataannya bahwa mensyaratkan sifat keberanian pada imam agar membela wilayah kaum muslimin dengan keteguhan dalam pertempuran, dan agar tidak takut menegakkan hudud kepada yang berhak, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli fikih, kami katakan: ini adalah hal yang berlebihan; karena cukup -menurut pendapat kami- bahwa imam memiliki pendapat yang tepat dengan makna yang telah kami jelaskan tadi saat membicarakan syarat pendapat; agar dia mewakilkan urusan perang kepada para komandan yang cakap yang dia percaya pada kemampuan mereka melaksanakan apa yang diserahkan kepada mereka dari perencanaan perang dan terjun ke medan perang. Kepentingan-kepentingan umat telah banyak dan beragam, dan setiap bidang di dalamnya membutuhkan spesialis yang fokus untuk melaksanakan kewajiban dalam hal itu. Jika demikian halnya, maka imam dapat mewakilkan kepada para komandan yang terbukti cakap apa yang berkaitan dengan urusan perang dari penyiapan pasukan, dan terjun ke medan perang dan lain-lain, dan dapat mewakilkan apa yang berkaitan dengan qishas dan penegakan hudud kepada lembaga-lembaga khusus, sebagaimana yang dipraktikkan sekarang dalam hukuman, yaitu dilaksanakan dan diawasi dalam semua yang berkaitan dengannya oleh lembaga peradilan dan eksekutif di negara.
Tetapi bukan berarti itu boleh mengangkat orang yang memiliki sifat penakut atau muncul padanya kelemahan ketika wajib baginya untuk memberikan perintah-perintah yang membutuhkan ketegasan hati, seperti mengumumkan perang terhadap musuh misalnya dengan menanggung konsekuensinya. Bahkan jika sifat ini ada padanya maka cukup untuk mengeluarkannya dari jabatan kepemimpinan, meskipun terpenuhi padanya syarat-syarat lain; karena dengan kepenakutan dan kelemahannya dia menjadi faktor dari faktor-faktor tamak musuh-musuh terhadap negara Islam, padahal yang seharusnya dari imam adalah menjaga agama dan tanah kaum muslimin.
Kita akan mempelajari mazhab-mazhab ini dengan dalil-dalilnya dalam kuliah-kuliah mendatang -insya Allah.
Kita cukupkan dengan ini dari kuliah ini, saya titipkan kalian kepada Allah, dan Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3 – Syarat-Syarat Kepala Negara (3)
Syarat Keturunan Quraisy dan Pengangkatan yang Terbaik
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kami Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du:
Kita telah membahas dalam kuliah-kuliah sebelumnya tentang syarat-syarat Imam Agung atau Kepala Negara, dan telah menjelaskan bahwa disyaratkan padanya: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, berijtihad, adil, memiliki pendapat yang tepat dalam politik, administrasi, dan perang, kemampuan fisik, dan kemampuan psikis. Tersisa dua syarat yang akan kita bahas sekarang, yaitu syarat keturunan Quraisy dan syarat mendahulukan yang terbaik.
Mengenai syarat keturunan Quraisy, yang berarti bahwa imam harus dari suku Quraisy, maka kami katakan—dan dengan pertolongan Allah:
Syarat ini adalah salah satu syarat yang para ulama sangat berbeda pendapat mengenainya, bahkan kelompok terkenal dari kelompok-kelompok Islam yaitu kelompok Khawarij, salah satu yang terkenal dari mereka adalah pendapat mereka tentang tidak wajibnya syarat ini. Kami akan menjelaskan pendapat-pendapat para ulama dalam hal itu, kemudian menjelaskan dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai sandaran.
Pendapat Para Ulama tentang Persyaratan Keturunan Quraisy:
Ahlussunnah dan mayoritas ulama berpendapat bahwa disyaratkan pada imam bahwa ia harus dari Quraisy. Sedangkan Khawarij berpendapat bahwa imamah boleh untuk orang Quraisy maupun non-Quraisy, tidak ada perbedaan dalam hal itu antara satu dengan yang lain karena nasab, suku, atau warnanya. Semuanya sama dalam kelayakannya untuk imamah, selama ia berpegang teguh pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan selama ia mampu menjalankannya.
Mengenai dalil-dalilnya, kami katakan:
Ahlussunnah berdalil dengan syarat nasab Quraisy berdasarkan Sunnah dan Ijma’.
Adapun dari Sunnah: mereka berdalil dengan hadits-hadits yang banyak, yang disebutkan dalam berbagai kitab Sunnah, dalam kitab-kitab Ahkam, bab-bab Imarah, Manaqib, dan lainnya. Di antara hadits-hadits ini adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersaid: “Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini, orang muslim mereka mengikuti muslim mereka, dan orang kafir mereka mengikuti kafir mereka.” Dalam riwayat lain: “Manusia mengikuti Quraisy dalam kebaikan dan keburukan.” Dan dalam riwayat ketiga: “Urusan ini akan tetap berada di tangan Quraisy selama masih tersisa dua orang dari manusia.” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: “Sesungguhnya urusan ini ada pada Quraisy, tidak ada yang memusuhi mereka kecuali Allah akan menelungkupkan wajahnya, selama mereka menegakkan agama.”
Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar, ketika pergi ke Saqifah Bani Sa’idah di mana kaum Anshar berkumpul untuk memilih khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berbicara dan tidak meninggalkan satu pun yang diturunkan tentang Anshar, atau yang disebutkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang urusan mereka kecuali ia menyebutkannya. Ia berkata: “Sungguh kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‘Seandainya manusia menempuh suatu lembah dan Anshar menempuh lembah lain, aku akan menempuh lembah Anshar.’ Dan sungguh engkau telah mengetahui wahai Sa’ad, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda—sementara engkau duduk—: ‘Quraisy adalah pemimpin urusan ini, orang-orang baik manusia mengikuti orang-orang baik mereka, dan orang-orang jahat mereka mengikuti orang-orang jahat mereka.’ Maka ia berkata kepadanya: ‘Engkau benar, kami adalah para menteri dan kalian adalah para pemimpin.'”
Dengan ini jelaslah bahwa Sunnah telah mewajibkan syarat ini dengan riwayat-riwayat yang beragam, selain ijma’. Telah terjadi ijma’ pada zaman para sahabat, dan juga setelah mereka, bahwa para imam adalah dari Quraisy.
Inilah yang dijadikan dalil oleh pemegang pendapat pertama, yaitu jumhur ulama yang berpendapat bahwa disyaratkan pada imam bahwa ia harus dari Quraisy.
Jika kita perhatikan dalil-dalil pendapat lain, yaitu Khawarij yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan syarat ini, maka mereka memiliki dalil-dalil atas apa yang mereka kemukakan.
Mereka berargumen dalam tidak disyaratkannya keturunan Quraisy dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan yang dinisbahkan kepada Umar bin Khaththab radiyallahu anhu, dan dengan dalil akal.
Adapun hadits-hadits yang menetapkan bahwa keturunan Quraisy bukan syarat dari syarat-syarat imamah, di antaranya adalah yang diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar, ia berkata: “Sesungguhnya kekasihku telah berwasiat kepadaku agar aku mendengar dan taat, meskipun ia adalah seorang budak yang terpotong-potong anggota badannya.” Artinya agar aku mendengar dan taat, walaupun ia adalah budak yang hina, yang anggota-anggota tubuhnya telah dipotong. Selama ia adalah pemimpin, maka ketaatannya wajib. Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Hushain, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji Wada’: “Walaupun diangkat atas kalian seorang budak yang memimpin kalian dengan Kitab Allah, maka dengarkanlah dan taatilah dia.” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: “Dengarlah dan taatlah meskipun diangkat atas kalian seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis.”
Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa keturunan Quraisy bukan syarat pada imam, karena Rasul shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada budak ketika ia menjadi pemimpin kaum muslimin. Diketahui bahwa Quraisy tidak memiliki budak yang nasabnya bersambung dengan mereka. Bahkan dalam salah satu hadits ini disebutkan wajibnya mendengar dan taat kepada budak Habsyi. Maka hal ini menunjukkan bahwa imam mungkin bukan dari Quraisy, dan inilah yang diklaim oleh pemegang pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan imam harus dari Quraisy.
Adapun dalil mereka dengan perkataan yang dinisbahkan kepada Umar radiyallahu anhu, diriwayatkan darinya bahwa ketika ia ditikam, kaum muslimin memintanya agar mengangkat khalifah yang ia ridhai untuk mereka, agar mereka tidak berselisih setelahnya. Mereka berkata kepadanya: “Tunjukkan kepada kami siapa yang akan mengurus urusan kami.” Maka ia radiyallahu anhu berkata: “Seandainya Salim maula Abu Hudzaifah masih hidup, aku akan menjadikannya khalifah.” Diriwayatkan juga darinya perkataannya: “Jika ajalku datang dan Abu Ubaidah masih hidup, aku akan menjadikannya khalifah. Jika ajalku datang dan Abu Ubaidah telah meninggal, aku akan menjadikan Muadz bin Jabal khalifah.”
Perkataan Umar ini menunjukkan bahwa ia tidak memandang wajibnya syarat keturunan Quraisy, karena ia berniat mengangkat Salim maula Abu Hudzaifah atau Muadz bin Jabal sebagai khalifah, dan keduanya bukan dari Quraisy. Bahkan yang pertama bukan orang Arab, dan yang kedua adalah Anshari yang tidak memiliki nasab di Quraisy.
Adapun dalil akal tentang tidak adanya syarat keturunan Quraisy pada imam, mereka berkata:
Sesungguhnya nasab tidak dipertimbangkan oleh Syari’ dalam melaksanakan urusan-urusan agama. Tidak ada kemuliaan atau kehinaan kecuali dengan amal saleh dan baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu atau tidak adanya hal itu. Allah berfirman: “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (Surat Al-Hujurat: ayat 13) Islam telah datang dengan prinsip kesetaraan di antara semua manusia, yang putih, hitam, dan merah mereka, yang mulia dan hina mereka. Tidak ada keutamaan seseorang atas yang lain kecuali dengan ketakwaan. Persyaratan keturunan Quraisy adalah kecenderungan kepada fanatisme, dan agar satu kelompok manusia berkuasa atas seluruh umat, dan inilah yang dibenci dan dimurkai oleh syariat yang bijaksana.
Setelah itu, seseorang benar-benar bingung dalam memadukan antara dalil-dalil yang menetapkan wajibnya keturunan Quraisy pada imam, di antaranya hadits-hadits yang beragam yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ijma’ kaum muslimin tentang hal itu. Kami katakan: benar-benar bingung dalam memadukan antara semua ini dengan perkataan Umar tentang Salim maula Abu Hudzaifah dan Muadz bin Jabal. Namun pada akhirnya harus condong kepada dalil-dalil yang menetapkan syarat keturunan Quraisy, karena dalil-dalil itu adalah nash-nash yang menunjukkan wajibnya syarat ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan telah dikuatkan oleh ijma’ para sahabat. Maka tidak ada jalan lain selain tunduk pada apa yang ditunjukkan oleh semua dalil ini, terutama karena hukum ini telah menjadi qath’i (pasti) dengan ijma’, tidak mengandung keraguan sedikitpun tentang wajibnya syarat ini.
Adapun apa yang dikatakan oleh Khawarij yang tidak mensyaratkan pada imam bahwa ia harus Quraisy, kami katakan: apa yang mereka katakan bahwa Islam melarang fanatisme, dan bahwa satu kelompok tertentu berkuasa atas seluruh kaum muslimin, dan bahwa Islam datang dengan kesetaraan di antara semua manusia, dan ini bertentangan dengan menjadikan khilafah di Quraisy, maka kami katakan sebagai jawaban kepada mereka:
Sesungguhnya Islam dengan mensyaratkannya bahwa imam harus Quraisy, tidaklah dengan hal itu mengajak kepada fanatisme yang dilarangnya. Sesungguhnya penguasa tertinggi dalam negara Islam tidak memiliki keistimewaan apapun atas seluruh anggota umat, dan keluarganya juga tidak memiliki hak tambahan sedikitpun atas hak-hak yang dijamin oleh Syari’ untuk seluruh anggota kaum muslimin. Imam dan anggota kaum muslimin, semuanya sama di hadapan hukum Islam, mereka tunduk pada hukum-hukumnya. Bahkan imam memikul beban yang menjadikannya sebagai orang yang paling berat bebannya dan paling berat perhitungannya di hari kiamat, karena ia bertanggung jawab atas rakyatnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah kita shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keistimewaan sedikitpun bagi keluarga yang darinya Abu Bakar atau Umar berasal atas anggota kaum muslimin manapun pada masa khilafah keduanya. Tindakan sewenang-wenang Bani Umayyah atas hak-hak kaum muslimin pada masa khilafah Utsman bukanlah hasil dari fanatisme dari Utsman, melainkan karena kelemahannya radiyallahu anhu dan ketidaktepatannya dalam memilih orang-orang yang mengurus urusan rakyat dari pihaknya, hingga hal itu menjadi penyebab kebangkitan fitnah yang melanda dunia Islam saat itu. Berkumpullah orang-orang awam, orang-orang yang memiliki hawa nafsu, dan para pengacau Islam, mereka berkumpul dalam kerumunan yang bergejolak yang akhirnya mengakibatkan terbunuhnya khalifah di rumahnya sementara ia sedang membaca Al-Quran. Islam tidak membuat satu kelompok berkuasa, artinya tidak menjadikan mereka memiliki kekuasaan, tidak menjadikan kekuasaan untuk satu kelompok manusia atas selain mereka dari anggota umat. Jika imam dari Quraisy, bukan berarti Quraisy menempati kedudukan tinggi yang di bawahnya adalah kedudukan seluruh kaum muslimin, karena Islam—sebagaimana kami katakan—tidak membedakan antara orang Quraisy dan non-Quraisy, dan tidak membedakan antara penguasa dan yang dikuasai. Umat dengan komitmennya pada hukum Islam adalah pemilik hak dalam mengendalikan khalifah, dan umat yang akan memecatnya kapan pun ia melihat itu sebagai kemaslahatan. Tidak ada kekuasaan keagamaan dalam Islam selain kekuasaan nasihat yang baik, ajakan kepada kebaikan, dan menjauhkan dari keburukan. Ini adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin yang paling rendah sekalipun.
Dengan ini, kami telah menjawab kerancuan yang dipegang teguh oleh Khawarij dan orang-orang yang bersama mereka dalam mengatakan tidak disyaratkannya keturunan Quraisy pada imam.
Namun apa hikmah dalam mensyaratkan keturunan Quraisy?
Kami segera mengatakan: Sesungguhnya keturunan Quraisy adalah syarat yang telah ditetapkan dengan hadits-hadits yang banyak, dan dengan ijma’ kaum muslimin atasnya pada generasi terbaik—sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari hikmah dari syarat ini, mungkin kita benar dalam hal itu, dan mungkin kita salah. Dalam hal ini tidak mempengaruhi bahwa syarat ini telah tetap, penentangnya tidak mampu meniadakannya, karena urusan dalam hal seperti ini tergantung pada berdirinya dalil dan ketegasannya. Jika dalil telah berdiri tentang suatu perkara, maka wajib mematuhinya, dan tidak wajib pada setiap hukum bahwa ia harus beralasan atau jelas hikmahnya. Sebagaimana harus diketahui bahwa hikmah dalam mensyaratkan keturunan Quraisy bukanlah karena kekerabatan dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena kekerabatan memiliki hukum-hukum khusus seperti warisan, atau pengharaman nikah, dan lain-lain. Tetapi kekerabatan tidak ada kaitannya dengan imamah, sebagaimana tidak ada kaitannya dengan pengangkatan wali pada suatu wilayah. Telah ditetapkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam mengangkat orang yang terikat dengannya dengan hubungan kekerabatan, dan orang yang tidak terikat dengannya dengan hubungan ini. Para ulama telah berusaha mencari hikmah dari mensyaratkan keturunan Quraisy pada imam, maka sebagian besar ijtihad mereka berkisar pada kedudukan yang dinikmati oleh Quraisy di antara bangsa Arab pada umumnya, yang memudahkan kepatuhan orang-orang kepada mereka karena kemuliaan dan kepemimpinan mereka. Dan bahwa pengkhususan Quraisy dengan imamah adalah faktor penting dari faktor-faktor menjaga agama ini, karena agama datang dengan bahasa mereka, dan rasul agama ini dari mereka, yang menjadikan mereka terdorong secara alami untuk menjaganya dan menyebarkannya.
Akhirnya kami katakan: Sesungguhnya Islam telah mensyaratkan pada Imam Agung bahwa ia harus dari Quraisy. Baik hikmah dalam hal itu jelas bagi kita atau kita salah dalam memahaminya, sesungguhnya hal itu tidak mempengaruhi kenyataan bahwa ini adalah syarat yang disyaratkan oleh Syari’, sebagaimana kami katakan sebelumnya.
Syarat Imam Harus yang Terbaik
Kemudian kita membahas sekarang tentang syarat lain yang telah kita janjikan untuk membahasnya, yaitu bahwa imam harus yang terbaik dari yang lain. Maka kami katakan:
Kami ingin menjelaskan pada awalnya bahwa semuanya telah sepakat bahwa imamah agung jika telah diangkat untuk seseorang, kemudian muncul orang yang lebih baik darinya, maka tidak beralih dari imam kepada yang lebih baik. Alasan dalam hal itu jelas, karena munculnya yang lebih baik mungkin terjadi setiap saat. Jika dibolehkan beralih kepada yang lebih baik, hal itu akan menyebabkan keadaan ketidakstabilan pemerintahan dalam negara, yang menyebabkan kekacauan yang tidak diridhai oleh Syari’ yang bijaksana. Demikian juga tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam bolehnya pengangkatan orang yang kurang utama jika kata-kata umat telah sepakat atasnya dan tidak ridha dengan yang lain sebagai penggantinya, atau jika ada alasan yang menghalangi pengangkatan yang lebih baik, seperti ketidakhadirannya, atau sakitnya, atau orang yang kurang utama lebih ditaati di kalangan masyarakat dan lebih dekat di hati rakyat.
Para ulama berbeda pendapat dalam hal adanya dua orang yang terpenuhi pada masing-masing mereka syarat-syarat yang diperlukan dalam imamah agung, kecuali bahwa salah satunya lebih baik dari yang lain. Dan orang yang kurang utama tidak mendapat kesepakatan umat untuk memilihnya, dan tidak ada alasan yang membenarkan beralih dari yang lebih baik kepada yang kurang utama. Apakah boleh dalam keadaan ini mengangkat imamah untuk orang yang kurang utama ataukah tidak boleh, dan wajib mengangkat imamah untuk yang lebih baik?
Sebelum kita menyebutkan pendapat-pendapat dalam hal itu dan apa yang dijadikan sandaran pendapat-pendapat ini, kami memandang perlu menjelaskan beberapa aspek yang dapat dibandingkan antara dua orang berdasarkan ada atau tidaknya aspek-aspek tersebut.
Misalnya: bahwa lebih dari satu orang sama-sama memiliki sifat-sifat yang diperlukan dalam imamah, kecuali bahwa satu sifat dari sifat-sifat yang diperlukan ini seperti ilmu atau keberanian—misalnya—tampak jelas pada salah satu mereka dan unggul atas yang lain dalam sifat itu. Apakah boleh ketika itu meninggalkan yang lebih baik dalam sifat ini dan mengangkat yang kurang utama, ataukah tidak boleh? Dan inilah yang akan kami jelaskan mengenai pendapat-pendapat para ulama.
Pendapat Para Ulama tentang Pengangkatan Kepemimpinan untuk yang Kurang Utama:
Abu Hasan Al-Asy’ari berpendapat bahwa imam harus yang terbaik dari ahli zamannya dalam syarat-syarat imamah, dan tidak sah pengangkatan imamah untuk seseorang dengan adanya orang yang lebih baik darinya. Jika suatu kaum mengangkat imamah untuk yang kurang utama, maka orang yang diangkat itu termasuk raja-raja bukan imam, artinya seolah-olah ia menguasai kekuasaan tanpa sandaran dari syariat.
Mayoritas ahli fiqih dan ahli kalam berpendapat bahwa imamah boleh untuk yang kurang utama saat adanya yang lebih baik, dan tidak menghalangi adanya yang lebih baik pengangkatan imamah untuk yang kurang utama selama ia memenuhi syarat-syarat imamah.
Dalil-Dalil yang Mengatakan Tidak Bolehnya Imamah yang Kurang Utama:
Para penganut pendapat tidak bolehnya imamah yang kurang utama dengan adanya yang lebih utama berdalil dengan hal-hal berikut:
Pertama: Bahwa para sahabat telah mengangkat imamah untuk yang terbaik lalu yang terbaik. Maka keempat khalifah, yang terbaik mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dalil ini telah dijadikan argumen oleh Abu Hasan Al-Asy’ari.
Kedua: bahwa akal menetapkan buruknya mendahulukan orang yang kurang utama atas yang lebih utama dalam menegakkan hukum-hukum syariat dan menjaga benteng Islam.
Ketiga: bahwa orang yang lebih utama lebih dekat kepada kepatuhan massa kepadanya dan terkumpulnya pendapat untuk mengikutinya.
Inilah dalil-dalil dari mereka yang berpendapat tidak bolehnya kepemimpinan orang yang kurang utama.
Dalil-dalil mereka yang berpendapat bolehnya kepemimpinan orang yang kurang utama:
Mereka yang berpendapat bolehnya kepemimpinan orang yang kurang utama dengan adanya orang yang lebih utama berdalil dengan beberapa dalil:
Pertama: mereka berkata: sesungguhnya enam orang yang dicalonkan Umar untuk menjadi khalifah setelahnya, di antara mereka ada—menurut ijmak umat—yang utama dan yang lebih utama, namun demikian Umar membolehkan untuk mengangkat salah satu dari mereka jika mereka sepakat kepadanya dan melihat kemaslahatan mereka dalam mengangkatnya. Ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan imam harus orang yang paling utama di antara manusia.
Kedua: para ulama bersepakat tentang terlaksananya kepemimpinan setelah empat khalifah untuk sebagian orang Quraisy, seperti Muawiyah misalnya, padahal di antara para sahabat yang masih hidup ada yang lebih utama darinya dari mereka yang berinfak sebelum penaklukan Makkah dan berperang.
Ketiga: bahwa keutamaan adalah perkara tersembunyi yang mungkin tidak diketahui oleh ahli halli wal aqdi, dan mungkin pencarian keutamaan akan menyebabkan terjadinya perselisihan dan kekacauan perkara.
Inilah dalil-dalil dari mereka yang berpendapat bahwa boleh mengangkat orang yang kurang utama dengan adanya yang lebih utama.
Setelah mengkaji dalil-dalil kedua kelompok, kami berpendapat bahwa harus diambil pendapat tentang wajibnya mendahulukan yang lebih utama. Dan jika kami mengatakan wajib mendahulukan yang lebih utama, maka kami katakan: jika hal itu tidak terlaksana dan yang kurang utama didahulukan lalu dibai’at oleh ahli halli wal aqdi yang mewakili umat, maka kepemimpinan pada saat itu terlaksana baginya, dan kami tidak mengatakan tidak terlaksana; agar tidak menyebabkan terjadinya fitnah dan kerusakan.
Dengan ini kami telah selesai membahas tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi pada imam agung atau kepala negara.
Pelajaran: 12 Cara-cara terlaksananya kepemimpinan, kewajiban-kewajiban imam dan hak-haknya serta sebab-sebab berakhirnya kewenangannya.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Syarat-syarat kepala negara (3)
Terlaksananya kepemimpinan melalui ahli halli wal aqdi
Sekarang kita membahas tentang cara-cara terlaksananya kepemimpinan negara. Pendapat para ulama secara umum:
Jumhur fuqaha dan mutakallimin berpendapat bahwa terpenuhinya syarat-syarat kepemimpinan pada seseorang tidak cukup dengan sendirinya untuk terlaksananya kepemimpinan baginya, bahkan harus ada cara yang dengannya jabatan ini dapat ditetapkan. Bahkan dengan asumsi bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam kepemimpinan tidak terpenuhi kecuali pada satu orang saja yang menyendiri dengannya dari seluruh anggota umat, maka jumhur ulama mengatakan tidak terlaksananya kepemimpinan baginya hanya dengan itu, bahkan harus ada pemilihan dari ahli halli wal aqdi kepadanya.
Jika para ulama telah mengatakan bahwa kelayakan saja tidak cukup untuk terlaksananya kepemimninan, bahkan harus ada otoritas yang menyerahkan kepemimpinan ini kepadanya, namun mereka berbeda pendapat tentang cara mana yang dapat menjadi penjelas terlaksananya kepemimpinan.
Syiah Imamiyah berkata: sesungguhnya terlaksananya—yaitu terlaksananya kepemimpinan—tidak ada jalan kecuali dengan nash (penunjukan). Ahli Sunnah berkata: sesungguhnya jalannya adalah bai’at dari ahli halli wal aqdi, atau penunjukan dari imam sebelumnya.
Ada dua cara lain menurut jumhur ulama umat untuk terlaksannya kepemimpinan, selain pemilihan ahli halli wal aqdi, yaitu: penunjukan dan penaklukan atau kemenangan. Kita akan membahas—dengan kehendak Allah—tentang semua yang telah kami sebutkan, yaitu pemilihan ahli halli wal aqdi, penunjukan, penaklukan atau kemenangan, dan nash yang diklaim oleh Syiah Imamiyah, dengan menyebutkan perbedaan pendapat ulama jika ada pada setiap perkara, dan merajihkan pendapat yang kami lihat.
Cara pertama: yaitu pemilihan ahli halli wal aqdi:
Pemilihan ahli halli wal aqdi, atau bai’at ahli halli wal aqdi, adalah cara asal terlaksananya kepemimpinan menurut jumhur ulama dari fuqaha dan mutakallimin. Jika jabatan kepemimpinan kosong karena wafatnya imam atau pemecatannya dari jabatannya, maka wajib atas umat yang diwakili oleh ahli halli wal aqdi untuk memeriksa keadaan orang yang dapat menjalankan beban jabatan ini. Siapa yang mereka lihat telah memenuhi syarat-syaratnya, mereka bai’at sebagai imam mereka. Jika tidak ada yang memenuhi syarat-syarat selain dia, maka wajib baginya menerima jabatan ini, jika tidak ada uzur yang membenarkan baginya menolak apa yang mereka tawarkan kepadanya. Adapun jika dia mempunyai uzur yang mencegahnya dari menjalankan beban jabatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh hukum-hukum syariat, maka pada saat itu mereka beralih darinya kepada yang lain, dengan memperhatikan dalam bai’at mereka kepada yang lebih utama, agar jabatan ini tidak dipegang oleh yang tidak berhak.
Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah berkata:
“Jika telah ditentukan oleh ahli pemilihan dari antara jamaah orang yang ijtihad mereka mengarah untuk memilihnya, mereka tawarkan kepada dia. Jika dia menerimanya, mereka bai’at dia untuknya, dan terlaksanalah dengan bai’at mereka kepadanya kepemimpinan. Maka wajib atas seluruh umat masuk dalam bai’atnya dan tunduk kepada ketaatannya. Jika dia menolak kepemimpinan dan tidak menerimanya, maka dia tidak dipaksa; karena itu adalah akad kerelaan dan pilihan, tidak masuk di dalamnya paksaan dan pemaksaan. Dan beralih darinya kepada yang lain dari yang berhak.”
Tetapi kita bertanya: mengapa pemilihan pemimpin diserahkan kepada kelompok khusus, seperti ahli halli wal aqdi?
Kami katakan: mungkin yang menarik perhatian para peneliti sistem pemerintahan Islam adalah apa yang telah ditetapkan oleh fuqaha Islam bahwa tugas memilih imam harus diserahkan kepada kelompok khusus tanpa anggota umat yang lain, yang mengisyaratkan—di lahirnya—tidak diperhitungkannya pendapat massa umat yang imam tidak dijadikan kecuali untuk mengurus kepentingan agama dan dunia mereka. Seharusnya tugas memilih imam diserahkan kepada setiap orang yang baligh dan berakal dari anggota rakyat, tidak ada perbedaan dalam hal itu antara satu dengan yang lain, agar pemilihan benar-benar mengekspresikan apa yang diridhai massa. Sama saja dalam hal itu apakah pemilihan ini dilakukan dengan cara langsung, seperti pemungutan suara umum, atau dengan cara tidak langsung, seperti pemilihan imam dilakukan melalui lembaga khusus yang dipilih oleh rakyat, yang diserahkan kepadanya menjalankan tugas penting ini. Pembatasan pemilihan imam kepada kelompok khusus adalah sesuatu yang menarik perhatian para peneliti; karena di lahirnya bertentangan dengan prinsip memberikan hak pemilihan kepada setiap warga negara, agar pemilihan mengekspresikan kehendak rakyat dengan sepenuhnya.
Benar bahwa Islam mewajibkan kepada semua—yaitu semua anggota umat—untuk membai’at imam dan masuk dalam ketaatannya, setelah terlaksananya kepemimninan baginya dengan akad ahli halli wal aqdi. Tetapi kewajiban itu dimaksudkan untuk menutup pintu perpecahan, agar tidak terjadi fitnah dan kekacauan di antara manusia. Oleh karena itu para ulama berkata: sesungguhnya jika bai’at telah sempurna dari ahli halli wal aqdi di satu wilayah, wajib atas mereka mengabarkan kepada seluruh ahli halli wal aqdi di wilayah-wilayah lain.
Sebagian orang berkata: jika sebagian ahli halli wal aqdi mengangkat seorang imam, maka gugurlah kewajiban mengangkat imam dari yang lain, dan orang yang mereka angkat menjadi imam. Wajib bagi mereka menampakkan itu dengan surat-menyurat dan korespondensi; agar yang lain tidak sibuk dengan imam selain dia padahal kewajiban telah tercukupi, dan agar tidak menyebabkan fitnah. Maka tidak dibai’atnya oleh seluruh anggota umat tidak mempengaruhi terlaksananya imam; karena akad terlaksana hanya dengan bai’at ahli halli wal aqdi. Akad tidak sah jika imam tidak dibai’at oleh ahli halli wal aqdi. Jika diasumsikan setelah wafat imam misalnya atau pemecatannya, berkumpul sejumlah orang dari selain ahli halli wal aqdi dan mengadakan bai’at untuk seseorang dari manusia, maka bai’at ini tidak diperhitungkan dan tidak mempunyai sifat syar’i yang memaksa anggota umat lainnya untuk masuk dalam ketaatan orang yang dibai’at oleh kelompok ini.
Sebelum kami menjelaskan makna ideal yang diperhatikan dalam menetapkan prinsip Islam yang mengatakan wajibnya menyerahkan tugas memilih kepala negara kepada kelompok khusus yang disebut secara istilah dengan kelompok ahli halli wal aqdi, harus kami katakan pada awalnya: bahwa jika kita benar-benar mencari cara paling baik untuk memilih kepala negara, harus kita akui dua perkara:
Pertama: bahwa pemilihan kepala negara harus tidak diserahkan kecuali kepada orang yang memiliki kemampuan membedakan antara yang layak dan tidak layak untuk memegang jabatan penting ini. Terpenuhinya kemampuan ini tidak terwujud kecuali dengan menetapkan syarat-syarat dan sifat-sifat khusus pada orang yang sah menjalankan tanggung jawab ini, syarat-syarat dan sifat-sifat yang akan menghasilkan kelayakan sempurna pada yang menjalankan tugas ini; karena ketika kepala negara tidak dipilih kecuali dari orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat khusus yang membuatnya layak menjalankan beban jabatan ini—yaitu yang telah kami jelaskan sebelumnya ketika membahas syarat-syarat yang diperlukan pada kepala negara—kami katakan: maka wajiblah pemilihan pemimpin tidak diserahkan kecuali kepada orang-orang yang memiliki kemampuan membedakan antara orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat ini dan orang yang tidak terpenuhi padanya.
Kedua dari dua perkara yang harus diakui: adalah tidak sahnya klaim bahwa organisasi-organisasi parlemen mewakili seluruh rakyat dengan perwakilan yang benar, sama saja dalam hal itu rakyat yang telah mencapai tingkat tinggi dari ilmu dan kematangan politik, dan rakyat yang belum mencapai tingkat ini, karena beberapa sebab:
Sebab pertama: bahwa parlemen secara keseluruhan mungkin tidak mewakili kecuali minoritas kecil dari pemilih. Itu jika kita menghilangkan dari perhitungan kita dua jenis suara: pertama suara orang yang tidak hadir yang tidak memberikan pendapat mereka dalam pemilihan ini. Mereka yang tidak hadir ini mewakili jumlah besar dibandingkan dengan anggota pemilih lainnya dalam setiap pemilihan, dan jumlah mereka mencapai di kebanyakan negara sekitar separuh jumlah pemilih. Kedua dari dua jenis yang harus tidak diperhitungkan adalah suara-suara yang gagal, yaitu suara-suara yang diperoleh calon-calon yang tidak berhasil dalam pemilihan ini. Jumlah kedua jenis ini membentuk jumlah besar, mungkin mayoritas dibandingkan dengan suara lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh statistik, sama saja dalam hal itu negara yang mengambil sistem pemungutan suara wajib dan negara yang tidak mengambil sistem ini. Oleh karena itu parlemen mungkin tidak mewakili kecuali minoritas kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih, dan dengan demikian tidak mewakili kecenderungan sebenarnya dari keseluruhan umat. Ini selain dari yang diperhatikan bahwa terjadi di banyak negara tunduknya mayoritas parlemen kepada dominasi sejumlah kecil pemimpin dan politisi yang mengarahkannya sesuai keinginan dan kecenderungan mereka. Mungkin kecenderungan dan keinginan ini tidak sejalan dalam kebanyakan keadaan dengan kecenderungan massa yang mereka wakili, meskipun mereka mengklaim dengan dusta bahwa mereka mengekspresikan kepentingan massa umat.
Sebab kedua dari sebab-sebab tidak sahnya klaim bahwa organisasi parlemen mewakili seluruh rakyat dengan perwakilan yang benar, adalah rusaknya pemilihan dalam banyak keadaan: sesungguhnya apa pun yang dikatakan tentang kebebasan pemilihan dan tidak campur tangannya kehendak di dalamnya, sesungguhnya dalam kenyataannya tidak lepas dari penggunaan banyak cara yang tidak sah, dari kecurangan, penipuan massa, memikat mereka dengan suap, dan memperdaya mereka dengan tujuan mendapatkan suara mereka, yang mempengaruhi hasil pemilihan dengan pengaruh besar.
Sebab ketiga: bahwa jika kita mengakui secara dialektis bahwa pemilihan terlaksana dengan cara bersih yang bebas dari hal yang mengotorinya yang telah kami sebutkan tadi, dan kita asumsikan bahwa parlemen benar-benar mewakili kehendak mayoritas pemilih, maka kami tidak mengakui dikatakan: bahwa parlemen mewakili massa umat sepanjang waktu; karena perbedaan kecenderungan pada massa dan arah mereka yang berbeda-beda, mungkin membuat dapat diterima klaim bahwa parlemen mewakili mereka dalam beberapa masalah tertentu untuk waktu singkat. Adapun klaim bahwa parlemen mewakili massa umat sepanjang waktu, maka ini tidak lebih dari sejenis kedaulatan wakil atas yang diwakili.
Setelah itu, telah jelas dari apa yang telah kami sebutkan bahwa klaim bahwa organisasi-organisasi parlementer mewakili kehendak massa dan mengungkapkan opini publik adalah klaim yang tidak dapat diterima begitu saja, karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan. Jelas bagi kita dari uraian sebelumnya bahwa penunjukan kelompok tertentu dalam sistem Islam untuk memilih kepala negara merupakan bentuk idealisme yang dicita-citakan Islam dalam perundang-undangannya. Maksudnya adalah adanya pihak tertentu atau kelompok tertentu yang disebut sebagai Ahlul Halli wal Aqdi (ahli yang berhak memutuskan dan mengikat) yang melakukan pemilihan kepala negara. Inilah hal yang penting, dan ini jauh lebih baik daripada yang ada dalam undang-undang buatan manusia dan sistem pemilihan buatan manusia yang telah terbukti gagal sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.
Namun apakah anggota kelompok yang melakukan pemilihan presiden ini dipilih, ataukah cukup dengan tersiarnya kabar tentang mereka, atau kabar tentang keutamaan, ilmu, dan keunggulan mereka di kalangan massa umat? Ini termasuk topik yang diperselisihkan di antara para ulama fikih.
Kepemimpinan adalah Akad seperti Akad-akad Lainnya:
Tidak boleh terlewatkan bagi kita untuk menunjukkan di sini bahwa para ulama fikih Islam dan ahli teologi telah menetapkan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah akad seperti akad-akad lainnya yang terjadi antara dua pihak. Umat di sini adalah pihak pertama, dan presiden atau imam adalah pihak kedua. Imamah adalah akad yang nyata yang dibangun atas dasar kerelaan, berdiri antara umat dan imam. Berdasarkan akad ini, pihak kedua yaitu imam atau presiden wajib menjalankan pemerintahan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan wajib bagi pihak pertama yaitu umat untuk memberikan ketaatan dan kepatuhan kepadanya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah dan larangan syariat.
Ketika para pemikir Islam telah menjelaskan bahwa hubungan antara penguasa dan yang diperintah dibangun atas dasar akad antara mereka dan penguasa, maka dengan itu mereka telah mendahului pemikiran Barat dalam penelitian hukum politik. Sebab Jean Jacques Rousseau yang dianggap oleh Eropa sebagai bapak demokrasi modern dengan bukunya “Kontrak Sosial” yang menjadi semacam Injil bagi para pemimpin Revolusi Prancis, dan yang di dalamnya dia memasukkan teorinya yang mengatakan: bahwa penguasa memperoleh kekuasaannya dari umat sebagai wakil mereka, berdasarkan kontrak yang dibuat di antara mereka, sesungguhnya Rousseau ini telah didahului oleh teori Islam selama berabad-abad. Jika para pemikir Islam telah mendahuluinya dan mendahului yang lainnya, dan berbicara tentang akad antara penguasa dan yang diperintah, maka mereka adalah para perintis di bidang pemikiran penting ini, terutama karena akad yang dibicarakan oleh Rousseau adalah akad yang dia bayangkan terjadi di zaman purba, dan tidak ada bukti sejarah yang dapat menjadi bukti nyata atasnya. Berbeda dengan akad yang dibicarakan oleh para pemikir Islam, karena itu adalah akad yang nyata dan tetap, sejak hari sistem khilafah ada, dan baiat umat menjadi bentuk realisasinya.
Di sisi lain, teori Islam tidak mengandung individu-individu yang melepaskan sebagian dari kebebasan dan kekuasaan mereka, melainkan kita memiliki umat yang diberi tanggung jawab yang mewakilkan kepada sebagian anggotanya untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan dalam perwakilan tidak ada pemilikan, dan tidak ada dugaan pemilikan. Baiat adalah akad yang mengikat penguasa dengan konstitusi khusus, dan menentukan baginya batas-batas tugasnya. Jika dia mematuhi syarat-syarat akad maka dia berhak mendapat ketaatan dari yang diperintah. Jika dia melampaui apa yang ditetapkan untuknya dan keluar dari syarat, maka dia terlepas dari perwakilan, dan keluar dari tanggung jawabnya dengan sendirinya, atau dengan pemecatan oleh rakyat yang mengangkatnya.
Makna Baiat:
Ibnu Khaldun menjelaskan makna baiat dengan mengatakan:
Baiat adalah janji atas ketaatan. Orang yang membaiat berjanji kepada pemimpinnya bahwa dia akan menyerahkan kepadanya pengurusan urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, tidak akan menyengketakan apapun dari itu, dan akan menaatinya dalam apa yang dibebankan kepadanya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ketika mereka membaiat pemimpin dan mengikat janjinya, mereka meletakkan tangan mereka di tangannya untuk menguatkan janji, sehingga itu menyerupai perbuatan penjual dan pembeli, maka dinamakanlah baiat.
Lafal baiat telah menjadi penggunaan majaz (kiasan) dalam arti menyetujui imam dan patuh kepadanya. Jika orang-orang menyetujuinya dan patuh kepadanya, maka saat itu dikatakan secara majaz: sesungguhnya mereka telah membaiatinya sebagai imam mereka. Oleh karena itu, para ulama fikih dan ahli teologi ketika berbicara tentang baiat, mereka tidak bermaksud bersalaman dengan tangan, tetapi mereka memaksudkan persetujuan, kepatuhan, dan mewujudkannya. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa bersalaman dengan tangan tidak disyaratkan untuk terwujudnya baiat.
Syarat-syarat Sahnya Baiat:
Agar baiat terjadi dengan cara yang benar, harus terpenuhi beberapa syarat di dalamnya. Kami akan menjelaskan syarat-syarat ini dengan menyebutkan perbedaan pendapat jika ada dalam salah satu syarat tersebut, yaitu:
Syarat Pertama: Bahwa terkumpul pada orang yang untuknya diambil baiat syarat-syarat yang diperlukan bagi kepala negara, yaitu yang telah kami jelaskan sebelumnya. Berdasarkan ini, kepemimpinan tidak sah bagi seseorang yang kehilangan salah satu dari syarat-syarat ini, kecuali dalam keadaan darurat, seperti keadaan penguasaan dan pengambilan kekuasaan dengan paksa atas pemerintahan, yang di zaman kita sekarang diungkapkan dengan istilah kudeta militer. Ini adalah cara yang telah dijelaskan para ulama tentang kemungkinan sahnya kepemimpinan dengannya. Juga jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan pada seseorang yang layak memegang jabatan ini, maka diperbolehkan saat itu untuk mengabaikan sebagian dari syarat-syarat ini, karena keadaan darurat. Maka diangkatlah yang paling utama lalu yang paling utama, agar masa tidak kosong dari pemimpin yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia.
Syarat Kedua: Bahwa yang mengadakan baiat untuk presiden adalah Ahlul Halli wal Aqdi. Jika yang mengadakannya selain mereka, maka tidak sah.
Syarat Ketiga: Bahwa orang yang untuk dirinya diadakan kepemimpinan menerima jabatan ini. Jika dia menolak, maka kepemimpinannya tidak sah, dan dia tidak dipaksa untuk menerimanya.
Syarat Keempat: Persaksian atas baiat. Ini adalah syarat yang diperselisihkan dengan tiga pendapat: Pertama, bahwa baiat tidak memerlukan persaksian. Pendapat kedua, wajibnya persaksian atasnya. Pendapat ketiga, dilihat jumlah yang mengadakan akad, jika mereka sejumlah orang maka persaksian tidak disyaratkan, dan jika yang mengadakan akad satu orang maka disyaratkan hal itu.
Syarat Kelima: Bahwa akad ini tidak dibarengi dengan akad lain, maka tidak boleh diadakan kepemimpinan untuk lebih dari satu orang.
Sebelum kami merinci perbedaan pendapat tentang syarat ini, kami perlu menjelaskan bahwa pengadaan akad berganda bisa terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja, atau terjadi bukan secara kebetulan dan tidak disengaja. Yang pertama terjadi ketika beberapa kelompok dari Ahlul Halli wal Aqdi melakukan baiat untuk seorang pemimpin tanpa ada hubungan dan koordinasi antara kelompok-kelompok ini. Salah satu kelompok membaiat seorang pemimpin misalnya, dan kelompok lain membaiat pemimpin yang lain, demikian seterusnya karena tidak tahunya masing-masing dari mereka tentang apa yang dilakukan kelompok-kelompok lain. Terjadilah baiat untuk beberapa orang, setiap orang dari mereka layak untuk kepemimpinan. Di sini terjadi akad berganda secara kebetulan dan tidak disengaja, tanpa Ahlul Halli wal Aqdi sengaja membaiat lebih dari satu orang.
Yang kedua: Terjadinya pengadaan akad berganda karena Ahlul Halli wal Aqdi sengaja membaiat lebih dari satu orang.
Para ulama telah bersepakat bahwa tidak sah diadakan baiat untuk lebih dari satu imam di satu negara, baik pengadaan akad berganda itu terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja, maupun selain itu.
Adapun jika pengadaan akad berganda itu di negara-negara yang berbeda yang berjauhan, para ulama berselisih tentang pengadaan akad berganda ini, apakah boleh atau tidak boleh.
Jumhur (mayoritas) ulama fikih dan ulama melarang pengadaan akad berganda, meskipun negara-negara itu berjauhan. Sebagian ulama—dan mereka minoritas—berpendapat bolehnya pengadaan imam berganda di negara-negara yang berbeda. Setiap satu dari dua kelompok ini memiliki dalil yang mereka sandari.
Dalil-dalil Jumhur tentang Larangan Pengadaan Akad Berganda:
Jumhur berdalil bahwa tidak boleh adanya imam berganda meskipun negara-negara berjauhan dengan beberapa dalil, di antaranya:
Pertama: Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” Hadis ini tegas tentang tidak disyariatkannya pengadaan akad berganda, dan pembunuhan imam yang terakhir adalah setelah dia dituntut untuk tidak berpegang pada baiat yang terjadi untuknya, dan tunduk kepada imam yang pertama. Jika dia menolak maka dia adalah pemberontak yang wajib diperangi. Bukan maksud hadis adalah membunuh imam yang lain hanya karena diadakan baiat lain untuknya, karena boleh jadi dia tidak tahu bahwa ada imam lain yang telah diadakan baiat untuknya sebelum dia.
Kedua: Mereka berdalil dengan ijma (kesepakatan ulama). Yaitu bahwa para sahabat telah bersepakat bahwa tidak boleh kecuali satu imam saja, sampai-sampai kaum Muhajirin tidak menyetujui kaum Anshar ketika mereka menyerukan pertama kali agar ada pemimpin dari mereka, dan pemimpin dari kaum Muhajirin. Kemudian kaum Anshar rela dengan apa yang dikemukakan kaum Muhajirin, maka jadilah ijma.
Dalil Ketiga juga tentang larangan pengadaan akad berganda: Bahwa pengadaan imam berganda mengakibatkan terjadinya perselisihan dan persengketaan, dan ini mengakibatkan kacaunya urusan agama dan dunia. Maka pengadaan imam berganda mengakibatkan kacaunya urusan agama dan dunia, dan itu tidak dibolehkan.
Adapun penganut pendapat lain, dan mereka minoritas dari para ulama, mereka berpendapat bolehnya pengadaan akad berganda, dan berdalil dengan itu bahwa imam dijadikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jika di setiap wilayah ada imam, maka setiap orang lebih mampu terhadap apa yang ada di tangannya, karena sedikitnya kemaslahatan saat itu, dan lebih dapat mengawasi para gubernur, hakim, dan seluruh pejabat yang dia angkat. Juga mereka berdalil bahwa ketika dibolehkan adanya lebih dari satu nabi di satu masa, dan tidak mengakibatkan batalnya kenabian, maka dibolehkan juga pada imam, bahkan lebih utama, karena imamah adalah cabang dari kenabian.
Tetapi kelompok ini telah dibantah oleh jumhur ulama, dan dalil-dalil mereka dibantah, dan jelas batilnya dalil-dalil ini.
Saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian.
2 – Sahnya Imamah Melalui Jalur Wasiat dan Penguasaan
Lanjutan Sahnya Imamah Melalui Jalur Ahlul Halli wal Aqdi
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du (setelah itu):
Pada perkuliahan sebelumnya kita telah membahas syarat Quraisy dan syarat mendahulukan yang lebih utama berkaitan dengan pemilihan imam dan berkaitan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi padanya. Kita telah mulai membahas cara-cara yang dengannya sahnya imamah kubra (kepemimpinan agung). Telah jelas bagi kita bahwa cara pertama adalah pemilihan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Kita telah membahas di dalamnya tentang baiat dan tentang syarat-syarat baiat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang cara ini, kita bicarakan tentang Ahlul Halli wal Aqdi, kemudian kita jelaskan syarat-syarat mereka. Kita katakan:
Ahlul Halli wal Aqdi sebagaimana mereka dinamakan oleh mayoritas ulama, atau ahli pemilihan sebagaimana mereka dinamakan oleh Imam Al-Mawardi, atau ahli ijtihad sebagaimana mereka dinamakan oleh sebagian ulama lainnya, adalah kelompok tertentu dari orang-orang utama umat yang diwakilkan kepada mereka pengurusan kemaslahatan agama dan dunia mereka, termasuk di dalamnya pemilihan kepala negara atau imam agung. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan orang-orang yang mungkin layak memegang jabatan penting ini, dan berijtihad dalam hal itu. Siapa yang mereka pandang layak memegang jabatan ini, mereka membaiatinya sebagai kepala negara berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya ketaatan kepadanya dalam setiap perintah yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada kelompok ini agar mereka dibedakan dari anggota-anggota umat lainnya, karena mereka—sebagaimana kita katakan—ditugaskan dengan memilih presiden. Jika mereka melaksanakan tugas ini atau sebagian anggota mereka melaksanakannya, gugurlah kewajiban mengangkat presiden dari mereka dan dari anggota umat lainnya. Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban ini, berdosalah seluruh Ahlul Halli wal Aqdi, sebagaimana halnya dalam kewajiban kifayah.
Kelompok ini tidak melakukan pemilihan imam kecuali mewakili seluruh umat. Mereka dengan melakukan pemilihan ini tidak mewakili diri mereka sendiri, tetapi mewakili seluruh umat. Oleh karena itu, ketika Ahlul Halli wal Aqdi membaiat imam, wajib bagi seluruh anggota umat untuk membaiatinya dan patuh kepadanya. Para ulama telah menjelaskan bahwa Ahlul Halli wal Aqdi adalah para ulama, para pemimpin, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mudah dikumpulkan pada setiap waktu.
Sekarang kita bicarakan tentang syarat-syarat Ahlul Halli wal Aqdi. Kita katakan: Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam bukunya “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah” halaman keenam dan seterusnya, menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan bagi mereka—yaitu bagi Ahlul Halli wal Aqdi—dia berkata: Adapun ahli pemilihan, syarat-syarat yang dipertimbangkan pada mereka ada tiga:
Yang pertama: Sifat adil yang mencakup semua syaratnya.
Yang kedua: Ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak menjadi imam berdasarkan syarat-syarat yang dipertimbangkan padanya.
Yang ketiga: Pandangan dan kebijaksanaan yang mengarah kepada pemilihan orang yang paling layak untuk imamah, dan paling mampu dan paling mengetahui dalam mengatur kemaslahatan.
Syarat-syarat yang dijelaskan oleh Al-Mawardi ini menentukan gambaran yang harus dimiliki oleh seseorang dari kelompok ahli halli wal aqdi (ahli yang berhak memilih dan mengikat). Adapun keadilan, telah kami jelaskan maksudnya ketika membahas syarat-syarat kepemimpinan. Sedangkan syarat kedua, yang dimaksud adalah bahwa seseorang harus berilmu tentang syarat-syarat yang wajib ada pada pemimpin negara sehingga ia dapat membedakan antara orang yang memenuhi syarat kepemimpinan umum dan orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat ketiga, dimaksudkan agar tersedia kemampuan untuk tidak mencampuradukkan antara orang yang mampu menjalankan beban kepemimpinan dan orang yang tidak mampu melakukannya. Ini adalah syarat yang berbeda dari syarat sebelumnya, karena mungkin ada seseorang yang memiliki ilmu tentang syarat-syarat yang dipertimbangkan pada pemimpin, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara orang yang layak memimpin dan mengatur kepentingan umat dengan orang yang tidak layak untuk itu.
Apakah ahli halli wal aqdi yang berada di ibu kota – yaitu negeri pemimpin – memiliki kelebihan atas yang lainnya?
Imam Al-Mawardi menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan: Orang yang berada di negeri Imam tidak memiliki kelebihan khusus atas orang lain dari berbagai negeri yang membuatnya didahulukan. Sesungguhnya orang yang hadir di negeri Imam menjadi yang mengadakan akad untuk Imam secara adat, bukan secara syarak, karena ia lebih dahulu mengetahui kematiannya, dan karena orang yang layak untuk khilafah pada umumnya berada di negeri mereka. Ketika Al-Mawardi telah menjelaskan bahwa syarak tidak memberikan kelebihan atau prioritas kepada ahli halli wal aqdi yang berada di ibu kota dalam melakukan pemilihan pemimpin negara, melainkan adat yang berlaku bahwa merekalah yang melakukannya, maka berdasarkan itu, jika sekelompok ahli halli wal aqdi dari luar ibu kota berinisiatif memilih pemimpin, maka itu adalah pilihan yang sah dan tidak ada cacat secara syarak. Semua ahli halli wal aqdi yang berada di ibu kota dan wilayah-wilayah lain wajib tunduk dan membaiat pemimpin yang telah dibaiat oleh kelompok ini. Jika adat telah berlaku di beberapa masa bahwa ahli halli wal aqdi yang berada di negeri pemimpin adalah yang berinisiatif mengadakan kepemimpinan, maka sesungguhnya adat-istiadat itu tidak tetap dan berubah dengan perubahan lingkungan dan pergantian zaman. Sarana komunikasi yang cepat di era modern ini dan perkembangan luar biasa di dalamnya tidak lagi memberikan kelebihan bagi orang yang berada di negeri pemimpin untuk lebih dahulu mengetahui kematian pemimpin. Bahkan berbagai perangkat komunikasi dan kecepatan penyampaian berita menjadikan penyiaran suatu berita di antara massa rakyat, bahkan di seluruh dunia, sebagai pekerjaan yang mudah dan ringan yang diketahui oleh orang yang jauh maupun dekat pada saat penyiarannya dan penyebarannya. Kemudian tidak dapat diklaim bahwa orang-orang yang layak memimpin negara di masa ini pada umumnya berada di negeri pemimpin, karena mereka tersebar di berbagai penjuru negeri dan tidak hanya berada di negeri pemimpin negara.
Jumlah ahli halli wal aqdi yang dengannya kepemimpinan sah terbentuk: Para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang besar tentang jumlah ahli halli wal aqdi yang dengannya imamah (kepemimpinan) sah terbentuk, dan kami akan menyebutkan hal itu:
Pendapat Pertama: Mengatakan bahwa Imam tidak sah kecuali dengan ijmak seluruh umat dari awal hingga akhir, agar keridaan menjadi umum dan penerimaan kepemimpinannya menjadi ijmak.
Pendapat Kedua: Bahwa imamah tidak sah kecuali dengan baiat mayoritas dari ahli halli wal aqdi.
Pendapat Ketiga: Berpendapat bahwa jumlah minimum yang dengannya imamah sah adalah empat puluh orang, karena akad imamah lebih besar risikonya daripada Jumat, dan Jumat tidak sah dengan kurang dari empat puluh orang, maka baiat Imam lebih utama.
Pendapat Keempat: Mengatakan bahwa Imam sah dengan lima orang yang berkumpul untuk mengadakannya, atau salah seorang dari mereka mengadakannya dengan keridaan empat lainnya. Penganut pendapat ini berdalil dengan dua hal:
Hal Pertama: Bahwa baiat Abu Bakar radhiyallahu anhu sah dengan lima orang yang membaiatnya, kemudian orang-orang mengikuti mereka dalam hal itu. Lima orang tersebut adalah: Umar bin Al-Khaththab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bishr bin Sa’ad, dan Salim maula (budak yang dimerdekakan) Abu Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma’in.
Hal Kedua: Bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika ingin memberikan wasiat sebelum wafatnya, ia berjanji kepada enam orang sahabat agar mereka memilih salah satu dari mereka dengan keridaan lima lainnya.
Pendapat Kelima: Mengatakan bahwa cukup bagi sahnya baiat bahwa dilakukan oleh empat orang, karena empat orang adalah lebih banyak dari setengah kesaksian.
Pendapat Keenam: Mengatakan bahwa imamah sah dengan baiat tiga orang, karena itu adalah jamaah.
Pendapat Ketujuh: Mengatakan bahwa jumlah minimum yang dengannya imamah sah adalah dua orang dari ahli wara’ (kehati-hatian) dan ijtihad seperti akad nikah yang tidak sah kecuali jika disaksikan oleh dua saksi.
Pendapat Kedelapan: Mengatakan bahwa imamah sah dengan para ulama umat yang hadir di tempat Imam, dan tidak ada jumlah tertentu untuk itu.
Pendapat Kesembilan: Mengatakan bahwa cukup bagi sahnya imamah bahwa dilakukan baiat oleh satu orang saja, tetapi dengan syarat-syarat:
Syarat Pertama: Bahwa yang melakukan akad adalah dari ulama mujtahid.
Kedua: Bahwa orang yang mengadakan akad ini memiliki sifat wara’.
Syarat Ketiga: Bahwa ia termasuk ahli pendapat dan pengaturan.
Syarat Keempat: Bahwa ia telah meraih ketenaran di kalangan massa umat.
Syarat Kelima: Bahwa orang yang untuknya diadakan baiat adalah orang yang paling utama dalam sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan ada pada Imam.
Setelah ini, inilah pendapat-pendapat dan dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para fuqaha berkaitan dengan jumlah yang dengannya imamah sah dari ahli halli wal aqdi.
Sekarang, apa pendapat yang kami condongkan dari pendapat-pendapat yang telah kami sebutkan ini dalam masalah jumlah yang dengannya kepemimpinan negara sah? Sebelum kami menjelaskan pendapat yang kami condongkan, kami ingin bertanya: bagaimana mungkin dapat dibayangkan sahnya akad imamah dengan baiat satu orang saja, padahal baiat satu orang untuk Imam hanya mengungkapkan pendapat dan keinginan satu orang ini saja, dan keinginan ini mungkin tidak menunjukkan pendapat dan keinginan sisa ahli halli wal aqdi. Urusan kepemimpinan negara lebih besar dari pendapat satu orang betapapun besar kedudukannya dan terkenal keutamaannya. Ia adalah perkara yang tanpa ragu memerlukan kajian, penelitian, dan musyawarah, dan ini adalah perkara-perkara yang memerlukan komunikasi dengan ahli halli wal aqdi untuk mengambil pendapat mereka tentang siapa yang mereka ingin angkat. Oleh karena itu, Umar bin Al-Khaththab menganggap inisiatifnya membaiat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhuma sebelum mengambil pendapat ahli halli wal aqdi sebagai faltah (tindakan tergesa-gesa), dan Allah melindungi kaum muslimin dari kejahatannya. Diriwayatkan dari beliau bahwa ia berkhutbah kepada manusia, lalu berkata: “Telah sampai kepadaku bahwa si Fulan berkata: Demi Allah, jika Umar bin Al-Khaththab telah wafat, aku akan membaiat si Fulan. Janganlah seseorang terkecoh dengan mengatakan: Sesungguhnya baiat Abu Bakar adalah faltah yang kemudian selesai. Sesungguhnya ia memang demikian, tetapi Allah melindungi dari kejahatannya. Dan tidak ada di antara kalian yang kepadanya leher-leher tertunduk seperti Abu Bakar. Barangsiapa membaiat seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka tidak ada baiat baginya, tidak bagi dia dan tidak pula bagi orang yang membaiatnya.”
Maka jelas dari ini bahwa asalnya dalam baiat adalah setelah bermusyawarah dengan ahli halli wal aqdi, dan bahwa Umar dengan perbuatannya menyalahi asal ini, maka jadilah faltah karena kondisi khusus yang mengharuskan itu, yaitu: takut terjadinya fitnah antara Muhajirin dan Anshar. Ini bukanlah asal syarak yang harus diamalkan selamanya. Barangsiapa membaiat seseorang tanpa musyawarah dari ahli halli wal aqdi, maka tidak sah bahwa dia dan orang yang dibaiatnya layak untuk baiat. Kita telah melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ingin mengusulkan Umar bin Al-Khaththab untuk mengurusi urusan manusia setelahnya, ia memperpanjang musyawarah dengan para sahabat senior. Ketika Abdurrahman bin Auf mengeluarkan dirinya dari pencalonan khilafah dan diserahkan kepadanya urusan memilih khalifah, ia tetap tiga hari matanya tidak dipejamkan dengan banyak tidur, sementara ia bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin dan Anshar tentang siapa yang layak untuk imamah. Seandainya baiat satu orang cukup dalam sahnya imamah, niscaya Abdurrahman bin Auf tidak akan mengerahkan semua usaha ini, dan tidak akan menyendiri dengan dirinya untuk berpikir tentang siapa yang menurutnya layak memegang jabatan ini, kemudian membaiatnya setelah ia yakin dengan kelayakannya untuk imamah. Sisa ahli halli wal aqdi dan seluruh individu umat setelah itu tinggal tunduk kepada khalifah baru dan ridha dengan baiat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seandainya berpendapat bahwa imamah sah dengan satu orang dari ahli halli wal aqdi, niscaya ia melakukan itu. Tetapi ia berpendapat bahwa imamah tidak sah dengan satu orang dari ahli halli wal aqdi. Oleh karena itu, ia melelahkan dirinya dalam musyawarah – dalam bermusyawarah dengan kaum muslimin – tentang siapa yang layak menjadi imam. Adapun berdalil bahwa ketika Umar membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhuma, para sahabat mengikutinya dan menyetujuinya, maka itu tidak sah, karena sebab para sahabat mengikuti Umar dalam baiat ini dan menyetujuinya adalah keridaan mereka bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
Maka jelaslah dari yang telah disebutkan bahwa perkataan bahwa imamah sah dengan satu orang tidak dapat diterima. Demikian pula perkataan tentang sahnya dengan jumlah sedikit seperti dua, tiga, empat, dan lima, karena urusan imamah – seperti yang telah kami katakan – tidak sah di dalamnya menyendirikan satu individu atau beberapa individu sedikit dalam memutuskan apa yang menjadi kepentingan seluruh umat, kecuali jika jumlah anggota kelompok ahli halli wal aqdi sedikit. Saat itu keadaan darurat yang memaksa untuk mengatakan sahnya imamah dengan jumlah sedikit. Namun ini tidak berarti kita mengatakan – sebagaimana yang dikatakan sebagian orang – bahwa tidak sah baiat kecuali dengan ijmak dari orang-orang utama umat di berbagai penjuru negeri, karena seandainya benar bahwa imamah tidak sah kecuali dengan ijmak dari ahli halli wal aqdi, niscaya tidak sah imamah Abu Bakar. Sebab yang tetap adalah bahwa Sa’ad bin Ubadah tidak membaiat Abu Bakar sebagai imam, malah ia meninggalkan pertemuan Saqifah dalam keadaan marah dan bergejolak, tidak ridha dengan baiat siapa pun dari Muhajirin. Dan Ali bin Abi Thalib tetap menahan diri dari membaiat Abu Bakar selama enam bulan sebagaimana dikatakan beberapa kitab sejarah. Jika kita mengatakan demikian juga, maka ini – sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm – adalah taklif (pembebanan) yang tidak dapat dilakukan, dan apa yang tidak mungkin, dan apa yang lebih besar dari kesulitan, dan Allah Ta’ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Sesungguhnya kami mengatakan dalam perkara ini tentang wajibnya baiat mayoritas dari ahli halli wal aqdi.
Kesimpulannya dalam hal ini: bahwa pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang berbeda ini berkaitan dengan jumlah yang dengannya imamah sah dari ahli halli wal aqdi adalah: pendapat yang mengatakan sahnya dengan mayoritas dari ahli halli wal aqdi, karena ahli halli wal aqdi betapapun memiliki sifat-sifat kesempurnaan, mereka adalah manusia yang tidak maksum (terpelihara dari dosa), maka kita tidak aman dari sisi hawa nafsu dan jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Maka mungkin saja minoritas cenderung kepada seseorang yang tidak berhak atas kepemimpinan lalu mereka membaiatnya. Agar kita aman dari itu atau setidaknya kita menduga keamanan dari itu, wajib disyaratkan mayoritas mutlak ketika membaiat pemimpin negara. Tidak sah memandang kepada negeri yang kepada mereka mayoritas ini termasuk. Baiat dari mayoritas mutlak dari ahli halli wal aqdi adalah sah meskipun tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari ibu kota, karena perkataan bahwa harus dalam sahnya akad imamah bahwa yang membaiatnya adalah ahli halli wal aqdi yang berada di negeri Imam adalah pernyataan sewenang-wenang tanpa bukti.
Sahnya Imamah melalui Jalur Mandat dari Imam yang Ada
Kemudian kita beralih sekarang kepada jalur kedua dari jalur-jalur yang dengannya kepemimpinan negara atau imamah kubra sah, yaitu: mandat (ahdun). Maka kami katakan: Mandat Imam kepada seseorang yang lain untuk menjadi Imam setelahnya adalah salah satu jalur yang para ulama anggap sebagai penyebab sahnya Imam. Maka kami katakan: Para fuqaha dan mutakallimun berbicara tentang mandat sebagai salah satu jalur sahnya imamah, yaitu bahwa Imam yang ada memberikan mandat imamah kepada seseorang yang ia pilih untuk menjadi Imam setelahnya.
Imam Al-Mawardi berkata: Adapun sahnya imamah dengan mandat dari yang sebelumnya adalah dengan apa yang atasnya ijmak terbentuk tentang kebolehannya, dan terjadi kesepakatan tentang keabsahannya karena dua hal yang kaum muslimin amalkan dan tidak mengingkarinya:
Pertama: Bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan mandat kepadanya kepada Umar radhiyallahu anhu, maka kaum muslimin menetapkan imamahnya setelahnya.
Kedua: Bahwa Umar radhiyallahu anhu memberikan mandat kepadanya kepada ahli syura, maka jamaah menerima kemasukan mereka ke dalamnya dan mereka adalah tokoh-tokoh masa itu karena keyakinan akan sahnya mandat kepadanya, dan para sahabat lainnya keluar darinya. Para ulama menetapkan bahwa Imam dengan memegang jabatannya hanya wajib atasnya untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan agama dan dunia mereka. Jika wajib atasnya memperhatikan selama hidupnya, maka memperhatikan kepentingan mereka setelah kematiannya mengikuti hal itu.
Sekarang kita berbicara tentang syarat-syarat sahnya kepemimpinan dengan mandat. Maka kami katakan: Imam bisa memberikan mandat kepada satu orang saja, atau memberikan mandat kepada lebih dari satu orang, dan kita akan berbicara tentang masing-masing dari dua kondisi ini.
Keadaan Pertama: Ketika wasiat kepemimpinan diberikan hanya kepada satu orang, maka agar wasiat tersebut sah, harus terpenuhi tiga syarat:
Pertama: Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang imam harus terpenuhi pada orang yang diberi wasiat, sejak saat dia diberi wasiat hingga saat dia menjabat khilafah setelah kematian imam yang memberikan wasiat. Oleh karena itu, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi pada dirinya saat diberi wasiat, misalnya dia masih kecil atau fasik pada waktu itu, maka wasiat tidak sah. Demikian pula jika dia masih kecil atau fasik saat diberi wasiat, namun sudah baligh dan adil saat kematian imam yang memberikan wasiat, maka dia tidak secara otomatis menjadi imam bagi kaum Muslim dengan wasiat tersebut. Tetapi harus ada bai’at dari ahlul halli wal aqdi (para pemangku kepentingan) kepadanya untuk khilafah.
Syarat Kedua: Orang yang diberi wasiat harus menerima wasiat tersebut. Jika orang yang diberi wasiat tidak menerima wasiat ini, maka ahlul halli wal aqdi wajib membaiat orang lain.
Syarat Ketiga: Imam yang memberikan wasiat harus melakukan wasiat ini saat kepemimpinan masih ada padanya. Jika dia memberikan wasiat kepemimpinan dalam keadaan munculnya halangan yang mengeluarkannya dari kepemimpinan, maka akad tidak sah.
Keadaan Kedua: Ketika wasiat diberikan kepada dua orang atau lebih, dan ini terbagi menjadi dua bentuk:
Bentuk Pertama: Imam menjadikan urusan kepemimpinan sebagai syura (musyawarah) di antara mereka tanpa mendahulukan salah seorang dari yang lain. Dalam keadaan ini, ahlul halli wal aqdi wajib memilih salah seorang dari mereka yang dijadikan syura untuk urusan kepemimpinan, atau semuanya menarik diri dari urusan kepemimpinan kecuali satu orang yang mereka serahkan hak mereka kepadanya. Para ulama telah mendalilkan hal ini dengan apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu setelah ditikam, dan dengan apa yang dilakukan para sahabat pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada beliau: “Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, tunjuklah penggantimu.” Maka dia berkata: “Aku tidak melihat ada orang yang lebih berhak atas urusan ini selain kelompok orang-orang ini yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka.” Lalu dia menyebutkan Ali, Utsman, Zubair, Thalhah, Sa’d, dan Abdurrahman. Ketika beliau wafat radhiyallahu anhu, berkumpullah kelompok yang dijadikan tempat urusan tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf berkata: “Serahkanlah urusan kalian kepada tiga orang di antara kalian.” Maka Zubair berkata: “Aku telah menyerahkan urusanku kepada Ali,” dan Thalhah berkata: “Aku telah menyerahkan urusanku kepada Utsman,” dan Sa’d berkata: “Aku telah menyerahkan urusanku kepada Abdurrahman.” Lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali dan Utsman: “Siapa di antara kalian berdua yang melepaskan diri dari urusan ini, maka kami akan menyerahkannya kepadanya, demi Allah dan Islam, sungguh dia akan memilih yang terbaik di antara kalian menurut pandangannya.” Maka keduanya terdiam. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata: “Apakah kalian menyerahkannya kepadaku? Demi Allah atas diriku, aku tidak akan mengabaikan yang terbaik di antara kalian.” Mereka berdua berkata: “Ya.” Maka dia memegang tangan Ali dan berkata kepadanya: “Engkau memiliki kerabat dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dahulu masuk Islam sebagaimana telah kamu ketahui, demi Allah atasmu, jika aku memberi amanah kepadamu maka berlaku adillah, dan jika aku memberi amanah kepada Utsman maka dengarlah dan taatlah.” Kemudian dia bersendirian dengan Utsman dan berkata kepadanya seperti itu juga. Kemudian pandangan Abdurrahman bin Auf menetap pada Utsman, lalu dia berkata kepadanya: “Angkatlah tanganmu wahai Utsman,” maka dia membaiatnya, dan Ali membaiat untuknya, lalu orang-orang berbondong-bondong membaiatnya.
Bentuk Kedua: Imam memberikan wasiat kepemimpinan kepada lebih dari satu orang dengan mengurutkan mereka, misalnya berkata: “Jika aku mati maka fulan adalah imam, jika dia mati maka imamnya adalah fulan, dan seterusnya.” Maka kepemimpinan pada waktu itu wajib untuk mereka yang disebutkan sesuai urutan yang telah dijelaskan. Hal ini didalilkan atau telah didalilkan dengan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan Mu’tah, kemudian berkata: “Jika dia gugur maka Ja’far bin Abi Thalib, jika dia gugur maka Abdullah bin Rawahah, jika dia gugur maka hendaknya kaum Muslim merestui seorang laki-laki.” Maka Zaid maju dan terbunuh, lalu Ja’far mengambil bendera dan maju lalu terbunuh, kemudian Abdullah bin Rawahah mengambil bendera dan maju lalu terbunuh, maka setelahnya kaum Muslim memilih Khalid bin Walid.
Sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis orang yang diberi wasiat dan hukum masing-masing dari mereka. Kita katakan: Orang yang diberi wasiat terbagi menjadi tiga bagian:
Bagian Pertama: Orang yang diberi wasiat adalah anak atau ayah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang bolehnya imam menyendiri dalam mengakadkan bai’at kepadanya menjadi tiga mazhab:
Mazhab Pertama: Tidak boleh imam menyendiri dalam mengakadkan bai’at untuk salah satu dari keduanya—yaitu tidak untuk anaknya dan tidak untuk ayahnya—tetapi harus ada persetujuan ahlul halli wal aqdi atas bai’at ini. Karena hal itu darinya merupakan tazkiyah (pujian) baginya yang berjalan sebagaimana kesaksian, dan penugasannya atas umat berjalan sebagaimana hukum, sedangkan dia tidak boleh bersaksi untuk ayahnya atau anaknya, dan tidak boleh memutuskan hukum untuk salah satu dari keduanya, karena dia secara alami condong kepada setiap satu dari keduanya.
Mazhab Kedua: Berpendapat bahwa imam boleh memberikan wasiat kepada ayah atau anak tanpa bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi, karena dia adalah hakim umat dan perintahnya berlaku atas mereka dan untuk mereka. Maka hukum jabatan lebih dominan daripada hukum nasab, dan tidak dijadikan tuduhan terhadapnya dalam hal itu sebagai jalan, serta menjadi dalam hal itu seperti wasiatnya kepada selain anaknya dan ayahnya.
Mazhab Ketiga: Berpendapat bahwa imam boleh menyendiri dalam mengakadkan bai’at untuk ayah. Adapun menyendiri dalam mengakadkannya untuk anak maka tidak boleh, karena secara alami dia lebih condong kepada anak daripada kecondongannya kepada ayah. Oleh karena itu, semua yang dia kumpulkan pada umumnya tersimpan untuk anaknya tanpa untuk ayahnya.
Bagian Kedua: Orang yang diberi wasiat bukan anak atau ayah, misalnya saudara, anak paman, atau orang asing. Di sini para fuqaha sepakat bahwa boleh imam menyendiri dalam mengakadkan bai’at kepadanya tanpa bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah disyaratkan tampaknya ridha dari ahlul halli wal aqdi hingga bai’at terlaksana atau tidak disyaratkan itu—ada perbedaan di antara para fuqaha.
Bagian Ketiga: Orang yang diberi wasiat sedang tidak hadir (ghaib). Pada waktu itu dilihat keadaannya. Jika kehidupannya tidak diketahui maka wasiat kepadanya tidak sah. Jika kehidupannya diketahui maka wasiat kepadanya sah dan bergantung pada kedatangannya. Jika imam yang memberikan wasiat meninggal sedangkan wali ahad masih tidak hadir, maka ahlul halli wal aqdi wajib memanggilnya. Jika dia datang maka dia menjabat kepemimpinan kaum Muslim. Jika dia tetap tidak hadir dan kaum Muslim dirugikan karena lamanya ketidakhadirannya, maka ahlul halli wal aqdi memilih orang lain sebagai wakil untuknya hingga dia hadir, dan hukum-hukumnya bagi mereka seperti hukum-hukum imam. Jika yang ghaib datang maka wakilnya turun.
Pendapat kami tentang waliyul ahad (putra mahkota): Terlihat dari menelusuri pembicaraan para fuqaha tentang wasiat bahwa jumhur mereka menganggap wasiat khalifah kepada satu orang cukup untuk terlaksananya kepemimpinan baginya, dan tidak memerlukan untuk sempurnanya bai’at kepada pembai’atan ahlul halli wal aqdi setelah wasiat imam. Bahkan dalam kemampuannya untuk memberikan wasiat kepada orang yang dilihatnya layak untuk kepemimpinan setelahnya tanpa bermusyawarah dalam hal itu dengan siapa pun. Semua yang ada padanya hanyalah dia harus berijtihad sedapat mungkin ijtihadnya dalam pemilihan ini.
Imam An-Nawawi berkata: Sesungguhnya khalifah jika ingin memberikan wasiat, wajib baginya berijtihad dalam mencari yang paling baik (maslahat). Jika tampak baginya satu orang, maka boleh dia menyendiri dalam mengakadkan bai’atnya tanpa kehadiran orang lain dan tidak bermusyawarah dengan siapa pun. Orang yang memperhatikan ini melihat bahwa para ulama dengan pendapat mereka ini sesungguhnya mendasarkan hal itu pada dua perkara:
Yang pertama: Bahwa imam yang diberi hak ini sesungguhnya adalah imam yang ideal yang pembai’atannya telah sempurna dengan cara syar’i yang benar, yang telah kami jelaskan syarat-syaratnya—pada bahasan sebelumnya—ketika membicarakan syarat-syarat kepemimpinan. Maka terpenuhinya syarat-syarat ini pada dirinya akan menjadikan kita mempercayai sepenuhnya apa yang dia lakukan dari urusan pemerintahan, dan kita yakin bahwa dia tidak menyimpang dalam apa yang dia lakukan berupa wasiat dari jalan yang wajib. Dia tidak memberikan wasiat kepada orang tertentu kecuali setelah melihatnya layak untuk memimpin umat, dan tidak terpengaruh dalam pekerjaan itu oleh kekerabatan, persahabatan, atau kecintaan. Bahkan dalam apa yang dia lakukan sesungguhnya dia bermaksud kemaslahatan umat dan wajah Allah Tabaraka wa Ta’ala.
Ibnu Khaldun berkata: Adapun jika tujuannya dengan wasiat adalah menjaga warisan bagi anak-anak, maka itu bukan termasuk tujuan-tujuan agama. Karena itu adalah urusan dari Allah yang Dia khususkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Seharusnya diperbaiki dalam hal itu niatnya semaksimal mungkin karena takut dari permainan dengan jabatan-jabatan agama. Maka pekerjaan ini yang mungkin menjadi penutup dari apa yang dia lakukan berupa perhatian terhadap urusan rakyat adalah termasuk yang akan dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya, dan akan berpengaruh pengaruh besar dalam kehidupan seluruh umat. Oleh karena itu Umar takut ketika mereka meminta darinya untuk menunjuk pengganti, lalu dia berkata: “Apakah aku menanggungnya dalam keadaan hidup dan mati?” Maka imam yang diberi wasiatnya pengaruh seperti ini dalam terlaksananya bai’at bagi yang menggantikannya, sesungguhnya adalah orang yang terkumpul padanya jaminan-jaminan kuat yang membentenginya pada umumnya prasangka dari penyimpangan dari jalan lurus. Maka kepercayaan kepada imam ini sempurna, dan ketakutannya kepada Allah pada umumnya prasangka terwujud. Jika imam ini diberi hak ini, maka dia akan pada umumnya mengekspresikan pendapat umat tentang orang yang dilihatnya layak untuk mengurus urusan setelahnya.
Adapun perkara kedua: Yang mendorong para ulama untuk berpendapat dengan terlaksananya bai’at semata-mata dengan wasiat imam kepada orang lain, adalah apa yang ditunjukkan oleh dua preseden sebelumnya yang dijadikan dalil oleh para ulama atas pertimbangan wasiat sebagai jalan dalam terlaksananya kepemimpinan, dan kami maksudkan keduanya: wasiat Abu Bakar kepada Umar, dan wasiat Umar kepada enam orang yang dia pilih. Maka sesungguhnya kedua preseden ini menunjukkan secara zhahir bahwa masing-masing dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma telah memberikan wasiat tanpa berkumpul bersama wasiatnya ridha umat yang terwakili dalam ahlul halli wal aqdi dari para senior sahabat.
Kami ingin menjelaskan bahwa masing-masing dari kedua perkara tidak sah untuk dijadikan landasan pendapat terlaksananya kepemimginan dengan wasiat dari imam sendiri. Hal itu karena:
Berkenaan dengan perkara pertama, sesungguhnya seberapa pun tinggi sifat-sifat kesempurnaan pada khalifah, maka sesungguhnya dia manusia yang tidak ma’shum (terjaga) dari kesalahan, tidak aman bahwa dia condong di saat lemah kepada kerabat atau teman lalu memberikan wasiat kepadanya urusan khilafah. Semua ini menunjukkan bahwa imam seberapa pun kami mensyaratkan padanya syarat-syarat, maka dia manusia, tidak ada yang mencegahnya dari menyimpang dari kewajiban dan condong mengikuti hawa nafsu, lalu memberikan wasiat kepada yang tidak berhak. Karena ‘ishmah (penjagaan dari dosa) tidak terbukti kecuali untuk para rasul—semoga shalawat Allah dan salam-Nya atas mereka.
Adapun berkenaan dengan perkara kedua yaitu: bahwa dua preseden wasiat Abu Bakar kepada Umar dan wasiat Umar kepada ahli syura menunjukkan secara zhahir bahwa wasiat dari khalifah cukup sendiri tanpa berkumpul bersamanya ridha umat yang terwakili dalam ahlul halli wal aqdi, maka sesungguhnya kami katakan berkenaan dengan preseden pertama—dan kami maksud dengannya wasiat Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma—sesungguhnya telah terbukti bahwa Abu Bakar memberi pilihan kepada orang-orang antara dua perkara: mereka memilih sendiri siapa yang akan menjabat khilafah setelahnya, atau mereka menyerahkan kepadanya urusan pemilihan ini. Maka mereka meminta darinya karena kepercayaan mereka kepadanya agar dia memilih untuk mereka.
Sesungguhnya Abu Bakar setelah merasakan dekatnya kepergiannya dari dunia memerintahkan agar orang-orang berkumpul untuknya. Maka mereka berkumpul, lalu dia berkata: “Wahai sekalian manusia, telah datang kepadaku dari qadha Allah apa yang kalian lihat, dan sesungguhnya pasti ada bagi kalian seorang laki-laki yang mengurus urusan kalian, shalat bersama kalian, memerangi musuh kalian, dan memerintah kalian. Jika kalian mau, kalian berkumpul lalu bermusyawarah kemudian kalian mengangkat atas kalian siapa yang kalian inginkan. Dan jika kalian mau, aku berijtihad untuk kalian pendapatku. Demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, aku tidak mengabaikan untuk diri kalian kebaikan.” Maka dia menangis dan orang-orang menangis, dan mereka berkata: “Wahai khalifah Rasulullah, engkau adalah yang terbaik dan paling berilmu di antara kami, maka pilihlah untuk kami.” Dia berkata: “Aku akan berijtihad untuk kalian dan memilih untuk kalian yang terbaik di antara kalian—insya Allah.”
Sungguh orang-orang ridha atas pekerjaan Abu Bakar dan menampakkan mendengar dan taat kepada orang yang diberi wasiat tanpa paksaan dari siapa pun. Maka sesungguhnya ketika pandangannya menetap pada Umar, dia mengawasi orang-orang sambil berkata: “Apakah kalian ridha dengan yang aku angkat sebagai pengganti atas kalian? Sesungguhnya aku demi Allah tidak mengabaikan dari usaha pendapat, dan tidak mengangkat yang memiliki kerabat, dan sesungguhnya aku telah mengangkat Umar bin Al-Khaththab sebagai pengganti, maka dengarlah kepadanya dan taatlah.” Maka mereka berkata: “Kami mendengar dan taat.”
Bahkan sebagian riwayat yang menggambarkan apa yang terjadi pada waktu itu menceritakan bahwa orang-orang sebelum mengetahui siapa yang diberi wasiat telah ridha dengannya karena kepercayaan sempurna mereka terhadap apa yang dilakukan Ash-Shiddiq, dan terdengar satu suara dari para senior ahlul halli wal aqdi yang menuntut khalifah agar tidak memberikan wasiat kecuali kepada Umar.
Memang benar telah terbukti bahwa sebagian sahabat karena mengetahui ketegasan Umar telah mendiskusikan dengan Abu Bakar dan menegurnya ketika sampai kepada mereka pemilihan Umar untuk mereka, tetapi mereka ridha setelah itu. Maka ini artinya: bahwa Abu Bakar—radhwanallahu Tabaraka wa Ta’ala alaih—tidak memberikan wasiat kepada Umar bin Al-Khaththab kecuali setelah bermusyawarah dengan orang-orang, mengambil pendapat ahlul halli wal aqdi, dan mereka menyetujui hal itu.
Adapun berkenaan dengan preseden kedua yaitu: wasiat Umar kepada enam anggota syura, maka sesungguhnya terbukti bahwa keenam orang ini telah mendapat ridha umat dan tidak ada selain mereka yang layak untuk kepemimpinan.
Dari semua ini kita sampai pada kesimpulan bahwa dua preseden yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang terbentuknya imamah melalui wasiat dari khalifah, pada kenyataannya menunjukkan bahwa imam berhak mencalonkan orang yang akan menggantikannya dalam kepemimpinan umat, dan dia dipercaya dalam kebaikan pilihannya selama telah terpenuhi padanya sifat-sifat yang diperlukan pada seorang imam, jauh dari tuduhan-tuduhan, bahkan jika dia mencalonkan anaknya atau ayahnya. Namun ini -sebagaimana telah kami katakan- hanyalah pencalonan yang tidak cukup sendiri untuk terbentuknya imamah bagi orang yang diwasiatkan kepadanya. Melainkan harus ada persetujuan dari ahlul halli wal aqdi (para tokoh yang berwenang mengangkat pemimpin) terhadap wasiat ini, dan bai’ah (sumpah setia) mereka kepada orang yang diwasiatkan kepadanya. Maka orang yang diwasiatkan kepadanya tidak terbentuk imamahnya kecuali setelah dibai’at oleh ahlul halli wal aqdi, dan mereka berhak untuk tidak membai’atnya dan memilih orang lain jika dia tidak layak menurut pandangan mereka untuk memegang jabatan ini. Inilah yang dipahami oleh para khalifah Bani Umayyah, karena mereka apabila mewasiatkan kepada kerabat mereka, tidak cukup dengan bai’ah yang berasal dari khalifah saja, tetapi bai’ah diambil dari rakyat untuk orang yang diwasiatkan kepadanya sementara khalifah yang berwasiat masih hidup, kemudian bai’ah diperbaharui setelah wafatnya. Seandainya mereka mengetahui bahwa wasiat dari imam saja sudah cukup untuk terbentuknya bai’ah, tentu mereka tidak perlu mengambil bai’ah dari rakyat. Dan kita mendapati Umar bin Abdul Aziz -yang merupakan seorang ahli fikih dan pengetahuannya tentang hukum-hukum syariat- setelah Sulaiman bin Abdul Malik mewasiatkan khalifah kepadanya, dan setelah surat wasiat dibacakan kepada rakyat setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, dia naik mimbar dan berkata: “Demi Allah, saya tidak diminta untuk urusan ini dan kalian memiliki pilihan.” Ini darinya merupakan dalil bahwa bai’ah tidak dianggap kecuali jika berasal dari ahlul halli wal aqdi yang mewakili keinginan umat. Seandainya wasiat dari khalifah sebelumnya cukup sendiri untuk terbentuknya imamah, tentu Umar tidak akan menemui rakyat untuk memberitahu mereka bahwa mereka memiliki pilihan penuh untuk membai’atnya sebagai imam atas mereka atau tidak membai’atnya.
Terbentuknya Imamah Melalui Jalan Kekerasan dan Kekuasaan
Kemudian kita berbicara sekarang tentang jalan ketiga dari jalan-jalan terbentuknya kepemimpinan, yaitu: terbentuknya melalui kekerasan dan kekuasaan, maka kami katakan:
Asal dalam terbentuknya kepemimpinan -sebagaimana telah kami katakan- adalah ahlul halli wal aqdi yang membentuknya bagi orang yang mereka pandang layak untuk memimpin kaum muslimin dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan padanya, dan itu terjadi setelah meneliti keadaan orang-orang yang diharapkan memiliki kesiapan lengkap untuk memikul beban kepemimpinan yang berat. Maka datangnya pemimpin adalah dengan kehendak dan pilihan umat yang diwakili oleh ahlul halli wal aqdi setelah tampak kelayakannya untuk jabatan ini. Ini dalam keadaan normal di mana tidak ada seseorang yang memaksakan kehendaknya kepada umat. Namun sering terjadi bahwa orang-orang yang memiliki sebab-sebab kekuatan dan kekuasaan melompat ke jabatan ini, dan memaksakan diri mereka kepada rakyat secara paksa dan keras sebagaimana yang terjadi dengan apa yang kita sebut di zaman kita dengan kudeta militer dan revolusi bersenjata. Maka apakah kepemimpinan dapat dianggap terbentuk bagi orang-orang yang mendapat kesempatan ini lalu mengambil pemerintahan dengan cara ini, ataukah itu tidak dianggap sebagai salah satu jalan yang dengannya terbentuk kepemimpinan?
Para ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua mazhab:
Mazhab pertama: Kaum Khawarij dan Mu’tazilah berpendapat bahwa imamah tidak terbentuk kecuali bagi orang yang datang melalui jalan bai’ah yang bebas dari paksaan atau kekerasan apapun.
Mazhab kedua yaitu mazhab mayoritas Ahlussunnah wal Jama’ah: Bahwa imam sah terbentuk bagi orang yang mengalahkan rakyat dan duduk dengan kekuatan di posisi pemerintahan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal ucapannya: “Barangsiapa mengalahkan mereka dengan pedang hingga menjadi khalifah dan disebut Amirul Mukminin, maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bermalam tanpa menganggapnya sebagai imam, baik dia berbuat baik maupun berbuat jahat.”
Jumhur ulama sepakat tentang terbentuknya kepemimpinan dengan cara ini, baik syarat-syarat imamah terpenuhi pada orang yang berkuasa ini atau tidak terpenuhi padanya, bahkan jika orang yang berkuasa itu fasik atau bodoh, imamahnya tetap terbentuk. Bahkan jika seorang wanita berkuasa atas imamah, maka terbentuk untuknya. Demikian pula jika seorang budak berkuasa atasnya. Itu karena para ulama memandang bahwa jika dikatakan tidak terbentuknya imamah orang yang berkuasa, hal itu akan menyebabkan terjadinya fitnah akibat benturan antara orang yang berkuasa dan para pembantunya, dengan imam yang ada dan orang-orang yang berpihak kepadanya. Dan akan menyebar kerusakan di antara rakyat karena tidak terbentuknya hukum-hukum yang dikeluarkan oleh orang yang berkuasa ini, karena mengharuskan tidak sahnya pernikahan orang yang dia nikahkan karena tidak ada wali baginya, dan bahwa orang yang memegang imamah kaum muslimin setelahnya harus menegakkan hudud lebih dahulu dan mengambil jizyah kedua. Bahkan para ulama menegaskan bahwa jika orang lain berkuasa atas orang yang berkuasa ini lalu menempati posisinya, maka yang pertama tersingkir dan yang kedua menjadi imam. Para ulama kemudian membandingkan antara dua jenis kejahatan lalu memilih yang paling ringan bagi umat, dan tidak berfatwa untuk menghadapkan umat kepada kejahatan yang paling besar. Namun harus dipahami bahwa ini adalah keadaan darurat, dan keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Ini adalah keadaan keterpaksaan dan keharusan seperti memakan bangkai dan daging babi, dan penerimaannya karena itu lebih baik daripada kekacauan yang melanda rakyat. Atas dasar ini, umat tidak boleh membiasakan diri dengan keberlangsungan keadaan ini, tetapi harus berupaya mengubah imamah yang kurang dengan imamah yang sempurna yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan pada imam yang benar dengan cara-cara yang tidak menimbulkan fitnah di antara rakyat. Dan harus selalu berusaha agar imam datang melalui jalan yang benar, yaitu jalan ahlul halli wal aqdi. Meskipun imamah orang yang berkuasa terbentuk mengingat keadaan darurat -sebagaimana telah kami katakan- namun mayoritas besar ulama muslimin tidak membolehkan kekerasan menjadi jalan terbentuknya imamah orang kafir atas kaum muslimin, karena keadaan kekerasan dapat ditolerir dalam beberapa syarat imamah seperti ilmu, atau keadilan, atau baligh, namun syarat Islam tidak dapat dijatuhkan sama sekali dari imam. Atas dasar ini, jika orang kafir berkuasa atas jabatan ini, maka tidak boleh secara syariat diam terhadap keadaan ini, dan wajib menggulingkan orang yang berkuasa ini dengan kekuatan senjata, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Surah An-Nisa ayat 141)
Dengan ini kita telah berbicara tentang jalan-jalan yang dengannya terbentuk imamah menurut mayoritas umat Islam. Tersisa kita berbicara tentang jalan terbentuknya menurut Syiah. Kaum Syiah Imamiyah dan Jarudiyah dari Zaidiyah berpendapat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menetapkan sebelum wafatnya orang yang akan menggantikannya dalam kepemimpinan umat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu wa ardhahu. Namun ada perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini tentang hakikat nash yang keluar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, apakah itu nash yang jelas, terang, tegas penunjukannya yang diketahui dengan pasti darinya imamah Ali bin Abi Thalib, ataukah nash yang tersembunyi yang tidak diketahui maksudnya dengan pasti? Ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini. Ini artinya: tidak ada jalan terbentuknya imamah menurut Imamiyah kecuali dengan nash. Maka mereka tidak mengakui jalan-jalan yang dengannya terbentuk imamah menurut jumhur fuqaha. Menurut mereka tidak ada jalan terbentuknya imamah kecuali dengan nash tentang imam.
Perlu kami ingatkan bahwa pembicaraan Syiah Imamiyah dalam masalah nash berkisar pada pembuktian dua klaim yang masing-masing berhubungan erat dengan yang lain. Yang pertama dari kedua klaim ini adalah: tidak ada jalan untuk terbentuknya imamah kecuali nash. Dan yang kedua adalah: bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berpulang ke Rafiq A’la (Allah) kecuali setelah menetapkan imamah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu wa ardhahu. Tampak bahwa klaim pertama yaitu: tidak ada jalan untuk terbentuknya imamah kecuali dengan nash, dimaksudkan oleh Syiah Imamiyah dengan pembuktiannya untuk melayani klaim kedua, yaitu: nash tentang imamah Ali radhiyallahu ‘anhu. Maksudnya, tujuan mereka yang diinginkan adalah sampai pada pembuktian imamah Ali bin Abi Thalib, dan bahwa dia lebih berhak atasnya daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ‘anhum.
Sekarang kita melihat kerancuan mereka berkenaan dengan bahwa nash adalah satu-satunya jalan untuk terbentuknya imamah. Kami katakan: Kaum Imamiyah berdalil bahwa tidak ada jalan untuk terbentuknya imamah kecuali nash dengan dalil-dalil yang banyak. Para ulama telah menjawab semuanya lalu membatalkannya. Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan, mereka berkata: Mereka berdalil dengannya bahwa nash adalah satu-satunya jalan untuk terbentuknya imamah. Mereka berkata: Jika boleh imam menjadi imam dengan pilihan, maka boleh pula seperti itu pada rasul dan nabi. Tetapi itu batil, maka terbukti tidak bolehnya imam dengan pilihan. Namun dijawab kepada mereka bahwa ini adalah qiyas (analogi) yang tidak benar, karena qiyas tidak sah kecuali dengan adanya ‘illah (sebab hukum) yang sama antara yang diqiyaskan dan yang dijadikan qiyas. Dan tidak ada ‘illah yang sama antara rasul dan imam sehingga qiyas sah. Kerasulan tidak terbukti dengan pilihan manusia karena rasul adalah hujjah (bukti) dalam apa yang dia sampaikan, maka harus ada jalan yang dengannya diketahui bahwa dia benar dalam kerasulannya. Dan pilihan bukan jalan yang darinya tampak kebenarannya dalam apa yang dia klaim. Tetapi keadaan pada imam berbeda dengan itu, karena dia pelaksana hukum-hukum dan urusan-urusan yang diketahui. Maka dia seperti qadhi (hakim), jika terpenuhi padanya syarat-syarat peradilan, maka sah pemilihannya untuk memegang jabatan peradilan. Ini artinya: kerancuan yang mereka sandari, bahwa mereka mengqiyaskan jabatan imamah pada jabatan kenabian, adalah kerancuan yang lemah. Oleh karena itu dalil mereka dalam hal ini tidak sah.
Kami cukupkan dengan kadar ini dari perkuliahan ini. Saya serahkan kalian kepada Allah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3 – Terbentuknya Imamah dengan Nash dan Tugas-tugas Imam
Terbentuknya Imamah Melalui Jalan Nash
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, Sayyidina Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita telah berbicara dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya tentang jalan-jalan terbentuknya imamah kubra (kepemimpinan tertinggi) menurut jumhur fuqaha, yang terwakili dalam pilihan ahlul halli wal aqdi, dan terwakili juga dalam wasiat dari imam sebelumnya, dan terwakili juga dalam sampai ke kekuasaan melalui jalan kekerasan dan kekuasaan atau yang disebut dengan bahasa zaman kudeta militer.
Kami katakan bahwa sebagian Syiah mengatakan bahwa imamah tidak terbentuk dengan pilihan, melainkan terbentuk dengan satu jalan saja yaitu nash tentang imam. Berdasarkan itu mereka mengatakan: Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menetapkan imamah orang yang datang setelahnya. Demikian pula setiap imam harus menetapkan orang yang datang setelahnya.
Kita akan melanjutkan sekarang pembicaraan tentang itu, maka kita berbicara tentang dalil-dalil Syiah dalam hal itu, dan kita akan melakukan bantahan terhadapnya. Kami katakan dengan taufiq Allah:
Syiah Imamiyah berusaha membuktikan bahwa tidak dapat dibayangkan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam meninggalkan kehidupan sebelum berwasiat tentang imam. Kemudian mereka menyusun atas dasar itu urusan lain lalu berkata: Selama Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat tentang imamah, maka orang yang diwasiatkan kepadanya adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka berdalil dengan itu dengan beberapa perkara:
Perkara pertama, mereka berkata: Sesungguhnya telah menjadi kebiasaan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau tidak keluar dari Madinah kecuali telah mengangkat pengganti yang mengurus urusan kaum muslimin di sana, dan kebiasaan beliau dalam hal itu tidak pernah tidak dilakukan walau satu kali pun. Jika ini kebiasaan beliau dalam hidup, maka pasti beliau telah memperhatikan itu berkenaan dengan waktu ketika beliau meninggalkan mereka menuju Rafiq A’la, karena pemeliharaan kepentingan kaum muslimin ketika ketidakhadiran beliau memungkinkan meskipun berat, namun setelah wafat beliau tidak memungkinkan.
Perkara kedua yang mereka jadikan dalil bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menetapkan imam: Bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku bagi kalian seperti orang tua bagi anaknya. Maka jika salah seorang kalian pergi ke tempat buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya.” Sebagaimana wajib atas orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya memelihara kepentingan mereka selama hidupnya, maka wajib atasnya juga memeliharanya setelah wafatnya agar mereka tidak tersia-sia. Dari yang diketahui bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam jika tidak menetapkan orang yang mengurus urusan mereka setelah beliau, mereka akan tersia-sia dalam agama dan dunia mereka. Maka wajib memastikan bahwa beliau telah menetapkan imam setelah beliau.
Perkara ketiga yang mereka jadikan dalil, mereka berkata: Dari yang diketahui bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam telah sangat penuh kasih sayang kepada umatnya, dan membimbing mereka kepada segala yang paling baik bahkan dalam perkara-perkara kecil, hingga beliau mengajarkan mereka dalam cara beristinja’ tiga puluh adab. Jika demikian keadaannya, dan jika penggantian Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bergantung padanya kepentingan-kepentingan terbesar dalam dunia dan agama, bukankah lebih utama dengan perhatian Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam terhadapnya dan tidak meninggalkan umatnya kecuali telah membimbing mereka kepada orang yang akan mengurus urusan mereka setelah beliau.
Adapun perkara keempat yang mereka jadikan dalil tentang nash Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang imam, mereka berkata: Sesungguhnya Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berpindah ke Rafiq A’la kecuali setelah sempurna agama sebagaimana firman Subhanahu wa Ta’ala: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku.” (Surah Al-Maidah ayat 3). Jika imamah adalah rukun agama yang paling besar, maka pasti ia juga telah sempurna sebelum wafat beliau. Dan tidak mungkin ia sempurna kecuali jika Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan orang yang akan menjadi imam setelah beliau.
Kemudian mereka berkata: Maka keempat perkara ini menunjukkan dengan jelas bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan dalam hidupnya orang tertentu yang mengurus urusan umat setelah beliau.
Inilah dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh Syiah Imamiyah bahwa imam tidak ditunjuk kecuali dengan nash tentang dirinya. Tetapi jumhur ulama telah membantah mereka dengan bantahan-bantahan berikut:
Pertama: Bahwa ada dari hadits-hadits dan atsar yang banyak yang tegas menyatakan bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menetapkan imamah seseorang. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta’ala ‘anhu, beliau berkata: “Dikatakan: Ya Rasulullah siapa yang engkau jadikan pemimpin? Maka beliau bersabda: Jika kalian menjadikan Abu Bakar pemimpin, kalian akan mendapatinya orang yang amanah, zuhud di dunia, dan berharap akhirat. Jika kalian menjadikan Umar pemimpin, kalian akan mendapatinya kuat, amanah, tidak takut dalam Allah celaan orang yang mencela. Jika kalian menjadikan Ali pemimpin -dan aku tidak melihat kalian melakukannya- kalian akan mendapatinya memberi petunjuk dan mendapat petunjuk, mengambil jalan yang lurus untuk kalian.” Dan ini adalah Ibnu Umar berkata: Aku hadir ketika ayahku terkena serangan, lalu mereka memuji dia dan berkata: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian mereka berkata kepadanya: Angkatlah pengganti. Maka dia berkata: Aku menanggung urusan kalian hidup dan mati? Aku berharap bagianku darinya seimbang, tidak untung tidak rugi. Jika aku mengangkat pengganti, maka sungguh telah mengangkat pengganti orang yang lebih baik dariku -maksudnya: Abu Bakar- dan jika aku meninggalkan kalian, maka sungguh telah meninggalkan kalian orang yang lebih baik dariku -maksudnya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Ketika Ali bin Abi Thalib terluka, orang-orang datang menjenguknya dan bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu jika kami kehilangan engkau, apakah kami membaiat Hasan?” Dia menjawab, “Aku tidak memerintahkan kalian dan tidak melarang kalian, kalian lebih tahu.” Kemudian seseorang dari kaum itu berkata kepadanya, “Tidakkah engkau membuat wasiat, wahai Amirul Mukminin?” Dia menjawab, “Tidak, tetapi aku membiarkan kalian sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka.”
Kedua: Di antara dalil atau bantahan yang dikemukakan oleh Jumhur (mayoritas ulama) kepada Syiah: Jumhur mengatakan: Sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu menunjukkan persetujuannya terhadap khilafah Abu Bakar, kemudian dia rela bersama orang-orang dengan wasiat yang diberikan Abu Bakar kepada Umar, bahkan dia menggantungkan keridhaannya pada syarat bahwa yang diberi wasiat itu adalah Umar bin Khattab. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar sakit parah, dia menampakkan diri kepada orang-orang dari balkon lalu berkata: “Wahai manusia, sesungguhnya aku telah membuat wasiat, apakah kalian ridha dengannya?” Orang-orang menjawab: “Kami ridha wahai Khalifah Rasulullah.” Maka berdirilah Ali dan berkata: “Kami tidak ridha kecuali jika itu adalah Umar.” Abu Bakar berkata: “Maka dia adalah Umar.”
Seandainya ada nash (teks) dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang imamah Ali, niscaya dia tidak akan ridha dengan khilafah Abu Bakar dan khilafah Umar, dan pasti dia akan menunjukkan nash ini, bangkit membelanya, dan mencegah orang lain untuk memimpin kaum muslimin. Bukankah kita telah melihat Abu Bakar berdiri di hadapan Anshar membela kekhususan Quraisy dalam imamah dengan berhujjah dengan hadits: “Para imam berasal dari Quraisy,” maka Anshar pun mentaatinya dan tunduk kepada khabar ahad (hadits dari satu perawi) dan meninggalkan apa yang mereka bela sebelumnya. Bagaimana kita dapat membayangkan bahwa ada nash yang jelas dan mutawatir dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang imamah Ali bin Abi Thalib, tetapi dia tidak membelanya, padahal dia berada di tengah kaum yang tunduk kepada khabar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meskipun itu khabar ahad? Adapun klaim Imamiyah bahwa keridaan Ali terhadap khilafah Abu Bakar dan Umar adalah karena taqiyah, itu tidak dapat dipercaya, karena keberanian Ali bin Abi Thalib sangat terkenal dan sikap-sikap kepahlawanannya dalam pertempuran yang dia ikuti bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam serta dalam perang Jamal dan Shiffin tidak dapat diperdebatkan. Bagaimana mungkin kita membayangkan, padahal keberaniannya seperti yang kita ketahui, bahwa dia akan pengecut dan diam tidak menyatakan haknya jika Rasul shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa dia adalah imam setelah beliau?
Ketiga: Di antara bantahan yang dikemukakan oleh Jumhur kepada Imamiyah Syiah: Mereka berkata bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sakit, Abbas meminta Ali agar mereka berdua pergi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan siapa yang beliau perintahkan untuk memegang khilafah, tetapi Ali tidak menyetujuinya. Kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari adalah: “Sesungguhnya Abbas memegang tangan Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang sakit—yaitu pada penyakit Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau wafat—seraya berkata kepadanya: ‘Mari kita pergi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kita tanyakan kepada siapa urusan ini, jika ada pada kita, kita akan mengetahui itu, dan jika ada pada selain kita, kita akan bicara dengannya agar dia berwasiat kepada kita.’ Maka Ali berkata: ‘Sesungguhnya demi Allah, jika kita memintanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu ditolak, maka orang-orang tidak akan memberikannya kepada kita setelah beliau, dan sesungguhnya demi Allah aku tidak akan memintanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.'”
Komentar terhadap hal itu: Seandainya ada nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang imamah Ali, tidak akan ada alasan untuk dialog yang terjadi antara Ali dan Abbas ini. Sikap mereka berdua menunjukkan bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan imamah Ali radhiyallahu anhu.
Keempat: Di antara bantahan yang dikemukakan oleh Jumhur kepada Imamiyah Syiah: Mereka berkata bahwa telah diriwayatkan secara mutawatir dari para sahabat bahwa mereka berkeyakinan bahwa tidak ada nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang imamah seseorang. Maka bidah nash yang jelas ini tidak diyakini oleh para sahabat dan tidak tersebar pada masa Tabiin. Seandainya ada nash yang jelas dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang imamah Ali bin Abi Thalib, maka keadaan para sahabat tidak lepas dari dua kemungkinan: Pertama, nash yang jelas ini sampai kepada mereka dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetapi mereka menyembunyikannya, atau kedua, khabar ini sama sekali tidak sampai kepada mereka dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun kemungkinan bahwa nash ini sampai kepada mereka dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetapi mereka menyembunyikannya adalah kemungkinan yang batil yang menunjukkan kebusukan pemikiran, penyimpangan akidah, hawa nafsu dan tujuan tertentu dalam perdebatan, karena kemungkinan ini pada hakikatnya adalah tuduhan kepada para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, padahal di antara mereka ada orang-orang yang terdahulu dari Muhajirin dan Anshar, ada sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga dan lainnya yang merupakan teladan tertinggi dalam petunjuk dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketenaran mereka dalam kesucian hati dan keikhlasan akidah dari kedengkian dan kebencian tidak mungkin menjadi objek perdebatan. Oleh karena itu, kita harus mengatakan: Sesungguhnya sama sekali tidak ada nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang imamah Ali bin Abi Thalib atau imamah orang lain. Seandainya nash seperti ini ada, mereka radhiyallahu anhum pasti akan menyampaikannya.
Dengan ini kita telah selesai membahas metode yang dikatakan oleh Imamiyah dari Syiah dalam penunjukan imamah atau terbentuknya imamah yaitu nash, dan kita telah melihat bantahan Jumhur kepada mereka. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang cara-cara terbentuknya imamah.
Kewajiban-Kewajiban Imam
Kewajiban dan hak-hak imam:
Imamah Kubra (Kepemimpinan Besar) atau khilafah adalah salah satu jabatan paling berbahaya dalam negara Islam dan dalam setiap negara. Dari sudut pandang Islam, sebagaimana telah kami sebutkan berkali-kali, ini dianggap sebagai amanah yang harus ditunaikan ketentuannya kepada yang berhak. Ia pada tingkat pertama adalah taklif (beban kewajiban) bukan kehormatan semata. Dari sinilah khalifah umat memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, dan sebagai imbalannya dia memiliki hak-hak atas umat. Inilah yang akan kami paparkan secara rinci berikut ini:
Pertama: Kewajiban atau fungsi khalifah:
Banyak fuqaha (ahli fikih) dan ulama muslim yang membahas masalah ini. Mungkin salah satu tulisan paling menonjol dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam hal ini. Al-Mawardi mengatakan dalam konteks ini: Yang menjadi kewajibannya—yaitu kewajiban imam—adalah sepuluh perkara umum:
- Pertama: Menjaga agama berdasarkan prinsip-prinsip yang telah mantap dan apa yang telah disepakati oleh salaf (generasi awal) umat. Jika muncul pelaku bidah atau orang yang menyimpang karena syubhat (keraguan), dia harus menjelaskan hujjah kepadanya, menunjukkan kebenaran, dan mengambil tindakan sesuai hak dan hudud yang wajib, agar agama terjaga dari kecacatan dan imamah terlindung dari kesalahan. Perkataan Al-Mawardi ini sangat indah dan sangat teliti serta akurat, karena berlaku untuk kewajiban imam dalam menjaga apa yang telah disepakati oleh salaf shalih dari agama dan memberikan kebebasan kepada umat di luar itu untuk berijtihad semampu mereka. Imam jika bukan termasuk ahli ijtihad harus berkonsultasi dengan ahli ilmu agar perkaranya berjalan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang selalu menjadi praktik salaf umat ini: dialog terus-menerus dan musyawarah antara penguasa dan ulama. Kadang-kadang ulama menaati penguasa dalam hal yang berbeda dengan ijtihad mereka jika tidak bertentangan dengan nash qath’i (pasti) dari Al-Quran dan Sunnah, atau tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh salaf. Oleh karena itu, ulama tidak menyetujui penguasa tentang pendapat penciptaan Al-Quran, dan cobaan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini terkenal dan mashur.
Penetapan tanggung jawab negara dalam sistem Islam dengan cara ini, meskipun berbeda dengan sistem parlementer yang menganggap bahwa kepala negara tidak memerintah dan karenanya tidak bertanggung jawab, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan wakilnya, melainkan tanggung jawab jatuh pada kabinet sebagai otoritas eksekutif di hadapan otoritas legislatif yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip konstitusi—namun sistem Islam menyerupai apa yang dikenal dalam sistem presidensial, yang menganggap kepala negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di hadapan rakyat atau di hadapan wakil mereka di parlemen, dan dialah yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya dan mereka bertanggung jawab penuh kepadanya.
- Fungsi kedua untuk kepala negara atau Imam Agung: Melaksanakan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan memutus perselisihan di antara orang-orang yang berselisih, agar pertolongan merata sehingga tidak ada orang zalim yang melampaui batas dan tidak ada orang yang terzalimi yang lemah. Kita telah melihat sebelumnya bahwa para imam pada awal Islam sendiri yang menangani peradilan, dan orang pertama yang menyerahkannya kepada hakim-hakim khusus adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimanapun juga, para hakim khalifah mewakilinya dalam memutus perkara di antara manusia dengan mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Meskipun dia memimpin mereka, itu tidak dianggap sebagai campur tangan yang tercela dari pihak kekuasaan eksekutif dalam pekerjaan peradilan, karena hakim dalam sistem Islam tunduk pada hukum syariat, dan khalifah juga tunduk padanya. Tentu saja dia tidak akan mengkritisi pekerjaan para hakim kecuali ketika mereka menyalahi hukumnya. Ini dianggap dalam sistem Islam sebagai penetapan kaidah yang mengatakan bahwa keadilan adalah fondasi kekuasaan dan kelangsungan negara.
- Ketiga dari fungsi yang dilakukan imam: Melindungi wilayah dan membela kehormatan agar manusia dapat beraktivitas dalam penghidupan dan bepergian dengan aman tanpa ada ancaman terhadap jiwa atau harta. Bidhah (wilayah) segala sesuatu adalah lingkupnya. Jadi dia melindungi lingkup umat atau apa yang sekarang dikenal sebagai keamanan umum melalui pengenaan kontrol negara terhadap para pemberontak sehingga tidak ada di negara apa yang mengancam keamanan dan stabilitas manusia.
- Fungsi keempat imam: Menegakkan hudud (hukuman) agar larangan-larangan Allah Taala terjaga dari pelanggaran, dan hak-hak hamba-hamba-Nya terlindungi dari kerusakan dan kehilangan. Ini tentu saja termasuk kewajiban paling khusus negara dalam konstitusi modern, yaitu negara yang melaksanakan hukum terhadap pelanggar yang keluar dari ketentuannya. Kepala negara dalam sistem Islam berada di puncak tanggung jawab dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya sebagaimana telah disebutkan.
- Fungsi kelima: Mengamankan perbatasan dengan persiapan yang mencegah dan kekuatan yang menangkis, sehingga musuh tidak berhasil masuk melalui celah untuk melanggar kehormatan atau menumpahkan darah muslim atau orang yang dilindungi. Di antara kewajiban terpenting negara modern adalah melindungi negara dari bahaya agresi luar, yaitu dengan menyiapkan pasukan kuat yang terlatih dan mampu memukul mundur agresi para agresor. Jelas dari penetapan berbagai kewajiban ini pada khalifah bahwa Islam memandangnya, sebagaimana telah kami sebutkan, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab langsung atas semua pekerjaan negara. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan pada khalifah syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan kecakapan dan kemampuannya memikul beban pemerintahan sebagaimana telah kami jelaskan secara rinci dalam syarat-syarat Imam Agung.
- Fungsi keenam: Berjihad melawan orang yang menentang Islam setelah dakwah hingga dia masuk Islam atau masuk dalam dzimmah (perlindungan), agar terlaksana hak Allah Taala dalam menampakkan agama-Nya atas semua agama. Diketahui bahwa jihad bisa bersifat ain (individual) dan kifayah (kolektif). Jihad wajib ain atas setiap mukallaf jika musuh menguasai sebagian negeri kaum muslimin dan mengusirnya tergantung pada itu, atau jika imam mengumumkan mobilisasi umum. Selain itu, jihad bersifat wajib kifayah jika sebagian orang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Jihad bisa dengan harta, dengan dakwah kepada Islam melalui dalil. Berdasarkan itu, wajib menaati imam dalam apa yang dia perintahkan dari sistem wajib militer dan pendidikan militer sebagai persiapan menghadapi musuh, sebagaimana firman Allah Taala: “Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Surat Al-Anfal: 60). Perintah di sini ditujukan kepada umat Islam termasuk imam karena dia adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk berjihad melawan para penentang setelah mendakwahi mereka.
- Fungsi ketujuh: Mengumpulkan fai’ (ghanimah) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat berdasarkan nash dan ijtihad tanpa ketakutan dan tanpa kekerasan. Ini dalam kenyataannya mengantarkan hak-hak kepada pemiliknya, karena pembuat syariat telah menjadikan harta-harta ini sebagai hak sebagian orang seperti fakir dan miskin terkait dengan sedekah, yang mungkin mereka tidak mampu menuntut hak mereka. Oleh karena itu, khalifah pertama memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat dalam apa yang dikenal sebagai perang riddah (kemurtadan) dalam sejarah Islam. Demikian juga khalifah wajib mengumpulkan harta fai’ dari kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak perlindungan) dan semacamnya. Orang pertama yang menetapkan kharaj adalah Umar bin Khattab pada masa khilafahnya setelah ditaklukkannya tanah Syam dan Irak.
- Fungsi kedelapan: Menetapkan pemberian dan apa yang menjadi hak dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan dan tanpa kikir, dan membayarkannya pada waktunya tanpa mendahului dan tanpa mengakhirkan. Ini mendekati apa yang dikenal di negara-negara modern sebagai penyusunan anggaran umum negara dan penyeimbangan antara pendapatan dan pengeluarannya yang mewujudkan keseimbangan anggaran tanpa berlebihan dan tanpa kikir, karena berlebihan dapat menyebabkan inflasi dan kemiskinan, sedangkan kikir dapat menyebabkan kezaliman terhadap rakyat. Semua itu diharamkan oleh syariat yang dia ditugaskan menjaganya.
- Fungsi kesembilan: Memilih orang-orang yang amanah dan mengangkat orang-orang yang nasehah dalam apa yang dia wakilkan kepada mereka dari pekerjaan dan dia amanahkan kepada mereka dari harta, agar pekerjaan-pekerjaan teratur dengan kecakapan dan harta-harta terjaga oleh orang-orang yang amanah. Penguasa dalam hal ini—yaitu ketika memilih para pegawainya—harus teliti dan memilih yang paling cakap, paling baik, paling nasehah, dan paling amanah, tanpa mempertimbangkan faktor nepotisme, kronisme, dan kadang-kadang suap. Diketahui bahwa kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, wajib mencurahkan upaya semaksimal mungkin ketika menyerahkan jabatan-jabatan umum kepada sebagian orang sehingga mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan kecakapan dan amanah, agar pekerjaan-pekerjaan sempurna dengan kecakapan dan harta-harta terjaga dengan amanah.
- Fungsi kesepuluh: Bahwa dia sendiri langsung mengawasi urusan-urusan dan memeriksa keadaan, untuk menjalankan politik umat dan menjaga agama, dan tidak mengandalkan pendelegasian karena sibuk dengan kesenangan atau ibadah, karena orang yang amanah bisa berkhianat dan orang yang nasehah bisa menipu. Allah Taala berfirman: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Surat Shad: ayat 26). Allah Subhanahu wa Taala tidak hanya menyebutkan pendelegasian tanpa pengawasan langsung, dan tidak meminta maaf dalam mengikuti (hawa nafsu) sampai-sampai menyifatkannya dengan kesesatan. Meskipun ini wajib atasnya karena hukum agama dan jabatan khilafah, namun ini termasuk hak politik bagi setiap pemimpin. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” Tetapi bukan berarti bahwa khalifah sama sekali tidak mendelegasikan. Tentu saja dia boleh meminta bantuan para gubernur, pembantu, dan menteri, dan mengkhususkan bagi setiap orang tanggung jawabnya. Namun dia harus mengawasi semua orang ini dan memeriksa keadaan mereka karena tanggung jawab utamanya sebagaimana telah kami sebutkan, dan karena orang yang amanah bisa berkhianat dan orang yang nasehah bisa menipu, sebagaimana kata Al-Mawardi.
Salah seorang peneliti telah menunjukkan bahwa hak khalifah dalam memeriksa keadaan rakyat terbagi menjadi dua bagian: karena ia bisa berkaitan dengan kelompok khusus atau dengan orang awam. Adapun kelompok khusus yaitu para pejabat tinggi dan hakim serta mereka yang memegang kekuasaan atas nama sultan, maka wajib bagi penguasa untuk memeriksa keadaan setiap orang dari mereka, apa yang berkaitan dengannya, apa yang keluar darinya, apa yang wajib atasnya, dan apa yang terjadi darinya. Jika ia mendapatinya berada di jalan yang benar, maka ia berterima kasih kepadanya dan memberikan anugerah kepadanya, dan jika ia mendapatinya sebaliknya, maka ia memberhentikannya. Adapun yang berkaitan dengan keadaan masyarakat umum atau rakyat di desa-desa, daerah pedalaman, tempat pertanian, dan peninggalan sejarah, maka tidak dapat tidak harus memeriksa keadaan mereka, mengetahui berita mereka, apa yang keluar dari mereka, memperhatikan urusan mereka, dan memperbaiki keadaan mereka.
Barangkali termasuk kewajiban penting yang harus diperhatikan dalam hal ini dan tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan sama sekali adalah kewajiban imam dalam bermusyawarah dalam setiap hal yang tidak ada nash dari Allah dan Rasul-Nya dan tidak terjadi ijma’ tentangnya, khususnya dalam urusan pemerintahan dan politik yang biasanya dibangun atas kemaslahatan; karena khalifah dalam sistem Islam bukanlah penguasa mutlak, melainkan ia terikat oleh nash-nash Alquran dan Sunah serta perjalanan umum para khalifah yang mendapat petunjuk. Perintah bermusyawarah telah disebutkan berkaitan dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka bagi yang di bawahnya lebih utama lagi; karena kemaslahatan umat itu banyak dan tidak dapat dibatasi, serta berbeda-beda sesuai perbedaan waktu dan tempat sehingga tidak dapat dibatasi, oleh karena itu musyawarah tidak dapat ditinggalkan.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kewajiban imam atau penguasa dalam negara Islam kembali kepada menegakkan agama dan menjaganya, mengatur urusan dunia dengan agama, mengelola urusan negara dengan keterampilan dan keahlian, menyebarkan ilmu dan pengetahuan dengan segala cara, menghormati dan menghargai para ulama. Betapa tersia-sianya negara-negara yang di dalamnya para ulama direndahkan dan para pendusta didahulukan. Imam wajib berupaya menyediakan kehidupan yang mulia bagi rakyatnya dengan menghiasi diri dengan apa yang ada pada para pendahulu umat di masa khilafah yang mendapat petunjuk, karena dalam sejarah mereka terdapat contoh-contoh yang harus diteladani.
Jika kita mencoba membandingkan antara apa yang ditetapkan dalam fikih politik Islam berkaitan dengan kewajiban khalifah dengan apa yang ditetapkan oleh konstitusi modern tentang fungsi negara, maka kita dapati bahwa fikih konstitusi modern menjadikan fungsi negara sebagai fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dapat kita pahami dari apa yang disebutkan para fuqaha Muslim tentang kewajiban imam atau khalifah, namun dengan memperhatikan sifat sistem Islam yang di dalamnya tidak ada pembuat hukum kecuali Allah Subhanahu Wataala, dan syariat di dalamnya adalah yang menentukan hak dan kewajiban baik bagi penguasa maupun rakyat. Namun demikian, tetap ada keistimewaan sistem Islam yang menjadikan fungsi imam sebagai kewajiban atasnya, ia dimintai pertanggungjawaban di hadapan umat atas pelaksanaannya sebelum menjadi kekuasaan baginya yang ia nikmati penggunaan dan praktiknya. Diketahui bahwa penguasa adalah wakil dari umat sehingga ditetapkan tanggung jawabnya atas kesalahannya di hadapan umat, dan kekuasaan tidak memberikannya keistimewaan apa pun yang mengangkatnya dari tingkat pertanggungjawaban. Para pemimpin dan yang dipimpin dalam kepatuhan mereka terhadap perhitungan dan hukuman adalah sama; karena dasar keutamaan antara manusia dalam timbangan syariat adalah takwa dan amal saleh. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dirinya sebagai preseden konstitusional pertama dalam hal ini. Ibnu Sa’d dalam kitab Thabaqat-nya meriwayatkan: Fadhal bin Abbas masuk menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika sakit lalu berkata: Wahai Fadhal, ikatkan sorban ini di kepalaku, maka ia mengikatkannya. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: Perlihatkan tanganmu, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan bangkit hingga masuk ke masjid, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: Sungguh telah dekat dariku hak-hak dari kalian yang ada di antara kalian, dan aku hanyalah manusia biasa. Siapa saja yang telah aku perlakukan buruk kehormatannya, maka ini kehormatanku agar ia mengambil balasannya. Siapa saja yang telah aku perlakukan buruk tubuhnya, maka ini tubuhku agar ia mengambil balasannya. Siapa saja yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku agar ia mengambil darinya. Ketahuilah bahwa orang yang paling dekat denganku adalah seseorang yang memiliki hal dari itu lalu mengambilnya atau menghalalkanku sehingga aku menemui Tuhanku dalam keadaan dihalalkan. Jika demikian keadaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka yang jauh di bawah itu seperti para khalifah, penguasa, dan imam lebih utama lagi?! Ini di samping tanggung jawab akhirat di hadapan Allah Taala jika penguasa berkhianat atas amanahnya dan menyia-nyiakan rakyatnya. Syariat telah memperingatkan dari hal itu sebagaimana firman Allah Taala: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Surat Al-Anfal: 27) Dan Allah Taala berfirman dalam surat Al-Qashash setelah menyebutkan kisah Firaun, keangkuhannya, dan kerusakannya di bumi: “Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Kami ikuti mereka dengan kutukan di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dihinakan.” (Surat Al-Qashash: 41-42) Asy-Syaukani berkata dalam tafsirnya: artinya Kami jadikan mereka pemimpin yang diikuti dan ditaati di kalangan orang-orang kafir, sehingga seolah-olah dengan kekafiran mereka yang terus-menerus dan berlanjut di dalamnya, mereka menyeru pengikut mereka ke neraka karena mereka mencontoh dan menempuh jalan mereka dengan meniru mereka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia mati pada hari ia mati sedangkan ia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang diberi Allah tanggung jawab atas urusan manusia sesuatu lalu ia bersembunyi dari kebutuhan mereka, maka Allah akan bersembunyi dari kebutuhannya pada hari kiamat.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar ketika ia meminta jabatan atau meminta diangkat, beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya itu adalah amanah dan sesungguhnya pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban atasnya di dalamnya.”
Demikianlah kewajiban imam atau fungsi imam.
Hak-Hak Imam
Kini kita berbicara tentang hak-hak imam. Ia memiliki kewajiban dan fungsi yang ia tunaikan, dan sebagai balasannya ia memiliki hak-hak terhadap rakyat atau yang diperintah. Di antara hak-hak terpenting ini adalah:
Pertama: Kewajiban Taat
Konsekuensi dari komitmen kekuasaan umum terhadap kaidah-kaidah keabsahan Islam adalah bahwa ia wajib ditaati dalam apa yang diperintahkan atau dilarangnya. Komitmen ini tidak terbatas pada mereka yang menyetujui pemilihan pemimpin kekuasaan ini berdasarkan bai’at umum, melainkan meluas kepada minoritas yang tidak menyetujui hal itu. Hal itu kembali kepada bahwa apa yang dipandang oleh mayoritas harus diikuti oleh minoritas berdasarkan nash-nash yang mewajibkan tidak keluar dari hukum jamaah, di samping bahwa kekuasaan umum dalam negara Islam tidak dapat menjamin hak-hak umat kecuali jika individu-individu umat mematuhi keputusan dan tindakannya yang dilakukan dalam lingkup hukum syariat Islam. Jika kekuasaan umum tidak dapat menjamin hak-hak Allah Azza wa Jalla dan hak-hak umat kecuali jika ia wajib ditaati, namun ketaatan ini tidak mutlak, melainkan pembuat hukum telah menentukan lingkupnya dengan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang mencegahnya keluar dari lingkup yang telah ditentukan baginya. Kita akan membahas pertama-tama sumber-sumber keabsahan kewajiban taat yang harus dipatuhi oleh umat, kemudian setelah itu akan menjelaskan lingkup kewajiban ini.
Sumber-Sumber Keabsahan Kewajiban Taat:
Ketaatan yang diwajibkan kepada kekuasaan umum telah diperkuat dalil-dalilnya dalam sumber-sumber keabsahan dengan nash-nash yang pasti, baik dalam Alquran maupun Sunah Nabi yang mulia atau ijma’. Dalam Alquran, Allah Azza wa Jalla berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Surat An-Nisa: dari ayat 59) Ayat ini menurut kesimpulan para mufassir dan fuqaha mewajibkan ketaatan kepada ulil amri dari kalangan imam dan penguasa; hal itu karena sahihnya khabar-khabar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan kepada mereka dalam hal yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi Allah dan kaum muslimin.
Dalil-dalil dalam Sunah sangat banyak dan semuanya mewajibkan ketaatan kepada ulil amri dari kaum muslimin. Di antara dalil-dalil ini adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Barangsiapa menaatiku maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku maka sungguh ia telah mendurhakai Allah, dan barangsiapa menaati pemimpinku maka sungguh ia telah menaatiku, dan barangsiapa mendurhakai pemimpinku maka sungguh ia telah mendurhakaiku.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mendengar dan taat atas seorang muslim dalam apa yang ia cintai dan benci, selama tidak diperintah kemaksiatan. Jika diperintah kemaksiatan maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Dengarlah dan taatlah meskipun diangkat atas kalian seorang budak Habasyah.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa membenci sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa keluar dari kekuasaan sejengkal lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.” Beliau juga bersabda: “Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci maka hendaklah ia bersabar atasnya, karena sesungguhnya barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejengkal lalu mati, kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyah.”
Di samping nash-nash yang pasti dalam Alquran dan Sunah Nabi yang mulia, telah terjadi ijma’ atas wajibnya menaati ulil amri dalam apa yang mereka perintahkan atau larang selama perintah dan larangan ini dalam batas-batas apa yang diperintahkan oleh pembuat hukum.
Kemudian kita berbicara tentang batasan ketaatan, kita katakan: Jika kekuasaan yang dipraktikkan oleh kekuasaan umum dalam batas-batas hukum syariat, maka kewajiban menaatinya dalam kondisi ini adalah pasti atas seluruh kaum muslimin, baik orang awam maupun khusus dari kalangan ulama dan fuqaha; karena praktik kekuasaan umum dalam kondisi ini bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, bahkan dalam kondisi-kondisi yang tidak jelas bagi yang diperintah manfaat dari praktik kekuasaan itu, maka perintah yang keluar darinya tetap wajib ditaati selama ia tidak menyalahi nash atau kaidah umum dari nash-nash dan kaidah-kaidah syariat. Hal itu karena kewajiban ketaatan sudah tetap dengan dalil-dalil yang pasti kesahihannya, dan keraguan yang ada pada yang diperintah tentang manfaatnya atau tidak tidaklah berdiri sebagai dalil untuk menentang nash-nash ini. Dalam lingkup hukum-hukum ijtihad yang berbeda pendapat di sekitarnya, maka hukum penguasa di dalamnya wajib ditaati, bukan hanya dari orang awam tetapi juga dari para fuqaha, baik mereka yang berpendapat seperti pendapat penguasa maupun mereka yang tidak menyetujui apa yang dilihat penguasa pada awalnya. Orang yang berbeda pendapat dalam kondisi ini dilarang untuk berfatwa yang bertentangan dengan apa yang disimpulkan penguasa, karena hukumnya dalam masalah-masalah yang tidak disepakati oleh pendapat para ulama tidak ditolak dan tidak dibatalkan sehingga tidak diperbolehkan fatwa yang bertentangan. Hal itu karena fatwa yang bertentangan dalam kondisi ini menyebabkan kekacauan hukum dan kontradiksinya serta menggoyahkan kepercayaan terhadap hukum penguasa, dan ini bertentangan dengan kemaslahatan yang untuk itu hukum ditetapkan.
Dan apabila ketaatan itu wajib dan dijamin oleh pembuat syariat dengan nash-nash yang pasti atas seluruh umat, maka tujuan mendasar dari kewajiban ini adalah agar kekuasaan umum dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat dari hak-hak yang wajib dijamin dan upacara-upacara yang wajib dijaga, maka pelaksanaan kekuasaan terikat erat dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat dan yang dikehendaki dari mewajibkan ketaatan atas seluruh umat, sehingga apabila kekuasaan umum keluar dari ruang lingkup yang telah digambarkan oleh pembuat syariat maka ketaatan pada saat itu tidak lagi wajib, dan dengan ungkapan yang lebih tepat ketaatan itu tidak diperbolehkan, dan inilah yang disimpulkan oleh para mufassir dari penafsiran mereka terhadap firman Allah Azza wa Jalla: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian” (Surah An-Nisa ayat 59), di mana mereka menetapkan bahwa ketaatan yang diwajibkan kepada para penguasa bukanlah ketaatan asli yang wajib sejak awal, tetapi merupakan ketaatan turunan yang terikat pada dasarnya dengan ketaatan para penguasa kepada Allah dan kepada Rasul, dan hal ini dipahami dari pengulangan perintah dalam kewajiban taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan tidak diulang ketika memerintahkan ketaatan kepada ulil amri, dan ini menjelaskan bahwa ketaatan ini pada dasarnya diambil dari ketaatan penguasa kepada Allah dan kepada Rasul, dengan mematuhi perintah-perintah mereka dan menahan diri dari larangan-larangan mereka serta bekerja untuk mewujudkan dan menjamin tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembuat syariat, dan sebagai kaidah yang tegas yang tidak boleh ragu untuk menerimanya maka itu berarti bahwa ketaatan tidak wajib kecuali dalam keadaan kekuasaan-kekuasaan umum berkomitmen pada kaidah-kaidah legalitas dalam fikih Islam, dan tidak wajib di luar itu, bahkan yang wajib atas kaum muslimin dalam keadaan ini adalah menolak dan mengingkari, dan ini terwujud dalam keadaan apabila perintah yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum terjadi bertentangan dengan dalil yang pasti dari nash atau ijmak atau qiyas yang jelas, atau bertentangan dengan dalil zhanni dan penguasa bukan mujtahid dan tidak melakukan musyawarah dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkannya dengan melanggar kewajiban musyawarah, dan apa yang dipandang oleh mayoritas ulama umat dan para fukaha dalam masalah ini, sebagaimana pelanggaran juga terwujud apabila keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum bertentangan dengan nash-nash legalitas yang tidak tersembunyi bagi siapa pun dari orang awam atau orang khusus, dan dalam keadaan ini ketaatan tidak wajib dari semua orang karena bahaya yang ditimbulkannya, sebagaimana pelanggaran terwujud dalam semua keadaan di mana perintah yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum menargetkan kepentingan selain kepentingan umum kaum muslimin sebagaimana halnya dalam keadaan penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan, atau melampaui batas-batas yang telah digambarkan oleh pembuat syariat, maka ketaatan tidak wajib pada saat itu, ketaatan tidak wajib apabila penguasa muslim itu zalim dan sewenang-wenang dalam hukum-hukumnya dan menyalahgunakan hak-hak rakyat, dan inilah yang ditetapkan oleh sebagian ulama dengan menetapkan bahwa ketaatan tidak wajib kecuali kepada penguasa yang adil; karena penguasa yang zalim, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari padanya, dan diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata: “Hak penguasa adalah menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah dan menunaikan amanah, apabila ia melakukan itu maka hak rakyat adalah mendengar dan taat”.
Dan apabila ketaatan dibatasi dengan batasan-batasan dan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam, namun dalam beberapa keadaan ketaatan ini mungkin mutlak dan kaum muslimin tidak memiliki pilihan selain menerimanya, bahkan dengan keluarnya dari kaidah umum yang ditetapkan oleh pembuat syariat untuk keadaan-keadaan biasa seperti apabila keadaan darurat menghendaki demikian, sebagaimana ketaatan mungkin wajib dalam keadaan kondisi darurat hanya terbatas pada yang diperintah saja, yaitu dalam semua keadaan di mana ketidaktaatan mengakibatkan kebinasaan atau dikhawatirkan perpecahan kesatuan umat, maka keadaan darurat dalam keadaan ini atau itu adalah yang mewajibkan ketaatan terhadap perintah-perintah dan keputusan-keputusan kekuasaan umum, dan kriteria ketaatan dalam keadaan kedua adalah memilih yang lebih ringan dan lebih mudah dari dua bahaya, apabila bahaya yang diakibatkan dari ketidaktaatan melebihi bahaya yang ditimbulkan dari mematuhi perintah-perintah kekuasaan umum maka tidak ada jalan lain selain menerima perintah-perintah ini, dan wajib taat untuk menolak bahaya yang lebih besar, dan sebaliknya apabila bahaya yang diakibatkan dari ketaatan melebihi bahaya yang ditimbulkan dari melanggar keputusan-keputusan ini maka tidak ada jalan lain selain tidak taat; untuk menghindari bahaya yang diakibatkan dari mematuhi perintah-perintah yang melanggar hukum seperti apabila hal itu menyebabkan kehancuran dan kebinasaan umat, dan dengan demikian maka batas hukum Islam yang ditetapkan untuk keadaan-keadaan biasa tidak wajib dalam semua keadaan di mana ketidaktaatan mengakibatkan bahaya besar pada umat, adapun dalam keadaan lapang dan pilihan maka tidak ada jalan lain dari menerapkan kaidah umum yaitu keharusan ketaatan dalam batas-batas kaidah-kaidah biasa dengan sumber-sumber legalitas dalam fikih Islam.
Dan kami mengakhiri dengan kadar ini dari kuliah ini, saya menitipkan kalian kepada Allah dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah atas kalian.
4 – Lanjutan Hak-Hak Imam, dan Berakhirnya Kekuasaannya
Lanjutan Hak-Hak Imam
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan, amma ba’du:
Kita telah memulai pembahasan dalam kuliah sebelumnya tentang hak-hak penguasa terhadap umat, dan kita telah mengatakan bahwa hak pertama terwujud dalam ketaatan kepadanya dalam hal yang bukan kemaksiatan, dan sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang hak kedua yaitu kewajiban memberikan pertolongan kepadanya, maka kami katakan:
Di samping hak ketaatan, umat Islam berkewajiban memberikan pertolongan kepada kekuasaan umum dan berdiri di belakangnya terhadap setiap pemberontakan yang dimaksudkan untuk memecah belah kesatuan umat Islam, apabila kewajiban ketaatan pada dasarnya menargetkan agar wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada kekuasaan umum di negara Islam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya -maka kewajiban memberikan pertolongan menargetkan menjaga kesatuan jamaah dan memberantas setiap upaya yang menargetkan merusak sistem pemerintahan yang ada, baik upaya ini dari luar yaitu dalam keadaan-keadaan di mana musuh menargetkan merusak eksistensi negara-negara Islam, maupun dari dalam yaitu dengan adanya pemberontak atau pemberontak yang mencoba merebut kendali urusan negara atau memisahkan diri dengan suatu wilayah dari wilayah-wilayah, maka dalam semua keadaan ini para fuqaha menetapkan bahwa umat Islam berkewajiban memberikan pertolongan kepada kekuasaan umum dan memberikan bantuan kepadanya.
Sebagian fuqaha mencampuradukkan antara kewajiban memberikan pertolongan dan kewajiban ketaatan dan mereka berpendapat bahwa kewajiban ketaatan termasuk dalam kewajiban memberikan pertolongan, dan pendapat ini tidak kami terima karena perbedaan keduanya dari dua sisi:
Sisi pertama: bahwa kewajiban ketaatan mungkin tidak mengakibatkan dalam kebanyakan keadaan yang mewajibkan ketaatan kecuali sekadar kewajiban negatif yang ada pada pundak yang diperintah, dan terwujud dalam keharusan komitmen jamaah Islam terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan kekuasaan umum dan tidak melanggarnya, sementara kewajiban kedua -yaitu pertolongan- adalah dalam semua keadaan membebankan pada jamaah Islam kewajiban positif yang jelas, yang mengharuskan mereka untuk memberikan usaha mereka untuk menolong kekuasaan umum dan membela sistem yang ada terhadap setiap serangan atau gangguan dari dalam atau luar terhadap kekuasaan yang sah di negara Islam.
Sisi kedua: bahwa kewajiban memberikan pertolongan menargetkan di samping pembelaan terhadap sistem pemerintahan yang ada, juga menargetkan menjaga jamaah Islam dari perpecahan dan kehancuran, yaitu dengan membelanya terhadap setiap upaya yang menargetkan memecah belah kesatuan umat Islam, dan inilah yang terlihat jelas dari perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika salah seorang sahabat bertanya kepadanya: apa yang harus dilakukan dalam keadaan fitnah? Maka beliau bersabda: “Berpeganglah pada jamaah kaum muslimin dan imam mereka”.
Ruang Lingkup Kewajiban Memberikan Pertolongan:
Kewajiban memberikan pertolongan seperti kewajiban ketaatan bukanlah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi umat Islam dalam semua keadaan, tetapi berbeda tergantung apakah bahaya yang mengancam kekuasaan umum di negara Islam adalah bahaya eksternal atau internal, sebagaimana berbeda tergantung apakah kekuasaan ini mendapatkan persetujuan umat dan kerelaan pilihan mereka dan berkomitmen pada hukum-hukum syariat Islam ataukah merampas kekuasaan dan tidak berkomitmen pada apa yang ditetapkan pembuat syariat dari kaidah-kaidah dan hukum-hukum.
Apabila bahaya itu eksternal maka kewajiban memberikan pertolongan adalah kewajiban mutlak, tidak boleh bagi seorang muslim pun untuk menghindar darinya atau lalai dalam menunaikannya, baik kekuasaan umum di negara Islam itu adil atau zalim; karena bahaya di sini berkaitan dengan eksistensi masyarakat Islam itu sendiri, dan dimaksudkan untuk merusak kemerdekaannya dan jatuhnya ke tangan musuh; oleh karena itu meskipun kezaliman dan kesewenang-wenangan terwujud dalam kekuasaan umum maka tidak boleh seorang pun meninggalkan pemberian pertolongan kepadanya, karena yang dimaksud dengan pertolongan dalam keadaan ini bukanlah kekuasaan umum itu sendiri, tetapi yang dimaksud adalah menjaga negara Islam dari jatuh ke tangan musuh; dan karena mengusir musuh adalah kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama berdasarkan kewajiban jihad dan ini menemukan dasar legalitasnya dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: “Jihad wajib atas kalian bersama setiap penguasa, baik yang baik maupun yang jahat, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar”.
Adapun jika serangan itu internal, yaitu yang terwujud dengan pemberontakan kelompok dan keluar mereka terhadap kekuasaan -maka urusan berbeda tergantung apakah kekuasaan merampas kekuasaan ataukah menerima kekuasaan melalui umat dengan berkomitmen pada hukum-hukum syariat, dalam keadaan perampasan kekuasaan melalui pemaksaan dan kekerasan maka tidak wajib kaum muslimin memberikan kewajiban pertolongan kepadanya, bahkan sebaliknya, apabila ada pemberontak yang menargetkan menggulingkannya untuk mengembalikannya ke hukum Islam maka wajib kaum muslimin membantunya; karena tujuan dalam keadaan ini adalah terwujudnya kekuasaan umum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum umum Islam, adapun jika pemberontak ini tidak menargetkan kembali ke hukum tetapi juga ingin merebut kekuasaan -maka pertolongan tidak wajib; karena masing-masing dari keduanya berebut dengan yang lain dalam hal yang tidak halal baginya, dan tidak wajib membantu atau menolong salah satu dari keduanya, adapun jika kekuasaan umum menerima kekuasaan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum syariat dan berkomitmen pada hukum-hukum syariat Islam -maka wajib atas kaum muslimin menolongnya terhadap setiap pemberontakan yang terjadi terhadap kekuasaan ini, sebagaimana wajib menumpas setiap upaya yang menargetkan menyerang sistem pemerintahan yang ada, dan jika sebab keluar terhadapnya adalah terjadinya sebagian kezaliman dari padanya maka wajib agar mendapat pertolongan kaum muslimin bahwa ia segera berhenti dari kezaliman yang terjadi; karena keluar karena kezaliman tidak dianggap sebagai pemberontakan dan pembangkangan terhadap kekuasaan.
Ketiga dari Hak-Hak Imam:
Dan di antara hak-hak imam juga adalah ia mendapat bagian dari harta kaum muslimin yang cukup untuknya dan untuk keluarganya, artinya: ditetapkan gaji untuknya yang cukup untuknya dan untuk keluarganya tanpa berlebihan dan tanpa kikir; karena ia telah sibuk dengan kepentingan-kepentingan umum kaum muslimin siang dan malam, dan tidak lagi memiliki waktu untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan dirinya, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dalam (Ath-Thabaqat) bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, di pagi hari ia pergi ke pasar dengan membawa kain-kain di lehernya untuk berdagang, lalu ia bertemu dengan Umar bin Al-Khaththab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhuma maka keduanya bertanya kepadanya: kemana Anda akan pergi wahai khalifah Rasulullah? Ia berkata: ke pasar, mereka berkata: untuk apa sedangkan Anda telah memimpin urusan kaum muslimin?! Ia berkata: dari mana saya memberi makan keluarga saya? Mereka berkata kepadanya: marilah sampai kami tetapkan sesuatu untukmu, maka ia pergi bersama mereka lalu mereka menetapkan untuknya setiap hari setengah kambing, dan ketika Abu Bakar merasa bahwa apa yang dikhususkan untuknya tidak mencukupi ia meminta kepada kaum muslimin agar menambahkannya maka mereka menambahkannya dengan lima ratus dirham.
Ketika Umar bin Khaththab mengambil alih kepemimpinan kaum muslimin setelah Abu Bakar, dia menetap beberapa waktu lamanya tidak mengambil sesuatu pun dari harta kaum muslimin hingga dia mengalami kesulitan (yaitu: kesempitan) dalam hal itu. Lalu dia meminta musyawarah para sahabat tentang apa yang layak untuknya dari harta ini setelah dia disibukkan dengan urusan kaum muslimin dari urusan dirinya sendiri. Maka Utsman berkata: Makan dan berilah makan. Dan Ali berkata: Makan pagi dan makan malam. Maka Umar mengambil pendapat itu, dan dia membelanjakan setiap hari dua dirham untuk dirinya dan keluarganya. Dia membelanjakan dalam ibadah hajinya seratus delapan puluh dirham, lalu berkata: Sungguh kita telah berlebihan dalam menggunakan harta ini.
Dalam hal ini kita melihat bahwa khalifah berhak mengambil gaji dari Baitul Mal meskipun dia adalah orang yang berkecukupan, karena sesungguhnya dia telah menahan dirinya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan menjadi sibuk dengan urusan mereka dari urusan pribadinya. Dia dalam hal ini seperti pegawai lain dalam negara meskipun dia berkecukupan. Adapun penolakan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz untuk mengambil dari Baitul Mal, hal itu tidak menunjukkan larangan, karena maknanya adalah bahwa mereka melepaskan hak-hak mereka. Seandainya keduanya mengambil dari Baitul Mal, tidak ada dosa atas mereka, karena Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma telah mengambil bagian mereka dari Baitul Mal kaum muslimin, dan keduanya termasuk orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin, karena tidak ada dosa bagi seseorang mengambil imbalan atas pekerjaannya, dan khalifah sebagaimana telah kita sebutkan, disibukkan dengan urusan kaum muslimin dari urusan pribadinya.
Keempat dari hak-hak imam:
Dari hak-hak imam atas umat adalah umat menasihatinya, memerintahkannya dengan kebaikan, melarangnya dari kemungkaran, dan mendoakan kebaikan untuknya. Sesungguhnya agama adalah nasihat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Agama adalah nasihat,” beliau mengatakannya tiga kali. Kami bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam mereka.” Dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik umat karena mereka memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena) kalian menyuruh (berbuat) makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah” (Surah Ali Imran: ayat 110). Yang patut disebutkan dalam hal ini bahwa kewajiban-kewajiban imam dan hak-hak yang disebutkan oleh para ulama muslim mendekati apa yang disebutkan oleh ahli hukum di bawah nama “fungsi-fungsi negara”. Khalifah atau imam pada masa Al-Mawardi dan lainnya yang menulis tentang hukum-hukum kekuasaan, imam adalah negara atau hampir demikian. Adapun sekarang, fungsi-fungsi negara memiliki fleksibilitas sehingga dipengaruhi oleh waktu, tempat, jenis-jenis sistem, filosofi pemerintahan, dan kondisi manusia.
Dengan ini kita telah selesai membahas tentang kewajiban-kewajiban imam atau fungsi-fungsi imam dan tentang hak-hak imam.
Berakhirnya Masa Jabatan Imam
Pemecatan imam atau kepala negara dari jabatannya:
Kita katakan: Keberadaan imam atau kepala negara dalam jabatannya tergantung pada kelanjutan kelayakannya untuk memimpin negara muslim. Kelayakan ini terpenuhi padanya selama syarat-syarat yang diperlukan bagi orang yang layak menduduki jabatan ini ada padanya. Hilangnya kelayakan ini menjadi sebab untuk meninggalkan jabatan kepemimpinan hingga diisi oleh orang yang layak untuk itu. Kita akan membahas dalam hal ini dua permasalahan yaitu: pemecatan imam oleh dirinya sendiri, dan pemberhentiannya bukan melalui dirinya sendiri.
Permasalahan pertama: Pemecatan kepala negara melalui dirinya sendiri:
Kita katakan: Para fuqaha (ahli fikih) muslim telah menjelaskan bahwa pemecatan imam oleh dirinya sendiri ada yang karena ketidakmampuan atau kelemahan seperti sakit dan pikun, ada yang bukan karena ketidakmampuan atau kelemahan tetapi karena dia lebih memilih meninggalkan jabatan ini untuk meringankan beban baginya di dunia dan akhirat, dan ada yang bukan karena ini dan bukan karena itu. Setiap keadaan ini memiliki hukum khusus.
Adapun keadaan pertama yaitu: Imam memecat dirinya sendiri karena ketidakmampuannya melakukan apa yang dibebankan kepadanya dari urusan manusia karena pikun, sakit, atau sejenisnya – maka dia diberhentikan jika dia memberhentikan dirinya karena itu, karena ketidakmampuan jika terbukti maka wajib hilang kepemimpinannya karena tidak tercapainya tujuan darinya. Bahkan wajib atasnya jika dia merasakan hal itu untuk memberhentikan dirinya sendiri karena menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Baik ketidakmampuan ini tampak bagi manusia maupun dia merasakannya dari dirinya sendiri, maka itu menjadi sebab untuk meninggalkan jabatan ini.
Adapun keadaan kedua yaitu: Dia memberhentikan dirinya bukan karena ketidakmampuan atau kelemahan tetapi lebih memilih meninggalkan untuk meringankan beban baginya di dunia agar tidak disibukkan dengan tugas-tugas besar yang dibebankan kepada pemimpin kaum muslimin, atau untuk meringankan beban baginya di akhirat agar tidak luas perhitungannya – maka para fuqaha memiliki dua pendapat dalam hal itu: Pertama: Dia diberhentikan dengan hal itu, karena sebagaimana tidak wajib baginya memenuhi ajakan untuk berbaiat, tidak wajib baginya pula tetap dalam jabatannya. Kedua: Tidak diberhentikan, karena Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu meminta kepada kaum muslimin agar mereka memberhentikannya dari jabatan khalifah. Seandainya pemberhentian dirinya sendiri berpengaruh, niscaya dia tidak akan meminta pemberhentian dari mereka.
Adapun keadaan ketiga yaitu: Imam memberhentikan dirinya sendiri tanpa uzur dari ketidakmampuannya melakukan urusan kaum muslimin, atau lebih memilih meninggalkan jabatan ini untuk meringankan di dunia dan akhirat – maka para fuqaha berbeda pendapat menjadi tiga pendapat:
Pendapat pertama: Tidak diberhentikan ketika itu. Dalil pendapat ini adalah bahwa hak dalam hal itu adalah milik kaum muslimin bukan miliknya.
Pendapat kedua: Dia diberhentikan, karena memaksanya tetap mungkin mendatangkan bahaya baginya di akhirat dan dunianya.
Pendapat ketiga: Dilihat, jika imam tidak menunjuk orang lain atau menunjuk orang yang lebih rendah darinya maka tidak diberhentikan sama sekali. Dan jika menunjuk orang yang lebih utama darinya atau orang yang setara dengannya maka ada dua pendapat: Pendapat yang mengatakan diberhentikan, dan pendapat yang mengatakan tidak diberhentikan.
Permasalahan kedua: Pemberhentian kepala negara bukan melalui dirinya sendiri:
Kaum muslimin bersepakat bahwa kepala negara jika tidak terjadi hal yang merusak keadilannya atau berubah keadaannya maka tidak boleh bagi umat memberhentikannya. Sebagian ulama berkata: Tidak boleh memakzulkan imam tanpa ada kejadian atau perubahan keadaan. Ini adalah kesepakatan, karena kaum muslimin pada masa fitnah yang terjadi pada masa Khalifah ketiga Utsman Radhiyallahu Anhu telah berbeda pendapat menjadi dua pendapat, tidak ada yang ketiga. Sebagian dari mereka berkata: Sesungguhnya dia melakukan hal-hal yang merusak kewajiban jabatannya maka wajib memberhentikannya. Dan sebagian dari mereka berkata: Sesungguhnya dia tidak melakukan hal yang merusak kewajibannya maka tidak boleh memberhentikannya. Maka apa yang keluar dari dua pendapat ini adalah batil berdasarkan kesepakatan. Juga karena imam tidak dibebani jabatan ini kecuali setelah terpenuhi padanya syarat-syarat khusus. Jika dia kehilangan syarat-syarat ini setelah pelantikannya maka ada sebab yang mengharuskan pemberhentiannya. Adapun jika dia tetap dalam keadaan baik, tidak ada yang diingkari darinya dari pengabaian urusan agama atau politik rakyat – maka menggagaskan pemberhentiannya saat itu tidak lain adalah mengikuti hawa nafsu dan main-main dengan jabatan yang merupakan jabatan kepemimpinan paling berbahaya, dan ini yang menyebabkan kerusakan. Adapun jika keadaannya berubah sehingga ditemukan darinya apa yang menyebabkan kekacauan keadaan kaum muslimin atau kemunduran urusan agama, maka dia keluar saat itu dari jalur imamah dan menjadi layak untuk disingkirkan dari jabatan ini.
Para ulama telah menjelaskan hal-hal yang dengannya keadaannya berubah. Di antaranya ada yang kembali kepada akhlak dan tindakannya, dan di antaranya ada yang kembali kepada tubuhnya. Kita akan membicarakan hal-hal ini dengan menjelaskan perbedaan pendapat ulama jika ada ketika membahas setiap hal darinya. Maka kita katakan:
Pertama, hal-hal yang merusak akad imamah sehingga imam diberhentikan karenanya adalah: Murtad. Jika kepala negara murtad dari Islam maka dia diberhentikan pada saat itu juga dari kepemimpinan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Surah An-Nisa: ayat 141). Jalan apa yang lebih besar dari jalan imam. Juga karena imam tidak dibebani jabatan ini kecuali untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Jika dia murtad dari Islam maka bagaimana terwujud darinya penjagaan agama. Sesungguhnya murtadnya dari agama menghilangkan tujuan imamah, dan semua yang menghilangkan tujuan imamah menyebabkan batalnya akadnya. Maka murtad menyebabkan batalnya akad imamah, dan ini adalah hal yang jelas tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menyalahinya.
Kedua, hal-hal yang menyebabkan diberhentikannya kepala negara: Hilangnya akal. Para ulama telah menjelaskan keadaan-keadaan hilangnya akal, dan menjelaskan untuk setiap keadaan hukumnya yang khusus. Mereka berkata: Sesungguhnya hilangnya akal ada yang sementara yang diharapkan hilangnya seperti pingsan, atau permanen yang tidak diharapkan hilangnya seperti gila dan kehilangan akal. Jika sementara yang diharapkan hilangnya seperti pingsan maka ini tidak membatalkan kepemimpinan, maka tidak boleh bagi mereka memberhentikannya, karena itu adalah penyakit yang sebentar. Dan jika permanen yang tidak diharapkan hilangnya seperti gila dan kehilangan akal, maka ada yang terus-menerus tidak diselingi sadar atau diselingi sadar. Jika terus-menerus tidak diselingi sadar maka ini membatalkan akad imamah, karena mencegah tujuan dari imamah yaitu menegakkan hak, memenuhi hak, dan melindungi kaum muslimin, karena orang gila wajib ditegakkan wali atasnya, maka bagaimana mungkin dia menjadi wali atas umat. Adapun jika diselingi kesadaran di mana dia kembali kepada keadaan sehat, maka ada yang kebanyakan waktunya gila atau kebanyakan waktunya sadar. Jika kebanyakan waktunya gila maka hukumnya seperti jika terus-menerus maka batal dengannya akad imamah. Dan jika kebanyakan waktunya sadar maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat: Pendapat yang mengatakan bahwa itu membatalkan akad imamah sebagaimana mencegah akad untuknya di awal, karena dalam hal itu ada pengabaian pertimbangan yang berhak di dalamnya. Dan pendapat yang mengatakan tidak membatalkan akad imamah meskipun itu mencegah akad untuknya di awal, karena diperhatikan di awal akadnya kesempurnaan yang lengkap dan dalam keluar darinya kekurangan yang lengkap.
Hal ketiga yang menyebabkan diberhentikannya kepala negara atau imam besar: Hilangnya indra yang berpengaruh pada pendapat atau perbuatan. Pembahasan dalam sisi ini mencakup tiga kekurangan yaitu: Buta, tuli, dan bisu.
Adapun buta: Jika pemimpin tertimpa hal itu setelah pelantikannya maka membatalkan kepemimpinannya sebagaimana membatalkan wilayah peradilan dan ditolak dengannya kesaksian. Adapun jika penglihatannya lemah maka dilihat, jika dia masih bisa mengenali orang-orang yang dilihatnya maka tidak cacat hal itu dalam kepemimpinannya, jika tidak maka batal kepemimpinannya. Adapun rabun senja yaitu tidak bisa melihat di malam hari, maka sebagaimana tidak menjadi penghalang dari akad kepemimpinan untuknya di awal, tidak menjadi cacat dalam kelangsungan kepemimpinan dari pintu yang lebih utama.
Adapun tuli: Para ulama berbeda pendapat tentang terjadinya hal itu pada kepala negara, apakah itu menjadi cacat dalam kepemimpinannya atau tidak, menjadi tiga mazhab:
Pertama dan ini yang paling benar: Dia diberhentikan dengan hal itu seperti diberhentikan dengan buta karena pengaruhnya pada pertimbangan dan perbuatan.
Kedua: Tidak diberhentikan, karena isyarat menggantikan pendengaran dan keluar dari kepemimpinan tidak terjadi kecuali dengan kekurangan yang lengkap.
Pendapat ketiga: Dibedakan antara jika dia bisa menulis dan jika tidak bisa menulis. Jika dia bisa menulis maka tidak batal kepemimpinannya dengan tuli, dan jika tidak bisa menulis maka batal kepemimpinannya dengannya, karena tulisan bisa dipahami dan isyarat samar. Adapun jika pendengarannya berat sehingga tidak mendengar kecuali suara keras maka berdasarkan kesepakatan itu tidak cacat dalam kepemimpinannya.
Adapun bisu: Para ulama berbeda pendapat tentang terjadinya hal itu pada pemimpin seperti perbedaan sebelumnya tentang tuli, dan yang paling benar sebagaimana sebelumnya dalam tuli bahwa dia diberhentikan dengannya.
Ini yang berhubungan dengan hilangnya indra yang berpengaruh pada pendapat atau perbuatan. Adapun yang hilangnya tidak berpengaruh pada pendapat dan perbuatan seperti hilangnya indra penciuman dan hilangnya pengecap yang dengannya merasakan makanan, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, pemimpin tidak diberhentikan dengannya.
Perkara keempat yang menyebabkan pemecatan kepala negara: kehilangan anggota tubuh yang kehilangannya mengganggu pekerjaan atau kemampuan berdiri, seperti terputusnya kedua tangan atau kedua kaki. Jika hal ini terjadi pada kepala negara, maka ia terpecat karenanya karena ketidakmampuannya untuk menjalankan hak-hak umat secara sempurna. Adapun jika terjadi sesuatu yang mempengaruhi sebagian pekerjaan atau sebagian kemampuan berdiri tanpa mempengaruhi yang lain, seperti terpotongnya salah satu tangan atau salah satu kaki, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi dua pendapat:
Pertama, dan ini yang paling benar: bahwa ia tidak terpecat karenanya meskipun hal tersebut menghalangi pengangkatannya sejak awal, karena yang diperhitungkan dalam pengangkatannya adalah kesempurnaan kesehatan, maka yang diperhitungkan dalam pemberhentiannya adalah kesempurnaan kecacatan.
Pendapat kedua: bahwa ia terpecat karenanya, karena kepala negara menjadi berkurang gerakannya. Adapun jika kepala negara kehilangan sesuatu yang kehilangannya tidak mempengaruhi pekerjaan maupun kemampuan berdiri, seperti terputusnya kemaluan, kedua buah zakar, terpotongnya hidung, atau hilangnya salah satu mata, maka hal itu tidak mengganggu kepemimpinannya.
Perkara kelima yang menyebabkan pemecatan kepala negara: batalnya tindakan kepala negara, dan di bawah ini tercakup beberapa bentuk:
Bentuk pertama: bahwa ia dikekang dan dipaksa oleh orang-orang dari pembantunya yang sewenang-wenang dalam mengatur urusan umat tanpa menampakkan kemaksiatan atau keluar dari ketaatan. Jika ini terjadi, maka para ulama dalam menerangkan hukumnya memperhatikan dua sisi: Sisi pertama: apakah kecakapannya untuk kepemimpinan masih ada atau dengan jatuhnya di bawah paksaan orang yang sewenang-wenang ini ia telah kehilangan kecakapannya untuk jabatan ini. Sisi kedua: apakah boleh membenarkan orang yang sewenang-wenang ini atas perbuatan dan tindakannya yang dirampasnya dari kepala negara atau tidak boleh membenarkannya. Adapun mengenai sisi pertama yaitu: apakah kecakapannya untuk kepemimpinan masih ada atau tidak, maka para ulama mengatakan: bahwa ini tidak merusak kepemimpinannya sehingga ia tidak terpecat karena paksaan ini dari jabatannya. Adapun mengenai sisi kedua yaitu: apakah boleh membenarkan orang yang sewenang-wenang ini atas perbuatannya atau tidak, maka dilihat tindakan-tindakan orang yang menguasai urusannya, apakah berjalan sesuai dengan hukum agama dan tuntutan keadilan atau tidak. Jika berjalan sesuai dengan hukum agama dan tuntutan keadilan, maka boleh membenarkannya, karena tidak membenarkannya berarti menghentikan sebagian kemaslahatan, dan ini menimbulkan kerusakan pada umat, sehingga keadaannya menjadi seperti ketika ia menguasai jabatan kepemimpinan itu sendiri dengan paksaan. Adapun jika perbuatannya keluar dari hukum agama dan tuntutan keadilan, maka tidak boleh membenarkannya, dan wajib bagi kepala negara untuk meminta bantuan rakyat hingga hilang dominasi dan kekuasaan orang yang mendominasi ini.
Bentuk kedua dari bentuk-bentuk batalnya tindakan kepala negara: bahwa kepala negara jatuh sebagai tawanan, dan penawanan tersebut bisa dari orang-orang musyrik atau dari pemberontak Muslim. Jika ditawan oleh orang musyrik, maka ia bisa diharapkan pembebasannya atau putus harapan darinya. Jika diharapkan pembebasannya dengan peperangan atau tebusan, maka ia tetap dalam kepemimpinannya dan wajib bagi seluruh umat untuk menyelamatkannya dari tangan mereka. Adapun jika putus harapan pembebasannya karena sangat mungkin ia tidak akan bebas hingga kematiannya, maka ia telah keluar dari kepemimpinan karena hal ini, dan ahli hal dan akad harus memilih orang lain yang saleh untuk memimpin umat, lalu membaiatnya sebagai kepala negara atas mereka. Adapun jika ditawan oleh pemberontak Muslim, maka dilihat juga dalam hal itu, apakah diharapkan pembebasannya dari tangan mereka atau putus harapan darinya. Jika diharapkan pembebasannya, maka ia tetap dalam kepemimpinannya dan wajib juga bagi seluruh umat untuk menyelamatkannya dari penawanan ini. Jika putus harapan pembebasannya, maka dilihat keadaan para pemberontak. Jika mereka belum memilih kepala negara selain dirinya, maka kepala negara yang ditawan di tangan mereka tetap dalam kepemimpinannya, karena baiatnya mengikat mereka dan ketaatan kepadanya wajib bagi mereka, sehingga keadaannya bersama mereka seperti ketika ia bersama ahli keadilan dalam keadaan di bawah pengekangan dari pembantunya yang sewenang-wenang, dan saat itu wajib menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk mengatur urusan negara sebagai wakil dari kepala negara bukan sebagai kepala negara, agar kepentingan umat tidak terganggu. Kepala negara yang ditawan lebih berhak memilih yang mewakilinya selama ia mampu menunjuk wakil. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka umat yang diwakili oleh ahli hal dan akad harus memilih wakil yang akan mengatur urusan umat hingga Allah menghendaki apa yang Dia kehendaki dari pembebasan kepala negara dari penawanan atau kematiannya. Jika putus harapan terpenuhi dan kepala negara bebas dari penawanan, maka wakilnya diberhentikan dan urusan negara kembali ke tangan kepala negara. Adapun jika kepala negara yang ditawan memberhentikan dirinya sendiri atau meninggal dalam penawanan, maka wakilnya tidak menjadi kepala negara kecuali dengan baiat ahli hal dan akad, karena ia adalah wakil dari orang yang ada, maka hilang dengan kehilangannya. Jika para pemberontak telah menunjuk kepala negara atas mereka yang mereka tunduki, maka kepala negara yang ditawan di tangan mereka keluar dari kepemimpinan negara, karena mereka telah memisahkan diri dengan wilayah yang hukumnya terpisah dari jamaah dan keluar dengannya dari ketaatan, sehingga ahli keadilan tidak lagi memiliki dukungan dengan mereka. Wajib bagi umat yang diwakili oleh ahli hal dan akad untuk memilih kepala negara lain selain dirinya. Jika kepala negara yang ditawan mampu melepaskan diri dari tawanannya, ia tidak kembali ke kepemimpinan, karena ia telah keluar darinya.
Bentuk ketiga dari bentuk-bentuk batalnya tindakan kepala negara: bahwa bangkit melawannya orang yang menguasai jabatan kepemimpinan dengan kekuatan, yang dikenal di zaman kita sebagai kudeta dalam pemerintahan, dan ini salah satu cara yang dengannya kepemimpinan terlaksana sebagaimana telah kami jelaskan. Kami telah menerangkan bahwa para ulama mengatakan dengan pemecatan kepala negara dan terlaksananya kepemimpinan bagi orang yang mendominasi, agar rakyat tidak jatuh dalam kekacauan perang saudara dan merajalela kerusakan. Ringkasnya: bahwa kepala negara terpecat dari jabatannya jika tindakannya batal karena penguasaan orang lain atas jabatan ini dengan kekuatan, baik kepala negara yang dipaksa itu datang ke pemerintahan melalui pemilihan ahli hal dan akad maupun ia juga dipaksa oleh pendahulunya.
Perkara keenam dari perkara-perkara yang menyebabkan pemecatan kepala negara: kezaliman kepala negara yaitu: menindas hamba-hamba Allah Yang Mahatinggi, dan kefasikannya yaitu: keluarnya dari ketaatan-Nya Yang Mahasuci lagi Mahatinggi. Kami katakan: para ulama berbeda pendapat dalam kezaliman kepala negara dan kefasikannya, yaitu: jika ia menjadi zalim dan tidak adil, apakah ia terpecat karenanya? Yaitu: apakah ia terpecat karena kezaliman dan karena kefasikan yang muncul padanya setelah ia menjabat kepemimpinan atau tidak?
Kami katakan: adapun golongan Khawarij, karena mereka berpendapat bahwa kefasikan mengeluarkan pelakunya dari keimanan, mereka mengatakan dengan pemecatan imam jika ia fasik, karena saat itu ia bukan mukmin, dan orang yang bukan mukmin tidak layak menjadi imam. Demikian juga golongan Muktazilah berpendapat dengan pemecatannya karena kezaliman dan kefasikan, karena jika wajib memecat hakim dan amir wilayah dengan munculnya kefasikan pada keduanya, maka lebih wajib lagi memecat imam jika ia melakukan itu. Sebagian juga berpendapat bahwa ia tidak terpecat karenanya, karena dalam pemecatan imam dan wajibnya menunjuk orang lain dapat membangkitkan fitnah karena kekuatannya.
Jika kita kembali kepada jamaah Hanafi, karena mereka tidak menjadikan keadilan sebagai syarat dalam sahnya kekuasaan, di mana menurut mereka sah memberikan kepemimpinan negara kepada orang fasik tetapi dengan kemakruhan sebagaimana telah kami jelaskan saat membahas syarat-syarat kepala negara – kami katakan: karena keadilan bukan syarat menurut mereka dalam sahnya kepemimpinan negara, maka mereka mengatakan: jika umat memilih imam yang terpenuhi padanya sifat-sifat keadilan kemudian ia zalim atau fasik, maka ia tidak terpecat dari jabatan imamah, tetapi ia pantas dipecat oleh ahli hal dan akad jika mereka aman dari terjadinya fitnah, dan jika tidak aman terjadinya, maka ia tidak terpecat. Artinya bahwa Hanafiyah mengatakan bahwa jika ia fasik maka dalam keadaan ini ia tidak wajib dipecat atau tidak terpecat hanya karena kefasikan ini, melainkan perkaranya diserahkan kepada ahli hal dan akad. Jika mereka berpendapat untuk memecatnya, mereka memecatnya, dan jika mereka berpendapat untuk mempertahankannya, mereka mempertahankannya. Tetapi dalam keadaan jika mereka berpendapat untuk memecatnya, mereka harus memperhatikan fitnah yang timbul dari pemecatannya. Jika timbul fitnah dari pemecatannya, maka mereka tidak boleh memecatnya dalam keadaan ini. Hanafiyah mendasarkan pendapat mereka ini pada bahwa para sahabat semoga Allah meridhai mereka shalat di belakang sebagian Bani Umayyah dan menerima kekuasaan mereka. Lebih dari satu orang dari mereka shalat di belakang Marwan bin Al-Hakam. Mereka berkata: dan Al-Bukhari meriwayatkan dalam sejarahnya: “Aku mendapati sepuluh orang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, semuanya shalat di belakang imam-imam yang zalim.”
Tidak terpecatnya kepala negara karena kefasikan adalah yang dilihat oleh kebanyakan ulama, karena generasi salaf memandang kefasikan tampak nyata dan kezaliman terjadi dari para imam setelah khulafaur rasyidin, dan mereka dengan itu tetap tunduk kepada mereka. Para sahabat, tabiin, dan yang setelah mereka memandang khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbas, padahal kebanyakan Bani Umayyah dan kebanyakan Bani Abbas adalah orang-orang fasik.
Setelah itu, inilah pendapat-pendapat para ulama dalam pemecatan kepala negara karena kefasikan dan kezaliman. Kami berpendapat bahwa pendapat yang mengatakan wajib memecat kepala negara karena kezaliman dan kefasikan jika tidak ada fitnah adalah yang lebih pantas diterima. Maka wajib bagi ahli hal dan akad di negara jika mereka melihat kezaliman kepala negara atau kefasikannya untuk mengumumkan pemecatannya dari jabatannya jika mereka aman dari terjadinya fitnah, dan untuk melakukan pemilihan orang yang layak untuk kepemimpinan setelah itu. Adapun jika mereka tidak aman dari terjadinya fitnah, maka tidak boleh bagi mereka memecatnya. Kami mengatakan dengan wajibnya memecatnya jika ia zalim atau fasik dengan syarat tidak ada fitnah, karena jika kita mensyaratkan keadilan pada orang yang diangkat sebagai kepala negara atas kaum muslimin, maka hilangnya syarat ini jika merusak kelayakan untuk menjabat imamah di awal, maka ia harus merusak keberlangsungan imamah juga, karena illah disyaratkannya syarat ini tidak hilang hanya dengan jabatan ini. Imamah adalah kepemimpinan untuk umat Islam, dan sebagaimana Rasul shallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi semua kaum muslimin, penguasa dan yang dikuasai, di semua zaman, maka kepala negara mereka harus sama seperti mereka dalam meneladani Rasul shallallahu alaihi wasallam dan tunduk pada hukum-hukum agama yang dipilih untuk menjaganya, karena rakyat mengikuti agama raja-raja mereka. Jika kepala negara fasik atau zalim padahal ia berdiri di puncak kekuasaan eksekutif di negara, maka keimanan rakyat pada kebajikan dan keadilan dapat melemah, dan dapat dijadikan oleh orang-orang yang Islam belum tertanam kuat dalam jiwa mereka dalam perilaku mereka sebagai teladan dan panutan, dan dalam hal ini terdapat bahaya terbesar pada agama dan umat.
Adapun apa yang dijadikan dasar oleh yang berpendapat tidak terpecat bahwa para sahabat shalat di belakang sebagian Bani Umayyah meskipun kefasikan mereka tampak, dan bahwa para tabiin mengakui khilafah Bani Abbas meskipun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, maka kami tidak menerima dalil ini, karena para penguasa ini adalah raja-raja yang menguasai urusan, dan orang yang menguasai dengan paksa imamahnya sah karena darurat, agar kepentingan kaum muslimin tidak terhenti, seperti penyelesaian perkara mereka, pernikahan bagi yang tidak punya wali, jihad melawan orang-orang kafir dan lain-lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Bukan syarat dalam sahnya shalat di belakang imam bahwa ia harus adil. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Jihad wajib atas kalian bersama setiap amir, baik ia berbuat baik maupun jahat, dan shalat wajib atas kalian di belakang setiap muslim, baik ia berbuat baik maupun jahat, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar.”
Dengan ini kami telah selesai dari pembahasan tentang sistem pemerintahan dalam Islam.
Saya titipkan kalian kepada Allah, dan salam sejahtera atas kalian serta rahmat Allah dan berkah-Nya.
Pelajaran 13: Arahan-arahan Pemikiran Manajemen Islam
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Arahan-arahan Pemikiran Manajemen Islam (1)
Kerja adalah Kewajiban Islam
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kini kita mulai membahas tentang sistem manajemen dalam Islam, maka kita katakan:
Organisasi manajemen adalah terjemahan praktis dan langsung dari sistem politik, dan merupakan lembaga eksekutif pertama bagi semua yang lahir dari otoritas politik berupa perencanaan dan proyek-proyek. Jika lembaga politik adalah yang mewakili kekuasaan dan mengumumkan tujuan-tujuannya untuk membangun negara dan meninggikan kedudukannya, maka lembaga manajerial adalah yang mewujudkan tujuan-tujuan ini dan bekerja untuk menegakkan pilar-pilar negara di atas fondasi yang kokoh. Para pegawai manajemen menjadi wajah para pemegang kekuasaan di hadapan rakyat dan jaringan komunikasi yang teliti yang memfasilitasi kedua pihak penting dari unsur-unsur negara ini untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang khusus dan umum dengan rela dan yakin. Keterkaitan organisasi manajemen dengan sistem politik datang selalu dan selamanya sebagai keterikatan yang menyerupai hubungan antara dua sisi mata uang, sehingga tidak dapat dinilai yang satu tanpa yang lain. Manajemen yang stabil adalah judul politik yang benar, dan manajemen yang goyah adalah simbol perpecahan dan kehancuran politik.
Dalam konteks pembahasan kita tentang sistem manajemen dalam Islam, kita akan membahas empat topik utama yaitu:
Pertama: Arahan-arahan pemikiran manajemen Islam.
Kedua: Metode manajemen Islam.
Ketiga: Organisasi manajemen dalam bidang penerapan praktis.
Keempat: Perangkat-perangkat manajemen. Dan sekarang kita mulai membahas tentang arahan-arahan pemikiran manajemen Islam:
Kita katakan: Sesungguhnya dua sumber terpenting bagi pemikiran manajemen Islam adalah: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, karena apa yang terdapat dalam dua sumber ini sangat menegaskan kekhasan pemikiran manajemen Islam, yang tidak memihak individu dengan mengorbankan kelompok seperti dalam pemikiran kapitalis, dan tidak memihak kelompok dengan mengorbankan individu seperti dalam pemikiran sosialis. Bahkan kita dapati pemikiran Islam berada di tengah-tengah secara adil, karena keduanya mewujudkan dalam keselarasan sempurna kepentingan individu dan kepentingan kelompok, dan Islam tidak mengizinkan dominasi salah satu atas yang lain. Tidak ada individualisme mutlak, dan tidak ada kolektivisme mutlak. Inilah arah yang bijaksana yang dicari kemanusiaan di dunia saat ini.
Cukuplah kita menyajikan berikut ini contoh-contoh petunjuk Al-Quran dan Nabi dalam hal ini, yaitu dalam dua bidang: bidang organisasi manajemen, dan bidang pengelolaan para pekerja.
Mengenai organisasi manajemen, kita katakan: Islam peduli dengan menetapkan aturan-aturan organisasi yang baik untuk pekerjaan, dengan menganggapnya sebagai poros organisasi manajemen bagi kelompok dan aktivitas-aktivitasnya, dan hal itu dengan cara yang menjamin pertumbuhan dan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan; dan dengan apa yang mencerminkan kekhasan pemikiran manajemen Islam dalam hal ini, dan inilah yang kita ungkapkan dalam topik-topik berikut:
Pertama: Kerja adalah Kewajiban Islam:
Oleh karena itu Allah memerintahkan kita semua untuk bekerja, sebagaimana Dia Yang Maha Suci berfirman: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'” (Surat At-Taubah: 105) Dan Dia menyeru Rasul-Nya yang mulia dalam hal ini dengan firman-Nya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Surat Asy-Syarh: 7) Dan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sabda beliau: “Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok.” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam memuji para pekerja dengan bersabda: “Barangsiapa yang sore hari dalam keadaan lelah karena pekerjaan tangannya (maksudnya: sangat letih), maka dia sore itu dalam keadaan diampuni.” Juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyaksikan seorang laki-laki yang tangannya bengkak karena bekerja, lalu beliau gembira seraya bersabda: “Ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.”
Sungguh Islam telah mengangkat kewajiban bekerja ke tingkat kewajiban agama; karena Islam selalu menghubungkan keimanan dengan amal saleh, yaitu: pekerjaan yang bermanfaat bagi individu dan kelompok sekaligus. Tidak ada satu ayat pun yang disebutkan dalam Al-Quran yang menyebut keimanan kecuali disebutkan bersamanya amal saleh; sebagaimana disebutkan ayat-ayat Al-Quran di banyak tempat, Allah Taala berfirman: “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh” (Surat Al-Baqarah: ayat 25) yang menegaskan bahwa Islam adalah akidah amal dan amal akidah. Sebagaimana kerja adalah kewajiban, maka ia juga sumber nilai. Ketika Islam menjadikan kerja sebagai kewajiban umum bagi semua orang, Islam mengangkat derajatnya. Kerja tidak lagi merupakan hal yang hina sebagaimana sebelumnya, bahkan menjadi sumber nilai manusia dalam kehidupan ini, dan tolok ukur tanggung jawabnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Surat An-Najm: 39).
Adapun perbedaan nilai-nilai manusia dasarnya adalah amal perbuatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat, dan tentang hal itu Tuhan kita Subhanahu wa Taala berfirman: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Surat Al-An’am: 132) Kerja adalah sumber nilai kemanusiaan, artinya: ia membuat pemiliknya memiliki nilai di masyarakat tempat ia hidup. Manusia dengan pekerjaannya adalah yang memberikan nilai kepada materi dengan apa yang ia lakukan terhadapnya berupa proses-proses produksi, industri, perdagangan, distribusi, penggunaan, dan konsumsi. Materi tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, artinya: ia tidak akan memiliki nilai kecuali dengan manusia dan dengan kerja manusia.
Jadi: Kerja manusia diperlukan untuk kemanfaatan individu dan kemanfaatan masyarakat. Dengan demikian arahan-arahan pemikiran Islam mengungkapkan kerja menurut konsep kemanusiaan yang luas, dan luasnya kerja, dan bahwa ia adalah sumber nilai. Arahan-arahan ini telah mendahului dalam perhatian terhadap kerja dan menganggapnya sumber nilai dalam hal itu lebih dari berabad-abad, mendahului ekonomi Barat dan pelopornya “Adam Smith” di Mesir, yang berpendapat bahwa kerja – menurut konsep materialisnya – adalah sumber nilai dan kekayaan. Apa yang dicapai oleh “Adam Smith” di Mesir – ahli ekonomi Barat yang terkenal – sesungguhnya telah dicapai oleh Islam kita sejak keberadaan Islam di bumi ini.
Kerja sebagai sumber objektif dan netral untuk menilai manusia berdasarkan kelayakan dalam Islam, mengharuskan penetapan standar kerja yang teratur, dan tingkat kinerja yang tertentu, dan inilah yang diperjuangkan oleh pemikiran manajemen kontemporer dalam arah ilmiahnya untuk mewujudkannya. Juga mengharuskan penetapan laporan-laporan kegiatan yang menunjukkan tingkat kinerja pekerja sebagai alat untuk mengevaluasinya.
Jadi: Istilah-istilah manajemen modern ini telah dikenal oleh fikih Islam, dan dikenal oleh syariat Islam.
Demikianlah Islam menghapuskan pertimbangan-pertimbangan keberpihakan pribadi dalam menilai manusia, baik sosial, ekonomi, maupun politik, karena Islam menjadikan kerja sebagai dasar dalam menilai manusia. Jika kerja adalah sumber nilai, maka ia juga adalah sarana penghasilan, karena kerja mewajibkan manusia sebagai sarana penghasilan dan sumber rezeki individu dan pendapatan pribadinya yang ia andalkan dalam penghidupannya. Allah telah menyediakan bagi kita cara-cara penghidupan dan mendapatkan rezeki, maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan.” (Surat Al-A’raf: ayat 10) Tetapi mewujudkan hal itu digantungkan pada usaha dan kerja; oleh karena itu Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (Surat Al-Mulk: ayat 15). Dan inilah yang ditegaskan oleh hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan dari hasil usaha tangannya.” Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: “Sebaik-baik penghasilan adalah hasil kerja tangan seseorang.” Dan Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kita bahwa kewajiban-kewajiban agama tidak menghalangi usaha untuk mendapatkan rezeki; maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban Jumat yang merupakan shalat berjamaah: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.” (Surat Al-Jumu’ah: 10) Dan ketika Islam memerintahkan kita untuk bekerja guna mendapatkan rezeki, maka Islam menghendaki penghasilan yang halal dan sah, maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (Surat Al-Baqarah: ayat 168) Allah Tabaraka wa Taala juga berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Surat An-Nisa: ayat 29).
Juga diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sabda beliau: “Mencari yang halal adalah kewajiban atas setiap muslim.” Dan Islam mewajibkan kerja sebagai sarana penghasilan untuk menjaga martabat manusia, dan agar ia menjaga dirinya dari kehinaan meminta-minta dan kebutuhan. Dan inilah yang diungkapkan oleh hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan dari beliau sabdanya: “Sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu datang dengan seikat kayu bakar dan menjualnya, lalu dengan hasil itu ia menjaga wajahnya (dari meminta-minta), itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang, apakah mereka memberinya atau menolaknya.” Dan diriwayatkan: “Bahwa dua sahabat datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mereka membawa saudara mereka. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentangnya. Mereka berkata: Sesungguhnya dia tidak berhenti dari shalat kecuali untuk shalat lagi, dan tidak berhenti dari puasa kecuali untuk puasa lagi, hingga menimpanya kelelahan (maksudnya: dari kepenatan) yang engkau lihat wahai Rasulullah. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‘Siapa yang menggembalakan untanya? Dan siapa yang berusaha untuk anak-anaknya?’ Mereka berkata: ‘Kami.’ Maka beliau bersabda: ‘Kalian berdua lebih ibadat daripadanya.'”
Dan diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang bersemangat dan kuat lewat di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, menuju ke tempat tertentu (maksudnya: mengarah ke tempat tertentu). Maka para sahabat beliau berkata: Wahai Rasulullah, seandainya (maksudnya: para sahabat berharap) orang ini di jalan Allah (maksudnya: kekuatan dan semangatnya, yaitu: para sahabat berharap agar laki-laki kuat yang berjalan di hadapan mereka menuju ke tempat tertentu ini menjadi muslim). Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Jika dia keluar berusaha untuk anak-anaknya yang masih kecil maka dia di jalan Allah, dan jika dia keluar berusaha untuk kedua orang tuanya yang sudah tua maka dia di jalan Allah, dan jika dia keluar untuk dirinya sendiri untuk menafkahinya maka dia di jalan Allah.” Demikianlah Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kerja yang dengannya manusia menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang sama dengan jihad di jalan Allah. Jika kerja adalah sarana penghasilan – sebagaimana kami jelaskan – maka ia juga dasar kemajuan. Mewajibkan kerja sebagai sarana penghasilan dan sumber pendapatan individu dapat mewujudkan kemajuannya secara ekonomi dan sosial.
Dan Islam bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kemajuan ini juga di tingkat masyarakat, dengan mendorong individu-individunya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, baik pertanian, industri, maupun perdagangan. Dan inilah yang dijelaskan dan ditegaskan oleh hadits-hadits Nabi berikut:
Dalam bidang pertanian:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam biji, lalu dimakan oleh burung atau manusia, melainkan itu menjadi sedekah baginya.” Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: “Barangsiapa yang menanam pohon, lalu ia bersabar menjaganya dan merawatnya hingga berbuah, maka baginya pada setiap yang dipetik dari buahnya adalah sedekah di sisi Allah Azza wa Jalla.” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memperhatikan pembangunan pertanian, bukan hanya sekadar untuk meraih keuntungan duniawi, tetapi juga mengharap pahala akhirat.
Dalam industri:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan tukang (perajin) jika ia jujur.” Industri adalah sumber penghasilan terbaik dalam Islam, karena di dalamnya terkandung kemajuan sejati bagi bangsa dan negara. Dan inilah yang benar-benar kita rasakan di dunia kontemporer kita.
Dalam perdagangan:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat orang-orang yang bekerja di bidangnya ke tingkat para nabi, orang-orang yang benar (shiddiqin), para syuhada, dan orang-orang saleh, jika mereka berpegang pada kejujuran dalam melaksanakannya. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Pedagang yang jujur bersama para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang saleh.” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya perdagangan sebagai sumber utama keuntungan, karena beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sembilan persepuluh rezeki ada dalam perdagangan.” Perdagangan berarti: pemasaran produksi dan peredarannya, apa pun jenisnya; untuk mencari keuntungan yang halal yang dihalalkan Allah tanpa riba; berdasarkan firman-Nya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surat Al-Baqarah: ayat 275).
Dan pengharaman riba – menurut perkataan Imam Ar-Razi – kembali kepada bahwa ia menghalangi manusia dari berusaha untuk mendapatkan penghasilan; karena pemilik uang jika ia mampu dengan cara akad riba untuk memperoleh tambahan uang secara tunai, baik dalam keadaan sadar maupun lupa, maka ringan baginya untuk berusaha mencari penghidupan. Maka ia hampir tidak mau menanggung beratnya usaha, perdagangan, dan kerajinan yang berat. Dan hal itu menyebabkan terputusnya manfaat-manfaat makhluk. Dan sudah diketahui bahwa kemaslahatan dunia tidak teratur kecuali dengan perdagangan, kerajinan, industri, dan pembangunan.
Islam mengharamkan riba karena dampak-dampak buruknya, karena ia membuat pemilik harta duduk-duduk tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mendapatkan penghasilan dan investasi, di samping apa yang terdapat di dalamnya berupa eksploitasi terhadap manusia lain, yang menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan sosial.
Karakteristik Kerja dalam Islam
Kita telah melihat bahwa Islam menjadikan kerja sebagai kewajiban umum sebagai implementasi prinsip kesetaraan di antara anak-anak Adam. Juga Islam menyeru berangkat dari kekhususannya untuk mengikuti jalan yang lurus, yang menghendaki menempuh perilaku yang baik dan benar; oleh karena itu Islam menetapkan spesifikasi dan aturan kerja yang mewujudkan perilaku ini. Cukuplah kita menyajikan di sini sebagian dari karakteristik-karakteristik kerja tersebut:
Kita katakan: Keimanan dan amal saleh; karakteristik pertama dari karakteristik kerja dalam Islam adalah keterkaitan keimanan dengan amal saleh. Islam adalah akidah amal dan amal akidah. Dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran Karim di lebih dari lima puluh ayat, dengan menghubungkan keimanan dan amal saleh, baik dengan kata tunggal dalam firman-Nya: “Barangsiapa yang beriman dan beramal saleh” (Surat Al-Kahfi: ayat 88) atau dengan kata jamak dalam firman-Nya: “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh” (Surat Al-Baqarah: ayat 25).
Dan keimanan adalah: keyakinan, kepastian, dan pembenaran terhadap suatu ide atau perilaku tertentu; sedangkan amal saleh berarti: secara mutlak, dan umum amal saleh yang mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan serta manfaat individu dan kelompok, baik dalam urusan dunia maupun agama. Al-Quran Karim menghubungkan keimanan dengan amal saleh sebagai hubungan asal dengan cabang, dan fondasi dengan bangunan. Ini adalah hubungan yang dengannya mustahil keberadaan salah satunya tanpa yang lain. Manusia tidak mengenal keimanan yang tidak menghasilkan amal saleh, dan tidak tegak amal saleh yang tidak didasarkan pada keimanan dan tidak lahir dari akidah. Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan orang-orang beriman yang beramal saleh dengan pemeliharaan yang sempurna, dan memberikan kepada mereka balasan dan pahala yang berlimpah di dunia dan akhirat, karena bagi mereka balasan berlipat ganda, balasan yang terbaik, pahala yang besar, pahala yang tidak terputus, surga tempat tinggal, dan surga kenikmatan. Dan mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebagaimana diceritakan Al-Quran Karim tentang sifat-sifat ini.
Dan inilah yang tergambar dalam penegasan-Nya Subhanahu ketika Dia berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Surat An-Nahl: 97) Dan dalam firman-Nya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.” (Surat An-Nur: ayat 55).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami menyimpulkan dua arahan berikut dalam bidang pemikiran administrasi Islam:
1 – Bahwa orang yang beriman dituntut untuk mengerjakan semua amal saleh, baik yang berkaitan dengan kemaslahatan individu pekerja maupun kemaslahatan kolektif organisasi, dan perilaku yang moderat yang muncul dari esensi Islam menuntut tercapainya keseimbangan dalam bekerja, antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok.
2 – Bahwa mengerjakan amal saleh -yaitu perbuatan-perbuatan yang bertujuan memperbaiki keadaan individu dan kelompok- harus bersumber dari iman, agar dapat mencapai hasil yang diharapkan; oleh karena itu Islam adalah amal dari akidah dan akidah dari amal, dan inilah pintu masuk akidah untuk setiap pekerjaan perbaikan, dan hal yang harus diterapkan untuk keberhasilan reformasi administrasi dalam masalah administrasi publik, dan keterkaitan iman dengan amal dalam berbagai bidang perbaikan memerlukan penyediaan dakwah yang diperlukan untuk perbaikan ini; dan kesadaran yang memadai tentangnya untuk keberhasilan penerapannya.
Di antara karakteristik pekerjaan dalam Islam adalah: bahwa pekerjaan harus direncanakan, karena pencapaian tujuan dan perencanaan mewakili aspek intelektual dari pekerjaan, dan mendahului penyelesaiannya, maka manusia yang Allah bedakan dari makhluk-makhluk-Nya yang lain dengan akal budi, bertindak dalam pekerjaannya dan tindakannya berdasarkan pemikiran terlebih dahulu; yang mencakup penentuan tujuan pekerjaannya, maksud-maksudnya, dan persiapan -yaitu: perencanaan untuknya, maka manusia yang berakal akan bertanya pada dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan apa pun: mengapa dia melakukannya? Dan menjawabnya berdasarkan apa yang dibimbing oleh pemikirannya dan yang menggerakkannya; dorongannya dalam hal itu adalah bahwa dia menentukan dengan tepat dan jelas apa yang ditargetkan dengan pekerjaannya, dan berdasarkan penetapan tujuannya dia mulai mempersiapkan dan menyiapkan pekerjaan ini; dengan mencari cara dan metode terbaik untuk menyelesaikannya, dan orang-orang, tempat-tempat, dan waktu yang paling sesuai untuk menyelesaikannya, dan ini adalah proses perencanaan pekerjaan -yaitu: persiapan untuknya- yang dimaksudkan oleh manajemen sebagai pengorganisasian kegiatan manusia kolektif yang bertujuan. Dan Islam ketika mengaktifkan akal, maka Islam sangat memperhitungkan niat -yaitu: maksud dalam melakukan pekerjaan- dan menjadikannya sebagai dasar evaluasinya; karena niat adalah dasar dalam menentukan pekerjaan dan menghakiminya; oleh karena itu Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Katakanlah: Setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (Surat Al-Isra: 84) Dan juga firman-Nya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan.” (Surat Al-Baqarah: dari ayat 148) Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya.”
Sebagaimana Islam -dalam mengaitkan pekerjaan dengan tujuannya- menyeru kepada kemuliaan tujuan-tujuan ini, dan mengarahkannya pada kebaikan, dan berlomba-lomba dalam melakukannya; untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Taala, maka jika setiap orang yang berakal harus memiliki tujuan yang dimaksudkan dengan pekerjaannya, maka tujuan itulah yang menjadi dasar dalam penerimaan dan penolakan pekerjaan; dialah timbangan yang dengannya diketahui derajat pekerjaan di sisi Allah, maka jika tujuannya luhur, dan maksudnya mulia, dan terkait dengan kehendak yang tetap, dan dengannya dicari keridhaan Allah, maka hal itu menjadi sebab yang kuat dalam diterimanya pekerjaan, dan terangkatnya derajat, dan pada waktu yang sama menjadi bukti nyata atas kuatnya keimanan pekerja kepada Allah, dan ketatnya pengawasannya terhadap Tuhannya, maka dia bertakwa, dan berbuat baik.
Dan Islam menyeru kita untuk menggambarkan tujuan ketika memulai melaksanakan pekerjaan apa pun; agar pekerjaan dalam metode, waktu, dan penentuan tempatnya konsisten dengan maksud; yaitu dengan mensyaratkan menghadirkan niat ketika melakukan pekerjaan apa pun, seperti dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti: shalat, puasa, haji, dan lainnya, dan Islam melihat dalam kesatuan tujuan: dasar kekompakan kelompok, dan keterpaduannya, dan inilah yang tergambar dalam firman-Nya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” (Surat Ali Imran: dari ayat: 103). Dan penetapan tujuan diikuti dengan perencanaan pekerjaan, dan persiapan untuk menghadapi tantangan penyelesaian pekerjaan di masa depan, dan tidak meninggalkannya di bawah belas kasihan keadaan dan kejutan-kejutan, bahkan kita mempertimbangkan prediksi masa depan, dan kemungkinan yang tersedia saat ini dan di masa depan, dan inilah yang tergambar dalam firman-Nya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.” (Surat Al-Anfal: dari ayat: 60) Dan jika ayat mulia ini disebutkan khususnya dalam perencanaan militer, maka ayat ini memberikan arahan umum kepada kita untuk menghadapi tantangan dan kemungkinan masa depan dalam berbagai bidang pekerjaan.
Dan bagi kita dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam terdapat contoh perencanaan sipil dalam bidang pangan, ketika dia memberitahukan kepada Firaun Mesir tentang takwil mimpinya, menjelaskan kepadanya bahwa negeri akan mencapai produksi pertanian yang melimpah selama tujuh tahun, setelah itu menghadapi tujuh tahun yang sulit, yang dengannya wajib mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan menabung dari produksi tahun-tahun kemakmuran; untuk menghadapi tahun-tahun kesulitan, dan dalam hal itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (Surat Yusuf: dari ayat: 47, 48).
Dan hal itu diperkuat dengan hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya” yang menyeru bahkan memerintahkan untuk mengambil perencanaan dalam pekerjaan, bukan hanya untuk jangka pendek, atau menengah, atau panjang, tetapi untuk waktu yang sangat panjang, dan pekerjaan juga harus disederhanakan; karena Islam mendorong pada kebaikan pelaksanaan, dan inilah yang ditegaskan oleh banyak ayat Al-Quran; maka Allah Subhanahu wa Taala menciptakan manusia dan kehidupan dan kematian; untuk menguji manusia dalam sejauh mana mereka menguasai pekerjaan-pekerjaan mereka di dunia mereka, maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, dan adalah Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (Surat Hud: dari ayat: 7) Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.” (Surat Al-Kahf: 7) Dan Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (Surat Al-Mulk: dari ayat: 2). Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala menetapkan pemberian imbalan kepada para pekerja atas kebaikan pelaksanaan, maka Allah berfirman: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik.” (Surat Al-Kahf: dari ayat 30) Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan menambah (balasan) kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan.” (Surat An-Nur: 38) Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai dari pekerja apabila dia bekerja agar dia berbuat baik” maka Islam mengandalkan pengawas diri religius, dan motivasi akidah internal dalam menjamin kebaikan pekerjaan, dan kualitas pelaksanaan, ini berkenaan dengan tugas-tugas pelaksanaan.
Adapun berkenaan dengan tugas-tugas konsultatif, yang terwujud dalam sekadar memberikan nasihat dan pendapat teknis, maka wajib merujuk padanya kepada ahli pengalaman dan spesialisasi dan ilmu, dan inilah yang ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Quran berikut; karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Dan tidak ada yang lebih memberitahumu seperti Yang Maha Mengetahui.” (Surat Fathir: dari ayat: 14) Dan Allah berfirman: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Surat An-Nahl: dari ayat: 43) Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” (Surat An-Nisa: dari ayat: 83).
Dan dari apa yang telah diuraikan: jelas bahwa Islam mewajibkan memperhatikan spesialisasi dan pengalaman dan merujuk kepada para ahlinya dalam setiap masalah yang muncul bagi kita, yang tidak ada pengetahuan dan tidak ada ilmu bagi kita tentangnya, tetapi para ahli spesialisasi dan pengalaman tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pendapat mereka, atau mengeluarkan perintah yang mengikat dalam hal ini, dan inilah yang ditunjukkan oleh ayat mulia dalam firman-Nya: “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.” (Surat Al-Ghasyiyah: dari ayat: 21, 22) Dan inilah yang diambil oleh pemikiran administrasi kontemporer.
Dan demikianlah Islam mendorong kita untuk menguasai pekerjaan, baik dengan seruan untuk kebaikan pelaksanaan dalam bidang pelaksanaan, atau dengan merujuk kepada ahli pengalaman dan spesialisasi dan ilmu dalam bidang nasihat, dan jika setiap pekerjaan memiliki prosedur tertentu yang dituntut oleh prinsip-prinsip penyelesaiannya, dan diperlukan oleh kebaikan pelaksanaannya, maka wajib mengambil dalam prosedur pekerjaan hal yang diperlukan dan perlu untuk keselamatan pelaksanaan; karena prosedur adalah sarana dan bukan tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak diragukan bahwa berlebih-lebihan dalam prosedur pekerjaan dan langkah-langkah penyelesaiannya tanpa alasan sesungguhnya adalah penyimpangan dari kesederhanaan dan moderasi; yang dicita-citakan Islam dalam seruan kepada perilaku yang baik, dan inilah birokrasi yang diperangi oleh Islam; dan birokrasi terwujud dalam prosedur-prosedur panjang untuk pekerjaan, dan langkah-langkahnya, dan oleh karena itu: Islam menganggap birokrasi ini sebagai penyimpangan dari kesederhanaan dan moderasi yang dicita-citakan Islam dalam seruan kepada perilaku yang baik.
Ini selain bahwa pemborosan dalam mengambil prosedur adalah bentuk pemborosan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana ia menghadapkan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam pemborosannya kepada kemarahan dan murka Allah Subhanahu wa Taala karena ayat mulia berfirman: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Surat Al-An’am: dari ayat: 141) Dan Islam tidak mengambil formalitas dan prosedur kecuali dengan kadar yang diperlukan yang dituntut oleh keselamatan transaksi; maka jika hal itu tidak ada wajib mengabaikannya; untuk memudahkan transaksi dan kecepatannya, dan ayat tentang utang-piutang menegaskan makna ini, karena mensyaratkan penulisan dalam transaksi tertunda; untuk menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi; adapun dalam transaksi tunai maka tidak ada kesulitan dalam melepaskannya; karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Surat Al-Baqarah: dari ayat: 282) Sampai firman-Nya: “Kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.”
Dan makna dari itu: bahwa prosedur atau formalitas yang mendahului transaksi, Islam membatasinya hingga batas maksimal; karena kelebihan di dalamnya sesungguhnya mengakibatkan birokrasi yang diderita oleh administrasi-administrasi modern di berbagai negara; dan oleh karena itu ayat mulia ini -ayat utang-piutang- menjelaskan kepada kita bahwa prosedur persaksian atas utang sesungguhnya adalah untuk utang yang tertunda; adapun jika perdagangan itu tunai dan tidak ada utang maka tidak ada yang menyerukan persaksian ini; dan ini adalah bukti bahwa Islam tidak menginginkan dan tidak menghendaki berlebih-lebihan dalam prosedur pekerjaan, dan langkah-langkah produksinya, dan tidak dengan formalitas dan prosedur yang tidak perlu.
Dan oleh karena itu: Islam memerangi pemborosan dalam menggunakan korespondensi kertas dalam transaksi; dan itu mewakili penyakit terburuk administrasi, yang mencerminkan kecenderungan pada komplikasi kekantorian, ciri birokrasi yang dominan di negara-negara berkembang, kita dapati Islam menyeru untuk memudahkan pekerjaan dan menyederhanakannya, dan mengingkari ketegaran dan kefanatikan dalam pekerjaan, dan inilah yang dapat dipahami dari hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini kecuali ia akan dikalahkan, tetapi luruskanlah, dan dekatkanlah, dan bergembiralah, dan mintalah pertolongan dengan (perjalanan) pagi dan sore, dan sedikit dari perjalanan malam” karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyeru pada kesederhanaan dan moderasi dalam ibadah tanpa ketegaran, atau kelalaian, dan tidak diragukan bahwa semua pekerjaan sesungguhnya termasuk dalam ibadah.
Dan sesuai dengan konsep ibadah yang menyeluruh -yang telah kita simpulkan sebelumnya- pelayanan publik termasuk dalam ibadah yang wajib secara akidah, penentuan prosedur pelaksanaannya dengan cara yang tidak mengakibatkan kesulitan atau kelelahan bagi para pemintanya; dan tidak merusak keselamatan dan kualitas penyelesaiannya, yaitu: tanpa berlebihan, atau mengurangi.
Dan berkaitan dengan penguasaan pekerjaan dan penyederhanaannya bahwa pekerjaan harus sesuai kemampuan; sebagai pelaksanaan kaidah Islam yang humanis: tidak ada pembebanan kecuali sesuai kemampuan, dan dalam hal itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Surat Al-Baqarah: dari ayat: 233) Dan firman-Nya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Surat Al-Baqarah: dari ayat: 286) Dan firman-Nya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.” (Surat Al-Baqarah: dari ayat: 286) Maka tidak ada kelelahan yang membahayakan pekerja secara jasmani, atau mental.
Dan kita menyimpulkan dari uraian di atas bahwa Islam mensyaratkan dalam pekerjaan yang baik secara intelektual harus memiliki ciri penentuan tujuan atau sasaran-sasaran yang ingin dicapai, serta persiapan sebelumnya, yaitu perencanaan untuknya. Secara perilaku diperlukan agar pelaksanaannya dilakukan dengan sempurna, sederhana, dan memungkinkan untuk dilakukan.
Sifat Pembentukan Organisasi
Kemudian sekarang kita berbicara tentang topik lain yaitu: sifat pembentukan organisasi.
Yang kami maksud dengan organisasi adalah kelompok yang melakukan pekerjaan tertentu, seperti orang-orang yang berada di pabrik tertentu. Keseluruhan orang-orang ini dalam aturan administrasi dan administrasi umum disebut: organisasi. Organisasi adalah susunan di mana dan melaluinya dilaksanakan aktivitas manusia kolektif yang menjadi objek pengorganisasian administratif. Organisasi mencerminkan dari segi sifat pembentukannya dua arah pemikiran administrasi kontemporer, dan kita telah menguraikan sebelumnya konsep-konsep arah pemikiran administrasi dalam hal ini.
Selanjutnya kami menunjukkan arahan pemikiran administrasi Islam yang baik dalam pembentukan organisasi, yaitu bagaimana mengorganisir kelompok yang melakukan pekerjaan tertentu di pabrik tertentu atau di perusahaan tertentu, keseluruhan individu-individu yang bekerja di tempat ini, atau di pabrik ini, atau di perusahaan ini disebut sebagaimana telah kami katakan dalam istilah administrasi: organisasi. Islam telah meletakkan arahan untuk organisasi ini dan bagaimana pelaksanaan kerja di dalamnya.
Hal pertama yang diserukan adalah: hierarki kepemimpinan. Islam telah membentuk organisasi sebagai pengorganisasian kolektif apapun bentuknya dan bidang aktivitasnya, berdasarkan hierarki kepemimpinan sebagai poros pengorganisasian struktural, untuk mewujudkan kepentingan organisasi dan anggota-anggotanya, serta mencapai tujuan bersama. Islam menganggap hierarki kepemimpinan ini sebagai ujian bagi kita, baik sebagai atasan maupun bawahan, karena mengungkapkan sejauh mana penggunaannya dalam mengeluarkan perintah-perintah yang mengikat yang mewujudkan kepentingan kelompok dan anggota-anggotanya secara bersamaan, serta ketaatan bawahan kepada mereka dengan mematuhi perintah-perintah ini dan bekerja sesuai dengannya. Ini adalah pengorganisasian fitrah yang mengupayakan kepentingan kelompok dan individu secara sama, karena memenuhi kebutuhan individu melalui aktivitas-aktivitas manusia kolektif yang diatur dan dikendalikan oleh hierarki kepemimpinan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu” (Surat Al-An’am ayat 165). Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan Kami telah mengangkat sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempekerjakan sebagian yang lain” (Surat Az-Zukhruf ayat 32). Ayat-ayat ini menunjukkan adanya hierarki.
Namun jika fitrah Allah menetapkan mengangkat sebagian manusia di atas sebagian yang lain beberapa derajat, yaitu dalam hierarki kepemimpinan, apakah hierarki ini berarti ada kelas-kelas sosial yang berbeda dan istimewa? Dan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan Islam yang manusiawi. Kenyataannya hierarki kepemimpinan ini tidak didasarkan pada kedudukan kelas yang otoriter dalam masyarakat, melainkan didasarkan pada pekerjaan, dan hanya itu sumber nilai kemanusiaan sebagaimana telah kami katakan sebelumnya. Karena individu-individu berbeda secara alami dalam pemahaman, kemampuan, dan kecakapan, maka mereka akan berbeda pula dalam tingkat pekerjaan dan pelaksanaannya. Hierarki kepemimpinan di sini didasarkan pada hierarki dan perbedaan pekerjaan, dan inilah yang dijelaskan Allah Tabaraka wa Ta’ala dengan firman-Nya: “Dan bagi masing-masing ada derajat dari apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (Surat Al-An’am ayat 132). Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “Dan bagi masing-masing ada derajat dari apa yang mereka kerjakan. Dan agar Dia mencukupkan kepada mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan” (Surat Al-Ahqaf ayat 19).
Tetapi apa dasar perbedaan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka? Dan dengan demikian hierarki mereka menurut pekerjaan-pekerjaan ini? Al-Quran Al-Hakim menjelaskan bahwa hal itu kembali kepada perbedaan dalam pengetahuan dan pengalaman, yang sumbernya adalah ilmu. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui” (Surat Yusuf ayat 76). Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan” (Surat Al-Mujadalah ayat 11). Karena pekerjaan dianggap sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan dalam Islam, maka individu-individu akan dibedakan sesuai dengan hierarki pekerjaan mereka dalam rezeki dan pendapatan, berupa upah dan keuntungan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam hal ini: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam rezeki” (Surat An-Nahl ayat 71). Dengan demikian kita menyimpulkan arahan-arahan dalam bidang pemikiran administrasi:
- Bahwa pembentukan fitrah kelompok, apapun bentuk dan sifat aktivitasnya, yang menjamin kelangsungan keberadaannya dengan mewujudkan tujuan-tujuannya dan memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, dasar dan pondasinya adalah hierarki kepemimpinan di antara anggota-anggotanya, sebagai poros pengorganisasian strukturnya, dan berdasarkan hal itu ditentukan kesatuan kepemimpinan dan pengarahan.
- Bahwa dasar hierarki kepemimpinan dalam organisasi adalah hierarki pekerjaan, yaitu jabatan dan profesi. Mewujudkan hierarki pekerjaan ini dalam setiap kelompok memerlukan studi terhadap berbagai pekerjaan di dalamnya, analisis masing-masing pekerjaan menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya, deskripsinya berdasarkan hal itu, penentuan pengetahuan teoritis dan praktis yang harus tersedia pada orang yang melaksanakan setiap pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan ini. Karena pekerjaan dalam Islam adalah sarana untuk memperoleh penghasilan dan sumber pendapatan yang sah, maka upah dan gaji dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkannya pekerjaan-pekerjaan dinilai dan dihierarki, sehingga upah atau gaji terkait dengan pekerjaan dalam keberadaan dan ketiadaan, tingkat dan jumlah, sebagai pelaksanaan firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik” (Surat Al-Kahfi ayat 30). Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “Dan sungguh akan Kami berikan kepada mereka balasannya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Surat An-Nahl ayat 97). Ini adalah kaidah upah yang setara dengan pekerjaan yang dianut oleh pemikiran administrasi Barat kontemporer, dan darinya muncul teori-teorinya yang berbeda dalam mengaitkan upah dengan produksi.
Selama hierarki dalam pekerjaan didasarkan pada perbedaan dalam ilmu dengan makna terluas dari kata ilmu, yaitu pengetahuan mutlak, baik teoritis maupun praktis, yang berbeda dalam jenis dan durasinya, maka harus disediakan kesempatan kerja untuk semua sesuai dengan kemampuan dan bakat pribadi, baik di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, atau pusat-pusat dan program-program pelatihan, dengan berbagai tahapan, spesialisasi, dan metodenya.
Dan kita cukupkan sampai di sini dari perkuliahan ini, saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian.
2 – Arahan Pemikiran Islam (2)
Lanjutan Sifat Pembentukan Organisasi
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du.
Kita telah berbicara dalam perkuliahan sebelumnya tentang sifat pembentukan organisasi, atau kelompok yang melakukan suatu pekerjaan. Dan telah jelas bagi kita bahwa di antara arahan pemikiran administrasi Islam untuk organisasi adalah harus ada hierarki kepemimpinan di antara anggota organisasi ini, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dan kita lanjutkan pembicaraan sekarang tentang arahan lain untuk organisasi ini yaitu: wewenang dan tanggung jawab.
Maka kami katakan: terkait dengan hierarki kepemimpinan adalah penentuan batasan wewenang dan tanggung jawab dalam berbagai tingkat hierarki ini, dan sepanjang apa yang dikenal dalam administrasi sebagai “garis wewenang”. Wewenang berarti kemampuan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan atau tindakan akhir, yaitu yang mengikat orang lain yang harus melaksanakannya dan bekerja berdasarkannya, sebagai ketaatan kepada sumbernya. Pemilik wewenang adalah ulil amri (pemegang urusan), yang Al-Quran Al-Karim mewajibkan ketaatan kepada mereka, mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” (Surat An-Nisa ayat 59).
Dan inilah yang diulang oleh Sunnah Nabi yang mulia sebagai penegasan, menghapuskan setiap pembedaan ras, etnis, atau kelas yang mungkin dijadikan alasan untuk menggagalkan perintah wajib ini, ketika Rasul yang mulia bersabda: “Dengarlah dan taatlah, walaupun yang diangkat menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habasyah yang kepalanya seperti kismis”. Ini adalah kesetaraan dalam bentuk kemanusiaan yang paling mulia. Islam tidak menggunakan istilah wewenang dalam hal ini, untuk menghindari kesan kecenderungan penguasaan dan otoritarianisme yang dikritik dalam pemikiran administrasi ilmiah, dan yang dicoba diperingan dampak buruknya oleh pemikiran administrasi humanistik.
Dan cukup bagi Islam dalam hal ini bahwa ia memerintahkan, demi keteraturan kelompok dan kedisiplinan anggota-anggotanya, untuk menjaga eksistensinya, untuk menaati ulil amri dalam kelompok, yaitu pemegang wewenang yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mengikat. Wewenang dalam administrasi disertai dengan tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Satu tidak ada tanpa yang lain, artinya wewenang harus bertanggung jawab, harus ada tanggung jawab. Tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab.
Dan Islam mengambil prinsip kerja yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab di sini bersifat personal. Setiap orang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan tangannya, dan tanggung jawabnya tidak berpindah kepada orang lain. Ini dijelaskan dalam ayat-ayat mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (Surat An-Nahl ayat 93). Dan Allah Ta’ala berfirman: “Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya” (Surat Ath-Thur ayat 21). Dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Setiap jiwa terikat dengan apa yang dikerjakannya” (Surat Al-Muddatstsir ayat 38). Dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan tidaklah setiap jiwa memikul (dosa) melainkan atas dirinya sendiri, dan tidak seorang yang berdosa memikul dosa orang lain” (Surat Al-An’am ayat 164). Dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Katakanlah: ‘Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kamu perbuat'” (Surat Saba ayat 25).
Dan tanggung jawab dalam Islam tidak terbatas pada aktivitas fisik, tetapi juga mencakup aktivitas mental. Allah Jalla Jalaluhu berfirman: “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (Surat Al-Isra ayat 36). Manusia bertanggung jawab dalam pikiran dan perilaku. Rasul yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam mengaitkan antara wewenang dan tanggung jawab secara humanistik dan sosial, di mana wewenang mengambil konsep fitrahnya yang benar yang dikenal umat manusia sejak awal dalam sel pertama masyarakat yaitu keluarga. Ini adalah pengayoman urusan orang lain dan pelayanan kepada mereka. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadits: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya”. Pemimpin (imam) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”. Ini adalah arahan tertinggi pemikiran Islam dalam bidang administrasi, yang di hadapannya pemikiran lainnya menjadi kecil, bagaimanapun kita memberikan kepadanya dan kepada pelopornya kesucian ilmiah.
Kemudian sekarang kita berbicara tentang keterkaitan sosial di antara anggota organisasi ini:
Maka kami katakan: Islam menyeru kepada ikatan persaudaraan di antara anggota kelompok, untuk menumbuhkan kesatuan perasaan di antara mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Surat Al-Hujurat ayat 10). Dan Allah mengingatkan kaum Muslimin tentang nikmat saling menyayangi, Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara” (Surat Ali Imran ayat 103). Dan Allah Jalla wa ‘Ala memerintahkan kita untuk bersatu, dan melarang perpecahan, Allah berfirman: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan jangan kamu bercerai-berai” (Surat Ali Imran ayat 103). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala memperingatkan kita dari akibat buruk perselisihan, Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang” (Surat Al-Anfal ayat 46). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menunjukkan bahwa bukan dari akal sehat jika kelompok saling membelakangi dan anggota-anggotanya berselisih, Allah berfirman: “Kamu mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti” (Surat Al-Hasyr ayat 14).
Dan hadits-hadits Nabi yang mulia datang menjelaskan manifestasi keterpaduan sosial ini dan metode-metodenya; sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzhaliminya, dan tidak boleh menyerahkannya (kepada musuh). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan barangsiapa melepaskan seorang muslim dari kesusahan, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat.” Dan beliau juga bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh mendustakannya, dan tidak boleh menghinakannya. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram: kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Takwa itu di sini -dan beliau menunjuk ke dadanya- cukuplah seseorang dikatakan buruk jika ia meremehkan saudaranya sesama muslim.” Demikianlah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan kepada kita.
Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mempersamakan keterpaduan sosial ini dan kekuatannya dengan jasad pada satu waktu, dan dengan bangunan pada waktu lain, maka beliau bersabda: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, belas kasih, dan simpati mereka adalah seperti satu jasad; jika satu anggota mengeluh sakit, maka seluruh jasad ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam.” Sebagaimana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya -dan beliau mengaitkan jari-jarinya-.”
Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganggap keluar dari jamaah dan memisahkan diri darinya sebagai kemurtadan jahiliyah; maka beliau bersabda: “Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu meninggal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.” Sebagaimana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejengkal lalu meninggal, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah.”
Dan juga di antara perkara atau arahan yang ditetapkan Islam untuk anggota organisasi atau kelompok ini yang melakukan pekerjaan tertentu adalah: saling bertukar musyawarah di antara individu-individu kelompok ini; karena Islam tidak membatasi seruan kepada keterpaduan sosial hanya pada aspek perilaku saja, bahkan meluas ke aspek pemikiran, yaitu dengan menyeru anggota kelompok untuk saling bertukar musyawarah di antara mereka, maka Allah Yang Maha Mulia berfirman: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (Asy-Syura: 38) sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam urusan keluarga yang paling penting yaitu memutuskan ikatan perkawinan: “Kemudian jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” (Al-Baqarah: 233) dan ini mewujudkan keterkaitan pemikiran dalam hubungan horizontal antara anggota kelompok satu sama lain, dan antara mereka dengan anggota kelompok-kelompok lain dalam seluruh urusan yang menyangkut mereka.
Dan Islam mewujudkan keterkaitan pemikiran ini dalam hubungan vertikal juga, sebab ia memerintahkan untuk saling bertukar musyawarah antara pemimpin dan bawahan dalam berbagai tingkat kepemimpinan dalam kelompok -yaitu: organisasi- sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada Rasul-Nya yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam dan sebagai arahan umum bagi seluruh pemimpin dan kepemimpinan: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Ali Imran: 159).
Islam jika membangun masyarakat dalam pengelolaan dan pengaturan urusan mereka, dengan menentukan sumber kepemimpinan di dalamnya, membangun masyarakat-masyarakat ini atas dasar musyawarah dan tukar pendapat, pemimpin bermusyawarah dengan bawahan, penguasa dengan yang dikuasai, dan tekad dalam perbuatan adalah atas apa yang dicapai melalui jalan musyawarah; Islam menetapkan ini dan menjadikannya sebagai urusan kaum muslimin dalam masyarakat mereka. Kenyataannya adalah bahwa saling bertukar musyawarah antara berbagai pekerja dalam organisasi tidak hanya mendukung kolektivitas pemikiran dan saling pengertian di antara mereka; bahkan mengembangkan kepribadian setiap individu, meningkatkan moralnya, dan menumbuhkan rasa memiliki dan loyalitasnya terhadap organisasi, karena ia berpartisipasi dengan pendapat dalam apa yang terjadi dari urusannya.
Dan Rasulullah yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan pendapat ketika diminta, dan hendaknya itu dengan amanah, dalam hal itu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang dimintai nasihat adalah orang yang dipercaya.”
Demikianlah Islam meletakkan bagi kita fondasi pembentukan struktural organisasi, dan membimbing kita kepada metode-metode efektif; untuk mewujudkan keterpaduan individu kelompok secara perilaku dan pemikiran, dalam pendekatan yang teratur dan lurus, yang tidak pernah dicapai oleh pemikiran administratif kontemporer dalam dua arah ilmiah dan kemanusiaannya yang ekstrem.
Pengawasan dan Tindak Lanjut Pencapaian
Dan di antara arahan pemikiran administratif Islam juga adalah: arahannya dalam bidang pengawasan dan tindak lanjut pencapaian.
Islam telah bersungguh-sungguh meletakkan arahan yang menjamin pengawasan diri dan tindak lanjut yang sadar terhadap perilaku manusia; yang muncul dari kebutuhan kelompok untuk menjaga keselamatan wujudnya; untuk menjamin kelangsungannya dalam pertumbuhan dan kemajuan, mewujudkan tujuan-tujuannya dalam memenuhi kebutuhan kolektif dan individual secara bersamaan; dan itu sesuai dengan apa yang akan kami jelaskan dalam pemaparan singkat kami tentang beberapa arahan ini -yaitu: arahan pemikiran administratif Islam- berkaitan dengan pengawasan dan tindak lanjut pencapaian:
Pertama: Pengawasan Diri:
Telah disebutkan sebelumnya bahwa pendekatan lurus Islam mengharuskan ia menjadi agama dan dunia; dan ini berarti bahwa ibadah di dalamnya memiliki konsep yang menyeluruh dan terpadu, karena artinya: mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dalam seluruh urusan dunia dan agama, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur’an Al-Hakim, dan dijelaskan oleh sunnah Nabi kami shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai sumber yang mensyariatkan, yang meletakkan bagi kami aturan perilaku dan pemikiran Islam yang lurus. Dan karena aturan-aturan ini menargetkan kebaikan umat manusia dalam urusan dunia dan agama; maka Islam bersungguh-sungguh agar kaum muslimin berkomitmen pada aturan-aturan ini, melalui jenis pengawasan diri yang dasarnya adalah: saling menasihati di antara mereka, dengan saling memerintahkan kebaikan dan saling melarang kemungkaran, dan dengan itu mereka mewujudkan masyarakat yang utama, dan mereka menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan ayat-ayat Al-Qur’an Al-Majid menegaskan makna-makna luhur ini, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar” (At-Taubah: 71) sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104) dan Allah Ta’ala berfirman: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah” (Ali Imran: 110).
Dan Rasulullah yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pentingnya nasihat sebagai dasar yang menjadi tumpuan pengawasan diri ini; maka beliau bersabda: “Agama adalah nasihat, untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh mereka.” Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala memperingatkan dari buruknya akibat membiarkan kemungkaran merajalela tanpa melarangnya; maka Allah Ta’ala berfirman: “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu” (Al-Ma’idah: 78-79) sebagaimana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan metode melarang kemungkaran dan mengubahnya, dan menjadikannya sesuai dengan kemampuan, maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.”
Sesungguhnya pengawasan diri ini adalah alat perubahan perilaku yang diyakini Islam; untuk mengembangkan masyarakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar-Ra’d: 11).
Dan pengawasan ini telah menjadi dasar sistem hisbah yang dikenal dalam administrasi publik di negara Islam, dan penerapan pengawasan ini di tingkat organisasi dan proyek mewujudkan: reformasi administratif yang diharapkan secara spontan, sebagaimana penerapannya di tingkat negara mewujudkan apa yang ditargetkan yaitu pengembangan sosial.
Dan yang berkaitan dengan pengawasan dan tindak lanjut pencapaian adalah: tindak lanjut pencapaian juga, karena Islam mengakui prinsip: tanggung jawab seseorang atas perbuatannya dalam kehidupan dunia, dan ini adalah tanggung jawab yang menemukan dasar akidahnya dalam iman kepada hari perhitungan; hari ketika Allah menghitung perbuatan manusia dan membalas mereka: baik dengan pahala surga atau siksa neraka, karena Dia Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Meliputi, Maha Melihat, Maha Mengetahui perbuatan mereka, dan Maha Mengawasi mereka, dan ini ditegaskan oleh banyak ayat Al-Qur’an Al-Hakim, di antaranya firman-Nya Ta’ala: “Dan adalah Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan” (An-Nisa’: 108) dan Allah Ta’ala berfirman: “Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Ali Imran: 156) dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 234) dan Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengawasi kamu” (An-Nisa’: 1).
Dan dalam cahaya tindak lanjut ilahi ini terhadap seluruh perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa Ta’ala membimbing kita untuk melakukan tindak lanjut pencapaian semacam ini dengan pengetahuan kita secara duniawi; dan ini ditunjukkan secara tegas oleh firman-Nya Ta’ala: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (At-Taubah: 105) sebagaimana ditunjukkan secara tersirat oleh firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat(kan kepadanya)” (An-Najm: 39-40).
Dan kami menyimpulkan dalam cahaya arahan-arahan yang telah dijelaskan bahwa selama pekerjaan dan usaha manusia dalam kehidupan ini adalah sumber nilainya dan tempat bergantung tanggung jawabnya; maka wajib pekerjaan ini dilihat oleh orang lain, dengan mengikuti berbagai cara tindak lanjutnya, baik melalui pengawasan dan apa yang diperlukannya dari keterampilan kepemimpinan, atau evaluasi pencapaian berdasarkan laporan kegiatan berkala, dan pelaksanaan inspeksi dan pengawasan dalam berbagai jenis dan aparatusnya, maka harus ada metode tindak lanjut yang aktif; yang menghitung kegiatan pekerja, dan menindaklanjuti usahanya untuk mengevaluasinya dari waktu ke waktu, dalam cahaya standar yang akurat dan diketahui, dan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan untuk biaya dan kinerja.
Dan yang juga berkaitan dengan pengawasan dan tindak lanjut pencapaian adalah: penetapan aturan dan standar, karena Islam menyeru -sebagaimana telah disebutkan- untuk komitmen terhadap pemikiran dan perilaku yang lurus dan benar, yang tidak mengenal berlebihan atau kekurangan, tidak menyimpang atau ekstrem, yang mengharuskan pengaturan dan pembakuan kegiatan-kegiatan manusia, sesuai dengan aturan tertentu dan standar yang ditetapkan dan diketahui, yang dipatuhi oleh individu, dan mereka dimintai pertanggungjawaban atas dasarnya; dan oleh karena itu harus ditetapkan aturan dan standar pencapaian untuk menimbang pekerjaan, dan pekerja dinilai atas dasarnya berdasarkan laporan kegiatan, dan ini menjadi sandaran pengawasan dan tindak lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah terbarunya dan metode teknisnya.
Dan bagi kita dalam arahan Al-Qur’an Al-Hakim adalah sebaik-baik pembimbing dalam hal ini; karena Allah menciptakan alam semesta, menyempurnakan ciptaan-Nya, dan mengatur perjalanannya dengan cermat, sesuai dengan aturan yang tepat yang telah Dia tetapkan, sebagaimana Dia Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Al-Qamar: 49) dan Allah Ta’ala berfirman: “Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” (Al-Furqan: 2) dan Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk tiap-tiap sesuatu itu ukuran(nya)” (Ath-Thalaq: 3) dan Allah Ta’ala berfirman: “Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu” (Al-Hijr: 21) dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui” (Yunus: 5) dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” (Yasin: 39-40).
Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala membimbing kita dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Dia menjalankan dalam penciptaan-Nya terhadap alam semesta dan menjalankannya sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan aturan tertentu yang Dia tetapkan dan putuskan, dan oleh karena itu patut bagi kita dalam cahaya bimbingan ilahi ini bahwa kita berjalan dalam pemikiran dan perilaku kita dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan prinsip dan aturan yang dibimbing oleh akal sehat.
Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta’ala—Yang Maha Mengetahui tabiat manusia dan Maha Mengenal perbuatan mereka—menetapkan standar yang benar dan timbangan yang adil bagi perbuatan manusia, Dia akan menghisab mereka berdasarkan hal tersebut pada hari kiamat, baik berupa pahala maupun hukuman. Dalam hal ini Allah Yang Maha Agung Kekuasaan-Nya dan Maha Tinggi Hikmah-Nya berfirman: “Dan Kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.” (Surat Al-Anbiya: ayat 47) “Dan penimbangan pada hari itu adalah benar. Maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.” (Surat Al-A’raf: ayat 8-9).
Berdasarkan petunjuk Al-Quran dalam menetapkan timbangan amal ini, kita wajib menetapkan standar kinerja dan tolok ukur bagi pekerjaan dalam kehidupan dunia kita, agar pertanggungjawaban dan penghitungan kita atas pekerjaan tersebut bersifat objektif dan akurat. Untuk mengukuhkan pengawasan dan tanggung jawab, pekerjaan harus dihitung dan pencapaian dicatat secara teliti dari waktu ke waktu, lalu didokumentasikan dalam laporan-laporan dan catatan yang terbuka. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Benar berfirman: “Dan setiap manusia Kami tetapkan (amal perbuatannya) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab atasmu.” (Surat Al-Isra: ayat 13-14). Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: ‘Alangkah celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan (mencatat) yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatatnya.’ Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun.” (Surat Al-Kahf: ayat 49).
Inilah prinsip-prinsip dasar Islam yang harus diperhatikan dalam menetapkan dan menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan terbaik, yang menjadi tujuan pemikiran manajemen kontemporer untuk mencapainya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengawasi para gubernur dan pegawainya. Delegasi Abdul Qais pernah mengadu tentang Al-Ala’ bin Al-Hadhrami yang menjadi gubernur Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam atas mereka. Setelah mendengarkan mereka dan memastikan kebenaran pengaduan mereka, beliau memberhentikan Al-Ala’ dan mengangkat Aban bin Sa’id sebagai gantinya, serta memberinya wasiat dengan bersabda: “Perlakukanlah Abdul Qais dengan baik.” Suatu kali beliau mengangkat seorang pria untuk mengurus sedekah. Ketika ia kembali, beliau menghisabnya, lalu orang itu berkata: “Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku.” Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Bagaimana dengan orang yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta’ala percayakan kepada kami, lalu ia berkata: ‘Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku.’ Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ada yang memberinya hadiah atau tidak? Kemudian beliau bersabda: ‘Barangsiapa yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan dan kami beri rezeki (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu adalah penyelewengan (ghulul).'”
Di antara arahan pemikiran manajemen Islam juga: yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Di sini kami mengacu pada beberapa arahan pemikiran Islam dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang dituju Islam untuk memuliakan kemanusiaan manusia, sesuai dengan metode perilakunya yang benar.
Hubungan Kemanusiaan dalam Kerja Kelompok
Mari kita berbicara tentang hubungan kemanusiaan dan pekerjaan:
Islam adalah agama keutamaan dan seruan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta’ala memuji akhlak Rasul-Nya yang mulia dalam firman-Nya: “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak agung.” (Surat Al-Qalam: ayat 4). Dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.” Cukuplah bagi kita menyajikan sebagian arahan Islam dalam hal ini, yang menegaskan perilaku manajemen yang benar, baik dalam bidang hubungan kemanusiaan maupun hubungan masyarakat:
Pertama: Hubungan Kemanusiaan:
Berikut kami paparkan sifat-sifat pribadi individu yang paling penting, yang membentuk etika tertinggi perilaku sosial mereka dalam berbagai bentuk aktivitas manusia kelompok:
Amanah dan keadilan, termasuk hal-hal pertama yang kita bicarakan terkait hubungan kemanusiaan adalah: amanah dan keadilan. Para individu adalah amanah atas apa yang dipercayakan kepada mereka untuk dilaksanakan dari pekerjaan—yaitu: jabatan dan profesi. Pegawai adalah amanah atas kepentingan masyarakat yang berurusan dengannya; amanah atas harta yang berada di tangannya dan barang-barang serta bahan yang menjadi tanggung jawabnya; amanah atas kebenaran data, informasi, dan pendapat yang ia sampaikan kepada atasan; amanah atas bawahannya dengan memberi nasihat dan bimbingan yang tepat kepada mereka, membina mereka dengan latihan dan pelatihan yang diperlukan, serta mengutamakan keadilan dalam memperlakukan, menilai, dan membimbing mereka.
Pekerja adalah amanah atas mesin yang ia operasikan, serta alat dan bahan baku yang ia gunakan. Karena itu, Islam sangat menekankan perintah untuk menunaikan amanah dan mengutamakan keadilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Surat An-Nisa: ayat 58). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menggambarkan orang-orang beriman dengan firman-Nya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.” (Surat Al-Mu’minun: ayat 8). Dan Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Surat Al-Qashash: sebagian dari ayat 26).
Adapun petunjuk Nabi dalam hal ini terwakili dalam perkataan Imam Ali Radhiyallahu ‘Anhu: “Kami sedang duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu datanglah seorang laki-laki dari penduduk Al-Aliyah—Al-Aliyah adalah nama tempat—lalu berkata: ‘Beritahukanlah kepadaku wahai Muhammad, tentang perkara yang paling berat dan paling ringan dalam agama ini.’ Beliau bersabda: ‘Wahai saudara Al-Aliyah, perkara yang paling ringan dalam agama ini adalah: kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Dan yang paling berat wahai saudara Al-Aliyah adalah: amanah. Ketahuilah, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya amanah, sekalipun ia berpuasa dan shalat.'” Penipuan dalam segala bentuk dan jenisnya bertentangan dengan amanah, seperti menyembunyikan cacat barang dagangan dan menampakkan kebaikannya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah melewati seorang laki-laki yang menjual makanan, lalu beliau tertarik dengan penampakannya. Beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan menemukan ada yang basah, lalu bersabda: “Apa ini wahai penjual makanan?” Ia menjawab: “Terkena hujan wahai Rasulullah—artinya: terkena air hujan.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Mengapa tidak kau letakkan di atas makanan agar orang-orang melihatnya? Kemudian beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: ‘Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.'”
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga memerintahkan kita dalam ayat sebelumnya untuk berlaku adil dalam menghukumi di antara manusia, yang mengharuskan kita mengutamakan keadilan dalam tindakan kita dan seluruh perlakuan kita terhadap orang lain, serta dalam menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya, tanpa pilih kasih yang didorong oleh kekerabatan, dan tanpa balas dendam yang dipicu oleh kemarahan. Karena itu Tuhan kita Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah berlaku adil sekalipun dia kerabat(mu).” (Surat Al-An’am: ayat 152). Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.” (Surat Al-Ma’idah: sebagian dari ayat 8). Dan diriwayatkan dari Rasulullah yang mulia sabdanya: “Tidaklah seorang pemimpin sepuluh orang melainkan ia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu, tidak ada yang melepaskannya kecuali keadilan.”
Dan Allah Yang Maha Agung memperingatkan kita agar tidak mengikuti hawa nafsu daripada mengutamakan keadilan, apa pun hubungan dan pertimbangannya, dalam firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Surat An-Nisa: ayat 135). Sebagian orang menafsirkan ayat mulia ini: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang senantiasa menegakkan keadilan, bersungguh-sungguh dalam menegakkannya, melaksanakan kesaksianmu karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kerabatmu. Jika yang disaksikan itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu menahan diri dari menyampaikan kesaksian karena condong kepadanya karena kekayaannya, atau karena kasihan kepadanya karena kefakirannya. Allah lebih tahu tentang keadaan orang kaya dan orang miskin daripada kalian, maka janganlah mengikuti hawa nafsu kalian karena tidak mau berlaku adil. Jika kalian memutar-balikkan dengan lidah kalian untuk menyembunyikan kebenaran atau menolak menegakkan kesaksian, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan membalasnya sesuai dengan yang pantas kalian terima.
Mengharuskan komitmen terhadap keadilan dalam transaksi berarti: menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firman-Nya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surat Al-Isra: ayat 35). Dan Allah memperingatkan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan dengan kecelakaan dan kerugian, dalam firman-Nya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Surat Al-Muthaffifin: ayat 1-3).
Demikianlah Islam mengajak kita untuk berkomitmen pada keadilan dalam seluruh tindakan kita, baik perkataan maupun perbuatan, dalam segala keadaan apa pun pertimbangan dan kondisinya. Hal ini menjamin netralitas dan objektivitas dalam perkataan dan perbuatan kita, serta membebaskannya dari kecenderungan untuk berpihak atau membalas dendam.
Yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan dalam bidang kerja adalah: kerja sama dan kasih sayang. Pekerja dituntut untuk mewujudkan kerja sama dalam seluruh hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, baik di dalam kelompok maupun di luarnya, dari rekan kerja, atasan, bawahan, atau masyarakat yang ia layani, demi mencapai kemaslahatan dan kebaikan bersama bagi kelompok dan anggota-anggotanya. Inilah yang diperintahkan Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Surat Al-Ma’idah: sebagian dari ayat 2).
Dan Nabi kita Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah urusan orang yang kesulitan di dunia, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” Beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang Allah anugerahi nikmat lalu Dia sempurnakan nikmat itu padanya, kemudian Allah jadikan kebutuhan orang-orang kepadanya, lalu ia merasa jengkel—artinya: tidak memenuhi kebutuhan tersebut—maka sesungguhnya ia telah menghadapkan nikmat itu kepada kehilangan.” Kerja sama ini mencapai tingkat tertinggi dalam Islam dengan mewujudkan jaminan sosial dalam bentuk kemanusiaannya yang paling mulia, yang belum dicapai oleh pemikiran manusia dalam doktrin sosial mana pun, ketika Islam memerintahkan orang yang memiliki kelebihan atau surplus dalam sesuatu untuk segera memenuhi kebutuhan orang lain darinya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa yang memiliki kelebihan kendaraan—yaitu: hewan tunggangan—hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memiliki bekal.”
Kerja sama berkaitan dengan kasih sayang, bahkan bertumpu padanya, dan kasih sayang adalah dasar risalah Islam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada Rasul kita—’Alaihish Sholaatu was Salaam—: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Surat Al-Anbiya: sebagian dari ayat 107). Allah Yang Maha Benar Tabaraka wa Ta’ala menggambarkan diri-Nya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah Yang Maha Agung berfirman: “Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.” (Surat Al-A’raf: sebagian dari ayat 156).
Rasulullah yang mulia Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya.” Beliau juga bersabda: “Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan membuatnya buruk.” Kerja sama dan kasih sayang meliputi perilaku individu dengan karakter kemanusiaan yang ditandai dengan kelembutan, baik terhadap manusia maupun hewan. Keduanya—yaitu: kerja sama dan kasih sayang—adalah nilai-nilai kemanusiaan tertinggi dalam Islam yang mewujudkan ikatan sosial yang efektif dan hubungan kerja yang konstruktif.
Yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan dalam bidang kerja yang diarahkan oleh pemikiran manajemen Islam adalah: kesederhanaan dan keseimbangan:
Perilaku yang benar yang dianjurkan Islam mengharuskan kesederhanaan dan keseimbangan dalam pekerjaan dan kedisiplinan, serta bijaksana dalam bertindak. Tidak ada kelalaian atau kekakuan, tidak ada kekikiran atau pemborosan, tidak ada kepasifan atau kekakuan, dan tidak ada kebebasan tanpa batasan atau batas.
Al-Quran Al-Karim telah menetapkan bagi kita kaidah yang benar dalam hal ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta’ala menggambarkan orang-orang beriman dengan firman-Nya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (Surat Al-Furqan: ayat 67). Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.” (Surat Al-Isra: ayat 29). Tidak diragukan lagi bahwa kaidah bijaksana ini bertentangan dengan pemborosan yang menyebabkan banyaknya kerugian dan pembuangan harta, usaha, waktu, dan bahan, serta berlebihan dalam menggunakan prosedur dan surat-menyurat tanpa keperluan, melampaui alokasi dana, dan tidak hemat dalam menggunakan apa yang dimaksudkan untuknya. Karena itu, Al-Quran Al-Karim melarang pemborosan dalam lebih dari satu ayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Surat Al-A’raf: sebagian dari ayat 21). Allah juga melarang kita mengikuti perintah orang-orang yang berlebih-lebihan, dalam firman-Nya Tabaraka wa Ta’ala: “Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan.” (Surat Asy-Syu’ara: ayat 151-152).
Di antara arahan petunjuk Nabi dalam hal itu adalah: sabda Rasulullah yang mulia Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: “Makan, minum, berpakaian, dan bersedekah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan.” Sesungguhnya komitmen terhadap kesederhanaan dan keseimbangan dalam pemikiran dan perilaku akan menghasilkan pengambilan keputusan yang bijaksana dan tindakan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi yang berkembang, yang dihadapi individu dalam seluruh aktivitasnya.
Dan di antara hal-hal lain yang diperhatikan oleh Islam dalam hubungan kemanusiaan antara orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan bersama: Kejujuran dan Keikhlasan:
Kejujuran berarti: komitmen terhadap kebenaran dan mencarinya dalam perkataan dan perbuatan, dan inilah yang menghasilkan kebenaran data, serta ketepatan informasi dan laporan yang disampaikan dalam berbagai urusan, sehingga rencana dan kegiatan kita berada di atas landasan yang realistis dan benar; oleh karena itu Al-Quran Al-Karim memuji kejujuran dan orang-orang yang jujur, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentang para nabi-Nya—semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepada mereka—: “Dan Kami telah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan untuk mereka lisan yang jujur lagi tinggi.” (Maryam: 50) Sebagaimana Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman: “Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ismail di dalam Kitab (Al-Quran), sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi.” (Maryam: 54) Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan orang-orang mukmin agar menjadi bagian dari orang-orang yang jujur, Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur.” (At-Taubah: 119) Dan kebohongan bertentangan dengan keimanan, sebagaimana Allah Yang Maha Benar Tabaraka Wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta.” (An-Nahl: 105).
Dan juga kemunafikan bertentangan dengan kejujuran, dan Allah telah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang jujur dengan pahala-Nya, dan memperingatkan orang-orang munafik dengan azab-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang-orang munafik jika Dia menghendaki, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Ahzab: 24) Dan Rasul yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat orang munafik, beliau bersabda: “Empat perkara, barang siapa memilikinya maka dia adalah munafik tulen, dan barang siapa memiliki salah satu dari sifat-sifat itu maka padanya terdapat satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya: jika diberi amanat dia berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika bertengkar dia berlaku curang.” Sebagaimana diriwayatkan dari beliau—semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepadanya—bahwa beliau bersabda kepada Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhuma: “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kebohongan itu keraguan, dan kejujuran itu ketenangan.”
Dan kita seharusnya tidak takut mengatakan kebenaran untuk menampakkan kebenaran, sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah rasa takut kepada manusia menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya.”
Sebagaimana bertentangan dengan kejujuran adalah perbedaan antara perkataan dengan perbuatan; oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (Ash-Shaff: 2, 3) Dan ini adalah perkara yang memiliki kepentingan sangat besar, khususnya dalam pernyataan, informasi, dan laporan pencapaian yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan keikhlasan terkait dengan kejujuran, yaitu mensyaratkan bahwa tindakan dan perkataan mengikuti tujuan yang sah, sehingga tidak tercampur dengan penyimpangan darinya, tujuan-tujuan ini yang dasarnya dalam Islam adalah kebaikan, sebagaimana kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam mewujudkannya; oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan bagi masing-masing ada kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.” (Al-Baqarah: dari ayat 148) Dan ini memiliki dampak penting dalam pelaksanaan kekuasaan dan wewenang tanpa penyimpangan.
Dan Al-Quran Al-Hakim memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya.” (Az-Zumar: 2) Dan Allah berfirman: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah: 5).
Inilah hubungan kemanusiaan antara anggota kelompok yang melakukan pekerjaan tertentu.
Cukup sampai di sini, saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian.
3 – Arahan-arahan Pemikiran Islam (3), dan Pengantar tentang Metode Administrasi Islam
Adanya Hubungan Umum antara Anggota Organisasi
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, amma ba’du:
Kita telah berbicara dalam kuliah-kuliah sebelumnya tentang arahan-arahan pemikiran administrasi Islam, dan kami telah menjelaskan bahwa di antara arahan-arahan ini adalah penjelasan bahwa pekerjaan adalah kewajiban umum, dan bahwa pekerjaan memiliki karakteristik tertentu yang harus diperhatikan, dan bagaimana membentuk organisasi yaitu: kelompok yang melakukan pekerjaan tertentu, adanya pengawasan dan tindak lanjut pencapaian, dan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan.
Dan kami melanjutkan dalam kuliah ini pembahasan tentang sisa arahan-arahan ini, maka kami katakan: sesungguhnya di antara arahan-arahan pemikiran administrasi Islam adalah adanya hubungan umum antara anggota organisasi yaitu: kelompok yang melakukan pekerjaan tertentu, kami katakan—dan dengan pertolongan Allah:
Hubungan masyarakat berarti mengembangkan pemahaman yang lebih baik antara kelompok yaitu: organisasi dan para anggotanya yang bekerja di dalamnya, dan antara warga negara yang berurusan dengannya dan yang mendapat manfaat dari layanannya dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Sarana hubungan masyarakat dalam mengembangkan pemahaman ini adalah dengan melakukan survei opini publik di antara mereka yang berurusan dengan kelompok tersebut dan yang mendapat manfaat dari layanannya, menginformasikan kepada mereka tentang layanan yang diberikan kepada mereka, mengedukasi mereka tentang cara memperoleh layanan tersebut, dan mendapat manfaat darinya dengan cara terbaik dengan pelayanan yang baik.
Dan telah dijelaskan kepada kita dalam arahan-arahan Islam dasar akhlak yang benar untuk mengembangkan hubungan ini, dan mencapai pemahaman bersama yang lebih baik antara kelompok manapun dengan mereka yang berurusan dengannya. Prinsip musyawarah dalam Islam yang dasarnya adalah firman Allah Yang Maha Bijaksana Subhanahu Wa Ta’ala: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.” (Asy-Syura: dari ayat 38) Prinsip ini akan mewujudkan pemahaman bersama tidak hanya di antara anggota kelompok saja, tetapi antara kelompok dengan kelompok-kelompok dan individu-individu lain yang berurusan dengannya, dan mendapat manfaat dari kegiatan dan pencapaiannya.
Sesungguhnya penerapan prinsip musyawarah Islam mengharuskan survei opini publik di antara orang-orang yang berurusan ini, untuk mengetahui kebutuhan mendesak dan nyata mereka sehingga dapat dipenuhi dengan cara yang baik dan terbaik sesuai dengan arah opini publik di antara pelanggan dan khalayaknya.
Dan survei pendapat khalayak yang berurusan dengan kelompok harus dilakukan dengan berbagai cara survei opini publik yang dikenal dan tersedia, seperti pers, kuesioner, dan keterlibatan penerima manfaat fasilitas dalam komite-komite penasihat.
Adapun mengumumkan kepada warga negara tentang layanan kelompok yaitu: organisasi, dan mengedukasi mereka tentang cara terbaik untuk memperoleh dan mendapat manfaat darinya, maka inilah yang diperintahkan oleh Islam dalam firman Allah Ta’ala: “Dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik.” (Al-Baqarah: 83) Yaitu: nasihat kepada mereka, dan bukan hanya berarti bersikap lembut dalam perkataan dan ramah dalam berbicara, karena yang baik adalah apa yang bermanfaat dalam agama atau dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, ‘Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik.'” (Al-Isra: 53) Dan Allah Yang Maha Benar Tabaraka Wa Ta’ala menggambarkan sejauh mana dampak bermanfaat yang diwujudkan oleh kata-kata yang baik, Allah berfirman: “Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun.” (Ibrahim: ayat 24 – 26). Dan Nabi kita shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kata-kata yang baik adalah sedekah, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan.” Dan tidak ada yang lebih mendorong terwujudnya pemahaman bersama antara kelompok dengan mereka yang berurusan dengannya selain perlakuan baik para anggotanya kepada mereka, dan inilah yang dianjurkan oleh Islam ketika Rasul yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam menyeru kepada kemudahan dalam transaksi kita, dan keramahan dalam hubungan kita dengan orang lain, beliau bersabda—semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepadanya—: “Semoga Allah merahmati orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli, ketika menagih, dan ketika membayar hutang.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin itu ramah dan disukai, suka meramahkan dan diramahkan, dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak ramah dan tidak diramahkan.”
Sesungguhnya memenuhi kebutuhan orang lain lebih utama daripada beriktikaf untuk beribadah, sebagaimana Rasul yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya salah seorang dari kalian berjalan bersama saudaranya dalam memenuhi kebutuhannya, lebih utama daripada beriktikaf di masjidku ini selama dua bulan.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada mereka yang berinisiatif memenuhi kebutuhan orang lain, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Dia pilih untuk memenuhi kebutuhan manusia, Dia membuat mereka dicintai untuk kebaikan dan membuat kebaikan dicintai oleh mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang aman dari azab Allah pada hari kiamat.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memperingatkan orang yang menghindar dari kebutuhan manusia dengan sabdanya: “Barangsiapa yang Allah berikan kepadanya sebagian urusan kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan mereka, maka Allah akan menghindar dari kebutuhannya pada hari kiamat.”
Penempatan Pegawai Berdasarkan Kepatutan
Dan di antara arahan-arahan pemikiran administrasi Islam adalah bahwa penempatan pegawai harus berdasarkan kepatutan, dan kami katakan dalam hal ini: Arahan-arahan Islam sejak berabad-abad lalu menetapkan komitmen terhadap prinsip kepatutan dalam mengisi jabatan, dan dengan demikian Islam telah mendahului negara-negara Barat maju yang menemukan prinsip ini pada abad yang lalu, setelah lama menderita dari kejahatan sistem nepotisme dan kerusakannya, serta dampaknya dalam melemahkan efisiensi layanan sipil. Dan komitmen terhadap prinsip kepatutan dalam penempatan pegawai dalam Islam terwujud dalam kewajiban mengangkat orang yang paling layak untuk jabatan, dan perhatian untuk mengembangkan efisiensi pemangkunya, dan inilah yang kami paparkan dalam cahaya arahan-arahan Islam yang bijaksana.
Pertama: Mengangkat yang Paling Layak:
Islam menyeru untuk menyerahkan pekerjaan yaitu: jabatan dan profesi kepada orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas, mengamalkan firman Allah Tabaraka Wa Ta’ala: “Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Al-Qashash: dari ayat 26) Dan yang kuat di sini adalah orang yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang diperlukan oleh pekerjaan sesuai dengan sifat dan persyaratan pelaksanaannya, dengan selalu memperhatikan pengangkatan yang paling layak. Rasul yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa diberi wewenang atas suatu urusan kaum muslimin lalu dia mengangkat seseorang, padahal dia menemukan orang yang lebih layak bagi kaum muslimin darinya, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk memimpin sepuluh orang, padahal dia tahu bahwa di antara sepuluh orang itu ada yang lebih baik dari yang dia angkat, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati jamaah kaum muslimin.”
Maka aturan-aturan hukum yang ditetapkan dalam sistem Islam dalam bidang pengangkatan jabatan publik, menekankan pada menjadikan kelayakan sebagai dasar pengangkatan ini, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang tidak layak, atau meninggalkan yang paling layak dan mendahulukan yang kurang layak, artinya jika pilihan jatuh pada salah seorang individu yang diakui kompetensinya, namun kompetensinya ini lebih rendah dari kompetensi orang lain, maka pemilihan dalam kasus ini telah melanggar prinsip syariat dalam Islam.
Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengambil ide ujian sebelum pemilihan, yaitu dalam menyerahkan jabatan kehakiman kepada Mu’adz bin Jabal, dan ini terungkap dari percakapan beliau—semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepadanya—dengan Mu’adz ketika bertemu dengannya, saat beliau bertanya: “Dengan apa engkau akan memutuskan perkara, wahai Mu’adz?” Maka dia menjawab: “Aku memutuskan dengan Kitabullah.” Lalu beliau bertanya: “Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?” Dia menjawab: “Aku memutuskan dengan Sunnah Rasulullah.” Lalu beliau bertanya: “Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah?” Maka dia menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan bermalas-malasan.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam saat itu bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.”
Di sisi lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak menugaskan seseorang pada suatu jabatan hanya karena ia memintanya atau karena bersahabat dengan seorang sahabat mulia, selama orang tersebut tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjabatnya. Dari Abu Musa, ia berkata: “Aku memasuki rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama dua orang laki-laki dari Bani Pamanku. Salah seorang dari mereka berkata: Ya Rasulullah, angkatlah kami untuk memimpin sebagian dari apa yang Allah azza wa jalla telah berikan kepadamu. Dan yang lain mengatakan hal yang serupa. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan mengangkat pekerjaan ini kepada seorang pun yang memintanya atau seorang pun yang bersemangat menginginkannya.”
Dan dikatakan bahwa Abu Dzar al-Ghifari berkata kepada Rasulullah alaihi shallatu wassalam: “Mengapa engkau tidak menugaskanku wahai Rasulullah—maksudnya: menugaskanku pada suatu pekerjaan—maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya di dalamnya.”
An-Nawawi berkata dalam komentarnya terhadap hadits ini: Ini adalah prinsip besar dalam menghindari jabatan, terutama bagi orang yang memiliki kelemahan. Dan termasuk orang yang masuk ke dalamnya tanpa keahlian dan tidak berlaku adil, maka sesungguhnya ia akan menyesal atas kelalaiannya ketika ia dibalas dengan kehinaan pada hari kiamat. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Lalu ditanyakan: Bagaimana penyia-siaannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.”
Demikianlah Islam sangat menjaga agar pengangkatan jabatan didasarkan pada kelayakan, dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat.
Islam telah menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak bekerja dan mendapatkan upah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (An-Nisa: 124). Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.” (Ali Imran: 195).
Yang berkaitan dengan pengangkatan berdasarkan kepatutan adalah pengembangan kemampuan. Petunjuk-petunjuk Islam menegaskan perlunya berbekal ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Petunjuk-petunjuk ini juga mengupayakan memotivasi individu untuk melanjutkan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh dan berijtihad, yaitu dengan berbagai cara pemberian motivasi yang dikenal. Hal ini akan kita bahas dalam bidang pelatihan dan insentif.
Mengenai pelatihan, kita katakan: Pelatihan bermakna membekali kita dengan kemampuan mental dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Ilmu adalah yang membekali kita dengan kemampuan-kemampuan ini dan mengembangkannya. Oleh karena itu, Islam mendorong kita untuk berbekal ilmu dan meminta tambahan darinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam: “Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Thaha: ayat 114). Hal ini dengan menganggap ilmu sebagai titik tolak untuk memperoleh berbagai kemampuan. Ini adalah seruan untuk mengembangkan pengetahuan khusus mengenai seluruh aktivitas kita yang bersifat agama maupun duniawi agar dapat melaksanakannya dengan kompetensi yang diperlukan.
Ilmu di sini memiliki konsep yang luas dan mencakup seluruh pengetahuan teoritis dan praktis yang bermanfaat bagi kita dalam seluruh aktivitas kita. Dengan demikian, ilmu di sini mencakup pelatihan dalam seluruh bidang pekerjaan, yaitu jabatan-jabatan dan keahlian-keahlian, yang mengambil hukumnya dari penghormatan Islam terhadapnya dan terhadap para ahlinya. Al-Quran al-Karim telah memerintahkan kita untuk berbekal darinya melalui tiga cara utamanya, yaitu membaca. Allah Subhanahu berfirman kepada Rasul-Nya yang terpercaya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.” (Al-Alaq: 1). Dan diulang dalam surat Al-Alaq yang sama dengan firman-Nya: “Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Al-Alaq: 3-5).
Juga mendorong untuk menuntut ilmu melalui pengamatan dan observasi dengan melihat, dan inilah yang sering diulang dalam banyak ayat Al-Quran al-Hakim. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.” (Yunus: ayat 101). Dan juga menuntut kita untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat melalui pendengaran. Allah Jalla ‘Ulaahu berfirman: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Az-Zumar: ayat 18).
Rasulullah yang mulia menuntut kita untuk berbekal ilmu secara terus-menerus, dan seberapa pun jauhnya jarak untuk memperolehnya. Beliau bersabda: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.”
Mengenai insentif, istilah insentif merujuk pada sekelompok cara dan rencana yang dapat membangkitkan lebih banyak perhatian individu terhadap pekerjaannya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Islam sangat menjaga ketersediaannya dan memperhatikannya dengan cermat. Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Al-Kahfi: ayat 30). Pahala di sini memiliki konsep yang mencakup seluruh keuntungan yang Allah sediakan bagi hamba-hamba-Nya yang saleh, baik yang bersifat materi maupun moral. Allah Tabaraka wa Ta’ala juga menyoroti ketelitian yang sangat dalam menerapkan insentif ini, baik yang bersifat positif yaitu pahala, atau negatif yaitu hukuman. Allah berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Az-Zalzalah: ayat 7, 8).
Inilah yang dituntut oleh kebijakan insentif yang benar dalam penerapannya, karena setiap ketidakseimbangan dalam timbangan insentif, baik berupa kelebihan atau kekurangan betapapun kecilnya, akan berdampak negatif pada moral para pekerja, pada keteraturan kelompok dan kedisiplinan urusannya, serta pada jalannya aktivitas-aktivitas dalam arah yang benar menuju pencapaian tujuan-tujuannya yang sah dengan efisiensi yang diinginkan. Upah sebagai imbalan materi bagi pekerjaan mencakup seluruh keuntungan tunai dan barang yang memiliki nilai finansial, yaitu insentif finansial. Penetapannya dalam Islam dibedakan dengan kebijakan yang benar, yaitu kaitannya dengan pekerjaan dan produksi. Allah Subhanahu berfirman: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Al-Ahqaf: 19).
Islam mengaitkan insentif pada dasarnya dengan pekerjaan, dan ini menuntut adanya analisis terhadap seluruh jenis pekerjaan yang berdasarkannya ditentukan sifat-sifat pelaksananya, tingkat kinerja, level dan derajatnya. Inilah yang diperjuangkan oleh pemikiran administrasi ilmiah dalam arah terbarunya.
Di sisi lain, Islam memperhatikan agar insentif finansial memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pekerja dan mengamankan pengeluaran keluarganya, karena upah bukan hanya imbalan pekerjaan, melainkan juga pendapatan individu yang menjadi sandaran utama pekerja dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Rasulullah yang mulia shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada yang memiliki tanggungan dua bagian—maksudnya: yang menanggung keluarga diberi dua bagian—dan memberikan kepada yang bujangan satu bagian, maksudnya: yang belum menikah diberi satu bagian. Beliau alaihi shallatu wassalam bersabda: “Barangsiapa yang diberi tugas pekerjaan oleh kami, dan ia tidak memiliki rumah maka hendaklah ia membuat rumah, atau tidak memiliki istri maka hendaklah ia menikah, atau tidak memiliki kendaraan maka hendaklah ia memiliki kendaraan.” Inilah yang diperjuangkan oleh pemikiran administrasi kemanusiaan dalam arah terbarunya juga.
Ini sekali lagi menegaskan arah yang benar dari pemikiran administrasi Islam yang diperintahkan oleh petunjuk-petunjuk Islam. Islam menuntut agar insentif-insentif ini ditentukan dan diketahui terlebih dahulu dengan kewajiban memenuhinya secara langsung agar memiliki pengaruh sebagai pendorong bagi pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya dengan baik. Di antara petunjuk dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah sabda Rasulullah yang mulia: “Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia menyebutkan upahnya”—maksudnya: hendaklah ia menentukan upahnya. Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: “Allah Ta’ala berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, dan barangsiapa yang Aku menjadi musuhnya maka Aku akan mengalahkannya: seseorang yang memberikan (janji) atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya, seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu ia mengambil manfaat penuh darinya tetapi tidak memberikan haknya.” Demikian pula sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
Sistem ini termasuk dari pilar-pilar masyarakat Islam yang berdiri di atas musyawarah dan saling menasihati di antara para anggotanya. Rasulullah yang mulia bersabda: “Agama adalah nasihat; kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada mereka semua.”
Demikianlah Islam mengembangkan gagasan saling menasihati di antara anggota kelompok dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada bawahan, dan usulan-usulan yang diajukan kepada atasan atas dasar kemanusiaan yang benar. Islam menyeru untuk menyediakan insentif sosial yang terwujud dalam pemberian seluruh layanan sosial kepada para pekerja, baik dengan menyediakan istirahat yang diperlukan bagi pekerja sehingga tidak ada kelelahan berlebihan yang membuatnya lelah secara mental dan fisik. Oleh karena itu, Rasulullah kita shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya bagi jiwamu atasmu ada hak, bagi tubuhmu atasmu ada hak, bagi istrimu atasmu ada hak, dan bagi matamu atasmu ada hak.” Demikian pula menyediakan layanan rekreasi bagi para pekerja. Rasulullah yang mulia bersabda: “Hiburlah hati sesaat demi sesaat, karena sesungguhnya jika hati-hati lelah maka ia akan buta.”
Juga jaminan sosial bagi keluarga mereka. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang meninggal tanpa meninggalkan harta, maksudnya: tanpa meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini: “Barangsiapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan keluarga yang terlantar—maksudnya: ahli waris—atau tanggungan—yaitu keturunan yang lemah—maka hendaklah ia datang kepadaku karena aku adalah pelindungnya.” Dengan demikian, beliau menetapkan kewajiban negara dalam menyediakan jaminan sosial bagi warganya untuk mewujudkan prinsip solidaritas sosial Islam.
Islam juga sangat menjaga penyediaan kesempatan kerja bagi mereka yang mampu bekerja untuk mengamankan mereka dari pengangguran. Diriwayatkan oleh Bukhari: “Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau memperhatikan urusannya karena ia menganggur dan tidak memiliki cara untuk mencari nafkah, dan tidak ada padanya apa yang dapat membantunya untuk mendapatkan makanan. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminta kapak dan meminta tongkat kayu lalu mempersiapkannya sendiri, dan memasukkannya ke dalamnya—yaitu: memasukkan kayu ke dalam kapak—kemudian memberikannya kepada laki-laki itu, dan memerintahkannya untuk pergi ke tempat tertentu dan menugaskannya bekerja di sana untuk mencari nafkahnya. Dan memintanya untuk kembali setelah beberapa hari untuk memberi tahu tentang keadaannya. Maka laki-laki itu kembali berterima kasih kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah dilakukannya untuknya, dan memberitahukan kepadanya tentang kemudahan keadaan yang telah terjadi padanya.”
Keberadaan Kepemimpinan yang Benar
Di antara petunjuk pemikiran administrasi Islam adalah keberadaan kepemimpinan yang benar. Dalam hal ini kita katakan:
Islam memberikan perhatian, baik dalam petunjuk-petunjuk dasarnya maupun dalam warisan pemikiran intelektualnya, untuk meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang benar. Inilah yang akan kita tunjukkan secara ringkas sebagai berikut:
Pertama: Kepemimpinan dalam Petunjuk Islam:
- Kebutuhan akan kepemimpinan: Islam menegaskan keniscayaan kepemimpinan sebagai kebutuhan sosial. Diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sabda beliau: “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir—misalnya di gurun—kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” Juga diriwayatkan sabda beliau alaihi shallatu wassalam: “Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.”
Imam Asy-Syaukani berkata dalam komentarnya terhadap dua hadits mulia ini: Bahwa keduanya mengandung dalil bahwa disyariatkan bagi setiap kelompok yang mencapai tiga orang ke atas untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, karena dalam hal itu terdapat keselamatan dari perselisihan yang mengakibatkan kehancuran dan ketersesat. Tanpa pengangkatan pemimpin, setiap orang akan bertindak menurut pendapatnya sendiri dan melakukan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga mereka semua akan binasa. Sedangkan dengan adanya pemimpin, perselisihan akan berkurang dan kata akan bersatu. Dan jika ini disyariatkan untuk tiga orang yang berada di padang pasir atau yang bepergian, maka disyariatkannya untuk jumlah yang lebih banyak yang tinggal di desa-desa dan kota-kota, dan memerlukan penolakan kezaliman serta penyelesaian perselisihan, adalah lebih utama dan lebih layak.
Dalam hal ini terdapat dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa wajib bagi kaum muslimin mengangkat para pemimpin, penguasa, dan hakim. Kepemimpinan diwajibkan oleh Islam untuk menjaga keberadaan kelompok, kekompakan dan kelangsungannya dalam mewujudkan tujuan-tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kolektif dan individual.
- Kewajiban-kewajiban kepemimpinan: Kepemimpinan menurut petunjuk Islam dicirikan sebagai kepemimpinan yang benar, bukan kepemimpinan yang otoriter dan kasar sesuai dengan arah ekstrem dalam pemikiran administrasi ilmiah, dan bukan pula kepemimpinan yang lemah dan tidak peduli sesuai dengan arah ekstrem dalam pemikiran administrasi kemanusiaan. Melainkan kita menemukannya berada di tengah-tengah antara keduanya. Arah yang benar ini dalam kepemimpinan Islam terwujud dalam firman Allah Ta’ala yang ditujukan kepada Rasul-Nya yang mulia, sebagai pemimpin umat Islam: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali Imran: 159).
Berdasarkan arah yang benar ini untuk kepemimpinan yang baik, kita akan membahas kewajiban-kewajiban dasar kepemimpinan dalam Islam, yang mencerminkan karakteristiknya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam pemikiran maupun perilaku.
Musyawarah: Allah telah memerintahkan Rasul-Nya yang mulia dalam ayat sebelumnya untuk bermusyawarah. Ini menuntut pemimpin untuk bermusyawarah dengan anggota kelompoknya dalam keputusan-keputusan yang diambil dan tindakan-tindakan yang dilakukan, yaitu dengan meminta pendapat mereka dalam tahap persiapan keputusan untuk mengetahui pandangan mereka. Maka jika ia sampai pada pendapat yang meyakinkan, ia melaksanakannya dan mengeluarkan keputusan berdasarkan itu. Pemimpin di sini tidak menyendiri dalam mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh kepemimpinan otoriter, dan tidak membiarkan kelompok mengambil keputusan sendiri seperti yang dilakukan oleh kepemimpinan yang lemah. Ini adalah kepemimpinan yang berada di tengah antara individual dan kolektif. Sesungguhnya kewajiban ini membebankan kepada anggota kelompok kewajiban timbal balik untuk bersikap amanah dan ikhlas dalam menyampaikan pendapat ketika diminta dari mereka.
Juga yang harus diperhatikan keteladanan yang baik, karena pemimpin harus menjadi teladan tertinggi bagi kelompoknya dalam pemikiran dan perilaku. Ia adalah panutan mereka yang mereka ikuti dalam tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, ia harus menjadi teladan yang baik dalam setiap ucapan atau perbuatan yang keluar darinya. Rasul yang mulia adalah sebaik-baik teladan bagi kaum muslimin, sebagaimana Allah Yang Mahasuci berfirman: “Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir” (Surat Al-Ahzab: 21). Hal ini mengharuskan anggota kelompok untuk mengikuti pemimpin mereka dan meneladaninya dalam tindakan-tindakannya.
Juga pemeliharaan dan tanggung jawab, karena pemimpin harus berasal dari kelompok atau organisasi yang ia pimpin dan ketuai, berada dalam posisi sebagai pengayom urusan-urusan mereka, peduli terhadap kebaikan dan kemajuan mereka. Ini adalah tanggung jawabnya dalam Islam. Kepemimpinan ini bertanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan kelompok dan para anggotanya serta menjaganya melalui pemeliharaan, bukan dominasi. Pada dasarnya, manajemen tidak lain adalah pemeliharaan urusan orang lain.
Islam mewajibkan pemimpin untuk berpegang pada aspek pemeliharaan dan tanggung jawab mewujudkannya, dengan demikian menghadirkan aspek kemanusiaan dalam kepemimpinan yang sehat dalam bentuknya yang paling tinggi. Ini adalah kepemimpinan yang sadar dan merasakan tanggung jawab sosialnya. Ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh Rasul yang mulia dalam hadits yang terkenal: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”
Memberikan nasihat kepada kelompok: Pemimpin juga harus memberikan nasihat kepada kelompoknya dan para anggotanya, dengan mengeluarkan instruksi-instruksi yang bermanfaat, mengarahkan mereka kepada apa yang baik bagi kelompok dan anggotanya, membimbing mereka untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan memberikan pelatihan yang diperlukan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya dan menjalankan peran aktif mereka dalam mencapai tujuan kelompok, sehingga terwujud kebaikannya. Oleh karena itu Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang Allah amanatkan kepadanya untuk memimpin rakyat, kemudian ia tidak memelihara mereka dengan nasihatnya, melainkan ia tidak akan mencium bau surga.” Pemimpin harus mengutamakan keikhlasan dalam memberikan nasihat kepada kelompok, di samping keikhlasan dalam memeliharanya, sebagaimana Rasul yang terpercaya bersabda: “Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin rakyat dari kaum muslimin, kemudian ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.”
Meyakinkan dengan cara yang baik: Karena kepemimpinan menurut konsep terbarunya berarti mempengaruhi tindakan orang lain, maka pemimpin harus meyakinkan kelompoknya untuk berkomitmen pada tindakan-tindakan yang ia anggap dapat mencapai tujuan mereka. Ia harus berpegang pada aspek hikmah dalam apa yang ia serukan kepada mereka, dan harus pandai berdebat dan berdiskusi dengan mereka. Ini adalah arah yang benar dalam meyakinkan orang lain, kemudian mempengaruhi mereka dalam pemikiran dan perilaku. Ini adalah salah satu keterampilan kepemimpinan penting yang dianjurkan oleh para ilmuwan kontemporer. Kita memiliki petunjuk Alquran sebagai sebaik-baik panduan dalam hal ini, sebagaimana Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman kepada Rasul-Nya yang mulia: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (Surat An-Nahl: dari ayat 125).
Pelajaran 14: Metode Manajerial dalam Islam
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Arahan Pemikiran Islam (3), dan Pengantar tentang Metode Manajerial Islam
Pengantar tentang Metode Manajerial Islam
Setelah kita berbicara tentang arahan manajerial Islam, sekarang kita berbicara tentang metode manajerial Islam yang telah digaris bawahi Islam bagi para pekerja. Metode Islam ini ada dalam perencanaan sebagaimana ada dalam pengorganisasian dan juga dalam pengawasan. Oleh karena itu, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang metode Islam dalam perencanaan.
Perencanaan sebagai fungsi manajerial telah menjadi sangat penting dalam semua pendekatan pemikiran manajerial, karena perubahan kondisi yang mengelilingi organisasi dan kondisi ketidakpastian yang mengelilingi masa depan menjadikan perhatian terhadap perencanaan sebagai kebutuhan vital untuk mencapai tujuan. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, perencanaan menjadi jalan utama yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan masyarakat dan kondisi di sekitarnya, karena ia meningkatkan tingkat kearifan dalam keputusan-keputusan saat ini yang bergantung pada perkiraan masa depan.
Perencanaan adalah aktivitas mendasar bagi sistem apa pun yang ingin meningkatkan kemungkinan keberhasilannya dalam mencapai tujuannya. Ada dua jenis rencana dasar:
Rencana strategis: yang berfokus pada tujuan umum dan cara mencapainya, dan rencana taktis yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan bagian yang melayani tujuan umum. Tidak ada cukup ruang untuk membahas teori-teori perencanaan dan konsepnya. Oleh karena itu, kami cukup menunjukkan bahwa definisi perencanaan yang paling tepat dan ringkas sebagaimana disimpulkan oleh para ahli manajemen dari studi mendalam tentang ide-ide teori-teori ini, dirangkum sebagai berikut: Pencarian alternatif terbaik yang mungkin untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu, dengan mempertimbangkan kemampuan yang tersedia di bawah kondisi dan keadaan yang ada.
Berdasarkan definisi ini, bidang-bidang perencanaan ditentukan sebagai berikut:
- Menentukan tujuan yang ingin dicapai.
- Menentukan cara-cara paling sederhana untuk mencapai tujuan ini, yang disebut menetapkan strategi.
- Menyediakan kemampuan manusia dan materi yang tersedia, dan koordinasi di antara keduanya.
- Memperhatikan faktor waktu ketika menentukan tujuan atau ketika menyediakan kemampuan.
- Menghadapi masalah-masalah yang mungkin menghalangi proses pelaksanaan.
Perencanaan terkait dengan filosofi yang diyakini oleh masyarakat. Filosofi sosial negara adalah yang menentukan bidang-bidang dan tujuan-tujuan di mana aktivitas berlangsung dan di mana perencanaan bekerja dalam lingkupnya. Filosofi sosial di negara Islam sepanjang tahap-tahapnya yang berbeda terwujud dalam tauhid, penghapusan jahiliyah, dan memindahkan manusia dari kegelapan kejahilan menuju cahaya Islam dan iman. Oleh karena itu, tujuan perencanaan secara umum adalah menjaga dakwah Islam dan mewujudkan tujuan-tujuannya yang ditentukan oleh Alquran dan Sunnah.
Yang mengejutkan adalah bahwa perencanaan Islam telah mencakup semua komponen perencanaan ilmiah yang baik. Mungkin dari sisi teori ada jarak dari penamaan yang dikenal sekarang, seperti menentukan masalah atau tujuan, mengumpulkan fakta dan informasi, dan menetapkan solusi alternatif. Namun dalam kenyataannya, ia mencakup semua elemen ini dan masuk ke dalam semua aspek aktivitas. Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi adalah yang menentukan tujuan-tujuan utama dan menyampaikannya kepada Rasul-Nya yang mulia shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya. Beliau shallallahu alaihi wasallam menyusun program dan kebijakan, mempercayakan kepada para sahabatnya untuk mempelajarinya, kemudian bermusyawarah dengan mereka tentangnya, dan mendengarkan mereka dalam semua catatan yang mereka sampaikan.
Hal ini terwujud sepanjang tahap-tahap sejarah Islam, mulai dari turunnya wahyu kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam hingga perencanaan yang sadar dan teliti untuk mengorganisir negara Islam. Sejarah Islam memberikan kepada kemanusiaan contoh-contoh praktis tentang keagungan perencanaan Islam dalam semua bentuk perencanaan, baik manajerial, militer, ekonomi, maupun sosial.
Dalam penelitian ini kami cukup membahas perencanaan manajerial, sedangkan bidang-bidang lainnya tidak cukup ruang untuk membahasnya.
Perencanaan manajerial bertujuan untuk mencapai hasil-hasil tertentu, dan semua rencana pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, perencanaan adalah cara yang digunakan manajemen untuk berpindah dari situasi yang ada ke situasi yang ditargetkan. Keberhasilan rencana bergantung pada pemilihan tujuan yang baik dan kemampuan untuk mendeskripsikannya secara tepat. Perencanaan untuk tujuan dianggap sebagai salah satu jenis rencana manajerial yang paling penting.
Kita akan melihat penerapan Islam untuk perencanaan manajerial melalui tiga model:
Pertama: Perencanaan untuk menyebarkan dakwah Islam.
Model kedua: Perencanaan untuk hijrah.
Model ketiga: Perencanaan kehidupan sipil setelah hijrah.
Kami cukupkan sampai di sini dalam perkuliahan ini. Saya titipkan kalian kepada Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 – Metode Islam dalam Perencanaan
Perencanaan untuk Menyebarkan Dakwah
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du.
Dalam perkuliahan sebelumnya kita telah selesai membahas arahan pemikiran manajerial Islam, dan memulai pembahasan tentang metode manajerial Islam. Kami telah menjelaskan bahwa metode ini dapat berupa perencanaan, pengorganisasian, atau pengawasan.
Sekarang kita berbicara tentang perencanaan untuk menyebarkan dakwah Islam.
Alquran yang mulia telah menentukan tujuan dakwah dalam tauhid dan memindahkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Pengasih. Penentuan tujuan ini adalah elemen pertama dari rencana Islam yang didukung oleh pemeliharaan Ilahi untuk Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam melengkapi komponen-komponennya dan menetapkan garis-garisnya. Beliau menggunakan semua kemampuan yang tersedia dan mempertimbangkan semua kemungkinan masa depan, sehingga rencananya menjadi rapi dalam tujuan, jelas dalam ciri-cirinya sebagai berikut:
Pertama dari ciri-ciri ini untuk perencanaan menyebarkan dakwah: Bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara rahasia di antara keluarga dan suku terdekatnya. Tahap ini berlangsung sekitar tiga tahun. Kemampuan yang tersedia tidak memungkinkan selain kerahasiaan dakwah, karena Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam sendirian, tidak didukung kecuali oleh pemeliharaan Ilahi, di tengah masyarakat yang penuh dengan kezaliman dan kegelapan, merana di bawah tekanan perbudakan terhadap berhala, dengan semboyan bertahan bagi yang terkuat, dan gerakannya didasarkan pada kepentingan pribadi, meskipun merugikan kepentingan masyarakat. Upaya Rasul alaihish shalatu wassalam untuk menghadapi masyarakat ini sendirian secara terbuka sejak hari-hari pertama dakwah adalah sesuatu yang keluar dari batas logika dan akal. Oleh karena itu, hikmah Ilahi menghendaki agar dakwah tetap rahasia selama periode ini hingga Rasul alaihish shalatu wassalam menemukan dari keluarga dan sukunya orang-orang yang berdiri di sampingnya dan membantunya. Pengetahuan tentang sifat masyarakat ini dan pemilihan waktu yang tepat untuk menghadapinya adalah salah satu faktor keberhasilan terpenting dakwah Islam. Tiga tahun ini cukup bagi Rasul shallallahu alaihi wasallam untuk dipenuhi dengan cinta dakwah dan dijiwai oleh keagungan risalah yang ditugaskan kepadanya, hingga beliau berkata kepada pamannya Abu Thalib dalam ucapannya yang terkenal: “Demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya, hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya.”
Sekarang kita membahas ciri kedua dari perencanaan untuk menyebarkan dakwah, yaitu menampakkan dakwah secara terbuka.
Setelah tiga tahun persiapan dan penyiapan untuk dakwah Islam, datanglah izin dari Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi kepada Rasul-Nya untuk menampakkan dakwah secara terbuka dalam firman-Nya: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik” (Surat Al-Hijr: ayat 94). Ayat-ayat terus turun memperkuat tekad dan membimbing langkah, Allah berfirman: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakai kamu, maka katakanlah: ‘Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan'” (Surat Asy-Syu’ara: 214-216).
Rasul shallallahu alaihi wasallam berhasil memanfaatkan semua kemampuan yang tersedia selama tahap ini: harta istrinya Khadijah, perlindungan pamannya Abu Thalib, dan usaha-usaha para sahabatnya yang beriman kepadanya seperti Abu Bakar, Ali, Bilal, dan lainnya. Beliau juga mencoba memanfaatkan rombongan suku-suku Arab yang mengunjungi Baitullah Al-Haram. Beliau mulai menampakkan dakwahnya secara terbuka di antara mereka. Orang-orang Arab karena sifat mereka lebih dekat dengan dakwah ini daripada penduduk Mekah yang dikuasai oleh kemegahan dan kemewahan hidup. Banyak dari mereka yang merespons dan menjadi penolong Islam. Beliau alaihish shalatu wassalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang beliau benar-benar sadari akan menghalangi dakwah dan rencananya, dengan menghadapinya seperti pemimpin yang berani, yaitu beliau menghadapi masalah-masalah ini seperti pemimpin yang berani dan pemilik risalah yang beriman pada risalahnya. Ayat-ayat Alquran turun dari waktu ke waktu untuk menguatkan semangat dan memperkuat tekadnya, Allah berfirman: “Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan” (Surat An-Nahl: ayat 127-128).
Ciri ketiga dari perencanaan untuk menyebarkan dakwah Islam: Dakwah dengan persuasi dan nasihat yang baik. Seandainya seorang laki-laki selain Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari salah satu suku paling mulia di Mekah, dan menyadari bahwa ia diutus oleh Yang Mahakuat lagi Mahakuasa untuk menyampaikan risalah-Nya kepada makhluk-Nya, ditugaskan dengan dakwah ini, ia tidak akan rela menanggung semua yang ditanggung Rasul shallallahu alaihi wasallam demi dakwah tersebut. Ia tidak akan rela jika duri diletakkan di jalannya, kotoran dilemparkan di kepalanya saat shalat, dan melihat para sahabatnya disiksa, sementara ia hanya bisa berkata kepada mereka: “Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga.”
Dan dari celah-celah sejarah kita mendengar suara Nabi Allah Nuh ketika dia berdoa kepada Tuhannya: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (Surat Nuh, ayat 26-27).
Dan kita membandingkan suara yang marah ini dengan suara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah beliau kembali dari Thaif, dan duduk di bawah naungan sebuah kebun, dan air mata mengalir dari kedua matanya, serta darah dari kedua kakinya, sebagai akibat dari apa yang beliau alami dari penduduk Thaif yang beliau kunjungi untuk menyeru mereka kepada Islam, namun mereka tidak merespons beliau, dan mereka mengerahkan anak-anak mereka dan orang-orang bodoh di antara mereka untuk melempari beliau dengan batu. Di tengah perasaan keras dan pahit ini, datanglah Jibril dan berkata kepadanya: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan berkata kepadamu: jika engkau menghendaki, aku akan menutupkan kedua gunung ini atas mereka.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab dengan perkataannya: “Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.” Kita mendengar suara Rasul dalam situasi ini, dan dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa pemilihannya ‘alaihish shalaatu wassalam untuk risalah yang bersifat umum bagi semua manusia, dan bagi seluruh umat manusia bukanlah pilihan yang acak, dan bahwa dukungan Ilahi yang datang kepadanya dari langit telah mengajarinya bagaimana hidup berdampingan dengan masyarakat yang diutus kepadanya, dan bagaimana melaksanakan setiap peran dari peran-perannya pada waktu yang tepat. Sifat risalah Islam pada tahap-tahap awalnya menuntut kelembutan, kebijaksanaan, dan kelapangan dada agar orang-orang tidak menjauh darinya. Oleh karena itu Allah berfirman: “Dan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Surat Ali Imran, dari ayat 159).
Oleh karena itu, tahap ini mengharuskan dakwah dengan persuasi dan nasihat yang baik dan berhenti pada batas ini: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (Surat An-Nahl, dari ayat 125). Dan Rasul yang mulia merespons seruan ini, dan selama tiga belas tahun beliau menyeru kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan menanggung dalam upaya itu apa yang tidak mampu ditanggung oleh manusia lain. Dan kami tidak mengatakan ini secara berlebihan, karena para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah siksaan terhadap mereka semakin berat, meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah melawan orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana Nuh berdoa kepada kaumnya, namun beliau dengan sifatnya yang dipersiapkan untuk risalah, menolak hal itu dengan keras.
Bukhari meriwayatkan dari Qais ia berkata: Aku mendengar Khabbab berkata: “Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau sedang bersandar pada kain, dan berada di bawah naungan Ka’bah, dan kami telah mengalami kesulitan dari orang-orang musyrik, maka aku berkata: Tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Maka beliau duduk dan wajahnya memerah, dan berkata: Sungguh ada orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi, apa yang ada di bawah tulang-tulangnya dari daging atau urat, hal itu tidak memalingkannya dari agamanya, dan gergaji diletakkan di atas ubun-ubunnya, lalu dibelah menjadi dua, hal itu tidak memalingkannya dari agamanya, dan Allah pasti akan menyempurnakan urusan ini hingga seorang penunggang kendaraan berjalan dari Shanaa ke Hadramaut, tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dan serigala terhadap kambingnya, tetapi kalian tergesa-gesa.”
Dan dengan iman kepada keagungan risalah ini, dan bahwa Allah akan menolongnya pada akhirnya, Rasul tetap selama tahun-tahun panjang ini menyeru dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan melarang kekerasan dan peperangan, hingga datang izin dari Allah untuk membalas agresi, setelah Islam memasuki tahap baru.
Dan ini yang mendorong kita untuk membicarakan ciri keempat dari perencanaan penyebaran dakwah, yaitu membalas agresi tanpa memulainya. Kami telah mengatakan: bahwa rencana yang berhasil adalah yang mempertimbangkan faktor waktu, dan menyesuaikan antara kebutuhannya dengan sifat tahap yang dilaluinya. Dan Rasul ‘alaihish shalaatu wassalam telah menerapkan prinsip ini dengan kebijaksanaan dan kepahaman selama tahap-tahap dakwah. Beliau ‘alaihish shalaatu wassalam menghabiskan tiga belas tahun menyeru kepada Tuhannya dengan hikmah dan nasihat yang baik, mematuhi perintah Tuhannya dan melaksanakan firman Allah Ta’ala: “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka.” (Surat Al-Ahqaf, dari ayat 35). Dan para sahabatnya setiap kali mengadukan kepada beliau apa yang menimpa mereka dari siksaan, dan meminta izin darinya untuk berperang, beliau berkata kepada mereka: Bersabarlah karena aku tidak diperintahkan untuk berperang. Dan akhirnya tibalah saat yang tepat, Islam telah menetap di Madinah, dan menjadi kekuatan yang mampu membalas agresi. Juga orang-orang Yahudi Madinah bekerja sama dengan Quraisy, dan mulai membuat tipu daya terhadap Rasul dan dakwahnya, sehingga harus menghalangi mereka. Dan datanglah izin dari langit dengan jelas dan tegas dalam firman Allah Ta’ala: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Surat Al-Hajj, ayat 39-40).
Namun izin ini bukanlah perintah untuk melakukan agresi, melainkan izin untuk membalas agresi. Dan ayat-ayat setelah itu datang menjelaskan makna dan menentukan tujuan: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Surat Al-Baqarah, ayat 190).
Dan mengenai penaklukan-penaklukan Islam, kita dapati bahwa Islam sebagai agama yang bersifat umum dan menyeluruh datang untuk membimbing semua manusia di timur dan barat bumi, sesuai dengan firman Allah Ta’ala: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.” (Surat Saba, dari ayat 28). Dan firman Allah Ta’ala: “Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.” (Surat Al-A’raf, dari ayat 158). Oleh karena itu, pemilik risalah ‘alaihish shalaatu wassalam harus menyampaikannya kepada semua bangsa di bumi. Barang siapa masuk ke dalamnya dengan rela dan ridha maka dia telah dibimbing ke jalan yang benar, dan barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, maka tidak ada paksaan dalam agama, dengan syarat tidak menghalangi jalannya dan tidak menyerang pemeluknya. Barang siapa berpegang pada prinsip ini, maka Islam mewasiatkan untuk memperlakukannya dengan baik. Dan barang siapa keluar dari jalan ini maka Islam memerintahkan kita untuk menghadapinya dan memeranginya. Dan ini adalah filosofi perang dalam Islam, perang-perang yang mulia tanpa ada agresi di dalamnya, tidak ada pelanggaran terhadap kehormatan, tidak ada penyerangan terhadap martabat kemanusiaan, hanya pembelajaran bagi yang berdiri di jalan dakwah hingga dia kembali ke kesadarannya dan mundur dari posisinya. Dan inilah yang disaksikan oleh orang asing sebelum kerabat, dan musuh sebelum teman.
Perencanaan untuk Hijrah
Dan setelah kita selesai dari model pertama perencanaan administratif dalam Islam, yaitu perencanaan untuk penyebaran dakwah Islam.
Kita beralih sekarang ke model kedua, yaitu perencanaan untuk hijrah. Maka kita katakan: peneliti ilmiah yang teliti dan netral tidak memerlukan banyak waktu untuk yakin dengan kenyataan bahwa semua prinsip perencanaan ilmiah telah terwujud dengan jelas dan pasti dalam tahap-tahap hijrah, seolah-olah Islam ingin memberikan melaluinya sebuah model yang patut dicontoh oleh kaum muslimin untuk perencanaan ilmiah yang benar.
Hijrah terlaksana dalam kondisi keras, dan pengepungan dari orang-orang musyrik, dan tantangan gila untuk mencegah terjadinya peristiwa ini yang Quraisy menyadari dampak berbahayanya bagi masa depan dan keberadaan mereka secara keseluruhan. Maka mereka berusaha maksimal untuk menghalanginya. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam didukung oleh pemeliharaan Tuhan, menyusun rencananya untuk menghadapi semua kondisi dan kemungkinan dengan cara yang membuat akal terhenti tidak berdaya di hadapan keagungan kecerdasan kenabian ini.
Tujuan dasar dari hijrah adalah mencari tanah yang layak untuk menegakkan masyarakat Islam setelah Rasul shalawaatullahi wasalaamuhu ‘alaihi yakin bahwa Mekkah bukanlah tanah yang siap untuk memeluk risalah Islam. Dan untuk mencapai tujuan ini, Rasul ‘alaihish shalaatu wassalam mulai mengumpulkan fakta-fakta, dan menggambarkan bidang yang akan dikerjakan di dalamnya. Dan sesuai dengan konsep-konsep administratif modern, langkah berikutnya adalah membandingkan alternatif-alternatif yang tersedia untuk memilih yang terbaik. Dan di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam saat itu ada tiga alternatif:
Alternatif pertama: Hijrah ke Thaif. Alternatif kedua: Hijrah ke Habasyah. Alternatif ketiga: Hijrah ke Madinah.
Dan kita berbicara sekarang tentang alternatif pertama, yaitu hijrah ke Thaif:
Mungkin kota Thaif datang ke pikiran Rasul ‘alaihish shalaatu wassalam sebagai alternatif pertama yang tersedia karena beberapa faktor positif, yang kami sebutkan di antaranya:
- Lokasi Thaif yang unik karena berdiri di tempat yang tinggi di antara kota-kota Hijaz, yang menyediakan bagi penduduknya iklim yang sesuai di samping kelimpahan dalam produksi pertanian.
- Thaif adalah tempat musim panas bagi penduduk Mekkah, dan tempat untuk menginvestasikan keuntungan mereka dari perdagangan.
- Suku Tsaqif Thaif adalah musuh bebuyutan bagi suku Quraisy, bersaing dengannya dalam bidang-bidang keagamaan dan perdagangan. Dan diharapkan bahwa Tsaqif akan bersemangat terhadap Islam untuk mengungguli musuh lamanya. Dan wajar bahwa mereka akan menyambut para muhajirin ini yang diusir Quraisy dari negeri mereka, agar menjadi duri di punggung Quraisy di masa depan. Faktor-faktor positif ini merupakan kekuatan pendorong bagi Rasul dan sahabatnya untuk hijrah ke Thaif.
Namun ada faktor-faktor lain yang negatif, yang beliau ‘alaihish shalaatu wassalam sadari dan beliau melihat bahwa faktor-faktor itu menjadi penghalang bagi penerimaan penduduk Thaif terhadap dakwah Islam. Dan di antara penghalang-penghalang ini:
Rasul ‘alaihish shalaatu wassalam menyadari bahwa suku Tsaqif memiliki kepemimpinan agama di Thaif yang setara dengan yang dimiliki Quraisy di Mekkah, dan bahwa mereka memiliki berhala bernama Al-Laat, dan mereka mendirikan di sekelilingnya tempat suci yang menyerupai Ka’bah, dan menyeru orang-orang untuk berhaji kepadanya. Bahkan mereka mendorong Abrahah untuk menghancurkan Ka’bah, agar hanya mereka yang memiliki haji orang-orang dari segala penjuru bumi. Rasul menyadari bahwa Islam akan mengakhiri penyembahan berhala buta ini, yang merupakan sumber penghasilan tetap bagi Tsaqif, dan bahwa suku ini tidak akan menerima hal itu dengan mudah.
Dan beliau ‘alaihish shalaatu wassalam mengetahui bahwa Tsaqif memiliki kepemimpinan politik di Thaif yang tidak kalah dari kepemimpinan Quraisy di Mekkah, dan bahwa berdirinya negara Islam di Thaif akan mengakhiri kepemimpinan ini, dan ini akan membuat mereka melawan dakwah Islam dengan keras. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam khawatir bahwa Tsaqif akan memandangnya sebagai salah satu anggota suku Quraisy, musuh bebuyutannya, dan tidak memandangnya sebagai pemilik risalah samawi.
Semua faktor-faktor ini dengan positif dan negatifnya ada dalam pikiran Rasul ‘alaihish shalaatu wassalam ketika beliau memikirkan Thaif sebagai salah satu alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan Islam dalam lingkungan yang layak untuk menegakkan masyarakatnya. Namun perjalanan penjajakan yang beliau lakukan bersama budaknya Zaid bin Haritsah, yang tidak memungkinkan untuk membicarakannya di sini, memastikan baginya bahwa situasi tidak sesuai untuk hijrah ke Thaif, dan bahwa itu juga bukan tanah yang cocok untuk menegakkan masyarakat Islam saat itu.
Kemudian kita beralih sekarang untuk membicarakan alternatif kedua, yaitu hijrah ke Habasyah:
Berdasarkan informasi yang tersedia bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kemampuan luar biasanya untuk mempelajari situasi di sekitarnya, menjadi jelas baginya bahwa Habasyah adalah tempat paling sesuai yang tersedia untuk hijrah sementara bagi kaum muslimin, karena beberapa alasan yang kami sebutkan di antaranya:
1 – Habasyah berdasarkan lokasinya jauh dari jangkauan orang-orang musyrik. Juga Quraisy memiliki perdagangan dengan Habasyah yang menghasilkan keuntungan melimpah bagi mereka, yang membuat ada kepentingan bersama di antara mereka yang mencegahnya dari masuk dalam peperangan atau konflik. Juga kepentingan bersama di antara mereka ini mungkin menguntungkan Islam di kemudian hari.
2 – Di puncak kepemimpinan Habsyah ada Raja Najasyi, seorang raja yang terkenal dengan keadilannya, sebagaimana ia terkenal dengan kekuatan kepribadian dan kecerdasan akalnya, yang menjadikannya memiliki bobot internasional. Oleh karena itu, menariknya ke dalam perkara Islam merupakan keuntungan yang sangat berharga, karena ia adalah penganut agama samawi dan memiliki kitab suci. Selain itu, agama Kristen pada masanya tidaklah murni esensinya, melainkan telah masuk ke dalamnya pemalsuan dan perubahan sebagaimana telah masuk ke dalamnya penyembahan berhala, yang menjadikan seorang seperti Najasyi dengan kecerdasan yang terkenal akan yakin dengan Islam ketika ditawarkan kepadanya sebagai agama samawi yang bersih yang belum masuk ke dalamnya pemalsuan.
3 – Dari sisi lain, penelaahan terhadap peristiwa-peristiwa menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap kaum Muslimin dari agama Kristen yang sedang berkembang di Habsyah saat itu, karena agama tersebut penuh dengan ambisi-ambisi dan penyembahan berhala. Dari mana datangnya kekhawatiran terhadap orang-orang yang telah dididik oleh Rasul tentang tauhid, dan menanamkan kebenaran-kebenaran iman di dalam jiwa mereka, sehingga mereka meninggalkan karena Islam negeri-negeri dan harta-harta mereka. Sesungguhnya orang-orang seperti mereka tidak akan menukar Islam dengan Kristen atau yang lainnya, bagaimanapun besarnya godaan-godaan.
Berdasarkan perhitungan yang cermat terhadap situasi ini, Rasul mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah sementara ke Habsyah, dan keputusan kenabian itu dikeluarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabatnya: “Seandainya kalian pergi ke Habsyah, maka sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak seorang pun dizalimi di sisinya, dan itu adalah negeri yang jujur, hingga Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar.” Dan izin ini mengandung dalam kata-katanya semua spesifikasi keputusan yang baik. Pertama: ia menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah hijrah sementara dengan sabdanya: “hingga Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar”, dan oleh karena itu ini bukanlah hijrah permanen.
Kedua: keputusan itu mencakup informasi-informasi yang membuat mereka yang melaksanakannya yakin dengannya. Terdapat dalam sabdanya: “maka sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak seorang pun dizalimi di sisinya, dan itu adalah negeri yang jujur”. Dan rencana hijrah itu mencakup jaminan keberhasilannya pada dua rukun yang ditetapkan oleh Rasul dengan kebijaksanaan pemimpin yang berpengalaman:
Rukun pertama: kepergian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, agar kaum Quraisy tidak mengetahui rencana itu dan menggagalkannya, dan inilah yang disebut dengan faktor kejutan.
Rukun kedua: agar hijrah dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, dan bukan dalam skala luas, agar tidak menarik perhatian kaum musyrikin. Sebagai jaminan untuk mewujudkan kedua sisi rencana tersebut, kaum Muslimin keluar dalam bentuk keluarga-keluarga menuju laut, hingga mereka menaiki dua kapal dagang yang berlayar dengan mereka ke Habsyah. Rencana itu berhasil dengan dukungan Allah dengan sangat gemilang, dan para sahabat Rasul mendapat perlakuan yang baik di Habsyah, serta perlindungan dan keamanan. Islam pun memiliki pendukung di negeri yang baik ini, dan Najasyi dengan segala pengaruhnya bergabung dengan Islam sebagai pendukung. Kesuksesan yang mengagumkan yang tercapai ini membuat sebagian peneliti dan penulis bertanya-tanya: mengapa Rasul tidak memanfaatkan kesuksesan ini dan pindah bersama keluarga dan para sahabatnya ke Habsyah, agar negeri itu menjadi tanah tempat didirikannya masyarakat Islam? Dan mengapa beliau sallallahu alaihi wa sallam bersikeras menjadikan hijrah kaum Muslimin ke sana sebagai hijrah sementara?
Untuk menjawab pertanyaan ini kami katakan: sesungguhnya analisis Rasul sallallahu alaihi wa sallam terhadap informasi yang tersedia baginya, dan kajiannya yang mendalam terhadap situasi menegaskan baginya sulitnya Habsyah menjadi tujuan bagi negara Islam, dan hal itu karena beberapa faktor:
Faktor pertama: bahwa Habsyah adalah wilayah terpencil yang tidak cocok sebagai tempat penyebaran dakwah yang baru, karena Islam sebagai dakwah universal membutuhkan wilayah yang terbuka terhadap dunia, dan Habsyah sepanjang sejarahnya tidak pernah menjadi wilayah peluncuran.
Faktor kedua: bahwa Habsyah tidak akan mengizinkan agama baru ini tumbuh di samping Kristen, dan bangsa Romawi yang saat itu mendominasi Kristen di dunia tidak akan mengizinkan Habsyah untuk itu meskipun rajanya masuk Islam.
Faktor ketiga: bahwa Al-Quran yang mulia turun dengan bahasa Arab dan lisannya, dan oleh karena itu memahaminya, mempelajarinya dan menghafalnya di lingkungan Habsyah ini merupakan perkara yang sulit, dan menjadi rintangan di jalan dakwah.
Karena semua alasan ini dan faktor-faktor ini, Rasul sallallahu alaihi wa sallam mengalihkan pandangan dari Habsyah sebagai tanah untuk hijrah permanen, dan memikirkan alternatif lain. Dan dapat dikatakan: sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam telah mencapai dengan hijrah ini keuntungan maksimal yang mungkin, dan mengambil keputusannya untuk hijrah sementara berdasarkan pengetahuan terbaik yang mungkin tentang masa depan keputusan ini, dan inilah yang menjadi dasar perencanaan ilmiah yang benar.
Kemudian kita berbicara tentang alternatif ketiga, yaitu hijrah ke Madinah, maka kami katakan:
Dari prinsip-prinsip manajerial yang dikenal bahwa semakin bertambah pengetahuan, semakin bertambah kesempatan untuk bertindak dengan benar, dan hal itu membantu keberhasilan keputusan.
Individu yang mengetahui dimensi dan hasil tugas yang dibebankan kepadanya akan lebih mampu bertindak dengan benar, dan keputusan yang benar bergantung pada sejauh mana informasi yang tersedia di hadapan pengambil keputusan, dan pada kemampuan pemiliknya untuk menganalisis informasi ini untuk menghasilkan kesimpulan yang benar.
Rasul sallallahu alaihi wa sallam mengetahui banyak hal tentang masyarakat Madinah, dan beliau mempertimbangkan banyak faktor positif yang membantu mewujudkan tujuan dakwah Islam. Kami sebutkan dari faktor-faktor ini:
1 – Kondisi politik dan sosial Madinah sepenuhnya memungkinkan berdirinya negara Islam di tanahnya. Jika kita kembali sedikit ke belakang untuk mengetahui sejarah Madinah, kita akan menemukan bahwa penduduk aslinya dari bangsa Arab adalah kaum Amaliqah yang dinisbahkan kepada Amliq bin Laud bin Sam bin Nuh. Kemudian datang ke Yatsrib suku-suku Yahudi yang berhijrah dari Palestina. Sebagaimana kebiasaan orang Yahudi, mereka selalu berusaha menguasai sumber-sumber ekonomi dan urusan keuangan di negeri-negeri yang mereka tinggali.
Setelah runtuhnya bendungan Marib, datang ke Yatsrib dua suku Yaman yaitu suku Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi mengizinkan kedua suku ini untuk tinggal di Yatsrib agar mereka menjadikan mereka sebagai tenaga kerja di pertanian-pertanian mereka, seolah-olah mereka budak yang bekerja di bawah sistem feodal. Namun kedua suku ini berhasil lepas dari dominasi ini dan mulai melakukan aktivitas ekonomi mandiri. Maka terjadilah konflik antara bangsa Arab Yaman dengan Yahudi yang berakhir dengan kemenangan suku Aus dan Khazraj. Ketika orang-orang Yahudi melihat hal itu, mereka memainkan permainan kesukaan mereka yaitu menyalakan api fanatisme suku di antara suku-suku Arab, maka terjadilah serangkaian perang antara Aus dan Khazraj yang hampir menghabisi kedua suku tersebut.
Di sinilah masyarakat Madinah menjadi masyarakat permusuhan dan konflik yang mengambil berbagai bentuk. Orang-orang Yahudi membenci bangsa Arab dan berusaha agar kekuasaan di Yatsrib menjadi milik mereka, dan mereka mencela mereka karena menyembah berhala. Suku-suku Arab selain membenci orang-orang Yahudi juga membenci satu sama lain, dan saling berperang untuk masing-masing memiliki kedaulatan atas Madinah. Dengan perang-perang yang dahsyat, masyarakat Yatsrib menjadi sangat membutuhkan nikmat ketenangan dan stabilitas, dan orang-orang mengharapkan dakwah apa pun yang dapat mewujudkan tujuan ini bagi mereka. Dan di antara dampak konflik-konflik ini adalah sebagai berikut:
Orang-orang Yahudi menyebarkan di Madinah bahwa seorang nabi akan dibangkitkan pada zaman ini, dan bahwa mereka yaitu orang-orang Yahudi akan mengikutinya, dan membunuh dengannya bangsa Arab seperti pembunuhan terhadap kaum Ad dan Iram. Ketika bangsa Arab mengetahui berita tentang kerasulan Muhammad, mereka mengetahui bahwa inilah nabi yang diancamkan oleh orang-orang Yahudi kepada mereka. Sebagai jaminan untuk dukungan Quraisy, masing-masing dari Aus dan Khazraj mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk bersekutu dengan Quraisy melawan satu sama lain. Dari takdir Allah dan baiknya perencanaan Rasul sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bertemu dengan utusan-utusan ini, maka banyak dari anggota-anggotanya kembali ke Madinah dengan iman dan cahaya kebenaran, bukan dengan persekutuan jahiliah.
2 – Sebagaimana kondisi politik dan sosial merupakan faktor penting dalam mempersiapkan masyarakat Madinah untuk menerima dakwah Islam, maka Madinah berdasarkan posisinya adalah wilayah peluncuran yang dihuni oleh bangsa Arab, dan penduduknya berbicara bahasa Arab, sehingga dakwah Islam dapat menemukan di sana landasan yang luas dan lisan Arab yang membaca dan menghafal Al-Quran.
3 – Dari perencanaan yang baik dari Rasul adalah beliau mengutus bersama utusan-utusan Madinah yang kembali dari Mekah Mushab bin Umair untuk mengajarkan kepada orang-orang prinsip-prinsip Islam. Mushab berhasil dengan taufik Allah, dan kondisi politik dan sosial Madinah serta kemampuan pribadinya membantunya dalam mempersiapkan iklim kota ini untuk mendirikan masyarakat Islam.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa sallam menyadari faktor-faktor positif yang membantunya dalam mengambil keputusannya memilih Madinah sebagai tempat tinggal untuk hijrah permanen kaum Muslimin, maka beliau tidak mengabaikan faktor-faktor negatif yang mungkin menghalangi tujuan ini atau menjadi rintangan di jalannya, di antaranya:
Bahwa orang-orang Yahudi di Madinah menganggap diri mereka sebagai kaum pilihan Allah, dan meskipun mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wa sallam melalui kitab-kitab mereka sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, namun iri hati membutakan hati mereka, sehingga mereka dendam kepada bangsa Arab karena Rasul dari antara mereka, karena mereka menginginkannya dari Bani Israil. Rasul yakin dari kenyataan pengetahuannya tentang mereka bahwa mereka akan menolak dakwah, melawannya dan menipu dengan segala cara.
2 – Dalam periode gencatan senjata antara suku Aus dan Khazraj yang bersamaan dengan hijrah Nabi, kedua suku sepakat untuk mendirikan pemerintahan bersama yang memerintah Yatsrib dan dipimpin oleh pemimpin Khazraj yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Makna berdirinya masyarakat Islam di Madinah adalah penghapusan pemerintahan seperti ini, dan hal ini membangkitkan kebencian terhadap Islam di hati Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya.
Dengan logika pemimpin yang berpengalaman dan ahli perencanaan yang terampil, Rasul menyeimbangkan antara faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif, dan beliau yakin bahwa hal-hal positif lebih banyak, dan bahwa kesempatan lebih siap daripada waktu lain mana pun untuk hijrah ke Madinah. Maka beliau mulai mempersiapkan iklim dan menyiapkan kondisi yang sesuai untuk mewujudkan tujuan. Maka datanglah rencana hijrah yang sangat rapi dan sangat jelas.
Para ahli perencanaan manajerial berpendapat bahwa di antara faktor keberhasilan suatu rencana adalah pembagian tugas-tugas dan pekerjaan, dan menentukannya dengan tepat, agar setiap orang mengetahui perannya sehingga tidak terjadi pertentangan kewenangan dan tidak tumpang tindih, dan pada saat yang sama tercapai keterpaduan antara kewenangan-kewenangan ini hingga pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Sungguh tugas-tugas yang diperlukan untuk keberhasilan rencana hijrah adalah:
1 – Tugas persiapan dan perlengkapan.
2 – Tugas penyediaan dan perbekalan.
3 – Tugas pengintaian dan komunikasi rahasia.
4 – Tugas bimbingan dan pelacakan jejak.
5 – Tugas pengelabuan dan penyamaran terhadap musuh.
Seandainya perencana adalah orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka diperlukan pasukan besar untuk meliput tugas-tugas ini, dan seandainya yang melaksanakan pekerjaan adalah orang-orang selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka diperlukan tentara yang sangat besar. Tetapi bersama Rasul dan para sahabatnya, urusannya berbeda.
Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu sendirian menanggung tugas persiapan dan perlengkapan untuk hijrah. Ia menyiapkan dua unta untuknya dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan ia membawa serta dalam hijrahnya seluruh hartanya dengan meninggalkan keluarganya dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana ia katakan.
Putrinya Asma radhiyallahu anha menanggung tugas penyediaan dan perbekalan. Ia membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di gua. Ia menanggung banyak pengorbanan demi hal itu. Suatu kali ia memotong pakaiannya dan menjadikannya sabuk untuk membawa makanan kepada mereka berdua, maka Rasul memanggilnya Dzatun Nithaqain (yang memiliki dua sabuk). Ia mengalami pemukulan yang sangat keras dari Abu Jahal ketika ia bertanya kepadanya tentang tempat dua muhajir yang mulia. Ketika ia menjawabnya bahwa ia tidak tahu, ia menamparnya di wajah dengan tamparan yang kuat sehingga ia terjatuh ke tanah karenanya.
Amir bin Fuhairah berkontribusi bersamanya dalam operasi penyediaan. Ia pergi ke gua pada malam hari dan menyediakan kepada Rasul dan sahabatnya kebutuhan mereka dari susu.
Abdullah bin Abu Bakar menanggung peran agen pengintaian. Ia bermalam bersama Rasul dan sahabatnya di gua, dan pada pagi hari bersama Quraisy seolah-olah ia bermalam bersama mereka, kemudian ia kembali dengan berita Quraisy ke gua.
Abdullah bin Uraiqqith, ahli gurun yang berpengalaman dan pemandu hijrah yang amanah, melaksanakan tugas bimbingan bagi para muhajirin di jalan dari Mekah ke Madinah.
Adapun tugas pengelabuan dan penyamaran, Amir bin Fuhairah turut serta di dalamnya, di mana ia berjalan dengan kambing-kambingnya di jalan yang dilalui Rasul dan sahabatnya untuk menghilangkan jejak kaki mereka berdua. Ia tetap melakukan tugas itu setelah setiap perjalanan Abdullah atau Asma, dan menghilangkan jejak kaki.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berpartisipasi dalam tugas ini dengan tidur di tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wa sallam pada malam hijrah untuk membuat Quraisy mengira bahwa Rasul ada di tempat tidurnya dan tidak meninggalkan rumahnya.
Setiap orang yang berpartisipasi dalam hijrah telah melakukan perannya dalam tugas pengelabuan dan penyamaran, yaitu dengan faktor kerahasiaan mutlak yang mereka terapkan pada rencana hijrah sehingga Quraisy tidak dapat mengetahui ciri-cirinya.
Jika kita merenungkan penugasan-penugasan ini, kita akan menemukan bahwa urusan-urusan telah berjalan dengan sangat tepat. Setiap orang dari orang-orang hijrah ditempatkan di tempatnya yang sesuai, semua celah ditutup, semua kebutuhan perjalanan terpenuhi, dan urusan dibatasi pada jumlah yang diperlukan tanpa tambahan atau pemborosan. Semua tugas dilakukan secara rahasia sehingga tidak memberi kesempatan kepada Quraisy untuk mengetahui tempat Rasul dan sahabatnya. Juga dilakukan dengan koordinasi yang mengagumkan sehingga tiga orang yang mendatangi gua pergi ke sana pada waktu yang berbeda, tidak pernah terjadi mereka bertemu. Bukankah kami katakan bahwa peristiwa-peristiwa hijrah layak menjadi kamus bagi prinsip-prinsip perencanaan ilmiah yang benar.
Perencanaan Kehidupan di Madinah Setelah Hijrah
Setelah kita selesai membahas tentang perencanaan hijrah, kita beralih untuk membicarakan tentang perencanaan kehidupan di Madinah setelah hijrah. Maka kita katakan: sejak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mulai merencanakan pembentukan masyarakat Islam yang syiarnya adalah tauhid, metodenya adalah Al-Quran, dan tujuannya adalah mengangkat panji-panji Islam. Dan sebagaimana layaknya seorang perencana yang ahli, Rasulullah memperhatikan sekelilingnya untuk mengkaji realita dan menilai situasi. Beliau mendapati bahwa masyarakat Madinah terdiri dari kelompok-kelompok yang berserakan: Arab, Yahudi, Muslim, dan non-Muslim, Aus dan Khazraj, kelompok-kelompok yang terpisah tanpa ada ikatan di antara mereka. Rasulullah harus memasukkan dalam pertimbangannya pembangunan masyarkat baru yang menjaga bagi semua orang keyakinan agama mereka, nilai-nilai akhlak dan kebangsaan mereka. Dan bertolak dari pemahamannya shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap peran hubungan kemanusiaan dan pengaruhnya terhadap individu-individu masyarakat, maka beliau bekerja untuk mewujudkan tiga tujuan:
Pertama: mengamankan kaum Muslim dan non-Muslim atas kehidupan dan rezeki mereka sehingga orang-orang beriman bertambah imannya, dan orang yang ragu-ragu, takut, dan lemah mau memeluk Islam. Juga menetapkan prinsip kebebasan berkeyakinan dan berpendapat bagi semua golongan masyarakat, maka tidak ada fitnah dalam agama, dan tidak ada kezaliman karena keyakinan atau pendapat. Juga menghapuskan perselisihan golongan antara suku-suku. Dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, rencana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mencakup tiga aspek:
Aspek pertama: Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar. Dengan keinginan darinya shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menghapuskan persaingan kesukuan, menghilangkan cinta diri dan keegoisan, dan mewujudkan semangat kerja sama, jamaah, dan cinta karena Allah, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan kebijakan yang bijaksana, yaitu menjadikan Muhajirin dan Anshar sebagai saudara karena Allah, setiap orang dari mereka memiliki hak atas yang lainnya seperti hak seorang saudara atas saudaranya. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bersaudaralah karena Allah, dua orang dua orang.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mulai mempersaudarakan antara seorang Anshar dengan seorang Muhajir. Beliau memilih pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai saudara bagi Zaid bin Haritsah, dan memilih Abu Bakar sebagai saudara bagi Kharijah bin Zuhair, dan seterusnya. Dan dalam hal ini, Anshar dan Muhajirin memberikan contoh-contoh yang luar biasa yang menunjukkan keagungan cinta dalam Islam. Diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu ‘anhu dari Anas, ia berkata: “Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mempersaudarakan antara dia dengan Sa’d bin Rabi’ Al-Anshari. Sa’d menawarkan kepadanya untuk membagi dua keluarga dan hartanya. Maka Abdurrahman berkata: Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, tetapi tunjukkanlah aku ke pasar.”
Dan sungguh Al-Quran Al-Karim memuji persaudaraan ini dan cinta karena Allah ini. Allah Ta’ala berfirman: “Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, maka menjadilah kalian karena nikmat Allah sebagai saudara-saudara. Dan kalian dahulu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk.” (Surah Ali ‘Imran: ayat 103)
Aspek kedua: Mewujudkan kesatuan politik dalam masyarakat Madinah secara keseluruhan. Setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar, beliau berusaha dengan segenap upayanya dan kemampuannya untuk menghapuskan akar permusuhan lama yang menyulut api perang antara suku Aus dan Khazraj. Dan karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengetahui tabiat orang-orang Yahudi dan pengkhianatan mereka, maka beliau berusaha mengamankan kaum Muslim dari mereka. Sebagaimana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berupaya untuk mewujudkan keamanan bagi mereka atas diri mereka. Dan untuk mewujudkan hal itu, beliau mengumpulkan penduduk Madinah dari Muhajirin, Anshar, dan Yahudi, lalu bermusyawarah dengan mereka, dan mereka sepakat untuk membentuk persekutuan yang meliputi semua penduduk Madinah. Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menulis perjanjian antara Muhajirin dan Anshar, dan membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan memberi mereka jaminan, serta mengakui agama dan harta mereka, dan menetapkan persyaratan kepada mereka dan memberikan syarat-syarat bagi mereka. Tujuan Rasulullah dari itu adalah agar Madinah menjadi satu kesatuan yang utuh yang membela dirinya, menjaga kepentingan-kepentingannya. Dan dokumen ini dalam prinsip-prinsipnya merupakan salah satu yang paling agung yang pernah dikenal dunia tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia sepanjang sejarah.
Dan aspek ketiga: Membangun masjid dan menjadikannya sebagai markas pemerintahan. Salah satu pekerjaan pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang mulia. Masjid tersebut adalah tempat dimana kaum Muslim melaksanakan ibadah mereka, belajar Al-Quran di dalamnya, dan mempelajari urusan agama mereka. Masjid juga menjadi markas pemerintahan, tempat musyawarah, tempat menuntut ilmu, dan tempat peradilan.
Dan dengan demikian kita telah selesai membahas tentang metode Islam dalam perencanaan, dimana kita mengambil penerapannya dalam tiga kasus: yaitu perencanaan untuk menyebarkan dakwah Islam, perencanaan hijrah, dan perencanaan kehidupan di Madinah setelah hijrah.
Dan kita cukupkan sampai di sini, saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian.
3 – Metode Administrasi Islam dalam Organisasi, Pengawasan, dan Manajemen di Masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar
Metode Islam dalam Organisasi
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam kepada yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kini kita memulai pembahasan tentang metode pemikiran administrasi Islam dalam organisasi. Maka kita katakan:
Tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama organisasi dalam makna umumnya. Dan orang yang merenungkan firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam, Kami tanggalkan siang darinya, maka tiba-tiba mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan telah Kami tetapkan tempat-tempat peredarannya, sehingga (setelah dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Surah Yasin: ayat 37-40) Orang yang merenungkan ayat-ayat yang agung ini akan melihat organisasi yang teliti dan menakjubkan, serta pengaturan yang dapat dirasakan untuk hal-hal yang bersatu dan bekerja sama dalam sistem yang teliti demi mewujudkan tujuan yang agung, yaitu keberlangsungan kehidupan di alam semesta. Dan tubuh manusia sebagaimana Allah ciptakan lalu sempurnakan dan dibuat sebaik-baik ciptaan, adalah contoh nyata yang menunjukkan organisasi yang teliti. Allah Ta’ala berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kalian benar-benar akan mati.” (Surah Al-Mu’minun: ayat 12-15)
Adapun organisasi dalam makna administratif: dapat dikatakan bahwa Islam telah meletakkan kaidah-kaidah umum untuk organisasi sosial. Dan orang yang merenungkan firman Allah Ta’ala: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Surah Az-Zukhruf: ayat 32) Kita katakan: orang yang merenungkan ayat ini akan memahami kebenaran ini dengan jelas. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah Ta’ala telah menjadikan perbedaan dan keberagaman di antara manusia sebagai sebab pembagian kerja di antara mereka dan perwujudan prinsip spesialisasi, masing-masing sesuai dengan tenaga, kemampuan, dan pengalamannya. Sebagaimana Islam menjadikan manusia berderajat-derajat agar yang lebih tinggi mempergunakan yang lebih rendah dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Dan Islam tidak menjadikan pempergunaan sebagian manusia terhadap sebagian lainnya berdasarkan pada ras, warna kulit, atau keinginan untuk berkuasa dan meninggikan diri, tetapi mengaitkan pempergunaan itu dengan tabiat manusia, kondisi mereka, dan kemampuan mereka, maka Allah menjadikan mereka berderajat-derajat sesuai dengan perbedaan mereka dalam kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, kesungguhan dan kemalasan, dan perbedaan-perbedaan lainnya.
Dan penting di sini untuk kita sebutkan bahwa derajat-derajat yang ditetapkan oleh Islam ini, yang dengannya Allah meninggikan sebagian manusia atas sebagian lainnya, dan yang dalam bidang administrasi kita dapat menyebutnya sebagai struktur jabatan, sesungguhnya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi setiap masyarakat dan sesuai dengan cara kerja yang dilakukan. Maka tidak ada yang menghalangi orang yang berada di derajat bawah untuk naik dengan imannya ke derajat yang lebih tinggi, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal. Dan selama pekerja telah berbuat baik dan mencapai kompetensi yang memenuhi syarat untuk memperoleh derajat tersebut, maka Islam membuka baginya pintu kemajuan dan kenaikan pangkat. Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan.” (Surah Ali ‘Imran: ayat 195) Dan Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (Surah Al-Kahfi: ayat 30) Dan kenaikan pangkat serta kemajuan dalam struktur jabatan Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Surah An-Nahl: ayat 97) Dan ini menegaskan apa yang telah kita katakan bahwa derajat kenaikan dan kemajuan hanya bergantung pada iman dan amal. Maha Benar Allah Yang Maha Agung yang berfirman: “Dan bagi masing-masing ada derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Surah Al-An’am: ayat 132)
Dan setelah Al-Quran yang mulia meletakkan kaidah-kaidah umum untuk organisasi sosial, hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang menjelaskan kaidah ini dalam berbagai situasi. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, belas kasihan, dan kelembutan mereka adalah seperti satu tubuh, apabila salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya ikut terjaga dan demam.” Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang Muslim bagi Muslim lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian lainnya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini memandang masyarakat Islam sebagai masyarakat yang terpadu, dan karena itu maka organisasi-organisasi yang ada di dalamnya adalah organisasi-organisasi sosial, yang di dalamnya semua tenaga bekerja sama demi mencapai tingkat yang paling tinggi. Dan bertolak dari bahwa setiap kerusakan pada satu bagian akan berpengaruh pada bagian-bagian lainnya, dan setiap kelalaian dalam satu spesialisasi akan berpengaruh pada banyak spesialisasi lainnya. Oleh karena itu, orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan tertentu tidak terbatas perannya hanya pada sekadar melaksanakan pekerjaannya dengan segenap tenaga yang dimilikinya saja, tetapi sebelum dan sesudah itu, ia memikul tanggung jawab untuk memberikan semua yang ia miliki berupa pemikiran, nasihat, atau pengalaman dalam bidang-bidang lainnya, bertolak dari konsep bahwa agama adalah nasihat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada para pemimpin kaum Muslim, dan kepada kaum Muslim pada umumnya. Dan sesuai dengan konsep keterpaduan Islam, maka ketika manajemen mendelegasikan wewenangnya kepada para spesialis, tanggung jawabnya atas pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan tidak berakhir, tetapi ia merupakan mitra dalam tanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan hingga pekerjaan terlaksana dengan cara yang mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan.
Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah meletakkan dasar-dasar organisasi sosial dalam negara Islam yang pertama. Beliau membagi pekerjaan menjadi departemen-departemen, dan memilih dari kaum Muslim yang paling kompeten di antara mereka untuk memikul tanggung jawab departemen-departemen ini. Abdullah bin Naufal adalah orang pertama yang memegang jabatan peradilan di Madinah, dan Mush’ab bin Umair adalah qari (pembaca Al-Quran) pertama di Madinah. Sebagaimana Zaid bin Tsabit adalah yang bertugas menerjemahkan, dimana ia menguasai bahasa Persia, Rusia, Qibti, Habsyi, dan Yahudi. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak lupa terhadap media dakwah agama, maka beliau menjadikan Hassan bin Tsabit dan Ka’ab bin Malik sebagai penyair-penyair untuk dakwah Islam. Dan setiap orang yang memegang suatu departemen memiliki pembantu-pembantu yang membantunya, menaati perintahnya, dan melaksanakan instruksinya. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengirim pasukan untuk peperangan dengan seorang komandan di kepalanya, dan khalifah (pengganti) untuk komandan tersebut, dan khalifah untuk khalifah. Sebagaimana Rasulullah yang mendapat ilham shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melupakan jabatan-jabatan konsultatif yang bertugas memberikan nasihat dan arahan. Maka beliau membentuk dewan syura yang terdiri dari empat belas orang naqib (pemimpin) yang dipilih dari antara orang-orang yang memiliki pendapat dan pandangan, serta pemilik akal dan keutamaan. Dan dewan ini mencakup semua spesialisasi agar menjadi rujukan bagi kaum Muslim, sebagai implementasi dari firman Allah Ta’ala: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (Surah Al-Anbiya: ayat 7)
Dan di masa Khalifah-Khalifah Rasyidin, ruang lingkup negara Islam meluas, maka ruang lingkup organisasi pun meluas. Namun tetap berjalan atas kaidah-kaidah yang sama seperti di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang terwujud dalam kompetensi dan pengalaman. Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu menyerahkan peradilan kepada Umar, sebagaimana ia menyerahkan amanat baitul mal kepada Abu Ubaidah, dan menyerahkan pengawasan tawanan perang kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang dilakukan Umar bin Al-Khaththab, dimana ia memegang sendiri urusan perbendaharaan, dan membagi pekerjaan-pekerjaan kepada orang-orang yang kompeten, masing-masing sesuai dengan pengalamannya, dan mengumumkan hal itu kepada masyarakat dengan berkata: Siapa yang ingin bertanya tentang fikih maka datanglah kepada Mu’adz bin Jabal, dan siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran maka datanglah kepada Zaid bin Tsabit, dan siapa yang ingin bertanya tentang harta maka datanglah kepadaku, karena sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai penjaga dan pembaginya.
Metode Islam dalam Pengawasan
Kemudian kita berbicara sekarang tentang metode Islam dalam pengawasan, maka kita katakan:
Pengawasan dalam makna umum adalah pemantauan terhadap apa yang terjadi; untuk memastikan bahwa hal itu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dan pengawasan sesuai dengan konsep administratif: adalah proses di mana manajemen melihat apakah yang terjadi memang seharusnya terjadi? Dan jika tidak demikian maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
Adapun konsep Islam tentang pengawasan adalah bahwa ia merupakan proses yang berkelanjutan, yang menjadi tanggung jawab semua pekerja di organisasi, dan tidak dikhususkan untuk satu pihak saja, dan dalam hal ini Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.
Dan dapat dikatakan bahwa ada tiga sumber pengawasan dalam Islam yaitu: pengawasan Ilahi, pengawasan diri, pengawasan umum. Dan kita berbicara sekarang tentang pengawasan Ilahi maka kita katakan:
Sumber utama pengawasan adalah pengawasan Ilahi, dan pengawasan ini bersumber dari perasaan seorang Muslim bahwa perbuatannya -meskipun tersembunyi dari aparat resmi, atau dari masyarakat- maka ia tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta’ala bahkan akan menjadi sumber pahala, atau siksa, pada hari kiamat, Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (dari Allah)” (Surat Al-Haqqah ayat 18) dan Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit” (Surat Ali Imran ayat 5) dan Allah Ta’ala berfirman: “(Yaitu) hari (ketika) mereka nampak (dari kubur), tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah” (Surat Ghafir ayat 16) dan Allah Ta’ala berfirman: “Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu” (Surat Al-Baqarah ayat 284) dan seluruh kaum Muslim meyakini kebenaran ini, dan selalu menyatakannya “Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan” (Surat Ibrahim ayat 38).
Adapun mengenai pengawasan diri maka kita katakan:
Metode Islam dibedakan dengan perhatiannya terhadap bentuk-bentuk pengawasan yang berbeda, namun ia memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengawasan diri yang bersumber dari hati nurani, dan menganggapnya sebagai metode pengawasan yang paling berhasil, dan hati nurani adalah suara Allah yang hidup dan tersimpan dalam diri manusia, dan sebagian mendefinisikannya sebagai: setiap kecenderungan kebaikan yang tersimpan dalam diri manusia secara fitri, dan sungguh Islam telah menanamkan dalam diri Muslim hati nurani yang hidup yang tidak pernah mati; karena ia menghubungkan Muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan ikatan permanen yang tidak ada akhirnya, dan hubungan kekerabatan yang tidak ada jaraknya, Allah Ta’ala berfirman: “Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah” (Surat Al-Baqarah ayat 115) dan Allah Ta’ala berfirman: “Dan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada” (Surat Al-Mujadilah ayat 7) dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu” dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian”. Dan dalam bidang pekerjaan, hati nurani manusia selalu mengingatkan kita kepada firman Allah Ta’ala: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Surat At-Taubah ayat 105).
Dan pengawasan diri membuat individu adalah yang mengevaluasi dirinya sendiri, dan memperbaiki kesalahannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda -dalam upaya menumbuhkan pengawasan ini dalam jiwa manusia: “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab” dan beliau bersabda: “Timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang atas kalian” dan beliau bersabda: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu”.
Adapun mengenai pengawasan umum maka kita katakan:
Islam mengenal pengawasan umum dengan dua konsep kontemporer: pengawasan positif yang berusaha menghindari kesalahan sebelum terjadinya, dan pengawasan negatif yang menghukum kesalahan yang terjadi dan mempertanggungjawabkannya, dan pengawasan umum dalam Islam bersumber dari konsep bahwa jiwa selalu mendorong kepada keburukan, dan oleh karena itu ia memerlukan yang mengawasi perbuatannya, dan menahan dirinya jika tidak tertahan oleh hati nurani internal, namun Islam adalah pelopor dalam mengambil konsep pengawasan positif, dan ungkapan Islam yang terkenal yang mengatakan: “Pencegahan lebih baik daripada pengobatan” adalah rujukan bagi konsep-konsep pengawasan positif di sekolah-sekolah pemikiran kontemporer.
Dan pengawasan positif adalah pengawasan efektif yang bertujuan untuk menemukan kesalahan pada waktu yang tepat, atau memperkirakannya sebelum terjadinya, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya, dan jenis pengawasan ini dianggap sebagai pendekatan kooperatif antara manajemen, dan para pelaksana; karena ia berusaha mengenali titik-titik kelemahan dalam organisasi, dan mengangkat laporan tentang hal itu kepada para pejabat, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan ini, sebelum mempengaruhi tujuan organisasi.
Adapun pengawasan negatif adalah yang menampakkan kesalahan yang benar-benar terjadi, dan mengungkapkannya di hadapan para pejabat; untuk mengambil tindakan hukuman terhadap mereka yang menyebabkannya.
Dan Islam dalam konsepnya tentang pengawasan negatif membedakan antara dua jenis kesalahan: ada kesalahan yang disengaja yang dimaksudkan untuk merugikan organisasi, dan ini harus diambil dengan ketegasan yang menjerakan, dan hukuman yang keras, dan ada kesalahan biasa yang diakibatkan oleh banyaknya pekerjaan, atau karena tidak memahami instruksi, atau karena sifat kemanusiaan seperti lalai, dan lupa, dan lainnya, dan ini ditangani dengan arahan, dan peringatan, dan penyadaran, dan Al-Quran Alkarim meringkas makna-makna ini dalam kata-kata yang tepat, dan fasih, maka Allah berfirman: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu” (Surat Al-Ahzab ayat 5).
Dan pengawasan umum dalam Islam -sebagaimana kita lihat- terbagi menjadi pengawasan internal, dan pengawasan eksternal, maka pengawasan internal yang kami maksud dengannya adalah pengawasan dari pihak manajemen, dan jenis pengawasan ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menerapkan metode pengawasan ini dalam dua bentuk:
1 – Mengirim orang yang beliau percaya pada integritas mereka untuk memantau pekerjaan para penggembala, dan gubernur di wilayah-wilayah.
2 – Menyelidiki keluhan yang dikirim kepadanya dari kaum Muslim terhadap penguasa.
Ini di samping bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah meletakkan beberapa aturan efektif yang menjamin baginya terwujudnya pengawasan penuh terhadap para pegawainya, di antaranya mengunjungi rumah-rumah kaum Muslim, dan memeriksa keadaan mereka, dan memperhatikan orang-orang yang sengsara dan miskin di antara mereka, dan juga pada musim haji beliau berkumpul dengan para pegawai, dan mendiskusikan dengan mereka tentang pekerjaan mereka, dan memperingatkan mereka dari melanggar batasan-batasan Allah Tabaraka wa Ta’ala dan juga Rasulullah memerintahkan para pegawainya di wilayah-wilayah ketika memasuki Madinah agar masuk di siang hari; agar semua orang melihat apa yang mereka bawa dari harta, atau hadiah.
Adapun mengenai pengawasan eksternal maka telah mencakup dalam Islam dua jenis: pengawasan rakyat, dan pengawasan peradilan.
Mengenai pengawasan rakyat: yang kami maksud dengannya adalah pengawasan rakyat terhadap aparat administratif negara dari puncak hingga dasar; karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi tindakan-tindakan ini, dan mengkritiknya dengan kritik yang membangun dengan apa yang mewujudkan kepentingan umum, dan dalam sistem Islam pengawasan rakyat terwujud dalam konsep nominal dalam metode hisbah, yang diambil oleh Islam, dan diwajibkan kepada muhtasib untuk mengawasi pekerjaan para khalifah, dan gubernur, dan para ulama, dan Islam telah menjadikan hisbah sebagai fardhu kifayah bagi masyarakat umum; karena wajib bagi semua orang untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi ia menjadikannya fardhu ain bagi orang-orang karena jabatan mereka, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”.
Adapun mengenai pengawasan peradilan:
Maka Islam telah mengenal pengawasan peradilan, yang terwujud dalam nazir mazalim (pengawas pengaduan) yang melaksanakan pekerjaan pengawasan administratif, dan ia memiliki dalam hal ini beberapa kewenangan yang kami sebutkan di antaranya:
1 – Memeriksa kezaliman gubernur terhadap rakyat.
2 – Kesewenang-wenangan pegawai dalam apa yang mereka pungut dari harta.
3 – Mempertanggungjawabkan penulis diwan dalam apa yang diserahkan kepada mereka dari pencatatan harta.
4 – Memeriksa apa yang terjadi antara warga negara, dan administrasi, dari sengketa.
Dan demikianlah kita lihat bahwa pengawasan dengan segala bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan masyarakat Islam, telah diambil oleh sistem Islam dalam pemikiran, dan praktik, dan mereka menganggapnya sebagai kewajiban atas mereka yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala sesuai dengan sabda Rasul kita shallallahu alaihi wasallam: “Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya”.
Dan hal itu lebih jelas dalam apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada orang-orang: “Bagaimana pendapat kalian jika aku mengangkat atas kalian orang terbaik yang aku ketahui, kemudian aku memerintahkannya untuk berbuat adil, apakah aku telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanku?” Mereka berkata: “Ya, wahai Amirul Mukminin,” ia berkata: “Tidak, sampai aku melihat dalam pekerjaannya apakah ia bekerja dengan apa yang aku perintahkan kepadanya atau tidak?”.
Administrasi pada Masa Nabi shallallahu alaihi wasallam
Kita beralih setelah itu kepada topik lain yaitu: Organisasi administratif dalam bidang penerapan praktis.
Setelah kami sebutkan arahan-arahan pemikiran administratif Islam dalam administrasi, dan metode Islam dalam administrasi, kami ingin melihat kepada realitas, dan menerapkan hal-hal teoritis yang telah kami pelajari kepada realitas, maka kami pelajari sekarang organisasi administratif dalam bidang penerapan, dan sebaik-baik penerapan untuk itu adalah apa yang terjadi pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam dan zaman para khalifah beliau yang benar, maka kami mulai -insya Allah- dalam pembicaraan tentang topik ini, yaitu organisasi administratif dalam bidang penerapan praktis.
Dan kami mulai sekarang dalam organisasi administratif pada masa Nabi kita shallallahu alaihi wasallam maka kami katakan:
Organisasi administratif negara Islam dianggap sebagai gambaran yang benar bagi pemikiran politik, dan perkembangannya di kalangan kaum Muslim, dan alat efektif yang menyertai pembangunan negara ini sejak fajar sejarahnya, dan alasan dalam hal itu kembali kepada bahwa organisasi administratif negara Islam bersandar kepada tradisi yang tinggi, dan dasar-dasar yang kokoh, yang diletakkan oleh Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam sendiri; karena beliau menyadari -alaihi ash-shalatu wassalam sejak menyatakan dakwah kepada Islam, beliau menyadari pentingnya organisasi administratif bagi anak-anak masyarakat Islam yang baru, dan perlunya koordinasi pekerjaan antara beliau alaihi ash-shalatu wassalam dengan para pelaksana organisasi penting ini; demi menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia, dan muncul pelopor-pelopor organisasi baru ini sejak Baiat Aqabah yang kedua, yang dihadiri oleh delegasi dari penduduk Yatsrib ke Mekah, pada tahun ketujuh dari hijrah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mereka membai’at Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ketika delegasi ini terdiri dari kelompok besar yang jumlahnya tujuh puluh tiga laki-laki dan dua perempuan, Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat perlunya meletakkan sistem bagi mereka dengan pertimbangan mereka adalah inti masyarakat yang baru, dan untuk menjaga keselamatan masyarakat ini dan koordinasi pekerjaan antara para anggotanya dalam rangka menyebarkan dakwah Islam, dan Rasul yang mulia menjelaskan kepada anggota delegasi Yatsrib tentang sistemnya, dan pentingnya, di mana beliau berkata kepada mereka sebelum kembali ke Yatsrib: “Keluarkanlah kepada saya dari kalian dua belas orang naqib (pemimpin) untuk menjadi pemimpin bagi kaum mereka dengan apa yang ada pada mereka” maka mereka keluarkan dari mereka dua belas naqib, sembilan dari Khazraj, dan tiga dari Aus, dan kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para naqib itu, atau para pelaksana sistem administratif pertama dalam Islam, menjelaskan kepada mereka metode kerja dengan bersabda: “Kalian adalah para penjamin bagi kaum kalian dengan apa yang ada pada mereka, seperti penjaminan para hawari (pengikut setia) bagi Isa bin Maryam, dan aku adalah penjamin bagi kaumku”.
Dan organisasi administratif awal ini mewujudkan buah yang menakjubkan pertamanya, dalam menyiapkan persiapan untuk hijrahnya Rasul ke Yatsrib, kemudian mempersiapkan suasana untuk keberhasilannya, meskipun ada tipu daya orang-orang kafir, dan luasnya pengaturan mereka, dan dimulai dengan perpindahan Rasul yang mulia ke Yatsrib tahap baru untuk organisasi administratif, demi meluangkan waktu untuk menunaikan risalah keagamaannya, dan mengangkat pondasi-pondasi masyarakat Islam yang baru lahir, dan negaranya yang baru tumbuh, dan terwujudlah ciri-ciri organisasi administratif ini dalam Piagam yang dibuat oleh Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan Yahudi Yatsrib, yang kemudian menjadi representasi sistem politik bagi jamaah kaum Muslim di Madinah, dan konstitusi permanen untuk negara Islam yang baru lahir, karena Piagam ini menggambarkan di samping syarat-syarat politik, dan apa yang terkait dengannya dari hak dan kewajiban, saya katakan: Piagam ini menggambarkan metode kerja antara semua kelompok sipil, dengan apa yang menjadikan organisasi administratif sebagai penerjemahan langsung, dan praktis, bagi apa yang tercakup dalam Piagam itu dari sistem politik, dan peneliti menyentuh dalam Piagam itu hubungan yang erat antara sistem politik, dan administratif, dan itu adalah kebenaran yang menjadi ciri khas yang membedakan semua sistem negara Islam, dan kaidah dasar yang dipegang oleh generasi penerus dari pendahulu sepanjang zaman kejayaan negara ini.
Kaidah-kaidah dasar bagi keterkaitan ini menjadi jelas dalam nash yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin adalah umat yang berbeda dari manusia lainnya, dan bahwa individu-individu dari umat ini harus mengorganisir pekerjaan di antara mereka secara administratif; demi menjaga keamanan, menindak tegas para perusak, dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus bersatu menghadapi siapa saja di antara mereka yang berbuat aniaya, dan tangan mereka bersatu melawannya, sekalipun ia adalah anak salah seorang dari mereka. Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam memilih dari kalangan para sahabat orang-orang untuk menjalankan administrasinya, masing-masing sesuai dengan bakat dan kesiapannya, serta membekali mereka dengan pelatihan yang memadai dan arahan-arahan yang sesuai dengan perkembangan negara dan perluasan kekuasaannya. Kemampuan untuk menyebarkan dakwah adalah dasar pertama untuk bekerja di bidang administratif. Yang terdepan sebagai petugas di bidang administratif ini adalah tujuh orang dari kaum Muhajirin dan tujuh orang dari kaum Anshar, di antaranya Hamzah, Ja’far, Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Sulaiman, Ammar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad, dan Bilal. Mereka semua dikenal dengan sebutan para Naqib (penjamin); karena mereka menjamin kepada Rasul tentang keislaman kaum mereka, dan Naqib adalah orang yang menjamin urusan yang ia tanggung jawabkan. Sistem para Naqib berhasil menjaga hubungan antara Nabi sebagai kepala negara yang baru dengan jamaah kaum muslimin, dan hal itu mengikuti kaidah yang telah ditetapkan secara administratif dalam Bai’at Aqabah yang kedua.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengetahui karakteristik orang-orang yang menjalankan administrasinya, dan kemudian mendorong manusia untuk memanfaatkan aktivitas mereka dengan cara yang paling baik. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling baik dalam memutuskan perkara adalah Ali, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu’adz bin Jabal, yang paling mengetahui tentang faraid (ilmu waris) adalah Zaid bin Tsabit, yang paling baik bacaan Qurannya adalah Ubay bin Ka’ab, dan setiap umat memiliki orang yang dapat dipercaya, dan orang yang dapat dipercaya dari umat ini adalah Abu Ubaid bin Jarrah.” Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: “Ambillah Quran dari empat orang: dari Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Mu’adz bin Jabal, dan Salim maula (budak yang dimerdekakan) Hudzaifah.” Yang terkenal dari kalangan Anshar yang menghafal seluruh Quran adalah: Ubay, Mu’adz, dan Zaid bin Tsabit. Dari kelompok para ulama sahabat ini dipilih para juru tulis untuk mencatat Quran segera setelah turunnya wahyu, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh urusan administratif di negara Islam yang baru lahir. Para sahabat yang menjadi juru tulis tersebut, baik pada masa Jahiliah maupun awal Islam, adalah mereka yang terkenal memiliki kemampuan menulis dalam bahasa Arab dan menguasai banyak keahlian. Jumlah juru tulis Nabi shallallahu alaihi wasallam mencapai empat puluh dua orang.
Setelah tahun delegasi (wufud), yaitu sejak tahun kesembilan Hijriah, mulai muncul kelompok petugas administratif; karena pertumbuhan negara Islam yang baru dan perluasan kekuasaannya di seluruh penjuru Jazirah Arab. Hal ini mengharuskan pembagian negeri-negeri tersebut menjadi unit-unit besar, untuk memudahkan pengaturan urusan penduduknya dan menghubungkannya secara langsung dengan ibu kota baru negara Islam di Madinah Munawwarah. Ibu kota dan daerah-daerah di sekitarnya tunduk pada administrasi langsung Nabi yang mulia shallallahu alaihi wasallam hingga Mekkah memiliki wali (gubernur) yang menerima arahan darinya dan segala hal yang diperlukan oleh administrasi yang baru.
Negeri-negeri Arab, selain dua kota suci tersebut, terbagi menjadi provinsi-provinsi berikut: Taima, Jund, Bani Kindah, Najran, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Sejak tahun delegasi, kebiasaan Rasul yang mulia adalah memilih dari antara orang-orang yang datang kepadanya yang paling layak untuk mengelola urusan kepemimpinan di provinsi dari mana delegasi tersebut berasal, berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut, tanpa memandang usia. Contohnya, ketika delegasi Tsaqif datang kepadanya, Rasul mengangkat Utsman bin Abi Ash sebagai pemimpin mereka, padahal ia adalah yang paling muda usianya; karena ia adalah yang paling berilmu di antara mereka. Kemudian Rasul yang mulia membekalinya dengan petunjuk ketika kembali ke tempat kepemimpinannya dengan berkata kepadanya: Wahai Utsman, ringanlah dalam shalat, dan ukurlah kemampuan manusia dengan yang terlemah di antara mereka; karena di antara mereka ada orang tua, anak kecil, orang lemah, dan yang memiliki kebutuhan. Di samping setiap pemimpin, Nabi menunjuk petugas lain dari pihaknya untuk mengumpulkan zakat dan sedekah, serta mengajarkan kepada manusia Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama dalam muamalat. Nabi sendiri melatih kelompok petugas ini hingga mereka menjadi teladan tinggi dalam kehormatan, kesucian, dan keikhlasan dalam bekerja.
Contoh dari hal itu adalah apa yang dilakukan Rasul yang mulia ketika mengutus Mu’adz ke Yaman, di mana beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, jika mereka telah mengenal Allah Ta’ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mematuhi hal itu, maka ambillah dari mereka, dan hindari harta-harta terbaik mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya; karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah.” Rasul yang mulia menulis kepada sebagian petugasnya sesuai kebutuhan, seperti yang ditulisnya kepada Amr bin Huraith, petugasnya di Najran, yang menjelaskan tentang fara’id (kewajiban-kewajiban), sunnah-sunnah, apa yang harus dilakukan dalam sedekah, dan diyat (denda pembunuhan).
Petugas-petugas Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kesucian dan keikhlasan dalam bekerja. Contohnya adalah Abdullah bin Rawahah yang ditugaskan Rasul shallallahu alaihi wasallam untuk menaksir hasil buah-buahan penduduk Khaibar dari kalangan Yahudi; orang-orang Yahudi mencoba memberikan suap kepadanya berupa perhiasan sambil berkata kepadanya: Ini untukmu, ringankanlah beban kami, dan berlakulah longgar dalam pembagian. Abdullah berkata kepada mereka: Wahai kaum Yahudi, kalian termasuk makhluk Allah Ta’ala yang paling kubenci, namun hal itu tidak membuatku berlaku tidak adil kepada kalian. Adapun suap yang kalian tawarkan kepadaku, sesungguhnya itu adalah haram, dan kami tidak memakannya. Mereka berkata: Dengan inilah langit dan bumi ditegakkan.
Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam terus melakukan pengawasan terhadap para petugas, khususnya yang berkaitan dengan urusan keuangan. Beliau pernah menugaskan seseorang untuk mengumpulkan sedekah, dan ketika beliau shallallahu alaihi wasallam menghisabnya, orang itu berkata: Ini untuk kalian, dan ini hadiah untukku. Maka Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Apa yang terjadi dengan orang yang kami tugaskan dalam pekerjaan yang Allah percayakan kepada kami, lalu ia berkata: ini untuk kalian, dan ini hadiah untukku? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah akan diberi hadiah atau tidak?” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang kami tugaskan dalam pekerjaan dan kami beri rezeki (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu adalah ghulul (pengkhianatan).”
Rasul juga mendengarkan setiap keluhan yang datang kepadanya tentang salah satu petugasnya. Contohnya, beliau memberhentikan Al-Ala’ bin Hadhrami, petugasnya di Bahrain; karena delegasi Abdul Qais mengadukan dia—artinya mengadukannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memberhentikannya dan mengangkat Aban bin Sa’id sebagai penggantinya, dan berkata kepadanya: Perlakukanlah Abdul Qais dengan baik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap berhati-hati dalam memilih orang-orang administrasinya dari mereka yang dikenal memiliki kompetensi, di antaranya Abu Sufyan bin Harb, yang diangkatnya untuk urusan Najran dalam hal shalat dan perang, sementara ia menugaskan Rasyid bin Abdullah bersamanya sebagai pemimpin untuk urusan peradilan dan penanganan kezaliman. Unsur kepemudaan adalah yang dominan di kalangan petugas administratif pada zaman Rasul shallallahu alaihi wasallam dan dari mereka yang memiliki wibawa di hati manusia. Tiga perempat petugasnya berasal dari Bani Umayyah, yang pada masa Jahiliah memiliki aktivitas luas dalam urusan administratif Mekkah.
Dengan demikian, kita telah selesai membahas tentang administrasi pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam.
Administrasi pada Masa Abu Bakar radiyallahu anhu
Sekarang kita beralih kepada administrasi pada masa Abu Bakar—semoga ridha Allah Tabaraka wa Ta’ala tercurah padanya—maka kita katakan:
Abu Bakar memulai masa kepemimpinannya dengan khutbah terkenalnya, yang oleh para sejarawan dan pengkritik—meskipun ringkas—dianggap sebagai konstitusi pemerintahan, dan keteguhan penuh terhadap sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, jihad di jalan Allah, dan mempersatukan hati kaum muslimin.
Abu Bakar berkata dalam khutbah pertamanya, setelah memuji Allah dan menyanjungnya, serta bershalawat atas Nabinya shallallahu alaihi wasallam:
Amma ba’du: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku hingga aku mengambilkan haknya—insya Allah—dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku hingga aku mengambil hak darinya—insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah melainkan Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka, dan tidaklah perbuatan keji tersebar di suatu kaum melainkan Allah akan menimpakan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan RasulNya, jika aku bermaksiat kepada Allah dan RasulNya maka tidak ada ketaatan bagiku atas kalian. Kemudian beliau berkata: Berdirilah untuk shalat kalian, semoga Allah merahmati kalian.
Inilah khutbah yang menjadi awal pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq atas kaum muslimin, setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar telah memberikan hak kepada umat Islam untuk mengawasi perbuatan khalifah. Perbuatan Abu Bakar dimulai sejak keislamannya, ketika ia meletakkan batu kedua secara berdampingan dalam dakwah Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan pendirian negara Islam, karena ia adalah orang Islam pertama, dan Muhajirin pertama, dan ia adalah penanggung jawab keamanan khusus bagi Rasul shallallahu alaihi wasallam dan penjaga rahasianya, serta penasihat utamanya dalam masalah agama dan rakyat. Periode panjang yang ia habiskan bersama Rasul shallallahu alaihi wasallam sejak penyebaran dakwah hingga wafatnya, telah memberinya pengalaman administratif luar biasa yang benar-benar membuatnya layak untuk berhasil mengelola negara yang baru tumbuh dan mengurus kepentingan kaum muslimin di tahap paling kritis dalam sejarah Islam.
Oleh karena itu, Abu Bakar setelah mengambil pemerintahan, bertekad sejak hari pertama untuk mengikuti jalan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan menelusuri jejaknya, serta menempuh jalan yang ditempuhnya dalam menyebarkan Islam dan menyatukan bangsa Arab, tanpa takut lemah, bingung, atau pengecut. Maka kebijakannya dalam pemerintahan adalah ikutan penuh terhadap kebijakan dan pemerintahan Rasul shallallahu alaihi wasallam. Ia mengikuti sirahnya dalam administrasi, dan mempertahankan para petugas yang membantu Rasul shallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin yang diangkatnya. Ia memilih Abu Ubaidah bin Jarrah untuk urusan keuangan, dan Umar bin Khattab untuk peradilan, serta mempertahankan Zaid bin Tsabit sebagai jurutulisnya. Ia juga mempertahankan ahli syura yang dipilih Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan perubahan pada beberapa orang karena penunjukan mereka sebagai gubernur di beberapa wilayah. Adapun peradilan di wilayah-wilayah dipercayakan kepada para gubernur dalam memilih mereka; karena mereka lebih mengetahui tentang hal itu, kemudian beliau memberikan wilayah peradilan kepada mereka.
Cukup sekian, dan wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4 – Administrasi pada Masa Umar bin Khattab
Sikap Umar terhadap Sistem Administratif di Negeri-Negeri yang Ditaklukkan
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, wash-shalatu was-salamu ‘alal mab’utsi rahmatan lil ‘alamin, sayyidina Muhammad, wa ‘ala alihi wa ashabihi, wa man tabi’ahum bi ihsanin ila yaumid din… Amma ba’du:
Pada perkuliahan sebelumnya kita telah membahas tentang metode Islam dalam organisasi, kemudian tentang metode Islam dalam pengawasan, kemudian kita mulai membahas tentang organisasi administratif dalam bidang penerapan praktis. Kita telah membahas tentang administrasi pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian membahas tentang administrasi pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radiyallahu anhu wa ardhahu.
Sekarang kita membahas tentang administrasi pada masa Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ardhahu—maka kita katakan:
Sistem administratif di negara Islam berkembang mengikuti ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam dan menjadi mampu menghadapi perkembangan dahsyat dan cepat yang disaksikan oleh negara tersebut, pada masa Khalifah Umar bin Khattab; hal itu karena penaklukan-penaklukan Islam yang terjadi pada masa khalifah ini menjadikan bangsa Arab sebagai penguasa Bulan Sabit Subur (Hilal Khasib), Persia, dan Mesir, yaitu tempat-tempat geografis penting yang merupakan pusat-pusat tertua sistem administratif di seluruh dunia. Maka bangsa Arab mewarisi sistem-sistem kuno tersebut yang tradisinya kembali ke zaman Yunani, Romawi, Persia, Fir’aun, Asyur, dan Babilonia, dan mereka menganggapnya sebagai warisan seluruh umat manusia yang telah jatuh kepada mereka, dan bahwa mereka telah menjadi penjaga dan penanggung jawab atas keselamatan warisan ini, kemudian memanfaatkannya.
Khalifah Umar bin Khattab sendiri memberikan contoh praktis dalam memanfaatkan sistem-sistem kuno tersebut, untuk membangun sistem administratif bagi negara Islam yang baru tumbuh. Hal itu karena pengelolaan wilayah-wilayah baru pada masanya merupakan masalah serius di hadapan otoritas Islam; karena wilayah-wilayah tersebut mencakup negeri-negeri dengan bangsa-bangsa yang berbeda bahasa dan tunduk pada pola administratif yang beragam. Mesir dan Syam, pengelolaannya berjalan mengikuti model-model Bizantium, sementara Irak dan Persia dikuasai oleh tradisi Pahlawi dalam bahasa dan sistem. Maka Khalifah Umar bin Khattab mempertahankan organisasi administratif, serta lembaga-lembaga administratif itu sendiri di negeri-negeri yang ditaklukkan sebagaimana adanya; agar jalannya pekerjaan tidak terganggu, dan untuk memanfaatkan pengalaman para petugas di sana juga. Pada saat yang sama, ia memberi roh baru Arab pada administrasi-administrasi ini yang telah diasah oleh Islam dan dibekali dengan ajaran-ajaran luhur yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia dan kesejahteraannya. Roh Arab mengambil unsur-unsurnya dari konsep kekuasaan dalam Islam, yang berdiri di atas prinsip bahwa kedaulatan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Dia adalah pemilik segala sesuatu, dan Dia adalah pelindung dan pengawas kepentingan umum. Maka harta di negara adalah harta Allah, dan tentara adalah tentara Allah, artinya kata Allah dalam istilah zaman sekarang adalah kepentingan umum, dalam arti bahwa harta Allah adalah harta publik sekarang, dan tentara Allah adalah tentara yang mengemban beban kepentingan umum. Namun Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak menjalankan pemerintahan dan administrasi sendiri, atau secara langsung di antara manusia, seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan kuno pada masa Fir’aun misalnya, melainkan kedaulatan tertinggi yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala diamanahkan kepada khalifah yang dianggap sebagai kepala sistem politik dan pengawas kendali sistem administratif. Khalifah adalah orang dunia yang mengelola pengawasan atas kepentingan umum yang adalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh karena itu, khalifah sendirilah yang memiliki hak untuk memilih siapa pun yang ia kehendaki untuk mengurus urusan administrasi dan pemerintahan, dan ia bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang ia pilih; karena mereka tunduk kepadanya, bekerja atas namanya, dan menjalankan kekuasaan mereka dengan pendelegasian darinya.
Konsep Islam tentang kekuasaan ini mengharuskan sistem administrasi yang terpusat; karena Khalifah adalah penanggung jawab pelaksanaan hukum, dan hubungan antara dirinya dengan para pegawainya harus merupakan hubungan langsung. Oleh karena itu, setiap pemberontakan terhadap para wali tersebut dianggap sebagai pemberontakan terhadap Khalifah itu sendiri, dan tanggung jawab pertama dan terakhir adalah tanggung jawab Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab beriman dengan konsep ini dengan keyakinan yang mendalam, yang dia ungkapkan dalam perkataannya: “Demi Allah, seandainya seekor unta tersandung di Irak, aku akan bertanggung jawab atasnya.” Kemudian dia menegaskan konsep ini berulang kali dalam berbagai kesempatan, yang terakhir adalah perkataannya: “Jika aku masih hidup, sungguh aku akan berkeliling di tengah rakyat selama setahun penuh, karena aku tahu bahwa masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang terputus dariku,” yakni berita tentangnya tidak sampai kepadaku. “Adapun para pegawai mereka” —maksudnya para pegawai rakyat— “tidak menyampaikannya, dan mereka” —maksudnya rakyat sendiri— “tidak bisa sampai kepadaku. Maka aku akan pergi ke Syam dan tinggal di sana dua bulan, lalu pergi ke Jazirah dan tinggal di sana dua bulan, lalu pergi ke Mesir dan tinggal di sana dua bulan, lalu pergi ke Bahrain dan tinggal di sana dua bulan, lalu pergi ke Kufah dan tinggal di sana dua bulan, lalu pergi ke Bashrah dan tinggal di sana dua bulan. Demi Allah, sungguh sebaik-baik perjalanan tahunan adalah ini.”
Khalifah Umar bin Khattab dengan semangat Islam yang luas wawasannya ini, dan dengan konsepnya tentang kekuasaan, menghadapi masalah pengorganisasian administrasi negara Islam yang sedang berkembang, dan mengambil langkah-langkah praktis dalam hal tersebut yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengoordinasikan semua sistem yang menjamin stabilitas negara dan menghindarkannya dari kesulitan dan goncangan yang merusak. Dia berhasil menggabungkan antara sistem-sistem administrasi yang telah ditetapkan kaidah-kaidahnya pada masa Rasulullah yang mulia shallallahu alaihi wasallam dengan tuntutan situasi baru negara Islam setelah penaklukan-penaklukan luas yang terjadi pada masanya. Dia membangun sistem administrasi terpusat yang menjamin ketenteraman dan kesejahteraan bagi semua penduduk di bawah naungannya, dan juga memberikan contoh praktis tentang konsep kekuasaan dalam Islam.
Awal mula harmonisasi antara konsep kekuasaan dalam Islam beserta sistem-sistem yang menyertainya dengan sistem-sistem lama di negeri-negeri yang ditaklukkan tampak dalam dipertahankannya jabatan amir oleh Khalifah Umar bin Khattab yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah yang mulia. Khalifah menunjuk seorang amir untuk setiap negeri dari negeri-negeri yang ditaklukkan, di samping tetap mempertahankan sistem-sistem administrasi negeri-negeri tersebut dan para pegawai dari putra-putra negeri tersebut.
Negara Islam pada masa Umar bin Khattab terbagi menjadi delapan wilayah untuk mempermudah pengaturan administrasinya, yaitu: Mekah, Madinah, Syam, Jazirah, Bashrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap wilayah memiliki seorang amir yang terkadang bergelar wali, dan tinggal di ibu kota wilayah, di mana dia mengambil tempat khusus yang terkenal dengan nama Dar al-Imarah (Kantor Pemerintahan). Amir dianggap sebagai wakil Khalifah dan pemimpin politik, serta penanggung jawab administratif atas semua urusan secara langsung kepada Khalifah. Wali memimpin umat Islam dalam shalat Jumat dan hari raya di masjid agung setiap wilayah sebagai wakil Khalifah, dan dengan demikian memperoleh gelar Amir al-Shalah (Pemimpin Shalat), yang merupakan penghormatan yang menunjukkan wibawa amir, karena mengimami shalat adalah urusan yang khusus untuk para khalifah, di mana masing-masing dari mereka bergelar Imam. Amir juga memimpin pasukan wilayah dan pada saat pengangkatan memperoleh gelar Wilayah al-Harb (Kepemimpinan Perang), dan menjadi kewajibannya untuk mengawasi urusan garnisun yang ada di negeri tersebut dan memimpinnya sendiri untuk mengamankan wilayahnya dan menangkis musuh. Amir terkadang—dan tidak selalu—menggabungkan tugasnya dengan tugas pengawasan administrasi keuangan wilayah yang pada waktu itu disebut kharaj, dan amir seperti ini dianggap sebagai sumber kekuasaan di wilayah tersebut.
Para ahli fikih sistem Islam menggambarkan corak pengorganisasian administratif pertama ini pada masa Umar bin Khattab sebagai imarah ammah (kepemimpinan umum), karena amir memimpin pasukan, mengimami shalat, memutuskan dalam persengketaan, dan mengumpulkan harta. Namun dengan stabilnya keadaan setelah penaklukan dan meluasnya tuntutan administratif, Umar bin Khattab terpaksa menunjuk di samping amir seorang amil untuk memungut kharaj. Amil kharaj pada gilirannya memiliki kewenangan luas, terutama di wilayah-wilayah yang berpenghasilan besar, dan dengan demikian menjadi pesaing amir itu sendiri. Umar bin Khattab mengambil langkah ini di Mesir, di mana dia menjadikan Amr bin Ash memimpin pasukan dan menunjuk Abdullah bin Saad bin Abi Sarh untuk memungut kharaj. Dengan demikian kepemimpinan Amr bin Ash menjadi khusus setelah sebelumnya bersifat umum. Imarah khashshah (kepemimpinan khusus) menurut para ahli fikih berarti bahwa amir di dalamnya khusus mengatur pasukan, memimpin rakyat, melindungi negara, dan mempertahankan kehormatan dalam batas-batas tertentu, dan dia tidak berhak mencampuri peradilan, atau hukum-hukum, atau pemungutan kharaj, atau sedekah dalam hal apapun. Bahkan mengimami shalat pun, mungkin hakim lebih berhak melakukannya daripada dia.
Amir dibantu dalam mengelola urusan administratif di negeri-negeri yang ditaklukkan oleh para tokoh administrasi lama yang dipertahankan oleh Khalifah Umar bin Khattab, baik mereka yang bekerja dalam administrasi Bizantium maupun Sasania. Khalifah ini dengan kecerdasan administratif yang luar biasa menyadari bahwa mengarahkan negaranya untuk kepentingan umum mengharuskan agar administrasi-administrasi lama tidak dilumpuhkan atau dihentikan fungsinya di wilayah-wilayah yang berada di bawah naungan Islam. Stabilitas keadaan negara Islam yang muda mengharuskan pemanfaatan pengalaman administrasi dan pemerintahan, baik dari Bizantium maupun Sasania. Umar bin Khattab dengan demikian memperoleh gelar Pendiri Kedua Negara Islam setelah Rasulullah yang mulia shallallahu alaihi wasallam.
Umar bin Khattab menunjukkan penghargaannya terhadap sistem-sistem administratif yang dia temukan di negeri-negeri yang ditaklukkan sejak kunjungannya ke wilayah Syam. Dia menetapkan untuk wilayah ini pembagian administratif yang menjadi contoh penggabungan antara sistem-sistem Islam dan Bizantium, serta kelangsungan administrasi untuk melindungi negeri dan keamanannya. Dia mempertahankan pembagian administratif yang berlaku di sana sebelumnya, yaitu sistem yang memiliki karakter khusus, di mana penguasa wilayah menggabungkan tugas-tugas sipilnya dengan kewenangan militer. Dia mempertahankan keadaan ini dan memberi bagian-bagian tersebut nama Arab al-ajnad (jamak dari jund), yang setara dengan kata Yunani “thema” pada Bizantium. Maka ajnad berarti wilayah-wilayah militer, di ibu kota masing-masing ditempatkan sebuah legiun dari legiun-legiun pasukan, dengan dasar-dasar administratif yang sama seperti yang berlaku dalam sistem Bizantium.
Wilayah Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab dianggap sebagai contoh sempurna sistem administrasi terpusat dari segi kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, dan karakteristik Islam yang baru. Tugas-tugas gubernur Bizantium umum yang dikenal dengan nama “Augustalis” di negeri tersebut beralih kepada Amr bin Ash, yang merupakan wali pertama di Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kekuasaan Amr bin Ash meluas ke berbagai aspek administratif dan aspek lain yang dituntut oleh keadaan Islam di negeri tersebut. Dia mengimami masyarakat dalam shalat mewakili Khalifah, yang pada waktu itu menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin tertinggi di negeri tersebut. Amr juga menggabungkan kekuasaan politiknya dengan hak pengawasan administrasi keuangan negeri, yang merupakan urusan sangat penting, di mana wali yang menggabungkan antara mengimami masyarakat dalam shalat dan mengumpulkan kharaj menjadi pemegang kekuasaan mutlak, artinya wilayahnya adalah wilayah umum, sesuai istilah yang digunakan para ahli fikih dari para peneliti urusan administratif negara Islam.
Amr bin Ash bangga dengan kekuasaan administratif ini hingga dia berkata: “Wilayah Mesir secara keseluruhan setara dengan kekhalifahan,” maksudnya menyamai kekhalifahan. Namun Amr bin Ash—meskipun memiliki kekuasaan luas ini—tetap menjadi contoh amir Muslim yang tunduk pada administrasi terpusat dan kekuasaannya, yang amanah dalam melaksanakan instruksi-instruksi langsungnya. Khalifah meminta kepada Amr bin Ash untuk meminta nasihat dari para tokoh besar Mesir dalam administrasinya dan mengetahui cara-cara terbaik untuk menghapuskan sisa-sisa administrasi Bizantium lama di sana, karena Mesir menderita banyak kesulitan di tangan administrasi kolonial Bizantium yang tujuannya adalah memeras kekayaan negeri. Mesir pada abad sebelum penaklukan Islam menderita keadaan kekacauan yang disebabkan oleh: orang-orang Bizantium—yaitu Romawi—menganggap para petani di sana hanya sebagai alat untuk memproduksi gandum, dan para pegawai administrasi di sana hanya ditugaskan untuk memeras harta dari rakyat, tanpa menjadi tugas mereka untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyat atau memperbaiki keadaan masyarakat dan memenuhi tuntutan mereka. Amr bin Ash mematuhi perintah Khalifah Umar dan bertanya kepada Benyamin, uskup Mesir, tentang cara terbaik untuk mengelola negeri dan mengatur urusannya. Benyamin menyarankan sebagai berikut:
Dia berkata kepadanya: “Wahai amir, engkau harus memakmurkan negeri ini—yaitu Mesir—dari lima aspek: kharaj dipungut pada satu waktu, ketika penduduknya selesai dari pertanian mereka,” artinya pada satu waktu ketika penduduk selesai memanen tanaman; “dan kharajnya dipungut pada satu waktu, ketika penduduknya selesai memeras anggur mereka,” artinya kharaj diambil dari mereka pada satu waktu ketika mereka selesai memeras anggur yang mereka tanam; “dan juga menggali kanal-kanal dan menutup saluran-saluran air serta tanggul-tanggulnya.” Ini adalah wasiatnya.
Benyamin menambahkan persyaratan untuk tidak memilih pegawai yang zalim untuk mengurus urusan masyarakat, karena dialah orang administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan syarat-syarat lain yang dia anggap perlu untuk kemakmuran negeri.
Amr bin Ash benar-benar mengikuti petunjuk perkataan Benyamin orang Mesir itu. Dia memungkinkan penduduk untuk berpartisipasi bersamanya dalam mengelola negeri, sehingga mereka dapat memanfaatkan keadilan administrasi Islam, sambil tetap mempertahankan—pada saat yang sama—sistem-sistem administratif yang telah mereka kenal di bawah negara Bizantium.
Diwan-Diwan yang Didirikan Umar bin Khattab
Dalam membahas administrasi pada masa Umar bin Khattab, kita wajib menyoroti beberapa sistem yang diciptakan dan dirintis oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang tidak ada sebelumnya, baik pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Di antara sistem-sistem administratif penting yang diciptakan dan dirintis Umar bin Khattab adalah: sistem diwan, pembentukan Baitul Mal, dan pengorganisasian pasukan Islam, yang akan kita soroti sebagai berikut:
Pertama: Diwan-Diwan:
Diwan adalah: tempat untuk menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kekuasaan dari pekerjaan-pekerjaan dan harta-harta, serta orang-orang yang menjalankannya dari pasukan dan pegawai.
Yang pertama kali mendirikan diwan dalam Islam adalah Umar bin Khattab. Umar adalah orang pertama yang membuat catatan diwan-diwan. Maksudnya dia membuat catatan diwan adalah dia mendirikannya, mencontoh diwan-diwan Persia dan Romawi. Diwan-diwan itu dicatatkan untuknya oleh Aqil bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal, dan Jubair bin Muth’im, yang merupakan orang-orang cerdas Quraisy.
Diwan-diwan penting yang didirikan Umar bin Khattab:
1- Diwan al-Insya atau al-Rasail (Diwan Surat-Menyurat):
Dapat dikatakan berdasarkan apa yang telah kita sebutkan bahwa diwan adalah catatan di mana dicatat statistik, nama-nama, gaji, instruksi-instruksi administratif, dan surat-surat yang dipertukarkan. Juga dapat dikatakan bahwa diwan adalah tempat di mana disimpan surat-surat, perjanjian-perjanjian, dan dokumen-dokumen. Jika demikian, kita dapat mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang mendirikan Diwan al-Insya dalam Islam, dan Umar telah membuat sebuah tabut—yaitu peti—untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjiannya.
Sebagian orang mengatakan: Adapun kantor penulisan administrasi, atau yang kemudian dikenal sebagai Diwan Al-Insha, tidak ada kebutuhan untuk mendirikannya pada masa awal tersebut, karena Khalifah Umar tidak mau kecuali berhubungan langsung dengan para gubernur dan pegawainya, ia membaca sendiri surat-surat yang datang dari mereka, dan menulis sendiri kepada mereka apa yang ia inginkan. Semua yang ada yang terkait dengan penulisan administrasi pada masa itu adalah para penulis yang serupa dengan penulis-penulis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu mereka yang menulis apa yang didiktekan oleh Khalifah kepada mereka. Di antara penulis Umar yang paling terkenal adalah: Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Al-Arqam.
Sebagian orang juga mengatakan: Tidak ada diwan resmi untuk menyimpan dokumen-dokumen resmi sebelum Umar mendirikannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menulis kepada para pegawainya dan kepada kepala-kepala negara asing dalam beberapa kesempatan, dan surat-surat ini beserta jawabannya disimpan di tempat beliau di Madinah. Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun di masa Umar, surat-surat bertambah banyak dengan tingkat yang biasa, maka ia mendirikan diwan khusus untuk itu di Madinah, yang disebut Diwan Al-Insha atau Diwan Al-Rasa’il (Diwan Surat-Menyurat).
Kita dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa yang disebut Diwan Al-Insha telah mengambil bentuk yang berbeda di masa Umar dari keadaannya di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar, dan bahwa Umar telah mendirikannya sebelum diwan-diwan lainnya. Adapun diwan-diwan lain seperti Diwan Al-Atha (pemberian), Diwan Al-Jund (tentara), dan Diwan Al-Jibayah (pemungutan pajak), adalah diwan-diwan yang didirikan Umar mencontoh yang serupa pada bangsa Persia dan Romawi.
2 – Sekarang kita berbicara tentang Diwan Al-Atha, atau yang disebut Diwan Al-Amwal (Diwan Harta):
Yaitu diwan untuk mendistribusikan harta kepada rakyat dan para pekerja di berbagai perangkat negara. Diwan ini menangani masalah-masalah keuangan, pencatatannya, pencatatan orang-orang yang berhak, dan cara mendistribusikan harta kepada mereka. Catatan ini, yaitu diwan, berada di Madinah dan terdiri dari lebih dari satu catatan, sehingga setiap suku memiliki catatan khususnya sendiri. Umar sangat bersungguh-sungguh dalam memastikan pemberian dan harta sampai kepada setiap orang yang berhak mendapatkan haknya. Dikatakan bahwa Umar membawa catatan setiap suku, dan pergi sendiri kepada mereka di tempat tinggal mereka, serta memberikan pemberian mereka ke tangan mereka sendiri.
Diwan yang didirikan Umar di Madinah ini memiliki cabang-cabang di Irak, Syam, dan Mesir. Dengan demikian, setiap Muslim dapat menerima pemberiannya dari negeri tempat ia berada, dan setiap gubernur bertanggung jawab untuk menyampaikan pemberian kepada pemiliknya di wilayahnya, sebagaimana Umar menyampaikan pemberian kepada pemiliknya di Madinah dan sekitarnya.
Di samping cabang-cabang diwan Arab ini, terdapat diwan-diwan lokal yang dibiarkan tetap ada di Irak, Syam, dan Mesir, sebagaimana keadaannya sebelum Islam. Umar mempertahankan diwan-diwan ini dengan pegawai-pegawai dan bahasa-bahasanya. Diwan Syam ditulis dalam bahasa Yunani, diwan Persia dan Irak dalam bahasa Persia, dan diwan Mesir dalam bahasa Qibti. Umar membiarkan jabatan-jabatan ini di tangan non-Muslim karena para penakluk adalah orang-orang Arab yang buta huruf, tidak mahir menulis dan berhitung. Mereka menggunakan Ahli Kitab atau individu-individu dari mawali non-Arab yang menguasainya dalam urusan perhitungan, dan hal ini jarang ada di kalangan mereka.
Umar bin Al-Khaththab memerintahkan para penulisnya untuk mencatat orang-orang berdasarkan urutan nasab, dimulai dari kerabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan seterusnya, yang paling dekat kemudian yang lebih dekat. Itulah kebijakan Umar, ia membedakan dalam pemberian antara kerabat Rasul dan yang lainnya, yang paling dekat kemudian yang lebih dekat. Jika dua orang setara dalam tingkat kekerabatan, maka ia mengutamakan yang lebih dahulu masuk Islam. Umar menyatakan alasan kecenderungan itu dengan perkataannya: “Tidaklah kita meraih keutamaan di dunia, dan tidak kita mengharapkan pahala di akhirat, kecuali dengan Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau adalah yang paling mulia di antara kita, dan kaumnya adalah yang paling mulia dari orang-orang Arab.” Terhadap selain kerabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Umar mengutamakan yang lebih dahulu dari yang belakangan masuk Islam, dan ia menegaskan hal itu dengan perkataannya: “Demi Allah, aku tidak akan menyamakan orang yang memerangi Rasulullah dengan orang yang berperang bersama beliau,” yaitu dalam pemberian.
Perlu disebutkan bahwa Abu Bakar memberikan pemberian yang sama kepada kaum Muslim, tanpa memandang nasab atau keutamaan dalam Islam. Ketika disarankan kepadanya untuk membedakan antara orang-orang berdasarkan keutamaan dan keunggulan, ia berkata: “Adapun yang kalian sebutkan tentang keunggulan dan keutamaan, maka aku mengetahuinya. Namun itu adalah sesuatu yang pahalanya di sisi Allah. Dan ini adalah penghidupan,” maksudnya harta yang dibagikan kepada orang-orang adalah penghidupan, “maka persamaan di dalamnya lebih baik daripada membedakan,” artinya orang-orang mengambil dengan sama rata daripada kita membedakan di antara mereka. Namun Umar di akhir masa hidupnya condong kepada pendapat Abu Bakar, dan diriwayatkan darinya perkataannya: “Jika aku hidup hingga malam ini tahun depan, sungguh akan aku samakan yang terakhir dengan yang pertama, sehingga mereka sama dalam pemberian.” Tetapi ia wafat sebelum itu.
Umar juga menetapkan untuk perempuan dan anak-anak, ia menetapkan pemberian untuk mereka. Ia menetapkan untuk anak setelah disapih, lalu ia menyadari bahwa orang-orang mempercepat menyapih anak-anak mereka agar mendapat pemberian, maka ia memerintahkan penyeru untuk menyerukan: “Jangan kalian percepat anak-anak kalian untuk disapih, karena kami menetapkan untuk setiap bayi yang lahir dalam Islam,” dan ia menulis hal itu ke berbagai wilayah agar ditetapkan untuk setiap bayi yang lahir dalam Islam. Umar menetapkan untuk setiap bayi yang lahir seratus dirham, jika sudah agak besar menjadi dua ratus dirham, jika sudah dewasa ditambah lagi pemberiannya. Umar berkata: “Demi Dzat yang tidak ada tuhan selain Dia, tidak ada seorang pun kecuali ia memiliki hak dalam harta ini, diberikan kepadanya atau ditahan darinya. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atasnya daripada yang lain, kecuali budak yang dimiliki. Dan aku di dalamnya tidak lain seperti salah seorang dari kalian. Tetapi kita pada kedudukan kita dari Kitab Allah Azza wa Jalla dan bagian kita dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka seseorang dan pengabdiannya dalam Islam, seseorang dan masa lamanya dalam Islam, seseorang dan kontribusinya dalam Islam, dan seseorang dan kebutuhannya dalam Islam. Demi Allah, jika aku masih hidup, sungguh akan datang penggembala di gunung Shanaa mendapat bagiannya dari harta ini sementara ia di tempatnya sebelum wajahnya memerah,” yaitu dalam mencarinya.
Penetapan pemberian tidak terbatas pada orang-orang Arab Muslim, bahkan pemberian ini mencakup sebagian orang-orang non-Arab dari Muslim dan lainnya. Umar juga menetapkan untuk Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani beberapa pemberian, dan membebaskan orang-orang tua di antara mereka dari jizyah. Umar pernah melewati seorang pengemis yang sudah tua dan buta, lalu ia menepuk lengannya dari belakang dan berkata: “Dari Ahli Kitab yang mana kamu?” Ia menjawab: “Yahudi.” Ia berkata: “Apa yang memaksamu hingga aku melihatmu seperti ini?” Ia menjawab: “Meminta jizyah, kebutuhan, dan usia tua.” Maka Umar mengambil tangannya ke rumahnya, memberinya sesuatu dari harta, kemudian mengirim pesan kepada bendahara Baitul Mal dan berkata kepadanya: “Perhatikan orang ini dan sejenisnya,” maksudnya yang serupa dengannya, “Demi Allah, kita tidak berbuat adil kepadanya. Kita makan masa mudanya, kemudian mengabaikannya ketika tua,” lalu ia membaca firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang miskin” (QS. At-Taubah: 60). Maka orang-orang fakir adalah kaum Muslim, dan ini termasuk orang-orang miskin dari Ahli Kitab.
Itulah Diwan Al-Atha yang didirikan dan ditetapkan Umar, menjelaskan di dalamnya, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Islam, statistik menyeluruh untuk warga Muslim, dan beberapa yang berhak dari Ahli Kitab dan orang-orang non-Arab, serta menetapkan untuk mereka pemberian-pemberian dan gaji-gaji tetap.
3 – Kemudian sekarang kita berbicara tentang Diwan Al-Jibayah, atau Al-Kharaj dan Al-Jizyah (Pemungutan Pajak dan Upeti):
Yaitu diwan yang mencatat harta-harta yang masuk ke negara dari zakat harta kaum Muslim, kharaj, dan jizyah yang dikenakan pada tanah-tanah yang ditaklukkan dan kepala-kepala orang yang tidak masuk Islam. Di masa Umar, Suriah, Palestina, dataran rendah Irak, dan sebagian besar wilayah Persia telah ditaklukkan. Mesir dan Afrika dari wilayah-wilayah Romawi juga ditaklukkan. Abu Ubaidah menulis dari Syam, sebagaimana sebelumnya Sa’d bin Abi Waqqash menulis dari Irak kepada Umar tentang pembagian tanah, fai’ (harta rampasan), dan ghanimah di antara kaum Muslim. Namun Umar—setelah bermusyawarah dengan ahli pendapat di Madinah—membiarkan tanah yang ditaklukkan tetap di tangan penduduknya, dan menetapkan kharaj atas mereka, yaitu pajak atas tanah, dan juga menetapkan jizyah atas mereka yaitu pajak kepala. Hal ini menjadi sebab utama dalam pendirian diwan ini, yang menjadi sumber utama dari sumber-sumber Baitul Mal.
Wajib Militer dan Berdirinya Baitul Mal
Di antara hal-hal penting yang diatur dan diperhatikan oleh Umar bin Al-Khaththab adalah pengorganisasian tentara Islam dan menjadikan wajib militer sebagai kewajiban. Tentara di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam belum terorganisir. Ketika Allah mengizinkan Rasul-Nya dan para sahabatnya untuk berperang, seruan jihad adalah bagi siapa yang mau secara sukarela. Peristiwa-peristiwa dalam sirah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa beliau mewajibkan sebagian sahabatnya untuk wajib militer, artinya beliau tidak mewajibkan siapa pun untuk berperang bersama kaum Muslim. Beliau cukup dengan mendorong orang-orang beriman untuk berperang. Beliau ‘alaihissalam lebih suka ditemani dalam pertempuran oleh orang yang menghadapi perang dengan rela dan sukarela. Adapun yang lamban dan berat, beliau bersabda kepada para sahabatnya jika mereka menyebutkan orang itu: “Biarkan dia, jika ada kebaikan padanya maka Allah akan menyusulkannya kepada kalian, dan jika tidak demikian, maka Allah telah meringankan kalian darinya.” Seringkali beliau bersabda kepada orang-orang beriman menjelang pertempuran: “Tidak keluar bersama kami kecuali yang ingin berjihad.” Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya, penaklukan Makkah yang nyata, dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Jumlah orang beriman menjadi besar, dan menjadi mungkin untuk menyiapkan kelompok yang mengurusi urusan perang. Namun tidak terbentuk wajib militer yang mengikat, melainkan tampak pada kaum Muslim ciri-ciri kesukarelaan dalam sebagian besar keadaan.
Barangkala kepemimpinan tentara telah mendapat bagian yang lebih besar dari pengorganisasian resmi dibandingkan dengan perekrutan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam biasa mengangkat seseorang untuk memimpin suatu pasukan meskipun di antara mereka ada yang lebih baik darinya, karena ia lebih waspada dan lebih berpengalaman dalam peperangan. Dengan demikian kita dapat memahami pemilihannya terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib, Sa’d bin Abi Waqqash, Khalid bin Walid, dan orang-orang semacam mereka untuk memimpin pasukan-pasukan, yang merupakan rahasia kemenangan dalam sebagian besar pertempuran yang dijalani kaum muslimin pada masa hidup Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar, ia mengikuti cara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam mengajak orang untuk berperang ketika dibutuhkan, dan terus mengerahkan orang-orang yang bersedia, serta tidak memaksa mereka yang tertinggal.
Namun dalam kondisi sosial yang melanda pinggiran Jazirah Arab dan negara-negara beradab yang berbatasan dengannya, tidak ada pilihan selain mengubah keadaan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memandang sistem perekrutan dengan pandangan baru, yang di dalamnya terdapat motivasi dan ketegasan. Adapun pandangan motivasi, ia mengingatkan orang-orang tentang kekeringan Jazirah Arab dan harta rampasan yang menanti mereka dalam menyelesaikan penaklukan Irak, karena Hijaz bukanlah tempat bagi mereka yang di dalamnya terdapat kemewahan dan kemajuan. Adapun pandangan ketegasan dan intimidasi, Umar memerintahkan para gubernurnya di berbagai wilayah untuk menghadirkan setiap penunggang kuda yang gagah berani, atau yang memiliki pandangan, atau kuda, atau senjata. Jika ia datang dengan sukarela (maka baik), jika tidak, mereka harus mengerahkannya dengan paksa dan membawanya secara paksa. Artinya, ia memerintahkan mereka untuk menghadirkan kepadanya setiap orang yang mampu berperang dan memiliki peralatan perang, meskipun ia tidak rela. Ia mendesak mereka dalam hal itu dengan ketegasannya yang terkenal dengan berkata: Jangan tinggalkan seorang pun kecuali kalian kirimkan kepadaku, dan cepat, cepat, artinya bersegeralah dalam hal ini.
Namun Umar memikirkan tentang wajib militer yang ditangguhkan untuk jihad. Ia tidak puas dengan kesukarelaan para sukarelawan. Ketika ia membuat daftar diwan dan mengatur gaji tahunan bagi kaum muslimin, gagasannya terwujud. Berdirinya diwan bersamaan dengan lahirnya perekrutan militer resmi yang terorganisir, dan ditetapkan tunjangan serta gaji bagi para prajurit reguler dari baitul mal kaum muslimin.
Di antara aspek pengorganisasian yang diterapkan Umar pada tentara adalah bahwa ia mengambil dasar-dasar sebagiannya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan melakukan beberapa modifikasi padanya, serta mengadopsi sebagian lainnya dari Persia dan Romawi untuk disesuaikan dengan kebutuhan tentara Islam. Umar menggunakan pangkat naqib dan ‘arif. Al-‘arafah dalam sistem Umar ini mencakup rakyat, seolah-olah mereka adalah sipil, sementara pengangkatan komando dan mobilisasi mencakup para prajurit, yaitu militer. Ini adalah keistimewaan pertama dari keistimewaan organisasi militer pada masa Umar. ‘Arif pada masa Umar mewakili sukunya, sedangkan ‘arif dalam tentara mewakili sepuluh prajurit. Sumber-sumber sejarah yang terpercaya menunjukkan bahwa tentara Islam pada masa Umar mengenal pangkat khalifah atas lima puluh prajurit, komandan atas seratus, amir kordos atas seribu, dan amir tentara atas sepuluh ribu atau lebih. Umar mendirikan kamp pelatihan di Madinah sebelum pengiriman pasukan, dan ia mengawasi sendiri pelatihan prajurit, terutama penunggang kuda di tempat bernama al-Ham yang dekat Madinah, sehingga ia menyaksikan—jika boleh dikatakan demikian—parade militer atau manuver perang. Ia membawa serta dalam latihan harian itu para ahli unta, yaitu para pakar penyakit dan kondisi unta, untuk mengawasi perawatan veterinernya.
Ia mengangkat Salman bin Rabi’ah al-Bahili untuk mengurusi kuda-kuda tentara di Kufah, sehingga orang-orang memanggilnya Salman al-Khail karena pengabdiannya dalam urusan itu dan keahliannya. Umar mendirikan benteng-benteng dan kamp-kamp permanen untuk istirahat para prajurit selama perjalanan, setelah sebelumnya mereka menempuh jarak jauh dengan menunggang kuda dan unta, dan hanya beristirahat di gubuk-gubuk yang terbuat dari pelepah kurma. Kemudian ia mendirikan kota-kota untuk prajuritnya agar mereka tinggal jauh dari penduduk tanah yang ditaklukkan. Garnisun-garnisun didirikan untuk menangkal serangan mendadak musuh. Kemudian ia membuat diwan tentara dan menetapkan gaji tetap bagi mereka. Ini adalah keistimewaan dari keistimewaan-keistimewaan dan kebanggaan dari kebanggaan-kebanggaan Umar, serta sebab terbentuknya tentara reguler.
Di antara hal-hal yang didirikan Umar juga adalah baitul mal.
Tidak ada kebutuhan mendesak untuk keberadaan baitul mal pada masa Rasulullah yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam, karena kehidupan masih sederhana. Pemasukan dari harta rampasan perang, zakat, dan lainnya datang ke negara yang baru berdiri, dan segera dibagikan kepada yang berhak, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Surah at-Taubah: 60) dan dalam firman Allah Ta’ala: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.” (Surah al-Anfal: sebagian ayat 41). Abu Bakar mengikuti cara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan melakukan seperti yang beliau lakukan. Urusan berjalan demikian pada masa awal kekhalifahan Umar. Namun meluasnya wilayah penaklukan meningkatkan harta fai’, sebagaimana membuka sumber lain yang lebih berlimpah dan lebih kekal, yaitu sumber kharaj dan jizyah. Melimpahnya harta dan sumber ini—sebelum selesainya penaklukan Persia dan sebelum dimulainya penaklukan Mesir—mencapai tingkat yang membuat Khalifah Umar memikirkan pembentukan sistem keuangan untuk negara yang baru berdiri. Maka tidak ada pilihan selain melakukan pengembangan dalam sistem negara Islam pada masa Umar bin Khattab, karena lamanya masa kepemimpinannya, dan karena Allah membukakan bagi kaum muslimin dalam masa kekhalifahannya negeri Persia, Syam, dan Mesir. Urusan negara Islam menjadi bercabang-cabang, tuntutannya bertambah, keuangannya meningkat. Pada saat yang sama, negara yang baru lahir ini berhubungan dengan peradaban-peradaban yang sudah mapan di negara-negara yang ditaklukkan, yang menyadarkan Umar untuk memanfaatkan sistem-sistem yang ada di negara-negara tersebut untuk memecahkan masalah-masalah administratif dan organisasional yang dihadapi negara Islam, dan untuk memajukannya beberapa langkah ke depan.
Demikianlah Umar mendirikan diwan-diwan sebagaimana telah disebutkan, dan sudah menjadi keharusan bagi Umar untuk mendirikan baitul mal, meletakkan fondasi-fondasinya, dan memajukannya. Ia telah mengangkat para hakim dan gubernur, mengatur prajurit, dan menjadikan kemiliteran sebagai pekerjaan tetap sebagaimana kita lihat. Para prajurit mulai bertugas di wilayah-wilayah perbatasan, dan mereka memiliki diwan tentara. Telah ditetapkan untuk mereka dan keluarga mereka gaji dan tunjangan yang teratur. Ia juga menetapkan pemberian untuk kaum muslimin, dan mereka memiliki diwan pemberian. Ia mendirikan diwan pemungutan untuk menerima kharaj dan jizyah. Komitmen Umar terhadap pemberian dan pencairan gaji kepada prajurit dan pegawainya membuatnya memerlukan tabungan untuk memenuhi komitmennya, dan oleh karena itu ia memerlukan baitul mal untuk menyimpan tabungan ini dan daftar orang-orang yang berhak. Baitul mal mencakup pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan harta negara, mulai dari zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan lain-lain.
Baitul mal disebut juga diwan tinggi atau diwan harta, dan ia adalah asal dari diwan-diwan dan rujukannya. Fungsinya adalah mencatat dalam arsipnya semua hak-hak baitul mal menurut kategori-kategorinya, baik berupa uang, hasil pertanian, maupun hewan. Ia juga mencatat harta yang menjadi kewajiban baitul mal seperti gaji tentara, hakim, harga senjata yang dibutuhkan, dan lain-lain yang dibelanjakan untuk kepentingan umum.
Syariat Islam dengan sistem-sistemnya telah memberikan kesempatan untuk mengatur urusan keuangan dalam Islam. Allah telah menjelaskan tempat-tempat penyaluran zakat, seperlima harta rampasan perang, dan fai’. Allah diam tentang penjelasan tempat-tempat penyaluran lainnya, menyerahkan hal itu kepada ijtihad para pemimpin, karena bagian yang dahulu untuk Rasulullah setelah wafatnya dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.
Demikianlah mengenai hal-hal yang didirikan oleh Umar radhiyallahu Ta’ala ‘anhu. Kita telah melihat bagaimana Umar menghentikan pemberian kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf) dan kerabat. Dengan demikian tersedialah bagi para pemimpin untuk mengatur hal-hal ini sesuai dengan kebutuhan. Umar menyalurkan zakat, seperlima harta rampasan perang, dan fai’ sesuai dengan yang telah ditetapkan syariat Islam. Ia menyimpan dari selain itu di baitul mal sejumlah yang cukup untuk memenuhi pengeluaran lain dan gaji sepanjang tahun. Demikianlah ia mendirikan baitul mal yang dianggap sebagai kementerian keuangan pertama dalam negara Islam.
Dengan ini kita telah menyelesaikan kuliah ini. Saya menitipkan kalian kepada Allah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5 – Pengawasan Umar bin Khattab terhadap Para Pegawainya, Administrasi pada Masa Bani Umayyah, dan Kewaziran dalam Islam
Pengawasan Umar bin Khattab terhadap Para Pegawainya
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, junjungan kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita telah membahas dalam kuliah sebelumnya tentang administrasi pada masa Umar bin Khattab, dan telah menjelaskan organisasi-organisasi administratif yang didirikan Umar bin Khattab yang terdiri dari berbagai diwan, kemudian pendiriannya baitul mal, lalu penetapannya wajib militer dalam tentara muslim. Sekarang kita ingin membahas tentang pengawasan Umar terhadap para pegawainya.
Umar memiliki cara-cara khususnya dalam memilih gubernur dan pegawai. Ia tidak mengangkat seorang gubernur atau pegawai kecuali setelah ujian yang luas, baik terbuka maupun rahasia, dan setelah ia menanyakan tentangnya dan memastikan kelayakannya. Ia mensyaratkan kepadanya agar tidak menutup pintunya dari kebutuhan-kebutuhan rakyat. Ia juga tidak mengangkat seseorang yang meminta jabatan tersebut. Ia berkata dalam hal itu: Barangsiapa meminta urusan ini, maka ia tidak akan diberi kekuasaan atasnya, artinya: tidak akan dimungkinkan baginya. Ia mengikuti cara ini meneladani Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada orang yang meminta jabatan: “Sesungguhnya kami tidak menggunakan dalam pekerjaan kami orang yang memintanya.”
Umar tidak mengangkat siapa pun yang tidak memiliki kasih sayang. Ia pernah memerintahkan untuk menulis surat pengangkatan untuk seorang laki-laki yang telah diujinya dan ingin mengangkatnya. Ketika penulis sedang menulis, datanglah seorang anak laki-laki lalu duduk di pangkuan Umar, maka ia mengelus-elusnya. Laki-laki itu berkata: Wahai Amirul Mukminin, aku memiliki sepuluh anak sepertinya, tidak ada satu pun dari mereka yang mendekat kepadaku. Umar berkata: Maka apa salahku jika Allah Azza wa Jalla telah mencabut kasih sayang dari hatimu. Sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hamba-Nya yang penyayang. Kemudian ia berkata: Robek surat itu, karena jika ia tidak mengasihi anak-anaknya, bagaimana ia bisa mengasihi rakyat. Umar melarang para pegawai dan gubernurnya untuk terlibat dalam transaksi-transaksi umum, baik sebagai penjual maupun pembeli. Diriwayatkan bahwa seorang pegawai Umar bin Khattab bernama al-Harits bin Ka’b bin Wahb menampakkan kekayaan. Umar bertanya kepadanya tentang sumber kekayaannya, ia menjawab: Aku keluar dengan modal yang kubawa lalu aku berdagang dengannya. Umar berkata: Demi Allah, kami tidak mengutus kalian untuk berdagang. Lalu ia mengambil darinya keuntungan yang diperolehnya.
Umar tidak mengangkat seorang pun dari kerabatnya. Ia telah mengumumkan prinsip ini dalam pemilihan sejak ia menjabat sebagai pemimpin, ketika ia berkata: “Barangsiapa memegang urusan kaum muslimin lalu mengangkat seseorang karena persahabatan atau kekerabatan, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.” Umar mengikuti cara ini meneladani cara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan tidak mengangkat kerabat untuk jabatan-jabatan penting di berbagai wilayah. Umar menjelaskan kepada orang-orang sikapnya terhadap para gubernur, ia berkata: Aku bertanggung jawab atas amanahku dan apa yang aku jalani, dan mengawasi apa yang hadir padaku dengan diriku sendiri insya Allah. Aku tidak mampu (mengawasi) yang jauh dariku kecuali dengan orang-orang terpercaya, artinya: aku tidak mengangkat untuk pekerjaanku yang jauh dariku kecuali orang-orang yang amanah dan orang-orang yang pemaaf di antara kalian terhadap masyarakat umum.
Ia juga menegaskan kebijakannya terhadap para pegawainya dengan berkata: Wahai manusia, demi Allah aku tidak mengirim kepada kalian pegawai-pegawai untuk memukuli tubuh kalian dan tidak untuk mengambil sepersepuluh kalian, tetapi aku mengutus mereka untuk mengajari kalian agama dan sunnah kalian. Barangsiapa diperlakukan dengan sesuatu selain itu, maka hendaklah ia laporkan kepadaku. Demi Zat yang jiwa Umar di tangan-Nya, sungguh aku akan menghukumnya. Ia berkata kepada para pegawainya di hadapan orang-orang: Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak mengutus kalian sebagai penguasa atau tiran, tetapi aku mengutus kalian sebagai pemimpin petunjuk agar kalian menjadi teladan. Maka tunaikan hak-hak kaum muslimin dan jangan memukuli mereka sehingga kalian menghinakan mereka, jangan mengingkari hak mereka sehingga kalian memfitnah mereka, jangan menutup pintu-pintu dari mereka sehingga orang kuat mereka memakan yang lemah, jangan mementingkan diri sendiri atas mereka sehingga kalian menzalimi mereka, dan jangan bersikap kasar kepada mereka. Jika kalian melihat mereka lelah, maka berhentilah dari itu, karena itu lebih efektif dalam perang melawan musuh kalian. Wahai manusia, aku persaksikan kalian atas para amir di berbagai wilayah, sesungguhnya aku tidak mengutus mereka kecuali untuk mengajari orang-orang tentang agama mereka, membagikan kepada mereka harta fai’ mereka, dan menghukumi di antara mereka. Jika ada sesuatu yang membingungkan mereka, maka hendaklah mereka ajukan kepadaku.
Umar menetapkan untuk para pegawai, panglima tentara, dan kepala desa dalam pemberian sesuai dengan kebutuhan mereka akan makanan dan apa yang mereka kerjakan, agar tidak ada alasan bagi seorang pun dari mereka sehingga tangannya tidak terulur kepada yang bukan haknya. Umar memilih untuk jabatan gubernur orang-orang yang paling baik dan paling mampu untuk mengurusi urusan kaum muslimin, dan ia tidak tunduk dalam hal itu terhadap tekanan atau godaan apa pun. Ia mengatur cara-cara perhitungan untuk para pegawainya yang membuatnya seolah-olah berada bersama mereka di mana pun mereka berada, dan menempatkan pengawas dan mata-mata kepada mereka yang membawa berita secara terus-menerus. Di antara hal-hal yang ia praktikkan dengan para pegawainya adalah bahwa ia menghitung kekayaan para gubernur ketika mengangkat mereka, artinya: ia menghitung harta para pegawai dan gubernur sebelum menjabat untuk menghitung pertambahan mereka setelah menjabat yang tidak masuk dalam hitungan kenaikan yang wajar. Barangsiapa dari mereka yang berdalih dengan perdagangan, ia tidak menerima klaimnya. Ia berkata kepada mereka: Sesungguhnya kami mengutus kalian sebagai gubernur, bukan sebagai pedagang. Umar mengandalkan dalam menghitung para pegawainya pada berbagai cara yang teliti, di antaranya adalah ia menempatkan pengawas dan mata-mata di sekitar mereka untuk melaporkan kepadanya apa yang tampak dan yang tersembunyi dari urusan mereka, sehingga gubernur baik yang besar maupun kecil takut kepada orang-orang terdekatnya bahwa mereka akan melaporkan beritanya kepada khalifah. Umar mengirim dari sisinya utusan-utusan yang mengumpulkan keluhan-keluhan orang yang mengeluh dan melakukan investigasi serta peninjauan terhadapnya, agar sempurna penelitian terhadap apa yang dilaporkan para pengawas dan mata-mata. Di antaranya adalah bahwa ia memerintahkan para gubernur dan pegawai untuk memasuki wilayah mereka pada siang hari ketika mereka kembali dari jabatan mereka agar tampak apa yang mereka bawa dalam kepulangan mereka dan beritanya sampai kepada para penjaga dan pengawas yang ia tempatkan di sepanjang jalan.
Umar tidak hanya puas dengan memilih para pegawainya dengan baik, tetapi ia juga berupaya maksimal untuk mengawasi mereka setelah mereka memangku jabatan; untuk memastikan bahwa perilaku mereka baik dan karena khawatir jiwa mereka akan menyimpang. Prinsipnya bagi mereka adalah: “Lebih baik bagiku memberhentikan seorang pejabat setiap hari daripada membiarkan orang yang zalim berkuasa satu jam saja di siang hari.” Dan ia berkata: “Pejabatku manapun yang menzalimi seseorang dan kezalimannya sampai kepadaku namun aku tidak mengubahnya, maka aku telah menzaliminya.” Dan ia berkata suatu hari kepada orang-orang di sekelilingnya: Bagaimana pendapat kalian jika aku mengangkat orang yang terbaik yang aku ketahui atas kalian, kemudian aku memerintahkannya untuk berlaku adil, apakah aku sudah menunaikan kewajibanku? Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: Tidak, sampai aku melihat pekerjaannya, apakah ia mengerjakan apa yang kuperintahkan atau tidak. Dan ia berkata: Mudahlah bagiku memperbaiki suatu kaum dengan mengganti seorang pemimpin dengan pemimpin yang lain.
Ketika Umar mengangkat seorang pejabat, ia mencatat hartanya, dan ia telah membagi harta lebih dari satu orang di antara mereka ketika memberhentikan mereka, di antaranya Sa’ad bin Abi al-Ash dan Abu Hurairah, para pejabatnya di Irak dan Bahrain. Ia memerintahkan para pejabatnya agar masuk pada siang hari dan tidak masuk pada malam hari agar mereka tidak menyembunyikan sesuatu dari harta sebagaimana telah kami sebutkan. Sa’ad bin Abi Waqqash membangun rumah untuk tempat tinggalnya di Kufah, dan pasar-pasar dekat dengan rumahnya. Suara-suara keras di pasar mengganggu Sa’ad, maka ia memasang pintu yang membatasi dirinya dari suara-suara orang di pasar. Hal itu sampai ke telinga Umar tentang rumah Sa’ad dan pintunya, dan bahwa orang-orang menyebutnya istana Sa’ad. Maka ia memanggil Muhammad bin Maslamah dan mengirimnya ke Kufah, dan berkata kepadanya: Pergilah ke istana itu, maksudnya: pergilah ke istana itu sampai kau membakar pintunya, kemudian kembalilah segera, maksudnya: kembalilah secepatnya. Maka ia berangkat hingga tiba di Kufah, lalu membeli kayu bakar, kemudian mendatanginya ke istana dan membakar pintunya, yaitu: pintu yang menghalangi rakyat dari pemimpin atau dari gubernur.
Ia melaksanakan beberapa hukuman publik bagi gubernur yang menyimpang. Telah sampai kepada Umar bahwa gubernur Homs, Abdullah bin Qurt, telah membuat bangunan tinggi yang ia gunakan untuk mengasingkan diri dari orang-orang – tempat yang tinggi – maka ia mengirimkan utusan kepadanya dan memerintahkannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar pintunya. Ketika utusan itu tiba di Homs, ia mengumpulkan kayu bakar dan membakar pintu bangunan tinggi itu. Orang-orang masuk menemui gubernur dan memberitahukan kabar kepadanya. Ia berkata kepada mereka: Biarkan dia, ia adalah utusan Amirul Mukminin. Kemudian utusan itu masuk menemuinya dan memberikan surat kepadanya. Ia tidak meletakkan surat itu dari tangannya sampai ia naik kendaraan. Ketika Umar melihatnya, ia berkata: Tahanlah dia dariku di bawah terik matahari selama tiga hari. Ini adalah hukuman publik bagi gubernur yang ingin meninggikan diri di atas rakyat dan yang ingin menutup pintunya di hadapan mereka. Orang-orang adalah sama di hadapannya. Oleh karena itu, sampai kepada Umar keluhan salah seorang Muslim bahwa gubernurnya, Abu Musa al-Asy’ari di Bashrah, telah memberikan sebagian bagian orang itu, namun ia menolak menerimanya kecuali sepenuhnya, maka Abu Musa mencambuknya dua puluh kali dan mencukur rambutnya. Oleh karena itu, Sayyidina Umar – semoga Allah tabaraka wa ta’ala meridhainya – meminta qishash (pembalasan) untuk orang ini dari Abu Musa, maksudnya: apa yang dilakukan Abu Musa terhadap orang ini, Umar bin al-Khaththab memerintahkan orang yang terkena tindakan itu untuk melakukan qishash terhadap Abu Musa al-Asy’ari.
Ia memberhentikan para gubernurnya karena dugaan-dugaan. Umar menerapkan kebijakan pemberhentian bahkan karena dugaan sebagai tindakan berjaga-jaga. Sekelompok orang dari Irak mengadu tentang Sa’ad bin Abi Waqqash, sahabat yang mulia, bahwa ia tidak membagi secara sama, tidak adil dalam perkara, dan tidak berperang dalam pasukan, maka ia memberhentikannya. Ia juga memberhentikan karena dugaan Khalid bin al-Walid, Abu Musa al-Asy’ari, al-Mutsanna bin Haritsah, dan lainnya bukan karena aduan atau qishash, tetapi karena dugaan yang muncul. Pendapatnya adalah menjauhi dugaan demi keselamatan negara. Sungguh merupakan kebijakan Umar jika terbukti ada dugaan penyelewengan terhadap harta kaum muslimin, maka ia menyita harta yang diperoleh atau membaginya terhadap kelebihan dari penghasilan wajar, ia meninggalkan separuhnya baginya dan memasukkan separuh lainnya ke baitul mal, ini di samping pemberhentian atau hukuman yang dijatuhkannya.
Ada kantor khusus untuknya yang menyerupai badan intelijen. Metode Umar dalam pemerintahan adalah memberikan kebebasan kepada pejabat dalam urusan lokal dan membatasinya dalam masalah umum serta mengawasi perilaku dan tindakannya. Ia memiliki badan rahasia yang terhubung dengannya untuk mengawasi kondisi para gubernur dan rakyat. Sumber-sumber sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa yang menyerupai intelijen hari ini sudah ada pada masa Umar. Sebagian orang berkata: Pengetahuan Umar tentang para pejabatnya yang jauh darinya sama seperti pengetahuannya tentang orang yang bermalam bersamanya di ranjang yang sama dan di bantal yang sama. Tidak ada di negeri manapun atau daerah manapun seorang pejabat atau panglima tentara kecuali ada mata yang tidak meninggalkannya. Ucapan-ucapan orang-orang di timur dan barat ada padanya setiap petang dan pagi mengingat apa yang kami sebutkan. Kita menyadari bahwa Umar sangat keras dan tegas terhadap para pejabatnya. Kebijakan ini mencerminkan kewaspadaannya agar para pejabat daerah tidak mengambil dari harta kaum muslimin. Ketika ia merasakan hal itu, ia membagi separuhnya sebagaimana kami sebutkan.
Umar bertanya kepada rakyat ketika mereka datang ke Hijaz pada musim haji tentang keadaan para pemimpin mereka dan perilaku mereka terhadap mereka. Mereka berkata baik. Lalu ia berkata: Apakah pemimpin kalian menjenguk orang sakit kalian, maksudnya: apakah ia mengunjungi orang sakit kalian? Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: Apakah ia menjenguk budak? Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: Bagaimana ia memperlakukan orang yang lemah, maksudnya: bagaimana ia berhubungan dengan orang lemah? Apakah ia duduk di pintunya? Jika mereka menjawab tidak untuk salah satu kebiasaan tersebut – ia memberhentikannya. Sebagian orang berkata dalam hal ini: Sesungguhnya Umar telah menjadikan musim haji sebagai konferensi umum tahunan untuk meminta pertanggungjawaban para gubernur di hadapan rakyat. Di sini Umar, menurut pendapat kita, mencapai puncak seni dalam pemerintahan dan administrasi. Allah telah mewajibkan haji kepada kaum muslimin sebagai rukun dari rukun akidah, dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan agar mereka mengingat nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini adalah musim di mana kaum muslimin dari timur dan barat bumi bertemu. Sungguh merupakan kejeniusan sejati dari Umar dan ilham asli padanya bahwa ia berusaha memanfaatkan kesempatan ini agar ia sendiri mengetahui kabar rakyatnya yang tidak dapat menghubunginya. Demikianlah ia lakukan sepanjang masa khilafahnya, setiap tahun ia mengumpulkan dan memanggil para gubernur daerah untuk menemuinya di Makkah. Di sana ia bertemu dengan para penguasa dan yang dikuasai secara langsung, mendengar dari mereka semua, dan menunaikan amanah pemerintahan dengan sempurna.
Pemikiran Umar sebelum terbunuh adalah bahwa ia akan berkeliling ke wilayah-wilayah secara pribadi, seperti semacam perjalanan inspeksi ke daerah-daerah; untuk mengawasi para pejabat, memeriksa kondisi rakyat, dan memastikan urusan negara yang luas. Umar berkata: Jika aku hidup – insya Allah – aku akan berkeliling di tengah rakyat selama setahun, karena aku tahu bahwa orang-orang memiliki keperluan yang terputus dariku – maksudnya: tidak sampai kepadaku. Adapun para pejabat mereka, mereka tidak menyampaikannya kepadaku, dan mereka sendiri tidak dapat menghubungiku. Maka aku akan pergi ke Syam dan tinggal di sana dua bulan, kemudian pergi ke Jazirah dan tinggal di sana dua bulan, pergi ke Mesir dan tinggal di sana dua bulan, kemudian pergi ke Bahrain dan tinggal di sana dua bulan, kemudian pergi ke Makkah dan tinggal di sana dua bulan, kemudian pergi ke Bashrah dan tinggal di sana dua bulan. Demi Allah, sungguh baik perjalanan tahunan ini.
Dengan ini kami cukupkan pembahasan tentang administrasi pada masa Umar bin al-Khaththab.
Administrasi pada Masa Bani Umayyah
Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab tetap menjadi landasan kokoh bagi organisasi administrasi sepanjang masa Khulafaur Rasyidin, dan menjadi standar yang tepat yang dijadikan rujukan oleh orang-orang untuk menilai para gubernur dan perilaku mereka. Standar ini mulai mengalami guncangan hebat sejak akhir khilafah Utsman bin Affan, ketika saat itu ambisi kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah terlepas, dan mereka berupaya memanfaatkan hubungan kekerabatan antara mereka dengan khalifah ini untuk mewujudkan keinginan mereka menguasai pusat-pusat terbesar negara. Tindakan ini membangkitkan perasaan orang-orang karena mereka merasakan kekacauan organisasi administrasi yang ditetapkan oleh Umar bin al-Khaththab untuk mereka. Ketidakpuasan yang melanda wilayah-wilayah negara Islam pada akhir masa Utsman bin Affan yang dikenal dengan nama fitnah, mengungkapkan keterkaitan antara sistem politik dan administrasi dalam negara Islam dan sejauh mana masing-masing dipengaruhi oleh yang lain. Ketika tali organisasi administrasi kacau, sistem politik pun kacau, dan Khalifah Utsman bin Affan membayar nyawanya sebagai harga bagi kekacauan administrasi dalam negara ini. Khalifah baru yaitu Ali bin Abi Thalib tidak mampu mengendalikan situasi karena ia tidak dapat menetapkan organisasi administrasi negara Islam. Sudut pandang khalifah ini adalah memberhentikan semua pejabat Utsman bin Affan, termasuk Mu’awiyah bin Abi Sufyan, karena mereka dianggap sebagai penyebab fitnah yang melanda negara Islam. Ia memilih sekelompok pejabat lain dan mengirimkan mereka ke pusat-pusat wilayah Islam. Namun pejabat yang dikirim ke wilayah Syam tidak mampu memasuki wilayah ini karena pasukan Mu’awiyah menghalanginya. Perselisihan pun terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, yang berakhir dengan berdirinya Dinasti Umayyah.
Situasi politik baru yang didasarkan pada sistem khilafah turun-temurun ini menuntut organisasi administrasi baru. Mu’awiyah bin Abi Sufyan mengambil tanggung jawab meletakkan dasar-dasarnya. Khalifah Umayyah pertama ini membuktikan bahwa ia ahli dalam mengoordinasikan antara sistem politik dan administrasi ketika ia berupaya mengambil desentralisasi dalam administrasi sebagai jalan untuk mengembalikan stabilitas dalam negara Islam di bawah situasi barunya dan juga berupaya memperluas wilayahnya. Karena itu, tindakan-tindakan Mu’awiyah bin Abi Sufyan membentuk dasar-dasar sistem administrasi desentralisasi dan tradisi yang diikuti oleh para khalifah Dinasti Umayyah yang datang setelahnya.
Hal pertama yang dilakukan Mu’awiyah dalam meletakkan dasar sistem administrasi desentralisasi adalah pemilihan dan persiapan badan yang baik yang akan melaksanakan kebijakan dan institusi administrasi baru dalam negara Islam. Ia menjadikan dasar badan administrasi ini bukan hanya kompetensi, tetapi juga keharusan bekerja agar orang-orangnya adalah dari pendukungnya yang setia atau dari mereka yang terikat dengan Dinasti Umayyah melalui ikatan materi atau kepentingan yang diperlukan oleh perkembangan baru negara. Mu’awiyah berhasil meletakkan dasar sistem administrasi desentralisasi dengan bantuan tiga faktor: Pertama: pekerjaannya setelah masuk Islam bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kedua: Lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang. Ketiga: Studi tentang perkembangan baru yang melanda wilayah-wilayah negara Islam sejak akhir masa Khulafaur Rasyidin. Lingkungan di mana Mu’awiyah tumbuh juga memiliki pengaruh besar dalam memilih orang-orang administrasinya yang desentralisasi dengan kepercayaan, studi, dan pengetahuan yang kokoh. Ia adalah anak Abu Sufyan, pemimpin Makkah dan tokoh terbesar yang paling bijaksana dan berpengalaman serta paling luas hubungan dan pengalaman dengan keluarga-keluarga besar di kota-kota Hijaz dan di luarnya juga. Mu’awiyah mempelajari dari ayah yang berpengalaman ini dasar-dasar pemerintahan dan administrasinya sebagaimana dipahami oleh penduduk Makkah, dan sesuai sudut pandang yang diyakini oleh Abu Sufyan tentang pembentukan pendukung dan pengikut serta merekrut orang-orang dan pejabat.
Pilihan Mu’awiyah jatuh pada putra-putra Tsaqif dari penduduk Thaif untuk membentuk administrasi barunya. Dari Bani Tsaqif muncul pada masa Mu’awiyah al-Mughirah bin Syu’bah yang menjabat sebagai pemimpin Kufah, dan Ziyad bin Abihi yang menjabat sebagai pemimpin Bashrah. Kedua orang ini dengan kesetiaan yang mendalam dan idealisme yang luar biasa mengusung bendera sistem administrasi desentralisasi di timur negara, dan berkontribusi bersama Mu’awiyah dalam meletakkan dasar sistem baru ini dan menetapkannya. Akhirnya Mu’awiyah memperkuat kelompok orang-orang administrasinya ini dengan kelompok yang dipilihnya dari mereka yang memiliki pengalaman luas dan juga dari mereka yang memiliki ambisi yang dapat dimanfaatkan melaluinya untuk mewujudkan tujuan sistem desentralisasinya. Karena itu muncul kelompok baru dari orang-orang yang dimanfaatkan oleh Mu’awiyah untuk menciptakan keseimbangan dalam administrasi desentralisasi dan berbagai badan yang bekerja di dalamnya. Kelompok ini terdiri dari putra-putra kelas menengah Quraisy yang Bani Umayyah tidak takut akan bahaya atau kerugian dari mereka, dan dimungkinkan untuk mengandalkan mereka dalam mengelola daerah terpencil atau wilayah-wilayah yang penuh dengan penyebab fitnah dan kerusuhan.
Muawiyah bin Abi Sufyan menetapkan dua aturan lain untuk menjamin berjalannya sistem desentralisasi dengan baik dan untuk mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi pada para pejabatnya. Aturan pertama adalah memisahkan administrasi keuangan wilayah dari ketergantungan kepada gubernur dan menjadikannya tunduk langsung kepada Khalifah di Damaskus. Kepala administrasi tersebut dikenal dengan nama Pemilik Kharaj (Shahibul Kharaj) yang menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh gubernur wilayah, terutama karena semua urusan keuangan berada di tangannya. Namun, penerapan aturan ini tidak mutlak, karena Bani Umayyah mempercayakan kepada sejumlah gubernur mereka yang terbukti setia dan sangat pengabdian untuk mengelola urusan keuangan atau menunjuk Pemilik Kharaj dari pihak mereka. Para gubernur tersebut kemudian memiliki kekuasaan yang luas dan merupakan contoh terbaik dari kepercayaan Bani Umayyah terhadap keamanan sistem administrasi desentralisasi mereka.
Aturan kedua yang ditetapkan oleh Bani Umayyah adalah menunjuk petugas untuk mengelola wilayah-wilayah yang tugasnya adalah berkorespondensi langsung dengan Khalifah dan memberitahukan segala yang terjadi di wilayah tersebut, baik yang berkaitan dengan gubernur maupun penduduk. Namun, aturan ini juga tidak menjadi pembatasan bagi para gubernur wilayah, melainkan merupakan cara untuk berpartisipasi dalam pengarahan yang menjaga stabilitas sistem administrasi mereka dan menghindari jebakan yang mungkin tidak disadari oleh para gubernur sendiri. Bani Umayyah tetap bersemangat memberikan kebebasan penuh kepada para gubernur wilayah karena keyakinan mereka bahwa saksi mata lebih mampu daripada Khalifah yang tinggal di Damaskus untuk memahami kondisi sebenarnya dan dengan demikian dapat memutuskan tanpa merugikan kepentingan rakyat. Para khalifah Bani Umayyah menghormati kebebasan yang dinikmati oleh para gubernur wilayah, terutama para khalifah yang dikenal sangat peduli terhadap kepentingan umum. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal karena keadilannya sebagai khalifah kelima yang bijaksana, yang bersemangat mengembalikan kebijakan Umar bin Khattab dalam mengelola negara Islam. Khalifah ini tetap berpegang pada aturan dasar sistem administrasi desentralisasi negara Umayyah dan menegaskan kebebasan para gubernur, serta mengarahkan masing-masing dari mereka untuk bekerja dengan kebebasan bertindak dan tanpa harus merujuk kepadanya dalam beberapa masalah yang penundaan keputusannya dapat merugikan kepentingan penduduk wilayah mereka.
Para ahli fikih Muslim mendefinisikan bentuk administrasi desentralisasi wilayah ini sebagai Imarah Istikfa (Kepemimpinan Pendelegasian), yaitu yang dibentuk oleh Khalifah untuk orang yang dipilihnya dari orang-orang yang cakap, dengan mendelegasikan kepada mereka kepemimpinan wilayah atas seluruh penduduknya, dan menjadikannya memiliki wewenang umum dalam semua urusannya. Maka Imarah Istikfa menjadi bentuk keistimewaan yang diberikan Khalifah kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan besar atau jasa besar bagi negara. Khalifah memberikan kepada individu dari mereka wewenang penuh atas suatu daerah tertentu atau beberapa daerah, artinya Khalifah mempercayakan kepada sekelompok orang ini tanpa yang lain, dan di tangan mereka semua kewenangan atas apa yang mereka pegang, sehingga mereka bertanggung jawab atas harta, peradilan, dan kepemimpinan umat.
Pemerintahan desentralisasi menuntut reorganisasi administrasi negara dengan cara yang memungkinkan Bani Umayyah mengendalikan secara efektif kendali urusan, dan mengarahkannya pada saat yang sama untuk menjamin kehormatan dan penghormatan bagi kekuasaan mereka di setiap tempat. Pembagian ini merupakan respons terhadap perkembangan yang terjadi di negara-negara Islam sejak fitnah pada masa Khalifah Utsman dan perbedaan orientasi dan keinginan yang menyertai perkembangan ini. Kemudian, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Bani Umayyah di Timur dan Barat menambah wilayah-wilayah luas ke negara Islam yang harus diatur untuk mencapai keharmonisan administrasi dengan negara yang luas. Bani Umayyah membagi negara mereka menjadi beberapa wilayah, yaitu: Wilayah Syam, kemudian Wilayah Tanah Arab, kemudian Wilayah Irak, kemudian Wilayah Jazirah, kemudian Wilayah Mesir.
Dengan ini kita telah selesai membahas tentang organisasi administrasi dalam penerapan praktis, di mana kita menjelaskan administrasi pada masa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, administrasi pada masa Abu Bakar, administrasi pada masa Umar bin Khattab, dan administrasi pada masa Bani Umayyah.
Pelajaran: 15 Hukum dan Jenis-Jenis Kementerian serta Hubungan Muslim dengan Non-Muslim dan Perjanjian
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Pengawasan Umar bin Khattab terhadap Pejabatnya, Administrasi pada Masa Bani Umayyah, dan Kementerian dalam Islam
Pengantar tentang Kementerian dalam Negara Islam
Sekarang kita membahas topik lain yaitu perangkat administrasi dalam negara. Al-Mawardi membagi wakil-wakil khalifah menjadi empat bagian:
Pertama: Pemilik wewenang umum dalam pekerjaan umum, yaitu para menteri.
Kedua: Pemilik wewenang umum dalam pekerjaan khusus, yaitu para gubernur wilayah.
Ketiga: Pemilik wewenang khusus dalam pekerjaan umum, seperti Hakim Agung.
Keempat: Pemilik wewenang khusus dalam pekerjaan khusus, seperti hakim suatu negeri tertentu atau wilayah tertentu.
Kita membahas tentang fungsi para wakil, yaitu: Pertama: Kementerian, Kedua: Kepemimpinan wilayah. Kita akan menjelaskan atau menyoroti Kementerian dan Kepemimpinan sebagai berikut.
Pertama: Kementerian
Kementerian dianggap sebagai salah satu manifestasi paling menonjol dari kekuasaan eksekutif dalam negara modern. Bahkan ketika istilah kekuasaan eksekutif disebutkan, ia mengacu pada Kementerian yang diberi tugas melaksanakan undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif. Biasanya kepala negara menugaskan seorang yang cakap untuk membentuk Kementerian, dan kepala negara mungkin melakukan pembentukan ini sendiri sehingga ia menjadi Menteri Pertama atau Ketua Dewan Menteri. Para menteri biasanya dipilih dari orang-orang yang cakap dan memiliki spesialisasi masing-masing di bidangnya. Untuk setiap administrasi negara atau fasilitasnya, ditunjuk seorang menteri yang menangani urusan fasilitas tersebut dan bertanggung jawab atas hal itu kepada Ketua Dewan Menteri. Para ulama fikih politik syariah telah membahas tentang Kementerian, di antaranya Al-Mawardi misalnya, dan kita akan menyajikan sebagian dari pembahasan para ulama tentang hal itu sebagai berikut.
Makna Kementerian:
Kementerian diambil dari kata kerja “wazara”, dan “wizr” adalah tempat berlindung. Dari sinilah firman Allah Ta’ala: “Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung” (Surah Al-Qiyamah: 11). “Wizr” juga bisa berarti beban berat, dari sinilah disebut menteri (wazir) adalah orang yang memikul beban raja dan membantunya dengan pendapatnya. “Wazarahu” pada suatu perkara berarti membantunya dan menguatkannya, asalnya adalah “azarahu”. Menteri khalifah berarti orang yang diandalkan pendapatnya dalam urusan-urusannya dan tempat ia berlindung. Disebut menteri sultan sebagai “wazir” karena ia memikul beban apa yang diserahkan kepadanya dari pengelolaan kerajaan.
Al-Mawardi menyebutkan dalam bukunya (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) bahwa nama Kementerian berbeda dalam asal-usul bahasanya menjadi tiga aspek:
Pertama: Ia diambil dari “wizr” yaitu beban, karena ia memikul beban-beban raja.
Kedua: Ia diambil dari “wizr” yaitu tempat berlindung, dari sinilah firman-Nya Ta’ala: “Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung” (Surah Al-Qiyamah: 11), artinya tidak ada tempat berlindung. Dinamakan demikian karena orang berlindung pada pendapat dan bantuannya.
Ketiga: Ia diambil dari “azr” yaitu punggung, karena raja dikuatkan oleh menterinya seperti kuatnya badan dengan punggung.
Yang dipahami dari perkataan Al-Mawardi adalah bahwa Kementerian membantu khalifah atau kepala negara dalam menjalankan tugasnya, karena menteri membantu dengan pendapatnya dalam mengelola urusan negara di bidang yang diserahkan kepadanya. Ini karena kepala negara secara alamiah tidak dapat menjalankan beban pemerintahan dalam berbagai urusan sendirian tanpa bantuan, maka kebutuhan menuntut pengangkatan para menteri.
Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah yang suci telah menunjukkan legalitas Kementerian. Allah Ta’ala berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa Kitab dan Kami jadikan bersamanya saudaranya Harun sebagai menteri” (Surah Al-Furqan: 35). Dan Allah Subhanahu berfirman: “Dan jadikanlah untukku seorang menteri dari keluargaku, (yaitu) Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku” (Surah Thaha: 29-32). Menteri adalah orang yang membantu karena ia memikul beban sultan, yaitu beratnya. Al-Mawardi berkomentar tentang permintaan Musa kepada Tuhannya agar menjadikan untuknya seorang menteri dari keluarganya: “Jika itu diperbolehkan dalam kenabian, maka dalam kepemimpinan lebih diperbolehkan, karena apa yang diserahkan kepada imam dari pengelolaan umat, ia tidak mampu menanganinya semuanya kecuali dengan pendelegasian. Dan pendelegasian menteri yang berbagi dengannya dalam pengelolaan lebih benar dalam pelaksanaan urusan daripada menyendiri dengannya, agar ia meminta bantuan dengannya pada dirinya dan dengannya akan lebih jauh dari kesalahan dan lebih terlindungi dari kerusakan.”
Dalam Sunnah yang suci juga terdapat petunjuk tentang legalitas Kementerian. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, Dia menjadikan untuknya menteri yang jujur; jika ia lupa, menteri mengingatkannya, dan jika ia ingat, menteri membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu padanya, Dia menjadikan untuknya menteri yang buruk; jika ia lupa, menteri tidak mengingatkannya, dan jika ia ingat, menteri tidak membantunya.”
Fungsi menteri dalam arti pembantu sudah biasa dan dikenal oleh para sahabat radhiyallahu ‘anhum. Oleh karena itu, Abu Bakar berkata pada hari Tsaqifah ketika Anshar radhiyallahu ‘anhum berkata: “Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin”, ia berkata kepada mereka: “Kami adalah para pemimpin dan kalian adalah para menteri”, artinya kami adalah para penguasa dan kalian membantu kami dalam menjalankan beban pemerintahan dan membantu kami dalam mengatur urusan.
Konsep Kementerian telah berkembang sehingga menjadi kebutuhan negara Islam yang tidak dapat diabaikan. Para khalifah Bani Umayyah mengadopsinya. Muawiyah radhiyallahu ‘anhu mengangkat Amr bin Ash dan Ziyad bin Abihi sebagai menteri. Para khalifah Bani Abbasiyah juga menggunakan bantuan para menteri. Bahkan Kementerian pada masa Abbasiyah telah menetapkan aturan-aturan dan sistemnya serta konsepnya meluas sehingga peran menteri tidak terbatas hanya pada membantu penguasa, tetapi menjadi berpartisipasi secara aktif dalam mengelola urusan negara dan ikut campur dalam semua aspek penting negara seperti masalah politik, perang, ekonomi, rahasia negara dan khalifah, dan sebagainya.
Dan semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
2 – Jenis-Jenis Kementerian dan Pendahuluan tentang Kebutuhan terhadap Kepemimpinan di Wilayah-Wilayah
Kementerian Pendelegasian
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada orang yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, junjungan kami Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan, amma ba’du:
Pembagian Kementerian:
Para ahli fiqih Muslim telah membahas dalam siyasah syar’iyyah (politik syariat) tentang dua jenis kementerian yaitu: kementerian pendelegasian, dan kementerian pelaksanaan. Berikut ini akan kami jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kedua jenis kementerian ini dari segi penentuan kewenangan menteri di masing-masingnya dan syarat-syarat yang harus terpenuhi padanya, serta hubungan masing-masing dari kedua menteri ini dengan kepala negara atau imam.
Pertama: Kementerian Pendelegasian:
Yang dimaksud dengan kementerian pendelegasian adalah: bahwa khalifah atau imam mempercayakan kepada seorang laki-laki dari kalangan ahli yang berpengalaman dan berkompeten, ia mempercayakan kepadanya untuk menangani atas namanya pengelolaan urusan negara dalam salah satu bidang yang menampakkan kompetensi dan keahliannya di dalamnya. Maka menteri yang terpilih atau yang dipercayai ini melaksanakan urusan-urusan berdasarkan pendapatnya dan ijtihad-nya sesuai dengan apa yang ia anggap tepat. Maka kewenangan menteri pendelegasian menyerupai perwakilan umum; karena ia didelegasikan secara penuh dalam apa yang dipercayakan kepadanya tanpa merujuk kepadanya kepada khalifah. Al-Mawardi berkata dalam hal ini: Adapun kementerian pendelegasian adalah bahwa imam mengangkat sebagai menteri seseorang yang kepadanya ia delegasikan pengelolaan urusan-urusan dengan pendapatnya dan melaksanakannya berdasarkan ijtihadnya. Intinya bahwa kewenangan menteri pendelegasian mengenai apa yang didelegasikan kepadanya adalah kewenangan penuh yang mandiri dari imam, dan kewenangannya termasuk yang paling luas sehingga ia dianggap pemegang jabatan kedua setelah khalifah dalam jabatan-jabatan negara.
Adapun yang disyaratkan pada menteri pendelegasian adalah apa yang disyaratkan pada khalifah atau imam dari syarat-syarat kecuali syarat nasab Quraisy sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Ya’la Al-Farra Al-Hanbali yang menjadikan syarat-syarat menteri pendelegasian sama dengan syarat-syarat khalifah tanpa pengecualian, ia berkata: Dan dipertimbangkan dalam pengangkatan kementerian ini syarat-syarat imam. Kami lebih memilih dalam hal ini mengambil apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi Asy-Syafi’i tentang pengecualian menteri pendelegasian dari syarat nasab Quraisy; karena adanya nash-nash khusus untuk imam sehingga tidak diqiyaskan kepadanya yang lain. Sungguh Abu Bakar berkata pada hari Saqifah kepada kaum Anshar: “Kami adalah para pemimpin dan kalian adalah para menteri,” dan karena mewajibkan kementerian hanya untuk kaum Quraisy tanpa nash berarti kesewenang-wenangan dan kezaliman yang diingatkan oleh syariat yang mulia dan dilarang darinya. Al-Mawardi berkata dalam hal ini: Dan dipertimbangkan dalam pengangkatan kementerian ini syarat-syarat imamah kecuali nasab saja; karena ia adalah pelaksana pendapat-pendapat dan pelaksana ijtihad maka dipersyaratkan bahwa ia harus memiliki sifat-sifat para mujtahid. Maka ia memerlukan syarat tambahan selain syarat-syarat imamah yaitu: bahwa ia harus dari kalangan ahli yang kompeten dalam apa yang diserahkan kepadanya dari urusan perang dan kharaj, memiliki keahlian dalam keduanya dan pengetahuan tentang rinciannya, karena ia terkadang melaksanakannya sendiri dan terkadang menunjuk wakil di dalamnya, maka ia tidak dapat menunjuk orang yang kompeten kecuali jika ia termasuk dari mereka, sebagaimana ia tidak mampu melaksanakannya langsung jika ia kurang dari mereka. Dan pada syarat inilah porosnya kementerian dan dengannya tertata politik.
Sifat-Sifat Menteri:
Harus terpenuhi beberapa sifat perilaku dan akhlak pada orang yang memegang jabatan kementerian selain syarat-syarat yang telah kami rinci sebelumnya ketika berbicara tentang syarat-syarat imam atau khalifah. Sebagian orang menyebutkan bahwa Khalifah Al-Ma’mun bin Harun Ar-Rasyid menulis tentang spesifikasi menteri, ia berkata: “Sesungguhnya aku mencari untuk urusan-urusanku seorang laki-laki yang mengumpulkan sifat-sifat kebaikan, yang memiliki sifat menjaga dalam akhlaknya, dan istiqamah dalam cara-caranya, yang telah dibentuk oleh adab, diberi pengalaman oleh peristiwa-peristiwa, dan diperkokoh oleh pengalaman-pengalaman. Jika dipercaya dengan rahasia-rahasia ia menjaganya, dan jika diberi tanggung jawab urusan-urusan penting ia bangkit di dalamnya. Kesabaran membuatnya diam, dan ilmu membuatnya berbicara. Cukup baginya sekilas pandang dan cukup baginya isyarat. Ia memiliki keberanian para pemimpin, dan kesabaran para ahli hikmah” dan seterusnya. Tampak dari apa yang disebutkan bahwa jabatan kementerian karena pentingnya harus orang yang memegangnya berada pada tingkat kompetensi tertinggi dan keseimbangan dalam kepribadiannya, sehingga tidak ada pada dirinya titik-titik kelemahan yang tampak agar tidak diserang dari sana sehingga terlewatkan kemaslahatan umat yang didelegasikan kepadanya.
Kewenangan Menteri Pendelegasian:
Kaidah umum adalah bahwa kewenangan menteri pendelegasian bersifat mutlak, baginya apa yang dimiliki kepala negara atau imam dari kewenangan-kewenangan. Baginya mengangkat para wali dan memberhentikan mereka, baginya memimpin tentara atau wilayah jihad, baginya menunjuk wakil yang ia kehendaki, baginya melaksanakan urusan-urusan yang ia kelola, baginya memutuskan perkara di antara manusia dan menangani kezaliman. Semua urusan ini boleh dari menteri pendelegasian sebagaimana boleh dari imam. Namun ada beberapa urusan yang dimiliki khalifah dan tidak dimiliki menteri pendelegasian meskipun kewenangannya mutlak, dan urusan-urusan ini telah dihitung oleh para ahli fiqih menjadi tiga: Wilayah ahad (suksesi), ia adalah hak khalifah semata, baginya memilih putra mahkotanya dengan syarat-syarat yang telah kami kemukakan, dan ini bukan untuk menteri pendelegasian betapapun kewenangannya mutlak; agar tidak melampaui hak imam dalam memilih putra mahkotanya. Di antara urusan yang juga untuk khalifah dan tidak untuk menteri pendelegasian: mengundurkan diri dari kekhalifahan, maka boleh bagi imam mengundurkan diri kepada umat dari imamah -yaitu: mengajukan pengunduran diri- dan tidak boleh itu bagi menteri pendelegasian. Juga bagi imam memberhentikan orang yang diangkat oleh menteri pendelegasian tetapi tidak boleh bagi menteri memberhentikan orang yang diangkat oleh imam; karena imam adalah penguasa asli dan kewenangannya adalah kewenangan pertama di negara. Dalam hal ini Abu Ya’la Al-Farra berkata: Dan atas menteri kementerian pendelegasian harus melaporkan kepada imam apa yang ia laksanakan dari wilayah dan pengangkatan; agar ia tidak menjadi seperti imam dengan kesewenang-wenangan. Dan atas imam harus memeriksa perbuatan-perbuatan menteri dan pengelolaannya terhadap urusan-urusan untuk menetapkan darinya apa yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan apa yang menyalahinya; karena pengelolaan umat diserahkan kepadanya dan kepada ijtihadnya.
Boleh bagi menteri ini memutuskan sendiri dan mengangkat hakim sebagaimana itu boleh bagi imam; karena syarat-syarat hakim dipertimbangkan padanya. Dan boleh ia menangani jihad sendiri dan mengangkat orang yang menanganinya; karena syarat-syarat jihad dipertimbangkan padanya. Dan boleh ia menangani kezaliman dan menunjuk wakil di dalamnya; karena syarat-syarat kezaliman dipertimbangkan padanya. Dan boleh ia langsung mengatur urusan-urusan yang ia kelola dan menunjuk wakil dalam pelaksanaannya; karena syarat-syarat pendapat dan pengelolaan dipertimbangkan padanya.
Al-Mawardi berkata setelah ia mengecualikan tiga urusan yang disebutkan dari kewenangan menteri pendelegasian: Adapun selain tiga ini maka hukum pendelegasian kepadanya mengharuskan bolehnya perbuatannya dan sahnya pelaksanaannya darinya. Jika imam menentangnya dalam membatalkan apa yang ia laksanakan, maka jika dalam hukum yang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dalam harta yang diletakkan pada haknya tidak boleh membatalkan apa yang dilaksanakan dengan ijtihadnya dari hukum, dan tidak mengambil kembali apa yang ia bagikan dengan pendapatnya dari harta. Dan jika dalam pengangkatan wali atau pengerahan tentara dan pengelolaan perang boleh bagi imam menentangnya dengan memberhentikan yang diangkat dan mengalihkan tentara ke mana ia pandang dan mengelola peperangan dengan apa yang lebih utama; karena bagi imam dapat meluruskan itu dari perbuatan-perbuatannya sendiri maka lebih utama ia meluruskannya dari perbuatan-perbuatan menterinya. Barangkali apa yang disebutkan Al-Mawardi menjelaskan kepada kita hubungan antara menteri pendelegasian dengan kemutlakan kewenangannya dan imam sebagai kepala tertinggi dan penguasa pertama dan kewenangannya yang didahulukan, yaitu bahwa jika tindakan-tindakan menteri pendelegasian bertentangan dengan tindakan-tindakan imam dalam pengelolaan urusan kaum muslimin dan penyelesaian perselisihan mereka maka wajib dibedakan dalam hal ini antara dua keadaan:
Keadaan Pertama: Jika apa yang dikeluarkan oleh menteri pendelegasian adalah putusan yang berkaitan dengan urusan harta atau peradilan seperti ia memerintahkan meletakkan sejumlah harta di salah satu tempat atau ia memerintahkan mengembalikan kezaliman kepada ahlinya -maka dalam keadaan ini putusan-putusannya berlaku dan imam tidak berhak mengomentarinya meskipun bertentangan dengan pendapatnya; karena selama itu adalah putusan-putusan ijtihad yang keluar dari orang yang ahli untuk itu dan tidak menyalahi nash dari Kitabullah Ta’ala dan tidak sunah Rasul-Nya maka tidak layak membatalkannya karena menyalahi ijtihad imam; karena tidak disalahkan ijtihad dengan ijtihad sebagaimana yang diketahui dari kaidah-kaidah ushul.
Keadaan Kedua: Jika apa yang keluar dari menteri pendelegasian adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan para wali atau pemberhentian mereka atau pengiriman tentara untuk memerangi musuh atau membuat perjanjian politik atau militer dengan negara-negara asing -maka dalam keadaan ini boleh bagi imam mengomentari pendapat menteri jika bertentangan dengan pendapatnya; karena imam adalah pemilik hak pertama dan baginya meluruskan itu dari perbuatan-perbuatannya sendiri maka ia meluruskannya dari perbuatan-perbuatan menterinya dari pintu yang lebih utama.
Penugasan Kementerian:
Kementerian pendelegasian dalam sistem Islam sebagaimana kami sebutkan adalah kementerian penting dengan kewenangan-kewenangan yang sangat luas dan kewenangan-kewenangan yang mutlak sampai batas tertentu sebagaimana kami isyaratkan. Dan berdasarkan ini para ahli fiqih menyebutkan bahwa ia memerlukan pengangkatan atau penugasan dengannya dari wali amr berdasarkan akad yang terjadi antara menteri pendelegasian dan imam, dan ia menyerupai sampai batas tertentu apa yang dikenal dengan pembentukan kabinet sekarang, di mana menteri diberitahu tentang pemilihannya berdasarkan surat atau surat pengangkatan dari orang yang memilihnya sehingga berakibat dari itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara menteri yang terpilih dan pihak yang memilihnya, baik ketua dewan menteri atau kepala negara sendiri.
Al-Mawardi menyebutkan bahwa disyaratkan dalam surat penugasan kementerian dua syarat: Pertama: keumuman penanganan; karena ini adalah urusan pendelegasian, di mana menteri memiliki kewenangan-kewenangan yang sama yang dimiliki khalifah biasanya. Kedua: Perwakilan, seperti khalifah berkata kepada menteri: Aku mengangkatmu untuk apa yang ada padaku sebagai wakil dariku dan semacam itu; karena menteri pendelegasian meskipun kewenangannya mutlak namun ia tidak melampaui dengannya hak imam, dan tidak sewenang-wenang dengannya tanpanya sebagaimana kami sebutkan.
Surat penugasan kementerian yang merupakan akad antara menteri dan orang yang mengangkatnya sebagai menteri adalah dalam hakikatnya akad antara menteri dan umat; karena imam yang mengangkatnya sebagai menteri hanya mewakili dalam itu tentang umat maka ia adalah akad perwakilan, dan menteri adalah wakil tentang umat meskipun imam yang memilihnya. Oleh karena itu ia tetap dalam wilayahnya tidak terpengaruh oleh kematian khalifah yang mengangkatnya. Seandainya ia wakil darinya tentu ia diberhentikan dengan kematiannya; karena wakil terikat dengan orang yang diwakili. Maka semua orang yang diangkat dengan akad pendelegasian berdiri dengan imam pada tingkat kesetaraan dalam bahwa mereka semua menunaikan hak-hak umat, dan mereka semua adalah para wali yang wilayah mereka tidak berbeda dari wilayahnya dalam jenis meskipun ada perbedaan antara keduanya dalam tingkat. Intinya bahwa imam berhubungan dengan umat secara langsung adapun mereka berhubungan melaluinya, maka ia adalah penghubung antara mereka dan umat. Dan ini adalah masalah yang diperlukan oleh kebutuhan untuk organisasi dan wajibnya pemusatan kewenangan di pihak tertentu dan penyatuan tanggung jawab agar terwakili dalam diri imam, sehingga umat dapat menghadapinya dan menghisabnya dan memutuskan urusannya dengan apa yang mereka kehendaki dengan tetap bahwa keberadaannya bagaimanapun tidak membebaskan para wali yang lain dari tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan umat apalagi tanggung jawab mereka di hadapannya sebagai wakil sistem. Al-Mawardi menyebutkan dalam (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah): Dan seandainya imam meninggal tidak diberhentikan para hakim-hakimnya, dan jika pengangkatan urusan dari pihak khalifah maka tidak diberhentikan dengan kematian khalifah, dan jika dari pihak menteri diberhentikan dengan kematian menteri; karena pengangkatan khalifah adalah perwakilan tentang kaum muslimin dan pengangkatan menteri adalah perwakilan tentang dirinya. Dengan demikian para ahli fiqih Muslim telah mendahului yang lain dalam memutuskan ide kesinambungan negara sebagai badan hukum tanpa memandang pribadi-pribadi penguasa dari segi bertahan atau hilang. Tetapi: apakah boleh menteri-menteri pendelegasian beragam di negara atau di wilayah yang satu?
Barangkali yang mendorong pertanyaan ini adalah kerumitan kewenangan-kewenangan menteri pendelegasian sebagai kaidah umum dengan kewenangan-kewenangan khalifah atau imam. Abu Ya’la Al-Farra dalam kitabnya (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) telah mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan rincian yang intinya: bahwa tidak boleh mengangkat dua menteri pendelegasian secara bersamaan, sebagaimana tidak boleh mengangkat dua imam; karena keduanya barangkali bertentangan dalam mengikat dan melepas dan pengangkatan dan pemberhentian. Allah Ta’ala telah berfirman: “Sekiranya ada di langit dan bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa” (Surat Al-Anbiya’, ayat: 22). Jika ia mengangkat dua menteri pendelegasian kita lihat, maka jika ia mendelegasikan kepada masing-masing dari keduanya keumuman penanganan tidak sah karena apa yang kami sebutkan. Kemudian kita lihat jika pada waktu yang sama batal pengangkatan keduanya bersama, dan jika salah satunya mendahului yang lain sah pengangkatan yang lebih dahulu dan batal pengangkatan yang terlambat. Dan jika ia menyertakan antara keduanya dalam penanganan dengan menyatukan keduanya di dalamnya dan tidak menjadikan kepada salah satu dari keduanya untuk menyendiri dengannya sah urusannya, dan kementerian ada pada keduanya tidak pada salah satu dari keduanya. Dan bagi keduanya melaksanakan apa yang mereka sepakati dan tidak bagi keduanya melaksanakan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dan menjadi tergantung pada pendapat khalifah dan keluar dari penanganan kementerian ini. Dan kementerian ini di dalamnya ada kekurangan dari kementerian pendelegasian mutlak dari dua tahap: Pertama: penyatuan keduanya untuk melaksanakan apa yang mereka sepakati. Kedua: hilangnya penanganan mereka tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Jika ia tidak menyertakan antara keduanya dalam penanganan melainkan menyendirikan masing-masing dari keduanya dengan pekerjaan yang ia umum dalam penanganan khusus dalam pekerjaan, seperti ia menyerahkan kepada salah satunya kementerian negeri-negeri Timur dan kepada yang lain kementerian negeri-negeri Barat, atau ia mengkhususkan masing-masing dari keduanya dengan apa yang ia umum dalam pekerjaan khusus dalam penanganan seperti ia mengangkat salah satunya sebagai menteri untuk perang dan yang lain untuk kharaj sah pengangkatan keduanya pada kedua cara. Namun keduanya tidak menjadi menteri pendelegasian dan keduanya menjadi wali atas dua pekerjaan yang berbeda; karena kementerian pendelegasian adalah apa yang umum dan berlaku perintah menteri dengannya dalam setiap pekerjaan dan setiap penanganan. Dan pengangkatan masing-masing dari keduanya terbatas pada apa yang dikhususkan dengannya dan tidak baginya menentang yang lain dalam penanganannya atau pekerjaannya.
Diperhatikan pada apa yang dikemukakan Abu Ya’la bahwa ia melihat kepada kemutlakan kewenangan menteri pendelegasian, dan karena itu ia menganggap orang yang dikhususkan dengan pekerjaan tertentu seperti perang atau kharaj dan semacam itu ia menganggapnya wali atau petugas dan tidak menganggapnya menteri; karena kementerian pendelegasian urusannya adalah keumuman dalam setiap penanganan dan dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu tidak boleh keberagaman dalam kementerian pendelegasian agar tidak mengakibatkan itu kepada perbedaan karena hak menteri pendelegasian dalam penanganan semua urusan negara tanpa mengkhususkannya dengan wilayah tanpa yang lain atau dengan pekerjaan tanpa yang lain. Tetapi boleh pengangkatan dua menteri pendelegasian ketika penyertaan antara keduanya dalam penanganan semua urusan dan dalam keadaan ini diambil dengan ucapan keduanya dalam apa yang mereka sepakati tanpa apa yang mereka perselisihkan di dalamnya.
Kementerian Pelaksanaan
Kementerian Pelaksanaan dianggap sebagai jenis kedua dari kementerian menurut para ahli fikih Islam, dan kedudukannya lebih rendah dari Kementerian Pendelegasian karena dalam kementerian ini menteri tidak memiliki kemandirian, melainkan hanya ditugaskan untuk melaksanakan urusan-urusan sebagaimana diperintahkan oleh khalifah. Ia menyampaikan berita-berita dari para gubernur dan rakyat, sebagaimana juga menyampaikan instruksi-instruksi khalifah kepada para gubernur, panglima, hakim, dan seluruh rakyat. Oleh karena itu, menteri pelaksanaan harus tidak jauh dari keberadaan imam, karena ia membutuhkan musyawarah dan konsultasinya dalam sebagian besar urusan yang terjadi. Jadi ia hanyalah perantara antara rakyat dan para penguasa, sehingga kedudukannya seperti yang diungkapkan al-Mawardi lebih mirip dengan perantara atau duta.
Al-Mawardi mengatakan dalam hal ini: Adapun Kementerian Pelaksanaan, maka hukumnya lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih sedikit, karena pengelolaan di dalamnya terbatas pada pendapat dan kebijakan imam, dan menteri ini adalah perantara antara imam dengan rakyat dan para gubernur. Ia menyampaikan apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang disebutkan, menjalankan apa yang diputuskan, memberitahukan tentang pengangkatan para gubernur dan pengerahan pasukan, dan memaparkan kepada khalifah apa yang datang dari urusan-urusan penting dan apa yang baru terjadi dari peristiwa-peristiwa, untuk kemudian ia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ia adalah pembantu dalam melaksanakan urusan-urusan dan bukan penguasa atasnya dan tidak memegangnya. Jika ia diajak bermusyawarah dalam pendapat, maka ia lebih tepat disebut dengan nama menteri, dan jika ia tidak berpartisipasi di dalamnya, maka ia lebih mirip dengan nama perantara dan duta. Mengingat bahwa menteri pelaksanaan hanyalah perantara antara imam dan rakyat dan bahwa ia tidak mandiri dalam urusan-urusan melainkan ia diperintah dalam setiap perkara, maka orang yang memegang kementerian ini tidak memerlukan surat pengangkatan atau penunjukan sebagaimana halnya dalam Kementerian Pendelegasian, melainkan cukup dengan izin untuk melaksanakan urusan-urusan saja. Dalam hal apapun, pandangannya terbatas pada menyampaikan kepada khalifah dan menyampaikan darinya.
Syarat-syarat Menteri Pelaksanaan:
Karena menteri pelaksanaan tidak mandiri dalam keputusan dan tidak menyendiri dalam kekuasaan, melainkan ia semata-mata diizinkan untuk melaksanakan saja, maka wajar jika syarat-syarat yang diperlukan padanya lebih sedikit dari syarat-syarat yang diperlukan pada menteri pendelegasian. Oleh karena itu para ahli fikih menyebutkan sejumlah syarat pada menteri pelaksanaan yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, di antaranya yang kami sebutkan sebagai berikut:
- Amanah: Disyaratkan padanya untuk menjadi orang yang amanah agar tidak berkhianat dalam apa yang telah diamanahkan kepadanya, dan tidak menipu dalam apa yang dimintai pendapatnya.
- Jujur dalam ucapan agar dapat dipercaya beritanya dalam apa yang ia sampaikan dan dapat diambil keputusan berdasarkan perkataannya dalam apa yang ia laporkan.
- Sedikit tamak, agar tidak menerima suap dalam apa yang ia kelola, dan tidak tertipu sehingga bersikap toleran.
- Terbebas dalam hubungannya dengan orang-orang dari permusuhan dan kebencian, karena permusuhan menghalangi dari keadilan dan mencegah dari saling tolong-menolong.
- Dzukuran, artinya: harus mengingat dan memahami apa yang ia sampaikan kepada khalifah dan darinya, karena ia adalah saksi untuknya dan saksi atasnya.
- Kecerdasan dan ketajaman pikiran agar urusan-urusan tidak dipalsukan sehingga membingungkannya dan tidak dikaburkan sehingga meragukan.
- Bukan termasuk ahli hawa nafsu yang membuatnya keluar dari kebenaran menuju kebatilan, dan membingungkannya antara yang benar dan yang batil, karena hawa nafsu dapat menipu akal dan memalingkan dari kebenaran.
- Kematangan pengalaman yang membawa pada pendapat yang benar dan kebijakan yang tepat, karena pengalaman dapat mengasah kepribadian seseorang dan memberikannya pandangan tentang akibat-akibat urusan. Namun syarat ini tidak diperlukan pada menteri pelaksanaan kecuali jika khalifah atau imam bermusyawarah dengannya dalam pendapat. Jika ia tidak bermusyawarah dengannya sebagaimana keadaannya, maka tidak perlu seperti ini, karena tidak ada yang bergantung pada pendapatnya, sebab semua urusan terbatas pada pendapat dan kebijakan imam.
- Harus laki-laki, sehingga tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk memegang kementerian ini atau lainnya yang mengandung makna kekuasaan, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu bahwa putri Kisra memegang kekuasaan -yakni memegang pemerintahan di negerinya- Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.”
Al-Mawardi mengatakan dalam hal ini: Tidak diperbolehkan perempuan untuk memegangnya -yakni Kementerian Pelaksanaan- meskipun beritanya dapat diterima, karena mengandung makna kekuasaan yang tidak boleh dipegang oleh perempuan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”, dan karena di dalamnya terdapat permintaan pendapat dan keteguhan tekad yang perempuan lemah dalam hal itu, dan di dalamnya ada keterlibatan dalam menangani urusan-urusan yang dilarang bagi mereka. Berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka diputuskan bahwa tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk memegang kementerian secara mutlak, karena itu adalah kekuasaan dan memerlukan keteguhan, kemampuan, pengalaman, dan kematangan, dan perempuan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk semua itu karena sifat pembentukannya. Yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa pekerjaan kementerian menuntut untuk tampil dalam menangani urusan-urusan, sedangkan seharusnya perempuan tertutup dan tidak bercampur dengan laki-laki, terutama di zaman-zaman ini yang di dalamnya rasa malu telah berkurang. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Orang Dzimmi dan Kementerian Pelaksanaan:
Yaitu: apakah diperbolehkan bagi dzimmi yang bukan muslim untuk memegang Kementerian Pelaksanaan? Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa Kementerian Pelaksanaan lebih rendah kedudukannya dari Kementerian Pendelegasian, oleh karena itu sebagian ahli fikih termasuk al-Mawardi berpendapat boleh bagi ahli dzimmah dari warga negara Islam untuk memegang kementerian ini. Jadi Islam bukan syarat bagi yang memegang kementerian ini, berbeda dengan Kementerian Pendelegasian, karena menteri pendelegasian mengangkat dan memberhentikan, melaksanakan pemerintahan, mengerahkan pasukan, dan mengelola baitul mal, berbeda dengan menteri pelaksanaan. Hal ini sebenarnya menunjukkan toleransi Islam sebagai sistem, karena tidak membedakan antara warga negara dalam negaranya berdasarkan agama atau keyakinan mereka. Orang dzimmi memiliki hak seperti kami dan kewajiban seperti kami sebagai kaidah umum, berbeda dengan apa yang ditetapkan di negara-negara Eropa dan Amerika yang paling maju di zaman ini, di mana orang yang berbeda agama bahkan terkadang berbeda mazhab tidak boleh memegang jabatan menteri hingga hari ini.
Sebagian ahli fikih berpendapat tidak boleh mengangkat dzimmi, dan mereka berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu.” (Surah Ali Imran, ayat: 73) dan firman Allah Ta’ala: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Surah Ali Imran, ayat: 118). Bathânah seseorang adalah orang-orang terdekatnya yang mengetahui urusannya. Allah Ta’ala telah melarang kita untuk mengambil orang kepercayaan dari selain kaum muslimin, karena telah tampak kebencian dalam perkataan mereka dan apa yang disembunyikan hati mereka dari kedengkian dan iri hati lebih besar lagi.
Namun kami lebih suka mengikuti pendapat al-Mawardi tentang bolehnya mengangkat ahli dzimmah untuk Kementerian Pelaksanaan, karena kekuasaan kaum muslimin dalam negara Islam tinggi dengan pujian bagi Allah Ta’ala, dan yang dilarang adalah jika non-muslim memiliki jalan untuk menguasai muslim. Hal ini dengan memperhatikan kecilnya kedudukan menteri pelaksanaan, karena kebijakan urusan-urusan dan pengelolaannya kembali kepada imam sebagaimana telah kami sebutkan, dan ia hanya semata-mata pelaksana atau diizinkan untuk itu saja. Ia lebih mirip dengan duta atau perantara antara imam dan rakyat. Namun dengan demikian kami mengatakan bahwa tidak sepatutnya non-muslim berkuasa atas kaum muslimin dalam negara mereka dengan bentuk apapun, karena itu tidak boleh baginya, dan inilah yang disimpulkan oleh al-Mawardi sendiri ketika ia berkata: kecuali jika mereka berkuasa berlebihan, maka mereka harus dicegah dari kekuasaan yang berlebihan.
Jenis-jenis Kementerian Pelaksanaan:
Pembacaan yang cermat terhadap apa yang ditulis dalam bidang ini menghasilkan kesimpulan bahwa para ahli fikih Islam telah membedakan antara dua jenis Kementerian Pelaksanaan:
Pertama: kementerian yang berasal dari kepala negara sendiri, maka menteri pelaksanaan dalam hal ini adalah menteri khalifah atau imam yang melaksanakan keputusan-keputusan dan melaksanakan perintah-perintah di seluruh wilayah negara Islam, kecuali jika khalifah menetapkan baginya kewenangan wilayah tertentu.
Kedua: Kementerian Pelaksanaan yang berasal dari gubernur wilayah, maka kewenangan menteri dalam hal ini terkait dengan wilayah ini saja tanpa wilayah lain dari negara. Ia mengikuti gubernur wilayah dan oleh karenanya tidak lebih baik keadaannya darinya. Dengan demikian kita dapat membayangkan di negara Islam adanya kementerian umum yang mengikuti khalifah kemudian kementerian-kementerian regional yang beragam dengan beragamnya wilayah, dan ini menyerupai sampai batas tertentu apa yang dikenal dalam sistem Amerika sekarang, ada pemerintah pusat umum kemudian ada untuk setiap negara bagian setelah itu perangkat administratif khususnya. Al-Mawardi mengatakan dalam hal ini: Jika khalifah mendelegasikan pengelolaan wilayah-wilayah kepada para gubernurnya dan menyerahkan pengelolaan kepada para penanggung jawab atasnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kami, maka diperbolehkan bagi pemilik setiap wilayah untuk mengangkat menteri -yakni menunjuk menteri- dan hukum menterinya seperti hukum menteri khalifah dengan khalifah dalam pertimbangan dua kementerian dan hukum-hukum kedua pengelolaan.
Perbandingan antara Kementerian Pendelegasian dan Kementerian Pelaksanaan
Sekarang kita ingin membuat perbandingan antara Kementerian Pendelegasian dan Kementerian Pelaksanaan. Kita akan menyebutkan dalam perbandingan ini antara kedua kementerian, sisi-sisi kesamaan kemudian sisi-sisi perbedaan di antara keduanya, dan dengan itu kita dapat mengetahui ciri-ciri penting masing-masing.
Pertama: Sisi-sisi Kesamaan:
Kedua kementerian sama dalam hal menteri di masing-masing harus memiliki hal-hal berikut:
- Mampu mengemban beban kementerian, artinya: mampu melaksanakannya, dan mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan dirinya.
- Mampu bekerja keras dan bersusah payah, serta sabar dalam kemurkaan dan keridaan.
- Ikhlas niatnya dalam ketaatan kepada khalifah dan batinnya seperti lahirnya.
- Berpihak kepada penguasa dan tidak menentang penguasa, menafsirkan untuk kepentingan penguasa dan tidak menentang penguasa, artinya: menjadi pembantu bagi khalifah dan imam dalam urusan-urusan, bukan menjadi penentang perintah-perintah imam atau menjadi penghalang dalam pelaksanaan perintah-perintah imam atau khalifah.
- Menjadikan Allah Ta’ala sebagai pengawas atas kerahasiaannya.
- Mendahulukan hak Allah Ta’ala atas hak selain-Nya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Pencipta. Diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa mencintai dunianya, ia akan merugikan akhiratnya, dan barangsiapa mencintai akhiratnya, ia akan merugikan dunianya. Maka dahulukanlah apa yang kekal atas apa yang fana.”
- Menteri harus mengetahui keadaan rakyat, dan mengawasi sendiri pekerjaan-pekerjaan, dan ia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain apa yang menjadi kekhususannya untuk dilakukan demi mencari kenyamanan dan kesenangan.
Inilah hal-hal yang sama antara kedua kementerian, Kementerian Pendelegasian dan Kementerian Pelaksanaan. Semua hal yang telah kami sebutkan ini harus dimiliki oleh menteri pendelegasian dan juga harus dimiliki oleh menteri pelaksanaan.
Kedua: Sisi-sisi Perbedaan antara Kedua Kementerian:
Perbedaan-perbedaan ini muncul antara kedua kementerian dari segi asal pengangkatan, dari segi syarat-syarat yang diperlukan pada setiap menteri, dan dari segi hak-hak pengelolaan atau kewenangan sebagai berikut:
Dari segi asal pengangkatan, kedua kementerian berbeda, karena Kementerian Pendelegasian memerlukan akad dan penunjukan, tidak demikian halnya Kementerian Pelaksanaan, bahkan cukup dengan izin saja sebagaimana telah disebutkan. Dari segi syarat-syarat yang diperlukan pada kedua kementerian, kita dapati bahwa kemerdekaan diperlukan pada Kementerian Pendelegasian bukan pada Kementerian Pelaksanaan, demikian juga Islam. Juga pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang memerlukan menteri menjadi mujtahid diperlukan pada Kementerian Pendelegasian bukan pada Kementerian Pelaksanaan. Demikian juga pengetahuan tentang urusan perang dan pajak tanah diperlukan hanya pada Kementerian Pendelegasian.
Adapun dari segi hak-hak pengelolaan atau kewenangan yang diberikan kepada para menteri, maka kedua kementerian berbeda dalam hal-hal berikut:
- Diperbolehkan bagi menteri pendelegasian untuk melaksanakan peradilan dan penyelesaian pengaduan, hal itu tidak berlaku bagi menteri pelaksanaan.
- Diperbolehkan bagi menteri pendelegasian untuk mandiri dalam mengangkat para gubernur, hal itu tidak berlaku bagi menteri pelaksanaan.
- Diperbolehkan bagi menteri pendelegasian untuk menyendiri dalam mengerahkan pasukan dan merencanakan peperangan, hal itu tidak berlaku bagi Kementerian Pelaksanaan.
- Diperbolehkan bagi menteri pendelegasian untuk mengelola harta baitul mal dengan mengambil apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang wajib darinya, hal itu tidak berlaku bagi menteri pelaksanaan.
- Dalam Kementerian Pendelegasian tidak diperbolehkan banyak menteri secara bersamaan sebagaimana tidak diperbolehkan mengangkat dua imam. Adapun dalam Kementerian Pelaksanaan, yang asli adalah banyaknya menteri, karena diperbolehkan bagi khalifah untuk mengangkat lebih dari satu menteri pelaksanaan untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan kepada mereka. Tidak ada pertentangan antara kewenangan menteri-menteri pelaksanaan, karena pekerjaan mereka bukan dari segi kekuasaan, melainkan dari segi perwakilan, berbeda dengan menteri-menteri pendelegasian.
- Dalam Kementerian Pendelegasian, diperbolehkan bagi menteri untuk mengangkat wakil darinya yang membantunya dalam urusan-urusan yang terkait dengannya kecuali jika khalifah melarangnya. Adapun dalam Kementerian Pelaksanaan, menteri tidak boleh mengangkat wakil untuknya, karena tugasnya terbatas pada pelaksanaan tanpa memiliki hak untuk mengangkat siapapun kecuali jika khalifah mengizinkannya.
Setelah mengkaji hukum-hukum kementerian dalam sistem Islam, kita mencatat bahwa jabatan menteri pendelegasian mendekati sampai batas tertentu apa yang dikenal di negara-negara modern sekarang dengan jabatan perdana menteri atau menteri pertama, karena menteri seperti ini dalam kementerian kontemporer tidak boleh banyak, dan ia bebas bertindak serta menggantikan kepala negara, jadi ia memiliki kekuasaan dan pengelolaan yang umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jabatan perdana menteri atau menteri pertama atau menteri pendelegasian telah ditetapkan oleh para ahli fikih Islam sebelum ahli fikih konstitusional kontemporer lainnya, karena jabatan ini tidak dikenal kecuali setelah zaman al-Mawardi dengan berabad-abad, pada abad ketujuh belas Masehi, yang menegaskan keaslian fikih politik pada kaum muslimin.
Jika boleh bagi kita membandingkan menteri pendelegasian dengan perdana menteri dalam sistem kontemporer, maka dapat dianggap bahwa para menteri lainnya dalam pemerintahan modern adalah menteri-menteri pelaksanaan, tugas mereka terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan kabinet dan melaksanakan keputusan-keputusan serta mengambil keputusan. Setiap menteri pelaksanaan khusus mengelola bidang tertentu, ini untuk keuangan, ini untuk pendidikan, ini untuk pertahanan, ini untuk keadilan… dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa menteri pelaksanaan kedudukannya menyerupai kedudukan menteri dalam sistem presidensial di mana ia dianggap sebagai sekretaris kepala negara, tugasnya melaksanakan kehendak dan kebijakan presiden. Adapun menteri pendelegasian, ia menyerupai menteri dalam sistem parlementer di mana menteri berbagi dengan kepala negara dalam pemerintahan, bahkan kementerian sebenarnya adalah yang merumuskan kebijakan pemerintahan dalam sistem ini.
Kepemimpinan Atas Wilayah-Wilayah
Sekarang kita beralih pada pembahasan tentang kepemimpinan, yaitu: kepemimpinan atas negeri-negeri atau atas wilayah-wilayah yang berbeda, maka kita katakan:
Sulit bagi khalifah sebagai pemimpin pertama dalam negara Islam untuk menjalankan sendiri urusan-urusan pemerintahan dan administrasi, terutama setelah wilayah negara Islam meluas dan batas-batasnya membentang sebagai akibat dari penaklukan-penaklukan yang diberkahi yang dilakukan oleh pendahulu yang saleh dari umat ini. Oleh karena itu, menjadi keharusan untuk membagi negara menjadi beberapa wilayah, dan mengangkat seorang amir (gubernur) untuk setiap wilayah agar menjadi semacam pembantu bagi imam dan wakilnya dalam mengelola urusan wilayah tersebut. Konsep kepemimpinan ini dapat disamakan dengan pembagian negara di zaman modern menjadi sejumlah provinsi, dan pengangkatan seorang gubernur untuk setiap wilayah sehingga dialah yang bertanggung jawab pertama atas urusan provinsi tersebut di hadapan otoritas tertinggi di ibu kota negara.
Kepemimpinan adalah sejenis wilayah (kekuasaan) dan oleh karena itu amir kadang-kadang disebut wali. Meskipun benih sistem ini telah dimulai pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendirikan negara di Madinah—beliau mengirim ke setiap suku orang yang mengajarkan mereka urusan agama, mengimami mereka dalam salat, dan mengumpulkan zakat dari mereka—namun organisasi ini tidak dikenal secara jelas dan mendasar kecuali setelah wilayah negara meluas sebagai akibat dari penaklukan-penaklukan sebagaimana telah kami sebutkan. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau mengukuhkan para petugas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada tugas-tugas mereka, dan beliau radhiyallahu anhu meminta bantuan para sahabat besar dalam mengelola pemerintahannya, meminta nasihat mereka dan bekerja dengan pendapat mereka. Negeri-negeri Islam pada masa Abu Bakar terbagi menjadi beberapa wilayah seperti Mekah, Madinah, Thaif, Sanaa, Hadramaut, Najran, dan Bahrain.
Ketika Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu wa ardhahu mengambil alih kekhalifahan setelah wafatnya Abu Bakar dan penaklukan-penaklukan meluas pada masanya serta wilayah negara bertambah—akibat dari itu dilakukan pembagian negara menjadi wilayah-wilayah besar untuk memudahkan pengaturan urusan dan pengelolaan masalah. Wilayah-wilayah ini yang terpenting di antaranya adalah wilayah Ahwaz dan Bahrain, wilayah Sijistan dan Kirman, wilayah Thabaristan, wilayah Khurasan, wilayah Kufah dan Basrah di negeri Irak, kemudian wilayah Homs, wilayah Damaskus di negeri Syam, wilayah Palestina, dan di Afrika adalah wilayah Mesir Hulu kemudian Mesir Hilir, kemudian barat Mesir dan gurun Libya. Dengan demikian, di negara kaum Muslim terbentuk perangkat administrasi yang terorganisir yang mengelola urusan wilayah-wilayah ini dalam cahaya kebijakan tinggi negara sebagaimana dikehendaki khalifah atau imam.
Pada masa Umayyah, negara meluas sangat luas, dan kekuasaan kekhalifahan membentang di wilayah yang besar dari timur terjauh hingga barat terjauh. Oleh karena itu, negara pada masa Umayyah dibagi menjadi lima wilayah, yaitu: Hijaz, Yaman, pedalaman negeri Arab, Mesir, dua Irak: Arab yang diwakili oleh negeri Babel dan Asyur, dan Ajam yang diwakili oleh negeri Persia, negeri Jazirah Arab: Afrika Utara dari barat Mesir hingga negeri Maghrib dan Andalus serta pulau-pulau Laut Tengah. Kewenangan para wali atau amir telah meluas pada masa Umayyah hingga menjadi hampir mutlak di wilayah mereka, dan barangkali yang diriwayatkan tentang Hajjaj bin Yusuf atstsaqafi di Irak adalah contoh paling menonjol tentang hal itu. Namun keadaan berubah setelah khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz datang ke kekhalifahan. Beliau bekerja mengembalikan urusan-urusan ke jalur yang benar dan membatasi kekuasaan banyak dari para wali ini dengan mengangkat kezaliman mereka dan menolak bahaya mereka terhadap rakyat.
Pada masa Abbasiyah, pengaruh para amir menyusut dan kedudukan mereka melemah pada awalnya, ketika kekuatan kekhalifahan menguat dan kekuasaan negara bertambah yang mengakibatkan pemusatan semua kekuasaan di tangan khalifah, sehingga para wali atau amir menjadi sekadar petugas yang tidak memiliki kecuali kewenangan yang sangat terbatas yang hampir terbatas pada mengimami salat dan memimpin pasukan; karena tugas mengurus urusan keuangan telah berpindah ke pemilik harta (bendahara), dan pengawasan urusan peradilan berpindah ke qadhi. Namun keadaan berubah dan berganti pada akhir pemerintahan Abbasiyah ketika negara melemah dan bersamanya melemah pula posisi kekuasaan umum atau kekuasaan khalifah, yang mendorong bertambahnya pengaruh para amir hingga sebagian dari mereka mengumumkan kemerdekaan dari kekuasaan pusat di ibu kota kekhalifahan, dan muncul di masyarakat-masyarakat Islam negara-negara kecil yang diperintah oleh para amir yang terikat secara lahiriah saja dengan Kekhalifahan Abbasiyah sementara dalam kenyataannya mereka merdeka sepenuhnya darinya.
Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya tercurah kepada kalian semua.
3 – JENIS-JENIS KEPEMIMPINAN ATAS WILAYAH-WILAYAH, DAN PENJELASAN DASAR-DASAR YANG MENJADI LANDASAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM ISLAM
JENIS-JENIS KEPEMIMPINAN ATAS WILAYAH-WILAYAH
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, junjungan kami Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.
Kita telah membahas dalam kuliah sebelumnya tentang jenis-jenis kewaziran dalam sistem Islam dan kita katakan bahwa ia terbagi menjadi wazir pendelegasian dan wazir pelaksana, dan kami jelaskan syarat-syarat wazir pada kedua jenis wazir tersebut, dan kami jelaskan juga aspek-aspek persamaan dan perbedaan antara kedua jenis wazir tersebut, kemudian kami memulai pembahasan tentang kepemimpinan atas wilayah-wilayah.
JENIS-JENIS KEPEMIMPINAN:
Para fuqaha politik syariah Muslim membagi kepemimpinan menjadi dua jenis: kepemimpinan umum, dan kepemimpinan khusus.
Sekarang kita membahas tentang kepemimpinan umum, maka kita katakan:
Kepemimpinan atau wilayah umum adalah: bahwa kewenangan amir adalah mutlak di suatu negeri dari negeri-negeri atau suatu wilayah dari wilayah-wilayah, sehingga amir memiliki pengawasan dalam semua pekerjaan termasuk pengawasan dalam mengatur pasukan, mengangkat para qadhi, memungut kharaj, menerima sedekah, menegakkan hudud, memilih pegawai-pegawai negara dan sebagainya. Ia menurut ungkapan Mawardi terhadap penduduk wilayah adalah wilayah atas semua penduduknya dan pengawasan dalam yang diamanatkan dari seluruh pekerjaannya, maka jadilah pengawasan yang umum dalam apa yang terbatas dari pekerjaan dan diamanatkan dari pengawasan.
Disyaratkan dalam kepemimpinan umum ini syarat-syarat yang sama yang disyaratkan dalam wazir pendelegasian; karena perbedaan antara keduanya hanyalah dalam kekhususan wilayah pada kepemimpinan dan keumumannya pada wazir. Mawardi berkata: Dan dipertimbangkan dalam kepemimpinan ini syarat-syarat yang dipertimbangkan dalam wazir pendelegasian; karena perbedaan antara keduanya adalah kekhususan wilayah dalam kepemimpinan dan keumumannya dalam wazir, dan tidak ada perbedaan antara keumuman wilayah dan kekhususannya dalam syarat-syarat yang dipertimbangkan padanya. Maka setiap dari amir dan wazir dalam wazir pendelegasian adalah mutlak kekuasaannya, tujuannya adalah bahwa amir khusus dengan kepemimpinannya dan wazir pendelegasian tidak khusus dengan wilayah tertentu.
PEMBAGIAN KEPEMIMPINAN UMUM:
Maka kita katakan: Kepemimpinan umum terbagi menjadi dua bagian: kepemimpinan istikfa’ (karena kecakapan), dan kepemimpinan istila’ (karena penguasaan paksa).
Adapun kepemimpinan istikfa’: ia adalah yang terbentuk dari pemilihan imam, maka ia mengadakan perjanjian dengan orang yang cakap untuk mengemban tugas-tugas kepemimpinan ketika syarat-syarat terpenuhi padanya. Ia menyerupai wazir pendelegasian—sebagaimana telah kami isyaratkan—dan cukup bagi khalifah ketika mengangkat salah satu wali atas suatu wilayah mengatakan: “Aku telah mengukuhkanmu atas wilayahmu di daerah ini,” atau “Aku telah memberikan kepadamu wilayah daerah ini; agar engkau menjadi pengawas umum atas penduduknya dalam segala hal yang berkaitan dengannya,” dan semacamnya dari ungkapan-ungkapan pengangkatan. Karena amir dalam kepemimpinan umum memiliki kekuasaan mutlak di wilayahnya, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil untuk dirinya wazir pelaksana dengan perintah khalifah maupun tanpa perintahnya, namun tidak diperbolehkan baginya untuk mengangkat wazir pendelegasian kecuali dengan izin khalifah dan perintahnya. Adapun tentang kewajiban-kewajiban amir dalam kepemimpinan umum—sebagaimana telah kami sebutkan—menyerupai kewajiban-kewajiban imam terhadap keumuman negara; yang ada hanyalah bahwa amir khusus dengan wilayahnya saja, maka ia mengelola semua urusannya dari segi-segi politik, keuangan, militer, agama, peradilan, dan sebagainya.
Adapun kepemimpinan istila’: ia adalah yang dibentuk oleh imam atau khalifah karena terpaksa, yaitu bahwa amir menguasai dengan kekuatan suatu wilayah, maka pemimpin tertinggi negara mengangkatnya atas kepemimpinannya, dan mendelegasikan kepadanya pengelolaannya dan kebijakannya, maka jadilah amir dengan penguasaannya bersikap independen dengan kebijakan dan pengelolaan; dan kepemimpinan istila’ sesungguhnya adalah jenis kedua dari jenis-jenis kepemimpinan umum.
Kepemimpinan istila’ muncul dari hukum darurat, atau ia adalah pengakuan terhadap politik fakta yang ada, dan tidak dikenal pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, tidak pada masa-masa Kekhalifahan Umayyah, dan tidak pada masa Abbasiyah awal, namun mulai menyebar sejak paruh kedua abad ketiga Hijriyah seiring dengan melemahnya Daulah Abbasiyah, dan kemerdekaannya beberapa wali dari kekuasaan kekhalifahan di ibu kota. Maka muncullah negara-negara kecil yang merdeka dari Daulah Abbasiyah seperti negara-negara: Buwaihiyah, Samaniyah, Ghaznawaiyah, Saljuqiyah, Thuluniyah, Ikhsyidiyah, dan lain-lain dari negara-negara kecil yang para amirnya memerintah melalui kekuatan dan pemaksaan, dan khalifah tidak memiliki kecuali mengakui mereka atas negara-negara kecil tersebut sebagai fakta yang ada yang tidak bisa dihindari, dan tidak ada ruang untuk mengingkarinya atau membatalkannya; agar tidak berujung pada lebih banyak perpecahan dan kehancuran, serta pertumpahan darah.
SYARAT DAN KEWAJIBAN AMIR ISTILA’:
Amir istila’ wajib sebagai imbalan pengakuan wilayahnya—sebagai fakta yang ada—untuk melakukan beberapa perkara, di antaranya: menjaga kedudukan imamah dalam khilafah kenabian, dan mengelola urusan agama; agar apa yang diwajibkan syariat dari penegakannya terpelihara, dan apa yang bercabang darinya dari hak-hak terlindungi. Menampakkan ketaatan agama yang dengan itu hilang hukum pembangkangan; bersatunya kalimat atas persahabatan dan tolong-menolong; agar kaum Muslim menjadi satu tangan terhadap selain mereka; bahwa akad-akad wilayah agama boleh, dan hukum-hukum serta keputusan-keputusan di dalamnya berlaku, tidak batal dengan rusaknya akad-akadnya, dan tidak gugur dengan cacatnya janji-janjinya; bahwa pemenuhan harta-harta syariat dengan hak yang dengannya lepas tanggungan pembayarnya, dan halal bagi pengambilnya; bahwa hudud dipenuhi dengan hak, dan ditegakkan atas yang berhak, maka sesungguhnya sisi orang beriman adalah larangan kecuali dari hak Allah dan hudud-Nya; bahwa amir berdiri dalam menjaga agama; dan bahwa ia berwara’ dari larangan-larangan Allah. Maka kewajiban-kewajiban ini tidak boleh tidak dilakukan oleh amir istila’ sebagai balasan pengakuan keabsahan penguasaannya, dan pengakuannya atas kekuasaan administrasi.
PERBEDAAN ANTARA KEPEMIMPINAN ISTILA’ DAN KEPEMIMPINAN ISTIKFA’:
Kami sebutkan sebelumnya bahwa kepemimpinan istila’ dibentuk karena terpaksa, sementara kepemimpinan istikfa’ dibentuk karena pilihan, dan dengan demikian para ulama membedakan antara kedua kepemimpinan dari empat aspek:
- Bahwa kepemimpinan istila’ ditentukan pada yang ditunjuk yaitu: tidak ada di hadapan imam kecuali mengangkatnya; adapun kepemimpinan istikfa’ maka ia terbatas pada pilihan yang diberi kecakapan yaitu: ia boleh memilih siapa saja dari orang-orang yang layak untuk mengemban tugas ini.
- Bahwa kepemimpinan istila’ mencakup negeri-negeri yang dikuasai oleh yang ditunjuk, dan kepemimpinan istikfa’ terbatas pada negeri-negeri yang tercakup dalam perjanjian yang diberi kecakapan.
Kemudian sekarang kita beralih kepada kepemimpinan khusus:
Kepemimpinan khusus yaitu yang berlawanan dengan kepemimpinan umum, ia adalah: bahwa amir terbatas kepemimpinannya hanya pada sebagian urusan saja di suatu negeri dari negeri-negeri, atau suatu wilayah dari wilayah-wilayah, seperti mengatur pasukan, mengelola rakyat, melindungi kehormatan, dan mempertahankan dari pelanggaran, dan tidak boleh baginya untuk campur tangan dalam peradilan, dan hukum-hukum, atau pemungutan, atau kharaj, dan sedekah. Karena kepemimpinan khusus lebih rendah pengaruhnya dari kepemimpinan umum dan ia terbatas hanya pada sebagian perkara—sebagaimana kami sebutkan—maka ia menyerupai sampai batas tertentu wazir pelaksana dibandingkan wazir pendelegasian; oleh karena itu dapat dikatakan bahwa: disyaratkan pada amir kepemimpinan khusus syarat-syarat yang sama dengan wazir pelaksana, kecuali bahwa dalam hal ini diperlukan bahwa amir adalah Muslim; karena dalam kepemimpinan ada makna wilayah, meskipun kepemimpinan khusus, dan begitu juga diperlukan bahwa amir adalah merdeka; karena wilayah atas orang lain bertentangan dengan perbudakan dan penghambaan, namun tidak disyaratkan bahwa amir kepemimpinan khusus dari ahli ilmu; karena ia tidak memiliki hukum dan tidak peradilan—sebagaimana kami sebutkan—maka ia tidak memerlukan ilmu, namun lebih baik bahwa ia dari para ulama, atau setidaknya dari orang-orang terpelajar, maka tidak menjadi bodoh sama sekali tentang hukum-hukum syariat; karena ini tidak memungkinkannya dari kemampuan untuk melaksanakan kewenangannya.
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN AMIR DALAM KEPEMIMPINAN KHUSUS
Yang termasuk dalam kewenangan Amir dalam kepemimpinan khusus adalah sebagai berikut:
- Menegakkan hukuman-hukuman (hudud) yang berkaitan dengan hak-hak Allah Taala seperti hukuman zina, karena hal itu termasuk dalam peraturan-peraturan pemerintahan, dan kewajiban perlindungan serta pembelaan terhadap agama. Demikian juga hukuman-hukuman yang berkaitan dengan hak-hak manusia, apabila penegakannya tidak memerlukan penelitian dan ijtihad. Adapun yang memerlukan hal tersebut karena perbedaan pendapat para ahli fikih di dalamnya, atau yang memerlukan pengajuan bukti karena adanya sengketa antara pihak-pihak yang bertikai, maka itu keluar dari kewenangan Amir, dan ia tidak boleh mencampuri hal tersebut karena ia bukan ahli ijtihad, apalagi mengingat kekhususan kewenanganannya.
Di antara kewenangan-kewenangannya juga adalah menangani kezaliman apabila pemegang kekuasaan dari kalangan penguasa dan hakim serta yang sejenisnya berbuat sewenang-wenang, dengan syarat kezaliman ini tidak dapat diajukan banding. Jika termasuk perkara yang dapat diajukan banding dan dimulai kembali peradilannya, maka Amir harus menahan diri untuk menanganinya. Dalam kondisi itu, ia harus mengembalikan perkaranya kepada hakim wilayahnya atau kepada hakim terdekat di wilayahnya. Namun ia boleh membantu hakim dalam memenuhi hak-hak, karena ia adalah pemilik wewenang bantuan, bukan wewenang penyelesaian.
Di antara kewenangannya juga adalah: mengimami salat dan mengelola ibadah haji, karena hal ini termasuk dalam kumpulan kewenangan yang didelegasikan kepada Amir.
Di antara kewenangannya juga—yaitu Amir dalam kepemimpinan khusus—adalah jihad. Namun dalam hal ini perlu dibedakan antara memulai perang terhadap musuh yang memasuki wilayah, maka hal itu tidak boleh kecuali dengan izin Khalifah, dan antara serangan yang benar-benar terjadi atas mereka, maka hal itu dibolehkan tanpa izin Khalifah, karena hak dalam pembelaan diri termasuk dalam hak-hak perlindungan dan tuntutan pembelaan terhadap kehormatan, yang termasuk dalam kewenangan-kewenangan Amir.
Kami cukupkan dengan bahasan ini tentang kepemimpinan dengan dua jenisnya: kepemimpinan khusus dan kepemimpinan umum. Dengan demikian kita telah selesai membahas tentang sistem administrasi dalam Islam.
DASAR-DASAR YANG MENJADI LANDASAN HUBUNGAN KAUM MUSLIMIN DENGAN LAINNYA
Sekarang kita beralih untuk membahas politik luar negeri negara Islam, yang merupakan salah satu topik yang ditetapkan dalam politik syariah. Kita akan membahas dalam topik politik luar negeri negara Islam tentang hubungan kaum muslimin dengan lainnya, kemudian kita akan membahas topik lain yaitu: pembagian negara menjadi: negara perang (dar harb) dan negara Islam (dar Islam), serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut. Setelah itu kita akan membahas tentang perjanjian-perjanjian dalam fikih Islam.
Sekarang kita mulai pembahasan tentang hubungan kaum muslimin dengan lainnya. Pembahasan tentang masalah ini—yaitu hubungan kaum muslimin dengan lainnya—dapat dibagi menjadi dua bagian:
Pertama: Dasar-dasar yang menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam.
Kedua: Asal dalam hubungan antara kaum muslimin dengan lainnya adalah perdamaian, bukan perang.
Mengenai bagian pertama yaitu: dasar-dasar yang menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam, kami katakan:
Dari petunjuk-petunjuk Islam dan penelitian terhadap hukum-hukumnya, terlihat jelas bagi kita bahwa hubungan-hubungan Islam menurut para ahli fikih berdiri di atas dasar-dasar yang merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan sosial, bahkan internasional. Kita akan membahas dasar-dasar ini sebagai berikut:
Pertama: Kesatuan Kemanusiaan
Kesatuan kemanusiaan terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya: Kesetaraan dalam asal usul. Dalam hal ini kami katakan: Manusia pada dasarnya sama, tidak ada keutamaan seseorang atas yang lain kecuali dengan ketakwaan, dan tidak ada perbedaan di antara manusia karena warna kulit, ras, atau bahasa. Semua termasuk keturunan Adam, dan Adam dari tanah.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu” (Surah An-Nisaa’: ayat 1). Ayat mulia ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta adalah satu, dan jiwa manusia adalah satu. Ayat ini juga mengarahkan khitab kepada seluruh manusia, karena menyangkut urusan universal kemanusiaan, bukan khusus untuk masyarakat regional atau temporal tertentu.
Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Kemudian Allah mengutus para nabi (untuk) memberi kabar gembira dan peringatan. Dan Dia menurunkan bersama mereka Kitab dengan (membawa) kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan” (Surah Al-Baqarah: ayat 213). Ayat ini menjelaskan bahwa umat manusia adalah satu umat. Allah Taala telah menetapkan bahwa semua manusia adalah satu umat, dan bahwa perbedaan itu bersifat sementara yang sumbernya adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Taala mengutus para rasul dengan petunjuk untuk memutuskan dengan perintah Allah Taala dalam perbedaan ini, dan untuk menjelaskan kepada mereka jalan petunjuk agar ditempuh oleh orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sementara yang lain sesat dan celaka.
Allah Taala berfirman: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa-bahasamu” (Surah Ar-Rum: ayat 22). Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit tidak menghalangi kesatuan kemanusiaan yang menyeluruh. Bahkan perbedaan ini merupakan sunnatullah Taala dalam penciptaan manusia, karena Dia menjadikan dalam diri manusia kekuatan yang dengannya ia dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan berinteraksi.
Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” (Surah Al-Hujurat: ayat 13). Artinya: kalian semua berasal dari satu ayah dan satu ibu, maka tidak ada keutamaan seseorang atas yang lain berdasarkan unsur dan sifat dasarnya. Jika Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maka Dia tidak menjadikan kalian demikian untuk mengutamakan suatu bangsa atas bangsa lain atau suku atas suku lain, melainkan agar hal itu menjadi sarana untuk saling mengenal.
Dengan kata lain: ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan manusia menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku bukan untuk saling berperang atau berselisih, tetapi untuk saling mengenal dan bekerja sama. Saling mengenal ini membuat setiap kelompok memperoleh manfaat dari kebaikan yang ada pada kelompok lain, dan semua kekayaan bumi menjadi milik anak bumi ini yaitu manusia. Hal ini tidak dapat terwujud kecuali dengan kerja sama dan saling mengenal kemanusiaan.
Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda menegaskan prinsip ini: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan dari kalian fanatisme jahiliah dan kesombongan dengan nenek moyang. (Yang ada hanya) mukmin yang bertakwa atau orang fasik yang celaka. Manusia adalah anak-anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah.”
Kesatuan Taklif (Kewajiban)
Kesatuan kemanusiaan mengharuskan kesatuan taklif, karena ketika Islam adalah dakwah universal, maka mengenai taklif, perintah-perintah dan larangan-larangan Al-Quran ditujukan kepada seluruh manusia. Tidak dikhususkan untuk satu bangsa tanpa bangsa lain, atau satu ras tanpa ras lain. Bahkan semua ras dan kelompok dituntut dengan perintah-perintah ini, tanpa memandang perbedaan-perbedaan pribadi di antara mereka seperti: laki-laki dan perempuan, putih dan hitam; atau perbedaan-perbedaan sosial seperti: pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan yang dikuasai, kaya dan miskin.
Dalam makna ini Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “(Syariat Islam) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan bukan (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa berbuat kejahatan, niscaya akan diberi balasan, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong baginya selain Allah” (Surah An-Nisaa’: 123).
Semua berada pada tingkat tanggung jawab yang sama di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat.
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesatuan kemanusiaan mengharuskan kesatuan taklif bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan semua manusia untuk bertakwa dan tunduk kepada agama-Nya. Taklif syariah adalah satu untuk seluruh umat manusia, dan hal itu jelas dalam firman-Nya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan pasangannya” (Surah An-Nisaa’: ayat 1). Risalah Muhammad adalah risalah universal, dakwah kepada seluruh umat manusia untuk memberi petunjuk kepada semua orang.
Kesatuan Agama
Kesatuan kemanusiaan mengharuskan kesatuan agama. Syariat Islam adalah kelanjutan dari syariat-syariat sebelumnya. Setiap syariat sesuai dengan zaman dan tempat di mana syariat itu diturunkan, hingga ketika umat manusia mencapai tingkat kesiapan dan kebutuhan akan syariat penutup, maka Syariat Islam hadir.
Risalah-risalah samawi semuanya bertemu dalam dasar-dasar umum. Adapun rincian-rinciannya berbeda sesuai perbedaan kondisi setiap syariat, sesuai dengan zaman dan tempat kemunculannya. Islam adalah agama semua nabi, sejak manusia ada di muka bumi.
Allah Taala berfirman: “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam” (Surah Ali Imran: ayat 19). Prinsip-prinsip pokok adalah satu.
Allah Taala berfirman: “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya” (Surah Asy-Syura: 13).
Agama adalah Islam pada semua nabi. Allah Taala berfirman: “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri (kepada Allah) dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik” (Surah Ali Imran: 67).
Allah Taala berfirman: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. ‘Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.’ Ataukah kamu menjadi saksi ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ‘Apa yang kamu sembah setelah aku (mati)?’ Mereka menjawab, ‘Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya.'” (Surah Al-Baqarah: 132-133).
Islam memerintahkan untuk beriman kepada semua rasul dan nabi terdahulu. Allah Taala berfirman: “Katakanlah (wahai orang-orang mukmin), ‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya.'” (Surah Al-Baqarah: 136).
Syariat Islam adalah penutup syariat-syariat samawi. Ia datang untuk kebahagiaan umat manusia yang sangat merindukannya, untuk menyelamatkan mereka dari apa yang mereka derita, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan menuju cahaya petunjuk dan keyakinan.
Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun sebuah rumah, lalu ia membaguskan dan menyempurnakannya, kecuali tempat satu batu bata. Maka orang-orang masuk ke dalamnya, mereka kagum dan berkata: Andai saja tempat batu bata ini (dilengkapi). Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Maka akulah (yang mengisi) tempat batu bata itu, aku datang dan menutup (barisan) para nabi.”
Kesatuan Nasib
Di samping kesatuan taklif dan kesatuan agama bagi seluruh umat manusia, maka nasib pun satu. Semua manusia sama dalam tahap-tahap kehidupan mereka dan dalam kesudahan mereka.
Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka (ketahuilah) Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (Kami biarkan kamu hidup) agar kamu sampai kepada usia dewasa” (Surah Al-Hajj: ayat 5).
Demikianlah kita menemukan bahwa kesatuan kemanusiaan adalah salah satu dasar yang menjadi landasan hubungan dalam Islam, baik hubungan individu, kelompok, maupun internasional. Tidak diragukan lagi bahwa perasaan individu, kelompok, atau negara bahwa mereka terikat erat dari segi asal usul dan nasib, mendorong mereka agar hubungan di antara mereka menjadi hubungan yang kokoh pondasinya, yang memperkuat ikatan dan memantapkan hubungan dalam berbagai bidang kehidupan.
Kedua: Hubungan Kemanusiaan
Di antara dasar-dasar yang menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam adalah: hubungan kemanusiaan. Dalam hal ini kami katakan:
Islam memandang umat manusia sebagai satu umat, semuanya berasal dari Adam alaihissalam. Maka tidak ada yang menghalangi adanya hubungan yang didasarkan atas kemanusiaan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dengan keadilan dan ihsan.
Allah Taala berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (Surah An-Nahl: ayat 90).
Al-Quran Al-Karim membolehkan kasih sayang kepada orang yang tidak memerangi kita dalam agama dari kalangan non-Muslim, tidak mengusir kita dari negeri kita, dan tidak membantu pengusiran kita.
Allah Tabaraka wa Taala berfirman: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Surah Al-Mumtahanah: 8-9).
Ayat ini turun berkenaan dengan Asma binti Abu Bakar. Diriwayatkan dari Asma radiyallahu anha bahwa ia berkata: “Ibuku datang dan dia masih musyrik pada masa Quraisy, ketika mereka membuat perjanjian. Maka aku mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dan dia ingin (bertemu denganku)—yaitu ingin menjengukku—apakah aku harus menyambung silaturahmi dengannya?’ Beliau bersabda: ‘Ya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu.'” Meskipun ibu ini bukan seorang muslimah, namun Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyambung silaturahmi dengannya.
Dan Al-Jashash berkata dalam (Ahkam Al-Quran) dalam menafsirkan firman-Nya: bahwa kamu berbuat baik kepada mereka: ini adalah ketentuan umum tentang bolehnya memberikan sedekah kepada ahli dzimmah (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam), karena mereka bukan termasuk orang yang memerangi kita, dan Islam mengajak pada hubungan kemanusiaan ini, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang anak tetangganya yang beragama Yahudi; telah diriwayatkan dari Anas: “Bahwa seorang anak—dari kalangan Yahudi—pernah sakit, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya dalam sakitnya itu, lalu duduk di dekat kepalanya, dan menawarkan Islam kepadanya, maka ayahnya berkata: Taatilah Abu al-Qasim (gelar Nabi Muhammad), maka anak itu masuk Islam, kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam bangkit sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya melalui aku dari neraka.”
Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada delegasi orang-orang musyrik, dan merangkul para pemimpin mereka, dan bertutur kata lembut kepada mereka, dan beliau bersabda: “Apabila datang kepadamu orang terhormat dari suatu kaum, maka hormatlah dia.”
Dan juga termasuk prinsip-prinsip yang menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam: kesetaraan di antara manusia, dan dalam hal itu kami katakan:
Manusia memberikan perhatian pada kesetaraan, dan menghargai siapa yang mengajak kepadanya dan mengamalkannya, dan hal itu kembali pada apa yang mereka lihat berupa kezaliman orang kuat terhadap yang lemah, karena fitrah jiwa yang cenderung pada kesombongan, keangkuhan, egoisme, dan perampasan hak-hak, maka dari itu termasuk hal terpenting yang diperhatikan oleh agama-agama adalah membatasi kezaliman tersebut, dan menghalangi manusia dari merampas hak-hak, dan itu juga merupakan tugas para Rasul—semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah atas mereka—. Fitrah manusia yang cenderung pada kesombongan dan perampasan hak telah bertabrakan dengan agama-agama dan para Rasul sejak zaman dahulu; yang menjadikan kehidupan para Rasul dan para penyeru dengan dakwah mereka sebagai rangkaian penderitaan yang banyak.
Dan sebelum diutusnya Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sistem kasta menguasai dunia dengan cara yang umum dan kejam, sistem ini tumbuh dalam kehidupan sosial dan politik secara bersamaan, bangsa Romawi membagi manusia menjadi orang merdeka dan bukan merdeka; orang merdeka menikmati semua hak, dan yang bukan merdeka terhalang dari menikmati hak apa pun, dan Jazirah Arab tidak lebih bahagia keadaannya, bahkan perbudakan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; sebagai akibat dari serangan-serangan dan peperangan yang berturut-turut, dan perbudakan merupakan pintu dari pintu-pintu perdagangan yang menguntungkan. Ketika Islam datang, tidak menyetujui kondisi-kondisi ini, sebagaimana membebaskan manusia dalam pemikiran dan akidahnya, membebaskannya dari penghambaan kepada tuan-tuannya dan kepada yang lain, dan kecenderungan adil ini adalah nilai yang dibela oleh para penguasa, dan diterapkan oleh para hakim di antara manusia.
Islam datang dengan teori kesetaraan yang sempurna, di mana menetapkan kesetaraan di antara semua manusia dengan perbedaan bangsa dan suku mereka, mereka setara dalam hak dan kewajiban, yaitu dalam sistem yang digambarkan oleh syariat Islam, dan Islam bersungguh-sungguh untuk menetapkan kesetaraan ini dalam bentuknya yang paling sempurna, dan menjadikannya sebagai bagian dari akidah-akidah dasar, yang harus diyakini oleh setiap Muslim, dan Islam mengingkari perlakuan yang berbeda-beda terhadap manusia, dan mengecam diskriminasi rasial, Allah Taala berfirman: Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia termasuk orang yang berbuat kerusakan (Surah Al-Qashash: 4). Dan kesetaraan yang disuarakan oleh Islam ini mencakup semua manusia, tanpa memandang agama yang mereka anut. Di sini Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu menghapuskan segala perbedaan antara Muslim dan non-Muslim, dan ini terlihat jelas ketika dia memerintahkan agar salah satu orang Koptik Mesir diqishash (dibalas setimpal) dari anak Amr bin al-Ash—Wali Mesir—ketika dia memukulnya.
Dan telah diriwayatkan bahwa Muhammad bin Amr bin al-Ash memukul seorang Mesir dengan cambuk sambil berkata kepadanya: Ambillah ini dan aku adalah anak dari orang-orang yang paling mulia, dan Ibnu al-Ash memenjarakan orang Mesir itu; karena khawatir anaknya akan mengadukan kepada Khalifah, ketika orang Mesir itu lolos dari penjaranya, dia pergi ke Madinah, dan mengadukan kepada Umar bin al-Khaththab apa yang menimpanya, maka Umar bin al-Khaththab menahan orang Mesir itu di Madinah.
Dan memanggil Amr dan anaknya dari Mesir, yaitu: meminta Amr bin al-Ash dan anaknya untuk datang kepadanya di istana Khilafah, dan memanggil mereka ke majelis qishash, ketika mereka hadir di sana, Umar memanggil: Di mana orang Mesir? Ambillah cambuk itu—yaitu: tongkat untuk memukul, artinya: ambillah tongkat itu lalu pukullah dengan itu anak orang yang paling mulia—maka orang Mesir itu memukul Muhammad hingga melemahkannya, dan Umar berkata: Pukullah anak orang yang paling mulia. Ketika orang itu selesai, dan ingin mengembalikan cambuk kepada Amirul Mukminin, dia berkata kepadanya: Letakkanlah di kepala botak Amr, demi Allah anaknya tidak memukulmu kecuali karena kekuasaan ayahnya. Amr berkata: Wahai Amirul Mukminin, sungguh dia telah membalas dan memuaskan. Dan orang Mesir itu berkata: Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku telah memukul orang yang memukulku. Dan Umar berkata: Sesungguhnya demi Allah seandainya kamu memukulnya, kami tidak akan—yaitu: tidak akan mencegahmu—menghalangi antara kamu dan dia, sampai kamu sendirilah yang melepaskannya. Dan dia menoleh kepada Amr dengan marah, dan berkata: Wahai Amr, sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang merdeka?!
Dan para hakim Muslim telah menerapkan prinsip kesetaraan dalam peradilan mereka sejauh mungkin; telah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib kehilangan sebuah baju besi—dan pada waktu itu dia adalah Khalifah kaum Muslimin—lalu dia menemukannya di tangan seorang Nashrani di pasar, maka Ali bin Abi Thalib pergi ke hakim kaum Muslimin Syuraih, menggugat Nashrani itu dalam perkara baju besi, dan berkata: “Ini baju besiku, dan aku tidak menjual, dan tidak menghibahkan” artinya: aku tidak menjualnya, dan tidak menghibahkannya. Dan Hakim Syuraih bertanya kepada Nashrani, dan berkata kepadanya: Apa katamu tentang apa yang disebutkan Amirul Mukminin? Maka Nashrani itu berkata: Baju besi itu tidak lain adalah baju besiku, dan Amirul Mukminin menurutku tidak berdusta. Maka Syuraih menoleh kepada Ali bertanya, wahai Amirul Mukminin: Apakah kamu punya bukti? Apakah kamu punya saksi bahwa baju besi ini milikmu? Maka Ali berkata: “Syuraih benar, aku tidak punya bukti.” Maka Syuraih memutuskan baju besi itu untuk Nashrani, lalu dia mengambilnya, dan pergi, sedangkan Amirul Mukminin melihatnya, dan tidak bisa berkata apa-apa.
Dan dari prinsip-prinsip umum juga yang menjadi dasar hubungan antara kaum Muslimin dengan yang lain adalah: kerja sama kemanusiaan, dan dalam hal itu kami katakan:
Tidak ada manusia yang mampu melakukan semua yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri, maka tak terelakkan dia harus meminta bantuan orang lain, sebagaimana orang lain meminta bantuan darinya; karena manusia adalah bagian dari lingkungan dan masyarakat, mempengaruhi dan dipengaruhi, dan berinteraksi dengan yang lain, sebagaimana yang lain berinteraksi dengannya; karena manusia berperadaban secara alami. Dan selama manusia berasal dari asal yang satu, maka itu lebih mendorong untuk bekerja sama; dan perbedaan manusia dalam bangsa dan suku bukanlah agar mereka saling bertarung, tetapi agar mereka saling mengenal, dan saling mengenal tidak terjadi kecuali dengan interaksi yang positif. Tuhan kita Subhanahu wa Taala berfirman: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (Surah Al-Hujurat: dari ayat 13). Dan kerja sama dalam Islam adalah prinsip umum dalam semua kelompok kemanusiaan, hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Taala: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (Surah Al-Maidah: dari ayat 2).
Dan kerja sama adalah pilar keluarga, dan pilar umat. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menyeru dengan perbuatan dan perkataan kepada kerja sama dalam hubungan negara satu sama lain; dan yang menunjukkan hal itu: bahwa ketika beliau datang ke Madinah, beliau membuat perjanjian dengan Yahudi yang dasarnya adalah kerja sama dalam kebajikan, dan perlindungan kebajikan, dan pencegahan bahaya, dan perjanjian ini dinamakan: “Ash-Shahifah” dan shahifah ini memuat banyak ketentuan yang menjelaskan cara mewujudkan kerja sama antara kaum Muslimin dan Yahudi; sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan suku-suku Arab, yang sumbernya adalah toleransi, dan rohnya adalah rahmat, di antaranya Perjanjian Hudaibiyah. Dan beliau membuat kerja sama internasional dalam bidang pertanian dengan Yahudi Khaibar, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan mereka di tanah mereka, dan untuk mereka separuh dari yang keluar darinya berupa buah-buahan atau tanaman. Hal itu ditunjukkan oleh: apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: “Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memperlakukan penduduk Khaibar dengan separuh dari yang keluar darinya” yaitu: dari tanah berupa buah-buahan atau tanaman. Dan dalam riwayat: “Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan Khaibar kepada Yahudi dengan syarat mereka mengerjakannya, dan bercocok tanam di sana, dan untuk mereka separuh dari yang keluar darinya.” Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada siapa yang menolong saudaranya sesama manusia di wilayah mana pun, dan di tempat mana pun, beliau bersabda shallallahu alaihi wasallam: “Dan Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” Dalam hadits ini Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan saudara, tetapi memumkannya, kata itu datang secara umum, maka mencakup persaudaraan kemanusiaan, dan tidak terbatas pada persaudaraan agama, atau wilayah.
Dan demikianlah kita melihat bahwa semua yang menyeru kepada kemajuan dan kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam kerangka kebenaran dan keadilan, syariat mendorongnya; karena itu adalah dari limpahan kerja sama dalam kebajikan dan takwa.
Dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya tercurah atas kalian.
4 – Sisa Dasar-Dasar yang Menjadi Landasan Hubungan Internasional dalam Islam
Kebebasan Beragama
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, pemimpin kami Muhammad, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, adapun setelah itu.
Kita telah memulai pembahasan dalam kuliah yang lalu tentang kebijakan luar negeri negara Islam, dan kita mulai membahas tentang dasar-dasar hubungan internasional dalam Islam, dan kita mulai menghitung dasar-dasar ini, dan kita sebutkan di antaranya: kesatuan kemanusiaan, hubungan kemanusiaan, kesetaraan di antara semua manusia, dan kerja sama kemanusiaan.
Dan dari prinsip-prinsip juga yang dibangun di atasnya hubungan internasional dalam Islam: kebebasan, dan dalam hal itu kami katakan:
Sesungguhnya kebebasan ini berarti: terbebasnya individu dari belenggu, dan kemampuannya untuk bertindak dengan pilihan; maka orang yang merdeka adalah orang yang memiliki dirinya sendiri, dan tidak tunduk pada perbudakan, atau penawanan. Dan kebebasan berarti: terlepas dari penawanan dan perbudakan, dan ia bertemu dalam keberadaannya dengan manusia yang merdeka, yang terjelma di dalamnya nilai kemanusiaan yang luhur, dan dari sini kebebasan mengambil turunannya dari kata merdeka, dan dia menghiasi diri dengannya. Dan orang yang merdeka pada hakikatnya adalah yang memulai dengan kedaulatan atas dirinya sendiri, dan jika itu terwujud baginya, dia menjadi merdeka.
Dan jika kita ingin mendefinisikan kebebasan dalam istilah fikih, kita katakan: Syariat Islam tidak mengenal makna istilah untuk kata kebebasan yang keluar dari makna-makna bahasa—yang telah kami tunjukkan sebagian darinya—dan para fuqaha Muslim terdahulu—juga—tidak mendefinisikannya, namun sebagian dari para ulama kontemporer mendefinisikannya sebagai: terlepasnya manusia dari penjara yang sempit, dan menikmati setiap hak kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan ia adalah hak alami bagi manusia, jika mereka dicabut darinya maka kehendak mereka telah dirampas, dan mereka kehilangan kemanusiaan mereka. Untuk itu Islam menetapkannya, dan mengangkat derajatnya, dan melarang dari bermain-main dengannya. Dan Islam datang; untuk mengangkat martabat manusia dari sisi dia adalah manusia, maka meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, dan mengutamakan manusia atas banyak makhluk.
Dan dalam hal itu Allah Tabaraka wa Taala berfirman: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (Surah Al-Isra: 70).
Dan Islam menghancurkan sistem kasta dari dasarnya; karena manusia dalam pandangannya adalah sama, mereka tidak berbeda kecuali dengan takwa, dan amal saleh. Allah Taala berfirman: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (Surah Al-Hujurat: dari ayat 13). Dan Allah Taala berfirman: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya (Surah An-Nisa: dari ayat 1). Dan dalam hal itu adalah penetapan kesatuan asal, yang mengharuskan tidak adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin, atau kasta. Sesungguhnya filosofi kebebasan dalam Islam terletak pada penghambaan yang sempurna kepada Allah Taala, dan penghambaan ini berarti bahwa manusia memiliki kebebasan penuh di antara sesamanya, dan itu karena selama semua adalah hamba-hamba Allah Taala maka mereka bebas di antara mereka, jika manusia memahami makna kebebasan ini, dia merasakannya dalam kenyataan, dan hidup di tengah-tengahnya dengan jiwa yang mulia, tidak terhina karena kekuatan, atau harta, atau kedudukan.
Dan pengajaran penghambaan ini kepada manusia adalah salah satu tugas terpenting para Rasul—semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah atas mereka—maka tugas mereka—semuanya—adalah menghilangkan penghambaan manusia kepada manusia; agar digantikan dengan penghambaan kepada Allah untuk semua manusia, dan dengan demikian menghadapi mereka yang melampaui batas-batas kemanusiaan, dan mengklaim ketuhanan yang palsu atas manusia seperti mereka; dan untuk mencegah kezaliman terhadap orang-orang yang mereka zalimi, dan mengklaim ketuhanan ini, dan membebaskan mereka dari penghambaan selain Allah, dan mengumpulkan mereka di bawah sistem kehidupan yang adil, yang di dalamnya tidak ada manusia yang menjadi hamba bagi manusia, tetapi semua manusia di dalamnya menjadi hamba-hamba Allah semata.
Dan dalam hal itu Allah Taala berfirman: Itulah Allah Tuhanmu, tidak ada tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu (Surah Al-An’am: 102). Dan Allah Taala berfirman: Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada suatu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah” (Surah Ali Imran: 64). Maka inilah seruan Rabbani yang membebaskan akal dan pikiran; dan membebaskan semua yang diberikan kepada manusia dari kekuatan akal dan materi dari belenggu penghambaan selain Allah; dan mengangkat dari mereka beban yang mereka alami di bawahnya.
Sesungguhnya kebebasan dalam Islam memiliki makna yang luas; Islam ketika menyeru kepadanya tidak menyeru kepada kebebasan individu saja, dan tidak kebebasan kelompok saja, tetapi menginginkan kebebasan ini menjadi milik dan hak bagi semua manusia secara sama, di berbagai penjuru bumi; manusia dalam pandangan manusia adalah merdeka dalam kemanusiaannya, dan merdeka dalam akidahnya, dan merdeka dalam menyatakan pendapatnya. Dan secara keseluruhan: Islam telah menjamin untuk setiap orang kebebasan kemanusiaan, dan sipil, dan politik, dan ilmiah, dan selain itu dari manifestasi kebebasan dengan berbagai jenisnya.
Dan kebebasan dengan pemahaman ini telah ditetapkan oleh Islam dalam hati nurani orang-orang beriman, dan menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari akidah mereka; dan karena itu kita dapati masyarakat Muslim tunduk pada hukum penghambaan kepada Allah Taala, dan melihatnya sebagai kewajiban atasnya, dan hak Allah yang telah menciptakannya, dan dengan itu dia menikmati kebebasan sepenuhnya.
Dan sebagaimana telah kami katakan: sesungguhnya kebebasan memiliki manifestasi yang beragam: ada kebebasan beragama, dan kebebasan politik, hingga berbagai kebebasan lain yang disebutkan oleh para ahli hukum. Tetapi apa yang ingin kami perhatikan adalah: kebebasan beragama yang ditetapkan oleh Islam bagi non-Muslim, dan kami katakan dalam hal ini:
Islam telah menetapkan kebebasan beragama dalam kitab sucinya yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang hal itu: “Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat” (Surah Al-Baqarah: 256). Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya terhadap ayat ini mengatakan: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak membangun urusan keimanan atas dasar pemaksaan dan tekanan, melainkan membangunnya atas dasar kemampuan dan pilihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika telah menjelaskan dalil-dalil tauhid dengan penjelasan yang memadai dan memutus alasan, berfirman setelah itu: bahwa tidak tersisa lagi setelah penjelasan dalil-dalil ini bagi orang kafir alasan untuk tetap dalam kekafiran, kecuali jika dia dipaksa untuk beriman dan dipaksakan kepadanya, dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di dunia yang merupakan tempat ujian, karena dalam paksaan dan pemaksaan dalam agama terdapat pembatalan makna ujian dan cobaan.
Yang menegaskan pernyataan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman setelahnya: “Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat” artinya: dalil-dalil telah tampak, bukti-bukti telah jelas, dan tidak tersisa setelahnya kecuali jalan paksaan, penghalangan, dan pemaksaan, dan itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan taklif (pembebanan).
Makna dari ini adalah: jika dipaksakan masuk Islam orang yang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, dan hasil dari paksaan ini adalah keislaman orang yang dipaksa tersebut, maka hukum Islam tidak berlaku baginya, sampai muncul darinya tanda-tanda yang menunjukkan keislamannya secara sukarela. Jika orang yang masuk Islam karena paksaan meninggal sebelum munculnya tanda-tanda ini darinya, maka hukumnya adalah hukum orang kafir, dan tidak diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang Muslim. Begitu pula jika dia kembali kepada kekafiran, tidak berlaku baginya hukum murtad, dan oleh karena itu tidak boleh membunuhnya. Hal ini karena dia dipaksa pada sesuatu yang Islam tidak membolehkan pemaksaan terhadapnya, maka tidak berlaku hukumnya baginya. Keadaan ini mirip dengan keadaan seorang Muslim jika dipaksa untuk kafir, di mana dia tidak dianggap kafir selama hatinya tetap tenang dengan iman. Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kekafiran) sedang hatinya tetap tenang dengan iman” (Surah An-Nahl: 106).
Maka Allah yang menciptakan manusia bebas dalam pemikiran mereka, bahkan mengagungkan kebebasan mereka, tidak memaksa mereka untuk beriman kepada-Nya dan menyembah-Nya. Dia tidak memperlakukan mereka dengan paksaan walaupun untuk kebaikan. Hal ini karena makna ibadah yang sejati dan makna taklif yang masuk akal tidak selaras dengan paksaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala -dari sisi lain- telah menetapkan tanggung jawab mereka, dan kemudian membiarkan hukum-hukum alam semesta bekerja pada individu dan masyarakat. Ini dibangun atas dasar bahwa ruh tauhid berdiri di atas kebebasan, dan bahwa iman adalah perkara yang lebih dari sekadar perasaan, melainkan dalam hakikatnya menyerupai kepuasan jiwa berdasarkan pengetahuan dan pemahaman.
Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala -dari sisi lain- berkuasa untuk menjadikan semua manusia satu umat dalam keimanan atau kekafiran. Namun perbedaan di antara manusia dalam agama mereka dan keyakinan terhadap agama-agama mereka akan tetap ada. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berharap agar semua orang beriman, dan beliau sedih atas kekafiran sebagian dari mereka. Di sinilah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman untuk melegakan hatinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang yang di bumi beriman seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Surah Yunus: 99). Ibnu Abbas dalam tafsirnya terhadap ayat ini berkata: “Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sangat bersemangat agar semua manusia beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala memberitahukan kepadanya: bahwa tidak beriman kecuali orang yang telah didahului kebahagiaan dalam catatan pertama, dan tidak sesat kecuali orang yang telah didahului kesengsaraan dalam catatan pertama.” Berdasarkan itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kita untuk tidak memaksa siapa pun masuk ke dalam agama Islam, karena agama Islam jelas dan terang, dalil-dalil dan bukti-buktinya tidak memerlukan pemaksaan siapa pun untuk masuk ke dalamnya. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dilapangkan dadanya, dan diterangi mata hatinya, dia akan masuk ke dalamnya dengan bukti yang jelas. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah, dikunci pendengaran dan penglihatannya, maka masuknya dia ke dalam agama secara terpaksa dan dipaksakan tidak akan memberinya manfaat.
Islam menetapkan hal itu karena memandang bahwa iman yang benar dan diterima di sisi-Nya adalah iman yang datang sebagai hasil dari kesadaran akal dan keyakinan hati dengan rela dan kehendak. Islam telah menawarkan dirinya dalam lingkup makna ini tanpa melampauinya sedikit pun. Islam menganggap kebebasan beragama sebagai hak fitrah bagi setiap manusia di setiap zaman dan tempat, yang harus dimungkinkan bagi mereka untuk menikmatinya selamanya. Bahkan ia merupakan hak paling utama yang dengannya melekat padanya sifat manusia. Jika dicabut darinya, maka telah dicabut kemanusiaannya. Maka Islam bukan tujuannya untuk memaksakan dirinya kepada manusia secara paksa, sehingga menjadi satu-satunya agama, karena setiap upaya dari jenis ini adalah upaya yang gagal, bahkan merupakan perlawanan terhadap sunnatullah alam semesta, dan menentang kehendak Tuhan Pencipta alam semesta.
Ada kebenaran-kebenaran yang ditanamkan Islam dalam pikiran para pengikutnya, yang membuat mereka toleran dalam bermuamalah dengan orang yang berbeda agama. Kebenaran-kebenaran ini terletak pada keyakinan Muslim terhadap kemuliaan manusia apa pun agamanya, jenis kelaminnya, atau warna kulitnya; keyakinannya bahwa perbedaan manusia dalam agama terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala; dan keyakinannya bahwa dia tidak dibebani dengan menghisab orang-orang kafir atas kekafiran mereka, karena penghisaban mereka kepada Allah pada hari perhitungan. Pada akhirnya kita harus memperhatikan bahwa: konsep kebebasan beragama dalam Islam berbeda dengan konsep dalam sistem-sistem kontemporer dengan perbedaan yang besar. Sistem-sistem kontemporer mengambil konsep kebebasan beragama yang mencakup kebebasan mengganti agama dan kebebasan murtad dari Islam.
Adapun sistem Islam, membedakan dalam hal ini antara dua perkara: Pertama: kebebasan beragama sejak awal, dan di sini tidak ada yang dipaksa masuk ke dalam agama Islam, di sini kebebasan dijamin bagi semua orang. Kedua: kebebasan murtad, artinya: keluar dari agama Islam setelah masuk ke dalamnya, dan kebebasan ini tidak diakui oleh Islam, dan diberi hukuman paling berat atas pelaksanaannya. Maka kebebasan beragama sejak awal dijamin oleh Islam bagi semua manusia apa pun agama mereka, dan siapa pun penganutnya, tidak ada perbedaan antara bangsa dengan bangsa.
Sekarang kita berbicara tentang karakteristik yang membedakan syariat dalam hal kebebasan beragama:
Karena akidah dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat maknawi, satu-satunya jalannya adalah: persuasi, maka karena itu ia tidak menerima paksaan. Akallah yang memutuskan penerimaannya, sehingga tertanam dalam hati, dan tidak ada jalan bagi paksaan kepadanya sebagaimana telah kami jelaskan. Melalui pemahaman tersebut, tampak beberapa karakteristik yang membedakan syariat dalam hal ini, di antaranya:
1 – Bahwa akidah Islam secara alami ditandai dengan kemudahan dan kesederhanaan, dan tidak ada di dalamnya hal-hal yang bertentangan atau masalah-masalah yang rumit. Dari sifat alami hal-hal yang jelas dan mudah adalah manusia menerimanya dengan mudah dan sederhana. Sebagaimana dari sifat alami hal-hal yang rumit dan bertentangan adalah manusia meragukan dan berpaling darinya, dan oleh karena itu memerlukan cara untuk memaksakan kepada mereka secara paksa, dan memaksa mereka kepadanya dengan tekanan, dan itu bukan dari sifat alami akidah Islam. Islam menetapkan bahwa iman yang datang melalui paksaan tidak ada nilainya, dan tidak ada kemuliaan bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada Firaun ketika dia hampir tenggelam dan berkata: “Aku beriman bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain (Tuhan) yang dipercayai oleh Bani Israil” (Surah Yunus: 90), maka Yang Haq menjawabnya dengan berfirman: “Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal kamu telah durhaka sebelumnya dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan” (Surah Yunus: 90-91). Dan Dia Mahasuci berfirman: “Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata: ‘Kami beriman kepada Allah saja, dan kami ingkari apa yang dahulu kami persekutukan dengan-Nya.’ Maka tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka, ketika mereka telah melihat azab Kami. Itulah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan binasalah di saat itu orang-orang kafir” (Surah Ghafir: 84-85).
Begitu pula Yang Hak Mahasuci menetapkan ketidakberlakuan taubat yang pendorongnya adalah paksaan dan menyaksikan azab. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan tidaklah taubat itu diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan: ‘Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.’ Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang pedih” (Surah An-Nisa: 18).
Dan di antara karakteristik juga: bahwa nash-nash syariah Islam menetapkan bahwa persuasi terhadap akidah Islam, caranya adalah nasihat yang baik dan berdebat dengan cara yang lebih baik, seperti halnya risalah-risalah samawi sebelumnya. Mari kita dengarkan Nabi Nuh Alaihissalam ketika berargumen dengan kaumnya, dan berdialog dengan akal mereka dengan dalil bukan dengan paksaan. Beliau berfirman: “Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi (rahmat itu) disamarkan bagimu. Apakah akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?” (Surah Hud: 28). Kemudian dengarkanlah kaum ‘Ad yang berkata kepada nabi mereka: “Mereka berkata: ‘Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu.'” (Surah Hud: 53). Oleh karena itu Nabi Hud berdoa kepada Tuhannya dengan berkata: “Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu” (Surah Hud: 56).
Kemudian dengarkanlah Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika berargumen dengan ayahnya dengan lemah lembut dan lembut di mana beliau berkata kepadanya: “Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan.’ Dia (ayahnya) berkata: ‘Apakah kamu benci kepada tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama'” (Surah Maryam: 42-46). Kemudian Nabi yang penyayang menjawab dengan berkata kepada ayahnya: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri dari kamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku” (Surah Maryam: 47-48).
Inilah cara para nabi, dan ini adalah cara penghulu para rasul Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: “Katakanlah: ‘Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata'” (Surah Yusuf: 108).
Dan di antara karakteristik juga bahwa pembawa dakwah Islam -Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam- tidak bertanggung jawab di hadapan Yang Hak Jalla wa ‘Ala atau di hadapan makhluk kecuali tentang penjelasan apa yang diturunkan melalui wahyu, yaitu tugas penyampaian dan peringatan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang” (Surah An-Nur: 54). Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka” (Surah Al-Ghashiyah: 21-22). Berdasarkan itu, Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak dituntut atas keimanan manusia, atau memaksa mereka kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki” (Surah Al-Baqarah: 272).
Keadilan
Kemudian kita beralih sekarang kepada fondasi lain dari fondasi-fondasi yang menjadi dasar hubungan internasional dalam Islam, yaitu keadilan. Kita katakan:
Islam sangat menjaga keadilan karena kedudukannya yang mulia dan posisinya yang tinggi. Ia adalah fondasi yang menjadi sandaran bangsa-bangsa dalam kemajuan dan kelangsungan mereka. Oleh karena itu, perintah tentangnya datang dalam berbagai gaya dalam Al-Qur’an Al-Karim sebagai pengagungan terhadap urusannya, dan penjelasan tentang pentingnya berpegang teguh padanya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran” (Surah An-Nisa: 135). Perintah keadilan di sini datang dengan bentuk mubalaghah (hiperbola): “penegak” agar pelaksanaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena ia adalah bentuk mubalaghah artinya: agar berulang dari kalian penegakan keadilan.
Makna: “jadilah kamu penegak” artinya: hendaknya mubalaghah (kesungguhan) dan perhatian dalam menegakkan keadilan dengan semestinya menjadi sifat dari sifat-sifat kalian, dengan mencarinya secara teliti sepenuhnya, sehingga menjadi perkara yang ditetapkan dalam jiwa kalian, tidak meninggalkannya apa pun keadaan yang mengelilingi kalian. Maka janganlah kalian condong dengan hawa nafsu bersama orang miskin karena kelemahannya, dan jangan pula terhadap orang kaya karena kekayaannya. Jadilah bersama kebenaran, karena Allah yang menguji orang ini dan memiskinkan orang itu lebih berhak terhadap orang miskin untuk memperkayanya dengan karunia-Nya dengan kebenaran, bukan dengan hawa nafsu. Dan Allah lebih berhak terhadap orang kaya untuk mengambil apa yang ada di tangannya dengan keadilan dan kebenaran, bukan dengan tipu daya dan penindasan terhadapnya.
Maka keadilan adalah hak musuh sebagaimana ia adalah hak para wali. Al-Qur’an Al-Karim menegaskan bahwa: tidak benar permusuhan membawa kepada kezaliman, karena keadilan terhadap musuh lebih dekat kepada takwa. Dalam hal itu Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa” (Surah Al-Maidah: 8). Artinya: janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membawa kalian untuk tidak berlaku adil dalam hukum kalian terhadap mereka, dan perilaku kalian di antara mereka, sehingga kalian berlaku zalim kepada mereka karena permusuhan yang ada antara kalian dan mereka. Ath-Thabari berkata: Maknanya Jalla Tsana-uhu (Mahasuci dan Mahatinggi) dengan firman-Nya: “Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa” artinya: berlakulah adil wahai orang-orang yang beriman terhadap siapa pun dari manusia, baik wali bagi kalian maupun musuh. Berlakukanlah kepada mereka apa yang Aku perintahkan kepada kalian untuk berlakukan kepada mereka dari hukum-hukum-Ku, dan janganlah kalian berlaku zalim terhadap siapa pun dari mereka. Berlaku adil terhadap mereka wahai orang-orang yang beriman lebih dekat bagi kalian agar kalian menjadi dengan mengamalkannya dari golongan ahli takwa.
Sesungguhnya Dia Jalla Tsana-uhu mensifati keadilan dengan apa yang Dia sifati dengannya bahwa ia lebih dekat kepada takwa daripada kezaliman, karena barangsiapa yang adil maka dengan keadilannya dia taat, dan barangsiapa yang taat kepada Allah maka dia tanpa keraguan termasuk ahli takwa. Dan barangsiapa yang zalim maka dia bermaksiat kepada Allah, dan barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah maka dia jauh dari takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan keadilan bahkan jika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang kafir. Dia Mahasuci berfirman: “Jika mereka (orang Yahudi itu) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Surah Al-Maidah: 42). Maka firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala: “maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil” artinya: dengan keadilan, dan itu adalah hukum dengan apa yang Allah jadikan sebagai hukum dalam hal yang serupa atas semua makhluk-Nya dari umat Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala menyukai orang-orang yang adil -yaitu orang-orang yang adil dalam keputusan mereka di antara manusia- yang memutuskan di antara mereka dengan hukum Allah yang Dia turunkan dalam kitab-Nya.
Yang harus diperhatikan adalah bahwa keadilan yang dibawa oleh syariat adalah: keadilan mutlak yang membahagiakan umat manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Ibnul Qayyim berkata tentang syariat: Ia semua keadilan, semua rahmat, semua kemaslahatan, semua hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada lawannya, dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari hikmah kepada main-main, maka ia bukan dari syariat, walaupun dimasukkan ke dalamnya dengan takwil. Maka syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara makhluk-Nya, naungan-Nya di bumi-Nya, dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya, dan yang juga menunjukkan kepada kebenaran Rasul-Nya Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
Menepati Janji
Salah satu dasar yang menjadi landasan hubungan internasional Islam adalah menepati janji. Dalam hal ini kami sampaikan:
Sesungguhnya menepati janji adalah akhlak mulia dan sifat yang baik. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk menepati janji. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Surat Al-Maidah, ayat 1) artinya: penuhilah akad-akad yang kalian janjikan kepada Tuhan kalian, dan akad-akad yang kalian janjikan kepada-Nya, dan kalian wajibkan dengan akad-akad itu atas diri kalian berupa hak-hak, dan kalian bebankan pada diri kalian untuk Allah Subhanahu Wata’ala berupa kewajiban-kewajiban, maka sempurnakanlah dengan menepati, menyempurnakan, dan menunaikannya dari kalian untuk Allah Subhanahu Wata’ala dengan apa yang Dia bebankan kepada kalian, dan untuk orang yang kalian berjanji dengannya, dengan apa yang kalian wajibkan untuknya atas diri kalian, dan janganlah kalian batalkan setelah menguatkannya.
Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (Surat Al-Isra, ayat 34) artinya: tepatilah akad yang kalian buat dengan manusia dalam perdamaian antara ahli perang dan Islam; dan juga di antara kalian sendiri, dalam jual beli dan sewa-menyewa, dan selain itu dari akad-akad. Dan Allah Subhanahu Wata’ala akan menanyai orang yang mengingkari janji tentang pengingkarannya itu. Allah berfirman: maka janganlah kalian membatalkan janji-janji yang sah antara kalian dengan orang yang kalian buat janji dengannya wahai manusia, lalu kalian meremehkannya dan berkhianat kepada orang yang kalian berikan janji itu.
Menepati janji adalah akhlak para nabi. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Dan ceritakanlah (Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) kisah Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya.” (Surat Maryam, ayat 54) Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wata’ala berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam: dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Kitab ini kisah Ismail bin Ibrahim, maka ceritakanlah kabarnya, sesungguhnya dia tidak pernah mendustai janjinya dan tidak mengingkari, tetapi jika dia berjanji kepada Tuhannya atau kepada seorang hamba dari hamba-hamba-Nya suatu janji, maka dia menepatinya. Menepati janji adalah salah satu sifat orang-orang mukmin. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.” (Surat Al-Mu’minun, ayat 8) yaitu: amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka, dan janji mereka—yaitu: akad-akad mereka—yang mereka buat dengan manusia, maka mereka memeliharanya—artinya: menjaganya—tidak menyia-nyiakannya, tetapi mereka menepati semua itu.
Al-Quran mengingatkan bahwa orang yang mengingkari janji akan tercela, bahkan dia adalah seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah Subhanahu Wata’ala. Al-Quran Al-Karim telah mencela orang-orang Yahudi karena mereka mengingkari janji yang ada antara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan mereka. Allah berfirman: “Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman, (yaitu) orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, kemudian mereka mengingkari janjinya itu pada setiap kalinya, sedang mereka tidak bertakwa.” (Surat Al-Anfal, ayat 55-56) Ibnu Abbas berkata: “Mereka adalah Bani Quraizhah, karena sesungguhnya mereka mengingkari janji Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan membantu orang-orang musyrik melawannya dengan senjata pada hari Badar, kemudian mereka berkata: Kami salah, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membuat perjanjian dengan mereka lagi, kemudian mereka mengingkarinya lagi pada hari Khandaq.”
Firman Allah: “sedang mereka tidak bertakwa” maknanya: bahwa kebiasaan dari hukum akal adalah bertakwa dari mengingkari janji, agar manusia tenang terhadap perkataannya dan percaya pada ucapannya. Dalam mengingkari janji terdapat dosa besar. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.” (Surat Ash-Shaff, ayat 2-3) artinya: wahai orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah dan Rasul-Nya: mengapa kalian mengatakan perkataan yang tidak kalian benarkan dengan amal, maka amal kalian bertentangan dengan perkataan kalian, sangat besar kebencian di sisi Tuhan kalian bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan.
Islam mewasiatkan untuk menghormati janji dengan negara-negara yang lemah sebagaimana menghormatinya dengan negara-negara yang kuat. Kelemahan negara tidak boleh menjadi alasan untuk mengingkari janji dengannya, bahkan harus menepati janji, tanpa penipuan dan tanpa pengkhianatan, karena itu dilarang. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipu di antara kalian, disebabkan adanya suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan itu. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kalian akan ditanya tentang apa yang telah kalian kerjakan. Dan janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipu di antara kalian, yang menyebabkan tergelincir kaki (kalian) sesudah kokoh tegaknya dan kalian rasakan akibat buruk karena kalian menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan kalian akan mendapat azab yang besar.” (Surat An-Nahl, ayat 91-94).
Ayat-ayat sebelumnya mengandung hal-hal berikut:
Mengandung perintah untuk menepati janji dan larangan membatalkannya setelah menguatkannya, karena Allah Azza wa Jalla menjadi saksi atasnya, penjaga dan penjaminnya, dan ini lebih mendorong untuk menepatinya.
Juga: ayat ini menyerupakan orang yang mengingkari, berjanji, dan menguatkan janjinya, kemudian membatalkannya dengan perempuan bodoh yang memintal benangnya dan membuatnya kuat, kemudian melepaskannya. Mengingkari janji adalah kebodohan yang menyebabkan putusnya hubungan antara individu, negara, dan kelompok, dan ini tidak lain karena buruknya pemikiran dan rusaknya perencanaan.
Ayat ini menjelaskan bahwa sedikit atau banyak tidak boleh menjadi alasan untuk mengingkari janji, bahkan harus menjaga janji dan berpegang teguh padanya. Allah Subhanahu Wata’ala menguji hamba-hamba-Nya dengan tantangan dan usaha sebagian mereka untuk menang atas sebagian yang lain, dan menguji mereka dengan itu, untuk melihat siapa yang berjihad melawan nafsunya dan menentangnya, dan siapa yang larut di dalamnya dan bekerja sesuai keinginannya.
Ayat ini juga mengandung ancaman bagi orang yang mengingkari janji dan membuat akad dengan menyimpan penipuan dan kerusakan di dalamnya setelah kokoh, dan kakinya tergelincir lalu jatuh ke tempat yang rendah. Mengingkari janji merendahkan kedudukan dan menyebabkan kehinaan, dan seterusnya. Kita menyimpulkan dari ayat-ayat:
Bahwa jalan untuk menjaga stabilitas perdamaian adalah perjanjian keamanan dan tidak menyerang, dan bahwa perjanjian tidak mendapatkan kekuatannya dari teks-teksnya, tetapi dari tekad pembuat perjanjian untuk menepati. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong untuk menepati, dan menganggap menepati janji dan perjanjian sebagai kekuatan, sedangkan mengingkarinya adalah mengambil sebab-sebab kelemahan.
Dan bahwa orang yang menguatkan janjinya dengan sumpah Allah telah menjadikan Allah sebagai penjamin penepatan janjinya, maka jika dia berkhianat dengan janjinya, dia telah menjadikan janji Allah untuk penipuan dan ucapan palsu. Dan tidak boleh motif pengkhianatan antara negara-negara adalah keinginan agar suatu umat menjadi lebih kuat dalam harta dan peralatan, lebih banyak jumlahnya, dan lebih luas wilayahnya dari umat lain.
Allah telah menjelaskan bahwa menepati janji adalah tujuan dasar dan tertinggi yang diarahkan oleh orang-orang mukmin untuk mewujudkan makna kesatuan kemanusiaan dengan kehendak dan pilihannya, dan terwujud apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wata’ala yang jika Dia menghendaki, pasti Dia menjadikan manusia tidak berselisih sama sekali, tetapi ada perbedaan agar Allah menguji kehendak-kehendak manusia dalam melaksanakan apa yang Dia perintahkan.
Jika Al-Quran Al-Karim menyeru orang-orang mukmin untuk menguatkan janji-janji, melaksanakannya, dan mewujudkan keamanan di antara manusia dengannya, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam—sebagai pembawa risalah Al-Quran—juga mendorong untuk menepati janji. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya orang yang berkhianat akan ditegakkan baginya sebuah bendera pada hari kiamat, lalu dikatakan: Ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan.” Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Rafi’, bahwa Abu Rafi’ memberitahunya, dia berkata: “Suku Quraisy mengutusku kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, maka ketika aku melihat Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, Allah Tabaraka wa Ta’ala memasukkan Islam ke dalam hatiku. Aku berkata: Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya aku tidak mengingkari janji—artinya: tidak membatalkan janji—dan aku tidak mengingkari utusan—artinya: tidak membatalkan dan tidak membunuh utusan—tetapi kembalilah—artinya: kembalilah kepada mereka—maka jika dalam dirimu seperti yang ada dalam dirimu sekarang, kembalilah. Dia berkata: Maka aku pergi, kemudian aku datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu masuk Islam.”
Kita menyimpulkan dari yang telah disebutkan:
Bahwa menepati janji adalah salah satu dasar yang menjadi landasan hubungan kemanusiaan internasional dalam Islam, karena di dalamnya terdapat penguatan ikatan, menjaga hubungan, dan memperbaiki relasi, dan inilah yang menjadi tujuan syariat Islam.
Kebajikan
Di antara hal-hal juga, atau dasar-dasar yang menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam adalah kebajikan. Dalam hal ini kami sampaikan:
Islam menyeru untuk menjaga kebajikan, baik hubungan itu bersifat individual, kelompok, maupun internasional, karena dalam hal ini terdapat pemeliharaan terhadap nilai-nilai luhurnya dan seruan untuk mendirikan masyarakat yang baik yang mampu memikul beban-bebannya.
Sesungguhnya Islam memandang hukum akhlak sebagai hukum umum yang mencakup orang kulit putih dan hitam, merah dan kuning, dan mencakup semua manusia di seluruh negara dan wilayah. Kebajikan menurut aturan perilaku yang baik adalah hak setiap manusia, dia berhak mendapatkannya karena kemanusiaannya yang merupakan sifat yang sama di antara semua anak Adam. Hal itu telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip Islam yang diterapkan kepada semua manusia. Yang paling kuat diajak oleh Al-Quran Al-Karim dalam perintah berbuat baik adalah: apa yang berkaitan dengan jihad, karena khawatir jiwa-jiwa terdorong dalam keadaan perang yang memanas untuk melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip penting itu.
Kebajikan adalah akhlak yang diterapkan bahkan kepada musuh dalam keadaan perang. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Maka barangsiapa menyerang kalian, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Surat Al-Baqarah, ayat 194) Takwa adalah kebajikan. Kebajikan melarang memutilasi orang yang terbunuh, meskipun musuh memutilasi orang-orang Islam yang terbunuh. Diriwayatkan dari Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika mengutus seorang pemimpin untuk suatu pasukan, dia berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah, dan kepada orang-orang Muslim yang bersamanya dengan kebaikan, dan bersabda: Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, dan janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian memutilasi, dan janganlah kalian membunuh anak-anak.”
Kebajikan menyeru kita untuk memperlakukan tawanan dengan baik, meskipun musuh memperlakukan tawanan kita dengan buruk. Allah Subhanahu Wata’ala memuji orang yang memberi makan tawanan dengan firman-Nya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan.” (Surat Al-Insan, ayat 8) Yang dimaksud dengan tawanan adalah: orang yang berperang dari penduduk negeri perang yang ditangkap secara paksa dengan kemenangan. Maka Allah memuji orang-orang yang baik ini karena memberi makan orang-orang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap keridaan-Nya, dan sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada mereka. Demikianlah perlakuan kaum Muslim terhadap selain mereka atas dasar kebajikan, tidak melampauinya. Kaum Muslim tidak membunuh orang-orang yang meminta perlindungan selama perang, meskipun musuh membunuh orang-orang Islam yang meminta perlindungan. Tidak ada peperangan kecuali dengan orang-orang yang berperang dan yang membawa senjata. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Surat Al-Baqarah, ayat 190) Perang hanya terhadap orang-orang yang menyerang.
Berdasarkan hal ini, kebajikan adalah kerangka di mana semua tindakan yang dilakukan oleh kaum Muslim berputar di dalamnya, yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang baik di tingkat lokal dan global.
Toleransi
Juga di antara dasar-dasar yang menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam adalah prinsip toleransi:
Islam telah memberikan teladan tertinggi dalam toleransi terhadap ahli dzimah. Islam membiarkan mereka dengan agama mereka, tidak diuji untuk meninggalkan agama mereka, dan tidak ada penindasan yang menimpa mereka. Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam telah meletakkan landasan toleransi beragama. Dalam perjanjian perdamaian yang dibuat antara Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam dengan orang-orang Kristen penduduk Najran, kita dapati bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengakui kebebasan mereka dalam keyakinan mereka. Dalam teks perjanjian ini disebutkan:
“Bahwa mereka mendapat jaminan Allah dan perjanjian-Nya, dan tidak akan diuji untuk meninggalkan agama mereka, dan tidak diubah dari apa yang mereka jalani, dan tidak diubah haknya dari hak-hak mereka dan patung-patung mereka—maksudnya: salib dan gambar—dan tidak diuji seorang uskup dari keuskupannya, dan tidak seorang rahib dari kerahibannya.”
Dari perjanjian ini terlihat jelas bagi kita sejauh mana toleransi yang diberikan oleh shallallahu ‘alaihi wasallam kepada penduduk Najran.
Juga, Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam mengakui kebebasan orang-orang Yahudi. Beliau menulis kepada Mu’adz bin Jabal—yang berada di Yaman—: “Ketahuilah, janganlah seorang Yahudi diuji untuk meninggalkan keyahudiannya.” Jika kita melihat apa yang dimuat dalam surat perdamaian yang dibuat antara Umar bin Al-Khathab dan penduduk Iliya (Yerusalem), kita dapati bahwa Umar memberi mereka keamanan untuk diri mereka, gereja-gereja mereka, dan salib-salib mereka, dan menjamin mereka agar gereja-gereja ini tidak ditempati, atau dihancurkan, atau dikurangi sedikitpun, dan dengan makna yang lebih umum: menjamin agar mereka tidak dipaksa dalam agama mereka, dan tidak dirugikan seorangpun dari mereka karena keyakinannya.
Dalam surat perdamaian yang dibuat antara Iyadh bin Ghanm dengan salah satu kota Syam, kita dapati bahwa dia mengakui mereka dalam keyakinan mereka, di mana dia memberi mereka keamanan untuk diri mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan menjamin agar tidak dirusak dan tidak ditempati.
Juga, kita dapati Khalid bin Al-Walid dalam perdamaian yang dibuat antara dia dengan penduduk Damaskus: dia mengakui mereka dalam keyakinan mereka, di mana dia mengamankan tempat-tempat ibadah ini.
Juga: apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khathab ketika dia memasuki Baitul Maqdis untuk membuat perjanjian dengan penduduknya. Waktu shalat datang ketika dia berada di Gereja Makam Suci, tetapi dia menolak untuk shalat di dalamnya, karena khawatir kaum Muslim akan menjadikannya masjid setelahnya, sehingga mereka menzalimi penduduknya.
Dan juga: ketika ia melihat sebuah tempat ibadah yang terkubur dalam tanah, kemudian ia tahu bahwa itu milik orang Yahudi, ia mulai membersihkan tanah darinya dengan keutamaan pakaiannya, maka pasukannya mengikuti apa yang ia lakukan, tidak lama berselang tanah telah hilang dari tempat ibadah tersebut.
Dan apa yang kami sampaikan ini hanya sebagai contoh, bukan batasan, yang menunjukkan dengan jelas tentang toleransi beragama di kalangan umat Islam, dan penerapan mereka terhadapnya sepanjang masa yang berurutan, tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan salah satu fondasi yang berkontribusi dalam membangun hubungan internasional kemanusiaan.
Rahmat
Dan juga termasuk fondasi yang menjadi dasar hubungan internasional dalam Islam adalah prinsip rahmat:
Sesungguhnya Islam adalah agama rahmat; oleh karena itu, saling berwasiat dengannya merupakan kewajiban di antara kaum muslimin, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk berkasih sayang” (Surah Al-Balad: 17) dan Rasul kaum muslimin adalah rasul rahmat, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Surah Al-Anbiya’: 107) dan rahmat yang diajak oleh Islam tidak hanya dinikmati oleh muslim saja, karena ia menaungi muslim dan non-muslim, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang, sayangilah orang yang ada di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Yang ada di langit” dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak akan menyayanginya” dan beliau juga bersabda shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidaklah dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang yang celaka”.
Bahkan Islam menjelaskan bahwa kelembutan terhadap hewan di dalamnya terdapat pahala yang besar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia kehausan, lalu ia menemukan sumur, maka ia turun ke dalamnya, lalu ia minum, kemudian ia keluar, ternyata ada seekor anjing menjilat tanah karena kehausan, maka orang itu turun ke sumur, lalu ia memenuhi sepatunya dengan air, kemudian ia memegang sepatu itu dengan mulutnya, lalu ia memberi minum anjing itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala bersyukur kepadanya, lalu mengampuninya, mereka bertanya: wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, apakah pada hewan-hewan ada pahala bagi kami?! Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: pada setiap yang memiliki hati yang basah ada pahala”. Dan diriwayatkan dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: “Ketika seekor anjing berkeliling di sebuah sumur yang hampir membunuhnya karena kehausan, tiba-tiba dilihat oleh seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israil, maka ia melepas sepatunya, lalu ia mengambil air untuknya, lalu ia memberinya minum, maka diampunilah dosanya karenanya” Jika kasih sayang kepada anjing dapat mengampuni dosa-dosa para pelacur, maka kasih sayang kepada manusia tidak diragukan lagi akan menciptakan keajaiban, bahkan Islam sangat keras dalam menghukum orang-orang yang hatinya keras terhadap hewan, dan meremehkan penderitaannya, dan telah kami jelaskan bahwa manusia -meskipun kedudukannya tinggi- masuk neraka karena perbuatan buruk yang ia lakukan terhadap hewan bisu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung, ia tidak memberinya makan, dan tidak pula ia melepaskannya agar bisa makan dari serangga-serangga bumi”.
Dan Islam mengajak kepada rahmat dengan makna yang paling luas terhadap muslim dan non-muslim, terhadap manusia dan hewan seperti yang telah kita lihat.
Dan dalam hubungan internasional, ia memberikan teladan tertinggi dalam keadaan perang, dan penggunaan rahmat terhadap musuh, maka wanita tidak dibunuh dalam keadaan perang selama mereka tidak ikut serta dalam pertempuran, demikian juga anak-anak dan orang-orang tua tidak dibunuh; telah diriwayatkan bahwa seorang wanita ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak”.
Dan betapa indahnya manifestasi rahmat yang ada dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hari penaklukan Makkah ketika ia memasukinya sebagai pemenang, dan suku Quraisy telah memenuhi masjid berbaris-baris, menunggu apa yang akan ia perbuat terhadap mereka? Kemudian beliau berkata: “Wahai sekalian Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku perbuat terhadap kalian? Mereka berkata: kebaikan, saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia, beliau berkata: maka sesungguhnya aku mengatakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Yusuf ‘alaihissalam kepada saudara-saudaranya: “Tidak ada cercaan terhadap kalian pada hari ini” (Surah Yusuf: dari ayat 92) Pergilah, kalian adalah orang-orang yang dibebaskan”.
Saya serahkan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan semoga kesejahteraan, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
5 – Perdamaian adalah Dasar Hubungan antara Kaum Muslimin dan Lainnya, Hukum-hukum Dua Wilayah, dan Pendahuluan tentang Perjanjian-perjanjian dalam Islam
Dasar Hubungan antara Kaum Muslimin dan Lainnya: Perdamaian
Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam tercurah kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, pemimpin kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan, amma ba’du:
Sesungguhnya kita telah berbicara -dalam ceramah yang lalu- tentang sisa fondasi yang menjadi dasar hubungan internasional dalam Islam, yaitu kebebasan beragama, keadilan, menepati janji, keutamaan, toleransi, dan rahmat.
Dan kita beralih sekarang kepada pembicaraan tentang dasar hubungan antara kaum muslimin dan lainnya, yaitu perdamaian, maka kami katakan: Asal dalam hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian -dan ketika Islam memutuskan bahwa perdamaian adalah salah satu prinsip hubungan kemanusiaan antara negara-negara- tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mencampuri urusan negara-negara kecuali untuk melindungi kebebasan umum, dan ketika orang-orang yang teraniaya meminta pertolongan kepada mereka, atau terjadi agresi terhadap orang-orang beriman yang beragama Islam; maka dalam keadaan-keadaan ini dapat dilakukan campur tangan untuk mencegah fitnah dalam agama.
Sesungguhnya Islam menghormati hak setiap negara untuk ada, dan haknya untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri, dan haknya dalam mempertahankan wilayahnya dan kedaulatannya, tidak ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, Islam menginginkan keselamatan, dan tidak menginginkan agresi, dan tidak menginginkan kesombongan di bumi, ia menginginkan perdamaian antara hamba dan Tuhannya; maka ia senantiasa berhubungan, senantiasa khusyuk dan muraqabah, dan ia menginginkan perdamaian antara bangsa-bangsa dengan lainnya, dan ia menginginkan perdamaian antara individu dan masyarakatnya, sesungguhnya pembunuhan dalam Islam tidaklah disyariatkan kecuali untuk membela kaum muslimin dan negara mereka, dan juga untuk menjamin kebebasan beragama, dan mencegah penindasan di dalamnya; maka ia disyariatkan untuk melindungi dakwah dan metodenya dalam kehidupan, sehingga setiap orang yang menginginkannya dapat berlindung kepadanya tanpa khawatir akan kekuatan yang akan menyerangnya, atau mencegahnya, atau memfitnahnya, maka pembunuhan hanya diwajibkan sebagai balasan terhadap orang yang berperang, bukan sebagai balasan terhadap kekufuran -artinya: bahwa pembunuhan hanya untuk orang yang memeranginya.
Dan demikianlah kita dapati bahwa Islam lebih memilih perdamaian daripada peperangan, dan tidak membolehkan peperangan kecuali dalam keadaan darurat, dan itu dianggap pengecualian dari pemikiran Islam tentang perdamaian, yang terletak pada kaidah: Perdamaian selamanya, dan perang adalah darurat; maka pembunuhan bukanlah dari hakikat Islam, bahkan dalam hakikatnya adalah maaf dan toleransi; barangsiapa yang tidak menjawab dakwah, dan tidak menentangnya, dan tidak memulai menyerang kaum muslimin dengan agresi; maka tidak halal memeranginya, dan tidak boleh mengubah keamanannya menjadi ketakutan, dan apa yang diputuskan oleh Islam dalam hal itu telah diterapkan oleh kaum muslimin, dan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa asal dalam Islam dalam hubungan kaum muslimin dengan lainnya adalah perdamaian, bukan perang; dari Al-Qur’an Al-Karim -Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan perangilah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta’ala orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Surah Al-Baqarah: ayat 190). Sisi petunjuk dari ayat: bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan izin kepada kaum muslimin dalam berperang sebagai pembelaan -di jalan Allah Subhanahu Wa Ta’ala- untuk dapat beribadah kepada-Nya, kemudian Dia memerintahkan mereka untuk tidak melakukan agresi dengan berperang, atau dalam berperang, adapun tidak melakukan agresi dengan berperang; maka terletak pada tidak memulai menyerang orang-orang kafir, dan adapun tidak melakukan agresi dalam berperang; maka terletak pada tidak membunuh orang yang tidak berperang; seperti wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, atau orang yang menyerahkan perdamaian kepada kaum muslimin atau menghentikan perang terhadap mereka.
Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang kaum muslimin dari agresi; karena agresi termasuk kejahatan yang diminta; maka ayat ini mengandung kaidah-kaidah legislatif yang menunjukkan roh prinsip-prinsip pertempuran Islam, di antaranya: kewajiban kaum muslimin dalam memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja.
Tidak diperbolehkan memulai menyerang seseorang yang bukan musuh dan bukan agresor dengan peperangan.
Kewajiban menghentikan peperangan ketika berakhir dengan sikap agresi yang menimpa mereka.
Maka ayat ini -meskipun mengandung izin tegas untuk berperang- namun ia bersyarat dengan pembelaan, dan tidak melakukan agresi terhadap orang lain; karena agresi menyebabkan murka Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan dari Al-Qur’an juga firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam perdamaian secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan” (Surah Al-Baqarah: dari ayat 208) dan yang dimaksud dengan perdamaian -di sini- adalah perdamaian, maka ayat ini menunjukkan bahwa menepati janji dan berdamai seharusnya menguasai di antara manusia, dan meninggalkan peperangan.
Dan disimpulkan dari ayat ini: juga bahwa iman orang-orang beriman mewajibkan mereka untuk masuk dalam perdamaian dengan lainnya, dan tidak menyerang siapa pun yang tidak menyerang mereka, dan tidak memerangi orang yang tidak memerangi mereka, dan dari Al-Qur’an juga: firman Allah Tabaraka Wa Ta’ala: “Maka jika mereka menjauhkan diri dari kalian sehingga mereka tidak memerangi kalian dan mereka menyampaikan perdamaian kepada kalian, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak memberikan jalan bagi kalian untuk (menyerang) mereka” (Surah An-Nisa’: ayat 90) Sisi petunjuk: bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang menjauhkan diri dari mereka sehingga tidak memerangi mereka, dan menyampaikan perdamaian kepada mereka -yaitu: perdamaian- dan dalam ayat ini terdapat penekanan dalam tidak menyerang orang-orang ini yang tidak memerangi kaum muslimin, dan menyampaikan perdamaian kepada mereka; di mana dinafikan pemberian jalan bagi kaum muslimin terhadap orang-orang ini yang tidak memerangi mereka.
Dan dari Al-Qur’an Al-Karim juga firman Allah Tabaraka Wa Ta’ala: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka” (Surah Al-Hajj: ayat 39) Sisi petunjuk bahwa ayat ini di dalamnya terdapat izin bagi orang-orang yang diperangi oleh kaum musyrikin -karena kezaliman kaum musyrikin terhadap mereka, bukan karena kekufuran mereka- maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kezaliman yang diisyaratkan olehnya -dan yang menimpa kaum muslimin- sesungguhnya terletak pada perampasan kebebasan beragama mereka, dan agresi terhadap mereka, serta menghalangi mereka dari dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala; maka mereka dianiaya, dan orang yang teraniaya berhak untuk membela dirinya, dan oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengizinkan mereka untuk berperang membela diri mereka -artinya: bahwa tidak ada yang mendorong kaum muslimin kepada peperangan kecuali kezaliman yang menimpa mereka yang ingin mereka tolak.
Inilah bukti-bukti dari Al-Qur’an Al-Karim, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kaum muslimin dan lainnya dasarnya adalah perdamaian, bukan perang, dan jika kita kembali kepada Sunnah Nabi yang mulia; maka kita dapati bahwa ada banyak hadits yang mendukung arah ini, dan yang menjadikan dasar hubungan antara kaum muslimin dan lainnya sesungguhnya adalah perdamaian, bukan perang, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala keselamatan, maka jika kalian bertemu dengan mereka maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang” dan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Biarkanlah orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian, dan tinggalkanlah orang Turki selama mereka meninggalkan kalian” Maka hadits ini memerintahkan kaum muslimin untuk berdamai dengan orang Habasyah dan Turki, dan tidak menyerang salah satu dari mereka selama mereka tidak menyerang kaum muslimin dengan peperangan atau lainnya, dan tidak ada makna untuk itu kecuali bahwa barangsiapa yang berdamai dengan kaum muslimin maka mereka harus berdamai dengannya, dan tidak menyerangnya dengan gangguan.
Dan termasuk bukti juga bahwa hubungan antara kaum muslimin dan lainnya sesungguhnya didasarkan pada perdamaian, bukan perang.
Sebab-sebab peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin: maka orang yang mengikuti peperangan-peperangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan menemukan bahwa peperangan-peperangan ini sesungguhnya adalah pembelaan menghadapi agresi yang terjadi, atau dalam proses akan terjadi dengan tanda-tanda yang menunjukkan perang; maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi kecuali setelah mereka mencapai tingkatan dalam perilaku yang kosong dari kehormatan, amanah, dan keadilan, dan ditandai dengan permusuhan; maka tidak ada antara kaum muslimin -di satu sisi- dan orang-orang Yahudi serta Nasrani -di sisi lain- selain keadaan perang.
Dan alasannya adalah karena mereka merampas hak-hak kaum muslimin dan kebebasan mereka, dan menghalangi mereka dari dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan berbagai cara, dan mereka menindas orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala lapangkan dada mereka untuk Islam, dan menimpakan kepada mereka berbagai macam siksaan yang dalam beberapa kasus mencapai kematian.
Dengan demikian kita melihat bahwa keadaan perang dianggap ada antara kaum muslimin dan orang-orang ini, dan berdasarkan hal itu; maka pertempuran-pertempuran yang terjadi antara kedua pihak sesungguhnya dilakukan oleh kaum muslimin dalam membela diri dan akidah.
Dan kita simpulkan dari apa yang telah disebutkan di atas: bahwa perang dalam Islam sesungguhnya adalah pengecualian dari prinsip umum, yaitu: Perdamaian dalam Islam.
HUKUM-HUKUM DUA NEGERI
Kita akan membahas sekarang tentang negeri Islam, negeri perang, dan pengaruh pembagian tersebut.
Mengenai pembagian negeri, kita katakan: Musuh-musuh Islam di Jazirah Arab dan negeri-negeri tetangga ingin memberantas Islam dan kaum muslimin secara tuntas, serta menghancurkan dakwah Islam di tempat kelahirannya sebelum tersebar luas dan memperoleh kesuksesan, kemenangan, dan kekuasaan. Hal ini menyebabkan Mekah dengan kepemimpinan Quraisy dan negeri-negeri musuh lainnya menjadi negeri perang, sedangkan Madinah dan sekitarnya menjadi negeri Islam. Sekelompok kaum muslimin membuat perdamaian dan hidup berdampingan dengan mereka, sehingga negeri mereka menjadi negeri perjanjian.
Dalam pengertian ini, Ibnu Qayyim berkata: Orang-orang kafir terbagi menjadi ahli harbi (penduduk negeri perang) dan ahli ahdi (penduduk negeri perjanjian). Ahli ahdi terbagi menjadi tiga golongan: ahli dzimmah, ahli hudnah, dan ahli amaan. Para fuqaha membuat bab tersendiri untuk setiap golongan, mereka mengatakan: bab hudnah, bab amaan, dan bab akad dzimmah. Kata dzimmah dan ahdi mencakup semua golongan ini pada dasarnya, demikian pula kata shulhu (perdamaian), karena dzimmah termasuk dalam kategori ahdi dan akad. Namun dalam istilah banyak fuqaha, ahli dzimmah adalah mereka yang membayar jizyah (upeti), dan mereka memiliki dzimmah yang kekal. Mereka telah membuat perjanjian dengan kaum muslimin bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya berlaku atas mereka, berbeda dengan ahli hudnah yang membuat perdamaian dengan kaum muslimin untuk tetap tinggal di negeri mereka sendiri, baik perdamaian tersebut dengan memberikan harta maupun tidak, tidak diberlakukan hukum-hukum Islam atas mereka seperti yang diberlakukan kepada ahli dzimmah, tetapi mereka wajib menahan diri dari memerangi kaum muslimin. Mereka ini disebut ahli ahdi, ahli shulhu, dan ahli hudnah.
Kita dapat menyimpulkan dari perkataan Ibnu Qayyim secara umum bahwa negeri dapat dibagi menjadi tiga:
- Negeri Islam
- Negeri Perang
- Negeri Perjanjian
Kita akan menyoroti masing-masing sebagai berikut:
NEGERI ISLAM
Sebagian ulama mendefinisikan negeri Islam sebagai negara yang diperintah oleh kekuasaan kaum muslimin, dan kekuatan serta perlindungan di dalamnya ada di tangan kaum muslimin. Negeri ini wajib bagi kaum muslimin untuk membela dan berjihad di dalamnya sebagai fardhu kifayah, selama musuh belum memasuki negeri atau imam tidak memobilisasi rakyat untuk berperang. Jika musuh memasuki negeri atau imam memobilisasi rakyat, maka jihad menjadi fardhu ain. Penduduk negeri Islam adalah kaum muslimin dan ahli dzimmah, yaitu mereka yang rela tinggal di negeri Islam dan berkomitmen pada hukum-hukum Islam sambil tetap menjalankan agama mereka dengan imbalan membayar jizyah. Seluruh negeri Islam adalah seperti satu negeri, meskipun negara-negaranya beragam dan penguasa-penguasanya berbeda, karena hukum Islam di dalamnya adalah hukum yang berlaku.
NEGERI PERANG
Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan negeri perang menjadi dua mazhab:
Pertama – berpendapat: bahwa negeri perang adalah negeri yang tidak memiliki kekuasaan dan perlindungan bagi penguasa muslim, dan tidak ada perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin yang mengikat dan membatasi kaum muslimin. Inilah yang diungkapkan Ibnu Qayyim dalam definisinya tentang negeri Islam dengan perkataannya: negeri Islam adalah negeri yang didiami oleh kaum muslimin dan hukum-hukum Islam berlaku atas mereka di dalamnya, dan negeri yang tidak diberlakukan hukum-hukum Islam tidak dianggap sebagai negeri Islam.
Bagi penganut pendapat ini, yang menjadi patokan adalah: perlindungan dan kekuasaan. Selama negeri itu berada di luar perlindungan kaum muslimin tanpa perang, maka itu adalah negeri perang yang pada umumnya diperkirakan akan menyerang. Penduduk negeri perang disebut: harbiyin (orang-orang perang). Harbi adalah orang yang antara kita dan negerinya terjadi perang dan permusuhan, dan tidak ada perjanjian damai atau persahabatan antara kita dengan kaumnya.
Pendapat kedua – penganutnya berpendapat: bahwa kekuasaan dan perlindungan berada di tangan non-muslim saja tidak cukup untuk menyebut suatu negeri sebagai negeri perang, tetapi harus terpenuhi tiga syarat agar negeri menjadi negeri perang, yaitu:
- Perlindungan dan kekuasaan tidak berada di tangan penguasa muslim, sehingga ia tidak dapat melaksanakan hukum-hukum syariat – artinya: hukum-hukum kekafiran tampak dan diterapkan di dalamnya
- Wilayah itu berbatasan langsung dengan negeri-negeri Islam, sehingga diperkirakan akan menyerang negeri Islam
- Tidak ada muslim atau dzimmi yang tinggal menetap di negeri tersebut dengan jaminan keamanan Islam yang pertama, yang memungkinkan rakyat muslim untuk tinggal di dalamnya, yaitu jaminan syariat karena Islam bagi kaum muslimin, dan karena akad dzimmah bagi ahli dzimmah
Kita simpulkan dari penjelasan di atas: bahwa para fuqaha dalam memahami pengertian negeri Islam dan negeri perang memiliki dua pendapat:
Pertama: melihat kepada hukum dan sistem. Jika hukum dan sistemnya Islami, maka negeri itu Islami. Jika hukum atau sistemnya tidak Islami, maka negeri itu bukan Islami, meskipun disebut sebagai Islami.
Kedua: melihat kepada keamanan muslim. Jika muslim aman di negeri tempat ia tinggal dengan keamanan Islam, maka negeri itu adalah negeri Islam.
JENIS KETIGA: NEGERI PERJANJIAN
Kita telah membahas negeri Islam dan negeri kekafiran, sekarang kita membahas negeri perjanjian.
Negeri perjanjian adalah negeri yang tidak ditaklukkan oleh kaum muslimin secara paksa, dan penduduknya membuat perdamaian antara mereka dengan kaum muslimin atas sesuatu yang mereka bayarkan dari tanah mereka, yaitu kharaj, tanpa diambil darinya jizyah, karena mereka berada di luar negeri Islam. Negeri ini tidak dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang, dan mereka tidak membuat perdamaian permanen – berdasarkan akad dzimmah sehingga syariat diterapkan di dalamnya – tetapi penduduknya masuk dalam akad dan perjanjian kaum muslimin dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan dan aturan-aturan yang ditetapkan.
Dengan kata lain: ahli ahdi adalah kaum yang membuat perdamaian dengan kaum muslimin untuk tetap berada di negeri mereka, baik perdamaian itu dengan harta maupun tanpa harta, tidak diberlakukan hukum-hukum Islam kepada mereka seperti yang diberlakukan kepada ahli dzimmah, tetapi mereka wajib menahan diri dari memerangi kaum muslimin. Istilah negeri perjanjian pada dasarnya cocok untuk hubungan internasional saat ini – antara kaum muslimin dan lainnya – untuk mencapai jaminan semua kepentingan ekonomi, penyelesaian masalah-masalah politik dan semacamnya, selama negara-negara Islam telah menerima komitmen terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka itu seperti perjanjian kolektif antara non-muslim dengan kaum muslimin.
Keterikatan negara-negara modern dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan negeri-negeri non-muslim saat ini sebagai negeri perjanjian. Setelah kita membahas negeri-negeri yang meliputi negeri Islam, negeri kekafiran, kemudian negeri perjanjian, sekarang kita membahas pengaruh pembagian negeri menjadi negeri Islam dan negeri perang.
Kita katakan: Para fuqaha berbeda pendapat tentang berlakunya hukum-hukum syariat terhadap warga negara Islam jika mereka berada di luar negeri Islam. Di antara hukum-hukum terpenting tersebut adalah: hukum-hukum pidana, qishash di negeri perang, riba, akad-akad yang fasad di negeri perang, dan kewajiban musta’man (orang yang mendapat jaminan keamanan) terhadap hukum-hukum Islam. Kita akan menyoroti setiap masalah sebagai berikut:
Mengenai Hukum-Hukum Pidana
Kita katakan: Jika muslim atau dzimmi melakukan perbuatan yang mengakibatkan hukuman had di negeri perang atau negeri perjanjian, apakah hukum-hukum Islam berlaku terhadapnya? Para fuqaha berbeda pendapat dalam menjawab hal tersebut menjadi dua pendapat:
Pertama: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum-hukum pidana Islam tidak berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Islam di negeri perang. Alasannya adalah bahwa imam tidak mampu menegakkan hukuman had di negeri perang karena tidak memiliki kewenangan. Kewajiban had disyaratkan dengan kemampuan, dan imam tidak memiliki kemampuan terhadapnya ketika ia berada di negeri perang, maka tidak ada kewajiban, kalau tidak demikian akan kosong dari manfaat, karena maksud dari penegakan had adalah pelaksanaan hukuman agar tercapai efek jera, sedangkan pada kenyataannya tidak ada kemampuan untuk itu. Jika seorang muslim melakukan sesuatu dari hal tersebut, kemudian kembali ke negeri Islam, tidak ditegakkan had atasnya karena perbuatan tersebut sejak awal tidak mengakibatkan kewajiban had.
Makna penjelasan di atas: bahwa peradilan dengan hukuman mengharuskan adanya kewenangan atas tempat kejahatan ketika kejahatan dilakukan, dan negara Islam tidak memiliki kewenangan atas tempat terjadinya kejahatan. Konsekuensinya adalah jika tempat kejahatan masuk dalam kewenangan negara Islam setelah kejahatan dilakukan, maka hukum syariat tidak diterapkan terhadap kejahatan tersebut, karena kewenangan tidak ada ketika kejahatan terjadi.
Pendapat kedua: Jumhur fuqaha dari Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa syariat diterapkan terhadap setiap kejahatan yang dilakukan oleh muslim atau dzimmi di negeri perang. Alasannya adalah bahwa muslim terikat dengan hukum-hukum Islam di mana pun ia berada, dan di antara hukum-hukum Islam adalah: kewajiban had bagi siapa yang melakukan sebabnya.
Kami berpendapat bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur, karena muslim adalah teladan dalam kebajikan di mana pun ia berada, maka tidak layak ia berubah menjadi perusak di muka bumi. Oleh karena itu, hukuman diterapkan terhadap kejahatan apa pun yang ia lakukan, tanpa memandang tempat terjadinya kejahatan, dan ditegakkan had atasnya setelah kembali ke negeri Islam jika dikhawatirkan orang yang ditegakkan had atasnya akan bergabung dengan ahli harbi.
Mengenai Qishash di Negeri Perang
Kita katakan: Jika muslim atau dzimmi melakukan kejahatan pembunuhan di negeri perang, apakah ia diqishash? Para fuqaha berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan ini menjadi dua pendapat:
Pertama: bahwa ia tidak dikenakan qishash meskipun pembunuhan itu disengaja, karena pelaksanaan qishash tidak mungkin kecuali dengan kekuasaan, sedangkan kekuasaan tidak ada di negeri perang. Juga, keberadaannya di negeri perang menimbulkan keraguan dalam kewajiban qishash, dan qishash tidak wajib dengan adanya keraguan. Pembunuh menanggung diyat – baik pembunuhan itu disengaja maupun tidak sengaja – dan diyat diambil dari hartanya, bukan dari aqilah (kerabat yang menanggung diyat). Mereka mengatakan diyat wajib agar darah yang terlindungi tidak sia-sia, dan karena hukuman badan tidak bisa dilaksanakan, maka diganti dengan hukuman harta, dan hal ini tidak menghalangi ta’zir dalam semua keadaan.
Pendapat kedua: pendapat jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa hukum qishash di negeri perang berlaku terhadap muslim dan dzimmi sebagaimana di negeri Islam sepenuhnya.
Mengenai Riba dan Akad-Akad Fasad di Negeri Perang
Kita katakan: Apakah hukum-hukum riba berlaku di negeri perang sebagaimana berlaku di negeri Islam? Para fuqaha berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan ini menjadi dua pendapat:
Pertama: Jumhur fuqaha dan Imam Abu Yusuf dari Hanafiyah berpendapat bahwa hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan riba berlaku di negeri perang sebagaimana berlaku di negeri Islam. Alasannya: bahwa keharaman riba tetap berlaku bagi pihak-pihak yang berakad. Adapun bagi kaum muslimin, jelas, dan adapun bagi harbi, karena orang-orang kafir terkena perintah larangan-larangan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan karena mereka memakan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya.” (Surah An-Nisa: sebagian dari ayat 161). Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan dengan dzimmi dan harbi yang memasuki negeri kita dengan jaminan keamanan.
Pendapat kedua: Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa jika seorang muslim atau dzimmi memasuki negeri perang – dengan jaminan keamanan – lalu berakad dengan harbi dengan akad riba atau akad-akad fasad lainnya menurut hukum Islam, maka itu diperbolehkan. Alasan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa mengambil riba dalam pengertian menghancurkan harta, dan menghancurkan harta harbi diperbolehkan karena tidak ada perlindungan bagi harta harbi. Ini alasan kebolehannya dengan harbi.
Adapun dengan muslim – dari penduduk negeri perang yang tidak hijrah kepada kita – bahwa mengambil riba dalam pengertian menghancurkan harta, dan harta orang yang masuk Islam di negeri perang tetapi tidak hijrah kepada kita tidak dijamin atas penghancuran. Buktinya bahwa dirinya tidak dijamin dengan qishash maupun diyat, dan kehormatan harta mengikuti kehormatan diri. Tidak diragukan dalam hal ini bahwa pendapat jumhur adalah yang rajih dalam masalah ini, dan bahwa muslim dituntut oleh hukum-hukum Islam di tempat mana pun ia berada.
Adapun yang berkaitan dengan kewajiban orang yang memperoleh jaminan keamanan (mustamin) untuk mematuhi hukum-hukum Islam, maka kami katakan: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang tinggal sementara di negeri Islam tidak diterapkan padanya hukum-hukum syariat jika ia melakukan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah – yakni: yang berkaitan dengan hak masyarakat – tetapi ia dihukum menurut syariat jika ia melakukan kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak individu.
Adapun tidak ditegakkan padanya hukuman – berkaitan dengan hak-hak Allah – karena ia tidak memasuki negeri Islam untuk menetap, melainkan untuk suatu keperluan yang ingin ia selesaikan, dan tidak ada dalam jaminan keamanan itu yang mewajibkannya dengan semua hukum syariat dalam hal kejahatan dan muamalat. Ia hanya wajib mengikuti apa yang sesuai dengan tujuannya memasuki negeri Islam dan apa yang berkaitan dengan pencapaian maksudnya, yaitu hak-hak hamba. Maka ia harus berkomitmen pada keadilan dan menahan diri dari menyakiti, selama kami telah berkomitmen mengamankannya dengan berlaku adil kepadanya dan menahan diri dari menyakitinya.
Qishas dan hukuman hudud untuk qadhaf (tuduhan zina) termasuk hak-hak hamba, oleh karena itu ia dikenakan kedua hukuman tersebut sebagaimana ia dikenakan hukuman kejahatan lain yang berkaitan dengan hak-hak individu seperti perampasan dan penggelapan. Adapun selain itu dari kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak individu, ia tidak wajib dikenakan hukumannya, seperti: zina. Maka Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman-hukuman hudud dasarnya adalah kekuasaan (wilayah), dan penguasa muslim tidak memiliki kekuasaan penuh atas orang yang diberi jaminan keamanan karena ia tinggal untuk waktu yang terbatas.
Abu Yusuf dari mazhab Hanafi dan jumhur (mayoritas) ulama fiqih berpendapat: bahwa syariat berlaku bagi semua orang yang tinggal di negeri Islam, baik tinggal mereka bersifat permanen seperti muslim dan ahli dzimmah, atau tinggal mereka bersifat sementara seperti mustamin. Alasannya: bahwa mustamin telah berkomitmen pada hukum-hukum kami selama ia tinggal di negeri kami dalam hal muamalat dan kebijakan, dan karena itu ditegakkan padanya semua hukuman hudud kecuali hukuman minum khamr jika ia melakukan perbuatan yang mewajibkannya.
Kami menyimpulkan dari uraian di atas bahwa mustamin diterapkan padanya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat keuangan berdasarkan kesepakatan. Ia dilarang bertransaksi dengan riba misalnya, karena ia bertransaksi dengan kaum muslimin, maka tidak diterapkan padanya kecuali hukum kaum muslimin. Berkaitan dengan hukuman-hukuman, telah jelas bahwa jika ia melakukan perbuatan yang mengandung pelanggaran terhadap hak seorang muslim, ahli dzimmah, atau mustamin lainnya, maka dijatuhkan padanya hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat, karena wajib menegakkan keadilan dan membela orang yang terzalimi dari orang yang zalim selama ia tinggal di negeri Islam.
Adapun jika pelanggaran tersebut terhadap salah satu hak Allah Taala seperti melakukan zina, maka jumhur ulama fiqih memutuskan bahwa dijatuhkan padanya hukuman yang dijatuhkan kepada muslim, karena kejahatan ini dan sejenisnya merusak masyarakat Islam, dan ia tidak datang ke negeri kami untuk menyebarkan kerusakan.
Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama fiqih dalam hal ini, di mana beliau berkata: tidak ditegakkan hukuman hudud pada mustamin berkaitan dengan kejahatan-kejahatan ini.
Dengan ini kami telah selesai membahas tentang negeri Islam, negeri perang, negeri perjanjian, dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pembagian negeri tersebut yang telah kami jelaskan sebelumnya.
Pengantar tentang Perjanjian-Perjanjian dalam Islam
Kini kami beralih ke topik lain dari topik-topik yang ada dalam kurikulum tentang hubungan atau politik luar negeri kaum muslimin dengan pihak lain, yaitu: perjanjian-perjanjian. Kami katakan: Hubungan internasional dalam Islam mengambil kaidah-kaidahnya dari prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam keadaan damai dan perang.
Keadilan, kebebasan, martabat kemanusiaan, menepati janji, dan perlakuan setimpal ketika ada kebutuhan dan keperluan, tanpa tercemar dengan kejahatan rendah dan hina, dan dari prinsip-prinsip tersebut juga keutamaan, kasih sayang, takwa, dan kerja sama kemanusiaan – sebagaimana telah kami jelaskan secara rinci – karena manusia adalah saudara bagi manusia; suka atau tidak suka, dan hal-hal semacam itu yang telah tercakup dan diumumkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Kaidah-kaidahnya juga diambil dari adat kebiasaan yang benar dan sesuai syariat, yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama ilahi yang benar, dan dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara kaum muslimin dengan pihak lain, seperti perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para khalifah rasyidin, raja-raja yang adil, dan para penguasa yang bertakwa dalam menetapkan jaminan keamanan, membuat perjanjian dzimmah, perdamaian. Kami akan membahas dalam hal ini konsep-konsep dasar tentang perjanjian, kepentingannya, keabsahannya, kemudian kaidah menepati janji, lalu kami jelaskan kerangka umum di mana perjanjian-perjanjian dibuat.
Pertama: Menentukan Konsep Perjanjian (muahadah), Piagam (mitsaq), Janji (ahd), dan Akad (aqd)
Kami katakan: Muahadah, mitsaq, ahd, dan aqd dalam asal bahasa Arab memiliki makna yang sama dan bersinonim, yaitu setiap ikatan antara dua pihak atas suatu urusan tertentu. Adapun menurut para ulama fiqih kami, maka muahadah adalah: ikatan janji antara dua kelompok atas syarat-syarat yang mereka tetapkan. Ahd dalam syariat Islam memiliki makna yang lebih luas dari kata ahd dalam hukum internasional positif, karena ia pada dasarnya adalah kesepakatan dua kehendak – tanpa memandang bentuk atau prosedurnya. Ahd dalam fiqih kami adalah: apa yang disepakati oleh dua orang atau dua kelompok dari manusia untuk dipatuhi di antara mereka demi kepentingan bersama mereka. Jika mereka memperkuat dan mempertegas dengan hal yang menuntut perhatian lebih dalam menjaganya dan menepatinya, maka disebut: mitsaq. Jika mereka memperkuatnya dengan sumpah khususnya, maka disebut: sumpah.
Kebiasaan yang berlaku saat ini menunjukkan kepada kami untuk membedakan ahd dari aqd dengan memberikan sifat keagungan, ketinggian, dan pengagungan pada ahd, dan mengkhususkannya dengan akad yang diperkuat dengan maksud menepatinya secara pasti, baik penguatan itu dilakukan dengan tulisan, sumpah, atau cara penguatan lainnya. Maka setiap kesepakatan adalah aqd, tetapi tidak setiap aqd adalah ahd. Akad nikah dalam Al-Quran disebut: “perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidha)” (Surah Al-Ahzab: ayat 7).
Demikian pula kebiasaan internasional yang ada menuntut kami untuk membedakan ahd dari muahadah. Ahd memiliki makna yang lebih luas dari muahadah. Setiap muahadah adalah ahd, tetapi tidak setiap ahd adalah muahadah. Ahd – sebagaimana telah kami jelaskan – adalah setiap kesepakatan antara dua pihak yang mereka patuhi demi kepentingan bersama, atau ia adalah akad yang diperkuat dengan tulisan, sumpah, atau jaminan lain yang memberikan kepercayaan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakannya dan menepati syarat-syaratnya. Ia mencakup apa yang terjadi antara dua orang seperti janji aman yang diberikan oleh muslim kepada orang kafir harbi yang meminta keamanan, sebagaimana juga mencakup apa yang terjadi antara kelompok dan individu seperti perlindungan suku atau kepala sukunya yang mewakilinya bagi orang yang meminta pertolongan dan bantuan serta dukungannya. Ia juga bisa terjadi antara dua kelompok atau dua negara seperti perjanjian perdamaian sementara – yaitu: gencatan senjata – dan perdamaian permanen atau abadi – yaitu: akad dzimmah.
Adapun muahadah, ia kini terbatas antara dua negara, bukan antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Objeknya terbatas pada mengatur hubungan internasional tertentu yang bersifat hukum – artinya: ia memiliki makna tertentu yang khusus dan sempit dari segi kedua belah pihak dan objeknya. Dengan demikian dapat didefinisikan muahadah – dalam istilah fiqih Islam saat ini – bahwa ia adalah: kesepakatan yang dikeluarkan antara negeri Islam atau negara Islam dengan negara lain atau kelompok tertentu yang tidak muslim dalam mengatur hubungan hukum yang bersifat internasional di antara mereka.
Adapun masalah-masalah parsial yang bersifat sampingan dengan kepentingan terbatas, tidak diatur oleh muahadah agar ia memiliki sifat unsur internasional yang penting. Contohnya: perintah pemimpin penguasa untuk mengakhiri perang dengan kota tertentu atau bangsa tetangga, seperti perjanjian pertukaran tawanan perang, dan semacamnya.
Adapun perjanjian-perjanjian internasional dalam perlakuan terhadap tawanan perang, kaidah-kaidah perang, keadaan-keadaan yang membolehkan pertempuran, atau penggunaan kekuatan, maka ia memiliki sifat muahadah dengan makna yang umum saat ini di antara negara-negara.
Pentingnya Perjanjian-Perjanjian dan Piagam-Piagam, serta Keabsahannya
Perjanjian-perjanjian dan piagam-piagam memberikan pada tindakan-tindakan bangsa, masyarakat, negara, dan individu unsur kepercayaan dan ketenangan. Ia bekerja untuk mengurangi ketegangan di dunia dan menjamin sampai batas yang jauh pelaksanaan syarat-syarat dan pasal-pasal serta terwujudnya kepentingan pada waktu tertentu yang membawa kebaikan, ketenangan, dan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Dengan perjanjian, perdamaian menggantikan perang, keamanan menggantikan kegelisahan dan ketakutan, cinta dan kejernihan mengganti kebencian. Manusia menikmati nikmat kebebasan yang tidak ada pembatasannya; mereka dapat fokus pada urusan kehidupan, menghidupkan pertanian, mengembangkan perdagangan, membuka pasar bagi ekspor dan impor, pertukaran produk, kemajuan dan perkembangan industri, serta mengarahkannya untuk kebaikan, kemaslahatan, dan manfaat manusia. Maka ia menjadi sarana saling pengertian dan kasih sayang, kemajuan dan peradaban, kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu manusia mengagungkan perjanjian-perjanjian dan menginginkannya, mensyariatkannya, dan lebih memilih menyelesaikan perselisihan kolektif melaluinya, serta mewujudkan tujuan dan cita-cita kemanusiaan yang mulia melaluinya. Bahkan penyebaran dakwah Islam di seluruh penjuru dunia tidak terlaksana kecuali dalam naungannya dan di tengah keamanan dan perdamaian yang terwujud dengannya.
Betapa banyaknya nash-nash syariat yang menunjukkan pada prinsip keabsahan perjanjian-perjanjian dengan musuh dalam damai dan perang dalam kerangka syarat-syarat yang disepakati dengan saling ridha dan pilihan. Di antara nash-nash tersebut firman Allah Taala: “Pernyataan pembebasan kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)” (Surah At-Taubah: ayat 1), dan firman-Nya: “kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Surah At-Taubah: ayat 7), dan firman-Nya: “kecuali orang-orang yang bersambung dengan suatu kaum yang antara kamu dengan kaum itu ada perjanjian” (Surah An-Nisa: dari ayat 90), dan firman-Nya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah” (Surah Al-Anfal: dari ayat 61), dan firman-Nya: “Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka wajib atasmu memberi pertolongan kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian” (Surah Al-Anfal: dari ayat 72), dan firman-Nya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah perjanjiannya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Surah At-Taubah: dari ayat 4).
Semua itu menunjukkan kesucian perjanjian-perjanjian dan keharusan menepatinya. Sunnah Nabi dalam perkataan dan perbuatan datang menegaskan makna-makna ini. Dalam perdamaian sementara – gencatan senjata atau muwaadaah – Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari seorang laki-laki dari Juhaynah: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendatanginya, beliau berkata: ‘Mungkin kalian akan memerangi suatu kaum dan kalian akan menang atas mereka, lalu mereka melindungi diri dengan harta mereka tanpa diri dan anak-anak mereka, maka mereka berdamai dengan kalian dengan suatu perdamaian, maka janganlah kalian mengambil dari mereka melebihi itu, karena sesungguhnya itu tidak baik bagi kalian.'” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda menjelang Perjanjian Hudaibiyah: “Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, mereka tidak akan memintaku suatu rencana yang di dalamnya mereka mengagungkan kehormatan Allah kecuali aku akan memberikannya kepada mereka.” Dalam perdamaian abadi atau mutlak – yang kami maksudkan dengannya akad dzimmah – beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah, barangsiapa menzalimi orang yang memiliki perjanjian, mengurangi haknya, membebaninya melebihi kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan menjadi lawannya pada hari Kiamat.” Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menyakiti ahli dzimmah, maka aku adalah lawannya, dan barangsiapa aku menjadi lawannya, aku akan melawannya pada hari Kiamat.”
Dalam akad jaminan keamanan individual dari seorang muslim, atau kolektif dari kelompok, atau dari pemimpin atau imam penguasa, beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Siapa pun laki-laki dari kalian yang paling jauh atau paling dekat, dari orang merdeka atau budak kalian, yang memberikan kepada seseorang dari mereka jaminan keamanan atau memberi isyarat kepadanya dengan tangannya lalu ia datang dengan isyaratnya, maka baginya jaminan keamanan sampai ia mendengar kalam Allah. Jika ia menerima, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama, dan jika ia menolak, maka kembalikanlah ia ke tempat amannya, dan mintalah pertolongan kepada Allah.”
Nash-nash ini pada masa Nabi menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian adalah sah dalam Islam, bahkan ia dalam metodenya adalah sarana efektif yang wajib untuk menjamin perdamaian, mendukung keamanan, menyediakan hak-hak asasi manusia, dan menjamin kebebasan-kebebasan yang Islam datang untuk menjamin dan menghormatinya.
Menepati Janji
Perjanjian-perjanjian dalam Islam bukanlah sekadar secarik kertas – sebagaimana halnya di negara-negara non-Islam kontemporer – dan bukan sarana untuk menipu musuh, bukan sarana untuk melaksanakan tujuan-tujuan khusus tertentu, bukan slogan untuk memaksakan kekuasaan yang kuat atas yang lemah atau yang kalah, dan bukan demi menetapkan perdamaian yang zalim yang tidak berdiri di atas kebenaran dan keadilan; sehingga ketika yang lemah menjadi kuat, ia mengabaikannya dan berperang untuk melepaskan diri dari ikatannya dan melepaskan diri dari belenggu yang kuat. Ia juga bukanlah gambaran kekuatan orang-orang kuat, dan bukan prosedur untuk mengatur perdamaian dan keadilan.
Akan tetapi perjanjian-perjanjian dalam Islam adalah terjaga dari segala pengkhianatan, penipuan, pemaksaan, atau menjamin kepentingan materi yang murahan, atau membuka jalur atau pasar untuk memasarkan barang dan produk serta surplus pertanian atau bahan-bahan yang dimiliki.
Maka Al-Qur’an yang mulia tidak memandang perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan untuk dibuat dengan pandangan yang hanya bersifat kepentingan semata, tetapi memerintahkan untuk memenuhi perjanjian secara mutlak tanpa adanya batasan, baik dalam keadaan lemah maupun kuat; hal itu untuk menegakkan perdamaian yang kokoh di atas fondasi dan prinsip yang paling kuat. Kaum muslimin berkomitmen untuk memenuhi perjanjian secara syariat dengan adil; untuk melindungi tujuan-tujuan luhur yang menjadi sasaran dakwah Islam, atau untuk mencapai perdamaian yang kokoh yang tidak mengandung agresi terencana, dan tidak diperbolehkan membatalkannya selama perjanjian masih berlaku, sebagaimana tidak diperbolehkan melanggar syarat-syarat atau pasal-pasalnya selama musuh tidak membatalkannya; sebagai pelaksanaan perintah Allah yang mutlak dalam berbagai ayat Al-Qur’an, seperti firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu” (Surat Al-Maidah ayat 1), dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan penuhilah janji Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (perjanjian) itu setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas (perjanjian)mu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Surat An-Nahl ayat 91), dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (Surat Al-Isra ayat 34), dan firman-Nya: “Maka sempurnakanlah perjanjian mereka sampai batas waktunya” (Surat At-Taubah ayat 4), “Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka” (Surat At-Taubah ayat 7).
Memenuhi janji adalah sifat yang melekat pada keimanan, dan merupakan prinsip dasar yang diagungkan yang tidak boleh dilanggar. Melanggar janji adalah perilaku orang-orang munafik, bukan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam menggambarkan orang-orang mukmin: “(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian” (Surat Ar-Ra’d ayat 20), dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan orang-orang yang memenuhi janjinya apabila berjanji” (Surat Al-Baqarah ayat 177).
Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menolong saudara-saudara mereka sesama muslim di negara non-Islam yang telah mengadakan perjanjian dengan kita dari kalangan kafir. Wasiat-wasiat Nabi tentang menghormati perjanjian sangat banyak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”. Dan beliau bersabda: “Setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari kiamat yang ditegakkan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada pemimpin umum”. Dan beliau menjadikan pengkhianatan, penipuan, dan pelanggaran janji sebagai sifat kemunafikan dan karakteristik orang-orang munafik. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Empat perkara, barangsiapa memilikinya maka dia adalah munafik tulen: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila berjanji ia mengkhianati, dan apabila berselisih ia berlaku kejam”.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan penghormatan terhadap pakta-pakta persekutuan Arab yang bersifat kemanusiaan yang dibuat pada masa jahiliah. Beliau bersabda tentang Hilful Fudhul yang bersifat kemanusiaan yang beliau hadiri ketika masih muda untuk menolong orang yang teraniaya dan melindungi pemimpin Mekah: “Sungguh aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud’an suatu persekutuan yang aku tidak ingin menukarnya dengan unta merah, dan seandainya aku diajak untuk ikut serta dalam Islam, pasti aku akan memenuhinya”. Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dengan menegaskan pentingnya memenuhi pakta-pakta jahiliah yang baik: “Penuhilah pakta-pakta jahiliah karena Islam hanya menambah kekuatannya, dan jangan membuat pakta baru dalam Islam”. Artinya Islam mengakui perjanjian untuk menolong kebenaran dan kebaikan dari manapun sumbernya, dan melarang persekutuan untuk fitnah, pertempuran kesukuan, dan agresi barbar.
Jenis-Jenis Perjanjian atau Kontrak:
Perjanjian berdasarkan jangka waktunya ada yang bersifat sementara seperti perjanjian aman dan gencatan senjata, atau bersifat permanen seperti perjanjian dzimmah.
Perjanjian berdasarkan tujuannya ada yang bersifat keagamaan, atau politik internal, atau eksternal, atau perdagangan. Berdasarkan tujuan ini mencakup hal-hal berikut:
Pertama: Perjanjian keimanan, atau bai’at atas Islam atau jihad.
Kedua: Perjanjian politik.
Ketiga: Perjanjian perdagangan.
Saya menitipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
Kuliah Keempat Puluh Empat: Jenis-Jenis Perjanjian dan Hukum-Hukumnya dalam Fikih Islam
Jenis-Jenis Perjanjian dalam Syariat Islam
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan shalawat serta salam tercurah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu pemimpin kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perjanjian, pengaturannya, dan dampaknya dalam fikih Islam. Dapat dikatakan bahwa perjanjian dapat dibagi menjadi dua bagian: perjanjian politik dan perjanjian ekonomi. Perjanjian ekonomi dalam konsep Islam adalah perjanjian yang dibuat dengan non-Muslim dengan tujuan menyebarkan Islam dan menyampaikan dakwah Allah, atau untuk mengakhiri perang, atau demi perdamaian dan keamanan dengan tujuan memasuki wilayah Islam untuk berkunjung, atau mendengar kalam Allah, atau bernegosiasi, atau berdagang, dan hal-hal serupa dari kepentingan orang asing.
Jenis-jenis perjanjian politik ada empat, yaitu:
- Perjanjian untuk tujuan hidup berdampingan secara damai antara kaum muslimin dan lainnya dalam satu negara.
- Perjanjian aman.
- Perjanjian perdamaian eksternal, atau yang kita sebut dengan perjanjian damai atau gencatan senjata.
- Perjanjian damai permanen, atau yang kita sebut dengan perjanjian dzimmah.
Pembahasan mengenai jenis-jenis ini adalah sebagai berikut:
Jenis Pertama: Perjanjian Hidup Berdampingan Secara Damai
Lebih penting dari perjanjian dzimmah, perjanjian ini dibuat antara kaum muslimin dan lainnya atas dasar lain selain perjanjian dzimmah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internal di wilayah Islam tanpa kewajiban membayar kompensasi finansial kepada kaum muslimin.
Isi perjanjian ini adalah: mengamankan non-Muslim atas jiwa dan harta mereka, dan membuat persekutuan, saling menolong, dan kerja sama timbal balik antara kaum muslimin dan lainnya di wilayah Islam tanpa batasan waktu. Contohnya: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah hijrah, tindakan politik pertama yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian dengan suku-suku yang tinggal antara Madinah dan pantai Laut Merah, dan suku-suku lainnya. Begitu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menetap di Madinah, beliau segera membuat perjanjian damai permanen lainnya dengan kelompok-kelompok Madinah, mempersatukan Aus dan Khazraj atas dasar hubungan baik bertetangga, juga dengan orang-orang Yahudi; beliau mengakui mereka pada agama dan harta mereka. Perjanjian ini merupakan perjanjian politik pertama dengan makna yang sebenarnya antara kaum muslimin dan suku-suku Madinah, dan dengan orang-orang Yahudi dengan kelompok-kelompok mereka yang berbeda. Dalam perjanjian ini diharamkan agresi antara pihak-pihak yang berperjanjian, dan mereka berkomitmen untuk bekerja sama dan bersatu untuk menangkal agresi eksternal, dan mereka membuat semacam aliansi pertahanan bersama antara dua bangsa, dan mewajibkan diri mereka untuk berkontribusi dalam pembiayaan bersama untuk kepentingan pertahanan, dan hal-hal serupa yang mengatur hubungan kaum muslimin satu sama lain, dan hubungan mereka dengan yang lain sebagai bangsa atau masyarakat yang bertetangga. Hal itu merupakan contoh baik dari prinsip-prinsip luar biasa dalam mengatur keadaan perdamaian dan keamanan internasional.
Kita perhatikan dalam perjanjian ini adanya sikap waspada terhadap orang-orang Yahudi yang licik, penetapan fondasi perdamaian yang wajib, pengakuan terhadap kebebasan beragama, deklarasi prinsip persatuan kaum muslimin, solidaritas mereka, dan kesetaraan mereka dalam darah, harta, dan hak-hak, serta independensi masing-masing kaum muslimin dan Yahudi dengan tetap menjaga hubungan baik bertetangga.
Perjanjian ini menetapkan prinsip menolong orang Yahudi dalam keadaan mereka diserang, bahwa agresi terhadap kelompok muslim adalah agresi terhadap seluruh umat Islam, dan bahwa tidak boleh menolong penjahat yaitu pelaku kejahatan, dan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan dengan berhukum kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan bahwa masing-masing Yahudi dan kaum muslimin adalah umat yang independen, mengikat mereka aliansi militer untuk menangkal agresi pihak lain, dan bahwa ada kebebasan beragama bagi masing-masing kaum muslimin dan Yahudi, dan bahwa setiap perselisihan diselesaikan dengan cara-cara damai, melalui saling menasihati dan bermusyawarah bukan dengan perang. Perjanjian tersebut menyatakan secara tegas prinsip menolong yang teraniaya dan menolong tetangga, bahwa pertolongan dalam perang harus sah, dan bahwa Quraisy adalah musuh kedua belah pihak yang bersekutu, dan bahwa kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhi panggilan terhadap perdamaian apapun yang menjaga keamanan dan mewujudkan ketenteraman, dan bahwa masa perjanjian berlaku terus-menerus selama orang Yahudi tidak membatalkannya, dan bahwa Madinah adalah negara terbuka dan wilayah aman, dan masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk tinggal dan berpindah.
Jenis Kedua dari Perjanjian Dasar: Perjanjian Aman
Saya telah menjelaskan bahwa perjanjian politik ada yang permanen dan ada yang sementara, dan hal itu ditentukan oleh kedua belah pihak yang berperjanjian, bukan subjeknya. Perjanjian sementara dengan waktu yang jelas, jika dibuat dengan jumlah yang tidak terbatas maka itu adalah perjanjian aman, dan jika dengan jumlah yang tidak terbatas untuk tujuan tertentu maka itu adalah gencatan senjata.
Aman adalah perjanjian yang memberikan jaminan untuk tidak membunuh dan tidak berperang dengan orang-orang harbi. Aman ini terbagi menjadi dua bagian: aman khusus dan aman umum. Aman khusus adalah yang diberikan kepada satu orang atau beberapa orang yang terbatas seperti sepuluh orang atau kurang, dan sebaiknya disebut perjanjian, bukan perjanjian internasional; karena perjanjian internasional di zaman kita adalah yang dibuat antara negara atau organisasi internasional, sebagaimana telah saya jelaskan dalam pembahasan istilah dan definisi di awal. Aman ini sah dari setiap muslim yang mukallaf dan merdeka untuk sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Jaminan kaum muslimin adalah satu, yang terendah dari mereka bisa memberikannya, maka barangsiapa yang mengkhianati seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia”. Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kaum muslimin darah mereka setara, mereka satu tangan terhadap selain mereka, dan yang terendah dari mereka dapat memberikan jaminan”.
Adapun aman umum adalah yang diberikan kepada kelompok besar yang tidak terbatas seperti penduduk suatu wilayah, dan tidak ada yang dapat membuatnya kecuali imam atau wakilnya seperti gencatan senjata dan perjanjian dzimmah, karena ini termasuk kepentingan umum yang tidak dapat diperkirakan selain oleh pemegang kekuasaan.
Sistem perlindungan mencakup semua jenis perlindungan dan perawatan yang dikenal secara modern bagi orang asing dan hartanya di negeri Islam, atau untuk mengadakan hubungan damai dan lainnya. Konsep perlindungan merupakan salah satu landasan penting untuk memperkuat perdamaian. Sebagai contoh: pemberian perlindungan kepada delegasi Kristen dalam Perang Salib -sebagai akibat dari toleransi Islam- dianggap sebagai dasar hubungan internasional. Dalil legitimasi perlindungan adalah firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Dan jika seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.” (Surat At-Taubah: sebagian dari ayat 6).
Ibnu Katsir berkata dalam tafsir ayat tersebut: Maksudnya adalah bahwa siapa pun yang datang dari negeri perang untuk menyampaikan pesan, atau berdagang, atau meminta perdamaian, atau gencatan senjata, atau alasan lainnya yang serupa, dan meminta perlindungan dari imam atau wakilnya, maka diberikan perlindungan selama dia berada di negeri Islam hingga dia kembali ke negerinya dan tempat amannya.
Kaum musyrikin biasa meminta pertemuan dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk membicarakan perdamaian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan dunia mereka.
Perlindungan Utusan dan Duta Besar dalam Islam: Islam telah menjamin berbagai jenis perlindungan, perawatan, kekebalan, dan penghormatan bagi para utusan dan duta besar, bahkan jika mereka diutus kepada kaum muslimin, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dan mewujudkan kebaikan serta perdamaian bagi dunia. Hal ini berdasarkan nash Al-Qur’an Al-Karim dalam ayat At-Taubah yang telah disebutkan sebelumnya: “Dan jika seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.” Hal ini juga dibuktikan dengan sunnah qauli (perkataan) dan fi’liyah (perbuatan). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membunuh utusan Musailamah Al-Kadzdzab dan bersabda: “Seandainya aku membunuh utusan, niscaya aku akan membunuh kalian berdua.”
Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Maka berjalanlah sunnah -artinya: berlaku sunnah- bahwa utusan tidak dibunuh.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengembalikan utusan Quraisy yang datang kepadanya, meskipun dia telah menyatakan keislamannya begitu melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau bersabda: “Sesungguhnya aku tidak mengkhianati perjanjian -maksudnya: tidak membatalkan kesepakatan- dan tidak menahan utusan. Tetapi kembalilah kepada mereka, jika yang ada di hatimu sekarang masih sama, maka kembalilah.”
Para ulama fikih sepakat tentang legitimasi perlindungan dan perlindungan terhadap utusan dan duta besar. Mereka membolehkan utusan politik untuk memasuki negeri kaum muslimin tanpa memerlukan perjanjian perlindungan, dan tidak membolehkan pengkhianatan terhadap utusan dan duta besar musuh, bahkan jika musuh membunuh sandera kaum muslimin yang berada di tangan mereka. Utusan mereka tidak boleh dibunuh, sebagaimana perkataan sebagian sahabat: Menepati janji tanpa khianat lebih baik daripada khianat dengan khianat.
Jenis ketiga dari perjanjian politik adalah: Perjanjian perdamaian luar negeri:
Atau yang disebut perjanjian damai atau gencatan senjata: Perdamaian sementara, atau gencatan senjata, atau muwada’ah adalah salah satu cara mengakhiri perang dan menetapkan perdamaian antara kaum muslimin dengan lainnya, atau antara Darul Islam dan Darul Harb. Hal ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.” (Surat Al-Anfal: sebagian dari ayat 61).
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membuat perjanjian damai yang terkenal di masa kenabian yang dapat dijadikan contoh untuk perjanjian-perjanjian damai, yaitu: Perjanjian Hudaibiyah.
Para ulama sepakat tentang legitimasi gencatan senjata. Perdamaian sementara adalah berdamai dengan ahli harb (orang yang berperang) untuk meninggalkan pertempuran untuk jangka waktu tertentu, dengan kompensasi atau tidak, baik di antara mereka ada yang diakui dengan agamanya atau tidak, tanpa mereka berada di bawah pemerintahan Islam. Atau perdamaian antara dua pemimpin dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat khusus.
Yang membuat gencatan senjata adalah imam atau wakilnya yang diberi wewenang untuk membuat perjanjian, meskipun dengan delegasi umum, seperti wali wilayah misalnya. Karena gencatan senjata memerlukan pandangan yang luas, pertimbangan terhadap kepentingan umum, dan pengaturan masalah-masalah perang serta akibat-akibatnya yang berjangka panjang atau berdampak jauh. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa selain imam.
Jika pembuatan gencatan senjata dilakukan oleh orang biasa tanpa delegasi dari imam, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap imam atau wakilnya, dan perjanjian tidak sah menurut jumhur ulama fikih.
Bagaimana Perjanjian Hudaibiyah terjadi? Dan apa sebab-sebabnya? Kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bermaksud melaksanakan umrah di Baitullah Al-Haram pada akhir tahun keenam Hijriyah. Kaum musyrikin menghalangi mereka untuk thawaf di Baitullah, dan rela membuat perjanjian damai dengan mereka dengan syarat-syarat yang merugikan kaum muslimin demi lebih mengutamakan perdamaian daripada perang. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, mereka tidak akan meminta dariku suatu usulan yang mengagungkan kehormatan Allah kecuali aku akan memberikannya kepada mereka.” Di antara syarat perdamaian adalah: Bahwa siapa yang datang dari kalian -yaitu dari kaum muslimin- kami tidak mengembalikannya kepada kalian, dan siapa yang datang kepada kalian dari kami, kalian kembalikan kepada kami. Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, apakah engkau menulis ini? Beliau menjawab: Ya, sesungguhnya siapa yang pergi dari kami kepada mereka, maka Allah menjauhkannya, dan siapa yang datang dari mereka, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya.”
Umar radhiyallahu ‘anhu menentang perdamaian dan membahas banyak syaratnya, hingga dia mengingkari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang perdamaian dengan berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Beliau menjawab: Benar. Dia berkata: Bukankah kita kaum muslimin? Beliau menjawab: Benar. Dia berkata: Bukankah mereka kaum musyrikin? Beliau menjawab: Benar. Beliau berkata: Aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya, aku tidak akan menentang perintah-Nya, dan Dia tidak akan menyia-nyiakanku.”
Kaum muslimin berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pasal perjanjian. Bahkan ketika Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang sebagai muslim kepada kaum muslimin, Suhail bin Amr meminta agar dia dikembalikan ke Makkah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya kami belum menyelesaikan perjanjian.” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengembalikannya kepada mereka. Al-Faruq Umar menentang hal itu -sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya- dia berkata: “Bukankah engkau benar-benar nabi Allah? Beliau menjawab: Benar. Umar berkata: Bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Beliau menjawab: Benar. Umar berkata: Lalu mengapa kita memberikan kehinaan dalam agama kita?!”
Nabi juga mengembalikan seorang laki-laki lain dari Quraisy yang datang sebagai muslim. Mereka mengutus dua orang untuk mengejarnya sebagai pelaksanaan perjanjian. Para ulama fikih sepakat bahwa yang membuat perjanjian dzimmah adalah wali amr: imam atau wakilnya. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar karena termasuk kemaslahatan umum yang memerlukan pertimbangan dan ijtihad.
Hal itu tidak mungkin dilakukan selain oleh imam yang dapat mempertimbangkan kemaslahatan umum kaum muslimin. Adapun perdamaian luar negeri, maka dibolehkan menurut sekelompok ulama fikih yang berpendapat bahwa asal dalam hubungan internasional antara kaum muslimin dan lainnya adalah perdamaian, bukan perang. Artinya dibolehkan membuat perjanjian damai permanen dengan non-muslim di negeri mereka, bukan di negeri kita yang mereka gasak atau mereka duduki, dengan cara yang menyediakan perdamaian, keamanan, dan hidup berdampingan secara damai, serta menjamin penyebaran dakwah Islamiyah melalui cara damai yang didasarkan pada logika, argumen, dan bukti, atau hikmah dan nasihat dengan ungkapan Al-Qur’an Al-Karim.
Demikian juga tidak ada larangan secara syar’i untuk membuat perjanjian dengan tujuan bertetangga baik, persahabatan, kerja sama, pertukaran perdagangan, atau untuk tujuan apa pun dari tujuan perjanjian internasional untuk menetapkan perdamaian, mengukuhkan pilar-pilarnya, dan pertukaran manfaat, agar setelah perjanjian tidak ada kemungkinan agresi kecuali dalam keadaan pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu kita dapati bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berdamai dengan Quraisy dan membuat Perjanjian Hudaibiyah dengan mereka, yang merupakan contoh jelas dari perjanjian perdamaian luar negeri.
Jenis keempat -dari perjanjian politik-: Perjanjian permanen, atau yang disebut: Perdamaian permanen, atau perjanjian dzimmah:
Perjanjian permanen mengakibatkan pengakhiran perang secara permanen antara kaum muslimin dan lainnya, atau antara Darul Islam dan Darul Harb. Hal ini dilakukan dengan salah satu dari dua cara: dalam negeri dan luar negeri. Adapun cara dalam negeri adalah perjanjian dzimmah, sedangkan cara luar negeri adalah perjanjian perdamaian permanen.
Perjanjian dzimmah atau akad dzimmah adalah komitmen untuk menetapkan non-muslim di negeri kita, melindungi mereka dari setiap agresi, dan membela mereka dengan imbalan pajak yang ringan yaitu jizyah, dengan syarat berkomitmen pada hukum-hukum Islam dan tunduk dari pihak mereka. Maka ahli dzimmah menjadi penduduk tetap di Darul Islam dan menjadi warga negara seperti kaum muslimin lainnya, selama mereka tidak melanggar perjanjian dan merusak kedamaian.
Contoh-contohnya dalam perdamaian permanen dari sunnah Nabawiyah sangat banyak, di antaranya perdamaian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan penduduk Najran.
Perjanjian di Masa Khulafaur Rasyidin:
Peperangan berlanjut di masa para sahabat antara kaum muslimin dengan negara Romawi dan Persia. Perjanjian tidak lagi dibuat untuk mengatur perdamaian, dukungan, atau kerja sama, melainkan baik untuk gencatan senjata atau untuk perjanjian dzimmah setelah musuh diberi pilihan -sebelum dimulainya perang- antara tiga hal: Islam, atau perjanjian dzimmah, atau perang. Kami cukupkan di sini dengan menyebutkan dua contoh perjanjian yang dibuat di masa Khulafaur Rasyidin:
Perjanjian pertama: Surat Amr bin Al-Ash kepada penduduk Mesir yang memilih untuk tetap pada agama Kristen, berisi: “Dia memberikan perlindungan kepada mereka atas diri mereka, agama mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, daratan dan lautan mereka. Tidak ada yang akan mengganggu hal itu, dan tidak akan dikurangi. Dan siapa yang masuk dalam perdamaian mereka dari Romawi, maka bagi mereka sama seperti yang mereka miliki, dan atas mereka sama seperti yang ditanggung mereka. Ini bagi yang ingin menetap dalam kekuasaan kami. Adapun yang menolak dan memilih pergi bersama Romawi, maka dia aman hingga sampai ke tempat amannya.”
Jenis kedua: Yaitu perdamaian Umar dengan penduduk Iliya -yaitu: Yerusalem- dan ini adalah perdamaian yang terkenal dan memiliki kepentingan besar dalam sejarah Islam, berisi: “Ini yang diberikan oleh Abdullah Amirul Mukminin kepada penduduk Iliya sebagai perlindungan. Dia memberikan perlindungan kepada mereka atas diri mereka dan harta mereka, gereja-gereja mereka dan salib-salib mereka, bahwa gereja-gereja mereka tidak akan dihuni dan tidak akan dihancurkan, tidak akan dikurangi dari gereja-gereja itu, dari batas-batasnya, dari salib mereka, dan dari sesuatu pun dari harta mereka. Mereka tidak akan dipaksa masuk agama mereka, dan tidak akan dianiaya seorang pun dari mereka. Dan tidak akan tinggal di Iliya bersama mereka seorang pun dari Yahudi.”
Kenyataannya, perjanjian-perjanjian ini merupakan contoh luar biasa dari contoh-contoh penjagaan terhadap non-muslim, hingga Umar tidak rela melaksanakan shalat di Gereja Kebangkitan karena khawatir kaum muslimin akan mencontohnya dan berkata: Di sinilah Umar shalat, sehingga shalat di dalam gereja menjadi hak, dan hal itu dapat mengakibatkan pengambilalihan gereja.
Di dalamnya juga: Ditetapkan kebebasan beragama dan berpindah tempat, serta kewajiban mereka membayar jizyah yang jumlahnya kecil.
Di masa Khulafaur Rasyidin terjadi banyak perjanjian lain yang menegaskan substansi perjanjian ini, seperti perjanjian Khalid bin Al-Walid dengan penduduk Damaskus yang berisi perlindungan atas darah mereka, harta mereka, dan gereja-gereja mereka sebagai imbalan jizyah.
Kemudian kita beralih ke jenis kedua dari perjanjian dalam Islam, yaitu perjanjian dagang:
Maka kami katakan: Dibolehkan secara syar’i membuat perjanjian dagang dan mengatur pertukaran luar negeri dengan non-muslim sebagai penguatan terhadap prinsip umum dalam hubungan kaum muslimin dengan lainnya, penetapan prinsip kebebasan perdagangan, penyediaan sumber daya yang diperlukan kaum muslimin dalam urusan kehidupan, dan pengamalan sunnah Nabawiyah taqririyah (penetapan). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan Hilful Muthaibin antara suku-suku Quraisy setelah wafatnya Qushay bin Kilab yang menyediakan makanan untuk para jamaah haji dari apa yang diberikan Quraisy kepadanya. Objek persekutuan adalah pembagian pelayanan kepada para jamaah haji untuk setiap suku, berupa pemberian air, pemberian makan, bendera, dan majelis.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Persekutuan apa pun yang ada pada masa jahiliah, maka Islam tidak menambahnya kecuali dengan kekuatan” -artinya: beliau menginginkan perjanjian untuk kebaikan, mengamankan kebutuhan jamaah haji, dan menolong kebenaran. Ada banyak perjanjian dagang antara bangsa Arab dan Eropa, di antaranya perjanjian tahun 913 H antara Amir Badis di Maghrib dengan penduduk Venesia yang mengizinkan orang-orang Venesia untuk singgah di Badis, berdagang dengan penduduknya, dan mengamankan diri serta harta mereka. Pihak berwenang Islam sangat toleran terhadap para pedagang.
Perdagangan merupakan salah satu sebab penyebaran Islam di Asia Timur dan Afrika. Namun dengan pemberlakuan beberapa pembatasan pada pertukaran dagang untuk mencegah pengeluaran senjata dan alat perang dari negeri kaum muslimin, serta larangan membeli dan mengimpor khamar, babi, dan semua kemungkaran, baik dari muslim atau non-muslim. Selain itu boleh untuk dipertukarkan, bahkan selama perang, seperti makanan dan semua bahan pangan, pakaian dan kain, bahan mentah non-logam, bahan kimia, produk pertanian dan industri -non-militer- dan seterusnya.
Hukum-Hukum Perjanjian dalam Syariat Islam
Kemudian kita akan membahas sekarang tentang pengaturan perjanjian dan akibat-akibat perjanjian. Kita katakan: pengaturan perjanjian membutuhkan banyak prosedur, konsultasi yang serius dan mendalam, serta penilaian kondisi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian karena memiliki kepentingan yang sangat besar. Hal itu karena perjanjian menjadi semacam undang-undang atau sistem yang mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan akibat-akibat penting dalam hubungan dan transaksi mereka. Perjanjian juga mempengaruhi individu-individu atau rakyat biasa di setiap negara dari kedua belah pihak. Perjanjian-perjanjian telah melalui berbagai tahapan di masa Nabi yang menyerupai tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengadakan perjanjian di era modern. Pembahasan ini mencakup hal-hal berikut terkait perjanjian:
Pertama: Cara Penyelenggaraan Perjanjian atau Bentuk Perjanjian
Perjanjian dalam Islam tidak tunduk pada pengaturan prosedural tertentu—seperti yang dipersyaratkan secara hukum saat ini antara negara-negara—karena inti perjanjian ditentukan oleh kehendak bebas para pihak. Namun tidak ada larangan secara syariat menurut penilaian saya untuk mengikuti prosedur formal modern, karena yang menjadi sandaran adalah isi substansial. Para fuqaha (ahli fiqih) Muslim mensyaratkan perlunya pengesahan dari khalifah atau imam terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat oleh komandan perang yang tidak diberi wewenang untuk mengadakan perdamaian. Orang yang diberi wewenang untuk mengadakan perdamaian akan melaporkan kepada khalifah tentang apa yang telah dilakukan, kemudian khalifah mengesahkan tindakannya jika syarat-syarat perjanjian itu sesuai syariat, seperti yang terjadi dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam dan para komandan lainnya. Mereka melaporkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab.
Jika khalifah sendiri yang mengadakan perjanjian—seperti yang dilakukan Umar dengan perdamaian penduduk Baitul Maqdis (Yerusalem)—maka perdamaian itu berlaku bagi kaum Muslim, karena khalifah adalah wakil umat dan perwakilan mereka dalam mengadakan perjanjian. Sebagai bentuk perhatian terhadap perjanjian dan penghormatan terhadapnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menuliskan semua persekutuan dan perjanjian sebagai bukti kesepakatan dan pelaksanaan syarat-syarat perjanjian, seperti yang terjadi dalam penulisan perjanjian politik pertama di Madinah dengan orang-orang Yahudi, dan seperti yang terjadi dalam penulisan Perjanjian Hudaibiyah yang didahului dengan perundingan melalui utusan dan duta dari kedua belah pihak.
Keadaan damai dimulai setelah selesainya perjanjian dan kesepakatan atas syarat-syarat perjanjian, bukan setelah pengumuman resmi perjanjian dan pertukaran ratifikasi seperti yang ditetapkan dalam hukum internasional kontemporer.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghadirkan saksi atas perjanjian, seperti yang dilakukan dalam Perjanjian Hudaibiyah, di mana beliau menghadirkan saksi dari kalangan Muslim dan dari kalangan musyrik untuk memperkuat perjanjian. Tidak ada larangan secara syariat untuk menulis perjanjian dalam dua bahasa atau lebih, seperti yang terjadi saat ini. Perjanjian-perjanjian Islam mencakup tiga unsur berikut:
- Pembukaan atau Pendahuluan
Biasanya dimulai—seperti yang kita lihat dalam contoh-contohnya—dengan basmalah yaitu: “Bismillahirrahmanirrahim” (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Di dalamnya disebutkan nama kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, utusan atau wakil mereka dalam perundingan, dan juga disebutkan tanggal perjanjian.
- Isi
Berisi ketentuan-ketentuan perjanjian dan pokok bahasannya dengan ungkapan singkat, tanpa pembagian atau penomoran pasal-pasalnya, seperti halnya perjanjian-perjanjian modern.
- Penutup
Disebutkan nama-nama saksi dan tanda tangan atau stempel mereka. Juga disebutkan nama pihak-pihak dalam perjanjian atau wakil-wakil mereka beserta stempel mereka. Ditutup dengan ungkapan yang menunjukkan anjuran untuk menepati janji dan ketegasan dalam menghormati perjanjian. Perjanjian biasanya didahului dengan tahap perundingan, kemudian dimulai tahap penulisan dan penyusunan, lalu penandatanganan dan ratifikasi.
Perundingan bisa dilakukan oleh khalifah sendiri atau wakilnya jika perjanjian tersebut penting, seperti jika topiknya berkaitan dengan gencatan senjata dengan pasukan musuh. Bisa juga dilakukan oleh amir, wali, atau komandan pasukan itu sendiri, atau orang yang diberi wewenang untuk itu jika perjanjiannya kurang penting.
Pihak non-Muslim bisa mengajukan pasal-pasal perjanjian dan syarat-syaratnya, dan wali Muslim mengirimkannya—maksudnya: mengirimkannya kepada khalifah untuk disahkan atau diubah, kemudian perjanjian diselesaikan, seperti yang terjadi dari pemimpin kota Suus yang dikepung oleh Abu Musa Al-Asyari. Dia mengirimkan surat kepada Abu Musa Al-Asyari meminta jaminan keamanan, kemudian Abu Musa mengirimkannya kepada Umar. Umar menyetujuinya dan mengadakan perjanjian dengan mereka.
Syarat-Syarat Perjanjian
Perjanjian diadakan antara kaum Muslim dan lainnya dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan yang sah dan mungkin, yang sesuai dengan prinsip dasar yang diinginkan dalam hubungan Muslim dengan lainnya—yaitu perdamaian. Ini berarti: perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:
- Kecakapan Berkontrak
Yaitu orang yang membuat perjanjian harus sudah baligh, berakal, dewasa, memilih dengan bebas, dan Muslim. Tidak sah perjanjian dari anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, orang mabuk, orang bodoh, orang yang dipaksa atau tidak dipaksa. Diperbolehkan jaminan keamanan dari perempuan secara syariat berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Kami telah memberi jaminan kepada orang yang engkau beri jaminan wahai Ummu Hani.” Sah jaminan keamanan dari anak mumayyiz menurut Imam Malik, Ahmad, dan Muhammad bin Al-Hasan, berbeda dengan imam-imam lainnya, berdasarkan hadits sebelumnya: “Dan yang paling rendah di antara mereka dapat memberikan jaminan perlindungan bagi mereka.”
Juga disyaratkan sahnya pemberian wewenang jika yang membuat perjanjian adalah bukan khalifah atau imam. Khalifah harus memberikan wewenang secara tertulis atau lisan untuk mewakilinya dalam membuat perjanjian atas nama negara Islam dengan negara atau bangsa lain. Pada dasarnya, perjanjian umum untuk kelompok besar, bangsa, atau wilayah, seharusnya perjanjian tersebut, atau pada dasarnya, perjanjian itu dibuat oleh khalifah atau wakilnya. Namun dia boleh memberikan wewenang kepada komandan pasukan atau wali untuk mengadakan perdamaian dengan musuh.
Imam memiliki pengawasan atas jaminan-jaminan yang dikeluarkan oleh individu berdasarkan wewenang umum yang dimilikinya, dan untuk mencegah bahaya terhadap penduduk negara Islam baik Muslim maupun dzimmi. Karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan dalam Islam. Tidak sah tindakan individu yang bertentangan dengan kepentingan umum atau berlawanan dengan prinsip umum dalam keabsahan jaminan keamanan. Jaminan keamanan tidak wajib ditepati kecuali jika sesuai dengan tuntutan pertimbangan syariat untuk seluruh rakyat dalam meraih kemaslahatan dan menolak bahaya. Pengawasan imam untuk menolak bahaya ada dua jenis: pengawasan khusus dan pengawasan umum.
Adapun Pengawasan Khusus:
Tampak jika seseorang melampaui wewenang yang diberikan kepadanya, seperti memberi jaminan keamanan kepada penduduk benteng atau wilayah, atau setelah imam melarang pemberian jaminan keamanan. Imam kemudian memilih antara melaksanakan jaminan keamanan atau menolak dan membatalkannya.
Adapun Pengawasan Umum:
Tampak dalam setiap jaminan keamanan yang dikeluarkan oleh individu, khususnya jaminan keamanan dari perempuan, budak, anak kecil, dan semacamnya.
Di antara syarat perjanjian juga: Kerelaan atau Kehendak Bebas yang Terbebas dari Cacat
Perjanjian—seperti kontrak perdata lainnya untuk terjadinya dan sahnya—memerlukan kerelaan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak yang berkontrak, dan bebas dari cacat kerelaan seperti paksaan, penipuan, dan ketidakjelasan. Karena ungkapan kehendak harus bebas, dan stabilitas perdamaian tidak tercapai tanpa kerelaan, kebebasan memilih, tanpa penipuan dan kesalahan. Perjanjian yang didasarkan pada paksaan, atau pemaksaan dan dominasi, atau penipuan, tidak dianggap dan tidak diakui karena bertentangan dengan tuntutan kontrak.
Di antara syarat perjanjian juga: Kejelasan Perjanjian
Disyaratkan bahwa perjanjian harus jelas dalam teksnya, terang tujuannya, menentukan hak dan kewajiban dengan jelas tanpa memerlukan takwil dan permainan kata-kata. Tidak boleh menggunakan ungkapan yang mengandung sindiran, penipuan, kecurangan, kesamaran, dan kelengkungan, seperti yang dilakukan politisi saat ini, yang menyebabkan kebingungan dan memerlukan penafsiran perjanjian melalui arbitrase atau peradilan internasional. Itu sering menyebabkan kegagalan tujuan perjanjian, hilangnya hak-hak yang sah, dan pembatalan apa yang telah disepakati, karena lambatnya peradilan dan buruknya niat negara-negara beradab.
Al-Quran Karim telah memperingatkan kita dari tipu daya musuh. Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan ambillah kehati-hatianmu” (QS. An-Nisa: 102, bagian dari ayat). Dan Allah juga berfirman: “Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah ia teguh (menginjak kebenaran) dan kamu akan merasakan keburukan (di dunia) disebabkan kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar (di akhirat).” (QS. An-Nahl: 94, bagian dari ayat). Perjanjian-perjanjian Nabi shallallahu alaihi wasallam seperti Piagam Madinah—maksudnya: seperti piagam atau dokumen yang beliau buat dengan orang-orang Yahudi ketika pergi ke Madinah setelah hijrah—dan seperti Perjanjian Hudaibiyah dan lainnya, sangat jelas dan terang.
Saya katakan: perjanjian-perjanjian ini sangat jelas, terang, dan menghindari semua yang dapat menyebabkan kesulitan di masa depan saat pelaksanaan.
Masa Berlaku Perjanjian
Kita berbicara tentang masa berlaku perjanjian. Kita katakan: pelaksanaan perjanjian dalam Islam biasanya dimulai setelah disepakati, tanpa perlu penulisan, penandatanganan, pengumuman, dan ratifikasi jika dikeluarkan oleh orang yang diberi wewenang untuk membuat perjanjian mewakili negara. Buktinya adalah pelaksanaan Perjanjian Hudaibiyah dan pengembalian orang yang datang kepada kaum Muslim—seperti yang telah kami jelaskan—sebelum perjanjian selesai.
Jika dalam perjanjian disebutkan tanggal tertentu untuk mulai berlakunya, maka perjanjian berlaku sejak tanggal tersebut. Adapun berakhirnya perjanjian secara syariat, biasanya disebutkan dalam perjanjian. Perjanjian berakhir dengan berakhirnya masa yang disepakati berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Maka sempurnakanlah perjanjian mereka sampai batas waktunya” (QS. At-Taubah: 4, bagian dari ayat).
Ukuran masa perjanjian berbeda menurut jenisnya, baik awal maupun akhir. Misalnya mengenai masa jaminan keamanan: jaminan keamanan dimulai setelah orang yang meminta jaminan mengetahui pemberian jaminan dari pemberi jaminan—menurut jumhur fuqaha—dan dengan terjadinya penerimaan—menurut Syafiiyah. Berakhir sesuai masa yang disepakati.
Para fuqaha memiliki pendapat tentang batas maksimal jaminan keamanan. Syafiiyah dan Malikiyah mengatakan: masa jaminan keamanan—gencatan senjata—tidak lebih dari empat bulan jika orang yang meminta jaminan bukan duta atau utusan politik, maka masa berakhir dengan selesainya tugasnya. Itu dalam kondisi kaum Muslim memiliki kekuatan.
Jika mereka dalam kelemahan, imam mempertimbangkan penentuan masa, dan boleh baginya memperpanjang masa jaminan keamanan sampai sepuluh tahun seperti gencatan senjata. Jika jaminan keamanan diberikan tanpa batas waktu, maka dibatasi empat bulan. Ini semua untuk jaminan keamanan laki-laki. Adapun perempuan, tidak perlu pembatasan masa dalam jaminan keamanan mereka. Jika masa jaminan keamanan berakhir, orang yang meminta jaminan harus dibawa ke tempat amannya.
Hanafiyah, Syiah Imamiyah, dan Zaidiyah mengatakan: masa jaminan keamanan tidak sampai satu tahun, agar orang yang meminta jaminan tidak menjadi mata-mata terhadap kaum Muslim dan membantu melawan mereka. Dalil mereka adalah memperhatikan darurat atau kebutuhan.
Hanabilah memberikan kelonggaran lebih dari yang lain. Mereka membolehkan jaminan keamanan tanpa membayar jizyah (pajak) untuk orang yang meminta jaminan dan utusan politik, baik mutlak atau dibatasi dengan masa, baik masa panjang atau pendek, berbeda dengan gencatan senjata yang tidak boleh kecuali dibatasi.
Masa Gencatan Senjata
Kita telah berbicara tentang masa jaminan keamanan, sekarang kita berbicara tentang masa gencatan senjata. Kita katakan:
Para fuqaha sepakat bahwa gencatan senjata harus dibatasi dengan waktu tertentu. Tidak sah gencatan senjata secara mutlak selamanya. Ini adalah kontrak sementara agar tidak menyebabkan terhentinya jihad. Tidak boleh menurut pendapat sejumlah fuqaha lebih dari sepuluh tahun seperti masa dalam Perjanjian Hudaibiyah, kecuali bahwa Syafiiyah menyebutkan bahwa pembatasan waktu gencatan senjata adalah untuk jiwa laki-laki. Adapun harta, boleh kontrak selamanya. Sah gencatan senjata dengan perempuan tanpa dibatasi masa.
Abu Hanifah dan Ahmad membolehkan masa lebih dari sepuluh tahun sesuai kebutuhan, karena menurut mereka masa yang disebutkan dalam Perjanjian Hudaibiyah yaitu sepuluh tahun bukan batas minimal, melainkan salah satu kasus, berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah” (QS. Al-Anfal: 61, bagian dari ayat).
Dapat dipadukan antara kedua pendapat berdasarkan ide perjanjian sementara yang dapat diperpanjang dengan menentukan sepuluh tahun. Kita katakan: diperpanjang otomatis saat dibutuhkan, kecuali jika salah satu pihak memberitahu pihak lain tentang tidak inginnya perpanjangan.
Masa Perjanjian Dzimmah
Mengenai masa perjanjian dzimmah atau kontrak dzimmah, kita katakan: kontrak dzimmah atau jizyah adalah perjanjian damai permanen—maksudnya: berdiri atas keabadian, kontrak ini berdiri atas keabadian. Ini adalah perjanjian damai permanen dengan non-Muslim untuk menetap di tanah Islam, karena Allah Ta’ala menjadikan tujuan perang adalah mencapai penerimaan perjanjian dengan kaum Muslim. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29, bagian dari ayat).
Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah komitmen terhadap hukum-hukum Islam. Tujuan dari pemberian jizyah—berdasarkan ijmak—adalah penerimaan dan komitmen. Kontrak dzimmah tidak memiliki batas waktu, melainkan secara alami adalah perjanjian permanen atau perdamaian permanen yang tidak dibatalkan kecuali dengan sesuatu yang merusak tujuannya, atau bertentangan dengan maksudnya, atau dengan peperangan dzimmi terhadap kaum Muslim, atau tidak mematuhi hukum-hukum Islam.
Bergabungnya Pihak Lain ke dalam Perjanjian
Kita berbicara sekarang tentang bergabungnya pihak lain ke dalam perjanjian. Kita katakan:
Ada di era kita dalam dunia hukum internasional dua jenis perjanjian: perjanjian tertutup dan perjanjian terbuka.
Tentang Jenis-Jenis Perjanjian
Adapun yang pertama: yaitu perjanjian yang tidak memuat ketentuan yang membolehkan negara-negara lain untuk bergabung ke dalamnya di kemudian hari; maka untuk bergabungnya pihak lain diperlukan terjadinya perundingan dengan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian asli, seperti perjanjian Pasar Eropa Bersama.
Adapun yang kedua: yaitu perjanjian terbuka; yaitu perjanjian yang memuat ketentuan yang membolehkan pihak lain untuk bergabung ke dalamnya seperti: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua jenis ini dikenal dalam Islam.
Perjanjian tertutup seperti jaminan keamanan umum untuk penduduk suatu negeri atau wilayah, dan perjanjian dzimmah (kependudukan) untuk sekelompok non-muslim yang menerima kewarganegaraan negara Islam, dan perjanjian perdamaian sementara atau gencatan senjata bisa jadi dari jenis ini, dan mungkin juga dari jenis yang terbuka. Perdamaian Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriah antara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan orang-orang musyrik Mekah termasuk jenis perjanjian terbuka; karena di dalamnya terdapat ketentuan yang membolehkan untuk bergabung kepadanya yaitu: “Barangsiapa yang ingin masuk dalam perjanjian Muhammad dan janjinya; ia boleh masuk ke dalamnya, dan barangsiapa yang ingin masuk dalam perjanjian Quraisy dan janji mereka; ia boleh masuk ke dalamnya.” Ini adalah ketentuan yang jelas yang membolehkan sisa suku-suku Arab untuk bergabung ke salah satu pihak yang berkontrak.
Tentang Materi dan Akibat Perjanjian
Kemudian kita berbicara tentang materi perjanjian, dan akibatnya, maka kita katakan:
Para ahli hukum internasional mensyaratkan bahwa materi perjanjian harus mungkin dilaksanakan, sah, dan kesahannya adalah jika sesuai dengan yang dibolehkan hukum, dan diakui oleh prinsip-prinsip moral. Para ahli fikih Islam mensyaratkan dalam materi perjanjian hal-hal berikut:
Pertama: Bahwa perjanjian harus sesuai dengan hukum-hukum Syariat Islam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah; maka ia batal” dan sabdanya: “Kaum muslimin terikat pada syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram” dan sabdanya: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami padanya; maka ia tertolak”.
Di antara syarat-syarat juga: mewujudkan kemaslahatan Islam. Disyaratkan bahwa dalam perjanjian terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin dan Islam; maka harus ada kemaslahatan yang sah dalam perjanjian perdamaian, jika tidak maka perjanjian tidak dibolehkan -sebagaimana dikatakan para ahli fikih kita-. Kemaslahatan yang sah dalam gencatan senjata -yaitu: perdamaian sementara- adalah kemungkinan memeluk Islam, atau menetapkan perdamaian, dan pertukaran hubungan ekonomi, atau bergabung dengan negara Islam, atau menolak bahaya dari kaum muslimin, dan lain-lain.
Juga disyaratkan: perjanjian harus atas dasar saling ridha kedua belah pihak sebagaimana telah kami jelaskan.
Juga disyaratkan: tersedianya niat baik pada kedua belah pihak; karena syarat niat baik diperlukan untuk sahnya perjanjian dalam Islam, sehingga perjanjian batal jika dibuat dengan motif penipuan dan niat buruk, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) setelah tetap tegak” (Surah An-Nahl: ayat 94) dan al-dakhal di sini adalah cacat tersembunyi yang masuk ke sesuatu lalu merusaknya.
Adapun akibat perjanjian berbeda-beda menurut jenisnya, dan jangka waktunya; maka ia tetap berlaku sepanjang masa yang disepakati selama tidak dibatalkan oleh musuh, dan akibatnya berbeda menurut jenisnya; jika ia merupakan jaminan keamanan khusus; maka akibatnya terbatas pada terjaganya darah orang yang dijamin, hartanya, anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya. Jika ia jaminan keamanan umum untuk suatu wilayah atau negeri; maka mencakup semua orang yang ada di sana. Jika ia gencatan senjata maka terbatas pada pihak-pihak yang berdamai. Jika ia perjanjian dzimmah; maka mencakup semua dzimmi (warga non-muslim).
Yang ditimbulkan dari perjanjian: mengakhiri peperangan, dan menetapkan perdamaian, dan terjaganya jiwa, darah, kehormatan, dan harta, dan kedua belah pihak hidup dengan aman, kasih sayang, perdamaian, dan ketentraman. Setiap pihak berkewajiban melaksanakan hukum-hukum perjanjian, dan syarat-syaratnya dengan niat baik; karena perjanjian menciptakan situasi hukum yang terwujud dalam kewajiban-kewajiban, dan hak-hak bagi kedua belah pihak yang berkontrak.
Tentang Berakhirnya Perjanjian
Kemudian kita berbicara sekarang tentang berakhirnya perjanjian: Perjanjian-perjanjian berakhir dengan keadaan-keadaan berikut:
Di antaranya -sebagai contoh- berakhirnya masa perjanjian, di antaranya pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian, di antaranya serangan dari salah satu pihak terhadap pihak lain, di antaranya dilakukannya beberapa kejahatan berbahaya oleh musuh, di antaranya juga pembatalan perjanjian dari pihak musuh; maka jika terdapat hal-hal ini; mengakibatkan berakhirnya perjanjian.
Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan tentang perjanjian-perjanjian, dan akibatnya dalam fikih Islam, kami titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
Pelajaran: 16 Peradilan Dan Sarana Penyelidikan Serta Pembuktian Dalam Sistem Islam
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 – Legalitas Peradilan, Kepentingannya, Sejarahnya, dan Syarat-Syarat Gugatan
Legalitas Peradilan dan Kepentingannya
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam tercurah kepada utusan rahmat bagi seluruh alam yaitu junjungan kami Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan, amma ba’du:
Kita mulai sekarang pembahasan tentang Sistem Peradilan dalam Islam, maka kita definisikan peradilan, dan menjelaskan dalil legalitasnya, dan menjelaskan kepentingannya, dan sejarahnya sepanjang masa-masa Islam yang berurutan:
Peradilan secara bahasa: berakhirnya sesuatu dan penyempurnaannya, dan memutuskan di antara manusia.
Secara syariat: adalah memutuskan perselisihan dan memotong persengketaan. Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah Ta’ala, yaitu: menampakkan hukum syariat dalam kenyataan. Peradilan dinamakan hukum karena di dalamnya terdapat hikmah yang mewajibkan menempatkan sesuatu pada tempatnya karena ia mengekang orang zalim dari kezalimannya. Dasar legalitasnya adalah Kitab (Al-Qur’an), Sunnah, dan Ijma’.
Adapun dari Al-Qur’an: firman Allah Ta’ala: “Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah” (Surah Shad: ayat 26) dan firman Allah Ta’ala: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah” (Surah Al-Ma’idah: ayat 49) dan firman Allah Ta’ala: “Maka putuskanlah perkara mereka dengan adil” (Surah Al-Ma’idah: ayat 42) dan firman Allah Azza wa Jalla: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu” (Surah An-Nisa’: ayat 105) dan ayat-ayat semacamnya.
Adapun dari Sunnah maka yang diriwayatkan dari Amr bin Al-Ash dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: “Apabila hakim berijtihad lalu benar maka baginya dua pahala, dan apabila berijtihad lalu salah maka baginya satu pahala” dan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Apabila hakim duduk untuk memutuskan, Allah mengutus dua malaikat kepadanya yang meluruskan dan membimbingnya; jika ia berbuat adil keduanya tetap -yaitu: terus bersama- dan jika ia berbuat curang keduanya naik dan meninggalkannya”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memutuskan di antara manusia, dan mengutus Ali dan Abu Musa Al-Asy’ari ke Yaman untuk peradilan dalam persengketaan, dan mengutus kepada mereka juga Mu’adz. Attab bin Usaid adalah hakim pertama bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena para Khalifah yang Rasyidin radhiyallahu ‘anhum memutuskan di antara manusia, dan Umar radhiyallahu ‘anhu mengutus Abu Musa Al-Asy’ari ke Basrah sebagai hakim, dan mengutus Abdullah bin Mas’ud ke Kufah sebagai hakim. Menjabat sebagai hakim adalah Umar, Ali, Mu’adz, Abu Musa, dan lain-lain. Kaum muslimin telah berijma’ tentang legalitas pengangkatan hakim-hakim, dan memutuskan di antara manusia karena dalam peradilan terdapat penegakan kebenaran, dan karena kezaliman mengakar dalam tabiat manusia, maka harus ada hakim yang memberikan keadilan kepada orang yang terzalimi dari orang yang zalim.
Jenis Legalitas:
Peradilan adalah kewajiban yang pasti dari kewajiban kifayah menurut kesepakatan para imam mazhab, maka wajib bagi pemimpin mengangkat hakim. Dalil kewajibannya: firman Allah Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan” (Surah An-Nisa’: ayat 135) dan karena -sebagaimana disebutkan- tabiat manusia dibentuk untuk saling menzalimi dan menahan hak-hak, dan jarang yang berbuat adil pada dirinya sendiri. Karena pemimpin biasanya tidak mampu memutuskan perselisihan sendiri karena banyaknya kesibukan-kesibukan umumnya; maka kebutuhan mendesak untuk mengangkat peradilan. Adapun karena ia kewajiban kifayah maka karena ia adalah amar ma’ruf, atau nahi munkar, dan keduanya adalah kewajiban kifayah. Peradilan adalah perkara dari urusan agama, dan kemaslahatan dari kemaslahatan kaum muslimin yang wajib diperhatikan; karena manusia sangat membutuhkannya, dan ia termasuk jenis-jenis pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para Nabi alaihimussalam mengerjakannya. Ibnu Mas’ud berkata: “Duduk sebagai hakim di antara dua orang lebih aku cintai daripada ibadah selama tujuh puluh tahun”.
Kepentingan Peradilan:
Sesungguhnya kepentingan sesuatu diukur dari tujuan-tujuannya, dan tujuan dalam peradilan adalah menegakkan keadilan dan membendung kezaliman. Di mana ada keadilan hilang kezaliman, dan kezaliman adalah kegelapan di dunia dan akhirat, dan ia adalah penindasan terhadap jiwa-jiwa, dan merampas hak-hak, dan melanggar kehormatan, dan ia buruk baik dalam hal besar maupun kecil. Allah menggambarkannya sebagai dosa besar yang paling buruk yaitu menyekutukan-Nya, Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (Surah Luqman: ayat 13). Karena besarnya urusan keadilan dalam melenyapkan kezaliman, dan bahwa keduanya adalah dua hal yang bertentangan yang tidak bisa berkumpul, keduanya disebut dalam satu ayat dengan perintah dan larangan, Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Surah An-Nahl: ayat 90). Umat manusia di berbagai zaman menyadari pentingnya keadilan maka mereka menjadikannya sebagai tujuan hukum-hukum mereka. Mereka mungkin berbeda dalam cara dan hasil, tetapi mereka bersatu dalam apa yang mereka tuju.
Karena keadilan adalah kekuatan yang bekerja mencabut kezaliman dan menghapus jejaknya, maka datanglah ungkapan mulia dengan gambaran paling fasih tentang hilangnya kezaliman ketika bertabrakan dengan keadilan, Allah Ta’ala berfirman: “Bahkan Kami melontarkan yang hak kepada yang bathil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang bathil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu selalu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya)” (Surah Al-Anbiya’: ayat 18). Dari sinilah menonjol pentingnya peradilan yang merupakan sarana untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Karena pentingnya tujuan itu dan bahayanya maka datanglah peringatan dan ancaman dalam menggunakan sarana ini; agar tidak digunakannya oleh orang yang tidak pandai menggunakannya sehingga ia menyimpang dari jalan yang lurus, dan tergelincir kakinya; lalu ia jatuh ke dalam kandang kezaliman dan kebohongan.
Sejarah Peradilan dalam Islam
Pertama: Kita berbicara sekarang tentang tahapan-tahapan yang dilalui peradilan di masa-masa awal Islam, maka kita sebutkan sekarang peradilan di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:
Ketika Islam datang melalui Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia mengibarkan panji keadilan, dan menetapkan kesetaraan penuh antara semua manusia, tidak ada perbedaan antara penguasa dan yang diperintah, tidak antara pemimpin dan rakyat jelata, tidak antara muslim dan lainnya. Semua sama di hadapan keadilan Islam. Islam telah menetapkan prinsip kesetaraan antara manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan kondisi yang paling ideal, dan menjadikan keadilan sebagai pilar bagi semua sistem atau undang-undang yang ditetapkannya untuk mengatur hubungan individu dan masyarakat antara satu sama lain. Islam menerapkan itu dalam semua aspek yang menuntut keadilan sosial, dan menuntut kehormatan manusia sebagai individu untuk diterapkan padanya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menjaga pembelajaran khusus manusia tentang keadilan, dan menegakkan keadilan di antara manusia, dan memutuskan dalam semua masalah dan persengketaan yang terjadi pada mereka; oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam harus bekerja dengan segala kemampuannya dan tidak menghemat energi dalam hal itu. Maka beliau mulai menjelaskan kepada manusia konstitusi peradilan dan berperkara, dan menjelaskan apa yang ditempuh hakim dalam peradilannya, dan apa yang wajib ia patuhi dalam memeriksa gugatan, dan dalam putusan yang ia keluarkan tentangnya, dan yang diakui Islam dengan mengambil dalam itu metode praktisnya yang diatur oleh petunjuk dari langit, mengajak manusia untuk meneladaninya dalam setiap tahap kehidupan. Peradilan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah undang-undang yang wajib diikuti baik peradilan itu penerapan ketentuan undang-undang yang diturunkan melalui wahyu, atau merupakan ijtihad darinya; karena dalam semua keadaan ia tidak dibenarkan atas kesalahan. Ijtihadnya berkedudukan seperti wahyu yang pasti, tidak ada perdebatan dalam hal itu, dan tidak ada keraguan sebagaimana pendapat yang ditetapkan oleh jumhur ulama dan ahli fikih, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Tidak lain (Al-Qur’an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Surah An-Najm: ayat 3, 4).
Mengenai Perkara yang Ada Nash dari Kitab atau Sunnah
Adapun mengenai perkara yang di dalamnya terdapat nash dari kitab atau sunnah, maka putusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengenainya menegaskan kelangsungan pengamalan dengannya, dengan apa yang mungkin menyertai hal ini berupa penjelasan terhadap nash syariat yang masih umum dan perincian terhadap kesamarannya. Dari sinilah wajib mengikuti putusannya alaihisshalatu wassalam dalam perkara yang merupakan penerapan dari sebuah nash, dan tidak boleh berpaling darinya ketika telah tetap kebenarannya bagi setiap hakim yang ingin menerapkan nash ini pada kasus serupa yang dihadapkan kepadanya.
Adapun putusannya shallallahu alaihi wasallam dengan ijtihadnya dalam perkara yang tidak ada nashnya maka banyak. Di antaranya adalah putusannya mengenai Fatimah binti Qais yang berperkara dengan suaminya kepada beliau, lalu beliau memutuskan menceraikannya secara talak bain, dan Rasulullah tidak menetapkan baginya tempat tinggal dan nafkah. Dalam Shahih Muslim dari Fatimah disebutkan: “Suamiku mentalakku tiga kali, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan bagiku tempat tinggal dan nafkah.” Dan dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wahai putri keluarga Qais, sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya bagi (istri) yang suaminya memiliki hak rujuk padanya.”
Di antara contoh lainnya adalah putusannya alaihisshalatu wassalam untuk memberikan pilihan kepada anak yang sudah mumayyiz antara ayah dan ibunya jika keduanya berpisah. Seorang wanita datang kepadanya dan berkata: “Sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku pergi, dan ia telah memberiku minum dari sumur Abu Inbah dan hal itu bermanfaat bagiku.” Maka alaihisshalatu wassalam bersabda: “Undi saja dia.” Suaminya berkata: “Siapa yang akan berselisih denganku mengenai anakku?” Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak itu: “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki” -maksudnya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada anak itu antara ayah dan ibunya- maka ia memegang tangan ibunya, lalu ibunya pergi bersamanya.
Kekuasaan Kehakiman di Masa Nabi
Mengenai kekuasaan kehakiman di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, kami katakan: Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah setelah hijrah, beliau menggabungkan semua kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan tidak ada hakim bagi kaum muslimin selain beliau. Adapun kekuasaan legislatif maka karena beliau adalah penyampai wahyu, pembawa panji syariat, dan atas beliau beban mengumumkannya kepada semua orang. Adapun kekuasaan yudikatif maka karena metode keadilan membutuhkan pelatihan, pengaturan, dan kepemimpinan praktis yang bijaksana yang menjadi petunjuk bagi manusia di setiap masa dan tempat, dan kepemimpinan ini sesungguhnya ditegakkan dengan pemeliharaan dan perhatian dari petunjuk langit. Maka sudah seharusnya kekuasaan kehakiman berada di tangan beliau alaihisshalatu wassalam, dan beliau menggabungkan dengan kekuasaan kehakiman ini untuk mengurus sendiri peradilan dan hukum dalam semua permasalahan dan perkara yang terjadi pada masyarakat pada waktu itu, yaitu ketika negara Islam masih dalam masa awalnya dan wilayahnya belum meluas, di mana beliau tidak membutuhkan bantuan dalam menerapkan peraturan peradilan di antara manusia karena sedikitnya jumlah perkara yang diajukan kepada beliau shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu.
Ketika Islam tersebar di Semenanjung Arab dan memenuhi cakrawala, Nabi shallallahu alaihi wasallam membutuhkan untuk menyerahkan peradilan kepada sebagian wakilnya yang beliau tunjuk untuk memerintah negeri-negeri yang jauh dari beliau, setelah beliau menjelaskan kepada mereka pedoman-pedoman peraturan kekuasaan kehakiman dan memerintahkan mereka untuk berpegang teguh padanya serta mewujudkan keadilan di antara semua manusia tanpa perbedaan antara pemimpin dan rakyat jelata, dan tidak antara muslim dan dzimmi. Semua sama di hadapan keadilan Islam sesuai dengan metode yang beliau tetapkan bagi mereka dalam bidang peradilan. Peradilan merupakan salah satu tugas wali yang wajib atasnya untuk memutuskan perkara di antara manusia sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam.
Kaidah, Prinsip, dan Sistem dalam Peraturan Kekuasaan Kehakiman
Sekarang kita berbicara tentang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan sistem-sistem yang tercakup dalam peraturan kekuasaan kehakiman beliau shallallahu alaihi wasallam. Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hal gugatan misalnya, alaihisshalatu wassalam menjelaskan bahwa setiap gugatan membutuhkan bukti yang dengannya tegak hujjah atas kebenaran pemiliknya. Jika tidak ada buktinya, maka gugatan itu menjadi seolah tidak ada. Dalam makna ini beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Seandainya manusia diberi (hak) karena gugatannya, niscaya ada orang-orang yang menggugat harta dan darah orang lain, tetapi bukti wajib atas penggugat, dan sumpah atas orang yang mengingkari.”
Rasul yang mulia shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan pentingnya mendengarkan kedua belah pihak atau para pihak sebelum memutuskan sengketa. Di antaranya adalah sabda beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu ketika mengangkatnya sebagai hakim di Yaman: “Jika dua orang yang bersengketa duduk di hadapanmu, maka jangan engkau putuskan hingga engkau mendengar perkataan yang kedua sebagaimana engkau mendengar perkataan yang pertama, karena hal itu lebih memungkinkan bagimu untuk tampak jelas putusannya.”
Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam apa yang beliau jelaskan dari peraturan peradilan, bahwa wajib bagi hakim untuk menyamakan antara kedua pihak yang bersengketa. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang diuji dengan peradilan di antara kaum muslimin, maka hendaknya ia berlaku adil di antara mereka dalam pandangannya, isyaratnya, dan tempat duduknya.” Dalam riwayat lain: “Barangsiapa yang diuji dengan peradilan di antara manusia, maka janganlah ia meninggikan suaranya kepada salah satu pihak dengan apa yang tidak ia tinggikan kepada pihak lain.”
Nabi shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para hakim untuk mencari kebenaran dan memutuskan dengannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa keadilan dalam peradilan akan mengangkat kedudukan hakim di sisi Allah Taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tahukah kalian siapa orang-orang yang terdahulu (mendapat) naungan Allah pada hari kiamat? Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda: Mereka yang jika diberi kebenaran menerimanya, dan jika diminta darinya mereka memberikannya, dan jika mereka memutuskan untuk kaum muslimin, mereka memutuskan seperti mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri.”
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari kezaliman dalam peradilan, maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah beserta hakim selama ia tidak berbuat curang, maka jika ia berbuat curang, Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri.”
Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa peradilan adalah jabatan yang sangat penting yang harus dijabat oleh orang yang paling berhak dan paling mampu atasnya, karena jabatan itu termasuk jabatan yang paling agung. Maka beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengurus sebagian urusan kaum muslimin lalu ia mengangkat atas mereka seseorang padahal ia mengetahui bahwa di antara mereka ada yang lebih berhak untuk itu dan lebih mengetahui tentang Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan jemaah kaum muslimin.”
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan agar hakim tidak memutuskan perkara saat ia sedang marah. Diriwayatkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam (bersabda): “Janganlah hakim memutuskan perkara antara dua orang sedangkan ia dalam keadaan marah.” Dan beliau juga bersabda: “Janganlah hakim memutuskan perkara kecuali ia dalam keadaan puas dan kenyang.”
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari menerima suap, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap dalam hukum.”
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa Islam tidak melarang hakim muslim untuk memutuskan perkara di antara Ahli Kitab dalam persengketaan mereka jika mereka meminta keputusan kepadanya atau meminta peradilan di hadapannya. Beliau alaihisshalatu wassalam telah memutuskan apa yang diajukan kepadanya dari perkara-perkara mereka. Demikian pula beliau mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu bersama delegasi Nasrani Najran untuk memutuskan perkara di antara mereka.
Dalam semua kondisi, Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan para hakim terhadap diri mereka sendiri untuk membuat putusan sebagaimana mereka kehendaki, tetapi beliau mewajibkan mereka dengan hukum langit dan syariat Islam. Beliau menjelaskan bahwa jalan mereka dalam hal itu adalah merujuk kepada Kitabullah terlebih dahulu. Jika tidak menemukan di dalamnya nash yang membahas peristiwa tersebut, mereka merujuk kepada Sunnah kedua. Jika mereka tidak menemukan di dalamnya hukum peristiwa tersebut, mereka mengandalkan ijtihad dalam mengeluarkan hukum berdasarkan petunjuk nash-nash Al-Quran dan Sunnah.
Dengan metode yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini, jalan keadilan menjadi jelas pedomannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari prinsip-prinsip dan apa yang dibawanya dari hukum-hukum.
Kedua: Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Masa Khalifah Pertama Abu Bakar
Sekarang kita berbicara tentang peradilan dan kekuasaan kehakiman di masa Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka kami katakan:
Kekuasaan kehakiman di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di tangan penguasa tertinggi, yaitu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keadaan sistem peradilan, dan tidak berbeda darinya kecuali dari sisi bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengkhususkan untuk peradilan seorang lelaki. Maka jabatan peradilan terpisah, dan pengkhususan untuknya sebagai pekerjaan tidak ada di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, di mana jabatan peradilan tergabung dengan jabatan kewilayahan -sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya-.
Adapun Abu Bakar, maka ia telah menunjuk Umar radhiyallahu anhu sebagai wakilnya dalam peradilan Madinah saja tanpa kewilayahannya. Meskipun ia menyerahkan peradilan kepada Umar, namun ia radhiyallahu anhu kadang-kadang menangani peradilan sendiri, yaitu ketika persengketaan dan perselisihan diajukan kepadanya. Ini tidak berarti ada pertentangan antara penanganannya peradilan sendiri dengan penyerahannya kepada Umar bin Al-Khaththab, karena khalifah adalah pemilik kekuasaan umum, dan dari haknya untuk memutuskan perkara sendiri meskipun ada orang yang ia tunjuk untuk menangani urusan ini. Hal ini karena peradilan termasuk fungsi-fungsi umum yang masuk di bawah kekhalifahan.
Ini menjelaskan kepada kita riwayat bahwa Umar selama setahun tidak ada dua orang yang datang kepadanya dalam urusan peradilan. Mungkin kedua pihak yang bersengketa pergi kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar, yaitu karena rasa takut para pihak untuk hadir di hadapannya, dan karena apa yang dikenal dari beliau mengenai ketegasan dan keteguhan di antara manusia dalam semua urusannya.
Adapun mengenai peradilan di luar Madinah: Maka peradilan merupakan bagian dari pekerjaan para wali dan termasuk dalam kekuasaan mereka. Sesuai dengan itu, para wali Abu Bakar untuk wilayah-wilayah ini juga adalah para hakimnya di tempat-tempat kerja mereka. Mungkin dalam hal ini beliau mengikuti metode Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, meskipun ada sebab-sebab lain di samping itu yang tidak membuatnya radhiyallahu anhu untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif dan politik sebagaimana yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu setelahnya.
Sebab-sebab ini antara lain: singkatnya masa jabatannya dalam kekhalifahan, di mana ia menjabat selama dua tahun, tiga bulan, dan beberapa hari. Perhatiannya selama masa itu tertuju untuk memberantas fitnah yang menyala-nyala apinya oleh sebagian suku-suku setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah bahwa beban-beban para wali di masanya tidak sebanyak yang dapat menghalangi mereka dari mengkhususkan diri untuk menjalankan peradilan dan memutuskan perkara di antara yang bersengketa.
Metode Abu Bakar dalam Peradilan
Kemudian kita berbicara tentang metode Abu Bakar dalam peradilan, maka kami katakan: Abu Bakar mengikuti metode dalam peradilan sebagai berikut:
- Merujuk kepada Kitabullah terlebih dahulu dalam perkara yang diajukan kepadanya untuk diputuskan. Jika ia menemukan di dalamnya nash, ia memutuskan dengannya.
- Jika ia tidak menemukan dalam Kitab hukum dalam sengketa yang ia tangani, ia memutuskan dengan Sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam jika menemukan di dalamnya hukumnya.
- Jika ia tidak menemukan hukum dalam Sunnah, ia mencari dalam putusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang serupa, dan memutuskan dengan putusan Rasulullah jika kedua perkara itu mirip.
- Memutuskan perkara jika ia tidak menemukan dalam putusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apa yang dapat dijadikan dasar putusan, ia bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat. Jika mereka bersepakat pada sesuatu, ia memutuskan dengannya. Jika mereka tidak bersepakat pada sesuatu dalam persengketaan itu, maka ia berijtihad dengan pendapatnya dan memutuskan dengan ijtihad.
Ketiga: Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Masa Umar bin Al-Khaththab
Kemudian kita berbicara sekarang tentang kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan di masa Umar bin Al-Khaththab, maka kami katakan:
Ketika Umar bin Al-Khaththab menjabat setelah wafatnya Abu Bakar, ia mengarahkan perhatiannya kepada peradilan dan penguatannya, serta memperhatikan urusannya khususnya setelah Allah membukakan kepada kaum beriman negeri Syam, Persia, Irak, dan Mesir. Wilayahnya meluas ke tempat-tempat berbeda di dunia di luar Jazirah Arab di masanya, mencakup Kufah, Bashrah. Di hadapan perluasan ini dalam wilayah negara Islam, sudah seharusnya Umar radhiyallahu anhu untuk menjadikan kekuasaan peradilan terpisah dari pekerjaan wali di sebagian wilayah yang membutuhkan hal itu, agar wali dapat mengkhususkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan banyak lainnya yang wajib ia khususkan diri untuknya. Di garis depan adalah menyebarkan keamanan dan ketenangan di seluruh wilayahnya, melindunginya dari musuh-musuhnya, dan mengawasi gerakan-gerakan dan konspirasi-konspirasi mereka.
Berdasarkan itu, Umar memisahkan peradilan di sebagian wilayah besar dari pekerjaan wali dan menjadikannya kekuasaan yang mandiri. Ia melaksanakan ini di wilayah: Kufah, Bashrah, dan Mesir.
Umar radhiyallahu anhu telah menjadikan kekuasaan kehakiman tergantung langsung kepadanya. Dialah yang mengangkat para hakim dan menulis kepada walinya di wilayah agar mengangkat si fulan sebagai hakim di tempatnya. Demikian pula ia mengarahkan para hakim dan berkorespondensi dengan mereka, dan mereka berkorespondensi dengannya dalam hal-hal yang sulit dalam peradilan. Mereka bertanya kepadanya: “Datang kepada kami begini dan begini, maka apa hukumnya?” Ia menjawab mereka dengan apa yang harus mereka ambil dan jalan apa yang harus mereka tempuh. Dengan sifat ini, ia adalah ketua tertinggi para hakim dan pemilik kebijakan yang mereka ikuti dalam peradilan mereka, tidak menyimpang darinya dan tidak menyelisihinya.
Meskipun demikian, Umar tetap membiarkan sebagian walinya untuk (juga menangani) peradilan. Mungkin ini kembali kepada bahwa kondisi mereka memungkinkan mereka di wilayah-wilayah mereka untuk menangani peradilan sendiri bersama dengan beban kekuasaan eksekutif, karena peradilan tidak menyibukkan mereka dari perhatian terhadap urusan wilayah.
Adapun para hakim Umar yang diangkatnya untuk jabatan kehakiman di Madinah adalah: Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan As-Saib bin Yazid. Umar mengkhususkan As-Saib untuk memutuskan perkara-perkara sederhana. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani bahwa Umar berkata kepada Yazid ketika mengangkatnya ke jabatan kehakiman: “Bebaskan aku dari urusan masyarakat dalam perkara satu dirham atau dua dirham” – maksudnya dalam perkara-perkara yang menyangkut jumlah yang kecil. Meskipun demikian, Khalifah Umar terkadang memutuskan perkara sendiri meskipun telah mengkhususkan hakim-hakim untuk Madinah, dan terkadang ia mengalihkan perkara-perkaranya kepada Zaid atau Ali, dan terkadang ia melibatkan keduanya dalam membahas suatu perkara yang menurutnya memerlukan penasihat.
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Umar membagi peradilan menjadi dua tingkatan: peradilan sederhana, yaitu khusus untuk perkara-perkara kecil, dan ini dialihkannya kepada As-Saib bin Yazid ketika ia memerintahkannya untuk memutuskan antara manusia dalam perkara satu dirham atau dua dirham; dan peradilan umum, yang dikhususkan untuk perkara-perkara selain itu – maksudnya: untuk yang lebih dari satu dirham atau dua dirham adalah peradilan umum – dan perkara-perkara ini ditangani oleh Ali bin Abi Thalib, atau Zaid bin Tsabit di Madinah, atau Umar sendiri, atau mereka semua, atau dua orang dari mereka sesuai dengan tuntutan keadaan dan kondisi. Pada dasarnya dalam sistem peradilan adalah menunjuk satu hakim untuk mengadili sendiri dalam wilayah yang dikhususkan untuknya, dan ini berjalan berdasarkan sistem hakim tunggal yang secara mandiri mengeluarkan putusan dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Sistem yang diterapkan oleh Umar ini adalah sistem yang masih berlaku di beberapa negara sekarang termasuk Mesir, yaitu untuk hakim-hakim pengadilan sebagian dan hakim-hakim perkara mendesak. Meskipun ini adalah asalnya, yaitu bahwa hakim mandiri sendirian dalam memutuskan, namun Umar juga dalam kekuasaan peradilannya memberi wewenang kepada satu hakim untuk meminta bantuan orang lain bersamanya dalam beberapa perkara penting, atau ia dapat menentukan syarat-syarat tertentu untuk beberapa perkara penting terlebih dahulu sehingga jika syarat-syarat ini berlaku pada perkara tersebut, maka ditunjuk lebih dari satu hakim untuk memeriksanya sebelum memutuskannya, dan Khalifah dapat memanggil mereka sendiri untuk memeriksa perkara bersama mereka, sesuai dengan keadaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Dari hal tersebut kita simpulkan bahwa satu perkara terkadang diperiksa oleh dua hakim bersama-sama atau lebih pada masa Umar, dan bahwa peradilan Islam tidak selalu berjalan dengan sistem satu hakim sebagaimana diklaim oleh sebagian orientalis, bahkan dalam nash-nash Islam, ajaran-ajarannya, dan perbuatan para khalifah ada yang membolehkan lebih dari satu hakim terlibat dalam satu perkara. Sistem ini bukanlah sistem modern dan lahir dari peradaban – sebagaimana diklaim oleh orang yang mengklaimnya – tetapi ini adalah dari sistem peradilan dalam Islam.
Metode Umar dalam peradilan dan konstitusi peradilan pada masanya: Umar radhiyallahu anhu dalam peradilannya mengikuti apa yang terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah. Jika tidak menemukan di keduanya apa yang dapat diputuskannya, maka ia melihat kepada keputusan Abu Bakar. Jika menemukan keputusan darinya, ia memutuskan dengannya, jika tidak maka ia bermusyawarah dalam hal itu dengan para fuqaha sahabat dan di antaranya yang terdepan adalah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit yang merupakan dua hakimnya. Disebutkan dalam Al-Mabsuth karya As-Sarkhasi: bahwa Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat meskipun ia memiliki pemahaman fiqih, sehingga jika suatu perkara diajukan kepadanya ia berkata: “Panggilkan kepadaku Ali dan panggilkan kepadaku Zaid,” maka ia bermusyawarah dengan mereka kemudian memutuskan sesuai dengan kesepakatan mereka. Perkara diajukan kepada Umar lalu ia mungkin merenung tentang hal itu selama sebulan dan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Umar bin Al-Khaththab telah menetapkan bagi para hakim sebuah konstitusi yang mereka ikuti dalam peradilan dan dalam memutuskan, yaitu pedoman yang ia jalankan sendiri dalam peradilan. Namun ia memandang perlu untuk membukukannya beserta semua hal yang berkaitan dengan peradilan dan pengorganisasiannya, tata cara pengadilan, putusan, syarat-syarat gugatan yang sah untuk diperiksa, dan lain-lain. Ia tuliskan itu dalam sebuah kitab khusus yang dianggap sebagai dasar ilmu peradilan di dunia peradilan, yaitu kitab yang ia kirimkan kepada Abu Musa Al-Asy’ari dan kepada hakim-hakim lainnya. Ini adalah teks kitab tersebut:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah bin Qais, salam untukmu, amma ba’du:
Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang kokoh dan sunnah yang diikuti. Maka pahamilah apabila diserahkan kepadamu, karena sesungguhnya tidak berguna perkataan tentang kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan. Samakan antara manusia dalam majelismu, wajahmu, dan putusanmu; agar orang terhormat tidak mengharapkan keberpihakan darimu, dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu. Bukti ada pada penggugat, dan sumpah ada pada orang yang menyangkal. Perdamaian dibolehkan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan barangsiapa mengklaim hak atau bukti, maka tentukanlah baginya tenggang waktu yang harus ia penuhi. Jika ia menunjukkan bukti, maka berikanlah kepadanya, dan jika hal itu memberatkannya maka wajibkanlah kepadanya putusan, karena sesungguhnya itu lebih jelas dalam memberi alasan. Dan janganlah menghalangimu sebuah putusan yang telah kamu putuskan hari ini lalu kamu tinjau kembali pendapatmu dan kamu diberi petunjuk kepada kebenarannya untuk kembali kepadanya, karena sesungguhnya kebenaran itu qadim (terdahulu) tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya, dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Kaum muslimin itu adil satu sama lain.
Ini termasuk dalam surat Umar bin Al-Khaththab, yang merupakan konstitusi peradilan hingga sekarang, dan akan terus berlanjut di masa depan – insya Allah.
Ketiga: Kemudian kita akan berbicara sekarang tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan pada masa Utsman, maka kita katakan:
Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjabat khilafah dan dibaiat pada tahun 17 Hijriah, ia menempuh jalan yang berbeda dari jalan yang ditempuh oleh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu dalam khilafahnya. Utsman memberhentikan dari peradilan Madinah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan As-Saib bin Yazid, dan ia memegang sendiri kekuasaan kehakiman dan peradilan. Ia sendiri yang memeriksa persengketaan dalam semua perkara penting yang bersifat yudisial. Ia memanggil hakim-hakim yang telah ia berhentikan dari jabatan hakim dan sahabat-sahabat lainnya untuk bermusyawarah dengan mereka tentang apa yang akan ia putuskan ketika memerlukan hal itu. Jika pendapat mereka sesuai dengan pendapatnya, ia melaksanakannya, dan jika pendapat mereka tidak sesuai dengan pendapatnya, ia melihat ke dalam persoalan setelahnya. Tampaknya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu memilih untuk menyerahkan urusan peradilan di wilayah-wilayah kepada para gubernur sendiri.
Keempat: Dan jika kita melihat peradilan pada masa Ali – yaitu kita berpindah sekarang untuk melihat peradilan pada masa Ali radhiyallahu anhu maka kita katakan: Dengan ilmu Ali yang luas dan melimpah dari doa Nabi shallallahu alaihi wasallam untuknya dengan sabdanya: “Ya Allah, ajarkanlah kepadanya tentang peradilan” dan dengan ijma’ para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa Ali adalah yang paling pandai di antara mereka dalam memutuskan perkara, namun peradilan dalam khilafahnya tidak mendapat banyak perhatian dan pemeliharaan darinya karena kondisi politik yang bergejolak dan fitnah-fitnah yang muncul pada masa itu, yang menjadi sebab bagi Ali radhiyallahu anhu untuk tidak memberikan perhatian pada urusan pengorganisasian wilayah-wilayah dan memusatkan perhatian penuh pada urusan peradilan secara khusus. Meskipun demikian, kondisi-kondisi sulit ini tidak menghalanginya untuk memperhatikan urusan peradilan dan mengerjakannya. Ia sendiri yang duduk untuk memutuskan dan mengadili antara manusia sebagaimana ia mempercayakannya kepada orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi. Ali radhiyallahu anhu menyerahkan urusan pemilihan hakim kepada para gubernur sendiri yang ia tunjuk di wilayah-wilayah setelah khilafahnya. Ia memberhentikan sebagian besar gubernur yang ada pada masa Utsman dan mengangkat yang lain. Ali radhiyallahu anhu memisahkan peradilan dari pemerintahan sebagaimana yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu meskipun ia mendelegasikan kepada para gubernur untuk menunjuk hakim dan memilih mereka dari unsur-unsur terbaik yang layak untuk peradilan tanpa harus memutuskan sendiri dalam perkara-perkara manusia untuk menjamin keadilan dalam peradilan antara manusia.
Kelima: Kemudian kita berbicara sekarang tentang peradilan pada masa Umayyah maka kita katakan: Pada masa khilafah Bani Umayyah, peradilan tidak banyak berbeda pada tahap ini dari tahap-tahap sebelumnya, khususnya masa Umar dari segi kekuasaan kehakiman, pengorganisasian peradilan, dan pemilihan unsur-unsur terbaik untuk menjabat jabatan peradilan. Demikian juga kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan politik dan kekuasaan eksekutif. Hakim dalam putusannya mengikuti cara yang mutlak dari segi ijtihad sebagaimana yang dilakukan para hakim di masa para khalifah Rasyidin. Kita dapat merangkum ciri-ciri atau karakteristik peradilan pada masa itu dengan hal-hal berikut:
1- Bahwa peradilan tidak terpengaruh oleh politik, karena para hakim mandiri dalam putusan-putusan mereka, tidak terpengaruh oleh kecenderungan negara yang berkuasa, bahkan mereka bebas bertindak, dan kata-kata mereka berlaku bahkan terhadap para gubernur dan petugas pajak.
2- Hakim memutuskan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ijtihadnya. Ia menyimpulkan hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, atau ijma’, atau ia berijtihad dalam memutuskan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan prinsip-prinsipnya.
3- Kekuasaan kehakiman berada di tangan Khalifah sebagai penguasa umum dengan kemandirian para hakim. Secara historis terbukti bahwa Khalifah mengawasi putusan-putusan peradilan, dan memberhentikan hakim yang menyimpang dari jalan yang benar.
4- Pembukuan putusan-putusan peradilan pada masa itu. Muncul kebutuhan akan adanya catatan untuk membukukan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim, yaitu karena banyaknya masalah dan sengketa yang berbeda-beda, berbeda dengan masa para Khalifah Rasyidin sebelumnya. Pengingkaran para pihak yang bersengketa dalam beberapa kasus terhadap putusan-putusan hakim menyebabkan dimasukkannya sistem pencatatan.
Keenam: Kemudian kita berbicara sekarang tentang sistem peradilan pada masa Abbasiyah maka kita katakan:
Peradilan pada masa Abbasiyah kedua berkembang dengan terpengaruh oleh politik, dan para khalifah mulai ikut campur dalam peradilan hingga mereka memaksa para hakim dalam banyak kesempatan untuk berjalan sesuai dengan keinginan mereka; dan karena alasan ini seringkali para hakim meminta maaf untuk tidak menerima penunjukan dalam jabatan-jabatan peradilan meskipun mereka mengetahui kehormatannya dan keutamaannya di antara manusia, yaitu karena khawatir akan campur tangan para khalifah dalam putusan-putusan peradilan mereka. Semangat ijtihad melemah pada masa ini karena munculnya empat mazhab, dan menjadi kewajiban bagi hakim untuk mengeluarkan putusan-putusannya sesuai dengan salah satu dari mazhab-mazhab ini. Demikian juga para hakim di wilayah-wilayah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mazhab-mazhab ini. Mazhab yang tersebar di Irak adalah mazhab Abu Hanifah An-Nu’man, di Syam, Maghrib, dan Andalusia para hakim mengeluarkan putusan-putusan mereka sesuai mazhab Imam Malik, di Mesir sesuai mazhab Imam Asy-Syafi’i. Jika terjadi persengketaan antara dua pihak yang bersengketa yang tidak menganut mazhab yang berlaku di suatu negeri, maka hakim menunjuk dari para hakim orang yang menganut mazhab para pihak yang bersengketa. Keempat mazhab ini terus berlanjut hingga waktu yang lama sebagai sumber peradilan dan putusan-putusan. Oleh karena itu, masa Abbasiyah disebut sebagai masa para imam mazhab. Ada mazhab-mazhab lain selain empat mazhab yang memiliki peradilan khusus mereka sendiri. Hakim mengikuti mazhab, di antaranya Zaidiyah di Yaman, Imamiyah dan Itsna ‘Asyariyah di Persia dan Irak, Imamiyah Sab’iyah atau Isma’iliyah di tempat lain. Adapun keinginan manusia untuk bertaklid dan memutuskan sesuai dengan mazhab yang diikuti oleh hakim atau mufti hanya muncul dengan munculnya Abu Al-Hasan Al-Asy’ari dan pemikirannya untuk kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah. Tidak boleh luput dari pikiran kita dalam hal ini bahwa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah yang empat – Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali – adalah sumber legislasi pada masa ini, dan bahwa yang menjabat sebagai hakim hanyalah orang-orang Sunni. Para hakim di Negara Abbasiyah adalah wakil dari qadhi al-qudhah (hakim agung), yang mirip dengan menteri kehakiman sekarang, dan ia tinggal di ibukota negara. Hakim Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, adalah orang pertama yang mendapat gelar ini pada masa Harun Ar-Rasyid. Masa Abbasiyah kedua ini berlanjut, dan kewenangan hakim meluas hingga ia memeriksa perkara-perkara perdata, gugatan dan wakaf, penunjukan wali, dan seringkali ditambahkan kepadanya urusan syarat-syarat, mazhalim, qishash, hisbah, dar adh-dharb (pencetakan mata uang), dan baitul mal.
Pada awalnya, setiap wilayah dari wilayah-wilayah Islam memiliki satu hakim untuk semua spesialisasi peradilan. Namun dengan meluasnya negara Abbasiyah, setiap wilayah ini memiliki para hakim yang mewakili empat mazhab, dan masing-masing dari mereka mengadili sengketa yang terjadi di antara orang-orang yang menganut keyakinan mazhabnya. Tempat hakim pada awalnya berada di masjid, kemudian kaum Muslim menemukan bahwa hal ini tidak sesuai dengan kesucian rumah-rumah Allah. Maka Khalifah Al-Mu’tadid melarang para hakim untuk bersidang di masjid. Pada beberapa kesempatan, hakim mengadili perkara di antara manusia di rumahnya sendiri. Qadhi Al-Qudhah (Hakim Agung) Baghdad memiliki dewan yang dikenal dengan Diwan Qadhi Al-Qudhah. Di antara pegawai terkenal dari dewan ini adalah juru tulis, penjaga pintu, pemeriksa keputusan, penjaga arsip pengadilan, dan para pembantunya. Perkembangan sistem peradilan pada masa ini juga mengharuskan penyelidikan terhadap para saksi. Jika saksi dikenal jujur dan tidak ada cacat pada dirinya, hakim menerima kesaksiannya. Jika tidak dikenal kejujurannya, kesaksiannya tidak diterima. Jika tidak dikenal, tetangganya ditanya tentangnya, kemudian muncullah sekelompok saksi yang dikenal sebagai saksi tetap, atau mu’addil (yang merekomendasikan), atau muzakki (yang mensucikan).
Ketujuh: Kita berbicara sekarang tentang kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan di Andalusia, maka kami katakan:
Peradilan di Andalusia memiliki kedudukan istimewa sebagaimana di negara-negara Islam lainnya. Amir atau Khalifah adalah kepala tertinggi peradilan karena jabatan ini terkait dengan agama. Qadhi Al-Qudhah di Andalusia disebut Qadhi Al-Jama’ah (Hakim Jamaah) karena berada di ibu kota negara. Disyaratkan dalam pengangkatan hakim bahwa ia harus menguasai fikih secara mendalam, dikenal jujur dan lurus, dan tidak disyaratkan bahwa ia harus Arab murni. Sering kali jabatan ini dipegang oleh mawali dan Berber, seperti yang terjadi dengan Yahya bin Yahya Al-Laitsi yang berasal dari Berber. Qadhi Al-Qudhah biasanya dipilih dari hakim-hakim daerah yang terkenal keunggulannya dalam peradilan, atau dari mereka yang memegang beberapa jabatan penting negara. Qadhi Al-Jama’ah berkedudukan di Cordoba, ibu kota negara Umayyah di Andalusia, dan diangkat oleh Amir atau Khalifah. Para hakim di daerah-daerah adalah wakilnya, dan mereka memutuskan perkara menurut mazhab Imam Malik, dan sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Para penguasa dan wali melaksanakan putusan-putusan peradilan mereka. Para Umayyah di Andalusia mengikuti jejak khalifah-khalifah Umayyah dan Abbasiyah di Timur dalam menugaskan para hakim mereka memimpin pasukan sebagai wakil mereka. Di antara wewenang hakim adalah mengawasi sumber-sumber wakaf dan catatan fatwa fikih, mengawasi shalat pada hari Jumat dan hari raya di Masjid Agung Cordoba, atau di Masjid Zahra yang didirikan oleh Khalifah Abdul Rahman An-Nashir di kota Zahra. Juga di antara wewenangnya adalah shalat istisqa (minta hujan), sehingga sering kali hakim disebut shahibu ash-shalah (pemimpin shalat). Keadaan tetap seperti ini hingga Abdul Rahman An-Nashir memisahkan jabatan, satu orang untuk shalat dan orang lain untuk peradilan. Para hakim Andalusia mengetahui bahasa Spanyol kuno, dan berdiskusi dengan para pihak yang berperkara dengan bahasa tersebut di majelis peradilan.
Dengan ini kita telah selesai menyoroti sejarah peradilan sejak awal dakwah Islam hingga para hakim di Andalusia.
Rukun-Rukun Peradilan
Sekarang kita beralih ke topik lain yaitu: rukun-rukun peradilan. Kami katakan:
Peradilan bersandar pada lima rukun yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
Pertama: Hakim – rukun pertama adalah hakim – yaitu qadhi yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutuskan perkara dan persengketaan. Dengan ini hakim berbeda dengan hakam (arbiter), yaitu orang yang disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa untuk menengahi sengketa di antara mereka.
Rukun kedua: Hukum/putusan, yaitu apa yang dikeluarkan oleh hakim berupa keputusan untuk menyelesaikan sengketa dan mengakhiri persengketaan, dan memiliki sifat mengikat. Maka putusan berbeda dengan fatwa, karena fatwa tidak mengikat. Putusan bisa berupa mewajibkan terpidana melakukan sesuatu seperti melaksanakan sesuatu atau memberikan sesuatu, ini disebut qadha’ ilzam (putusan kewajiban). Atau hakim mencegah persengketaan dengan perkataannya kepada penggugat: kamu tidak memiliki hak pada lawanmu karena ketidakmampuanmu membuktikan, dan ini disebut qadha’ at-tark (putusan penghentian).
Rukun ketiga dari rukun peradilan: Mahkum bih (objek putusan), yaitu dalam qadha’ ilzam apa yang diwajibkan oleh hakim kepada terpidana berupa memenuhi hak penggugat, dan dalam qadha’ at-tark adalah penghentian persengketaan oleh penggugat. Pada intinya, mahkum bih adalah hak, baik hak Allah, hak hamba, atau gabungan keduanya.
Rukun keempat dari rukun peradilan: Mahkum ‘alaih (terpidana), yaitu orang yang diputuskan menentangnya, atau orang yang diambil darinya hak, baik ia tergugat maupun tidak.
Rukun kelima dari rukun peradilan: Mahkum lah (yang dimenangkan), yaitu penggugat yang menuntut haknya, baik hak murni miliknya seperti hak utang atau kewajiban harta, atau murni hak Allah seperti hudud syar’i, atau gabungan antara kedua hak dan hak Allah yang lebih dominan yaitu had qadzaf (tuduhan zina) menurut pendapat Hanafiyah, atau hak hamba yang lebih dominan yaitu hak qishash (pembalasan). Jika hak itu murni untuk Allah atau hak Allah di dalamnya dominan, maka mahkum lah adalah syariat, dan di sini tidak disyaratkan gugatan dari orang tertentu. Setiap orang bahkan hakim berhak mengajukan perkara, yaitu da’wa al-hisbah (gugatan publik), yang dalam zaman kita diwakili oleh Kejaksaan.
Gugatan dan Syarat-Syaratnya
Kemudian kita beralih sekarang ke topik lain yaitu gugatan dan bukti-bukti. Kami katakan:
Gugatan (ad-da’wa) secara bahasa: perkataan yang dimaksudkan manusia untuk menetapkan hak atas orang lain, atau permintaan dan harapan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan” (Yasin: 57). Jamaknya adalah da’awa atau da’awi.
Gugatan menurut syariat: pemberitahuan tentang hak seseorang atas orang lain di hadapan hakim. Rukunnya adalah perkataan seseorang “aku memiliki hak atas fulan”, atau “di sisi fulan sekian”, atau “aku telah memenuhi hak fulan”, atau “ia membebaskanku dari haknya”, dan sejenisnya.
Syarat-syarat gugatan: Syarat pertama dari syarat gugatan: kecakapan akal atau tamyiz (kemampuan membedakan). Disyaratkan bahwa penggugat dan tergugat berakal. Tidak sah gugatan orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz, sebagaimana tidak sah gugatan terhadap keduanya. Mereka tidak diwajibkan menjawab gugatan orang lain terhadap mereka dan bukti tidak didengar terhadap mereka.
Syarat kedua gugatan: harus di majelis peradilan, karena gugatan tidak sah di luar majelis ini.
Syarat ketiga: gugatan penggugat harus terhadap lawan yang hadir di hadapan hakim saat mendengar gugatan, bukti, dan putusan. Gugatan terhadap orang yang tidak hadir tidak diterima sebagaimana tidak diputuskan terhadap orang yang tidak hadir menurut Hanafiyah, baik tidak hadir saat kesaksian maupun setelahnya, baik tidak hadir dari majelis hakim maupun dari kota tempat hakim berada. Syarat ini tidak disyaratkan dalam mazhab-mazhab lain.
Syarat keempat: objek gugatan harus sesuatu yang diketahui. Pengetahuan tentangnya bisa dengan menunjuknya di hadapan hakim jika benda bergerak, atau dengan menjelaskan batas-batasnya jika dapat dibatasi seperti tanah, rumah, dan seluruh barang tidak bergerak, atau dengan pemeriksaan yang dilakukan hakim atau wakilnya jika objek gugatan tidak dapat dibatasi seperti batu penggilingan, atau dengan menjelaskan jenis, macam, jumlah, dan sifatnya jika objek gugatan adalah utang seperti uang, gandum, jelai, dan lainnya, karena utang tidak menjadi jelas kecuali dengan menjelaskan hal-hal ini. Alasan disyaratkannya pengetahuan tentang objek gugatan adalah bahwa tergugat tidak diwajibkan menjawab gugatan penggugat kecuali setelah mengetahui objek gugatan. Demikian pula saksi-saksi tidak dapat bersaksi tentang sesuatu yang tidak jelas. Kemudian hakim tidak dapat mengeluarkan putusan atau memutuskan gugatan kecuali jika objek gugatan adalah sesuatu yang diketahui.
Syarat kelima dalam gugatan: subjek gugatan harus perkara yang memungkinkan tergugat diwajibkan dengannya – yaitu tuntutan harus sah dan mengikat dalam pemahaman kita saat ini. Jika tidak memungkinkan mewajibkan tergugat dengan sesuatu maka gugatan tidak diterima, seperti seseorang mengklaim bahwa ia adalah wakil lawan ini di hadapan hakim dalam suatu urusan, atau menggugat seseorang dengan permintaan sedekah, atau pelaksanaan akad yang batal. Hakim tidak mendengar gugatannya ini jika lawan mengingkarinya, karena wakalah (perwakilan) adalah akad tidak mengikat sehingga ia dapat memberhentikan pengklaim wakalah saat itu juga.
Keenam: objek gugatan harus sesuatu yang memungkinkan untuk dibuktikan, karena gugatan tentang sesuatu yang mustahil ada secara hakikat atau kebiasaan adalah gugatan bohong. Jika seseorang berkata kepada orang yang lebih tua darinya: ini anakku, gugatannya tidak didengar karena mustahil orang yang lebih tua menjadi anak orang yang lebih muda. Demikian pula jika ia berkata kepada orang yang diketahui nasabnya dari orang lain “ini anakku”, gugatannya tidak didengar.
Ini adalah syarat-syarat sahnya gugatan agar didengar di hadapkan hakim. Kita cukupkan sampai di sini, saya titipkan kalian kepada Allah, dan semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya tercurah kepada kalian.
2 – Gugatan, Pertentangannya, dan Alat-Alat Pembuktian
Gugatan
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu junjungan kita Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du:
Kita akan memulai pembahasan dalam kuliah ini tentang jenis-jenis gugatan dalam peradilan. Kami katakan: Gugatan ada dua jenis: sah dan batal.
Gugatan sah adalah yang memenuhi syarat-syarat kesahan, dan terkait dengannya hukum-hukum yang dimaksudkan darinya, yaitu menghadirkan lawan ke pengadilan dengan perantaraan pembantu hakim, menuntutnya menjawab gugatan penggugat, dan sumpah jika ia mengingkari objek gugatan. Hak penggugat ditetapkan dengan bukti atau dengan penolakan tergugat untuk bersumpah.
Gugatan batal adalah yang tidak memenuhi syarat kesahan, dan tidak terkait dengannya hukum-hukum yang dimaksudkan darinya, seperti gugatan terhadap orang yang tidak hadir, atau objek gugatan tidak jelas, karena yang tidak jelas sulit dibuktikan dengan kesaksian. Para saksi tidak dapat bersaksi dengannya, dan hakim tidak dapat memutuskan perkara yang tidak jelas, baik dengan bukti maupun dengan penolakan sumpah.
Sekarang kita bahas tentang: siapa penggugat dan tergugat? Kami katakan: karena masalah-masalah gugatan bergantung pada pengenalan penggugat dan tergugat, dan ini termasuk hal terpenting yang menjadi dasar gugatan, terutama berkaitan dengan apa yang diwajibkan kepada salah satu dari keduanya berupa bukti atau sumpah dan sejenisnya, maka perlu ditetapkan orang yang memiliki sifat penggugat dan orang yang memiliki sifat tergugat.
Dalam menetapkannya ada berbagai definisi, di antaranya: penggugat adalah orang yang tidak dipaksa untuk berperkara jika ia meninggalkannya, karena ia adalah penuntut. Atau ia adalah orang yang perkataannya bertentangan dengan zhahir (keadaan yang tampak) – yaitu keadaan yang tampak. Sedangkan tergugat adalah orang yang dipaksa untuk berperkara karena ia adalah yang dituntut. Atau ia adalah orang yang perkataannya sesuai dengan keadaan yang tampak, dan yang zhahir adalah bebas dari tuntutan.
Dan dikatakan: Penggugat adalah orang yang berusaha dengan ucapannya untuk mengambil sesuatu dari tangan orang lain, atau menetapkan hak dalam tanggungannya, dan tergugat adalah orang yang mengingkari hal itu. Dan dikatakan: Tergugat adalah orang yang mengingkari dan yang lainnya adalah penggugat.
Dan sekarang kita berbicara tentang hukum gugatan, atau apa yang wajib atas tergugat setelah adanya gugatan, maka kita katakan:
Hakim memiliki peran penting dalam gugatan. Jika penggugat datang ke pengadilan bersama lawannya, hakim bertanya kepadanya tentang pokok gugatan. Jika gugatan itu sah dengan syarat gugatan tersebut ditujukan kepada lawan yang hadir dan memenuhi syarat-syaratnya, hakim meminta tergugat memberikan jawabannya tentang gugatan tersebut; karena memutus akar perselisihan adalah perkara wajib. Maka hukum gugatan -dengan demikian- adalah wajibnya tergugat memberikan jawaban dengan mengatakan tidak atau ya, bahkan jika ia diam maka diamnya itu adalah pengingkaran, maka kesaksian penggugat diterima, dan diputuskan dengannya terhadap tergugat. Jika tergugat mengakui pokok gugatan, hakim memutuskan terhadapnya; karena ia tidak tertuduh dalam pengakuannya terhadap dirinya sendiri, dan ia diperintahkan untuk menunaikan hak kepada pemiliknya. Dan jika ia mengingkari, hakim meminta dari penggugat untuk membuktikan haknya dengan saksi. Jika ia menghadirkan saksi, diputuskan dengannya karena sisi kebenaran lebih kuat daripada kebohongan dengan adanya saksi. Dan jika penggugat tidak mampu menghadirkan saksi, dan meminta sumpah lawannya yaitu tergugat, hakim mengambil sumpahnya. Dan dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada penggugat dalam kisah al-Hadhrami dan al-Kindi: “Apakah kamu memiliki saksi? Ia menjawab: Tidak. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Maka bagimu sumpahnya,” yaitu: sumpah tergugat. Jika penggugat berkata: Aku memiliki saksi yang hadir di negeri ini, dan meminta sumpah dari tergugat, maka ia tidak disumpah menurut Abu Hanifah; karena hak penggugat dalam meminta sumpah didasarkan pada ketidakmampuannya menghadirkan saksi sebagaimana dalam hadits yang disebutkan sebelumnya.
Dan Abu Yusuf berkata: Ia disumpah karena permintaan sumpah adalah hak penggugat berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Saksi atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang mengingkari.”
Kemudian sekarang kita berbicara tentang hujah-hujah kedua pihak yang bersengketa atau cara-cara pembuktian hak, maka kita katakan:
Cara-cara pembuktian yang dijadikan dasar dalam peradilan adalah: kesaksian, sumpah, penolakan bersumpah (nukul), pengakuan, atau kesaksian bersama sumpah, atau petunjuk-petunjuk dalam beberapa keadaan.
Adapun kesaksian: maka itu adalah hujah penggugat; karena sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Saksi atas penggugat” dan karena penggugat mengklaim perkara yang tersembunyi; maka ia memerlukan untuk menampakkannya, dan saksi memiliki kekuatan untuk menampakkan. Dan sebab penggugat dituntut menghadirkan saksi atau kesaksian adalah karena pihaknya lemah; karena gugatannya bertentangan dengan asal, maka ia dituntut hujah yang kuat yaitu saksi. Dan bahwa pihak tergugat kuat; karena ia berpegang pada asal, yaitu bebas dari tanggungan; maka cukup darinya hujah yang lemah, yaitu sumpah.
Dan saksi: bisa berupa kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang saksi dan sumpah, atau empat orang laki-laki, atau empat orang perempuan.
Adapun sumpah: maka itu adalah hujah tergugat berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Dan sumpah atas tergugat.” Jika tergugat bersumpah, hakim memutuskan untuk mengakhiri gugatan, dan perselisihan antara kedua pihak gugatan berakhir sampai penggugat mampu menghadirkan saksi. Dan jika ia menolak untuk bersumpah, yaitu jika tergugat menolak untuk bersumpah, maka apakah sumpah dikembalikan kepada penggugat atau diputuskan terhadapnya hanya dengan penolakan?
Dalam hal ini ada dua pendapat para ahli fikih, yang akan saya sebutkan sebagai berikut:
Maka kita katakan: Jika tergugat enggan bersumpah, apakah penggugat bersumpah? Atau diputuskan dengan penolakan lawannya untuk bersumpah? Sebagaimana kami katakan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:
Mazhab Maliki berkata: Sumpah dikembalikan kepada penggugat setelah penolakan dalam perkara harta, dan apa yang berujung kepadanya saja. Dan mazhab Syafii berkata: Sumpah dikembalikan kepada penggugat dalam semua hak kecuali tindak pidana pembunuhan dan hudud, dan diputuskan untuknya dengan apa yang digugatnya, dan tidak diputuskan hanya dengan penolakan tergugat.
Dan sumpah yang dikembalikan dianggap sebagai pengakuan secara hukum, dan inilah yang dibenarkan oleh Imam Ahmad.
Dan berdasarkan ini: pendapat Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad adalah berpendapat mengembalikan sumpah kepada penggugat; namun pendapat pilihan pada mazhab Hanbali adalah tidak mengembalikan sumpah.
Dan Jumhur yang berpendapat mengembalikan sumpah kepada penggugat dalam keadaan tergugat menolak, mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikan sumpah kepada penuntut hak, dan karena tergugat jika menolak bersumpah setelah diminta darinya, maka tampaklah kebenaran penggugat dan kuatlah pihaknya sehingga disyariatkan sumpah dalam haknya seperti tergugat sebelum penolakannya, dan seperti penggugat jika disaksikan untuknya seorang saksi. Dan Allah Taala berfirman: “Atau mereka takut sumpah-sumpah akan dikembalikan setelah sumpah-sumpah mereka” (Surah al-Maidah: dari ayat 108) yaitu: setelah penolakan dari sumpah-sumpah yang wajib, maka hal itu menunjukkan perpindahan sumpah-sumpah dari satu pihak ke pihak lain. Dan tidak diputuskan menurut Jumhur hanya dengan penolakan karena penolakan sebagaimana mungkin berupa penolakan dan kehati-hatian dari sumpah dusta, mungkin juga berupa sikap wara’ dari sumpah yang benar, maka tidak diputuskan untuk penggugat dengan keragu-raguan tergugat, karena tidak dipastikan dengan penolakannya kebenaran penggugat, maka tidak boleh memutuskan untuknya tanpa dalil. Maka jika penggugat bersumpah, sumpahnya menjadi dalil ketika tidak ada yang lebih kuat darinya.
Dan mazhab Hanafi dan Hanbali -dalam pendapat masyhur mereka- berkata: Sumpah tidak dikembalikan kepada penggugat, tetapi diputuskan terhadap tergugat hanya dengan penolakan dari sumpah, dan ia dibebankan dengan apa yang digugat terhadapnya.
Dan penolakan bisa secara hakiki, seperti ucapannya: Aku tidak akan bersumpah, atau secara hukum, seperti jika ia diam. Dan sumpah ditawarkan kepada tergugat satu kali, tetapi untuk tambahan kehati-hatian dan berlebihan dalam memberikan alasan, seharusnya hakim mengulangi penawaran sumpah kepadanya tiga kali, dengan mengatakannya: Sesungguhnya aku menawarkan kepadamu sumpah tiga kali, jika kamu bersumpah maka itulah, dan jika tidak aku akan memutuskan terhadapmu dengan apa yang digugat lawanmu. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Saksi atas penggugat dan sumpah atas orang yang mengingkari” maka beliau menjadikan jenis sumpah-sumpah atas orang-orang yang mengingkari sebagaimana menjadikan jenis saksi atas orang-orang yang menggugat. Dan mazhab Hanafi juga berdalil bahwa penolakan adalah dalil bahwa tergugat mengakui hak yang digugat terhadapnya ini, dan kalau tidak demikian tentu ia berani bersumpah untuk menolak bahaya gugatan dari dirinya, dan melakukan kewajiban; karena sumpah wajib atasnya, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Dan sumpah atas orang yang mengingkari” dan kata “atas” menunjukkan kewajiban.
Dan seharusnya hakim berkata kepada tergugat: Sesungguhnya aku menawarkan kepadamu sumpah tiga kali, jika kamu bersumpah dan jika tidak aku akan memutuskan terhadapmu dengan apa yang digugat penggugat. Maka jika ia mengulangi penawaran kepadanya tiga kali, ia memutuskan terhadapnya hanya dengan penolakannya.
Tata Cara Sumpah, dan Pengaruhnya dalam Gugatan:
Sumpah memiliki tata cara tertentu, baik itu sumpah yang dikembalikan, atau dengan saksi, atau sumpah dari tergugat. Para ulama sepakat bahwa: sumpah adalah dengan nama Allah Azza wa Jalla tanpa yang lain, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Siapa yang akan bersumpah maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah ia diam” dan berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh ia telah kafir.”
Dan mereka juga sepakat bahwa: sumpah yang disyariatkan dalam hak-hak yang dengannya debitur bebas adalah sumpah dengan nama Allah.
Dan mazhab Syafii berkata: Dianjurkan penguatan sumpah, meskipun lawan tidak meminta penguatannya dalam perkara yang bukan harta, dan tidak dimaksudkan dengannya harta, seperti nikah dan talak dan li’an dan qishash dan perwalian dan perwakilan, dan dalam harta yang mencapai nishab zakat tidak yang kurang darinya. Dan penguatan misalnya: dengan menambah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti mengucapkan: Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan, atau demi Allah Yang Menuntut Yang Mengatasi Yang Mendapati Yang Membinasakan, Yang Mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi.
Dan mazhab Hanbali berkata: Sumpah yang dengannya debitur bebas adalah sumpah dengan nama Allah, meskipun yang bersumpah adalah kafir, berdasarkan firman-Nya Taala: “Maka keduanya bersumpah dengan nama Allah: Sesungguhnya kesaksian kami lebih benar daripada kesaksian keduanya” (Surah al-Maidah: dari ayat 107) dan firman-Nya Subhanahu: “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh sumpah mereka” (Surah an-Nur: dari ayat 53).
Sebagian mufassir berkata: Siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka sungguh ia telah bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah.
Dan mazhab Hanafi berkata: Bagi hakim boleh menyumpah orang Muslim tanpa penguatan seperti: Demi Allah atau Wallahi, dan boleh baginya menguatkan yaitu menegaskan sumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah Taala, seperti ucapannya katakan: Wallahi yang tiada tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, ar-Rahman ar-Rahim, Yang mengetahui dari yang tersembunyi apa yang diketahui dari yang terang-terangan, bahwa si fulan ini tidak ada haknya atasku, dan aku tidak menerima harta ini yang digugatnya, dan itu sekian dan sekian, dan tidak sedikitpun darinya. Dan boleh baginya menambah pada rumusan ini dan boleh baginya mengurangi darinya.
Dan bersumpah seharusnya secara pasti atau atas penafian pengetahuan. Maka seseorang bersumpah dengan kesepakatan imam-imam mazhab yang empat secara pasti, yaitu memastikan dan memutuskan dalam perbuatannya baik penetapan atau penafian; karena ia mengetahui keadaan dirinya sendiri, dan melihatnya; maka dalam jual beli dalam keadaan penetapan: Wallahi sungguh aku telah menjual dengan sekian, atau membeli dengan sekian, dan dalam keadaan penafian ia berkata: Wallahi aku tidak menjual dengan sekian, dan tidak membeli dengan sekian.
Dan demikian juga seseorang bersumpah secara pasti atas perbuatan orang lain jika perkara itu berupa penetapan seperti jual beli dan perusakan dan gasab; karena mudah mengetahui yang terjadi dan bersaksi dengannya. Dan jika berupa penafian maka ia bersumpah atas penafian pengetahuan yaitu: tidak mengetahui bahwa demikian karena tidak mengetahui apa yang dilakukan orang lain, maka ia berkata: Wallahi aku tidak mengetahui bahwa ia melakukan demikian.
Dan yang diperhitungkan dalam sumpah adalah niat hakim yang mengambil sumpah. Maka diperhatikan bahwa: Niat dalam bersumpah adalah niat hakim yang mengambil sumpah dari lawan, yaitu yang melakukan pengambilan sumpah dari lawan, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: “Sumpah atas niat yang mengambil sumpah” dan hadits ini dibawa kepada hakim; karena ialah yang memiliki wewenang pengambilan sumpah. Maka jika diambil niat yang bersumpah maka batallah manfaat sumpah-sumpah, dan sia-sialah hak-hak, karena setiap orang bersumpah atas apa yang ia maksudkan. Maka jika yang bersumpah melakukan tauriyah dalam sumpahnya dengan maksud berbeda dari zhahir lafazh ketika pengambilan sumpah hakim, atau ta’wil, yaitu: meyakini berbeda dari niat hakim, atau yang bersumpah mengecualikan seperti ucapannya setelah sumpahnya -insya Allah-, atau menyambung dengan lafazh syarat seperti: Jika aku masuk rumah, sehingga hakim tidak mendengar ucapannya, maka tidak menolak apa yang disebutkan nama sumpah dusta, yaitu: bahwa tidak bermanfaat baginya hal-hal ini, dan tidak ta’wil-ta’wil ini; karena jika kita lakukan itu maka sia-sialah maksud dari sumpah, yaitu terjadinya rasa takut dari berani melakukannya.
Pengaruh Sumpah dalam Gugatan
Pengaruh sumpah dalam gugatan adalah memutus persengketaan dan perselisihan serta menghentikan tuntutan hak untuk sementara waktu, bukan secara mutlak, melainkan hanya hingga bukti ditegakkan. Jadi, sumpah tidak membebaskan tanggungan tergugat menurut jumhur fuqaha (mayoritas ulama fikih).
Pertentangan Dua Gugatan dengan Pertentangan Dua Bukti
Sekarang kita akan membahas hukum pertentangan dua gugatan dengan pertentangan dua bukti dalam kepemilikan. Ada tiga kemungkinan dalam hal pertentangan dua gugatan dengan pertentangan dua bukti dalam kepemilikan, yaitu:
Pertentangan dua gugatan antara pihak luar dengan pihak yang menguasai barang, maksudnya: pertentangan antara orang yang menguasai suatu barang yang digugat dengan orang lain yang tidak menguasainya. Orang yang tidak menguasai barang tersebut kita sebut pihak luar. Ini kemungkinan pertama.
Kemungkinan kedua adalah pertentangan dua gugatan antara dua pihak luar yang sama-sama tidak menguasai barang. Maksudnya: barang yang digugat berada di tangan pihak ketiga, sedangkan kedua pihak yang bersengketa tidak menguasai barang tersebut, dan masing-masing mengajukan gugatan yang bertentangan satu sama lain.
Kemungkinan ketiga: pertentangan dua gugatan antara dua pihak yang sama-sama menguasai barang. Maksudnya: barang berada di tangan dua orang sekaligus, dan masing-masing mengklaim bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri tanpa ada hak bagi pihak lainnya.
Mari kita bahas ketiga kemungkinan ini:
Pertama: Pertentangan Dua Gugatan antara Pihak Luar dan Pihak yang Menguasai Barang
Yaitu pertentangan gugatan antara orang yang menguasai barang dengan orang yang tidak menguasainya. Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat dengan rincian sebagai berikut:
- Jika gugatan dari pihak luar terhadap pihak yang menguasai barang tanpa menyebutkan tanggal, maka dalam hal ini bukti penggugat (disebut bukti pihak luar) lebih diutamakan untuk diterima, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Bukti wajib bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat”. Beliau menjadikan jenis bukti sebagai kewajiban penggugat, sehingga tidak perlu memperhatikan bukti pihak yang menguasai barang (pihak penguasa) karena ia bukan penggugat, maka bukti bukan menjadi hujjahnya. Dalil bahwa ia bukan penggugat adalah tidak terpenuhinya sifat tergugat padanya, karena penggugat adalah orang yang memberitahukan tentang sesuatu yang ada di tangan orang lain sebagai miliknya, dan sifat ini berlaku pada pihak luar bukan pihak yang menguasai barang, karena ia memberitahukan tentang sesuatu yang ada di tangannya sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi ia bukan penggugat melainkan tergugat, sehingga bukti bukan menjadi hujjah baginya dan buktiny dianggap batal serta tidak dipertimbangkan. Juga karena bukti penggugat lebih banyak manfaatnya sehingga wajib didahulukan seperti mendahulukan bukti jarh (cacat) atas ta’dil (keadilan). Dalil banyaknya manfaatnya adalah bahwa bukti itu menetapkan sesuatu yang belum ada, sedangkan bukti pihak yang mengingkari hanya menetapkan hal yang sudah tampak yang ditunjukkan oleh penguasaan, sehingga tidak bermanfaat, artinya: buktiny tidak memberi manfaat lebih dari yang diberikan penguasaan saja.
- Jika kedua bukti disebutkan tanggalnya dan tanggalnya sama, yaitu: keduanya sama dalam tanggal, maka dalam hal ini diputuskan untuk penggugat dari pihak luar, yaitu: bukan pihak penguasa, karena tidak terbukti kebenaran kepemilikan salah satunya, sebab batalnya pertimbangan kedua waktu karena pertentangan, maka keadaan tetap seperti keadaan gugatan kepemilikan mutlak seperti pada kasus pertama.
- Jika tanggal salah satunya lebih dahulu dari yang lain, yaitu: jika tanggal salah satu gugatan lebih dahulu dari yang lain, maka dalam hal ini diputuskan untuk yang lebih dahulu, diputuskan untuk yang lebih dahulu waktunya siapapun itu menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, karena bukti pemilik waktu yang lebih dahulu menunjukkan kepemilikan baginya pada waktu yang tidak ada seorangpun yang menyengketakannya, maka terbukti baginya hak atas objek sengketa, kecuali jika pihak lain membuktikan adanya sebab perpindahan kepemilikan kepadanya.
- Jika salah satunya menyebutkan tanggal dan yang lain tidak, yaitu: jika salah satunya menyebutkan tanggal gugatannya dan yang lain tidak, maka dalam hal ini diputuskan untuk pihak luar, yaitu: bukan pihak penguasa menurut Abu Hanifah dan Muhammad, karena kepemilikan mutlak mengandung kemungkinan tertunda atau lebih dahulu, karena boleh jadi pemilik bukti mutlak bila menyebutkan tanggal buktiny waktuny lebih dahulu, maka terjadi kemungkinan dalam mendahului kepemilikan yang diberi waktu. Dan jika terjadi kemungkinan dalam sesuatu maka gugur pertimbangannya, sehingga gugur pertimbangan waktu, dan gugatan tetap sebagai gugatan kepemilikan mutlak, maka diputuskan untuk pihak luar.
Abu Yusuf berkata: diputuskan untuk pemilik bukti yang bertanggal, karena bukti pemilik waktu menunjukkan kepemilikan baginya pada waktu tertentu yang khusus baginya, tidak ada bukti penggugat kepemilikan mutlak yang menentangnya dengan yakin, melainkan buktiny mengandung kemungkinan pertentangan dan tidak ada pertentangan. Dan pertentangan tidak terbukti dengan keraguan, maka bukti pemilik tanggal tetap selamat dari pertentangan, sehingga diputuskan untuknya.
Inilah rincian yang menjadi pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali.
Sekarang kita lihat pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah dalam masalah ini. Mazhab Maliki dan Syafi’i dalam berbagai kasus ini berpendapat: bahwa bukti pihak yang menguasai barang -yaitu: pihak penguasa- dan disebut bukti pihak dalam, didahulukan secara mutlak tanpa melihat apakah gugatan ini bertanggal atau tidak bertanggal, dan jika bertanggal, apakah salah satunya lebih dahulu dari yang lain atau tidak. Mereka berkata: bukti pihak yang menguasai barang, dan disebut bukti pihak dalam, didahulukan secara mutlak, karena keduanya setara dalam mengajukan bukti, maka kedua bukti bertentangan, dan bukti pihak yang menguasai barang lebih kuat dengan penguasaannya, seperti menguatkan salah satu dari dua hadits yang bertentangan dengan qiyas, maka diputuskan barang untuk pihak yang menguasai. Juga karena bukti tergugat memberikan makna tambahan atas keberadaan barang yang digugat di tangannya, dan karena sisi tergugat lebih kuat dalam mempertahankan asal (istishab), maka asal bersamanya, yaitu tetapnya sesuatu seperti keadaan semula, dan sumpahnya didahulukan atas sumpah penggugat. Jika kedua bukti bertentangan maka wajib memenuhi atau membiarkan tangan pihak yang menguasai barang tetap seperti keadaan semula, dan ia didahulukan seperti jika tidak ada bukti bagi salah satu dari dua pihak yang bersengketa. Ini diperkuat dengan hadits Jabir bin Abdullah bahwa dua orang bersengketa kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang hewan tunggangan atau unta, masing-masing mengajukan bukti bahwa itu miliknya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan hewan itu untuk orang yang menguasainya.
Kedua: Pertentangan Dua Gugatan antara Dua Pihak Luar dari Pihak yang Menguasai Barang
Yaitu keadaan pertentangan dua gugatan antara dua pihak luar dari pihak yang menguasai barang dalam kepemilikan mutlak. Maksudnya: barang di tangan seseorang, dan datang dua orang lain yang bersengketa tentang kepemilikannya, sedangkan tangan keduanya jauh dari barang ini.
Jika dua orang bersengketa tentang suatu barang yang ada di tangan orang ketiga, dan ia mengingkarinya, lalu masing-masing mengajukan bukti untuk menetapkan haknya, maka para fuqaha berbeda pendapat: siapa yang diputuskan baginya barang ini?
Mazhab Syafi’i dalam pendapat yang lebih kuat berkata: kedua bukti saling menjatuhkan, yaitu: keduanya gugur dan batal karena saling bertentangan, baik kedua bukti tanpa tanggal atau keduanya dengan tanggal yang sama atau salah satunya tanpa tanggal dan yang lain bertanggal. Ini menyerupai pertentangan dua dalil tanpa ada yang lebih kuat, sehingga seolah-olah tidak ada bukti dan kembali kepada putusan dalam perkara seperti bila keduanya bersengketa tanpa ada bukti bagi salah satunya, maka masing-masing bersumpah satu kali dan diputuskan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah.
Demikian juga Mazhab Maliki berkata: kedua bukti gugur, dan diputuskan seolah-olah tidak ada bukti, maka masing-masing bersumpah satu kali, dan barang dibagi antara keduanya. Jika salah satunya bersumpah tanpa yang lain, diputuskan untuknya.
Pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Hanbali: kedua bukti gugur dan kedua penggugat diundi untuk sumpah seperti bila tidak ada bukti. Siapa yang keluar undianny dia bersumpah dan mengambil barang.
Adapun mazhab Hanafi, mereka memiliki rincian dalam kasus ini:
Mereka berkata: jika gugatan dari dua pihak luar, dan kedua bukti tentang kepemilikan mutlak tanpa tanggal atau tanggalnya sama, dan barang di tangan pihak ketiga, maka dalam hal ini diputuskan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah, dengan mengamalkan kedua bukti sesuai kemampuan untuk menjaga keduanya dari pembatalan, karena mengamalkan dalil wajib sesuai kadar yang mungkin. Ini diperkuat bahwa dua orang bersengketa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang unta, dan masing-masing mengajukan bukti bahwa itu miliknya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskannya dibagi antara keduanya setengah-setengah.
Mereka juga berkata: jika tanggal salah satunya lebih dahulu dari yang lain, maka yang lebih dahulu lebih diutamakan, karena masing-masing dari dua pihak luar terpenuhi padanya sifat penggugat, maka bukti keduanya didengar dan diterima dalam putusan, lalu salah satunya dikuatkan dengan mendahului tanggal, karena ia menetapkan kepemilikan pada waktu yang tidak ada bukti lain yang menentangnya, maka pihak yang menguasai barang diperintahkan untuk menyerahkan barang yang dipersengketakan kepada pihak yang diputuskan untuknya, hingga pihak lain membuktikan perpindahan kepemilikan kepadanya dengan cara apapun.
Mereka juga berkata: jika salah satunya menyebutkan tanggal dan yang lain tidak, maka dalam hal ini diputuskan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, dan tidak ada pertimbangan untuk tanggal.
Ketiga: Pertentangan Dua Gugatan dalam Kepemilikan Mutlak antara Dua Pihak yang Menguasai Barang
Yaitu: barang di tangan dua orang bersama-sama, dan masing-masing mengajukan bukti bahwa itu adalah haknya semata. Jika ada rumah yang dikuasai dua orang, yaitu: di bawah tangan keduanya, lalu masing-masing mengklaimnya, dan masing-masing mengajukan bukti atas kepemilikannya secara sendiri-sendiri.
Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal itu. Mazhab Syafi’i dalam pendapat yang shahih pada mereka berkata: kedua bukti saling menjatuhkan, yaitu: keduanya gugur dan batal karena saling bertentangan, seperti pertentangan dua dalil tanpa ada yang lebih kuat bagi salah satunya, maka diputuskan rumah tetap di tangan keduanya seperti semula, karena tidak ada salah satunya yang lebih berhak atas rumah dari yang lain.
Mazhab Hanbali berkata: jika dua orang bersengketa tentang barang yang ada di tangan keduanya, dan masing-masing mengajukan bukti, dan kedua bukti setara, maka keduanya bertentangan, dan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah, berdasarkan riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu: “Bahwa dua orang bersengketa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang unta, masing-masing mengajukan dua saksi, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan unta itu dibagi antara keduanya setengah-setengah”.
Adapun mazhab Hanafi, cara mereka dalam hal ini sama dengan cara mereka pada dua kemungkinan sebelumnya yaitu dengan rincian. Mereka berkata:
Jika masing-masing dari dua pihak yang menguasai barang mengajukan bukti bahwa barang itu miliknya tanpa menyebutkan tanggal, maka diputuskan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah. Jika masing-masing menyebutkan tanggal buktiny dan tanggalnya satu, maka dalam hal ini juga diputuskan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah seperti pada kasus pertama. Adapun jika tanggal salah satunya lebih dahulu, maka yang lebih dahulu lebih diutamakan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Muhammad berkata: tidak ada pertimbangan untuk tanggal bagi pihak yang menguasai barang, maka barang dibagi antara keduanya setengah-setengah.
Juga jika salah satunya menyebutkan tanggal tanpa yang lain, maka diputuskan barang dibagi antara keduanya setengah-setengah menurut Abu Hanifah dan Muhammad, dan tidak ada pertimbangan untuk waktu, karena gugur pertimbangannya karena adanya kemungkinan mendahului atau tertunda dari tanggal bukti yang lain.
Abu Yusuf berkata: untuk pemilik tanggal, yaitu: untuk yang lebih dahulu tanggalnya, atau untuk yang menyebutkan tanggal tanpa yang tidak menyebutkannya.
Apakah Bukti Salah Satu Pihak yang Bersengketa Dikuatkan dengan Banyaknya Jumlah Saksi atau Terkenalnya Keadilan?
Dalam kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya dan kasus lain dari keadaan pertentangan bukti-bukti, jumhur fuqaha memutuskan: bahwa salah satu dari dua bukti tidak dikuatkan dengan banyaknya jumlah saksi, dan tidak dengan terkenalnya keadilan, karena masing-masing dari dua bukti adalah hujjah yang sempurna dari kedua belah pihak menurut takaran syara’, maka tidak dikuatkan dengan tambahan, sebagaimana halnya diyat (tebusan darah) yang tidak berbeda jumlahnya dengan perbedaan orang-orangnya. Imam Malik berkata: dikuatkan dengan tambahan keadilan.
Dengan ini kita telah selesai membahas pertentangan dua gugatan dan dua bukti, dan bagaimana pertentangan ini diselesaikan menurut fuqaha mazhab-mazhab sebagaimana telah kami jelaskan.
ALAT-ALAT PEMBUKTIAN
Dan sekarang kita beralih kepada pembahasan mengenai bukti-bukti keadaan (qarinah/indikasi), dan perannya dalam pembuktian:
Peradilan dengan bukti-bukti keadaan adalah salah satu prinsip dasar dalam syariat, baik dalam keadaan adanya bukti-bukti atau pengakuan, maupun dalam keadaan tidak adanya alat bukti apapun dari alat-alat pembuktian.
Bukti keadaan dapat menghalangi didengarnya gugatan, seperti tuntutan orang miskin yang kesulitan bahwa ia meminjamkan uang kepada orang kaya yang berkecukupan. Bukti keadaan dapat menolak saksi atau pengakuan ketika ada tuduhan seperti hubungan kekerabatan saksi dengan yang disaksikan untuknya, atau pengakuan yang dilakukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Bukti keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang menguatkan ketika terjadi pertentangan antara bukti-bukti, seperti: penguasaan barang dan sejenisnya sebagaimana yang telah kita ketahui. Bukti keadaan dapat dianggap sebagai alat bukti tunggal yang berdiri sendiri jika tidak ada bukti lain selainnya, seperti penolakan gugatan istri yang tinggal bersama suaminya tentang tidak diberi nafkah dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Ibnu Qayyim berkata: Barangsiapa yang mengabaikan sama sekali tanda-tanda dan bukti-bukti keadaan dalam syariat, maka ia telah meniadakan banyak hukum, dan menyia-nyiakan banyak hak.
Definisi Bukti Keadaan (Qarinah):
Qarinah secara bahasa adalah: tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Secara istilah: setiap tanda yang jelas yang menyertai sesuatu yang tersembunyi, lalu menunjukkan kepadanya.
Dan dipahami dari definisi ini: bahwa dalam bukti keadaan harus ada dua hal. Pertama: adanya perkara yang jelas dan diketahui yang layak dijadikan dasar untuk diandalkan. Kedua: adanya hubungan yang berpengaruh antara perkara yang jelas dengan perkara yang tersembunyi. Sesuai dengan kekuatan hubungan ini, bukti keadaan terbagi menjadi dua bagian: bukti keadaan yang kuat, dan bukti keadaan yang lemah. Para ahli fikih dan peradilan memiliki peran yang nyata dalam menyimpulkan hasil-hasil tertentu dari bukti-bukti keadaan.
Di antara bukti keadaan dalam fikih: menganggap bahwa barang-barang rumah tangga yang cocok untuk laki-laki ketika terjadi perselisihan antara suami istri tentang kepemilikannya adalah milik laki-laki, seperti sorban dan pedang. Sedangkan yang hanya cocok untuk perempuan, seperti perhiasan adalah milik perempuan berdasarkan kesaksian yang tampak, pengamatan terhadap kebiasaan, dan keadilan.
Di antara bukti keadaan dalam peradilan: memutuskan bahwa barang menjadi milik orang yang menguasainya, dengan pertimbangan bahwa penguasaan adalah bukti keadaan atas kepemilikan berdasarkan yang tampak. Jika bukti keadaan bersifat pasti mencapai tingkat keyakinan, seperti memutuskan seseorang sebagai pembunuh jika ia terlihat bingung, berlumuran darah, dan membawa pisau di samping mayat yang berlumuran darah di suatu tempat, maka itu sendiri dianggap sebagai bukti akhir yang cukup untuk memutuskan perkara.
Adapun jika bukti keadaan tidak bersifat pasti, tetapi berdasarkan dugaan yang kuat, seperti bukti-bukti keadaan yang berdasarkan kebiasaan atau yang disimpulkan dari fakta-fakta gugatan dan tindakan-tindakan para pihak yang berperkara, maka itu dianggap sebagai alat bukti yang menguatkan salah satu pihak yang berperkara apabila hakim yakin dengannya dan tidak ada bukti lain selainnya, atau tidak terbukti sebaliknya dengan cara yang lebih kuat. Menurut mayoritas ahli fikih, tidak boleh memutuskan dengan bukti-bukti keadaan ini dalam perkara hudud, karena hudud ditolak dengan adanya keraguan. Juga tidak boleh memutuskan dengannya dalam qishas kecuali dalam qasaamah (sumpah dalam perkara pembunuhan), karena kehati-hatian dalam masalah pertumpahan darah dan merenggut nyawa. Boleh memutuskan dengannya dalam lingkup muamalah keuangan dan ahwal syakhshiyyah (hukum keluarga) ketika tidak ada saksi dalam pembuktian hak-hak yang timbul darinya.
Namun, mazhab Maliki membuktikan minum khamar dengan bau, dan membuktikan zina dengan kehamilan bagi perempuan yang tidak menikah. Ibnu Qayyim sependapat dengan mereka dalam membuktikan zina dengan kehamilan. Mazhab Hambali memberikan rincian, mereka berkata: perempuan hamil dijatuhi hukuman zina dan suaminya jauh darinya, jika ia tidak mengklaim ada syubhat, tetapi zina tidak terbukti dengan kehamilan perempuan yang tidak mempunyai suami. Ibnu Qayyim berkata: Mayoritas ahli fikih –seperti Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah– memperhatikan bukti-bukti keadaan yang jelas dan dugaan kuat yang mendekati kepastian dalam kekhususan masing-masing dari mereka terhadap apa yang sesuai dengannya. Mereka berpendapat bahwa gugatan dikuatkan dengan sesuatu yang jauh lebih lemah dari itu, seperti penguasaan –yaitu: penguasaan barang– dan kebebasan dari tanggungan, dan nusyuz (enggan bersumpah), dan sumpah yang dikembalikan, dan satu saksi dengan sumpah, dan satu laki-laki dengan dua perempuan, sehingga hal itu menimbulkan dugaan yang menguatkan gugatan. Dan diketahui bahwa dugaan yang terjadi di sini –yaitu yang terjadi dari bukti-bukti keadaan– lebih kuat dengan banyak tingkatan daripada dugaan yang terjadi dari hal-hal tersebut. Dan ini tidak mungkin dipungkiri dan ditolak.
Allah Subhanahu Wata’ala telah menetapkan atas kebenaran yang ada dan yang disyariatkan tanda-tanda dan bukti-bukti yang menunjukkan kepadanya dan menjelaskannya. Dia menetapkan atas iman dan kemunafikan tanda-tanda dan dalil-dalil. Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya –setelah beliau– mempertimbangkan tanda-tanda dalam hukum-hukum, yaitu: bukti-bukti keadaan dalam hukum-hukum dan mengambilnya, serta menjadikannya sebagai penjelasan bagi hukum-hukum ini. Sebagaimana mereka mempertimbangkan tanda-tanda pada barang temuan dan menjadikan sifat yang diberikan oleh orang yang mencarinya sebagai tanda dan bukti atas kejujurannya, dan bahwa barang itu miliknya. Para Sahabat menjadikan kehamilan sebagai tanda dan dalil atas zina, lalu menghukum perempuan karenanya meskipun ia tidak mengakui dan tidak disaksikan oleh empat orang. Bahkan mereka menjadikan kehamilan lebih jujur daripada kesaksian. Mereka menjadikan bau khamar dan muntahnya sebagai tanda dan bukti atas meminumnya yang setara dengan pengakuan dan dua orang saksi.
Nabi shallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dalam baligh (dewasa) dan menjadikannya sebagai tanda dan bukti baligh. Maka beliau membunuh dari tawanan perang pada Perang Bani Quraizhah siapa yang ditemukan padanya tanda tersebut, dan membiarkan hidup siapa yang tidak memilikinya. Juga beliau menjadikan haid sebagai tanda atas kosongnya rahim dari kehamilan.
Demikianlah Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita bahwa para Sahabat –semoga Allah meridhai mereka– mengambil bukti-bukti keadaan. Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk mengambilnya, agar hak-hak tidak hilang. Dan kami cukupkan sampai di sini, kami titipkan kalian kepada Allah, dan semoga kesejahteraan, rahmat, dan berkah Allah atas kalian.
- PEMERIKSAAN ALAT-ALAT PEMBUKTIAN SERTA HUKUM DAN PERADILAN DI KERAJAAN ARAB SAUDI
Pemeriksaan Alat-Alat Pembuktian
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas utusan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba’du (adapun setelah itu):
Kita membahas dalam perkuliahan ini tentang: tugas hakim dalam memeriksa alat-alat pembuktian. Maka kami katakan:
Alat untuk membuktikan gugatan mungkin berupa kesaksian, dan mungkin alat pembuktian lainnya. Sebagaimana diharuskan bagi hakim untuk memahami gugatan dan jawaban, serta memahami pernyataan-pernyataan penggugat dan tergugat, demikian pula dalam keadaan memeriksa alat pembuktian gugatan, wajib baginya untuk memeriksanya dengan baik. Bahkan dalam keadaan ini lebih ditekankan kepada hakim ketepatan pemahaman dan kejernihan pikiran.
Karena yang lazim dalam pembuktian gugatan dilakukan melalui kesaksian, baik yang tertulis –seperti akta-akta– atau yang diucapkan, maka saya memandang perlu membatasi pembahasan pada mendengarkan kesaksian, dan apa yang seharusnya dilakukan hakim terhadap para saksi ketika memberikan kesaksian.
Karena disunahkan bagi hakim apabila para saksi hadir di hadapannya untuk memberi izin kepada mereka dalam memberikan kesaksian, dan tidak sepatutnya bagi mereka memberikannya sebelum itu, berdasarkan apa yang terbukti dalam Shahih dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Sesungguhnya setelah kalian akan ada suatu kaum yang berkhianat dan tidak dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak dimintai kesaksian,” yaitu: mereka memberikan kesaksian sebelum diminta dari mereka.
Hadits ini menunjukkan celaan terhadap tergesa-gesa dalam memberikan kesaksian. Itu karena betapa berbahayanya kesaksian. Dan karena memberikannya tanpa diminta menyebabkan merendahkan kedudukannya di hati manusia. Maka wajib menjaganya, baik lafazh maupun maknanya. Ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dengan sanadnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Maukah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik saksi?!! Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta.”
Para ulama berkata: Hadits ini diartikan bagi orang yang mempunyai kesaksian untuk seseorang tentang suatu hak, dan orang tersebut tidak mengetahui bahwa ia menjadi saksi. Maka ia datang kepadanya lalu memberitahunya bahwa ia menjadi saksi untuknya.
Adapun cara hakim memberi izin kepada para saksi dalam memberikan kesaksian adalah dengan kalimat pertanyaan, seperti mengatakan kepada mereka: Apa yang engkau saksikan? Atau mengatakan: Siapa yang mempunyai kesaksian maka sebutkanlah jika ia mau. Dan jangan mengatakan kepada mereka: Bersaksilah! Karena itu adalah perintah yang menunjukkan keberpihakan hakim kepada salah satu pihak yang berperkara. Dan yang dituntut dari hakim adalah berpegang pada prinsip netralitas dalam persidangan sedapat mungkin.
Jika saksi mulai memberikan kesaksian, maka hakim harus mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepadanya yang ingin ia tanyakan kepadanya, yang tidak ada kaitannya dengan menegakkan kesaksian sesuai bentuknya: untuk menyesuaikan gugatan. Yang lebih baik: memberikan kesempatan yang cukup kepada saksi untuk menyampaikan semua yang ia miliki berkaitan dengan kesaksian tanpa campur tangan hakim dalam hal itu dengan sesuatu yang berarti mengoreksi perkataan saksi atau mengarahkan perhatiannya untuk menutupi celah-celah dalam kesaksiannya atau memperbaiki kelepasan lidahnya. Sehingga ketika ia selesai, hakim bertanya kepada saksi yang lain sebagaimana ia bertanya kepada yang pertama, agar dengan itu dapat diketahui titik-titik kesesuaian dan perbedaan.
Jika hakim meragukan perkataan para saksi, maka ia memisahkan mereka, dan mendiskusikan masing-masing secara terpisah, seperti bertanya tentang apa yang berkaitan dengan yang disaksikan, kapan memikul kesaksian? Di tempat mana? Siapa yang hadir saat itu? Apa yang terjadi pada saat itu? Dan seterusnya. Dengan cara ini dapat dibedakan kesaksian, dan dipahami titik-titik kelemahan pada para saksi dalam kesaksian mereka. Jika perkataan mereka sesuai, hakim menerima kesaksian, kemudian bertanya tentang keadilan mereka.
Jika perkataan mereka berbeda, hakim menolak kesaksian mereka, dan meminta kepada penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi lain jika ia mau.
Di antara yang seharusnya dilakukan hakim ketika memberikan kesaksian adalah mempertahankan kehormatan dan wibawa. Maka tidak boleh menyulitkan para saksi, dengan mengatakan kepada mereka: Mengapa kalian bersaksi? Apa kesaksian ini? Atau mendalami hal-hal yang menyulitkan mereka dan menempatkan mereka dalam kesulitan dan kesusahan, yang tidak mempunyai kepentingan khusus dengan pembuktian. Demikian pula tidak boleh membentak saksi, seperti berteriak kepadanya atau menghardiknya. Karena itu dapat menyebabkan kegugupan dan tergagapnya dalam bicaranya, dan menakut-nakuti dari kesaksian. Semua ini menyebabkan menakut-nakuti dari hakim, dan tidak berani memberikan kesaksian. Yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya hak-hak dan banyaknya kerusakan.
Saksi mungkin tidak mampu menyampaikan apa yang ingin ia saksikan dengan hafalan dari hati, karena kesaksian itu panjang atau bercabang-cabang. Ketika itu, para ulama membolehkan saksi menulisnya atau dituliskan untuknya kemudian dibacakan kepadanya, dan ia bersaksi dengan apa yang tertulis. Karena dalam menghafal kesaksian yang kecil ada kesulitan baginya, dan dalam meninggalkannya bersaksi ada hilangnya hak. Maka hal itu dibolehkan untuk menghilangkan kesulitan.
Para ahli fikih menyebutkan: bahwa di antara yang wajib ketika mencatat kesaksian adalah membedakan para saksi. Mereka berkata: hakim harus menulis nama saksi, nama ayahnya, kakeknya, kunyahnya jika diketahui, demikian juga nama sukunya, pekerjaannya, dan daerah tempat tinggalnya. Jika dalam hal ini tidak ada yang membedakannya dari yang lain, seperti terjadi kesamaran dan kesamaan dengan apa yang disebutkan, maka harus mencari ciri khusus untuk menghilangkan kemungkinan kesamaran. Demikian juga mereka berkata –yaitu para ahli fikih berkata–: hakim harus mencatat tanggal kesaksian, seperti mengatakan: pada hari sekian bulan sekian tahun sekian. Kemudian menyimpan catatan ini, agar kesaksian tidak terpapar pemalsuan dengan penambahan atau pengurangan padanya.
Apa yang disebutkan para ahli fikih tentang membedakan para saksi menunjukkan kepada kita pentingnya pembuktian identitas, dan bahwa hal itu mempunyai asal dalam fikih Islam. Dan karena pentingnya, maka ditemukan dari cara-cara yang menjamin membedakan setiap individu dari yang lain.
Yang mengherankan adalah: apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah yang merupakan yang dianut dalam pembuktian identitas di zaman ini dari sifat-sifat fisik, di mana ia berkata: Maka hakim menulis –yaitu hakim menulis– tentang saksi sifat-sifat tertentu, di antaranya: ia menulis hitam atau putih, atau bibir tipis atau bibir tebal, agar dibedakan, dan tidak terjadi nama yang sama dengan namanya.
PENGAMPUNAN DALAM ALAT BUKTI
Pengertian Pengampunan
Yang dimaksud dengan pengampunan adalah memutus alasan dan celaan dari orang yang dituju.
Dan pengampunan menurut istilah ulama Malikiyah adalah: pertanyaan hakim kepada orang yang dituju atau kepada orang yang dikenai kewajiban hukum, apakah ia memiliki sesuatu yang dapat menggugurkannya dengan pertanyaannya: “Apakah masih ada keberatan yang tersisa untukmu?”
Artinya pengampunan yang dimaksud adalah: bahwa jika dijatuhkan hukuman terhadap seseorang atau terhadap pihak lawan atau jika ditemukan alat-alat bukti pembuktian yang lengkap, maka hakim sebelum memutuskan hukuman terhadapnya harus mengarahkan pengampunan ini kepadanya, dan berkata kepadanya: “Apakah kamu memiliki bukti yang bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawan ini? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk mendiskreditkan kesaksian ini? … dan seterusnya.”
Dalil-Dalil dari Al-Quran
Telah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ayat-ayat yang banyak menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman tidak boleh kecuali setelah memutus hujah dengan hilangnya alasan dari orang yang berhak mendapat hukuman. Di antaranya adalah firman Allah Taala dalam kisah burung Hud-hud: “Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau aku akan menyembelihnya kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas” (Surah An-Naml, dari ayat 21). Dan Allah Taala berfirman: “Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (Surah Al-Isra, dari ayat 15). Dan Allah Taala berfirman: “Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan azab sebelum (kedatangan) nya, tentulah mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah'” (Surah Thaha, dari ayat 134). Dan Allah Taala berfirman: “(Mereka Kami utus) sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah setelah (kedatangan) rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Surah An-Nisa, ayat 165).
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di antara prinsip-prinsip keadilan adalah tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang pantas menerimanya kecuali setelah memberikan pengampunan kepadanya agar ia datang dengan apa yang dapat menyelamatkannya. Jika ia tidak mendatangkannya maka dalam hal itu terdapat pembenaran untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Demikian pula putusan hukum, karena tidak sah kecuali setelah pengampunan di dalamnya karena di dalamnya terdapat jenis hukuman dengan mempertimbangkan orang yang dihukumi.
Tempat Pengampunan
Tampak dari perkataan para ulama bahwa pengampunan hanya ada dalam kesaksian, di mana mereka mengatakan: Dan pengampunan hanya berdasarkan dugaan dan tuduhan terhadap para saksi. Dan ini menunjukkan bahwa tempat pengampunan hanya dalam kesaksian, dan mungkin itu dari segi praktik nyata, karena kesaksian adalah cara yang paling luas dalam pembuktian.
Namun jika kita memperhatikan illat (alasan hukum) pengampunan dalam kesaksian, kita dapati bahwa ia tidak berbeda dengan yang lainnya dari cara-cara pembuktian. Karena sebagaimana pencacatan dalam kesaksian dengan pemalsuan adalah mungkin, demikian juga mungkin pencacatan pada yang lainnya dengan pemalsuan, seperti dokumen-dokumen dan bukti-bukti serta yang sejenisnya. Oleh karena itu adalah hak orang yang dihukumi—sebagaimana dilihat oleh sebagian ulama—pengampunan kepadanya dalam segala yang diajukan oleh pihak lain dari hujah-hujah syar’i dan alat-alat bukti, dan baginya pencacatan yang mematikan dalam hal itu.
Kemudian para ulama mengecualikan beberapa keadaan yang pengampunan tidak bermanfaat di dalamnya, dan yang mungkin pengampunan di dalamnya menjadi jalan menuju meluasnya kejahatan dan penyebaran kerusakan. Di antara keadaan-keadaan itu adalah:
- Pelaku Kerusakan yang Nyata
Setiap orang yang berdiri atasnya bukti dengan kerusakan atau perampasan atau perbuatan melampaui batas, jika ia termasuk orang-orang yang kerusakannya nyata atau dari golongan zindiq yang terkenal dengan apa yang dinisbatkan kepada mereka. Itu karena pengampunan kepada mereka adalah jalan menuju penyebaran kerusakan tanpa manfaat yang diharapkan; oleh karena itu tidak diberi pengampunan kepada mereka.
- Pengakuan atau Pengingkaran di Majelis Hakim
Setiap orang yang berdiri atasnya kesaksian dengan apa yang terjadi padanya berupa pengakuan atau pengingkaran di majelis hakim. Itu karena hakim ikut serta dengan para saksi yang hadir, maka menjadi konsekuensi dari pengampunan kepada mereka adalah pengampunan hakim terhadap dirinya sendiri.
- Kesaksian yang Tersebar Luas
Demikian juga orang yang tersebar luas atasnya kesaksian-kesaksian karena sebab syar’i atau karena kemudharatan salah satu pasangan terhadap yang lain; karena pengampunan tidak bermanfaat dengan tersebarnya kesaksian-kesaksian. Tidak mungkin mendiskreditkan semuanya sebagaimana tidak mungkin baginya mendatangkan apa yang dapat menggugurkan kesaksiannya.
Waktu Pengampunan
Dan pengampunan tidak boleh kecuali setelah pemenuhan para saksi dan penyelesaian penelitian; karena pengampunan dalam sesuatu yang kurang tidak bermanfaat apa-apa. Adapun waktu pengampunan maka di dalamnya ada dua pendapat—sebagaimana disebutkan oleh ulama Malikiyah:
Pendapat Pertama: Bahwa ia sebelum putusan hukum. Dan ini berarti: bahwa hakim jika memeriksa gugatan dan hujah-hujah, ia memberi pengampunan di dalamnya kepada orang yang akan diputuskan hukuman atasnya. Dan atas pendapat ini adalah praktik pada ulama Malikiyah.
Pendapat Kedua: Bahwa pengampunan adalah setelah keluarnya putusan hukum.
Dan yang tampak bahwa pendapat pertama adalah yang benar; karena tujuan dari pengampunan adalah jika terdapat bagi orang yang dihukumi apa yang membatalkan dengannya hujah orang yang diputuskan untuknya. Maka lebih baik dalam hal itu bahwa pengampunan dari cara-cara yang paling dekat untuk menolak kemudharatan dari kedua belah pihak. Adapun atas pendapat kedua—yang mengatakan bahwa pengampunan adalah setelah keluarnya putusan hukum—maka kemudharatannya lebih besar dari manfaatnya; karena pengampunan setelah putusan hukum menyebabkan hilangnya kesempatan bagi orang yang dihukumi dalam meraih haknya. Kemudian sesungguhnya di dalamnya terdapat kemungkinan tasharruf (perbuatan hukum) dengan yang diputuskan jika ia dapat ditasharrufkan.
Oleh karena itu saya berpendapat: bahwa tidak ada larangan dari penerapannya setelah mendengar kesaksian dan sebelum ta’dil (penyaksian keadilan); karena dengan kemungkinan pencacatan kesaksian, maka tidak ada manfaat dari ta’dil mereka; di mana pencacatan didahulukan atas ta’dil menurut para ulama; karena pencacatan memberikan manfaat pengetahuan tambahan selama ta’dil tidak mengandung penafian tambahan itu, seperti jika saksi bertaubat dari apa yang ia dicacat dengannya, maka ketika itu ta’dil yang didahulukan.
Dan kesimpulan dari ini: bahwa harus diperhatikan apa yang lebih baik dalam waktu pengampunan untuk meraih kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
Hasil Pengampunan dan Penangguhan di Dalamnya
Pengampunan mungkin dari hak tergugat untuk membatalkan gugatan pokok, dan mungkin dari hak penggugat untuk membatalkan gugatan pembelaan, sebagaimana mungkin dari hak tergugat—juga—untuk membatalkan pembelaan. Maka pengampunan tidak dikhususkan untuk tergugat.
Dan orang yang diberi pengampunan tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan:
Keadaan Pertama: Bahwa ia menafikan adanya alasan terhadap apa yang berdiri melawannya berupa hujah atau kesaksian. Dan dalam keadaan ini hakim memutuskan atasnya setelah penafian alasan secara langsung.
Keadaan Kedua: Bahwa ia mengklaim alasan terhadap apa yang berdiri melawannya. Dan dalam keadaan ini mungkin bukti alasan tidak berdiri, maka baginya meminta penangguhan untuk menghadirkannya. Telah disebutkan dalam surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu anhuma perkataannya: “Dan barangsiapa mengklaim orang yang tidak hadir atau bukti, maka tetapkan baginya batas waktu, yaitu ajal yang berakhir padanya. Jika ia membuktikannya maka berikan haknya, dan jika hal itu menyulitkannya maka aku menghalalkan atasnya putusan, karena sesungguhnya itu adalah yang paling menyampaikan dalam alasan.”
Adapun masa penangguhan maka ia berbeda dengan perbedaan perkara-perkara, keadaan-keadaan dan keadaan-keadaan; oleh karena itu para ulama pergi kepada bahwa penetapan ajal diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan baiknya penelitian dalam urusan kedua pihak yang bersengketa dan tidak ada di dalamnya batas yang terbatas yang tidak dilampaui, tetapi ia untuk ijtihad.
PUTUSAN HUKUM
Dan kita berbicara sekarang tentang putusan hukum dalam perkara-perkara. Maka kita katakan:
Sesungguhnya hasil akhir dalam proses peradilan dan pengadilan setelah menjalankan gugatan atas prinsip-prinsip syar’inya adalah menampakkan hukum syar’i sesuai dengan apa yang jelas bagi hakim. Dan ini jika tidak berakhir dengan hal yang menghalangi seperti perdamaian atau pelepasan atau semacam itu. Dan agar hakim memutuskan dalam perkara, keadaan menuntut bahwa ia menguasai tiga perkara:
Pertama: Pengetahuannya dengan dalil syar’i yang tetap dengan Al-Kitab atau As-Sunnah atau yang diistinbathkan dari keduanya.
Kedua: Pengetahuannya dengan bukti-bukti yang jelas dengannya jalan putusan hukum ketika sengketa.
Ketiga: Pengetahuannya dengan sebab putusan hukum, syarat-syaratnya, dan penghalang-penghalangnya. Dan ini diketahui dengan indera atau berita atau kebiasaan. Dan pengetahuan perkara ini menyebabkan penjelasan kelayakan putusan hukum dalam tempat tertentu atau hilangnya darinya. Dan bilamana ia salah dalam salah satu dari perkara-perkara ini, ia salah dalam putusan hukum.
Definisi Putusan Hukum
Dan yang dimaksud dengan putusan hukum dalam bahasa: memutuskan dalam sesuatu bahwa ia begini atau bukan begini. Adapun dalam istilah maka sebagian ulama mendefinisikannya bahwa ia: perkara jiwa yang diungkapkan terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan, dan terkadang dengan isyarat.
Dan ini berarti bahwa putusan hukum bukan perkataan, perbuatan dan isyarat, tetapi perkara-perkara ini menunjukkan atasnya.
Jenis-Jenis Putusan Hukum
Untuk putusan hukum terdapat jenis-jenis yang banyak dari beberapa sisi, tetapi yang terpenting adalah dua jenis:
Jenis Pertama: Putusan hukum dengan keabsahan, yaitu putusan hukum dengan keabsahan tasharruf (perbuatan hukum) dalam yang diputuskan. Dan jenis ini masuk pada perbuatan-perbuatan hukum dari akad-akad dan lainnya. Dan ia adalah tingkat putusan hukum yang paling tinggi karena sempurnanya syarat-syaratnya, yaitu: tetapnya kepemilikan pemilik, dan penguasaannya terhadap benda yang ditasharrufkan, dan kelayakan orang yang melakukan tasharruf, dan keabsahan tasharruf.
Jenis Kedua: Putusan hukum dengan akibat, yaitu putusan hukum dengan akibat-akibat yang ditimbulkan atas tasharruf atas orang yang keluar darinya tasharruf dengan akibat tasharruf itu. Dan jenis ini tidak disyaratkan di dalamnya tetapnya kepemilikan bagi orang yang melakukan tasharruf, tetapi dicukupkan dengan dua syarat: kelayakan tasharruf dan keabsahan shighat (redaksinya). Dan hanya dibolehkan putusan hukum dengan akibat walaupun tidak tetapnya kepemilikan karena mungkin sulit membuktikan kepemilikan. Jika jelas setelah itu tidak adanya kepemilikan, wajib membatalkan putusan hukum.
Syarat-Syarat Putusan Hukum
Agar putusan hukum menjadi sah dan dianggap untuk pelaksanaan, para fuqaha mensyaratkan untuk itu syarat-syarat. Kita sebutkan di antaranya sebagai berikut:
Pertama: Bahwa didahului gugatan yang sah. Dan ini disyaratkan untuk keabsahan putusan hukum dalam hak-hak hamba, karena putusan hukum dalam hak-hak hamba tidak boleh kecuali dengan tuntutan dari orang yang mengklaim hak. Dan ini berbeda dengan putusan hukum dalam hak-hak Allah Taala, maka tidak tergantung pada syarat ini. Itu karena keabsahan putusan hukum di dalamnya tanpa tuntutan; karena mendapatkannya adalah wajib atas semua dari hakim dan lainnya.
Kedua: Disyaratkan bahwa putusan hukum dengan lafazh yang memberikan manfaat kewajiban, seperti ia berkata: Aku putuskan atau aku hukumkan atau aku laksanakan atasmu putusan hukum, dan seperti itu.
Dan para fuqaha telah berbeda pendapat dalam beberapa shighat: Apakah memberikan manfaat kewajiban atau tidak? Seperti perkataan hakim: Tetap padaku bahwa bagi ini atas ini sekian, atau perkataannya: Tampak padaku atau sah padaku atau aku mengetahui dan semacam itu. Maka pergi sebagian Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah kepada: bahwa shighat-shighat ini tidak menunjukkan atas kewajiban, maka tidak menjadi putusan hukum. Oleh karena itu berkata sebagian ulama Hanafiyah: Tidak boleh tidak bahwa hakim berkata dalam putusan hukumnya: Aku putuskan atau aku hukumkan atau aku laksanakan atasmu putusan hukum.
Dan pergi sebagian Hanafiyah kepada bahwa shighat-shighat yang terdahulu yang diperselisihkan di dalamnya memberikan manfaat putusan hukum seperti shighat-shighat yang disepakati atasnya. Tetapi yang lebih baik: bahwa ia menjelaskan bahwa tetapnya dengan bukti atau pengakuan; karena putusan hukum hakim dengan bukti menyelisihi putusan hukum dengan pengakuan. Dan yang tampak bahwa yang lebih baik apa yang pergi kepadanya jumhur karena layaknya, yaitu: bahwa tidak boleh tidak dari shighat-shighat tertentu, seperti perkataannya: Aku hukumkan atau aku putuskan. Itu karena layaknya pendapat ini dan layaknya ta’lil (alasan) mereka untuk itu, dan karena shighat-shighat yang diperselisihkan di dalamnya tidak menunjukkan atas kewajiban dengan cara yang mengangkat kemungkinan dan kesamaran dengan tidak berakhirnya dengan putusan hukum. Maka adalah yang lebih baik pembedaan dengan apa yang memberikan manfaat kepastian dan kewajiban, seperti perkataannya: Aku putuskan atau aku hukumkan dan semacam itu.
Ketiga: Disyaratkan bahwa putusan hukum jelas, maka tidak boleh tidak dari penentuan yang diputuskan, demikian juga penentuan yang diputuskan untuknya, dan yang diputuskan atasnya dengan gambaran jelas yang mengangkat setiap kemungkinan atau kemiripan; karena putusan hukum jika samar-samar atau di dalamnya kesamaran, tidak mungkin melaksanakannya. Dan dengan demikian tidak memutuskan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.
Keempat: Disyaratkan dalam putusan hukum bahwa didahului pengampunan untuk memutus hujah orang yang dihukumi. Dan ini syarat untuk keabsahan putusan hukum sebagaimana dinashkan atasnya pada ulama Malikiyah.
Kelima: Disyaratkan kehadiran kedua pihak yang bersengketa di majelis putusan hukum ketika keluarnya putusan hakim. Kecuali bahwa berdiri atas orang yang dihukumi akibat putusan hukum, kemudian ia tidak hadir maka kehadirannya dan ketidakhadirannya sama. Seperti jika ia mengakui dengan yang digugat, kemudian tidak hadir sebelum putusan hukum maka sesungguhnya diputuskan atasnya. Dan jika syarat ini atas apa yang pergi kepadanya ulama Hanafiyah dalam tidak memutuskan hukum kecuali dengan kehadiran pihak yang bersengketa. Itu karena larangan mereka memutuskan hukum atas orang yang tidak hadir atau untuknya kecuali dalam beberapa keadaan.
Namun, syarat ini harus dipertimbangkan jika tidak terpenuhi syarat-syarat hukum dalam peradilan terhadap orang yang tidak hadir, yang disyaratkan oleh para ulama yang membolehkannya selain Mazhab Hanafi.
Keenam: Bahwa putusan hukum yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan dalil yang dituntut secara syar’i dalam perkara yang diputuskan, dan ini mengharuskan agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an atau Sunnah atau Ijmak atau Qiyas Jali, yaitu yang telah dipastikan dalam menghubungkan cabang dengan asalnya.
Syarat ini merupakan salah satu syarat hukum yang paling penting, bahkan yang terpenting; karena kesalahan dalam hal ini pasti akan menimbulkan kezaliman.
Penerapan syarat ini mengharuskan hakim untuk mengetahui wajah hukum, dari segi pemahaman terhadap perkataan kedua pihak yang berperkara, dan keadaan perkara yang diajukan. Jika ia tidak mengetahui wajahnya karena tidak memahami perkara, maka wajib baginya mengulangi pemeriksaan hingga hal itu jelas baginya secara tegas. Jika perkara itu menjadi samar baginya dan hukumnya membingungkan, seperti ia tidak menemukan asal perkara tersebut dalam Al-Qur’an, Sunnah, atau lainnya, atau ia ragu: apakah perkara ini berasal dari asas ini atau asas itu? Atau ditarik oleh dua asas? Dan tidak ada yang lebih kuat? Maka hendaknya ia bermusyawarah dengan ahli ilmu. Jika masalah tetap ada, maka yang lebih baik dalam hal itu adalah perdamaian, dan ini untuk hal-hal yang dapat didamaikan, bukan untuk hal yang tidak dapat didamaikan seperti perceraian.
Alasan-alasan Putusan:
Tidak diragukan bahwa pengetahuan tentang alasan-alasan putusan merupakan hal mendasar untuk memeriksa perkara apa pun yang memerlukan putusan di dalamnya. Namun, para fuqaha tidak menyebutkan alasan-alasan putusan sebagai syarat dari syarat-syaratnya, dan mungkin hal itu karena pentingnya, dan karena ia merupakan hal yang sangat jelas, yang dianggap sebagai kaidah dan asas bagi putusan, dan ini berkaitan dengan hakim ketika memutuskan.
Adapun dari segi penguatan putusan dengan alasan-alasannya ketika penjelasan atau memberitahukan kepada pihak yang diputuskan terhadapnya: maka para fuqaha menganggap baik melakukan hal itu.
Imam Asy-Syafi’i berkata: Dan aku suka bagi hakim jika ia ingin memutuskan terhadap orang lain agar ia mendudukkannya dan menjelaskan kepadanya, dan berkata kepadanya: Engkau telah berdalil di hadapanku dengan begini, dan telah datang kesaksian atasmu dengan begini, dan lawanmu berdalil dengan begini, maka aku memandang putusan atasmu dari sisi begini, agar lebih menenangkan bagi jiwa orang yang diputuskan terhadapnya, dan lebih jauh dari tuduhan, dan lebih layak: jika hakim lalai tentang tempat yang di dalamnya ada hujjah agar ia menjelaskannya, maka jika ia melihat di dalamnya sesuatu yang jelas baginya untuk kembali, atau menjadi samar baginya, agar ia berhenti hingga jelas baginya. Jika ia tidak melihat sesuatu di dalamnya, maka ia memberitahukan bahwa tidak ada sesuatu baginya di dalamnya, dan ia memberitahukan tentang wajah yang ia pandang: bahwa tidak ada sesuatu di dalamnya. Dan jika ia tidak melakukannya, maka putusannya sah, namun ia telah meninggalkan tempat memberikan alasan kepada pihak yang diputuskan terhadapnya ketika memutuskan. Dan dinukil dari sebagian fuqaha Mazhab Syafi’iyyah pernyataan tegas mereka bahwa hakim darurat, yaitu orang yang menjabat sebagai hakim tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya pengangkatan hakim, wajib baginya menjelaskan sandaran hukumnya dalam seluruh putusannya, dan tidak diterima perkataannya “aku memutuskan dengan begini” tanpa penjelasan sandarannya. Dan jika ini dianggap baik oleh para fuqaha, dan mungkin wajib dalam beberapa keadaan, maka ia termasuk hal yang mendesak di zaman kita sekarang karena pentingnya dalam mengawasi kerja para hakim, dan membenarkan yang benar di antaranya, dan mengkritik yang batil, dan ini di samping apa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu memberikan ketenangan pada hati orang yang diputuskan terhadapnya, dan pengawasannya terhadap hal yang terjadi; untuk memutuskan alasannya, dan menghilangkan kemungkinan tuduhan terhadap hakim.
Dan yang patut diisyaratkan: bahwa pemberian alasan putusan merupakan syarat sahnya dalam sistem-sistem positif, dan bahwa mengabaikan hal itu mengakibatkan pembatalan putusan dan kebatilannya.
Kehujjahan Putusan dan Keberlakuannya:
Sebagaimana diketahui bahwa penerbitan putusan dalam suatu perkara mengharuskan pengetahuan tentang alasan-alasannya, dan terpenuhinya syarat-syaratnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di samping mengetahui keadaan perkara dan seluk-beluknya, dan ini berarti bahwa keadaan yang melingkupi perkara memiliki pengaruh besar dalam menilai kelayakan putusan dalam perkara yang diminta putusannya. Dan hal itu tidak terwujud kecuali dengan pandangan dan ijtihad hakim, ini dari satu sisi.
Dan dari sisi lain, sesungguhnya dari tujuan putusan dan terjadinya adalah agar sesuai dengan kebenaran dan hakikat. Jika telah keluar putusan pengadilan dan disertai dengan alasan-alasannya dan pertimbangannya serta memenuhi syarat-syarat sebelumnya, maka ia menjadi hujjah yang wajib dilaksanakan.
Pembatalan Putusan:
Jika putusan keluar dengan melengkapi sifat-sifat syar’inya, dan sesuai lahirnya dengan batinnya, maka ia menjadi hujjah dalam perkara yang diputuskan di dalamnya, dan wajib kelaziman dan pelaksanaannya, dan tidak boleh membatalkannya dengan keadaan apa pun. Tetapi putusan kadang keluar bertentangan dengan asas-asas syar’iyyah baik lahir maupun batin bersama-sama, maka ketika itu wajib membatalkan putusan.
Dan di antara keadaan-keadaan yang dibatalkan putusannya adalah sebagai berikut:
Pertama: Jika putusan keluar, dan bertentangan dengan nash dalam Al-Qur’an atau Sunnah atau bertentangan dengan Ijmak, maka wajib membatalkannya, dan haram melaksanakannya; karena putusan dalam keadaan ini adalah kezaliman secara pasti dan yakin dalam hal yang bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijmak, dan yang demikian itu adalah putusan dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka wajib menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Surat Al-Ma’idah, ayat 45). Dan dalam Shahihain dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersaid: “Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak”. Maka berdasarkan ini: pembatalan adalah untuk apa yang jelas bertentangan dengan kebenaran, dan bukan merupakan tempat perbedaan atau tempat ijtihad. Jika ia merupakan tempat ijtihad, maka tidak dibatalkan, seperti jika putusan keluar dengan ijtihad, kemudian muncul hukum yang bertentangan dengannya yang terjadi dengan ijtihad lain, maka ini tidak membatalkan yang pertama karena adanya Ijmak tentang hal itu.
Kedua –yaitu dari keadaan-keadaan yang dibatalkan putusannya–: Jika putusan berjalan tidak sesuai dengan asas-asas syar’iyyah yang dipertimbangkan untuk sahnya putusan, dan terbitnya putusan tidak sesuai dengan asas-asas yang diperlukan memiliki bentuk-bentuk di antaranya:
1 – Yang berkaitan dengan zat putusan, seperti tidak melengkapi alasan-alasan dan syarat-syaratnya; seperti putusan keluar dalam hak-hak hamba tanpa didahului gugatan, maka putusan ini dibatalkan karena hilangnya apa yang menjadi syarat sahnya, yaitu gugatan. Demikian pula jika putusan keluar sebelum pemberian kesempatan (i’dzar), maka ia dibatalkan; karena i’dzar merupakan syarat sahnya dan tidak ada i’dzar merupakan alasan untuk membatalkannya. Demikian pula jika hakim memutuskan sebelum ta’dil dan tazkiyah untuk para saksi, maka putusannya dibatalkan karena ta’dil para saksi merupakan syarat untuk diterimanya kesaksian dan dianggapnya sebagai hujjah.
2 – Jika putusan keluar dalam gugatan yang tidak boleh bagi hakim memutuskan di dalamnya, karena berkaitan dengan hakim atau bagi orang yang memiliki hubungan dengan hakim yang menjadi sebab mendatangkan tuduhan, dan prasangka buruk, seperti putusan hakim terhadap musuhnya, dan putusannya untuk dirinya sendiri atau mitranya atau ashalnya seperti bapak-bapaknya atau cabangnya seperti anak-anaknya.
3 – Putusan-putusan yang keluar dari para hakim yang tidak terpenuhi pada mereka kelayakan peradilan karena kekurangan dalam beberapa syarat yang diperlukan untuk menjabat peradilan, seperti hakim yang zalim, dan hakim yang zalim, dan berikut penjelasan tentang hal itu:
Hakim yang Zalim: Jika hakim dikenal dengan kezaliman dalam putusan-putusannya, dan tidak adil dalam keadaan dan perjalanannya, maka dibatalkan semua putusannya, baik ia berilmu atau bodoh, nampak kezalimannya atau tersembunyi; karena tidak aman dari sisinya, walaupun dalam hal yang lahirnya benar; karena mungkin batinnya dalam kecurangan dan kezaliman.
Hakim yang Bodoh: Adapun hakim yang bodoh jika ia adil, maka putusan-putusannya diungkap dengan menelusuri kembali, maka apa yang benar dari antaranya dilaksanakan dan diteruskan, dan apa yang salah nyata dari antaranya dibatalkan. Dan sebagian ulama berkata: dibatalkan putusannya, walaupun kesalahan yang diperselisihkan jika ia tidak dikenal dengan musyawarahnya dengan ahli ilmu; karena putusannya tanpa musyawarah ahli ilmu adalah dugaan dan perkiraan, dan ini berarti: bahwa musyawarah ahli ilmu memiliki pengaruh dalam kehujjahan putusan, terutama jika hakim kurang kelayakan ilmunya.
Dan jika benar menelusuri kembali putusan-putusan, dan membatalkan apa yang merupakan tempat pembatalan, maka apakah wajib hal itu bagi hakim dalam putusan-putusan orang sebelumnya?
Kami katakan: Yang jelas dari perkataan sebagian fuqaha: bahwa tidak wajib bagi hakim menelusuri kembali putusan-putusan orang yang sebelumnya, kecuali jika ada pengadu kepadanya yang diputuskan terhadapnya sebelumnya, maka ia melihat dalam apa yang diadukan di dalamnya. Jika putusan bertentangan dengan syariat atau merupakan tempat pembatalan, maka ia membatalkannya. Dan jika merupakan hasil ijtihad di dalamnya, maka ia membiarkannya dan tidak membatalkannya.
Ketiga: Dibatalkan putusan jika orang yang diputuskan terhadapnya menjelaskan pembelaan yang benar yang muncul setelah putusan pertama, walaupun putusan pertama melengkapi asas-asas syar’inya, dan itu karena wajibnya kembali kepada kebenaran. Contohnya: jika seseorang menggugat rumah yang dalam penguasaan orang lain bahwa ia warisan baginya dari ayahnya, dan ia membuktikan hal itu, kemudian setelah putusan jika muncul dokumen yang berlaku yang menjelaskan bahwa ayah penggugat telah menjual rumah tersebut kepada ayah pihak yang menguasai, maka ia menjadi gugatan pihak yang menguasai, dan jika ia membuktikan hal itu, dibatalkan putusan pertama, dan ditolak gugatan penggugat.
PERADILAN DI KERAJAAN ARAB SAUDI
Kemudian kita berbicara sekarang tentang peradilan di Kerajaan Arab Saudi, maka kita akan membahas beberapa poin.
Dari poin-poin pertama ini adalah: kondisi peradilan dan metodologinya. Kami katakan:
Sesungguhnya sistem peradilan di Arab Saudi adalah satu-satunya sistem di negara-negara Arab yang bersumber dari Syariat Islam; bahkan sistem ini telah mendahului dalam banyak aspeknya berbagai peraturan perundang-undangan buatan manusia yang dikeluarkan di negara-negara Arab setelah mengambilnya dari hukum-hukum asing tanpa mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, warisan, syariat, dan akidah. Sementara Kerajaan -pada waktu yang lebih awal- berinisiatif mengeluarkan sistem peradilan dan sistem acara peradilan, dan mengambilnya dari fikih Islam yang kaya untuk menjadi pelopor dalam hal tersebut.
Adapun metodologi Negara Saudi dalam mengambil hukum-hukum syariat, maka telah dikeluarkan keputusan Badan Peradilan nomor 3 tanggal 7/1/1347 Hijriah yang disertai pengesahan tinggi tertanggal 24/3/1347 Hijriah, dan berbunyi sebagai berikut:
Poin 1: Bahwa jalannya peradilan di semua pengadilan harus sesuai dengan pendapat yang difatwakan dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal; mengingat kemudahan merujuk kitab-kitabnya dan komitmen para penulis yang mengikuti mazhabnya untuk menyebutkan dalil-dalil setelah masalah-masalahnya.
Poin (b): Apabila jalannya pengadilan-pengadilan syariah berjalan sesuai dengan penerapan pendapat yang difatwakan dari mazhab yang disebutkan, dan para hakim menemukan dalam penerapannya pada suatu masalah dari masalah-masalahnya ada kesulitan dan bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka dilakukan pengkajian dan penelitian dari mazhab-mazhab lainnya sesuai dengan yang dikehendaki kemaslahatan, dan ditetapkan untuk berjalan menurut mazhab tersebut dengan mempertimbangkan apa yang telah disebutkan.
Dan keputusan Badan Peradilan sebelumnya telah menetapkan penentuan kitab-kitab yang diakui di Kerajaan dari mazhab Hanbali, maka disebutkan di dalamnya: Bahwa pengadilan-pengadilan dalam jalannya menurut mazhab Imam Ahmad bergantung pada kitab-kitab berikut:
(Syarh al-Muntaha) yaitu: (Muntaha al-Iradat) karya Manshur bin Yusuf al-Bahuti, kemudian (Syarh al-Iqna’).
Poin kedua: Jenis-jenis pengadilan:
Pengadilan-pengadilan syariah terdiri dari empat jenis, yaitu:
Jenis pertama: Majelis Peradilan Tertinggi, dan terdiri dari sebelas anggota, lima yang purna waktu dengan pangkat ketua mahkamah banding, dan Majelis Peradilan Tertinggi memiliki kewenangan mengawasi pengadilan-pengadilan, dan menetapkan prinsip-prinsip umum syariah dalam masalah-masalah yang dianggap perlu oleh Menteri Kehakiman.
Jenis kedua: Mahkamah Banding, dan Mahkamah Banding terdiri dari: seorang ketua dan sejumlah hakim yang memadai, dan Mahkamah Banding terdiri dari tiga dewan, yang masing-masing diketuai oleh Ketua atau salah satu wakilnya.
Jenis ketiga: Pengadilan-pengadilan Umum: Dan disusun dari seorang hakim atau lebih, dan penyusunannya, penetapan kedudukannya, dan penentuan kewenangannya dilakukan dengan keputusan dari Menteri Kehakiman.
Jenis keempat: Pengadilan-pengadilan Parsial: Dan terdiri dari seorang hakim atau lebih, dan penyusunannya, penetapan kedudukannya, dan penentuan kewenangannya dilakukan dengan keputusan dari Menteri Kehakiman.
Dan dengan ini kita telah selesai dari pembahasan tentang sistem peradilan dalam Islam, dan dengan selesainya pembahasan tentang sistem peradilan dalam Islam maka kita telah selesai dari materi Siyasah Syar’iyah (Politik Syariat).
Demikian dan semoga Allah memberikan taufik.
Penulis : Kurikulum Universitas Al-Madinah Internasional
Editor : Muhammad Abid Hadlori S,Ag.,Lc.